Selintas Prasasti Dari Melayu Kuno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bab 2 Landasan Teori
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1. Tinjauan Umum 2.1.1. Letak Geografis Sumatra Barat Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 00 54’ Lintang Utara sampai dengan 30 30’ Lintang Selatan serta 980 36’ – 1010 53’ Bujur Timur dengan luas wilayah 42.29730 Km2 atau 4.229.730 Ha. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 186.500 Km2 dengan jumlah pulau besar dan kecil sekitar 345 pulau. 2.1.2. Kedatangan Majapahit Di Minangkabau Pada tahun 1339 Adityawarman dikirim sebagai uparaja atau raja bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang. Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Prof. C.C. Berg, tokoh ini dianggapnya identik dengan Adityawarman. Setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan, pada tahun 1347 masehi atau 1267 saka, Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharajadiraja dengan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan namaMalayapura. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu sebelumnya, dan memindahkan ibukotanya dari Dharmasraya ke daerah pedalaman (Pagaruyung atau Suruaso). Dengan melihat gelar yang disandang Adityawarman, terlihat dia menggabungan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya, Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayadityavarman pernah disandang salah seorang raja Sriwijaya serta menambahkah Rajendra nama penakluk penguasa Sriwijaya, raja Chola dari 3 4 Koromandel. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Swarnnabhumi. 2.1.3. Kerajaan Pagaruyung Masa Kebudayaan Islam Sultan Alif Khalifatullah naik tahta sekitar tahun 1560. Beliau merupakan raja (sultan) pertama di Kerajaan Pagaruyung yang memeluk agama Islam. -

Region Kabupaten Kecamatan Kelurahan Alamat Agen Agen Id Nama Agen Pic Agen Jaringan Kantor
REGION KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN ALAMAT AGEN AGEN ID NAMA AGEN PIC AGEN JARINGAN_KANTOR NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA DEWANTARA ULEE PULO GAMPONG ULEE PULO 213IB0107P000076 INDI CELL INDIRA MAYA RISWADANA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA SEUNUDDON ALUE CAPLI DUSUN MATANG ARON 213IB0115P000048 DUA PUTRA MANDIRI RATNA JELITA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET DUSUN KRUENG CUT 213IA0115P000031 KIOS NASI IBU BETA SURYANI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000039 KIOS WARKOP PAYONG 1903 HERI DARMANSYAH PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005130 MOCHY CELL ERNI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010046 KIOS ARRAHMAN ARAHMAN KAUNUS PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000026 KIOS ZAIMAN ZAIMAN NURDIN S.PT PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010008 ARITA NEW STEEL MASRI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005091 USAHA HIJRAH SYAIF ANNUR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL MALAHAYATI 213IA0115P005080 USAHA BARU T ISKANDAR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL. LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000004 PUTRA MAMA ANWARDI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH -

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Kabupaten
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Kabupaten Dharmasraya dengan ibukota Pulau Punjung adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang berada di persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang, Pekanbaru hingga Jambi. Terletak di ujung tenggara Sumatera Barat antara 00 47’ 7” LS – 10 41’56” LS & 1010 9’ 21” BT- 1010 54’ 27” BT. Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Sebelah utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Riau, sebelah selatan dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi sedangkan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yang juga merupakan Kabupaten paling muda di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2003. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m – 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dan karet, dan dua tanaman inilah yang menyumbang pendapatan daerah paling besar bagi Dharmasraya, sehingga ia merasa mampu 1 untuk menjadi Kabupaten sendiri memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nama Dharmasraya sendiri tentu tidak begitu asing di telinga kita dikarenakan Dharmasraya merupakan Ibukota Kerajaan Melayu di Swharnabhumi atau yang biasa kita ketahui sebagai Sumatra. Lalu jika kita mengkaji lebih dalam maka akan kita temui hubungan antara Kerajaan Dharmasraya dan juga Kabupaten Dharmasraya yang tidak lain merupakan wilayah Kerajaan Dharmasraya itu sendiri. -

The Planggatan Temple Strengtheners of Religious People's Solidarity in Central Java
TAWARIKH: Journal of Historical Studies, VolumeVolume 10(1), 10(2), October April 20192018 Journal of Historical Studies BAYU ANGGORO, SARIYATUN & SUSANTO Volume 10(1), October 2018 Print-ISSN 2085-0980 The Planggatan Temple Strengtheners of Religious People’sContents Solidarity in Central Java ABSTRACT: Culture is a very long root of a human civilization. No human being does not create culture; Forewordon the other. [ii] hand, humans always create thinkers to take action and make a term, and this is called “culture”. Special culture in the Indonesian archipelago, and more specifically Java and contemporary times, Hindu-Buddhist is about a place of worship called “Candi” (Temple). Temple as the highest form of ETTYsociety SARINGENDYANTI, when it became a representation NINA HERLINA of civilization & MUMUH (copyright, MUHSIN taste, ZAKARIA, and intention), all of which are Trithe Tangtu result ofon human Sunda thought Wiwitan in theDoctrine past that in canthe beXIV-XVII realized Century in the form. [1-14] of temples. This article, by by using the historical method, qualitative approach, and literature study, tries to elaborate the Javanese material RETNOculture, WINARNI especially the & RATNAPlanggatan ENDANG temple site,WIDUATIE, and its function as making the religious people solidarity in Jember’sCentral JavaDevelopment in the period from of Hindu-Buddhist.the Traditional The Authority Planggatan to Modern temple siteGovernment has had a. different[15-30] pattern from the other temples in Java. The Planggatan temple site is also a picture of harmony solidarity contained in one corner of the relief. A temple is a place of worship from the relics of the past that originated from Hindu- MUHAMMADBuddhist religion, ADI which SAPUTRA, has meaning UMASIH “Candika & SARKADI, Graha”, meaning that “Candika” is Goddess of Death and The“Graha Impact or Griyo” of Discovery is House, Learning which applies and Criticalto the whole Thinking house to live in the spirit that has left the world. -

BACKGROUND to the SRI VIJAYA STORY PART V (Conclusion)
BACKGROUND TO THE SRI VIJAYA STORY PART V (Conclusion) Paul Wheatley, Impressions of the Malay Peninsula in Ancient Times (Eastern University Press, Singapore, 1964}, pp. 264, plates; and O.W. Wolters, The Fall of Sri Vijaya in Malay History (Oxford University Press, Kuala Lumpur and Singapore, 1970), pp. 274. 22. THE POST-SRI VIJAYA PERIOD (1260-1300 A.D.) With the death of Chandrabanu in Ceylon about 1260, the Sri Vijaya Empire, if I may call it by such a highfalutin name, came to an end. The histories of the Malay Peninsula and Sumatra then took separate courses. The city-states sent embassies to the Chinese court, which the Chinese still recorded as coming from San-fo-tsi; but complete control of the Malacca Straits, based on Muara Takus (Malayu) in Central Sumatra and Kedah on the west coast of the Peninsula, was no more. Into this vacuum stepped the Thai and the Javanese. We have seen m section 18 that about the beginning of the 13th century, Tao U-Thong, king of Ayodbia, had already gone down the Peninsula to Bang Sa pan in Prachuab Kirikhand Province and divided the Peninsula with Chao Phya Sri Thammasokaraja of Nakorn Sri Tbammaraj. Half a century later Sri In tara tit, King of Sukhothai, went down to Nakorn and co-operated with Chandrabanu in acquiring the image known as the Buddha Sihing fron:i Ceylon (section 18). By the end of the century Ram Kambaeng, Intaratit's youngest son who came to the throne of Sukhothai about 1279, claimed sovereignty over Nakorn to "where the sea marks the limit". -

Perjuangan Adityawarman Di Kerajaan Dharmasraya Nusantara Tahun 1339-1376
PERJUANGAN ADITYAWARMAN DI KERAJAAN DHARMASRAYA NUSANTARA TAHUN 1339-1376 Charles Robenta, Tontowi Amsia dan Yustina Sri Ekwandari FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624 e-mail: [email protected] Hp 085769447085 The purpose of this research is to know the process of struggle Adityawarman at Dharmasraya Kingdom archipelago at 1339-1376 . In this research the method use is historical method. The data collection techniques uses literature and documentation techniques. The data analysis technique in this research is qualitative data analysis technique. The results of this research showed that Adityawarman struggle process Dharmasraya Kingdom archipelago conquest led various kingdoms in the Malay Sultanate Aru Barumun among such as, Silo kingdom, and small kingdoms around it. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara tahun 1339-1376. Metode penelitian ini menggunanakan metode historis. Tehnik pengumpulan data mengunakan tehnik kepustakaan dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara yakni diawali dengan Mengadakan berbagai penaklukan kerajaan yang ada di Melayu diantaranya Kesultanan Aru Barumun, Kerajaan Silo, dan kerajaan kecil yang ada disekitarnya. Kata kunci : adityawarman, kerajaan dharmasraya, perjuangan PENDAHULUAN dengan Ekspedisi Pamalayu yang Kerajaan Dharmasraya adalah dilakukan oleh Kerajaan Singasari. Ketika kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri para pasukan tentara Kerajaan Singasari sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya telah menyelesaikan tugasnya, mereka terletak di Selatan Sawahlunto, Sumatera membawa pulang dua putri Melayu yang Barat sekarang dan di Utara Jambi. bernama Dara Petak dan Dara Jingga. -

Suvarnadvipa and the Chryse Chersonesos*
SUVARNADVIPA AND THE CHRYSE CHERSONESOS* W. J. van der Meulen The title of Paul Wheatley’s book, The Golden Khersonese: Studies in the historical geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500 (1961) does not leave any doubt about the author’s confidence that the Malay Peninsula indeed represents the Golden Peninsula which features in Ptolemy’s Geographike Hyphegesis (Manual for Mapping out the Earth).1 The text of his book conveys the same conviction, adding that, though the Indian Suvarnabhumi or Suvarnadvipa (Gold Land or Gold Island) in dicated only some indistinct ’’eastern eldorado,” it was somehow espe cially connected with the Malay Peninsula, since it must have been the matrix of Ptolemy’s ehersonesos (peninsula). In spite of my admiration of the way in which Wheatley brought together his rich source materials, for which any future historian of Southeast Asia will be indebted to him, I do not share his confidence as to the location of the Golden Khersonese. In this paper I would like to present some of the reasons for my doubts. I. Suvarnadvipa Suvarnabhumi and Suvannabhumi are the most common names connected with gold in old-Indian literature, both Sanskrit and Pali. The adjec tive ’’gold” is also used in connection with other geographical fea tures, but in Sanskrit works mostly in the compound Suvarnadvipa.2 It is obvious that these names, as Wheatley rightly notes, only ’’featured in early Indian folklore as an eastern eldorado where great riches might be won.”3 It must be doubted, however, whether this statement remains true when subsequently ’’ancient Indian folklore” is changed * This article is an extended and revised English version of a paper read in Indo nesian at the ’’Seminar Sejarah Nasional II” in Yogyakarta (August, 1970). -
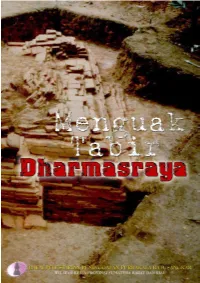
Menguak Tabir Dharmasraya
Menguak Tabir Dharmasraya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Peninggalan Purbakala BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA BATUSANGKAR Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Menguak Tabir Dharmasraya Penanggung jawab |Drs. Marsis Sutopo, M.Si.| Penulis |Drs. Budi Istiawan & Drs. Bambang Budi Utomo| Desain Sampul & Lay Out |Sri Sugiharta, S.S.| Penerbit |Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar [Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan KepulauanRiau ] |Cetakan |I| Tahun |2006| Copyright © 2006 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Batusangkar ii |kata pengantar | alai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang Bmempunyai wilayah kerja di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Secara struktural, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar berada di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan, khusus- nya yang berkenaan dengan pelestarian peninggalan purbakala, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar mempunyai program untuk mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan purbakala, baik yang berhubungan dengan aspek sejarah dan budayanya maupun hal-hal lain yang melingkupinya. Buku ini, yang merupakan kumpulan dari dua tulisan, mencoba mengungkap lebih lanjut tentang hal-hal -

Inventory of Oriental Manuscripts of the Library Of
INVENTORIES OF COLLECTIONS OF ORIENTAL MANUSCRIPTS INVENTORY OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF LEIDEN VOLUME 15 MANUSCRIPTS OR. 14.001 – OR. 15.000 REGISTERED IN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY IN THE PERIOD BETWEEN AUGUST 1973 AND JUNE 1980 COMPILED BY JAN JUST WITKAM PROFESSOR OF PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY OF THE ISLAMIC WORLD IN LEIDEN UNIVERSITY INTERPRES LEGATI WARNERIANI TER LUGT PRESS LEIDEN 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007. The form and contents of the present inventory are protected by Dutch and international copyright law and database legislation. All use other than within the framework of the law is forbidden and liable to prosecution. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the author and the publisher. First electronic publication: 12 November 2006. Latest update: 13 August 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007 2 PREFACE The arrangement of the present volume of the Inventories of Oriental manuscripts in Leiden University Library does not differ in any specific way from the volumes which have been published earlier. For the sake of brevity I refer to my prefaces in those volumes. A few essentials my be repeated here. Not all manuscripts mentioned in the present volume were viewed by autopsy, but many were. The sheer number of manuscripts makes this impossible. At a later stage this may be achieved, but trying to achieve this at the present stage of inventorizing would seriously hamper the progress of the present project. -

Singsing Director of the Center for Being Used As Tinapa Wrapper, Kapampangan Studies
1 RECENT Center launches translated 1621 Kapampangan grammar VISITORS translations that the Center is under- taking to make early Spanish archival documents accessible to scholars and students. The next are Fray Diego Bergaño’s Vocabulario en la Lengua Pampanga (1732) and his own grammar Arte de la Lengua Pampanga (1729), both already completed; Fray Alvaro de Benavente’s Arte y Diccionario Pampango (1700); and documents from BEA ZOBEL DE AYALA, JR GOV. GRACE PADACA the Luther Parker Collections, the Na- tional Archives and the Manila Archdiocesan Archives. “Coronel’s Arte is significant be- cause it was written in the early 1600s, barely a few years after the Spaniards first made contact with the Kapampangans,” Center Director Robby Tantingco said. “Because our ancestors used the ancient writing sys- JUSTICE JOSE VITUG REP. SALACNIB BATERINA tem of baybayin, Coronel’s Arte rep- resented the colonizers’ earliest at- The Center recently released the En- tempts to reconfigure our language and glish translation of Fray Francisco their efforts to make us unlearn what Coronel’s Arte y Reglas de la Lengua we were already using.” Pampanga, the oldest extant Fr. Santos, a former Benedictine, Kapampangan grammar. It was translated is a guest priest of the Archdiocese of by Fr. Edilberto V. Santos on a University San Fernando. grant. The book is available at the Cen- Coronel’s book is the first in a series of DEAN RAUL SUNICO REP. CYNTHIA VILLAR ter and in bookstores in Manila. Consultant presents paper at Illinois conference Prof. Lino Dizon, Director of the Center for Tarlaqueño Studies and history consultant for the Center for PROF. -

Pendahuluan Jambi, Secara Geografis, Terletak Di Bagian Timur Pulau
SEJARAH MELAYU JAMBI DARI ABAD 7 SAMPAI ABAD 20 Benny Agusti Putra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi [email protected] Abstract: Abstract: History of Malay Jambi From 7th Century to 20th Century. Some historians said that Malay was the first kingdom to control Jambi. The center of its kingdom in Jambi city is now also a legacy of the Malay Kingdom. Another thing about the existence of Malays in Jambi is that there are several records from China during the T'ang Dynasty that mentioned Mo-lo-yu. The author attempts to position the history of Jambi Malay in hopes of providing a formula amid increasingly complex life. Malay as the identity of Jambi society is very important in the Historiography "historical writing" in the archipelago of malay. This study will discuss three main topics, classical I and II Malay (Hindu Buddhism), Malay Malay II (Colonial Islam), Jambi Malay post-independence and the establishment of Jambi province. This research is a conceptual research, in which this research is a historiography "historical writing" of Malay writings. The sources of writing in this article come from previous studies. Keywords: History, Melayu, Jambi. Abstrak: Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad 20. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa Melayu merupakan kerajaan pertama yang menguasai Jambi. Pusat kerajaannya berada di kota Jambi sekarang juga merupakan peninggalan Kerajaan Melayu. Hal lainnya mengenai keberadaan Melayu di Jambi adalah adanya beberapa catatan dari Tiongkok pada zaman Dinasti T’ang menyebut Mo-lo-yu.Penulis berupaya memposisikan sejarah melayu Jambi dengan harapan memberikan sebuah formula ditengah kehidupan yang semakin komplek. -

Potensi Sejarah Dan Purbakala Das Batanghari
Analisis Sejarah Vol.9 No. 1, 2020 Labor Sejarah Unand Potensi Sejarah dan Purbakala Das Batanghari Witrianto Staf pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang Abstract Batang Hari River Basin is an area bounded by topography and blunt receiving rain water, sediment and nutrients, and running it through its tributaries. Batanghari DAS consists of three parts, namely the upstream, midstream and downstream, located in West Sumatra and Jambi province, each of which has different physical characteristics. In the upper region is located at an altitude 500- 1000 meters above sea level with rainfall 3000 mm / yr and the geology is dominated Bukit Barisan mountains that are volcanic quarter. Culture that flourished in the upper reaches of the culture, especially in the Minangkabau of West Sumatra Province, located in Solok District, South Solok, and Dharmasraya, while the center is a cultural area with a mixture of Malay Minangkabau Jambi is located in the district of Bungo and Tebo, the downstream Malay culture is an area located in the city of Jambi Jambi, District Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung East. Along the Batang Hari River flows are historical relics from the small kingdoms and large, like a Malay kingdom, Dharmasraya, Siguntur, Alam Surambi Sungaipagu, Pulaupunjung, and others. Keywords: Watershed, culture, historical PENDAHULUAN Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi pembatas topografi (punggungan bukit) yang menerima, mengumpulkan