ARSITEKTURA Vol 16, No.1, 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reisgids 2020-2021 Chili Panama Peru Cuba Argentinië Bolivië Brazilië Suriname • REISGIDS 2020-2021 Noo Rd Groenland -At Lan Tis Ch E O Z Ce U Aa Id N -A Tla
reisgids 2020-2021 reisgids Kleine personen groepen 8 tot van 16 © johan van cutsem www.oogenblik.be cutsem van johan © HOBO • BEGELEIDE WERELDREIZEN • REISGIDS 2020-2021 Bondgenotenlaan 165 3000 Leuven e-mail [email protected] website www.hoboreizen.be Een overzicht van onze bestemmingen tel. 016 20 80 47 Jszee Noordelijke I Groenland Alaska IJsland Faroer Eilanden Canada n a a e c Kazachstan O e Mongolië h c Georgië is Oezbekistan t Noord-Korea n Armenië Kirgizstan Verenigde Staten a l Tibet Zuid-Korea t Libanon Japan A China an - Marokko Iran ea d c r Bhutan O o le Jordanië il o Nepal t Taiwan S Cuba N India Mexico Oman Laos Honduras Myanmar Guatemala Vietnam Panama Costa Rica Suriname Ethiopië Cambodja St Colombia Oeganda Sri Lanka ill Sulawesi e O Kenia Borneo cea Ecuador an Tanzania In n Peru Brazilië dische Oceaa Java/Bali Zambia Bolivië n Zimbabwe a a e Namibië Botswana Madagaskar c Australië O e h c Zuid-Afrika is Chili t Argentinië n la t Nieuw-Zeeland -A d ui Z www.hoboreizen.be VOORWOORD Waarde wereldreiziger, 32 jaar Hobo Wie het reisvirus eens te pakken heeft raakt nooit meer genezen. Met Hobo reizen kan u het virus de baas! In onze brochures wereldreizen en Europareizen vindt u ongetwijfeld een aangepaste remedie tussen de tientallen bestemmingen. Al meer dan 30 jaar bieden wij de fervente reiziger een hele reeks klassiekers aan zoals Peru, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, reizen die vroeg in het seizoen al het bordje uitverkocht opgespeld krijgen. Hobo reizen was in het verleden dikwijls de pionier van minder voor de hand liggende bestemmingen zoals Noord-Korea, Mongolië en Vietnam. -

Manifestasi Budaya Indis Dalam Arsitektur Dan Tata Kota Semarang Pada Tahun 1900 - 1950
MANIFESTASI BUDAYA INDIS DALAM ARSITEKTUR DAN TATA KOTA SEMARANG PADA TAHUN 1900 - 1950 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta Disusun Oleh : T R I P A R T O N O C 0 5 0 5 0 0 3 F A K U L T A S S A S T R A D A N S E N I R U P A UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET S U R A K A R T A 2 0 1 0 i HALAMAN PERSETUJUAN MANIFESTASI BUDAYA INDIS DALAM ARSITEKTUR DAN TATA KOTA SEMARANG PADA TAHUN 1900 - 1950 Disusun Oleh : T R I P A R T O N O C 0 5 0 5 0 0 3 Telah Disetujui oleh Pembimbing Tiwuk Kusuma H, S.S. M.Hum NIP. 197306132000032002 Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum NIP. 19540223198601200 ii HALAMAN PENGESAHAN Disusun Oleh : T R I P A R T O N O C 0 5 0 5 0 0 3 Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Pada Tanggal ..... ................ 2010 Jabatan Nama Tanda Tangan Drs. Warto, M. Pd Ketua NIP. 196109251986031001 (………………) Dra. Hj. Isnaini W. W, M. Pd Sekretaris NIP. 195905091985032001 (………………) Tiwuk Kusuma H, S.S. M.Hum Penguji I NIP. 197306132000032002 (………………) Drs. Soedarmono, SU Penguji II NIP. 194908131980031001 (………………) Dekan Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Drs. Sudarno, M.A NIP. 195303141985061001 iii PERNYATAAN Nama : TRI PARTONO Nim : C 0505003 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Manifestasi Budaya Indis dalam Arsitektur dan Tata Kota Semarang Pada Tahun 1900-1950” adalah betul-betul karya sendiri, bukan dari plagiat dan tidak dibuat oleh orang lain. -

1. Arsitektur Kolonial
PERPUSTAKAAN FTSi> VU HADJfl.H/BEU TGL. TERIMA : 2t2^ it- ^^7 — NO. JUDUL 34^3; — NO. !NV. 'UGAS AKHIR NO. i'vDUX. - -.DO£4$X TAMAN BACA DAN REKREASI KRIDOSONO READING COURT ANDRECREATION KRIDOSONO Penataan fasilitas Taman Baca dan Rekreasi dengan pendekatan Arsitekiur kolonial Emphasis at settlementof Reading court facility and recreation with approach of Architecture colonial \ v. Disutetnfbleh: Pratintya Ambar Sari 02512163 JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEHNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2007 MILK P€RPUS7AKAAN I! K-Rt;OiAAH Ui! YOGYAICARTA ! LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR TAMAN BACA DAN REKREASI KRIDOSONO READING COURT AND RECCREATiGN KRIDOSONO Penekanan pada penataan fasilitas taman baca dan rekreasi dengan pendekatan Arsitektur kolonia! Emphasis at settlement of reading court facility and recreation with approach of Architecture colonial Disusun olehi Pratintva Ambar Sari 02512163 Yogyakarta, 1 Maret 20U7 MENGESAHKAN DOSEN PEMBifviBiNG TUGAS AKHIR V \ Ir. H. Hanif Budiman. MSA KETUA JURUSAN ARSITEKTUR FTSP U\\ !r. Hastutl Saptorim, MA KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini masih selalu terjaga dalam Iman dan Islam. Dan atas rahmat-Nya pula akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk meneyelesaikan jenjang studi S1 pada Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir yang dipertahankan di depan tim penguji. Tugas Akhir ini mengambil judul "TAMAN BACA DAN REKREASI KRIDOSONO, dengan penekanan pada penataan fasilitas Taman baca dan rekreasi dengan pendekatan Arsitektur kolonial." Dengan ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. -

Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab Di Surakarta the Dynamics of Kampung Arab Development in Surakarta
Volume 18 Issue 2 October 2020, pages:249-264 Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab di Surakarta The Dynamics of Kampung Arab Development in Surakarta Najmi Muhamad Bazher * MENARA, Study and Research Center of Arab Ancestry in Indonesia Email : [email protected]* DOI: https://doi.org/10.20961/arst.v18i2.43363 Received:July 28, 2020 Revised: September 17, 2020 Accepted: September 18, 2020 Available online: October 31, 2020 Abstract A majority of modern-day Arab-Indonesians are the descendant of Hadramaut immigrants who came to Indonesia. They have stayed and settled in area near each other that are now known as kampung Arab. Most kampung Arab in Indonesia show that Arabs had similar pattern in their way of settling. Surakarta, as the chosen location, has kampung Arab located at Pasar Kliwon. There are theories about how these kampung Arab, including Pasar Kliwon, were developed. The objective of this study is to explore the four theories of Kampung Arab Pasar Kliwon development factors and the chronological sequence of those factors. This study is a qualitative research that uses secondary analysis of the previous studies as its method. Data verification utilised triangulation method, using various approaches, such as observation, interview, and participatory mapping. All four theories are considered valid. Based on the history of Kampung Arab Pasar Kliwon development, the factors in chronological order are economic activities, community, keraton (imperial) government policy, and colonial government policy. Keywords: Arab-Indonesian, district, kampung Arab, Pasar Kliwon, settelement. 1. PENDAHULUAN Munawar di Palembang, dan Kampung Arab Ampenan di Lombok adalah sedikit contoh Mayoritas orang Arab yang kini tinggal di Kampung Arab di Indonesia. -

Por-Tugu-Ese? the Protestant Tugu Community of Jakarta, Indonesia
School of Social Sciences Department of Anthropology Por-Tugu-Ese? The Protestant Tugu Community of Jakarta, Indonesia. Raan-Hann Tan Thesis specially presented for the fulfilment of the degree of Doctor in Anthropology Supervisor: Brian Juan O’Neill, Full Professor ISCTE-IUL March, 2016 School of Social Sciences Department of Anthropology Por-Tugu-Ese? The Protestant Tugu Community of Jakarta, Indonesia. Raan-Hann Tan Thesis specially presented for the fulfilment of the degree of Doctor in Anthropology Jury: Dr. Shamsul Amri Baharuddin, Distinguished Professor, Institute of Ethnic Studies, National University of Malaysia Dr. Maria Johanna Christina Schouten, Associate Professor, Department of Sociology, University of Beira Interior Dr. Ema Cláudia Ribeiro Pires, Assistant Professor, Department of Sociology, University of Évora Dr. António Fernando Gomes Medeiros, Assistant Professor, Department of Anthropology, School of Social Sciences, ISCTE- University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) Dr. Marisa Cristina dos Santos Gaspar, Research Fellow, Orient Institute, School of Social and Political Sciences, University of Lisbon (ISCSP-UL). Dr. Brian Juan O’Neill, Full Professor, Department of Anthropology, School of Social Sciences, ISCTE-University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) March, 2016 ABSTRACT Por-Tugu-Ese? The Protestant Tugu Community of Jakarta, Indonesia Keywords: Mardijkers, Betawi, Portuguese identity, Christian village, Keroncong Tugu Although many centuries have passed since Portugal’s Age of Discoveries, enduring hybrid communities are still surviving in places where the Portuguese had been present. Portuguese identity in Malacca, Larantuka, and East Timor, for example, has always been associated with Catholicism. But in Batavia, the Portuguese-speaking population (the Mardijkers, slaves, and Burghers) was converted to Calvinism under Dutch colonization, forming the Protestant Portuguese community in Indonesia. -

Candi, Space and Landscape
Degroot Candi, Space and Landscape A study on the distribution, orientation and spatial Candi, Space and Landscape organization of Central Javanese temple remains Central Javanese temples were not built anywhere and anyhow. On the con- trary: their positions within the landscape and their architectural designs were determined by socio-cultural, religious and economic factors. This book ex- plores the correlations between temple distribution, natural surroundings and architectural design to understand how Central Javanese people structured Candi, Space and Landscape the space around them, and how the religious landscape thus created devel- oped. Besides questions related to territory and landscape, this book analyzes the structure of the built space and its possible relations with conceptualized space, showing the influence of imported Indian concepts, as well as their limits. Going off the beaten track, the present study explores the hundreds of small sites that scatter the landscape of Central Java. It is also one of very few stud- ies to apply the methods of spatial archaeology to Central Javanese temples and the first in almost one century to present a descriptive inventory of the remains of this region. ISBN 978-90-8890-039-6 Sidestone Sidestone Press Véronique Degroot ISBN: 978-90-8890-039-6 Bestelnummer: SSP55960001 69396557 9 789088 900396 Sidestone Press / RMV 3 8 Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden CANDI, SPACE AND LANDscAPE Sidestone Press Thesis submitted on the 6th of May 2009 for the degree of Doctor of Philosophy, Leiden University. Supervisors: Prof. dr. B. Arps and Prof. dr. M.J. Klokke Referee: Prof. dr. J. Miksic Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde No. -

Town Planning and Architecture on Eighteenth Century St Eustatius
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1995 Town Planning and Architecture on Eighteenth Century St Eustatius Dana Elizabeth Triplett College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the Caribbean Languages and Societies Commons, History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, Social and Cultural Anthropology Commons, Urban, Community and Regional Planning Commons, and the Urban Studies and Planning Commons Recommended Citation Triplett, Dana Elizabeth, "Town Planning and Architecture on Eighteenth Century St Eustatius" (1995). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539625949. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-wcdt-2e89 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. TOWN PLANNING AND ARCHITECTURE ON EIGHTEENTH CENTURY ST. EUSTATIUS A Thesis Presented to The Faculty of the Department of Anthropology The College of William and Mary in Virginia In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Dana Triplett 1995 APPROVAL SHEET This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Author' Approved, June, 1995 Norman Barka Kathleen J. Bragdon Marley R. Br'own III u Table of Contents Page Acknowledgements.................................. iv List of Figures................................... v Abstract.......................................... ix Introduction...................................... 2 Chapter I. Historical Background............... 7 Chapter II. The Development of the Port Town at St. -

Candi Space and Landscape: a Study on the Distribution, Orientation and Spatial Organization of Central Javanese Temple Remains
Candi Space and Landscape: A Study on the Distribution, Orientation and Spatial Organization of Central Javanese Temple Remains Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus Prof. mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op woensdag 6 mei 2009 klokke 13.45 uur door Véronique Myriam Yvonne Degroot geboren te Charleroi (België) in 1972 Promotiecommissie: Promotor: Prof. dr. B. Arps Co-promotor: Dr. M.J. Klokke Referent: Dr. J. Miksic, National University of Singapore. Overige leden: Prof. dr. C.L. Hofman Prof. dr. A. Griffiths, École Française d’Extrême-Orient, Paris. Prof. dr. J.A. Silk The realisation of this thesis was supported and enabled by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), the Gonda Foundation (KNAW) and the Research School of Asian, African and Amerindian Studies (CNWS), Leiden University. Acknowledgements My wish to research the relationship between Ancient Javanese architecture and its natural environment is probably born in 1993. That summer, I made a trip to Indonesia to complete the writing of my BA dissertation. There, on the upper slopes of the ever-clouded Ungaran volcano, looking at the sulfurous spring that runs between the shrines of Gedong Songo, I experienced the genius loci of Central Javanese architects. After my BA, I did many things and had many jobs, not all of them being archaeology-related. Nevertheless, when I finally arrived in Leiden to enroll as a PhD student, the subject naturally imposed itself upon me. Here is the result, a thesis exploring the notion of space in ancient Central Java, from the lay-out of the temple plan to the interrelationship between built and natural landscape. -
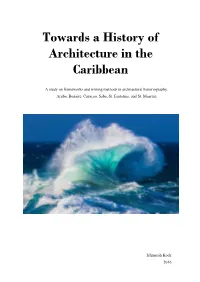
Towards a History of Architecture in the Caribbean
Towards a History of Architecture in the Caribbean A study on frameworks and writing methods in architectural historiography. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten Ichmarah Kock 2016 TOWARDS A HISTORY OF ARCHITECTURE IN THE CARIBBEAN A study on frameworks and writing methods in architectural historiography. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, and St. Maarten Ichmarah Kock Student number: 10335404 Master thesis History of Architecture Faculty of Humanities Universiteit van Amsterdam / University of Amsterdam Prof. dr. Lex Bosman Dr. Petra Brouwer Augustus 2016 Image front page: “Ocean Fan” (Photograph by Armando Goedgedrag. Copyright by Artmando Multimedia, accessed August 13, 2016, http://www.artmandomultimedia.com/paintings-2/wave-photography/). © 2016 Ichmarah Kock ALL RIGHTS RESERVED Acknowledgements Foremost, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor prof. dr. Lex Bosman of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam for his support of my MA thesis research, for his motivation, enthusiasm, guidance and immense knowledge. Additionally, I am also grateful to dr. Madelon Simons for her encouragement and providing useful suggestions about this thesis. I would also like to acknowledge dr. Petra Brouwer of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam as the second reader of this thesis. A special thanks to Helen Lambert and Francis Rugebregt for their supportive input and advice. Finally, words cannot express how profoundly grateful I am to my parents Marcia Kock- de Cuba and Inrich Kock, and my brother Inrich Kock, for their continuous encouragement and their unfailing support through the process of researching and writing this thesis. -

TIPOLOGI BANGUNAN KOLONIAL BELANDA DI SINGARAJA Typology of Dutch Colonial Building in Singaraja
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Forum Arkeologi TIPOLOGI BANGUNAN KOLONIAL BELANDA DI SINGARAJA Typology of Dutch Colonial Building in Singaraja Gendro Keling Balai Arkeologi Bali Jl. Raya Sesetan No. 80 Denpasar 80223 Email: [email protected] Naskah diterima: 06-04-2016; direvisi: 13-06-2016; disetujui: 25-07-2016 Abstract The presence of architecture, both traditional and colonial architecture, has historical and archaeological values and can be regarded as an identity of a city. However, modernization often leaves no place for historical buildings that actually have important roles in shaping the characteristic of place. The aim of this research is to identify the typology or the types of colonial architecture buildings in Singaraja and its characteristics. This research used descriptive- qualitiative method. The data were collected through literature study, observation, and interview. The analysis was done through categorization based on the similarity of types, form, structure, and character of building. The result of this research shows that some of the architectural styles which exist in Singaraja are art deco style, landhuis style, and gothic style. In general, the typologies of colonial buildings in Singaraja are government building, residential building, public infrastructures, etc with relatively small in size and very adaptive to the climate and natural conditions in Indonesia, especially Singaraja. Keywords: architecture, typology, colonial, singaraja. Abstrak Keberadaan arsitektur, baik tradisional maupun kolonial, memiliki nilai historis dan arkeologis dan dapat dianggap sebagai identitas suatu kota. Namun, modernisasi seringkali tidak menyisakan tempat untuk bangunan tua atau bersejarah yang sebenarnya memiliki peran penting dalam pembentukan karakteristik suatu tempat. -

SEJARAH ARSITEKTUR Melalui Visual - Estetik Diorama Dan Litografi Nusantara
SEJARAH ARSITEKTUR Melalui Visual - Estetik Diorama dan Litografi Nusantara YUKE ARDHIATI SEJARAH ARSITEKTUR Melalui Visual-Estetik Diorama dan Litografi Nusantara YUKE ARDHIATI PENERBIT UP2M FTUP JAKARTA Sejarah Arsitektur : Melalui Visual-Estetik Diorama dan Litografi Nusantara Yuke Ardhiati Hak Cipta Yuke Ardhiati Cetakan 20, Mei 2020 Diterbitkan oleh UP2M FTUP Jl. Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah Jakarta 12640 Jakarta Selatan Tel.021- 7864730 email: [email protected] Desain Sampul : Menyunting lukisan Borobudur: Nature in Meditation (2000) karya Srihadi Soedarsono (lahir 1931) Medium lukisan oil in canvas 90 x 100 cm (35.4 x 39.4 in) Perpustakaan Nasional – Katalog Dalam Terbitan Ardhiati, Yuke, Pengantar, Antariksa Sudikno. Jakarta- UP2M FTUP, 2020 Xvi + 148; 15,5 cm x 23 cm ISBN : 978-602-53164-6-3 i Sejarah Arsitektur : Melalui Visual-Estetik Diorama dan Litografi Nusantara Y U K E A R D H I A T I Penerbit: UP2M FTUP Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah Jakarta Selatan ii Cetakan Pertama, 2020 Hak cipta pada penulis. Dilarang menerbitkan ulang atau mengalihmediakan terbitan ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penulis. UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta iii ....Teruntuk Anak Bangsa, yang mencintai karya Arsitektur sebagai ungkapan rasa bersyukur dan cara untuk mencintai kecerdasan Ilahiah yang mewujud dalam sosok rupa lahiriah ... dari sebuah ruang di tengah kesunyian untuk pengisi semesta harapan Jakarta, era pandemic covid-19, 2020 iv Ungkapan terimakasih tak terkatakan, kepada seluruh pribadi mulia, yang ikut menyemai kebajikan, hingga buku ini hadir tersedia, semoga jejak pena ini menginspirasi Anak Bangsa v Kata Pengantar sekaligus Sambutan Dari Pakar Arsitektur Prof. -

The Indis Style: the Transformation and Hybridization of Building Culture in Colonial Java Indonesia
Paramita:Paramita: Historical Historical Studies Studies Journal, Journal, 28 (2),28(2), 2018: 2018 137 -151 ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v28i2.16203 THE INDIS STYLE: THE TRANSFORMATION AND HYBRIDIZATION OF BUILDING CULTURE IN COLONIAL JAVA INDONESIA Djoko Soekiman & Bambang Purwanto Department of History, Faculty of Humanities, Universitas Gadjah Mada ABSTRACT ABSTRAK This historical study is focused on Indis style Kajian sejarah ini difokuskan pada rumah dan houses and buildings in Java during colonial bangunan bergaya Indis di Jawa pada masa period. The study discusses the reception and kolonial. Tulisan ini mendiskusikan tentang adaptation of Dutch and other cultures togeth- resepsi dan adaptasi budaya Belanda dan bu- er with the local cultures in the transformation daya lainnya bersama-sama budaya tempatan and hybridization of Indonesian architectural dalam transformasi dan hibridisasi pada proses design production and reproduction. The produksi dan reproduksi desain arsitektur In- study concludes that Indis style is a proof for donesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa ga- the western inability to avoid the social and ya Indis merupakan bukti dari ketidakmampu- cultural influence of the locals, representations an Barat untuk menghindar dari pengaruh of new hybrid identities who want to show sosial dan kebudayaan tempatan, representasi themselves as closer to the west and distance dari identitas hibrid baru yang ingin menun- from the indigenous, representation of new jukkan dirinya lebih dekat kepada Barat na- identity among those who found a new defi- mun berjarak dari penduduk asli, representas nite motherland since others consider them- dari identitas baru bagi mereka yang selves alien, symbol of modernity for those menemukan ibu pertiwi yang baru ketika ke- who were looking for a new social status and lompok lain menganggap mereka sebagai justify their existence, and a representation of orang asing, simbol modernitas bagi mereka the history of colonialism itself.