Download This PDF File
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Appendix Appendix
APPENDIX APPENDIX DYNASTIC LISTS, WITH GOVERNORS AND GOVERNORS-GENERAL Burma and Arakan: A. Rulers of Pagan before 1044 B. The Pagan dynasty, 1044-1287 C. Myinsaing and Pinya, 1298-1364 D. Sagaing, 1315-64 E. Ava, 1364-1555 F. The Toungoo dynasty, 1486-1752 G. The Alaungpaya or Konbaung dynasty, 1752- 1885 H. Mon rulers of Hanthawaddy (Pegu) I. Arakan Cambodia: A. Funan B. Chenla C. The Angkor monarchy D. The post-Angkor period Champa: A. Linyi B. Champa Indonesia and Malaya: A. Java, Pre-Muslim period B. Java, Muslim period C. Malacca D. Acheh (Achin) E. Governors-General of the Netherlands East Indies Tai Dynasties: A. Sukhot'ai B. Ayut'ia C. Bangkok D. Muong Swa E. Lang Chang F. Vien Chang (Vientiane) G. Luang Prabang 954 APPENDIX 955 Vietnam: A. The Hong-Bang, 2879-258 B.c. B. The Thuc, 257-208 B.C. C. The Trieu, 207-I I I B.C. D. The Earlier Li, A.D. 544-602 E. The Ngo, 939-54 F. The Dinh, 968-79 G. The Earlier Le, 980-I009 H. The Later Li, I009-I225 I. The Tran, 1225-I400 J. The Ho, I400-I407 K. The restored Tran, I407-I8 L. The Later Le, I4I8-I8o4 M. The Mac, I527-I677 N. The Trinh, I539-I787 0. The Tay-Son, I778-I8o2 P. The Nguyen Q. Governors and governors-general of French Indo China APPENDIX DYNASTIC LISTS BURMA AND ARAKAN A. RULERS OF PAGAN BEFORE IOH (According to the Burmese chronicles) dat~ of accusion 1. Pyusawti 167 2. Timinyi, son of I 242 3· Yimminpaik, son of 2 299 4· Paikthili, son of 3 . -

Formen Der Javanischen Pilgerschaft Zu Heiligenschreinen
Formen der javanischen Pilgerschaft zu Heiligenschreinen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Geowissenschaftlichen Fakultät der Albert- Ludwigs- Universität Freiburg i. Br. vorgelegt von Klaus Fuhrmann aus Bad Hersfeld 2000 Referent: Prof. Dr. Seitz Koreferent: Prof. Dr. Käser Dekan: Prof. Dr. Behrmann Tag der Beschlussfassung des Promotionsausschusses: 10.5.2001 INHALT Verzeichnis der Illustrationen...........................................................................................VI Vorwort und Danksagung................................................................................................IX 1 EINLEITUNG ................................................................................................1 1.1 Die Erforschung des Pilgerwesens...........................................................1 1.2 Theoretische Perspektiven.......................................................................2 1.2.1 Das theoretische Modell von Victor Turner....................................................2 1.2.2 Turner-Kritik und neuere Ansätze....................................................................8 1.3 Schriftliche Quellen...............................................................................12 1.4 Zielsetzungen und Textgestaltung............................................................18 1.5 Orthographie, Zitierweise und Personennamen........................................20 1.6 Feldforschungsgeschichte.....................................................................21 2 JAVA: EINE EINFÜHRUNG -

Tracing the Concept of Political Leadership of Islam Nusantara
Journal of Malay Islamic Studies Vol. 1 No. 1, June 2017 TRACING THE CONCEPT OF POLITICAL LEADERSHIP OF ISLAM NUSANTARA Zaki Faddad Faculty of Ushluddin and Islamic Thought Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia E-mail: [email protected] Abstract Certain community both based ethnicities and nationalities have different characteristics on the notion of political leadership. Studies on the political leadership concept in Indonesia cannot escape from the Javanese political leadership characteristics. The reason is simply, because most of Indonesian leaders are from Java. Ben Anderson (1990) sees the Sukarno and Suharto leadership as the representation of Islamic Mataram Kingdom that was absolute and totalitarian typical leadership. Then, it follows cultural stereotyping of political leadership based on ethnicity in Indonesia. Jajat Burhanuddin (2014) sees that Melayu has democratic political culture, while Jawa has authoritarian political culture based on the creed “Manunggaling Kawula Gusti” – Unity between God-ruler or Subject-ruler. However Burhanuddin (2014) does not explain the nature of the creed in Javanese typical political leadership. Naim (2014) controversially sees that there are bipolar characteristics of political leadership in Indonesia. Jawa has absolute and totalitarian typical leadership that is influenced by Javanese local belief; otherwise Melayu (Outside Jawa) has egalitarian and democratic political leadership that is strong influenced by Islamic teaching. This paper tries to dig the understanding of principles on political leadership in Indonesia by making comparison both Jawa and Melayu on the nature of political leadership. The paper engages Talal Asad (2009) conceptual frameworks on discursive tradition. Thus from Asad point of view political leadership is the result of a dynamic process between agency and structure. -

Intervensi Voc Dalam Suksesi Di Istana Mataram 1677-1757
INTERVENSI VOC DALAM SUKSESI DI ISTANA MATARAM 1677-1757 SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Oleh: Mubtadilah NIM:10120095 JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015 HALAMAN MOTTO “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” [(Qs Al Baqarah : 153)] Tetaplah Tersenyum, Tetaplah Berusaha Dalam Keadaan Apapun Selalu Berikan Manfaat Untuk Orang-orang Disekitar Kita dan Jangan Segan untuk Membantu dan Memberikan Pertolongan Kepada yang Membutuhkan (mubta) Sebaik-baiknya Manusia Adalah Manusia yang Paling Banyak Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain iv HALAMAN PERSEMBAHAN Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan karya ini untuk: Almamater tercinta Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ayahanda Tercinta Bapak Barokah, Ibunda tercinta Ibu Taslimah, dan Keluarga Besar Tercinta v ABSTRAK Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada 1585, mencapai puncak kejayaannya pada rentang 1613 hingga 1677, dengan cakupan wilayah di barat mencapai perbatasan Banten dan Jakarta saat ini, hingga selat Bali di timur. Pada saat yang sama VOC dari daratan Eropa mulai datang untuk mengadakan kontak dagang dengan negara-negara di Nusantara, termasuk Mataram. VOC yang sebenarnya hanya membutuhkan beras untuk logistik dan kayu untuk transportasi serta garam, kemudian mengambil permusuhan dengan Mataram setelah penyerangan yang dilakukan Sultan Agung dengan mengepung kantor pusat VOC di Batavia pada 1628-1629, namun setelah tahun 1677 atau setelah terjadi pemberontakan Trunojoyo, maka Mataramlah yang kemudian merapat pada VOC karena terpikat oleh militernya yang kuat pada waktu itu. -

Variasi Genetika Lokus STR Codis (THO1,TPOX) Pada Temuan
“KOTA LAMA SEMARANG” SITUS SEJARAH YANG TERPINGGIRKAN “OLD CITY OF SEMARANG” THE ABANDONED HISTORICAL SITE Ika Dewi Retno Sari SMA 14 Semarang ABSTRACT The existence of Semarang city as a trading town on the north coast of Java had been going on since the founding of Old Mataram Kingdom and continues to grow, until the period of Dutch colonial rule. The rapid development as a city of Semarang in the Dutch colonial period was marked by the establishment of the buildings at the site which is now called Semarang Old Town. Most of these buildings serve as offices and private VOC trade. Over time, Semarang became not only a trading center but it evolved into a gemeente (municipality), up to the present period. Nevertheless, there seems to be lack of interest in making the history of Semarang as a subject in teaching history at the local level, especially in educational circles, as the subject matter in teaching history. As a source of considerable historical importance, there is nothing wrong if a teacher of History, especially in the city of Semarang, making the Old City as a source of learning for students in the city of Semarang. Therefore the existence of sites as well as historical buildings in the city of Semarang is should no longer simply regarded as old buildings that have without meaning. And at least it will foster public awareness of Semarang city, especially among students to participate in regard to keep the existence of the Old Town and make it as an asset of History and Tourism in the city of Semarang. -

State and the Statecract of the Centrals of Government Mataram Islam Kingdom in Java
IJSS.Vol.12, No.2, September 2016 STATE AND THE STATECRACT OF THE CENTRALS OF GOVERNMENT MATARAM ISLAM KINGDOM IN JAVA HY. Agus Murdiyastomo3 Abstract This study is aimed to examine the dynamic of Islamic Mataram kingdom, focusing more on administrative system in Islam Mataram. This research used the five stages historical research method according to Kuntowijoyo, which are topic selection, heuristic, verification, interpretation and writing. Panembahan Senopati defeated Pajang and built a palace in Kotagede which later was used by Mataram kings until their peak of glory under Sultan AgungHanyakrakusuma. However the defeat of Mataram from VOC caused them to lose their ground, moreover after Sultan AgungHanyakrakusuma deceased. His successor, Amangkurat I think that Kotagede as the central of economic activities considered to be no longer suitable for the central of government. Therefore he ordered to move the palace from Kotagede to Pleret. Raden Mas Rahmat, as ‘Amangkurat II’, didn’t want to go back to Pleret because it had been taken by Puger Prince, and then built new palace in Kartasura. Amangkurat III escaped to the east when Kartasura was taken. But this palace would also be abandoned later, and moved to Surakarta when Pakubuwono II ruled the place. Mataram moved its government four times, from Kotagede, Plered, Kartasura, and lastly, Surakarta. Keywords: government, Islamic Mataram. 3 Yogyakarta State University. Email: [email protected] 31 HY. Agus Murdiyastomo:State and The Statecrac of the Centrals.... Introduction During the Islam period in Indonesia, many Initially Islam Mataram Kingdom had cities used territories in coastal area, such as the capital city in Kota Gede, 6 km far to the Samudra Pasai, Demak, Banten, and Makassar. -

Sejarah Dan Arkeologi Madura·Barat Abad XIV-XVIII: Sebuah Pengenalan Tentang Penguasanya
Sejarah Dan Arkeologi Madura·Barat Abad XIV-XVIII: Sebuah Pengenalan Tentang Penguasanya Lucas Partanda Koestoro Keywords: heritage, Madura, artifact, ethnography, history, culture How to Cite: Koestoro, L. P. Sejarah Dan Arkeologi Madura·Barat Abad XIV-XVIII: Sebuah Pengenalan Tentang Penguasanya. Berkala Arkeologi, 15(2), 45–61. https://doi.org/10.30883/jba.v15i2.660 Berkala Arkeologi https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/ Volume 15 No. 2, 1995, 45-61 DOI: 10.30883/jba.v15i2.660 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. SEJARAH DAN ARKEOLOGI MADURA·BARAT ABAD XIV-XVIII: Sebuah Pengenalan Tentang Penguasanya Lucas Partanda Koestoro (Balai Arkeologi Yogyakarta) 1. Pengantar Selat Madura yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura sejak dulu digunakan sebagai lalu lintas pelayaran yang menghubung kan bagian barat dan bagian timur Nusantara. Berdasarkan hal itu, maka Selat Madura berfungsi sebagai jalur simpang dari jalur pokok pelayaran tradisional • yang membentang dari Laut Jawa ke timur. Dengan demikian, Selat Madura tidak hanya berperan sebagai jalur perdagangan laut melainkan digunakan pula sebagai jalur perluasan kekuasaan politik, penyebaran agama, dan kebudayaan Peninggalan kepurbakalaan d1 Pulau Madura bag1an barat, meru pakan hasil budaya pada masanya. Peninggalan-peninggalan itu sebagian besar berupa makam dan yang lainnya --yang sekarang ha nya tersisa namanya saja-- lebih dikenal sebagai bekas lokasi pusat pemerintahan yang berupa kraton. Di antara makam-makam itu yang terkenal antara lain Makam Aermata lbu, Pasarean Makam Agung, Ma kam Agung Blega, dan Makam Sultan. Sementara itu, nama tempat yang dikaitkan dengan pusat-pusat kekuasaan Madura Barat ''tempo dulu" adalah Madegan, Palakaran, Tonjung, Sembilangan, dan Bangkalan. -
The Role of Jayengrana in the Golek Rod Puppet Show During Javanese Succession War Sri Wahyuning Septarina1*, I Nyoman Artayasa2
International Journal of Culture and Art Studies (IJCAS) Vol. 04, No. 2, 2020 | 39 – 43 IJCAS International Journal of Culture and Art Studies The Role of Jayengrana in the Golek Rod Puppet Show During Javanese Succession War Sri Wahyuning Septarina1*, I Nyoman Artayasa2 1,2, Program Studi Seni, Program Doktor Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Indonesia. Abstract. The second Javanese succession war began after Pakubuwono I and the Company won the first Javanese succession war. Jayengrana struggling together with the descendants of the Sultan of Mataram succeeded in making Pakubuwono I. anxious. The second Javanese succession war illustrated the spirit of the struggle of the son of Untung Surapati in fighting for truth and justice. The two problems discussed in this article are to make objective reconstruction of the past. Second, how the influence of Islam on the kingdoms in Java. The author collects and enforces facts to get a conclusion in a scary show. The study method includes qualitative analysis, the historical approach of Karl Marx, and F. Engels's perspective in understanding history as a past event. Keyword: Jayengrana, Golek Puppet Show, Javanese Received 02 June 2020 | Revised 03 June 2020 | Accepted 29 October 2020 1 Introduction The Javanese Succession War is often called the Javanese throne war or civil war in the struggle for the throne in Sultan Agung's descendants. The war which lasted for 12 years was not just a long history. Still, the cost and the number of victims was fantastic, nearly two million Javanese or as many as one-third of the entire population experienced destruction. -

Cirebon Di Bawah Kekuasaan Mataram Tahun 1613 – 1705 : Kajian Historis Mengenai Hubungan Politik, Sosial Dan Agama
CIREBON DI BAWAH KEKUASAAN MATARAM TAHUN 1613 – 1705 : KAJIAN HISTORIS MENGENAI HUBUNGAN POLITIK, SOSIAL DAN AGAMA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Oleh: Moh. Rahmat Hidayat NIM. 1110022000020 PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H / 2017 M Lembar Pernyataan Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 22 Maret 2017 Moh Rahmat Hidayat Dedikasi “ Teruntuk Bapak Drs. H. Ahmad Sholeh, M.Pd.I dan Ibu Dra. Hj. Syamkhiyah, Maulana Syafaat dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan Skripsi ini” “Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.” iv UCAPAN TERIMA KASIH Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak penulis temui rintangan dan hambatan. Sungguh pun begitu Alhamdulillah atas kerja keras semangat dan dukungan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. -

Overview of Diplomatic Letters
Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically and Chronologically by Diplomat Region: Africa Egypt Location: Cairo Diplomat Name Alternative names Hekimo ğlu Ali Pasha Grand Vizier Hekimo ğlu Ali Pasha Period (from/to): 1756- 1757 Historically known?Y Number of letters: 1 Ethiopia Location: Addis Ababa Diplomat Name Alternative names Iyasu I Joshua I Period (from/to): 1682- 1706 Historically known?Y Number of letters: 3 Location: Gondar Diplomat Name Alternative names Yohannes I A'ilaf Sagad Period (from/to): 1667- 1682 Historically known?Y Number of letters: 1 South Africa Location: Cape of Good Hope Diplomat Name Alternative names Sultan Abdul Bashir (exile) Period (from/to): 1700- 1701 Historically known?Y Number of letters: 2 www.sejarah-nusantara.anri.go.id - ANRI TCF 2015 Page 1 of 224 Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically and Chronologically by Diplomat Raden Suryakasuma Saloringpasar Period (from/to): 1722- 1726 Historically known?N Number of letters: 5 Not to be confused with the son of Pakubuwono I Son of Damala Daeng Mamongon Period (from/to): 1741- 1741 Historically known?N Number of letters: 1 Kaicili Putra Ahmad Period (from/to): 1786- 1786 Historically known?N Number of letters: 1 Location: Robben Island Diplomat Name Alternative names Raja Christofeel Manoppo Raja Bolaang Period (from/to): 1773- 1773 Historically known?N Number of letters: 1 Region: East Asia China Location: Amoy Diplomat Name Alternative names Bu Yuan of Xiamen Period (from/to): 1688- 1688 Historically known?N Number of letters: 2 -
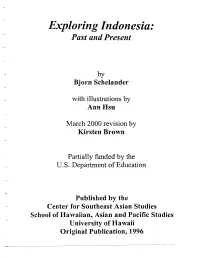
Exploring Indonesia.Pdf
Exploring Indonesia: Past and Present by Bjorn Schelander with illustrations by Ann Hsu IV[arch 2000 revision by Kirsten Brown Partially funded by the U.S. Department ofEducation Published by the Center for Southeast Asian Studies School of Ha-vvaiian, Asian and Pacific Studies IJniversity of Hawaii Original Publication, 1996 The Center for Southeast Asian Studies School of Hawaiian. Asian and Pacific Studies University of Hawai'i Honolulu, Hawai'j Copyright © Center for Southeast Asian Studies Table of Contents PREFACE CHAPTERl 1 INTRODUCTION TO THE LM'DS AND PEOPLES OF INDONESIA 1 THE GEOGRAPHY OF INDONESIA 1 The Southeast Asian Setting. 2 The Major Island Groups of Indonesia 3 The "Ring ofFire" 5 Climate 6 Fauna and Flora 8 Resources and Land Use 11 THE PEOPLE AND CULTURES OF INDONESIA 14 Major Ethnic Groups ofIndonesia 20 Languages and Dialects 26 Patterns ofReligious Beliefs 28 Music, Arts, and Crafts 32 Food and Drink 39 The Cycle ofLife 41 Summary: 43 EXERCISES 44 CHAPTER 2 49 EARLY INDONESIAN SOCIETIES 49 THE SOURCES OF EARLY INDONESIAN HISTORY 50 Linguistic Evidence 51 Early Inscriptions and Chronicles 52 Ethnographic Evidence: Studying Present-day Societies 53 Legends and Folk Tales 55 Accounts from Foreign Traders and Rulers 57 Weighing the Evidence 59 EARLY FOREIGN CONTACTS 61 China 61 India 62 Madagascar, Malaysia, and the Philippines 64 EARLY INDONESIAN EMPIRES 65 Srivijaya 65 Shailendra 70 Mataram 71 Majapahit 74 EXERCISES 76 CHAPTER 3 83 THE DEVELOPMENT OF THE SPICE TRADE AND THE COMING OF ISLAM 83 THE RISE OF MELAKA 83 THE WORLD OF SOUTHEAST ASIAN TRADE 84 The Spread ofMalay 87 The Spread ofIslam 88 THE WORLD OF INDONESIA IN THE SIXTEENTH CENTURY 92 EUROPEAN PARTICIPATION IN THE ASIAN TRADE ROUTES 97 Economic Motives: 97 Scientific Advances: 99 Religious Motives: 100 Portuguese Presence in Southeast Asia. -

Dominasi Kekuasaan Amangkurat I Dalam Pertunjukan Kethoprak Lakon Rembulan Wungu Karya Bondan Nusantara
DOMINASI KEKUASAAN AMANGKURAT I DALAM PERTUNJUKAN KETHOPRAK LAKON REMBULAN WUNGU KARYA BONDAN NUSANTARA SKRIPSI Oleh: Nurulia Sarawati NIM 14124124 FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 2019 i DOMINASI KEKUASAAN AMANGKURAT I DALAM PERTUNJUKAN KETHOPRAK LAKON REMBULAN WUNGU KARYA BONDAN NUSANTARA SKRIPSI Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Seni Teater Jurusan Pedalangan Oleh: Nurulia Sarawati NIM 14124124 FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 2019 i ii PERSEMBAHAN Ku persembahkan karya ini untuk Tuhan Yang Maha Esa Bapak dan ibu tercinta (Ibu Suji dan Bapak Suparno), adik laku- lakiku (Fandi) dan Agus Triono, merekalah yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan bagi penulis sehingga karya ini selesai dengan baik. Teman–teman angkatan 2014, yang telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis dalam suka maupun duka. Prodi Seni Tetaer ISI Surakarta yang telah memberikan pengalaman kehidupan yang berharga bagi penulis. iii MOTTO “Jadikanlah ilmumu sebagai petunjuk untuk keberkahan kehidupanmu” -Ibu Suji- “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” -Nelson Mandela- “Pada kaum muda kita menitip masa depan, jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam” -Najwa Shihab- “Kesempurnaan hanya milik Tuhan” -Nurulia Sarawati- iv PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Nurulia Sarawati NIM : 14124124 Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 15 November 1995 Alamat :.Dalon, Rt 01/ Rw 11, Jaten, Karanganyar Program Studi : Seni Teater Fakultas : Seni Pertunjukan Menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “Dominasi Kekuasaan Amangkurat I dalan Kethoprak Lakon Renmbulan Wungu Karya Bondan Nusantara” adalah benar–benar hasil karya cipta sendiri, saya buat dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan jiplakan (plagiasi).