1 Eksistensi Tanah Eks Swapraja
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta
110?0'0"E 110?12'0"E 110?24'0"E 110?36'0"E 110?48'0"E 111?0'0"E WINDUSARI SECANG SIMO KARANGMALANG Mt. Merbabu BabadanNOGOSARI Tempuredj KALIWUNGU PLUPUH KALIWIRO KALIANGKRIK Magelang JAWA TENGAH AMPEL SAMBI KALIJAMBE SAPURAN BANDONGAN TEGALREJO MASARAN SRAGEN PAKIS GONDANGREJO KEDAWUNG WONOSOBO MAGELANG SELATAN Banjumari SELO Ranousari CEPOGO NGEMPLAK Djambangan CANDIMULYO SAWANGAN BOYOLALIBojolali KEBAKKRAMAT KEPIL KAJORAN Gatakan Mt. Merapi COLOMADUBANJARSARI WADASLINTANG BANYUDONO KERJO MARTOYUDAN DUKUN TERAS JEBRES TEMPURAN BOYOLALI Kartosuro MOJOGEDANG MAGELANGMUNTILAN KARTASURA MUSUK MOJOSONGO LAWEYAN Surakarta TASIKMADU BRUNO Broena SRUMBUNG SAWIT JATEN PASAR KLIWON KARANGANYAR GATAK SALAMAN Balaboedoer Srumbung TULUNG SERENGAN PITURUH MOJOLABAN BENER MUNGKID KARANGANYAR Bener KEMALANG POLANHARJO KARANGPANDAN 7?36'0"S 7?36'0"S SALAM WONOSARI BAKI GROGOL GEBANG BOROBUDUR TURI CANGKRINGAN Bandjarsari DELANGGU Pablengan JATINOM MATESIH KEMIRI Bedojo Pangkalan POLOKARTO NGLUWAR KARANGANOM PAKEM SUKOHARJO JUMANTONO TEMPEL KARANGNONGKONGAWEN JUWIRING Kemiri LOANO Kaliredjo Bangsri Koeangsan MANISRENGGO CEPER BENDOSARI KALIBAWANGSAMIGALUH SLEMAN KLATEN SLEMAN PEDAN SUKOHARJO Purworedjo Purworejo NGAGLIK NGEMPLAK KEBONARUM Klaten KARANGDOWO JUMAPOLO PURWOREJOBAYAN Sleman PURWOREJO JOGONALAN KALIKOTES KUTOARJO KALIGESING SEYEGAN TAWANGSARI Belang MINGGIR PRAMBANANKLATEN SELATAN TRUCUK BUTUH MLATI NGUTER NANGGULAN KALASAN KLATEN TENGAH Cawas Karangasem JATIPURO Purworejo Kutu Kalasan BANYU URIP Naggulan CAWAS GODEAN DEPOK WEDI MOYUDAN JETIS -

Perspectives of Research for Intangible Cultural Heritage
束 9mm Proceedings ISBN : 978-4-9909775-1-1 of the International Researchers Forum: Perspectives Research for Intangible Cultural Heritage towards a Sustainable Society Proceedings of International Researchers Forum: Perspectives of Research for Intangible Cultural Heritage towards a Sustainable Society 17-18 December 2019 Tokyo Japan Organised by International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), National Institutes for Cultural Heritage Agency for Cultural Affairs, Japan Co-organised by Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, National Institutes for Cultural Heritage IRCI Proceedings of International Researchers Forum: Perspectives of Research for Intangible Cultural Heritage towards a Sustainable Society 17-18 December 2019 Tokyo Japan Organised by International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), National Institutes for Cultural Heritage Agency for Cultural Affairs, Japan Co-organised by Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, National Institutes for Cultural Heritage Published by International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), National Institutes for Cultural Heritage 2 cho, Mozusekiun-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-0802, Japan Tel: +81 – 72 – 275 – 8050 Email: [email protected] Website: https://www.irci.jp © International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI) Published on 10 March 2020 Preface The International Researchers Forum: Perspectives of Research for Intangible Cultural Heritage towards a Sustainable Society was organised by the International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI) in cooperation with the Agency for Cultural Affairs of Japan and the Tokyo National Research Institute for Cultural Properties on 17–18 December 2019. -

Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Diponegoro University Institutional Repository PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA SENI BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA) TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Oleh : Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH B4A 007 100 Pembimbing : Dr. BUDI SANTOSO, S.H., MS PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009 HALAMAN PENGESAHAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA SENI BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA) TESIS Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Oleh : Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH NIM. B4A 007 100 Tesis dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak Mengetahui, Pembimbing Ketua Program Magister Ilmu Hukum Dr. Budi Santoso, S.H., MS Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., MH NIP. 131 631 876 NIP. 130 531 702 HALAMAN PENGUJIAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA SENI BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA) Disusun Oleh : RINDIA FANNY KUSUMANINGTYAS, SH NIM. B4A 007 100 Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 25 Maret 2009 Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Mengetahui, Pembimbing Ketua Program Magister Ilmu Hukum Dr. Budi Santoso, S.H., MS Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., MH NIP. 131 631 876 NIP. 130 531 702 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadiratan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis yang sederhana ini dengan judul ”Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)”. -

REVITALIZATION MODEL of ETHNIC SETTLEMENT to PRESERVE CULTURAL HERITAGE and SUPPORT TOURISM in SURAKARTA by Dra
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq REVITALIZATION MODEL OF ETHNIC SETTLEMENT TO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiPRESERVE CULTURAL HERITAGE AND SUPPORT TOURISM IN SURAKARTA opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgby Dra. Sariyatun, M.Pd, M.Hum. hjklzxcvbnmqwerLecturer at History Educationtyuiopasdfghjklzxc Department [Jurusan Pendidikan Sejarah] –Faculty of Educational Sciences, Sebelas Maret University [FKIP-UNS] vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [email protected] wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui[2009] opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz REVITALIZATION MODEL OF ETHNIC SETTLEMENT TO PRESERVE CULTURAL HERITAGE AND SUPPORT TOURISM IN SURAKARTA by Dra. Sariyatun, M.Pd, M.Hum Lecturer at History Education Department [Jurusan Pendidikan Sejarah] –Faculty of Educational Sciences, Sebelas Maret University [FKIP-UNS] [email protected] ABSTRACT The main aim of this research is to formulate a revitalizing model of ethnic settlement through interpretation to preserve cultural heritage and support community-based tourism in Surakarta. It is a qualitative research which uses primary and secondary sources. The research data is gathered by in-depth interviews, guided group discussion, -

Dinaspu Report Renja
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KOTA JAMBI NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator kode Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif 1.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran 1.01.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan 52,500,000 APBDKOTA 55,125,000 Perizinan 1.01.03.01.01.02 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi 480,690,000 APBDKOTA 504,724,500 Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.03.01.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 3,065,797,350 APBDKOTA 3,219,087,218 Aset 1.01.03.01.01.04 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga 220,000,000 APBDKOTA 231,000,000 Administrasi/Teknis Perkantoran 1.01.03.01.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang 84,000,000 APBDKOTA 88,200,000 Cetakan dan Penggandaan 1.01.03.01.01.06 Penyediaan Makanan dan Minuman 21,000,000 APBDKOTA 22,050,000 1.01.03.01.01.07 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan 488,250,000 APBDKOTA 512,662,500 Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor 1.01.03.01.01.09 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi 700,000,000 APBDKOTA 735,000,000 Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional 1.01.03.01.01.10 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi 420,000,000 APBDKOTA 420,000,000 Gedung/Bangunan Utilitas Kantor 1.01.03.01.02 -

POLITIK KOLONIAL DAN PERKEMBANGAN SENI TARI DI PURO PAKUALAMAN PADA MASA PEMERINTAHAN PAKU ALAM IV (1864-1878) Oleh : HY
POLITIK KOLONIAL DAN PERKEMBANGAN SENI TARI DI PURO PAKUALAMAN PADA MASA PEMERINTAHAN PAKU ALAM IV (1864-1878) Oleh : HY. Agus Murdiyastomo ABSTRAK Pusat budaya di Yogyakarta selama ini yang lebih banyak diketahui oleh masyarakat adalah Kraton Kasultanan Yogyakarta, tetapi sesungguhnya selain Kraton Kasutanan masih terdapat pusat budaya yang lain yaitu Pura Paku Alaman. Di Kadipaten telah terlahir tokoh-tokoh yang sangat memperhatikan kelestarian budaya Jawa khususnya seni tari tradisi. Salah satunya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam IV, yang pada masa ia berkuasa, budaya Barat yang dibawa oleh kaum kolonialis melanda daerah jajahan. Hadirnya budaya asing tentu sulit untuk ditolak. Namun demikian denga piawainya KGPAA Paku Alam IV, justru mengadopsi budaya Barat, tetapi ditampilkan dengan rasa dan estetika Jawa, dalam bentuk tari klasik. Sehingga pada masanya lahir repertoar tari baru yang memperkaya seni tari tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perkembangan seni tari di Pura Pakualaman pada masa pemerintahan KGPAA Paku Alam IV, dan hal-hal apa yang melatarbelakangi penciptaannya. Dalam rangka mewujudkan rekonstruksi ini dilakukan dengan metode sejarah kritis, yang tahapannya meliputi Pertama, Heuristik, atau pencarian dan pengumpulan sumber data sejarah, yang dalam hal ini dilakukan di BPAD DIY, dan di Perpustakaan Pura Pakualaman. Di kedua lembaga tersebut tersimpan arsip tentang Paku Alaman, dan juga naskah- naskah yang berkaitan dengan penciptaan tari. Kedua, Kritik, atau pengujian terhadap sumber-sumber yang terkumpul, sumber yang telah terkumpul diuji dari segi fisik untuk memperoleh otentisitas, kemudian membandingkan informasi yang termuat dengan informasi dari sumber yang berbeda, untuk memperoleh keterpercayaan atau kredibilitas. Ketiga, Interpretasi yaitu informasi yang ada dikaji untuk diangkat fakta-fakta sejarahnya, yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kisah sejarah. -

ISLAMIC NARRATIVE and AUTHORITY in SOUTHEAST ASIA 1403979839Ts01.Qxd 10-3-07 06:34 PM Page Ii
1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page i ISLAMIC NARRATIVE AND AUTHORITY IN SOUTHEAST ASIA 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page ii CONTEMPORARY ANTHROPOLOGY OF RELIGION A series published with the Society for the Anthropology of Religion Robert Hefner, Series Editor Boston University Published by Palgrave Macmillan Body / Meaning / Healing By Thomas J. Csordas The Weight of the Past: Living with History in Mahajanga, Madagascar By Michael Lambek After the Rescue: Jewish Identity and Community in Contemporary Denmark By Andrew Buckser Empowering the Past, Confronting the Future By Andrew Strathern and Pamela J. Stewart Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation By Daniel Martin Varisco Islam, Memory, and Morality in Yemen: Ruling Families in Transition By Gabrielle Vom Bruck A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java By Ronald Lukens-Bull The Road to Clarity: Seventh-Day Adventism in Madagascar By Eva Keller Yoruba in Diaspora: An African Church in London By Hermione Harris Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century By Thomas Gibson 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page iii Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia From the 16th to the 21st Century Thomas Gibson 1403979839ts01.qxd 10-3-07 06:34 PM Page iv ISLAMIC NARRATIVE AND AUTHORITY IN SOUTHEAST ASIA © Thomas Gibson, 2007. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. First published in 2007 by PALGRAVE MACMILLAN™ 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. -
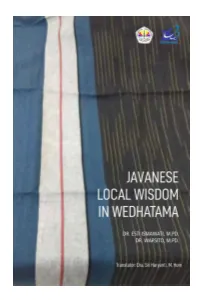
Javanese Local Wisdom in Wedhatama
i ii JAVANESE LOCAL WISDOM IN WEDHATAMA PART I iii Laws of the republic of Indonesia No.19 of 2002 concerning Copyright Copyright Scope 1. Copyright is an exclusive right for an Author or a Copyright Holder to announce or reproduce his Work, which arises automatically after a work is born without reducing restrictions in accor- dance with applicable laws and regulations. Criminal Provisions 1. Anyone who intentionally or without the right to commit acts as referred to in Article 2 para- graph (1) or Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) shall be sentenced to a minimum impris- onment of 1 (one) month each and / or a minimum fine Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah), or a maximum imprisonment of 7 (seven) years and / or a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). 2. Anyone who intentionally broadcasts, exhibits or sells to the public a Work or goods resulting from infringement of Copyright or Related Rights as referred to in paragraph (1) shall be sen- tenced to a maximum of 5 years and / or a maximum fine of Rp. 5.00,000,000.00 (five hundred million rupiah). iv JAVANESE LOCAL WISDOM IN WEDHATAMA PART I DR. ESTI ISMAWATI, M.PD DR. WARSITO, M.PD TRANSLATOR: DRA. SRI HARYANTI, M.HUM v First published 2021 by Gambang Buku Budaya Perum Mutiara Palagan B5 Sleman-Yogyakarta 55581 Phone: +62 856-4303-9249 All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission inwriting from the publishers. -
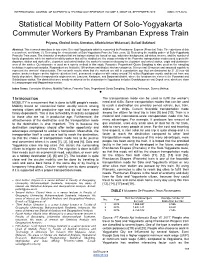
Statistical Mobility Pattern of Solo-Yogyakarta Commuter Workers by Prambanan Express Train
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 09, SEPTEMBER 2019 ISSN 2277-8616 Statistical Mobility Pattern Of Solo-Yogyakarta Commuter Workers By Prambanan Express Train Priyono, Choirul Amin, Umrotun, Afiotria Intan Wulansari, Suliadi Sufahani Abstract: This research was done in two cities; Solo and Yogyakarta which is connected by Prambanan Express (Prameks) Train. The objectives of this research are as follows: (1) Reviewing the characteristic of Solo-Yogyakarta Prameks Train users, (2) Reviewing the mobility pattern of Solo-Yogyakarta Prameks Train users. The character of workers that are being reviewed are based on age, education background, job status, income, and the number of family dependents, while the worker‘s mobility pattern that will be studied are: the usage intensity of the Prameks, transportation modes used to go to the departure station and work office, departure and arrival station, the worker‘s reason in choosing the departure and arrival station, origin and destination area of the worker. Questionnaire is used as a survey method in this study. Purposive Proportional Quota Sampling is also used as the sampling technique to gathered samples. Respondent are limited to 100 workers and divided into two categories; 50 men and 50 women and assumed capable to represent the workers‘ characteristic. The research results show that the workers are still in a productive age that are dominated by 21-25-year-old worker, bachelor degree as the highest education level, permanent employees with salary around 3-6 million Rupiah per month, and do not have any family dependent. Most of respondent‘s origin area are Laweyan, Kartosuro, and Banjarsari district, where the locations are closer to the Purwosari and Solobalapan station. -

Appendix Appendix
APPENDIX APPENDIX DYNASTIC LISTS, WITH GOVERNORS AND GOVERNORS-GENERAL Burma and Arakan: A. Rulers of Pagan before 1044 B. The Pagan dynasty, 1044-1287 C. Myinsaing and Pinya, 1298-1364 D. Sagaing, 1315-64 E. Ava, 1364-1555 F. The Toungoo dynasty, 1486-1752 G. The Alaungpaya or Konbaung dynasty, 1752- 1885 H. Mon rulers of Hanthawaddy (Pegu) I. Arakan Cambodia: A. Funan B. Chenla C. The Angkor monarchy D. The post-Angkor period Champa: A. Linyi B. Champa Indonesia and Malaya: A. Java, Pre-Muslim period B. Java, Muslim period C. Malacca D. Acheh (Achin) E. Governors-General of the Netherlands East Indies Tai Dynasties: A. Sukhot'ai B. Ayut'ia C. Bangkok D. Muong Swa E. Lang Chang F. Vien Chang (Vientiane) G. Luang Prabang 954 APPENDIX 955 Vietnam: A. The Hong-Bang, 2879-258 B.c. B. The Thuc, 257-208 B.C. C. The Trieu, 207-I I I B.C. D. The Earlier Li, A.D. 544-602 E. The Ngo, 939-54 F. The Dinh, 968-79 G. The Earlier Le, 980-I009 H. The Later Li, I009-I225 I. The Tran, 1225-I400 J. The Ho, I400-I407 K. The restored Tran, I407-I8 L. The Later Le, I4I8-I8o4 M. The Mac, I527-I677 N. The Trinh, I539-I787 0. The Tay-Son, I778-I8o2 P. The Nguyen Q. Governors and governors-general of French Indo China APPENDIX DYNASTIC LISTS BURMA AND ARAKAN A. RULERS OF PAGAN BEFORE IOH (According to the Burmese chronicles) dat~ of accusion 1. Pyusawti 167 2. Timinyi, son of I 242 3· Yimminpaik, son of 2 299 4· Paikthili, son of 3 . -

SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY in the NEW ORDER a Thesis Presented to the Faculty of the Center for Inte
SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER A thesis presented to the faculty of the Center for International Studies of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Sony Karsono August 2005 This thesis entitled SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER by Sony Karsono has been approved for the Department of Southeast Asian Studies and the Center for International Studies by William H. Frederick Associate Professor of History Josep Rota Director of International Studies KARSONO, SONY. M.A. August 2005. International Studies Setting History Straight? Indonesian Historiography in the New Order (274 pp.) Director of Thesis: William H. Frederick This thesis discusses one central problem: What happened to Indonesian historiography in the New Order (1966-98)? To analyze the problem, the author studies the connections between the major themes in his intellectual autobiography and those in the metahistory of the regime. Proceeding in chronological and thematic manner, the thesis comes in three parts. Part One presents the author’s intellectual autobiography, which illustrates how, as a member of the generation of people who grew up in the New Order, he came into contact with history. Part Two examines the genealogy of and the major issues at stake in the post-New Order controversy over the rectification of history. Part Three ends with several concluding observations. First, the historiographical engineering that the New Order committed was not effective. Second, the regime created the tools for people to criticize itself, which shows that it misunderstood its own society. Third, Indonesian contemporary culture is such that people abhor the idea that there is no single truth. -

Terrorism in Indonesia: Noordin’S Networks
TERRORISM IN INDONESIA: NOORDIN’S NETWORKS Asia Report N°114 – 5 May 2006 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... i I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 II. THE MARRIOTT BOMBING NETWORKS ............................................................. 2 A. THE LUQMANUL HAKIEM SCHOOL........................................................................................2 B. THE LEFTOVER EXPLOSIVES .................................................................................................3 C. THE NGRUKI LINKS...............................................................................................................3 D. THE FINAL TEAM ..................................................................................................................4 III. THE AUSTRALIAN EMBASSY BOMBING ............................................................. 5 A. THE EAST JAVA NETWORK ....................................................................................................5 B. THE JI SCHOOL NETWORK IN CENTRAL JAVA .......................................................................7 C. THE NETWORK THUS FAR.....................................................................................................9 D. FAMILY AND BUSINESS IN WEST JAVA..................................................................................9 E. MOBILISING THE NETWORK