1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Konteks Penelitian Tanah Sunda Yang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
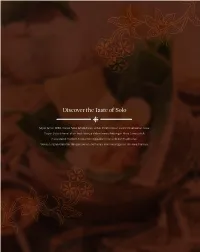
Discover the Taste of Solo
Discover the Taste of Solo Sejak tahun 1988, Dapur Solo berdedikasi untuk melestarikan kuliner tradisional Jawa. Dapur Solo dikenal akan keahliannya dalam kreasi hidangan khas Jawa untuk masyarakat modern, tanpa meninggalkan nilai unik dan tradisional. Seluruh sajian dimasak dengan penuh perhatian akan keunggulan dan keasliannya. KHAS SOLO 01 01. Nasi Urap Solo 40,5 Nasi, sayuran urapan dengan rasa sedikit pedas, pilihan lauk ayam / empal goreng, tempe bacem Dengan nasi kuning +1.000 02. Nasi Langgi Solo 41,5 Nasi langgi kuning khas Solo yang disajikan dengan ayam / empal goreng, terik daging, sambal goreng kentang, abon sapi, telur dadar tipis, serundeng kelapa, kering kentang, lalap serta kerupuk udang dan sambal Dengan nasi putih 40.500 02 04 03. Nasi Langgi Si Kecil 30,5 Nasi kuning dengan pilihan ayam goreng, abon sapi, telur dadar tipis dan kerupuk udang 04. Nasi Liwet Solo 40,5 Nasi gurih dengan suwiran ayam kampung, telur pindang, tempe bacem dan potongan ati ampela ayam disiram dengan sayur labu dengan rasa gurih sedikit pedas Menu favorit Menu pilihan anak 05 06 05. Lontong Solo 40,8 Lontong yang disiram dengan kuah opor kuning lengkap dengan suwiran ayam, telur pindang dan sambal goreng kentang 06. Timlo Solo 37,5 Sop kuah bening berisi sosis Solo, suwiran ayam, dan telur pindang 07. Selat Solo 41 Perpaduan daging semur yang manis dan mustard yang asam serta sayuran, menghasilkan cita rasa perpaduan dua budaya Jawa dan Belanda 07 Menu favorit Menu pilihan anak NUSANTARA 01 01. Nasi Timbel Sunda 42 Nasi timbel dengan pilihan lauk ayam / empal goreng, sayur asem, ikan asin, tempe bacem serta disajikan dengan kerupuk udang, lalap dan sambal 02 02. -

Microorganisms in Fermented Foods and Beverages
Chapter 1 Microorganisms in Fermented Foods and Beverages Jyoti Prakash Tamang, Namrata Thapa, Buddhiman Tamang, Arun Rai, and Rajen Chettri Contents 1.1 Introduction ....................................................................................................................... 2 1.1.1 History of Fermented Foods ................................................................................... 3 1.1.2 History of Alcoholic Drinks ................................................................................... 4 1.2 Protocol for Studying Fermented Foods ............................................................................. 5 1.3 Microorganisms ................................................................................................................. 6 1.3.1 Isolation by Culture-Dependent and Culture-Independent Methods...................... 8 1.3.2 Identification: Phenotypic and Biochemical ............................................................ 8 1.3.3 Identification: Genotypic or Molecular ................................................................... 9 1.4 Main Types of Microorganisms in Global Food Fermentation ..........................................10 1.4.1 Bacteria ..................................................................................................................10 1.4.1.1 Lactic Acid Bacteria .................................................................................11 1.4.1.2 Non-Lactic Acid Bacteria .........................................................................11 -

Khazanah Sajian Nusantara Buffet Dinner Menu a 2019
Khazanah Sajian Nusantara Buffet Dinner Menu A 2019 RAMPAIAN PEMBUKA SELERA Sambal belacan, Cincaluk, Budu, Acar Buah, Sambal Mempelam & Acar Jelatah sambal Gesek Chili Padi Kicap, Sambal Kelapa Pudina, Sambal Nenas & Sambal Kecap Air Asam Rojak Buah counter Mangga Muda, Nanas, Bengkuang, Timun, Jambu Air, Buah Kedondong, Kuah Rojak, Kacang Tumbuk & Bijan dan Yu Char Kway KERABU Kerabu Daging Salai Kerabu Suhun Kacang Gajus Kerabu Taugeh dan Sotong Kering Kerabu Suhun Dan Udang Tauhu Sambal Kering Berkacang Marinated Jelly Fish with Mango Salad Mixed Fruits Cocktail with Crab Stick Marinated Mango Salad with Japanese Octopus Thai Style Kerabu Chicken Feet telur Masin, Ikan Masin, Jeruk Ikan Masin, Begedil, Hati Ayam Goreng kan Bilis Petai & Paru Goreng Berlada Tempeh Goreng Sambal JAJAN Keropok Ikan, Papadum, Keropok Udang & Keropok Sayur JERUK Jeruk Mangga, Jeruk Cermai, Jeruk Betik, Jeruk Buah Pala, Jeruk Sengkuang & Jeruk Anggur SUP Sup Gear Box Sup pindang lautan – Pahang Aneka Jenis Roti & Roti Bengali HIDANGAN PELBAGAI JENIS NASI Nasi Dagang – Terengganu Nasi Kerabu – Kelantan Nasi Daging – Kedah Nasi Kabuli – Johor Nasi Biryani Chicken Nasi Biryani Kambing MASAKAN NUSANTARA Gulai Daging Rebung Muda - Kedah Masak Lemak Ayam – Negri Sembilan Gulai Ikan Tongkol - Terengganu Ketam Masak Lemak Nenas – Johor Gulai Nangka Muda & Ikan Bilis – Perlis Kacang Panjang goring hati - Selangor NASI KANDAR PENANG Ayam Hitam Manis Kurma Kambing Sambal Udang Kanavai Porial Milagu Podi Sambar MASAKAN ORIENTAL Nyonya Otak-Otak – Melaka Ketam masak -

News Release
news release Mandarin Oriental, Jakarta Jalan M.H. Thamrin, PO BOX 3392 Jakarta 10310, Indonesia Tel: +62 (21) 2993 8888 MO GOURMET TO YOUR DOOR OLEH MANDARIN ORIENTAL, JAKARTA Jakarta, 7 April 2020 – Mandarin Oriental, Jakarta meluncurkan layanan food-delivery terbarunya, MO Gourmet to Your Door di mana para tamu dapat menikmati hidangan khas mereka dalam kenyamanan rumahnya masing-masing. Cukup melakukan pemesanan melalui nomor WhatsApp dan menyelesaikan transaksi tanpa batas melalui transfer bank, makanan akan dikirim dengan cepat. Tim kuliner telah menyiapkan 4 jenis suguhan untuk dinikmati para tamu dengan berbagai menu dan pilihan. Dimulai dari Mini Treats untuk konsumsi tunggal (single consumption), Nusantara Treats menawarkan hidangan khas Indonesia, Oriental Treats yang menawarkan masakan Cina dan Western Treats dengan pilihan makanan khas barat. 1. MINI Treats seharga IDR 60,000 nett a. Nasi Kuning Abon Sapi b. Nasi Uduk Ayam Goreng Lengkuas c. Nasi Goreng Ikan Asin d. Ayam Lada Hitam e. Nasi Goreng Kebuli f. Nasi Cap Cay g. Chicken Rollade h. Nasi Tutug Oncom i. Ayam Tuturuga j. Bubur Ayam 2. Nusantara Treats seharga IDR 88,000 nett a. Set 1; Gado Gado Salad, Ayam Bakar Kalasan, Nasi Uduk and Sliced Fresh Fruits b. Set 2; Rujak Buah Salad, Ikan Bakar Dabu-dabu, Steamed Rice and Sliced Fresh Fruits c. Set 3; Tahu Gejrot, Nasi Goreng Buntut, Lalap and Sliced Fresh Fruits 3. Oriental Treats seharga IDR 118,000 nett a. Set 1; Spicy Chicken Salad with Sesame Dressing, Sweet and Sour Chicken, Yang Zhou Fried Rice and Sliced Fresh Fruits b. Set 2; Dongbei Wood Ear Fungus with Dried Bean Curd, Kung Pao Chicken, XO Seafood Fried Rice and Sliced Fresh Fruits c. -

Halia Restaurant Ramadhan Buffet 2018 (17/5,20/5,23/5,26/5,29/5,1/6,4/6,7/6,10/6/2018)
HALIA RESTAURANT RAMADHAN BUFFET 2018 (17/5,20/5,23/5,26/5,29/5,1/6,4/6,7/6,10/6/2018) MENU1 Live Stall 1- Appitizer Thai Som Tum Salad, Kerabu Mangga, Sotong Kangkung (Live) Ulam Ulaman Tradisonal (Pegaga, Daun Selom, Ulam Raja, Jantung Pisang, Kacang Botol, Tempe Goreng) Sambal Belacan, Sambal Mangga, Sambal Tempoyak, Cincaluk, Budu, Sambal Gesek Ikan Masin Bulu Ayam, Ikan Masin Sepat dan Ikan Kurau, Ikan Perkasam, Telor Masin Keropok Ikan, Keropok Udang, Keropok Sayur dan Papadhom Live Stall 2 - Mamak Delights Rojak Pasembor with Peanut Sauce & Crackers Live Stall 3 - Soup Aneka Sup Berempah (Bakso Daging, Ayam, Daging, Perut, Tulang Kambing, Tulang Rawan, Ekor, Gear Box) ( Mee Kuning, Bee Hoon, Kuey Teow) Condiments – (Taugeh, Daun Bawang, Daun Sup, Bawang Goreng, Cili Kicap) Roti Benggali Curry Mee with Condiments Bubur - Bubur Lambuk Berherba dan Sambal Main Dishes Ayam Masak Lemak Rebung Stired Fried Beef with Black Pepper Sauce Perut Masak Lemak Cili Padi Ikan Pari Asam Nyonya Prawn with Salted Eggs Sotong Sambal Tumis Petai Stired Fried Pok Choy with Shrimp Paste Nasi Putih Live Stall 4 - Japanese Section Assorted Sushi and Sashimi, Assorted Tempura, Udon / Soba & Sukiyaki Live Stall 5 – Pasta Corner Assorted Pizza (Margarita, Pepperoni, Futi De Mare ) Spaghetti, Penne & Futtuchini with Bolognese, Cabonnara and Tomato Concasse Sauce Live Stall 6 - Sizzler Hot Plate (Assorted Vegetables, Squid, Fish Slice, Clam, Prawn, Mussel, Bamboo Clam) (Sauces: Sweet & Sour, Black Oyster Sauce, Black Pepper & Tom Yam) Live Stall 7 - Steamboat -

Ragi Tapai and Saccharomyces Cerevisiae As Potential Coculture in Viscous Fermentation Medium for Ethanol Production
African Journal of Biotechnology Vol. 9(42), pp. 7122-7127, 18 October, 2010 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB DOI: 10.5897/AJB10.933 ISSN 1684–5315 ©2010 Academic Journals Full Length Research Paper Ragi tapai and Saccharomyces cerevisiae as potential coculture in viscous fermentation medium for ethanol production Azlin Suhaida Azmi 1,2*, Gek Cheng Ngoh 1, Maizirwan Mel 2 and Masitah Hasan 1 1Department of Chemical Engineering, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. 2Biotechnology Engineering Department, Kulliyah of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan Gombak, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia. Accepted 30 August, 2010 A comparison study on the ethanol production from 20% (w/v) of unhydrolyzed raw cassava starch using Saccharomyces cerevisiae and Candida tropicalis was performed and compared with the commercialized ragi tapai. The findings showed that S. cerevisiae , C. tropicalis and ragi tapai produced 23, 20 mg/l and 26 g/l of ethanol in 72 h, respectively. Subsequent coculturing of the two best performing strains namely ragi tapai and S. cerevisiae were performed to improve ethanol production and to reduce the accumulation of inhibitory concentration of reducing sugar with 10% (w/v) unhydrolyzed raw cassava starch. The coculture of ragi tapai with S. cerevisiae using the unhydrolyzed raw starch in a single step-fermentation produced an ethanol concentration of 35 g/l when the starch was inoculated with ragi tapai and cocultured with S. cerevisiae. The yield was 46% higher than the one inoculated with ragi tapai only (24 g/l). The glucose concentration was maintained at a low concentration in the coculture medium as compared to the medium with pure ragi tapai. -

Annual Report 2018
INNOVATING A CONVENIENT LIFESTYLE 2018 KAWAN Food Berhad Annual Report 640445-V (Incorporated in Malaysia) KAWAN Food Berhad 640445-V KAWAN Annual Report 2018 KAWAN Food Berhad 603 3099 1188 640445-V (Incorporated in Malaysia) 603 3099 1028 Lot 129351 Jalan Sungai Pinang 4/19 Taman Perindustrian Pulau Indah [email protected] Selangor Halal Hub, Fasa 2c 42920 Pulau Indah Selangor Darul Ehsan Malaysia www.kawanfood.com Vision Mission To be the leading international company that provides • To enrich people’s lives through consistent delivery products which create values and enhance lifestyle of of high quality, safe and convenient food. our customers. • To be the leader in developing our new innovation with advance technology. • To create values in a sustainable way to our stakeholders and contribute to economic, social and environmental developments. Values Responsibility Teamwork Integrity Discipline Innovative We take ownership We work together as We are committed to We are dedicated and We embrace new and responsibility of a team to achieve our be fair & honest in committed to achieve ideas and constantly our results. mission by having all our dealings and higher efficiency and changing to meet open communication, adhere to the highest effectiveness. customers’ needs. mutual respect and ethical standards. sharing of knowledge. INSIDE THIS REPORT Notice of Annual General Meeting 2 Corporate Governance Overview Statement 54 Corporate Information 6 Audit Committee Report 68 At a Glance 8 Additional Compliance Information pursuant to the -

1. Kuliner Ikonik Dari Provinsi Aceh
Dalam pengembangan pariwisata suatu daerah atau Provinsi dari seluruh Indonesia biasanya terdapat juga Kuliner yang menjadi ikon dan khas dari daerah tersebut. Kuliner ikonik ini contohnya Mie Aceh dari Provinsi Aceh, Rendang dari Sumbar ada juga Ayam Taliwang dari Lombok NTB nah artikel ini akan mengupas lebih dalam terkait ragam kuliner Ikonik yang menyebar di seluruh Nusantara. 1. Kuliner Ikonik dari Provinsi Aceh Terkenal dengan Syariat Islam kota Banda aceh menyimpan ragam kuliner yang siap menyambut para wisatawan yang datang ke kota ini. Salah satu yang paling ikonik ialah Mie Aceh, versi lain dari mi aceh ini ada mie racing namun miimin sendiri belum pernah mencicipi mi racing ini, so kita akan membahas mi aceh biasa aja yang mudah di temui di Banda Aceh. 1.a Mie Aceh dan Timun Serut kelezatan mi aceh kering dan basah (img custom via google img) Varian dari mie aceh terdiri dari mi aceh basah dan kering, sementara varian campuran terdiri dari, kepiting, daging sapi, udang dan telur ayam. Biasanya konsumen akan memesan sesuai selera, untuk anda yang kolestrol tinggi mungkin jangan varian kepiting yang standar biasa aja. Tidak lupa pelengkap minuman yang khas dari pasangan miaceh yaitu timun serut. Jika anda mengininkan makanan berat ada ayam sampah atau ayam tangkap, yang dicampur dengan dedaunan khas Banda Aceh. 1.b Kopi Sanger (Bean Gayo) Kenikmatan kopi sanger espresso banda aceh (img via kampretnews) Jenis kopi sanger ini terdiri dari Hot dan Ice, dengan campuran susu kenikmatan kopi sanger aceh ini sangat pas. Bean yang digunakan dalam racikan kopi ialah Gayo yang di mix antara robusta dan arabika dengan roasting standar barista aceh. -

Rumah Makan Cibiuk Wangsa Maju
Rumah Makan Cibiuk Wangsa Maju P007 Nasi Liwet Komplit Ayam Kampung Bakar Delivery Yes Category TRADISI CIBIUK Price MYR 16.90 Description Name :P007 Nasi Liwet, Ayam Kampung Bakar Description: Nasi Liwet, Ayam Bakar, Tahu Tempe, Ikan Masin, Jering Goreng, Ulam & Sambal Cibiuk Category :TRADISI CIBIUK Price :MYR 16.90 Available for delivery P006 Nasi Liwet Komplit Ayam Kampung Goreng Delivery Yes Category TRADISI CIBIUK Price MYR 15.90 Description Name :P006 Nasi Liwet Komplit Ayam Kampung Goreng Description: Nasi Liwet,, Ayam Goreng, Tahu Tempe, Ikan Masin, Jering Goreng, Ulam & Sambal Cibiuk Category :TRADISI CIBIUK Price :MYR 15.90 Available for delivery P005 Nasi Timbel Komplit Lele Goreng Delivery Yes Category TRADISI CIBIUK Price MYR 14.90 Description Name :P005 Nasi Timbel Komplit Lele Goreng Description: Nasi Timbel, Lele Goreng, Tahu Tempe Goreng, Sayur Lodeh, Ulam& Sambal Cibiuk Category :TRADISI CIBIUK Price :MYR 14.90 Available for delivery 1 of 7 P004 Nasi Paket Ayam Kampung Bakar Cobek Delivery Yes Category TRADISI CIBIUK Price MYR 16.90 Description Name :P004 Nasi Paket Ayam Kampung Bakar Cobek Description: Nasi Putih, Ayam Goreng Bumbu Cobek, Perkedil Jagung, Tahu Tempe, lalapan & Sambal Cibiuk Category :TRADISI CIBIUK Price :MYR 16.90 Available for delivery P003 Nasi Bakar Pulen Komplit Ayam Kampung Bakar Delivery Yes Category TRADISI CIBIUK Price MYR 16.90 Description Name :P003 Nasi Bakar Pulen Komplit Ayam Kampung Bakar Description: Nasi Berbumbu, Ayam Bakar, Tahu Tempe, Ulam Sambal, Perkedil Jagung Category :TRADISI -

A Review of the Malaysia's Heritage Delicacy Alongside with The
Ismail et al. Journal of Ethnic Foods (2021) 8:19 Journal of Ethnic Foods https://doi.org/10.1186/s42779-021-00095-3 REVIEW ARTICLE Open Access The Malay’s traditional sweet, dodol:a review of the Malaysia’s heritage delicacy alongside with the rendition of neighbouring countries Norsyahidah Ismail1, Muhammad Shahrim Ab. Karim1* , Farah Adibah Che Ishak1, Mohd Mursyid Arsyad2, Supatra Karnjamapratum3 and Jiraporn Sirison3 Abstract The Malaysia’s cultural heritage is authentic, unique and colourful with various local cuisines of different races and cultures. It is mainly originated from the Malay culture being the largest ethnic group in the country. The Malays themselves have contributed to many local cuisines ranging from appetiser, soup, main course and dessert. However, some Malay heritage foods have almost been forgotten and jeopardized in quality. This is especially happening to the Malay sweets or desserts which have gradually become less appealing to the younger generations. They are not even familiar with Malay foods, let alone consuming them. Among the popular Malay heritage foods in Malaysia are lemang, ketupat, rendang, wajik and dodol. Dodol specifically has been listed as one of the endangered heritage foods in Malaysia. Preserving the Malay cuisines is part of sustaining the Malay culture and this should begin with a great amount of knowledge and understanding about any elements within the culture itself. This article highlights a nostalgic and evergreen Malay’s traditional sweet, known by the locals as dodol by discussing its history, different types and names of dodol, as well as the recipes, preparation, cooking methods and packaging. -

Pengetahuan Bahan Makanan
PENGETAHUAN BAHAN MAKANAN UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). PENGETAHUAN BAHAN MAKANAN Dr. -

Kitchen Art's Brasserie
KITCHEN ART’S BRASSERIE MENU BUFFET HI-TEA MENU A 2020 Garden Salad 4 Type of Lettuce, 4 Type of Kerabu, 2 Type Toast Salad Dressings and Condiments Homemade Pickled Shallot, Sesame Seed and Crusted Nut Thousand Island, Caesar Dressing, Italian Vinaigrette, Roasted Sesame Dressing, Honey Soya Dressing Balsamic Vinegar and Olive Oil Fruit Counter Rojak Buah Serves with Condiment Italian Counter BBQ Pizza Margarita Pizza Soup Cream of Mushroom Soup Serves with Bread Loafs, Bread Rolls & Butter Sauna Box Assorted Mini Pau Noodle Action Live Laksa Penang with Condiment Counter on Fire Satay Chicken & Satay Beef Serves with Peanut Sauce, Cucumber, Onion and Rice Cake Stall 1 Pasembor Serves with Condiments Stall 2 Rotisserie Chicken Serves with Au Jus, Sautéed Mix Vegetable & Potato Stall 3 Nasi Biryani Ayam Biryani Acar Mentah Stall 4 Shawarma Greek Style Chicken Shawarma Serves with Lettuce, Tzatziki Sauce, Tomato & Cucumber Main Fair Kampung Fried Rice Singapore Fried Mee Hoon Sweet & Sour Fish Mutton Curry with Potatoes Stir Fried Mix Vegetables Buffalo Chicken Wing Beef Lasagna Roasted Baked Duo Potatoes Kid’s Station Chocolate Fountain with Condiments Caramelized Popcorn Popia Sambal & Samosa Desserts Assorted Nyonya Kuih Sago Gula Melaka Bread Butter Pudding Assorted Jelly in the Glass & Crème Caramel, 4 type of Ice Cream with Condiments Fresh Cut Tropical Fruits Hot & Cold Sweet Congee Chilled Longan Bubur Kacang HI TEA MENU B 2020 Garden Salad 4 Type of Lettuce, 4 Type of Kerabu, 2 Type Toast Salad Dressings and Condiments Homemade