Materi Kuliah (Tatap Muka Di Kelas)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
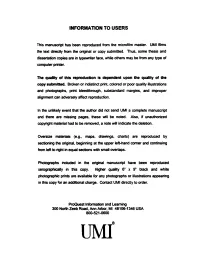
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy sutxnitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bieedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that tfie author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 UMI' THE NOTION OF POWER AS IT IS REFLECTED IN THE EDIBLE WOMAN AND KARMILA: A COMPARATIVE STUDY by Herawaty Abbas Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts In the Joint Women’s Studies Programme at Mount Saint Vincent University Dalhousie University Saint Mary’s University Halifax, Nova Scotia September 2001 © Copyright by Herawaty Abbas, 2001 National Library Bibliothèque nationale 1 ^ 1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibliographiques 395 Waflington Slroet 395. -

Buku Karya, Pengarang, Dan Realitas Dalam Novel Pop Indonesia 1970
LAPORAN PENELITIAN/ BUKU KARYA, PENGARANG, DAN REALITAS DALAM NOVEL POP INDONESIA 1970-AN 2000-AN Oleh: Ketua: Muhamad Adji, M.Hum. Anggota: 1. Lina Meilinawati, M.Hum. 2. M. Irfan H., M.Hum. Dibiayai oleh Dana Hibah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN 2008 1 LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN SUMBER DANA HIBAH FAKULTAS SASTRA TAHUN ANGGARAN 2008 1. a. Judul Penelitian : Karya, Pengarang, dan Realitas dalam Novel Pop1970-an 2000-an b. Macam Penelitian : ( ) Dasar (X) Terapan ( ) Pengembangan c. Kategori : 1 2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar : Muhamad Adji, M.Hum. b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. Golongan Pangkat dan NIP : IIIa/ Penata Muda / 132321079 d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli e. Jabatan Struktural : Sekretaris Program Studi f. Fakultas/Jurusan : Sastra/ Sastra Indonesia g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran 3. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang a. Nama Anggota Peneliti I : M. Irfan Hidayatullah, M.Hum. b. Nama Anggota Peneliti II : Lina Meilinawati, M.Hum. c. Nama Anggora Peneliti III : Deva Astarini 4. Lokasi Penelitian : Bandung-Jatinangor 5. Kerjasama dengan Institusi lain : - 6. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan 7. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) a. Sumber dari Unpad : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) b. Sumber lain : - Jatinangor, September 2008 Mengetahui, Ketua Peneliti Ketua Panitia Hibah Dr. Wahya Muhamad Adji, M.Hum.. NIP 131832049 NIP 132321079 Menyetujui dan Mengesahkan, Dekan Fakultas Sastra Unpad Prof. Dr. Dadang Suganda NIP 131409660 2 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang intensnya penelitian terhadap novel populer Indonesia, sementara di sisi lain perkembangan novel populer begitu pesat sejak tahun 1970-an sampai saat ini dengan berbagai corak dan kemasan sehingga membutuhkan kajian yang lebih intens dalam dunia akademik. -

Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977
Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977 1 / 3 Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977 2 / 3 23 Oct 2012 - 98 minStreaming dan Download Gratis Badai Pasti Berlalu Full movie - aDiEx YouTube. flv on .... 9 Mei 2014 ... Pertama kali gue tahu film Badai Pasti Berlalu itu waktu gue SD, ... Hmm, mungkin gue harus download ulang dengan kualitas yang lebih tinggi .... Download lagu mp3 Download video Badai pasti berlalu, gratis Badai pasti berlalu ... Download Ost Video Film Mp3, juga dilengkapi dengan kumpulan lirik lagu. ... Semusim - By Chrisye - Ost Badai Pasti Berlalu 1977 - Iph's Video Collections. 10 Nov 2014 ... Jadi disini saya mau membahas versi film Badai Pasti Berlalu yang dirilis tahun 1977 dan disutradarai oleh Teguh Karya. Versi film Badai Pasti .... Roy Marten, Christine Hakim, Slamet Rahardjo. ... Her brother introduces her to his friend Leo, who is known as a womanizer. ... What she doesn't know is that Leo decided to be with her as she was a part of a bet.... Badai Pasti Berlalu 1977 Movie Download http://shurll.com/bmymjBadai Pasti Berlalu 1977 Movie Download cc4e9f5eb6 may 18 korean film downloadkachche .... Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 1977. pelangi by chrisye - ost badai pasti berlalu Badai Pasti Berlalu is a 1977 Indonesian film based ... Marga T. Undangan gratis Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film Indonesia yang ... Released in 1977 on (catalog no. download.. Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 1977. Film ini disutradarai oleh Teguh Karya pada tahun 1977 yang .... Film BADAI PASTI BERLALU (1977) Director : Teguh Karya. -

Habis Badi Gelap Pasti Terbitlah Terang Berlalu the Following Lexicon Is an Effort to Clarify How Indonesian Politics Is Naturalized
farid rakun Habis Badi Gelap Pasti W e Terbit- lah a t h e Terang r 1 Berlalu 1 Translatable to: “After the darkness of storm light is born will surely pass.” It is a mash-up of Marga T.’s 1974 S novel Badai Pasti Berlalu c (The Storm Will Surely Pass, holding similar a meaning with p “every cloud has a silver lining”) with Habis e Gelap Terbitlah Terang (After g Darkness, Light is Born). The first was adapted into a film o by Teguh Karya in 1977 with a a soundtrack hit with the same title by Chrisye, which t Erwin Gutawa restaged into a live orchestra recording in 1999, then into a 26-episode 8 soap opera series in 1996, and finally re-made by Teddy Soeriaatmadja in 2007. The latter is a book composed by J.H. Abendanon using letters by Kartini, first published in 1911 with the title Door Duisternis Tot Licht. It was first translated in an abridged format to Malay in 1922 by Armijn Pane, with a different title and order. 162 Habis Badi Gelap Pasti Terbitlah Terang Berlalu The following lexicon is an effort to clarify how Indonesian politics is naturalized. The Indonesian language—historically a melting-pot of outside influences—mixes Malay, Sanskrit, Indian, Portuguese, Dutch, Arabic, and increasingly English. For the purpose of this piece, the original Indonesian is kept with my English translation. I started by selecting terms that either portray the naval and/or oceanic hegemony increasingly grasping the national imagination, and those that are metaphorically utilized by the most popular national media to render anything political also natural. -

Bab I Pendahuluan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH “Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni” (Renne dan Wellek, 1993:3). Bila pengertian sastra merupakan kegiatan kreatif, sastra merupakan hasil imajinasi bermediumkan bahasa yang didalamnya terdapat unsur keindahan. Definisi sastra selanjutnya adalah institusi sosial yang bermediumkan bahasa (Renne dan Wellek, 1993:109). Dari pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa sastra merupakan suatu refleksi kehidupan nyata yang dituangkan kedalam cerita fiksi melalui penggunaan bahasa. Suatu kegiatan kreatif dengan menggunakan medium bahasa menghasilkan dengan apa yang disebut karya sastra. “Karya sastra sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta yang melukiskan penderitaan manusia, perjuangan, kasih sayang, kebencian, nafsu, dan segala yang dialami oleh manusia” (Mursal Esten dalam Bambang Trisman, 2003:12). Dari pendapat tersebut, diasumsikan bahwa karya sastra merupakan sebuah refleksi kehidupan manusia dengan segala rasa dan tingkah lakunya dengan media bahasa. Isi karya sastra yang berupa refleksi kehidupan nyata menunjukkan bahwa sastra merupakan cermin masyarakat, maksudnya sampai sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat. Menurut Ian Watt (dalam Damono, 1979:4) “pengertian “cermin” dalam hal ini masih sangat kabur, dan oleh karenanya dapat disalahtafsirkan dan disalahgunakan”. Jika dalam penelitian sastra pendapat bahwa sastra cermin masyarakat selayaknya seorang peneliticommit harus to user menyikapi dengan lebih teliti, sebab 1 perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 2 telah sesuai dengan pemaparan di atas bahwa “cermin” pengertiannya masih kabur sehingga dapat menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya, karya sastra merupakan tanggapan pencipta (pengarang) terhadap dunia (realita sosial) yang dihadapinya. “Sastra di dalamnya berisi pengalaman-pengalaman subjektif pengarangnya, pengalaman subjektif seseorang (fakta individual atau libidinal), dan pengalaman sekelompok masyarakat (fakta sosial)” (Sangidu, 2004:41). -

Download Novel Badai Pasti Berlalu Pdf 95
Download Novel Badai Pasti Berlalu Pdf 95 Download Novel Badai Pasti Berlalu Pdf 95 1 / 3 2 / 3 Sri Suktam Lyrics In Malayalam Pdf Download > http://shorl.com/pryprybrubabedre. Sri Suktam ... download novel badai pasti berlalu pdf reader laiq hussain .... Free Pdf Problems In Electrical Engineering By Parker Smith ... Read & Download Ebook solved ... download novel badai pasti berlalu pdf 95.. Novel terbaik tulisan orang Indonesia dalam bahasa Indonesia yang ... Para Priyayi: Sebuah Novel ... Badai Pasti Berlalu ... 95. Camar Biru: Cinta Tak Selal... Camar Biru: Cinta Tak Selalu Tepat ... boleh ikutan ya mas? saya milih aja dari daptarnya mas tomo yg udah saya baca:D berarti ini daptar novel aja .... PDF | On Oct 1, 2002, Jeremy Wallach and others published Exploring Class, ... Download full-text PDF ... Exploring Class, Nation, and Xenocentrism 95 ... 5* Chrissye Badai Pasti Berlalu [The Newly arranged songs from ... illuminate several novel relationships (e.g. between basic psychological needs, .... Directed by Teguh Karya. With Roy Marten, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Rahayu Effendi. Based on the famous novel, this is a story about Siska, a young .... Badai Pasti Berlalu. 3,8 rb suka. Buku Masterpiece Karangan Chandra Putra Negara. Pemesanan via sms 0817338678. (Belum termasuk Ongkir). Rp 175.000 .... "Novel ini pernah terbit sebagai cerita bersambung dalam harian Kompas." Reproduction Notes: Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010.. Jual NOVEL AFEKSI - ZAKA BAGAS WIRAWAN dengan harga Rp52.800 dari toko ... Buku Badai Pasti Berlalu dan TTD asli bapak CHANDRA PUTRA NEGARA.. Check out Badai Pasti Berlalu (Itu Yang Aku Tahu) by Marcello Tahitoe on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com. -
Pendekatan Integrasi Dengan Basis Biaya Elementer
IN THE BOYS’ CLUB: A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE ROLES OF WOMEN IN THE INDONESIAN CINEMA 1926-MAY 1998 Grace Swestin Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya Email: [email protected] ABSTRAK Artikel ini mendeskripsikan peran perempuan dalam perfilman Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1926 hingga masa sebelum lahirnya perfilman Indonesia generasi baru. Melalui sebuah tinjauan historis, peran perempuan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah peran mereka di balik layar film, baik sebagai sutradara dan produser maupun dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan industry dan regulasi perfilman. Kedua, artikel ini memaparkan bagaimana perempuan direpresentasikan di dalam cerita dan plot film-film yang diproduksi sebelum masa reformasi. Peneliti menemukan bahwa peran perempuan dalam perfilman Indonesia di masa ini, secara keseluruhan masih berada di bawah bayang-bayang dominasi tokoh-tokoh laki-laki. Hal tersebut terutama disebabkan karena sedikitnya jumlah perempuan yang memegang posisi pengambilan keputusan baik secara artistik maupun industrial. Kata kunci: Indonesian cinema, women and cinema, jistorical review. INTRODUCTION Women have occupied an ambivalent and often controversial position in Indonesia since the inception of the cinema in the country. One of the most telling aspects surrounding the rise of the New Indonesian Cinema post-New Order Indonesia is the role of women in the cinema. As studies have suggested (e.g. Trimarsanto, 2002; Swestin, 2009), there have been more women film directors in the past ten years compared to the previous seven decades in the history of the Indonesian Cinema. In the previous generations of the Indonesian cinema, very few women were in positions of control in the administrative and artistic spheres of the film industry. -

Majalah Pusat Edisi 9 Plus Cover.Pdf
PUSAT MAJALAH SASTRA pendapa PUSAT ada dasarnya apa yang disebut dengan mentalitas majalah sastra diterbitkan oleh Pbangsa adalah sebuah gagasan yang luas dan tidak Pusat Bahasa mudah dirumuskan dengan sederhana. Namun, jika Gedung Dharma, Lt. 3 Jalan Daksinapati Barat IV, kita berpegang pada apa yang dikemukakan Lao Tse Rawamangun, Jakarta 13220 berabad-abad lalu, yaitu: “Jika ingin memperbaiki suatu Pos-el: [email protected] bangsa, perbaikilah bahasanya”, maka “mentalitas Telepon: (021) 4706288, 4896558 Faksimile (021) 4750407 bangsa” memiliki kaitan yang erat dengan bahasa. Bahkan, mentalitas bangsa kerap kali ditentukan oleh Pemimpin Umum Kepala Badan Pengembangan bagaimana bahasa diperhatikan, dikelola,dihidupi, dan Pembinaan Bahasa dan dikembangkan. Jika ada yang mengatakan bahwa Manager Eksekutif Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Sekretaris Badan Bahasa Bahasa) merupajan ujung tombak dalam urusannya dengan mentalitas bangsa, maka anggapan tersebut Pemimpin Redaksi Kepala Pusat Pengembangan tidak sepenuhnya salah. Bahkan, Revolusi Mental yang dan Perlindungan menjadi dasar bagi pemerintah di bawah Presiden Joko Wakil Pemimpin Redaksi Widodo. tidak terlalu salah jika orang beranggapan Mu’jizah sangat erat terkait dengan kiprah pemerintah melalui Konsultan Badan Bahasa. Agus R. Sarjono Sutan Takdir Alisyahbana —sastrawan, budaya-wan Dewan Redaksi dan penulis awal buku Tata Bahasa bahasa Indonesia, Budi Darma pernah mengatakan bahwa bahasa bisa apa saja —bunyi, Hamsad Rangkuti Putu Wijaya struktur, dsb.— tapi yang jelas dan pasti pada bahasa Manneke Budiman adalah pikiran. Keteraturan dan struktur berpikir bangsa Indonesia dapat dilihat dari struktur bahasa Indonesia. Staf Redaksi Abdul Rozak Zaidan Adab dan budinya dapat dilihat dalam cara masyarakat Ganjar Harimansyah Indonesia berbahasa, yang secara sederhana suka Saksono Prijanto Puji Santosa disebut sebagai budi bahasa. -

Traditions Redirecting Contemporary Indonesian Cultural Productions
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/319644365 Traditions Redirecting Contemporary Indonesian Cultural Productions Book · July 2017 CITATIONS READS 0 233 1 author: Monika Arnez University of Hamburg 19 PUBLICATIONS 109 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Environmentalism in Java and East Kalimantan: transregional dimensions of integration (EU-funded project SEATIDE) View project Education and morality: concepts of orders in Islamic contemporary literature in Indonesia (German Research Foundation) View project All content following this page was uploaded by Monika Arnez on 12 September 2017. The user has requested enhancement of the downloaded file. Traditions Redirecting Contemporary Indonesian Cultural Productions Traditions Redirecting Contemporary Indonesian Cultural Productions Edited by Jan van der Putten, Monika Arnez, Edwin P. Wieringa and Arndt Graf Traditions Redirecting Contemporary Indonesian Cultural Productions Edited by Jan van der Putten, Monika Arnez, Edwin P. Wieringa and Arndt Graf This book first published 2017 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2017 by Jan van der Putten, Monika Arnez, Edwin P. Wieringa, Arndt Graf and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-8993-8 ISBN (13): 978-1-4438-8993-3 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ................................................................................... -

Ekranisasi Novel Critical Eleven Karya Ika Natassa Ke Dalam Film Critical Eleven: Implikasinya Bagi Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia
EKRANISASI NOVEL CRITICAL ELEVEN KARYA IKA NATASSA KE DALAM FILM CRITICAL ELEVEN: IMPLIKASINYA BAGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SKRIPSI oleh M. Apriansyah NIM: 06021381419061 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam sastra, pengembangan dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai. Sastra tersebut mendukung upaya pengembangan agar tradisi bersastra di kalangan sastrawan dan penikmat sastra tumbuh secara baik. Pengembangan sastra, baik dalam bentuk fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya, dilakukan terhadap sastra yang bernilai untuk aktualisasi. Aktualisasi yang dimaksud adalah penuangan dalam bentuk aktual atau mengadaptasi suatu karya ke karya yang lain. Dalam hal tersebut, sastra bukan hanya bisa diterjemahkan melainkan dialihwahanakan. Alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya dapat diterjemahkan tetapi juga dapat dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain. Kegiatan di bidang ini membuktikan bahwa sastra dapat bergerak kesana kemari, berubah-ubah unsur-unsurnya agar sesuai dengan wahananya yang baru (Damono, 2005:96). Menurut Damono, karya sastra juga bisa diubah menjadi nyanyian, film dan lukisan ataupun sebaliknya. Perubahan karya sastra dari novel ke film sudah banyak di lakukan oleh seniman baik dalam negeri maupun luar negeri. Damono juga menyatakan bahwa, karya sastra juga bentuk audiovisual seperti, sinetron, film dan film Pendek kegiatan ini disebut dengan ekranisasi. Memfilmkan karya sastra sering disebut adaptasi atau ekraniasi. Ekranisasi adalah pelayarputihan atau alih wahana dari sebuah novel ke dalam film ataupun sebaliknya (ecran dalam Bahasa francis berarti layar), pemindahan novel ke dalam film atau film ke novel atau layar putih mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan oleh sebab itu, dapat dikatakan ekranisasi adalah proses perubahan (Eneste, 1991:60). -

Soeharto and Mao
POLICY AND ITS INFLUENCE ON LITERATURE: SOEHARTO AND MAO Nurni W. Wuryandari1 Abstrak Sastra dan kebijakan pemerintah sering dianggap tak dapat dipisahkan. Sastra memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan atau tujuan politik, juga menjadi alat untuk menyampaikan kritik. Membandingkan antara Indonesia dengan Cina, Indonesia memiliki situasi yang berbeda dengan Cina. Pemerintah Indonesia tidak pernah menggunakan sastra sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan, dan tidak menjadikan sastra sebagai agenda penting dalam rapat-rapat partai. Akan tetapi keputusan-keputusan politik pemerintah, atau instruksi- instruksi presiden, yang sering kali didukung kekuatan militer, juga membawa dampak pada sastra dan tren sastra. Sementara karena fungsi dari sastra yang salah satunya bisa dijadikan alat menyampaikan kritik, pemerintah Cina sangat peka terhadap sastra. Mereka sering menggunakan kekuasaan untuk mengawasi sastra, dan juga menggunakan sastra untuk menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Situasi seperti ini membuat sastra di Cina memiliki hubungan erat dan langsung dengan pemerintah. Garis-garis politik pemerintah seringkali menentukan tren sastra di sana. Berdasarkan kasus-kasus di kedua negara tersebut, khususnya dalam periode Soeharto dan Mao Zedong, dapat dilihat bahwa sastra dapat memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan pemerintah, dan hubungan ini membawa dampak positif dan negatif pada sastra dan tren sastra pada kurun waktu tertentu. Kata Kunci : pemerintah, kebijakan, sastra, tren sastra 1 Lecturer at Departement of Chinese Studies, Faculty of Letters University of Indonesia, currently a post-graduate (Ph.D) student at Tamkang University Taiwan. Contact address: [email protected]. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. 1 Tahun 2011 47 Introduction Literature and government’s policies are often considered inseparable, as both sides have tight relations to one another. -

Buku Sejarah Sastra Indonesia Berperspektif Gender.Pdf
0 Maman Suryaman Wiyatmi Nurhadi BW Else Liliani SEJARAH SASTRA INDONESIA BERPERSPEKTIF GENDER 1 BAB I SEJARAH SASTRA INDONESIA BERPERSPEKTIF GENDER A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah membaca dan memahami materi ini diharapkan mahasiswa mampu mendapatkan pengetahuan dan menjelaskan konsep sejarah sastra Indonesia, perlunya sejarah sastra Indonesia berperspektif gender, dan metode penulisan sejarah sastra Indonesia berperspektif gender. B. MATERI PEMBELAJARAN 1. Sejarah Sastra Indonesia Sejarah Sastra merupakan salah satu dari tiga cabang ilmu sastra, di samping Teori Sastra dan Kritik Sastra (Wellek & Warren, 1990). Sejarah sastra mempelajari perkembangan sastra yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks Indonesia, maka Sejarah Sastra akan mempelajari perkembangan sastra nasional (Indonesia). Melalui Sejarah Sastra, seseorang akan memahami karya-karya sastra apa sajakah yang pernah dihasilkan masyarakat atau bangsa tertentu, siapa sajakah para penulisnya, persoalan apa sajakah yang ditulis dalam karya-karya sastra tersebut? Telah cukup banyak buku sejarah sastra Indonesia ditulis orang dan dipakai sebagai bahan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa contoh buku tersebut antara lain adalah Pokok dan Tokoh dalam Sastra Indonesia (A.Teeuw, 1955), Sastra Baru Indonesia (A. Teeuw, 1980), Sastra Indonesia Modern II (A Teeuw, 1987), Perkembangan Novel Indonesia (Umar Junus, 1974), Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia (Ajip Rosidi, 1969), dan Perkembangan Sastra Drama dan Teater Indonesia (Jakob Sumardjo,