Penghargaan Kebudayaan Tahun 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Batu Bara Masih Lebih Murah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Masih Mendominasi Jumlah Pembangkit Listrik Di Indonesia
Disway News Network Spirit Akal Sehat Info Berlangganan: (0542) - 8520236 SENIN, 29 JUNI 2020 Eceran Rp. 6000 | Langganan Rp. 135.000 Batu Bara Masih Lebih Murah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Melimpahnya batu bara menjadikan energi tersebut lebih ekonomis. Tanpa harus impor. Lalu, bagaimana dengan energi baru terbarukan? Yang ditarget 23 persen hingga 2025. USKAR Radianto adalah sosok yang ramah. Ketika Disway Kaltim menemuinya, manager PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pem- bangkitan (UPDK) Balikpapan itu, menyambut terbuka. Ia men- ceritakan instalasi listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) dan YKalimantan Utara (Kaltara) secara gamblang. Awalnya, yang ingin ditemui GM UIW wilayah Kaltimra, Sigit Witjak- sono. Namun ia merujuk Yuskar untuk membahas persoalan yang lebih teknis. Pekan lalu, Sigit sudah menyampaikan pula terkait rencana usaha pembangkit listrik (RUPTL) 2019 -2028. Ketika ditemui di kantornya di PLTU Teluk Balikpapan. Di kawasan Kariangau. Yuskar menceritakan alasan mengapa pembangkit PLTU men- dominasi produksi energi listrik PLN. Karena hal itu memang mengacu pada RUPTL sebelumnya. Yang telah ditetapkan pemerintah. Pertimbangan lainnya, adalah sumber daya batu bara yang dimiliki negara Indonesia. Jumlahnya melimpah. Tidak perlu harus impor. Energi pemanfaatan batu bara ini juga untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bumi. Biaya operasionalnya jauh lebih tinggi ke- timbang pembangkit batu bara. Karena itu, beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke depannya akan menjadi back up saja. “Potensi batu bara di wilayah Kalimantan juga melimpah. Sehingga tidak perlu impor. Biaya operasional memang jauh selisihnya,” kata ANDI M HAFIZH/ DISWAY KALTIM Yuskar Radianto, saat dijumpai Jumat (26/6) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Batakan, Balikpapan, saat ini menjadi cadangan PLN Kaltimtara jika terjadi masalah dalam jaringan. -
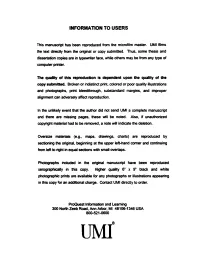
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy sutxnitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bieedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that tfie author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 UMI' THE NOTION OF POWER AS IT IS REFLECTED IN THE EDIBLE WOMAN AND KARMILA: A COMPARATIVE STUDY by Herawaty Abbas Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts In the Joint Women’s Studies Programme at Mount Saint Vincent University Dalhousie University Saint Mary’s University Halifax, Nova Scotia September 2001 © Copyright by Herawaty Abbas, 2001 National Library Bibliothèque nationale 1 ^ 1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibliographiques 395 Waflington Slroet 395. -

Analisis Data Sepak Bola Indonesia Super League 2014 Dengan
Prosiding Statistika ISSN: 2460-6456 Analisis Data Sepak Bola Indonesia Super League 2014 dengan Distribusi Poisson Data Analysis of Football Indonesia Super League 2014 with Poisson Distribution 1Bayu Dwi Purnama, 2 Siti Sunendiari, 3Suwanda 1,2,3Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116 email: [email protected] Abstract. In a football game scoring to the opponent is a thing that should be done by every football team in order to win the game. Goals scored by each team football or conceded a goal can illustrate the power of attack and strength endure every team. This paper applies the poisson model to describe the strength of the attack and the weaknesses persist at every football team while playing at every home and away Football League system.Poisson model can be used by the football spectators to see the power of the strike and the strength of his team survive at a time when playing an away or enclosure. In this paper to illustrate the strength of each team attacking at the moment playing cage symbolized by α, then β denoted to illustrate the weaknesses persist at the time of each team playing away. For the weaknesses persist at the time each team play cage symbolized by γ, and the strength of each team attacked at the time away playing denoted by δ. The value of maximum likelihood estimates (MLE) ofthePoissondistribution isusedto getthevalueofthese parameters ,then the parameters value to use itersari exemplified by Maher (1982). Poisson model to get the strength to attack and strength endure every team on the playing enclosure or the amount of data needed away to score each of their games. -

DRUGS Prestasi
Rp 2000,- 28 HALAMAN BERLANGGANAN HUBUNGI: BALIKPAPAN: 0542-735015 PHONE/WA: 08115470799 SAMarinDA: 0541-202416 PHONE/WA: 08115578008 RABU, 28 AGUSTUS 2019 No. 109/Tahun 17 @tribunkaltim tribunkaltim.co @tribunkaltim newsvideo tribunkaltim Harga Tanah Ibukota Naik 4 Kali Lipat XX Gubernur Isran Sebut Lokasi di Muara Jawa dan Semoi SAMBOJA, TRIBUN - Kepu- mulai masuk ke wilayah tusan Presiden Republik Samboja dan Muara Jawa, Indonesia Joko Wi- BERIT Kutai Kartanegara. dodo menetapkan A Seperti diketahui, EKSKLUSIF Kalimantan Ti- sebagian wilayah mur sebagai ca- Kukar, yakni lon ibukota negara yang Samboja dan Muara baru, Senin (26/8) Jawa bakal menjadi kemarin membuat lokasi ibukota negara kasak-kusuk para spekulan tanah z Bersambung Hal 11 Desainnya itu masih dilengkapi dan disesuaikan oleh tim. Titik koordinatnya (lokasi Istana Negara) akan dimasukkan Undang-Undang IKN ISRAN NOOR Gubernur Kaltim Samboja & Sepaku Lokasi Ibukota Baru Samboja Terletak di pesisir timur Kutai Sepaku Kartanegara, di antara Ada Lahan Milik Adik Prabowo Kecamatan Sepaku, PPU Balikpapan dan Samarinda POLITIKUS Partai Gerin- Dahnil Anzar Simanjun- memiliki luas wilayah 1172,36 l Terhubung dengan Tol dra membenarkan kepe- tak, juru bicara Prabowo Km2 Balikpapan-Samarinda milikan lahan keluarga Subianto, menjelaskan l Berada di atas ketinggian 500 sepanjang 99 km Prabowo Subianto di loka- soal lahan yang disebut- meter di atas permukaan laut l Dari Bandara SAMS si yang akan menjadi ibu- sebut milik Ketua Umum l Penduduk di Sepaku pada Sepinggan ditempuh melalui kota negara baru di Ka- Partai Gerindra Prabowo limantan Timur. Namun Subianto di Kabupaten Pe- 2017 tercatat 32.073 jiwa jalan darat sekitar 1 jam 16 menit demikian, Prabowo siap najam Paser Utara. -

Gelar a Tribute to Teguh Karya Slamet Rahardjo Dan Christine Hakim Kamis, 15 September 2005 Teater Populer Bakal Menggelar a Tr
Gelar A Tribute to Teguh Karya Slamet Rahardjo dan Christine Hakim Kamis, 15 September 2005 Teater Populer bakal menggelar A Tribute to Teguh Karya yang rencananya akan digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (28/9) mendatang. Sejumlah penyanyi dan musisi akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya, Idris Sardi dan Erros Djarot (komposer musik), Addie MS (konduktor), serta sejumlah penyanyi yang akan diiringi oleh Twilite Orchestra. Dalam konser ini akan ditampilkan original soundtrack film-film karya Teguh Karya seperti film Pacar Ketinggalan Kereta, November 28, Badai Pasti Berlalu, Ibunda, Wajah Seorang Lelaki dan lain-lain. Selain didukung oleh musisi kawakan, acara ini juga akan diramaikan oleh para penyanyi senior seperti Anna Mathovani yang pernah mengisi vokalnya di soundtrack film Cinta Pertama, Berlian Hutahuruk (Badai Pasti Berlalu), Aning Katamsi, Harvey Malaihollo, Ruth Sahanaya, Rafika Duri, Marini, Christopher Abimanyu, Fryda Luciana, serta para aktor kawakan lainnya yang pernah membintangi film-film karya Teguh Karya seperti Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Roy Marten, Leny Marlina, Alex Komang, Jenny Rahman, Niniek L Karim, N. iantiarno, dan Rima Melati. Slamet Rahardjo yang menjadi salah satu penggagas acara ini mengatakan bahwa acara ini bukanlah upaya untuk mengkultuskan seorang Teguh Karya. Tetapi, dalam kegairahan perfilman saat ini perlu diberikan sebuah keteladanan yang bisa dipetik dari sosok Teguh Karya. "Kegiatan ini juga didasari oleh pengertian bahwa film bukan hanya sekedar akting saja, melainkan di dalamnya ada juga unsur musik yang mempengaruhi sebuah karya film," ujar Slamet Rahardjo di sanggar Teater Populer, Jalan Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Slamet mengatakan, A Tribute to Teguh Karya adalah salah satu wasiat yang diamanahkan kepada dirinya setahun sebelum Teguh Karya meninggal pada 11 Desember 2001 lewat ungkapan Teguh yang berbunyi "kreativitas tidak boleh mati". -

Proyek Jurassic Park Tak Berhenti Blok
HARGA KORAN ECERAN : Rp.5.000.- LANGGANAN : Rp.55.000,- (Jabodetabek) LUAR JABODETABEK : Rp. 7.500,- Jumat, 6 Agustus 2021 INFO NASionAL INFO OTonoMI INFO LEGISLATIF MANTAN SURATI CEMAS KORUPTOR JADI KEMENKES PENYEDERHANAAN KOMISARIS DIBALAS SURAT SUARA 3 5 VAKSIN 6 4PERTUMBUHAN 7,07 PERSEN 4BUKAN PENCAPAIAN LUAR BIASA HMI Tetap Ngotot DATA BERbaNDING Demo di Istana TERbalIK REALITA JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di Yuwono, dalam keterangan Pasalnya, hanya instrumen sebesar 5,9 persen (yoy). pers yang disaksikan secara pemerintah yang menjadi Lebih tinggi dibandingkan JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Is kuartal kedua membangkitkan euforia. daring, Kamis (5/8/2021). tumpuan pertumbuhan se per tumbuhan periode yang lam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin mengin Angkanya cukup fantastis, mencapai “Meski memang ada per lama pandemi. sama tahun sebelumnya yang struksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi 7,07 persen secara year on year (yoy). tumbuhan, tetapi ini masih Tercatat dalam pencapa terkontraksi dalam minus 5,5 (Badko) HMI seIndonesia agar menggelar aksi unjuk tumbuh di bawah kondisi ian Produk Domestik Bruto persen, dan kuartal pertama rasa menjelang dua tahun kepemimpinan JokowiMaruf Tapi, pemerintah mesti waspada. Ini ekonomi normal atau pra (PDB) atas dasar harga 2021 yang juga masih terkon Amin. bisa jadi jebakan. COVID19,” sambungnya. Hal berlaku kuartal kedua, men traksi minus 2,2 persen. Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor inilah yang perlu dicermati capai Rp4.175,8 triliun, se Investasi juga tumbuh tinggi 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut Pertumbuhan 7,07 persen hanya 3,31 persen saja. lebih jauh sebelum pemerin dangkan atas harga dasar sebesar 7,5 persen (yoy) sete mereka, Presiden dan Wapres JokowiMaruf Amin yang secara tahunan tentu melebih “Itulah penjelasan kenapa tah larut dalam euforia. -

Inventaris Arsip Perseorangan Guruh Sukarno Putra 1973 - 1990
INVENTARIS ARSIP PERSEORANGAN GURUH SUKARNO PUTRA 1973 - 1990 DIREKTORAT PENGOLAHAN DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2016 KATA PENGANTAR Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional wajib melakukan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional agar dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengguna arsip dan masyarakat secara luas. Salah satu hasil pengolahan arsip statis yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2016 adalah Inventaris Arsip Perseorangan Guruh Sukarno Putra 1973-1990. Substansi arsip yang dimuat dalam Inventaris Arsip ini terdiri dari arsip tekstual yang tercipta atas kegiatan pencipta arsip yang dalam hal ini adalah Guruh Sukarno Putra (GSP) sebagai seorang seniman dan anggota masyarakat. Dengan tersusunnya inventaris arsip ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap arsip statis Perseorangan Guruh Sukarno Putra yang tersimpan di ANRI. Kami menyadari inventaris arsip ini masih belum sempurna, namun inventaris arsip ini sudah dapat digunakan untuk mengakses arsip statis Perseorangan Guruh Sukarno Putra periode 1973- 1990 yang tersimpan di ANRI. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, Keluarga Besar Guruh Sukarno Putra, para anggota tim dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin. Jakarta, Maret 2017 Direktur Pengolahan Drs. Azmi, M.Si ii ! DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii I. PENDAHULUAN 1 A. Riwayat Hidup 1 B. Sejarah Arsip 10 C. Pertanggungjawaban Pembuatan Inventaris Arsip 12 D. Petunjuk Akses Arsip 17 1. Persyaratan Akses Arsip 17 2. -

A Semiotic Analysis on Football Club Logos of Indonesia Super League 2009-2010
A SEMIOTIC ANALYSIS ON FOOTBALL CLUB LOGOS OF INDONESIA SUPER LEAGUE 2009-2010 THESIS Composed by: Raffri Setiawan NIM 060110101050 ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS JEMBER UNIVERSITY 2011 A SEMIOTIC ANALYSIS ON FOOTBALL CLUB LOGOS OF INDONESIA SUPER LEAGUE 2009-2010 A thesis presented to the English Department, Facul requirements to obtain the award of Sarjana Sastra THESIS ty of Letters, Jember University as one of Degree in English study Composed by: Raffri Setiawan NIM 060110101050 ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS JEMBER UNIVERSITY 2011 ii This thesis is dedicated to: DEDICATION PAGE 1. My dearly loved mother, Mistri, you are the best mo patience and for everything you do for me. 2. My late father, M. Samsul Arifin. You had trained m person. The times with you are the sweetest memory 3. My beloved sister, Anis Wulandari. You are my lovel sacrifice, support and wish. m ever. Thanks for your 4. My families and my friends. 5. My Alma Mater. e to be a responsible for me ever. y sister. Thanks for your iii MOTTO (Optimus Prime‘No sacrifice in the filmno victory’ Transformers) iv I hereby state that this thesis entitled ‘A Semioti Logos of Indonesia Super League 2009-2010’DECLARATION is an or that the analysis and the result in this thesis hav other degree or any publication in this situation. the content without any pressure from other parties academic punishment if someday the statement is pro c Analysis on Football Club iginal piece of writing. I certify e already been not submitted for any I make responsible for the validity of and I would be ready to get ved untrue. -

Buku Karya, Pengarang, Dan Realitas Dalam Novel Pop Indonesia 1970
LAPORAN PENELITIAN/ BUKU KARYA, PENGARANG, DAN REALITAS DALAM NOVEL POP INDONESIA 1970-AN 2000-AN Oleh: Ketua: Muhamad Adji, M.Hum. Anggota: 1. Lina Meilinawati, M.Hum. 2. M. Irfan H., M.Hum. Dibiayai oleh Dana Hibah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN 2008 1 LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN SUMBER DANA HIBAH FAKULTAS SASTRA TAHUN ANGGARAN 2008 1. a. Judul Penelitian : Karya, Pengarang, dan Realitas dalam Novel Pop1970-an 2000-an b. Macam Penelitian : ( ) Dasar (X) Terapan ( ) Pengembangan c. Kategori : 1 2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar : Muhamad Adji, M.Hum. b. Jenis Kelamin : Laki-laki c. Golongan Pangkat dan NIP : IIIa/ Penata Muda / 132321079 d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli e. Jabatan Struktural : Sekretaris Program Studi f. Fakultas/Jurusan : Sastra/ Sastra Indonesia g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran 3. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang a. Nama Anggota Peneliti I : M. Irfan Hidayatullah, M.Hum. b. Nama Anggota Peneliti II : Lina Meilinawati, M.Hum. c. Nama Anggora Peneliti III : Deva Astarini 4. Lokasi Penelitian : Bandung-Jatinangor 5. Kerjasama dengan Institusi lain : - 6. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan 7. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) a. Sumber dari Unpad : Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) b. Sumber lain : - Jatinangor, September 2008 Mengetahui, Ketua Peneliti Ketua Panitia Hibah Dr. Wahya Muhamad Adji, M.Hum.. NIP 131832049 NIP 132321079 Menyetujui dan Mengesahkan, Dekan Fakultas Sastra Unpad Prof. Dr. Dadang Suganda NIP 131409660 2 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang intensnya penelitian terhadap novel populer Indonesia, sementara di sisi lain perkembangan novel populer begitu pesat sejak tahun 1970-an sampai saat ini dengan berbagai corak dan kemasan sehingga membutuhkan kajian yang lebih intens dalam dunia akademik. -

Part 2 Identity and Citizenship
part 2 Identity and Citizenship ⸪ Laurens Bakker - 9789004329669 Downloaded from Brill.com10/01/2021 11:24:42PM via free access <UN> Laurens Bakker - 9789004329669 Downloaded from Brill.com10/01/2021 11:24:42PM via free access chapter 6 Militias, Security and Citizenship in Indonesia Laurens Bakker The first of June is Indonesia’s annual Pancasila Day. It is celebrated in com- memoration of Soekarno’s presentation on 1 June 1954 of Pancasila, the philo- sophical foundation of the unity of the Indonesian state, embodying ideals of its society and citizenry.1 The day, generally, has dignitaries delivering speeches on the state of Indonesia and the nature of Pancasila. Speaking at a meeting at the People’s Constitutive Assembly (mpr) on Pancasila Day 2012, Vice- President Boediono reminded his audience that, for the continued existence of Indonesia as a nation, creating unity in diversity and finding ways to live together harmoniously were crucial. Ethnic and religious differences should not stand in the way of Indonesian unity as exemplified, Boediono suggested, by the friendship of Soekarno – a Muslim – with Catholic priests during his exile in Flores in 1938. Religious fanaticism, Boediono warned, is a threat to the nation and to the peace of religious minorities (Aritonang, 1 and 2 June 2012). Pancasila’s emphasis on unity is Indonesia’s ultimate ideological source of authority and, as such, is supposed to guide and pervade all legislation. In the preamble of the constitution, the elements of Pancasila are given as (1) belief in the -

Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977
Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977 1 / 3 Download Gratis Film Badai Pasti Berlalu 1977 2 / 3 23 Oct 2012 - 98 minStreaming dan Download Gratis Badai Pasti Berlalu Full movie - aDiEx YouTube. flv on .... 9 Mei 2014 ... Pertama kali gue tahu film Badai Pasti Berlalu itu waktu gue SD, ... Hmm, mungkin gue harus download ulang dengan kualitas yang lebih tinggi .... Download lagu mp3 Download video Badai pasti berlalu, gratis Badai pasti berlalu ... Download Ost Video Film Mp3, juga dilengkapi dengan kumpulan lirik lagu. ... Semusim - By Chrisye - Ost Badai Pasti Berlalu 1977 - Iph's Video Collections. 10 Nov 2014 ... Jadi disini saya mau membahas versi film Badai Pasti Berlalu yang dirilis tahun 1977 dan disutradarai oleh Teguh Karya. Versi film Badai Pasti .... Roy Marten, Christine Hakim, Slamet Rahardjo. ... Her brother introduces her to his friend Leo, who is known as a womanizer. ... What she doesn't know is that Leo decided to be with her as she was a part of a bet.... Badai Pasti Berlalu 1977 Movie Download http://shurll.com/bmymjBadai Pasti Berlalu 1977 Movie Download cc4e9f5eb6 may 18 korean film downloadkachche .... Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 1977. pelangi by chrisye - ost badai pasti berlalu Badai Pasti Berlalu is a 1977 Indonesian film based ... Marga T. Undangan gratis Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film Indonesia yang ... Released in 1977 on (catalog no. download.. Badai Pasti Berlalu adalah sebuah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 1977. Film ini disutradarai oleh Teguh Karya pada tahun 1977 yang .... Film BADAI PASTI BERLALU (1977) Director : Teguh Karya. -

Pembelaan Pada Persebaya Dan Glorifikasi Bonek Dalam Pemberitaan Jawa Pos Tentang Konflik Persebaya Dan Pssi
54 Komuniti, Vol. 10, No. 1, Maret 2018 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623 PEMBELAAN PADA PERSEBAYA DAN GLORIFIKASI BONEK DALAM PEMBERITAAN JAWA POS TENTANG KONFLIK PERSEBAYA DAN PSSI Fajar Junaedi1, Prof. Dr. Heru Nugroho2, Dr. Sugeng Bayu Wahyono3 1Mahasiswa Program Doktor Kajian Budaya dan Media UGM Dosen Ilmu Komunikasi UMY - Yogyakarta 2,3Program Doktor Kajian Budaya dan Media UGM Email:1 [email protected] ABSTRAK Relasi olahraga dan media telah menjadi isu yang signifikan, meskipun jurnalisme olahraga sering disebut sebagai jurnalisme mainan karena sifatnya yang tidak serius dibandingkan dengan jurnalisme politik dan ekonomi. Namun demikian, olahraga bukan sekadar apa yang terjadi di arena olahraga, namun berkelindan dengan beragam aspek lain, mulai dari ekonomi, politik dan sosial. Konflik yang terjadi antara Persebaya dan PSSI sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2017 membuktikan bahwa olahraga bukan hanya apa yang terjadi di lapangan hijau namun berkelindan dengan aspek politik. Oleh Jawa Pos, berita tentang konflik Persebaya dan PSSI tidak lagi dikemas dalam jurnalisme mainan, namun ditempatkan di halaman muka yang biasanya diisi berita politik dan ekonomi. Di sekitar pelaksanaan Kongres PSSI pada tahun 2016 dan 2017, Jawa Pos secara massif mengalokasikan halaman korannya untuk memberitakan tentang Persebaya dan Bonek yang memperjuangkan pengakuan kembali Persebaya oleh PSSI. Jawa Pos dalam berbagai pemberitaannya secara eksplisit membingkai keberpihakan kepada Persebaya dan sekaligus membingkai Bonek sebagai fans yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi dalam membela Persebaya. Bonek dalam pemberitaan Jawa Pos mengenai konflik Persebaya dan PSSI diglorifikasi sebagai pahlawan yang memperjuangkan Persebaya. Keberpihakan Jawa Pos pada Persebaya dan Bonek berujung pada pembelian saham PT Persebaya Indonesia oleh PT Jawa Pos Sportindo, sebuah perusahaan yang menjadi bagian dari konglomerasi Jawa Pos.