Carita Orang Basudara Kisah-Kisah Perdamaian Dari Maluku
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Glossary.Herbst.Bali.1928.Kebyar
Bali 1928 – Volume I – Gamelan Gong Kebyar Music from Belaluan, Pangkung, Busungbiu by Edward Herbst Glossary of Balinese Musical Terms Glossary angklung Four–tone gamelan most often associated with cremation rituals but also used for a wide range of ceremonies and to accompany dance. angsel Instrumental and dance phrasing break; climax, cadence. arja Dance opera dating from the turn of the 20th century and growing out of a combination of gambuh dance–drama and pupuh (sekar alit; tembang macapat) songs; accompanied by gamelan gaguntangan with suling ‘bamboo flute’, bamboo guntang in place of gong or kempur, and small kendang ‘drums’. babarongan Gamelan associated with barong dance–drama and Calonarang; close relative of palégongan. bapang Gong cycle or meter with 8 or 16 beats per gong (or kempur) phrased (G).P.t.P.G baris Martial dance performed by groups of men in ritual contexts; developed into a narrative dance–drama (baris melampahan) in the early 20th century and a solo tari lepas performed by boys or young men during the same period. barungan gdé Literally ‘large set of instruments’, but in fact referring to the expanded number of gangsa keys and réyong replacing trompong in gamelan gong kuna and kebyar. batél Cycle or meter with two ketukan beats (the most basic pulse) for each kempur or gong; the shortest of all phrase units. bilah Bronze, iron or bamboo key of a gamelan instrument. byar Root of ‘kebyar’; onomatopoetic term meaning krébék, both ‘thunderclap’ and ‘flash of lightning’ in Balinese, or kilat (Indonesian for ‘lightning’); also a sonority created by full gamelan sounding on the same scale tone (with secondary tones from the réyong); See p. -

Kualitas Mikrobiologis Dangke Dengan Berbagai Jenis Pelapis Dan Lama Penyimpanan Pada Suhu Ruang Dan Suhu Refrigerasi
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Hasanuddin University Repository KUALITAS MIKROBIOLOGIS DANGKE DENGAN BERBAGAI JENIS PELAPIS DAN LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU RUANG DAN SUHU REFRIGERASI SKRIPSI Oleh AYU SORAYA I 111 11 902 FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016 KUALITAS MIKROBIOLOGIS DANGKE DENGAN BERBAGAI JENIS PELAPIS DAN LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU RUANG DAN SUHU REFRIGERASI Oleh AYU SORAYA I 111 11 902 Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016 ii PERNYATAAN KEASLIAN 1. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ayu Soraya NIM : I 111 11 902 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa: a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli b. Apabila sebagian atasu seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. 2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. Makassar, Maret 2016 Ttd Ayu Soraya i ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan taufik-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kualitas Mikrobiologis Dangke dengan Berbagai Jenis Pelapis dan Lama Penyimpanan yang Berbeda pada Suhu Ruang dan Suhu Refrigerasi Penulis dengan rendah hati mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini utamanya: 1. Ibu Prof. Dr. drh. Hj. Ratmawati Malaka, M.Sc. sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. Muhammad Irfan Said, S,Pt, MP. selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat serta motivasi sejak awal penelitian samapai selesainya penulisan skripsi ini. -

Fenomena Kesenian Karawitan Di Gancahan 8 Godean Sleman Yogyakarta
FENOMENA KESENIAN KARAWITAN DI GANCAHAN 8 GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan oleh: Yunar Cahya Kurniawan 11208241015 JURUSAN PENDIDIKAN SENI MUSIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016 FENOMENA KESENIAN KARAWITAN DI GANCAHAN 8 GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan oleh: Yunar Cahya Kurniawan 11208241015 JURUSAN PENDIDIKAN SENI MUSIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016 i PERSETUJUAN Skripsi yang berjudul Fenomena Kesenian Karawitan di Gancahan 8 Godean Sleman Yogyakarta ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan. Yogyakarta, ……………….. Yogyakarta, ……………….. Pembimbing I Pembimbing II Dr. Ayu Niza Machfauzia, M.Pd Drs. Bambang Suharjana, M.Sn NIP: 19660130 199001 2 001 NIP: 19610906 198901 1 001 ii PENGESAHAN Skripsi yang berjudul berjudul Fenomena Kesenian Karawitan di Gancahan 8 Godean Sleman Yogyakarta ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 11 Maret 2016 dan dinyatakan lulus. DEWAN PENGUJI Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Drs. Sritanto, M.Pd Ketua Penguji ____________ ______ Drs. Bambang Suharjana, M.Sn Sekretaris Penguji ____________ ______ Drs. Kusnadi, M.Pd Penguji I ____________ ______ Dr. Ayu Niza Machfauzia, M.Pd Penguji II ____________ ______ Yogyakarta, April 2016 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Dekan, Dr. Widyastuti Purbani, M.A NIP. 19610524 199001 2 001 iii PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : Yunar Cahya Kurniawan NIM : 11208241015 Program Studi : Pendidikan Seni Musik Fakultas : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. -
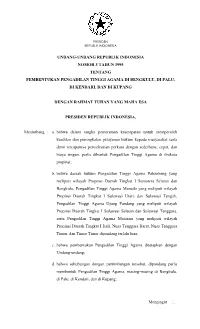
UU Nomor 3 Tahun 1995.Pdf
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota propinsi; b. bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas; c. bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang; d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang; Mengingat :… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEN-TUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG. -

Connecting Orff Schulwerk and Balinese Gamelanаа
Connecting Orff Schulwerk and Balinese Gamelan CAIS Workshop presented by Elisabeth Crabtree, March 9, 2015 e[email protected] or e[email protected] What is Gamelan? Gamelan refers to a set of Balinese instruments that form up a percussion orchestra (metallophones, bamboo xylophones, gongs, drums, other percussion, and the bamboo flute). It also refers to the style of Balinese music that is played upon the instruments. There are over 30 different types of Gamelan, with various tunings. Gamelan groups perform music to accompany dancers, masked dancers (topeng), and puppet shows (w ayang). There are also “sitting pieces” that are just for listening. The music can be both secular and sacred. Why Teach Gamelan? ➢ Translates easily to Orff Instruments, recorder, and small percussion ➢ Uses cycles and ostinatos, music like the elemental style of Orff ➢ Offers opportunities for differentiated instruction ➢ Teaches cultural awareness and diversity ➢ Has direct applications to many 5th grade California State Standards ➢ It has influenced many composers such as Debussy, Satie, Lou Harrison & others ➢ It’s fun and enjoyable! Students love it and remember it many years later Warm Up Hocket Game 123 (ClapStompSnap) ● With a partner, trade off counting to three. Groups of three are no good for this game. ● Add a clap every time someone says “one.” Next add a stomp for “two” and finally a snap for “three.” Celebrate if you make a mistake, and start again. ● Variation: take out the words and only do body percussion ● Celebrate whenever you make a mistake and try again, increasing the speed ● Point out the pattern: The person who starts says “132” and the second person says “213.” ● Final practice phase, two large groups performing the body percussion piece in hocket Hocket Game: Speaking a Rhyme Tell a nursery rhyme with a partner; alternate each person saying a stanza or phrase. -

Indonesia: Crisis Communication Channels
INDONESIA: CRISIS COMMUNICATION CHANNELS Case Studies in Humanitarian Communication Preparedness and Response By Matt Abud 2013 ACKNOWLEDGEMENTS The Internews’ Humanitarian Media Team takes a leadership role in understanding how media and communications plays a role in humanitarian crises. Many thanks are due to a great number of people who helped during this research. They include: the Google Crisis Response team, both for supporting the research and their questions and discussion along the way. Gladys Respati and the whole team at OnTrack Media Indonesia, for going beyond the call with all collaboration and support provided. Juni Soehardjo, for research and several insights in the section on national issues. Many others provided both their time, and greatly facilitated further interviews. They include: colleagues at Palang Merah Indonesia and several IFRC member societies operating in Indonesia, including American Red Cross in Banda Aceh. Staff of local disaster manage- ment agencies in Jakarta; in Kupang and Sikka in east Indonesia (BPBD); and in Aceh (BPBA); and of the national disaster management agency (BNPB). Staff at UNOCHA and at the Australia Indonesia Disaster Reduction Facility. The Urban Poor Consortium for facilitating much of the fieldwork in north Jakarta. And of course numerous journalists, editors, humanitarian workers and digital activists in each of the areas researched gave invaluable insights throughout. Most of all, thanks are due to the residents along the Ciliwung River and in Muara Baru in Jakarta; to the residents displaced from Palue Island; and the residents in Banda Aceh who shared their experi- ences and perspectives. CREDITS Design: Kirsten Ankers, Citrine Sky Design CONTENTS 1. -

The Making of Middle Indonesia Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde
The Making of Middle Indonesia Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Edited by Rosemarijn Hoefte KITLV, Leiden Henk Schulte Nordholt KITLV, Leiden Editorial Board Michael Laffan Princeton University Adrian Vickers Sydney University Anna Tsing University of California Santa Cruz VOLUME 293 Power and Place in Southeast Asia Edited by Gerry van Klinken (KITLV) Edward Aspinall (Australian National University) VOLUME 5 The titles published in this series are listed at brill.com/vki The Making of Middle Indonesia Middle Classes in Kupang Town, 1930s–1980s By Gerry van Klinken LEIDEN • BOSTON 2014 This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution‐ Noncommercial 3.0 Unported (CC‐BY‐NC 3.0) License, which permits any non‐commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. The realization of this publication was made possible by the support of KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies). Cover illustration: PKI provincial Deputy Secretary Samuel Piry in Waingapu, about 1964 (photo courtesy Mr. Ratu Piry, Waingapu). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Klinken, Geert Arend van. The Making of middle Indonesia : middle classes in Kupang town, 1930s-1980s / by Gerry van Klinken. pages cm. -- (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892; volume 293) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-26508-0 (hardback : acid-free paper) -- ISBN 978-90-04-26542-4 (e-book) 1. Middle class--Indonesia--Kupang (Nusa Tenggara Timur) 2. City and town life--Indonesia--Kupang (Nusa Tenggara Timur) 3. -

Campursari Karya Manthous: Kreativitas Industri Musik Jawa Dalam Ruang Budaya Massa
Campursari Karya Manthous: Kreativitas Industri Musik Jawa dalam Ruang Budaya Massa Wadiyo Universitas Negeri Semarang, Kandidat Doktor Seni Pertunjukan UGM Jalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta Timbul Haryono; R.M. Soedarsono Tenaga Pengajar Sekolah Pascasarjana UGM Jalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta Victor Ganap Tenaga Pengajar ISI Yogyakarta. Jln. Parang Tritis, KM 6.5. Sewon, Bantul, Yogyakarta ABSTRACT Manthous’s Campursari is a blend of Javanese gamelan pentatonic music with popular music in Indonesia which is based on Western diatonic music. The tones of gamelan and the frequencies of the tune are all transformed into diatonic tone frequency. However, the harmonization which is used is pentatonic harmony of Javanese gamelan. Manthous’s Campursari has succesfully become one of the major music industries since it is supported by three components, namely the organizers of the music productions, the current distribution of music productions, and the needs of the community. The role of mass media is also very helpful toward the existence of this work. News about Manthous’s and his Campursari spread out widely to the public through the mass media. In a relatively short time of its emergence, Manthous’s Campursari has become a mass cultural Javanese music. Keywords: Campursari, mass culture, music industry ABSTRAK Campursari karya Manthous adalah sebuah campuran dari musik pentatonik gamelan Jawa dengan musik populer di Indonesia yang mengacu pada 2 musik diatonis Barat. Nada gamelan dan frekuensi lagu semuanya ditransformasikan menjadi nada frekuensi diatonis. Namun, harmonisasi yang digunakan adalah harmoni pentatonis gamelan Jawa. Campursari karya Manthous telah berhasil menjadi salah satu industri musik besar karena didukung oleh tiga komponen, yaitu penyelenggara produksi musik, distribusi produksi musik, dan kebutuhan masyarakat. -

Sorowako Dan Sekitarnya Akan Sangat Kental Kami Sajikan
WELCOME TO SOROWAKWHERE TRANQUILITY AND HUSTLE-BUSTLE ENTWINE IN HARMONYO Bersantai di Pantai Ide Trekking di Atap Langit Towuti Buah Tangan dari Bumi Batara Guru Pembaca yang berbahagia, Di edisi ini, nuansa kelokalan Luwu Timur, khususnya Sorowako dan sekitarnya akan sangat kental kami sajikan. Hal itu karena cukup banyak perkembangan dan peruba- han yang mengagumkan terjadi di Sorowako dan sekitarnya dalam waktu dua tahun terakhir. Kota ini tampak terasa semakin hidup dengan munculnya berbagai fasilitas, spot rekreasi hingga tempat nongkrong baru berbasis usaha kecil dan menengah dan in- dustri kreatif. Tentu hal ini menjadi kabar yang membanggakan dan menggembirakan bagi Luwu Timur yang memang memproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Selatan juga motor baru penggerak ekonominya. Editorial Semoga majalah ini dapat menjadi panduan Anda ketika liburan dan jalan-jalan di Sorowako dan sekitarnya. Selamat menjelajah! Salam Dear readers, In this edition, the local nuances of East Luwu, especially Sorowako and its surround- ings, will be very strong. It’s because quite a number of amazing developments and chang- es have taken place in Sorowako and its surroundings in the past two years. This city seems to be increasingly alive with the development of various facilities, recreation spots to new hangout places based on small-medium businesses and creative industries. For sure, this growth brings pride and excitement to East Luwu who is indeed projecting itself as one of the tourist destinations in South Sulawesi, as well as an eco- nomic driving force. We hope this magazine can guide you whenever you are having a holiday or do sight- seeing in Sorowako and its surroundings. -

In Informal Preferencing in Civil Service: Cases from Kupang, Eastern Indonesia
Jo urnal of Asia Pacific Studies ( 2010 ) V ol 1, No 3, 545 -569 Problematizing ‘Ethnicity’ in Informal Preferencing in Civil Service: Cases from Kupang, Eastern Indonesia Sylvia Tidey, University of Amsterdam Abstract In an increasingly interconnected, globalized, world a paradoxical preoccupation with ‘belonging’ draws scholarly attention. This concern with belonging has most dramatically come to the fore in post-Suharto Indonesia in the form of various communal conflicts. Less violent in character, the importance of ‘belonging’ is also voiced in the state-dependent Eastern Indonesian town of Kupang as suspicions regarding informal favoring in local civil service. Informal preferencing in civil service is assumed to be based on ethnic favoring. Reflecting a popular social discourse for marking differences rather than a social reality, however, a focus on ethnicity is more obscuring than helpful in analyzing how informal favoring takes place. This article therefore aims to address the usefulness of ethnicity as an analytical concept. Drawing on several ethnographic examples this article argues that social capital -if necessary complemented with other forms of capital- instead of ‘ethnicity’ facilitates informal preferencing in Kupang’s service. Keywords: civil service, informal favoring, ethnicity Introduction During my fieldwork in city-level government offices in the Eastern Indonesian town of Kupang I often noted suspicions concerning informal favoring in civil servant recruitment. That informal selection procedures exist alongside formal ones was never questioned, but what facilitated one in getting ahead in this informal competition was subject to debate. Oftentimes it was supposed that somehow ‘ethnicity’ had something to do with it, meaning that jobs were given out informally based on ethnic favoring. -
![SUSU POTENSI PANGAN PROBIOTIK. Sri Melia Endang Purwati Yuherman Indri Juliyarsi Ferawati Hendri Purwanto. [24343].Pdf](https://docslib.b-cdn.net/cover/4306/susu-potensi-pangan-probiotik-sri-melia-endang-purwati-yuherman-indri-juliyarsi-ferawati-hendri-purwanto-24343-pdf-1154306.webp)
SUSU POTENSI PANGAN PROBIOTIK. Sri Melia Endang Purwati Yuherman Indri Juliyarsi Ferawati Hendri Purwanto. [24343].Pdf
SUSUPOTENSI PANGAN PROBIOTIK Sri Melia Endang Purwati Yuherman Indri Juliyarsi Ferawati Hendri Purwanto Andalas University Press SUSU POTENSI PANGAN PROBIOTIK Penulis : Sri Melia Endang Purwati Yuherman Indri Juliyarsi Ferawati Hendri Purwanto Desain Sampul : Dyans Fahrezionaldo Tata Letak : Dyans Fahrezionaldo Safriyani Ikhsanul Anwar Syamsul Hidayat ISBN : 978-602-6953-40-7 Ukuran Buku : 23 x 15,5 cm Tahun Terbit : Juli 2018 Cetakan : Pertama Anggota : : Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Dicetak dan diterbitkan oleh : Andalas University Press Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129 Telp/Faks. : 0751-27066 email : [email protected] Hak Cipta Pada Penulis © 2018 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. PRAKATA Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya sehingga buku ajar Susu Potensi Pangan Probiotik dapat penulis selesaikan. Pembahasan materi pada buku ajar ini menjelaskan landasansample andalas teori sampai university pada press hasil (percetakan – hasil penelitian unand) tentng susu dan potensinya sebagai salah satu sumber probiotik yang penulis lakukan di laboratorium. Buku ajar ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam perkuliahan maupun penelitian terkait susu sebagai probiotik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas Peternakan, Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Ketua Bagian Teknologi Hasil Ternak, dan DIKTI dalam skim penelitian PDUPT 2017 serta rekan-rekan peneliti yang terlibat selama penelitian dan penulisan buku ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini sangat penulis harapkan. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca terutama mahasiswa untuk materi tambahan perkuliahan maupun pembahasan hasil penelitian. -

Dangke: Kuliner Khas Masyarakat Enrekang Dangke: Specific Culinary Enrekang Society
WALASUJI Volume 12, No. 1, Juni 2021: DANGKE: KULINER KHAS MASYARAKAT ENREKANG DANGKE: SPECIFIC CULINARY ENREKANG SOCIETY Masgaba Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166 Pos-el: [email protected] ABSTRACT This study aimed to describe the processing methods and cultural values contained in the business of making Dangke. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The study result showed that Dangke is a kind of Enrekang people’s culinary. Initially, buffalo milk was the main ingredient used in making dangke, but it is replaced with milk from dairy cows today, because of the population of buffalo has decreased. The process of making Dangke used simple technology. Dangke was made using a coconut shell, thus its shaped like a dome, then packed using banana leaves. The values contained in the business of making Dangke were the cultural, social, economic, cooperation, accuracy, and used-effort values. Keywords: dangke, culinary, values. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pengolahan dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam usaha pembuatan dangke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dangke merupakan kuliner khas masyarakat Enrekang. Pada awalnya, susu kerbau merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan dangke, tetapi saat ini diganti dengan susu sapi perah, karena populasi kerbau sudah berkurang. Pembuatan dangke diolah dengan teknologi sederhana. Dangke dicetak dengan menggunakan tempurung kelapa, sehingga berbentuk seperti kubah, kemudian dikemas dengan menggunakan daun pisang.