Ÿþm Icrosoft W
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SURVEI NASIONAL DAN KAJIAN OPINI PUBLIK; REFLEKSI PENANGANAN PANDEMI DAN DAMPAK KONSTELASI POLITIK 2024 Pengantar
INDONESIA POLITICAL OPINION SURVEI NASIONAL DAN KAJIAN OPINI PUBLIK; REFLEKSI PENANGANAN PANDEMI DAN DAMPAK KONSTELASI POLITIK 2024 Pengantar Lembaga riset sosial dan opini berbasis kajian akademik. Telah melakukan penelitian dalam bidang media, demokrasi, isu gender dan politik sejak tahun 2013. Indonesia Political Opinion (IPO) dalam kemajuannya fokus pada riset sosial terkait politik dan opini publik. IPO berkantor pusat di Jl. Tebet Raya, No. 2D, Jakarta. dan telah memiliki perwakilan tetap di Kota Bandung, Yogyakarta, Kota Batam dan Kota Mataram. Visi dan Misi IPO, menjadi lembaga kajian berbasis riset yang INDONESIA menguatkan relasi civil society, dan meneguhkan Demokrasi POLITICAL OPINION sebagai sistem politik berkeadaban, serta menjunjung tinggi keterbukaan. Direktur Eksekutif Dr. Dedi Kurnia Syah Putra INDONESIA Metodologi POLITICAL OPINION Multistage random sampling (MRS) IPO terlebih dulu menentukan sejumlah Desa untuk menjadi sample, pada setiap desa terpilih akan dipilih secara acak –menggunakan random kish NASIONAL grid paper– sejumlah 5 rukun tetangga (RT), pada setiap RT dipilih 2 keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih 1 responden dengan pembagian PROP 1 PROP K laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor genap, sehingga total responden laki-laki dan perempuan. Pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak. DS 1 … DS N DS 1 … DS M Metode ini memiliki pengukuran uji kesalahan (sampling error) 2.50 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat. Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. KK KK KK KK KK Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. -

ADVISORY October 2019
ADVISORY October 2019 Second Term Cabinet Members Announced: New and Old Faces Today (Wednesday, 23 October 2019), President Joko Widodo officially announced the members of his new “Indonesia Maju/Onwards Indonesia” Cabinet that will work with him in the second term of his presidency. Along with the announcement of the new members, in the new Cabinet some of the titles have changed, such as ‘The Coordinating Minister of Maritime Affairs and Resources’ which has been changed to ‘The Coordinating Minister of Maritime Affairs and Investment’ and ‘The Minister of Tourism’ which has been changed to ‘The Minister of Tourism and the Creative Economy’. Several ministers who served during President Joko Widodo’s first term such as Sri Mulyani Indrawati and Yasonna Laoly also made a comeback along with many new faces. The new faces include prominent youth and professional figures who are pioneers and leading individuals in their respective fields. The announcement of such names as Nadiem Makarim, Erick Thohir and Wishnutama Kusubandio as new Cabinet members has been received positively by the general public. Below is a complete list of the newly appointed Cabinet members. 1. Coordinating Minister in the Field : Mohammad Mahfud of Law, Politics and Security (Mahfud MD) 2. Coordinating Minister in the Field : Airlangga Hartarto of the Economy 3. Coordinating Minister of Maritime : Luhut Binsar Pandjaitan Makarim & Taira S. Affairs and Investment Summitmas I, 16th & 17th Fls. 4. Coordinating Minister in the Field : Muhajir Effendy Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 of Human Development and Culture Indonesia 5. Minister of Defense : Prabowo Subianto P: (62-21) 5080 8300, 252 1272 F: (62-21) 252 2750, 252 2751 6. -

Keputusan Presiden No. 84/P Tahun 2009
www.bpkp.go.id KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/P TAHUN 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 telah menetapkan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 periode 2009-2014, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2009; b. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009- 2014; c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan mengangkat sebagai Menteri Negara terhitung mulai saat pelantikan, masing- masing: 1. Sdr. Marsekal TNI (Purn) Djoko - Menteri Koordinator Bidang Suyanto Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Sdr. dr. H. R. Agung Laksono - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Sdr. Sudi Silalahi - Menteri Sekretaris Negara; 5. Sdr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. - Menteri Dalam Negeri; 6. -

Yusri Wahyuni Nim: 16160480000004
URGENSI LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: YUSRI WAHYUNI NIM: 16160480000004 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1439 H / 2018 M LEMBAR PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Yusri Wahyuni Nim : 16160480000004 Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 13 Mei 1996 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Syariah dan Hukum Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 10 Juli 2018 YUSRI WAHYUNI NIM:16160480000004 iv ABSTRAK Yusri Wahyuni, NIM 16160480000004,“Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H/2018 M. x + 72 halaman 5 lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan melihat perbandingan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, komposisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta melihat urgensi nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. -

Mengawal-Demokrasi-Pengalaman
MENGAWAL DEMOKRASI Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUUPA Tim Penulis Salemba Tengah Diterbitkan atas kerja sama 2007 Mengawal Demokrasi Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUUPA Cetakan Pertama, 2007 xvi - 198, 15 x 21 cm ISBN: ............................. Penulis : Tim Salemba Tengah Pengantar : Yappika Otto Syamsuddin Ishak Tata Letak: Moelanka Cover : Moelanka Diterbitkan oleh: Yappika Jl. Pedati Raya No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, Phone: +62-21-8191623, Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670, e-mail: [email protected] Buku ini diterbitkan atas dukungan CIDA Buku ini di dedikasikan kepada seluruh elemen gerakan masyarakat sipil di Aceh Pengatar Penerbit Belajar Demokrasi Dari Aceh ceh, dengan situasi konfliknya yang panjang, pernah membuat kita marah dan menangis ketika menyaksikan kekerasan yang Aterjadi secara sistematik telah menyebabkan harkat dan martabat kemanusiaan di Aceh berada pada titik yang paling rendah. Aceh pun, dengan perjalanannya yang panjang menuju perdamaian yang penuh liku, pernah membuat kita lega ketika terjadi beberapa kali pembicaraan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung dalam hitungan puluhan tahun itu. Dan sekali lagi, kita pun merasa penuh harap bercampur was-was ketika terjadi nota kesepakatan damai di Helsinski. Penuh harap karena kita menginginkan kesepakatan Helsinski ini benar-benar menjadi akhir dari konflik Aceh, menyusul beberapa skema penyelesaian konflik sebelumnya yang tidak pernah berujung pada kondisi damai yang sesungguhnya. Beberapa skema penyelesaian konflik yang digagas sebelumnya justru berakhir dengan meningkatnya eskalasi konflik, baik dalam bentuk perang argumen para pihak maupun perang bersenjata yang terus menambah jatuhnya korban jiwa dan harta. Kita was-was karena khawatir perjanjian Helsinki akan terperosok pada lubang yang sama, seperti yang pernah terjadi pada inisiatif-inisiatif perdamaian sebelumnya. -

Kata Airlangga, Golkar Dan PPP Punya Banyak Kesamaan
Kata Airlangga, Golkar dan PPP Punya Banyak Kesamaan Realitarakyat.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki banyak kesamaan. “Jadi kalau diperhatikan Partai Golkar dan PPP ini ada beberapa kesamaan,” kata Airlangga usai makan malam bersama Ketum PPP Suharso Monoarfa di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (30/3/2021) malam. Airlangga menjelaskan kesamaan antara Golkar dan PPP diantaranya warna bendera Partai Golkar didominasi warna kuning, dengan pohon beringin warna hijau di tengahnya. Kemudian bendera PPP didominasi warna hijau, dengan banyak warna kuning. Selain itu, Golkar dan PPP bersama-sama bekerja dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mengawal operasionalisasi UU Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah hingga peraturan Presiden. “Terkait politik, kita sama-sama sepakat untuk tidak merubah UU terkait Pilkada,” ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa jika dua partai itu merupakan partai yang memiliki banyak kesamaan diantaranya sama-sama go publik, partai terbuka, bisa dimiliki siapa saja hingga partai berada di tengah. “Kita membicarakan hal-hal ke depan, tentu ada tahapanannya, seperti yang kami nikmati makan malam saat ini,” kata Suharso. Selain sebagai ketua umum partai, mereka berdua juga menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Airlangga Hartarto saat ini sebagai Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Sementara Suharso Monoarfa merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas).[prs]. -

Highlights of the Week
YOUR GUIDE TO INDONESIA’S POLITICAL & BUSINESS AFFAIRS | September 14th, 2018 Highlights of the week Team Jokowi forges ahead, Team Prabowo struggles The battle between Joko “Jokowi” Widodo and Prabowo Subianto are entering new phase. With the election campaign slated to start on Sept.23, incumbent President Jokow has put together his dream team. On the other hand, challenger Prabowo was reported to struggle building his own dream team. Overcoming the outbreak of the collective corruption Corruption oh corruption. The recently exposed collective corruption cases in several regional legislative councils are carrying two urgencies: the need for long-term anti-corruption programs and electoral system restructuring to end the vicious circle of corruption. OJK involves fintech association to police industry The Financial Services Authority (OJK) has stepped up its enforcement on the rapidly growing financial technology sector (fintech). The issuance of Regulation No. 13/2018 provides a thorough legal umbrella for the industry. With a lot of untapped potentials available, the regulator is teaming with industry’s players, such as the Indonesian Fintech Association (AFTech Indonesia) to avoid taking the wrong step. A fresh start to fix Garuda’s financial woes State owned airline Garuda Indonesia is attempting for a fresh start after being trapped with corruption and mismanagement issues. The appointment of new president director is slated to rejuvenate the biggest premium class airline in Indonesia. Nevertheless, tough challenges await the new board to bringing the company back on track. SUBSCRIBERS COPY, NOT FOR DISTRIBUTION For subscription: [email protected] 2 POLITICS Team Jokowi forges ahead, Team Prabowo struggles With the election campaign slated to start on Sept. -

Kandidat Capres-Cawapres Dari Klaster Menteri
TEMUAN SURVEI CAPRES-CAWAPRES POTENSIAL 2024 BERDASARKAN KLASTER FIGUR PENGANTAR . Kendati pemilihan presiden (pilpres) 2024 masih kurang tiga tahun lagi, namun riset opini publik soal siapa figur-figur yang potensial meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional mendatang perlu dilakukan secara reguler. Hal ini penting mengingat bahwa seorang presiden ataupun wakil presiden bukan lahir dari ruang kosong. Rekam jejak (track record), kapasitas, dan integritas yang jelas merupakan modal penting untuk mendapatkan dukungan publik. Survei ini bermasuksud mendeteksi secara dini siapa figur anak bangsa yang potensioal jadi capres-cawapres 2024. Tentu karena 2024 tidak ada incumbent, maka peta pilpres mendatang akan sangat cair dan kompetitif. Apalagi menurut temuan survei kami Arus Survei Indonesia—dan juga temuan survei lembaga-lembaga lainnya—belum ada figur paling dominan elektabilitasnya. Sehingga setiap anak bangsa punya peluang yang sama untuk memilih dan dipilih. Atas dasar itulah, Arus Survei Indonesia melakukan pengukuran terhadap figur putra-putri terbaik bangsa yang layak jadi capres-cawapres 2024 dari berbagai klaster. Ada klaster Partai Politik, Kepala Daerah, Menteri, TNI, Polisi, Tokoh Agama, Akademisi-Teknokrat dan Pengusaha. Harapannya, selain publik disuguhkan menu pilihan lebih variatif dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, ini juga bagian upaya kita terhindar dari istilah memilih pemimpin bak kucing dalam karung. Artinya, semakin banyak pilihan capres-cawapres maka semakin baik bagi publik. Semakin cepat capres-cawapres muncul maka kesempatan publik untuk ‘menguliti’ rekam jejaknya juga semakin panjang waktunya. TEMUAN SURVEI NASIONAL Periode Survei : 1 - 7 Mei 2021 2 METODOLOGI SURVEI . Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah Multistage Random Sampling. Jumlah responden yakni 1000 responden dengan margin of error +/- 3.10% pada tingkat kepercayaan 95%. -

Keppres No 84 Tahun 2009
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 84/P TAHUN 2009 .: .: .I PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA, Menintbang : a. bahwa Kornisi a~&ilihan,Urnurn dengan Keputusan Nomor -373/~pit&PU/~ahun2009 tanggal 18 Agustus 2009 telah menetapkan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono sebagai Residen dan WakiI Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 peiiode 2009-2014, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik di hadapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2009; b. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalarn menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalarn rangka mewujudkan tujuan nasional, dipandang perlu membentuk dan menganglcat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu 11 periode 2009-20 14; c. bahwa rnereka yang namanya tercantum dalarn diktum PERTAMA Kepiatusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Qbinet Indonesia Bersatu 11; Mengingat : I. Pasal4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (I), ayat (21, &n ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 166, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nornor 49 16); PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSW : , Menetapkan : FERTAMA : Membentuk Kabinet Indonesia. Bersatu I1 periode 2009-2014 dan .., .. nlenganght sebagai Menteri Negara terhitung rnulai saat pelantikan, masing-masing : ,' 1. Sdr. Marsekal TNI (Purn) - Menteri Koordinator Bidang 6. Djoko Suyanto ..' , politik, Hh,dan Keamanan; 2. Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa - Menteri Koordinator ida an^ . 3. Sdr. dr. H. R ~guniLaksono - Menteri ~oordinatorBidang 6. Sdr. Dr. Raden Mohammad - Menteri Luar Negeri; arty~ulkna Natakgawa 7. Sdr. Prof. Dr. Ir. Purnomo - Menteri Pertahanan; Yusgiantoro 8. -

Jelang Pemerintah Umumkan Nasib Demokrat, Golkar Dan PPP Adakan Pertamuan
Jelang Pemerintah Umumkan Nasib Demokrat, Golkar dan PPP Adakan Pertamuan Realitarakyat.com – Jelang Pemerintah mengumumkan keputusan terkait Kisruh Partai Demokrat antarakubu Cikeas dengan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) sebagai ketua umum dengan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) yang rencananya di umumkan pada Rabu (31/3) besok , Partai Golkar dan PPP adakan pertemuan. Sehingga menjadi pertanyaan apakah ada hubungan dengan Demokrat, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan sama sekali tidak ada kaitannya. ” Ini hanya silaturrahmi politik saja, Sebagaimana diketahui beberapa pekan lalu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto bertandang dan bersilaturahmi ke kediaman Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Sabtu 13 Maret 2021. Kini Airlangga kembali menerima kunjungan politik dari Ketum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (30/3/2021), ” Ujar Lodewijk F. Paulus Sekjen Partai Golkar yang juga mantan Pangdam Bukit Barisan ini. Terlihat Airlangga bersama jajaran kepengurusan DPP Partai Golkar menyambut kehadiran Suharso dan rombongan di lobi kantor DPP partai berlambang pohon beringin tersebut. Adapun, rombongan Suharso tiba di lokasi sekitar pukul 19.14 WIB. Kedua pimpinan partai tersebut saling bertegur sapa dan sesekali melontarkan canda tawa. Setelah itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu pun langsung mempersilahkan Suharso dan rombongan menuju tempat pertemuan. Kendati demikian, kedua pimpinan parpol tersebut tak ada satupun yang menyinggung perihal topik yang dibahas dalam pertemuan malam ini. Selanjutnya, pertemuan pun dilangsungkan secara tertutup. Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyampaikan bahwa pertemuan kedua pimpinan parpol tersebut membahas sejumlah hal terkait situasi politik nasional. Salah satunya, terkait pembahasan mengenai RUU Pemilu. “Apakah itu berkaitan dengan keluar masuknya RUU Pemilu, namanya aja pembicaraan politik. -
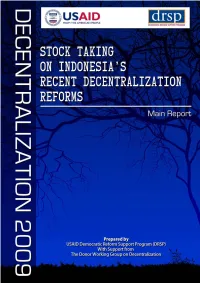
Decentralisation Indonesia Summary Report 2009
DECENTRALIZATION 2009 Stock Taking on Indonesia’s Recent Decentralization Reforms Update 2009 Main Report Stock Taking on Indonesia’s Recent Decentralization Reforms Update 2009 DECENTRALIZATION 2009 DECENTRALIZATION 2009 Stock Taking on Indonesia’s Recent Decentralization Reforms Update 2009 Main Report Prepared by USAID Democratic Reform Support Program (DRSP) With support from the Donor Working Group on Decentralization July 2009 Stock Taking on Indonesia’s Recent Decentralization Reforms Update 2009 Published by Democratic Reform Support Program (DRSP) Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 20th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Tel. No. ++ 62 21-5152541 Fax. No. ++ 62 21 5152542 Email: [email protected] Web. www.drsp-usaid.org v DECENTRALIZATION 2009 pReface MAX POHAN Deputy for Regional Development and Regional Autonomy BAPPENAS IN ACCOrdANCE with the National Long-term This study is expected to form the input for the Development Plan (RPJPN) 2005-2025 that is di- preparation of the policy and planning for the RPJMN rected towards improving the implementation of 2010-2014. In addition, the lessons contained within decentralization and regional autonomy during the it can also provide useful input in the revision of Law period 2010-2014, within the context of the prepa- No. 32 of 2004 on Regional Administration. ration of the National Medium-term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 a review of the decentral- We would like to express our appreciation for the ization and regional autonomy policy needs to be support and cooperation of the various parties conducted. This is expected to provide input for the that have made it possible to conduct this study reformulation of the decentralization and regional effectively, especially the USAID Study Team as the autonomy policy in Indonesia. -
Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy
Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Djayadi Hanan, M.A. Graduate Program in Political Science The Ohio State University 2012 Dissertation Committee: R. William Liddle, Adviser Richard Paul Gunther Goldie Ann Shabad Copyright by Djayadi Hanan 2012 i Abstract This study explores the phenomenon of executive – legislative relations in a new multiparty presidential system. It seeks to understand why, contrary to arguments regarding the dysfunctionality of multi-party presidential systems, Indonesia’s governmental system appears to work reasonably well. Using institutionalism as the main body of theory, in this study I argue that the combination of formal and informal institutions that structure the relationship between the president and the legislature offsets the potential of deadlock and makes the relationship work. The existence of a coalition-minded president, coupled with the tendency to accommodative and consensual behavior on the part of political elites, also contributes to the positive outcome. This study joins the latest studies on multiparty presidentialism in the last two decades, particularly in Latin America, which argue that this type of presidential system can be a successful form of governance. It contributes to several parts of the debate on presidential system scholarship. First, by deploying Weaver and Rockman’s concept of the three tiers of governmental institutions, this study points to the importance of looking more comprehensively at not only the basic institutional design of presidentialism (such as dual legitimacy and rigidity), but also the institutions below the regime level which usually regulate directly the daily practice of legislative – executive relations such as the legislative organizations and the decision making process of the legislature.