Bukanlah Sesuatu Yang Baru 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Youth Perception on Features and Accessibility of Bus Rapid Transit Mebidang in Bridging Interconnected Areas in North Sumatera
International Journal of Research and Review www.ijrrjournal.com E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237 Research Paper Youth Perception on Features and Accessibility of Bus Rapid Transit Mebidang in Bridging Interconnected Areas in North Sumatera Yusuf Aulia Lubis, Sirojuzilam, Suwardi Lubis Regional Planning Department, School of Post-Graduate, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia Corresponding Author: Yusuf Aulia Lubis ABSTRACT One of Indonesian problems in infrastructure development is how to nationally avail Bus Rapid Transit having transit rail system in its development system. In the macroeconomic perspective, the availability of urban transport infrastructure services can affect the marginal productivity of private capital, while in the microeconomic perspective; such services can also decrease production costs. Moreover, the contribution of urban transport infrastructure to improving quality of life is indicated by the increase in welfare, productivity and access to employment, as well as macroeconomic stability. This research is descriptive trying to gain youth’s perception on Bus Rapid Transit in Medan. In this study, the primary and secondary data sources are used and the populations include all users of Trans Mebidang. The samples are taken from those using the routes of Tanjug Anom to Down Town (or Pusat Kota), Jamin Ginting to Down Town, and Simpang Pos to Down Town and the samples chosen are only 15% of population. Sampling technique is purposive and accidental. It can be concluded that partially the Feature Perception (X1) gives impacts on the uutilization of Trans Mebidang and partially the Accessibility Perception also brings effect to the utilization of Trans Mebidang. Keywords: perception, features, accessibility, bus rapid transit, Medan INTRODUCTION Mamminasata). -

Studi Kinerja Operasional Dan Kualitas Kepuasan Layanan Bus Trans Mebidang Koridor 1 Dan Koridor 2 Menggunakan Persepsi Penumpang
STUDI KINERJA OPERASIONAL DAN KUALITAS KEPUASAN LAYANAN BUS TRANS MEBIDANG KORIDOR 1 DAN KORIDOR 2 MENGGUNAKAN PERSEPSI PENUMPANG TESIS Oleh COK NANDO PANONDANG 157016003 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2018 Universitas Sumatera Utara STUDI KINERJA OPERASIONAL DAN KUALITAS KEPUASAN LAYANAN BUS TRANS MEBIDANG KORIDOR 1 DAN KORIDOR 2 MENGGUNAKAN PERSEPSI PENUMPANG TESIS Untuk Memperoleh Gelar Magister Teknik dalam Program Studi Magister Teknik Sipil pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Oleh COK NANDO PANONDANG 157016003 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2018 Universitas Sumatera Utara Judul Tesis : STUDI KINERJA OPERASIONAL DAN KUALITAS KEPUASAN LAYANAN BUS TRANS MEBIDANG KORIDOR 1 DAN KORIDOR 2 MENGGUNAKAN PERSEPSI PENUMPANG Nama Mahasiswa : Cok Nando Panondang Nomor Pokok : 157016003 Program Studi : Teknik Sipil Bidang Studi : Manajemen Prasarana Publik Menyetujui Komisi Pembimbing, Tanggal Lulus: 23 Agustus 2018 Universitas Sumatera Utara Telah Diuji Pada Tanggal : 23 Agustus 2018 PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE Anggota : Medis Sejahtera Surbakti, ST, MT, Ph.D Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia, M.Sc Ir. Zulkarnain A. Muis, M.Eng. Sc Universitas Sumatera Utara PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diakui dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Medan, Oktober 2018 COK NANDO PANONDANG 157016003 Universitas Sumatera Utara ABSTRAK Sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Medan kian hari semakin akut. -

Press Release/Informasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia Desember2016
PRESS RELEASE/INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA DESEMBER2016 Perihal: Transportation Outlook 2017 Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) adalah suatu organisasi profesi independen dan nir-laba yang menyediakan platform komunikasi dan diskusi dalam permasalahan transportasi di Indonesia. MTI membangun aliansi dengan berbagai organisasi nasional dan internasional dalam mendorong diskursus publik dalam isu-isu nasional dan lokal transportasi diharapkan kebijakan publik dalam bidang transportasi dapat diimplementasikan sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Gambaran Umum Gambaran mengenai transportasi 2016 adalah pergantian Menteri Perhubungan dari Ignasius Jonan kepada Budi Karya Sumadi. Pergantian kepemimpinan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dan gaya kepemimpinan yang berimplikasi pada layanan publik. Namun komitmen untuk terus membangun sarana transportasi di daerah-daerah agar bisa saling berhubungan satu sama lain, tetap dilanjutkan. Konektivitas itu diperlukan sebagai konsekuensi dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun untuk mewujudkannya diakui oleh Menteri Budi Karya, bukan hal yang mudah, karena adanya kompleksitas yang dihadapi. Penyelesaian masalah transportasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena layanan transportasi yang baik akan menjamin mobilitas warga dan barang semakin lancar, sehingga barang-barang kebutuhan pokok dapat terdistribusi secara merata, Outlook Transportasi 2017 - MTI Pagina 1 dan mobilitas -

Evaluasi Penyelenggaraan Tiket Terpadu Antar Moda
EVALUASI PENYELENGGARAAN TIKET TERPADU ANTAR MODA (TITAM) DI STASIUN GAMBIR Siti Maimunah *l Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat A BS1RACT Organizing TIT AM or inter-modal integrated ticketing is a form of public transport service impravement in praviding service and convenience for the users in order to support the imple mentation of inter-modal transport effectively and efficiently. By using conjoint analysis method is expected to knaw the preferences of respondents in the implementation of TIT AM, while the descriptive analysis is used to evaluate the implementation TIT AM. The results shaw that not many people who knaw TITAM evident from the survey results there are 60 % of respondents do not know TITAM. Hawever, the expected of respondents by TITAM implementation is to increase comfort and to reduce queues in the purchase of tickets to make shorter travel time. Through conjoint analysis method was concluded that the willingness of society to the imple mentation of TIT AM are buying tickets online and manual (in combination), and type of elec tronic tickets, as well as connecting mode of train, bus and ship the first choice of respondents who indicated the highest utility or satisfaction for service users. Keywords: integrated ticket, conjoint analysis PENDAHULUAN Kemacetan lalu lintas merupakan menengah ke atas untuk lebih memilih permasalahan yang sudah dianggap hal menggunakan kendaraan pribadi dalam yang wajar di Jakarta dan bahkan melakukan aktivitas sehari-hari. kemacetan yang tetjadi saat ini mencakup Kondisi tersebut mencerminkan bahwa area yang lebih luas, tidak hanya di pusat pemerintah belum mampu menyediakan pusat kota Jakarta namun juga ke area angkutan umum yang sesuai dengan sekitarnya. -

Analisis Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Damri
ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAMRI BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN DPD BEKERJASAMA DENGAN TENAGA KONSULTAN Dr. HENDRI SAPARINI I. Pendahuluan Perusahaan Umum DAMRI merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 yang menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang, angkutan perintis berdasarkan penugasan Pemerintah, dan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kegiatan pelayanan angkutan Perum DAMRI ini dilaksanakan oleh Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada era 70-an, hampir seluruh masyarakat Indonesia begitu akrab dengan perusahaan yang mengelola jasa angkutan ini. Namun, setelah rentang waktu puluhan tahun, jasa angkutan jalan raya ini bukan lagi “milik” Perum DAMRI, lantaran persaingan yang ketat. Hal ini dikarenakan mulai menjamurnya berbagai perusahaan otobus yang dikelola swasta murni secara profesional yang memberikan fasilitas lebih menawan. Selain itu, muncul pula berbagai permasalahan dalam tubuh Perum DAMRI yang pada akhirnya menuai demo besar dan aksi mogok kerja, khususnya dari ratusan kru bus DAMRI. Ratusan kru bus ini menuntut hak-hak normatif, seperti gaji dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang belum dibayarkan. Permasalahan Perum DAMRI pun semakin meluas pada besaran gaji dan status kekaryawanan para kru yang belum memperoleh kejelasan. Salah satu alasan mengapa Perum DAMRI belum membayarkan gaji dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada para karyawannya adalah karena kondisi keuangan Perum DAMRI yang sedang bermasalah, dimana antara penerimaan dan biaya operasional tidak seimbang. Hal ini dikarenakan hanya trayek-trayek khusus saja yang bisa memberikan keuntungan bagi Perum DAMRI, seperti trayek jurusan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang bersifat monopolistik. -

Manajemen Angkutan Umum
5/23/2016 MANAJEMEN ANGKUTAN UMUM Latar Belakang Angkutan Umum sebagai Obat Mujarab Permasahalan Transportasi Perkotaan 1 5/23/2016 3 Singapura di Tahun 1970-an 2 5/23/2016 Singapura Saat Ini 5 Korea tahun 1990-an 6 3 5/23/2016 Korea Saat Ini 7 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN SEBAGAI PROGRAM NASIONAL (NKRI) (Bukan hanya program Kemenhub, bukan hanya program Pemda, dan bukan hanya program Perum DAMRI/PPD) Merupakan visi dan misi Sesuai Dengan Pemerintahan Jokowi-JK Dituangkan dalam Amanat UU 22/2009 (Nawa Cita) sebagai satu- RPJMN 2015-2019 & PP 74/2013 satunya visi Pemerintah dan (Perpres No. 2/2015) Pemda Telah dituangkan dalam Seharusnya Seharusnya didukung dan Renstra Kemenhub didukung dalam program dituangkan dalam Renstra 2015-2019 Kementerian/Lembaga 2015-2019 di Pemda terkait (KM No. KP.430/2015) terkait 4 5/23/2016 KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ “ Pasal 139 ” • Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara; • Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi; • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. • Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RPJMN 2015-2019 6.6.2 MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN SASARAN 1. MENINGKATKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN A. -

Integrated Improvement Plan for the MRT Station and Bus Terminal in Blok M Area
Integrated Improvement Plan for the MRT Station and Bus Terminal in Blok M Area Study Report February 2006 Engineering and Consulting Firms Association, Japan Nippon Koei Co., Ltd. This work was subsidized by the Japan Keirin Association through its Promotion funds from KEIRIN RACE. Integrated Improvement Plan for MRT Station and Bus Terminal in Block M Area Table of Contents Executive Summary…………………………………………………………………... 1. Introduction .......................................................................................................1 1.1 Background ..........................................................................................1 1.2 Objectives.............................................................................................1 1.3 Target area............................................................................................1 2. Existing Conditions............................................................................................3 2.1 Outline of socio-economy and transport problems. ...............................3 2.2 Public transport.....................................................................................4 2.3 Urban structure.....................................................................................7 2.4 Existing urban management and control policies...................................7 2.5 Consideration on expected role of Block-M ..........................................7 3. Current Conditions of Block-M..........................................................................9 -

THE ROLE of HISTORICAL SCIENCES on the DEVELOPMENT of URBAN PUBLIC TRANSPORTATION in 21St CENTURY INDONESIA
THE ROLE OF HISTORICAL SCIENCES ON THE DEVELOPMENT OF URBAN PUBLIC TRANSPORTATION IN 21st CENTURY INDONESIA 1 Muhammad Luthfi Lazuardi, 2 Moses Glorino Rumambo Pandin 1 2 Faculty of Humanities, Airlangga University [email protected]; [email protected] ABSTRACT Public transportation is one of the most critical needs for a city, including in Indonesia. The fast and dynamic movement of society makes public transportation expected to accommodate the needs of city residents to move more quickly and efficiently. Available public transport can also reduce congestion because many city residents are switching from their private vehicles. Many cities in Indonesia are competing to develop their public transportation to modernize the life of the town. Problems will arise if the city government does not learn from history in planning the development of public transport in the city. This study aims to examine the role of historical science in the development of urban public transportation in Indonesia. The method used in this research is descriptive-qualitative through literature review by analyzing data and information according to the topic of the research topic. The data and information are sourced from 20 journal articles and five credible online portal sites with published years between 2019-2021. The result of this study is the role of historical science in the development of urban public transportation in Indonesia as a reference for city governments to reorganize their transportation systems in the future. This research has research limitations on the development of urban public transport in Indonesia in the 21st century. -

Perum Damri) Kantor Pusat Matraman Jakarta Timur
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI) KANTOR PUSAT MATRAMAN JAKARTA TIMUR ZUZEN MEDI CANDRA 8135128159 Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016 ii iii KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Sub Bagian Pemasaran Perum Damri Kantor Pusat, Matraman, Jakarta Timur tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Berbagai tantangan dan kendala pun dihadapi praktikan dalam proses penyusunan Laporan Praktik Kerja. Ungkapan terimakasih praktikan tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan kepada praktikan, yaitu : 1. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM,M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan 2. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM,M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 3. Bapak Drs. NurdinHidayat, MM,M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 4. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 5. Ibu Wiwin, Bapak Heri dan Bapak Bondet selaku pembimbing praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Perum Damri Kantor Pusat 6. Bapak Dono Unggul selaku Senior Manajer Pemasaran, Bapak Boko dan Bapak Haris selaku Asisten Senior Manajer Pemasaran Perum Damri Pusat, yang telah memberi kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 7. -
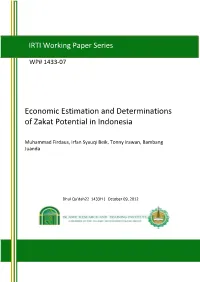
Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia
IRTI Working Paper Series WP# 1433‐07 Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda Dhul Qa’dah22 1433H | October 09, 2012 Abstract The Government of Indonesia has granted zakat fund as one of financial sources for the country in addition to tax fund. The collection and distribution of zakat fund should be improved continuously. For indonesia case, the number of research related to zakat potential is still limited. This study aims to estimate the potential of zakat in Indonesia and explore the relationship between demographic characteristics and zakat payment. The primary data were obtained through survey in two cities and two districts comprising 345 households, whereas the secondary data were obtained from many sources. The empirical analysis are done through descriptive and multivariate analysis. The results show that total of all zakat potential in Indonesia from various sources is approximately 217 trillion rupiah. This number is equal to 3.4% of Indonesia’s 2010 GDP. The study shows that education, occupation and income are important factors which influence respondent’s frequency and choice of place when paying zakat and alms. Keywords: zakat development, income transfer, logistic regression IRTI Working Paper Series has been created to quickly disseminate the findings of the work in progress and share ideas on the issues related to theoretical and practical development of Islamic economics and finance so as to encourage exchange of thoughts. The presentations of papers in this series may not be fully polished. The papers carry the names of the authors and should be accordingly cited. -
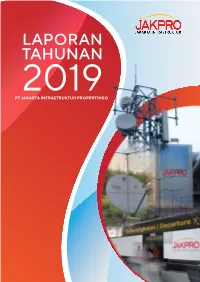
Annual-Report-2019.Pdf
2 LAPORAN TAHUNAN 2019 PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO 3 PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO LAPORAN TAHUNAN 2019 DAFTAR ISI 01 RINGKASAN KINERJA KEUANGAN 8 Total Aset 8 Total Liabilitas 8 9 Total Ekuitas Pendapatan Usaha 9 Laba (Rugi) Bersih 10 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN 11 12 IKHTISAR KINERJALAPORAN MANAJEMEN IKHTISAR KINERJALAPORAN Laporan Posisi Keuangan 13 Laporan Laba Rugi 14 Laporan Arus Kas Rasio Keuangan 15 02 LAPORAN MANAJEMEN 17 Laporan Dewan Komisaris 17 Profil Dewan Komisaris 20 Laporan Direksi 23 Profil Direksi 26 4 LAPORAN TAHUNAN 2019 PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO 03 PROFIL PERUSAHAAN 28 Identitas Perusahaan 28 Sejarah Singkat Perusahaan 30 Visi Misi Perusahaan 29 Nilai Perusahaan 31 Bidang Usaha 35 Struktur Perusahaan 36 Sumber daya Manusia 39 Pengembangan Sumber daya Manusia 45 PROFIL PERUSAHAAN Bidang Hukum 49 Bidang Keuangan 56 04 KINERJA BISNIS DAN OPERASIONAL 61 Pilar Bisnis Infrastruktur 63 Pilar Bisnis Telekomunikasi 66 Pilar Bisnis Digital 73 Pilar Bisnis Apps/IOT/Content 77 OPERASIONAL Pilar Bisnis Internet 78 KINERJA BISNIS & KINERJA 05 TATA KELOLA PERUSAHAAN 81 06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 97 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 99 07 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 5 PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO LAPORAN TAHUNAN 2019 Menjadi “perusahaan yang unggul untuk menjadikan JAKARTA lebih baik 6 “ LAPORAN TAHUNAN 2019 PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO LEMBAR PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO TAHUN BUKU 2019 Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dan data dalam Laporan Tahunan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun Buku 2019 telah dimuat secara benar dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. -

Bab I Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada zaman sekarang semakin tingginya tingkat mobilitas warga DKI Jakarta berpengaruh juga kepada peningkatan kendaraan pribadi di Jakarta. Kendaraan pribadi yang meningkat juga berimbas pada marak nya kemacetan di jalan-jalan ibukota menurut Kementrian Pekerjaan Umum Kemacetan dicirikan, secara teoritik, oleh arus yang tidak stabil, kecepatan tempuh kendaraan yang lambat, serta antrian kendaraan yang panjang, yang biasanya terjadi pada konsentrasi kegiatan sosial-ekonomi atau pada persimpangan lalu-lintas di pusat- pusat perkotaan. Kemacetan yang parah sebagaimana terjadi di Jakarta dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yakni sisi supply (penyediaan) dan sisi demand (kebutuhan). Saat ini Pemerintah sedang berfokus memerbaiki kualitas layanan umum terutama dalam hal layanan transportasi. Transportasi merupakan salah satu hal penting yang harus dibenahi karena hal itu sangat berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang dilkakukan oleh warga Jakarta. Fasilitas umum seperti metromini, kopaja, dan mikrolet banyak yang dalam kondisi buruk dan tidak layak jalan. Pada tahun 2004 salah satu solusi dibuat demi mengatasi masalah ketidak layakan angkutan umum di Jakarta. Solusi tersebut adalah bus transjkarta yang saat itu dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Transajakarta (saat ini menjadi PT. Transjakarta). 1 2 Transjakarta dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Transjakarta (Pramudi, petugas bus, petugas halte, dan petugas kebersihan) sekitar 6.000 orang. Jumlah rata-rata harian pengguna Transjakarta diprediksikan sekitar 350.000 orang. Sedangkan pada tahun 2012, Jumlah pengguna Transjakarta mencapai 109.983.609 orang. Transjakarta hingga saat ini memiliki 12 koridor yang tersebar dijakarta dana melayani berbagai rute tujuan. Ke-duabelas koridor tersebut dioperasikan oleh perusahaan yang berbeda beda seperti BMP, JMT, JTM, TJ, dan DAMRI.