Buku Versi Agustus 2018.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The KNIGHT REVISION of HORNBOSTEL-SACHS: a New Look at Musical Instrument Classification
The KNIGHT REVISION of HORNBOSTEL-SACHS: a new look at musical instrument classification by Roderic C. Knight, Professor of Ethnomusicology Oberlin College Conservatory of Music, © 2015, Rev. 2017 Introduction The year 2015 marks the beginning of the second century for Hornbostel-Sachs, the venerable classification system for musical instruments, created by Erich M. von Hornbostel and Curt Sachs as Systematik der Musikinstrumente in 1914. In addition to pursuing their own interest in the subject, the authors were answering a need for museum scientists and musicologists to accurately identify musical instruments that were being brought to museums from around the globe. As a guiding principle for their classification, they focused on the mechanism by which an instrument sets the air in motion. The idea was not new. The Indian sage Bharata, working nearly 2000 years earlier, in compiling the knowledge of his era on dance, drama and music in the treatise Natyashastra, (ca. 200 C.E.) grouped musical instruments into four great classes, or vadya, based on this very idea: sushira, instruments you blow into; tata, instruments with strings to set the air in motion; avanaddha, instruments with membranes (i.e. drums), and ghana, instruments, usually of metal, that you strike. (This itemization and Bharata’s further discussion of the instruments is in Chapter 28 of the Natyashastra, first translated into English in 1961 by Manomohan Ghosh (Calcutta: The Asiatic Society, v.2). The immediate predecessor of the Systematik was a catalog for a newly-acquired collection at the Royal Conservatory of Music in Brussels. The collection included a large number of instruments from India, and the curator, Victor-Charles Mahillon, familiar with the Indian four-part system, decided to apply it in preparing his catalog, published in 1880 (this is best documented by Nazir Jairazbhoy in Selected Reports in Ethnomusicology – see 1990 in the timeline below). -
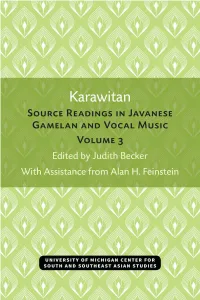
Source Readings in Javanese Gamelan and Vocal Music, Volume 3
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN CENTER FOR SOUTH AND SOUTHEAST ASIAN STUDIES MICHIGAN PAPERS ON SOUTH AND SOUTHEAST ASIA Editorial Board A. L. Becker Peter E. Hook Karl L. Hutterer John K. Musgrave Nicholas B. Dirks, Chair Ann Arbor, Michigan USA KARAWITAN SOURCE READINGS IN JAVANESE GAMELAN AND VOCAL MUSIC Judith Becker editor Alan H. Feinstein assistant editor Hardja Susilo Sumarsam A. L. Becker consultants Volume 3 MICHIGAN PAPERS ON SOUTH AND SOUTHEAST ASIA Center for South and Southeast Asian Studies The University of Michigan Number 31 Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/ Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program. Library of Congress Catalog Card Number: 82-72445 ISBN 0-89148-034-X Copyright ^ by © 1988 Center for South and Southeast Asian Studies The University of Michigan Publication of this book was assisted in part by a grant from the Publications Program of the National Endowment for the Humanities. Additional funding or assistance was provided by the National Endowment for the Humanities (Translations); the Southeast Asia Regional Council, Association for Asian Studies; The Rackham School of Graduate Studies, The University of Michigan; and the School of Music, The University of Michigan. Printed in the United States of America ISBN 978-0-89148-041-9 (hardcover) ISBN 978-0-472-03820-6 (paper) ISBN 978-0-472-12770-2 (ebook) ISBN 978-0-472-90166-1 (open access) The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS vii APPENDIX 1: Glossary of Technical Terms Mentioned in the Texts 1 APPENDIX 2: Javanese Cipher Notation (Titilaras Kepatihan) of Musical Pieces Mentioned in the Texts 47 APPENDIX 3: Biographies of Authors 429 APPENDIX 4: Bibliography of Sources Mentioned by Authors, Translators, Editors, and Consultants 447 GENERAL INDEX 463 INDEX TO MUSICAL PIECES (GENDHING) 488 This work is complete in three volumes. -

Gender, Ethnicity, Infrastructure, and the Use of Financial Institutions in Kalimantan Barat, Indonesia
GENDER, ETHNICITY, INFRASTRUCTURE, AND THE USE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN KALIMANTAN BARAT, INDONESIA _______________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _______________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _____________________________________________________ by CHRISTINA POMIANEK DAMES Dr. Mary Shenk, Dissertation Supervisor JULY 2012 © Copyright by Christina Dames 2012 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School have examined the dissertation entitled GENDER, ETHNICITY, INFRASTRUCTURE, AND THE USE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN KALIMANTAN BARAT, INDONESIA presented by Christina Pomianek Dames, a candidate for the degree of doctor of philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. Assistant Professor Mary Shenk Associate Professor Craig Palmer Associate Professor Todd VanPool Professor James S. Rikoon This dissertation is dedicated to the memory of my parents. ACKNOWLEGEMENTS Now at the conclusion of my graduate studies in anthropology, I look back and recognize the many people who have been instrumental in helping me to discover, pursue, and achieve my goals. In thanks. First and foremost, to my dissertation advisor and mentor, Dr. Mary Shenk, for her guidance and for the many hours she has spent reading and commenting on drafts of this dissertation. To my late mentor Dr. Reed Wadley, who is solely responsible for opening my eyes to Indonesia and in Kalimantan Barat. Although we only worked together for a few short years, meeting Dr. Wadley completely changed the course of my life. I am deeply saddened that we are not able to share our ―stories from the field,‖ but I am forever grateful that our paths crossed at all. -

FOMRHI Quarterly
_. " Elena Dal Cortiv& No. 45 October 1986 FOMRHI Quarterly BULLETIN 45 2 Bulletin Supplement 8 Plans: Bate Collection 9 Plans? The Royal College of Music 12 Membership List Supplement 45 COMMUNICATIONS 745- REVIEWS: Dirtionnaire des facteurs d'instruments ..., by M. Haine £ 748 N. Meeus', Musical Instruments in the 1851 Exhibition, by P. £ A. Mactaggart; Samuel Hughes Ophideidist, by S. J, Weston} Chanter! The Journal of the Bagpipe Sodiety, vol.1, part 1 J. Montagu 14 749 New Grove DoMi: JM 65 Further Detailed Comments: The Gs. J. Montagu 18 750 New Grove DoMi: ES no. 6J D Entries E. Segerman 23 751 More on Longman, Lukey £ Broderip J. Montagu 25 752 Made for music—the Galpin Sodety's 40th anniversary J. Montagu 26 753 Mersenne, Mace and speed of playing E. Segerman 29 754' A bibliography of 18th century sources relating to crafts, manufacturing and technology T. N. McGeary 31 755 What has gone wrong with the Early Music movement? B. Samson 36 / B. Samson 37 756 What is a 'simple' lute? P. Forrester 39 757 A reply to Comm 742 D. Gill 42 758 A follow-on to Comm 739 H. Hope 44 759 (Comments on the chitarra battente) B. Barday 47 760 (Craftsmanship of Nurnberg horns) K. Williams 48 761 Bore gauging - some ideas and suggestions C. Karp 50 7632 Woodwin(On measurind borge toolmeasurins and gmodems tools ) C. Stroom 55 764 A preliminary checklist of iconography for oboe-type instruments, reeds, and players, cl630-cl830 B. Haynes 58 765 Happy, happy transposition R. Shann 73 766 The way from Thoiry to Nuremberg R. -

Bahasa Melayik Purba
K. Alexander Adelaar BAHASA MELAYIK PURBA Rekonstruksi Fonologi dan Sebagian dari Leksikon dan Morfologi BAHASA MELAYIK PURBA Diterbitkan dalam kerangka kcija sama aniaea Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahama, >anemcn Pendidikan dan Kebudayaan Rcpublik Indoncs dan Univcrsiias Leiden, Belanda PUBLIKASI BERSAMA dan PEMBINAAN DAN PENGEMBANCAN UNIVERSITAS LEIDEN BAHASA BAHASA MELAYIK PURBA Rekonstruksi Fonologi dan Sebagian dari Leksikon dan Morfologi oleh K. Alexander Adelaar RUL Jakarta 1994 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ADELAAR, K. Alexander Bahasa Melayik Purba : rekonstruksi fonologi dan sebagian dari leksikon dan morfologi / K. Alexander Adelaar, - Jakarta: RUL, 1994 xviii, 385 him.; 22,5 cm, - (Seri publikasi bersama) Diterbitkan atas keija sama dengan Universitas Leiden, Belanda ISBN 979-8310-03-9 1. Bahasa Melayu - Fonologi I. Judul. II. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa III. Universitas Leiden IV. Seri 419.9 Redaktur W.A.L. Stokhof Asisten Redaktur A.E. Almanar Penasihat Redaktur Hasan Alwi, Hans Lapoliwa, Hein Steinhauer DAFTAR ISI Kata Pengantar ix Daftar Singkatan xiii Simbol-simbol yang digunakan xv Bahasa-bahasa yang diacu, dengan singkatan dan sumber leksikal yang penting xvii BAB I : Pendahuluan 1 BAB II : Deskripsi Fonologis dalam Isolek-isolek Melayik 13 2.1 Sistem Foriem dalam Isolek Melayu Baku 13 2.2 Sistem Fonem dalam Isolek Minangkabau 17 2.3 Sistem Fonem dalam Isolek Banjar Hulu 22 2.4 Sistem Fonem dalam Isolek Serawai 25 2.5 Sistem Fonem dalam Isolek Iban 32 2.6 Sistem Fonem dalam Isolek -

Studi Deskriptif Pembuatan, Teknik Permainan, Dan
STUDI DESKRIPTIF PEMBUATAN, TEKNIK PERMAINAN, DAN FUNGSI ALAT MUSIK SAPE’ DALAM KEBUDAYAAN SUKU DAYAK KAYAAN, DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SKRIPSI SARJANA DISUSUN O L E H NAMA : YOLANDA R. NATASYA NIM : 130707057 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI 2020 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA LEMBAR PENGESAHAN STUDI DESKRIPTIF PEMBUATAN, TEKNIK PERMAINAN, DAN FUNGSI ALAT MUSIK SAPE’ DALAM KEBUDAYAAN SUKU DAYAK KAYAAN, DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SKRIPSI Dikerjakan Oleh Nama : YOLANDA R. NATASYA N I M : 130707057 Disetujui oleh Pembimbing I, Pembimbing II, Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. Drs. Perikuten Tarigan, M.A. NIP: 196512211991031001 NIP: 195804021987031003 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYAPROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI MEDAN 2020 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DISETUJUI OLEH: Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara MEDAN Program Studi Etnomusikologi Ketua, Arifni Netrirosa, SST., M.A. NIP: 196502191994032002 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PENGESAHAN Diterima Oleh: Panitia ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk melengkapi salah satu syarat ujian Sarjana Seni (S.Sn) dalam bidang Etnomologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan. Hari : Tanggal : Fakultas Ilmu Budaya USU Dekan, Dr. Budi Agustono, M.S. NIP. 196008051987031001 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu PerguruanTinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Medan, Januari 2020 YOLANDA R. -

MANDAU SENJATA TRADISIONAL SEBAGAI PELESTARI RUPA LINGKUNGAN DAYAK Oleh
47 RITME Volume 2 No. 2 Agustus 2016 MANDAU SENJATA TRADISIONAL SEBAGAI PELESTARI RUPA LINGKUNGAN DAYAK Oleh : Hery Santosa dan Tapip Bahtiar [email protected] Departemen Pendidikan Seni Musik - FPSD Universitas Pendidikan Indonesia ABSTRAK anyaknya pulau yang terhampar di wilayah Indonesia, menyebabkan tumbuhnya berbagai kebudayaan yang beragam. Hal ini merupakan realitas yang menguntungkan bagi negara Indonesia. Kekayaan budaya yang menjadi asset tak ternilai yang tumbuh menjadi pesona alam Indonesia. Dayak merupakan salah satu suku bangsa yang terkenal di Indonesia. Suku bangsa yang tinggal di pulau Kalimantan ini memiliki berbagai produk budaya. Aneka produk budaya telah dilahirkan di suku bangsa Dayak. Salahsatu produk budaya Dayak adalah senjata tradisional yang diberi nama Mandau. Mandau pada dasarnya dibuat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun disamping itu ada juga yang dibuat khusus untuk digunakan dalam upacara ritual. Pada perkembangan selanjutnya, Mandau ada yang dibuat untuk keperluan tanda mata atau souvenir. Kata Kunci : Kebudayaan, Dayak, Mandau, senjata tradisi, Bagian-bagian Mandau. PENDAHULUAN teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Bertolak dari pendapat itu, diduga nenek moyang orang Hamparan pulau bumi Indonesia yang Dayak berasal dari beberapa gelombang migrasi. demikian luas dan jumlah yang banyak sangat Gelombang pertama terjadi kira-kira 1 juta tahun menunjang lahir dan banyaknya aneka ragam seni yang lalu tepatnya pada periode Intergasial- tradisi dan keunikan budaya yang ditunjukan Pleistosen. Kelompok ini terdiri dari ras setiap pulau, wilayah, dan atau suku bangsa. Australoid (ras manusia pre-historis yang berasal Salah satu yang kaya dengan ragam kesenian dari Afrika). Pada zaman Pre-neolitikum, kurang tradisional yaitu pulau Kalimantan. Pulau lebih 40.000-20.000 tahun lampau, datang lagi Kalimantan terbagi dalam beberapa wilayah kelompok suku semi nomaden (tergolong administratif, yaitu wilayahnya Kalimantan manusia moderen, Homo sapiens ras Mongoloid). -

Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014
Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539 Herdiansah, A.G. Vol.3 No. 2 2017, Hal. 169-183 POLITISASI IDENTITAS DALAM KOMPETISI PEMILU DI INDONESIA PASCA 2014 Ari Ganjar Herdiansah Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, ari. [email protected] ABSTRACT Identity has always been a political commodity driven by politicians in the electoral competition in Indonesia. This paper analyzes how the politicization of identity strengthens after the 2014 election and explains its potentials for political instability and national integration. The data used in this study gathered from the literature review and news analysis of identity and election, especially in the post-2014. This paper reveals that the weak party institutionalization encourages politicians to collaborate with civil society actors to reproduce identity issues for the sake of elections winning. The personalization of the party by its leader connected to a network of identity mass bases run the politicization in a natural setting. The further development of the politicization of the identity has the potential to divert substantial political issues such as government programs and public interests. In the economic field, political upheaval that involving the masses would weaken the confidence of investors and business actors in propelling the economic wheels. Also, political discord based on identity could damage social capital and decrease people’s ability to produce its best endeavor. Keywords Election, identity politics, political party, national stability Politik Identitas 169 02 JURNAL BAWASLU.indd 169 12/6/17 3:47 PM ABSTRAK Identitas senantiasa menjadi komoditas politik yang digulirkan oleh para politikus dalam pertarungan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana politisasi identitas menguat pasca pemilu 2014 dan menjelaskan potensi-potensinya terhadap instabilitas politik dan integrasi bangsa. -

Jurgita Nagrockytė DAMBRELIO RAIDA LIETUVOS MUZIKINIUOSE
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ETNOLOGIJOS IR FOLKLORISTIKOS KATEDRA Jurgita Nagrockytė DAMBRELIO RAIDA LIETUVOS MUZIKINIUOSE ANSAMBLIUOSE Magistro baigiamasis darbas Etninės kultūros studijų programa, valstybinis kodas 62407H101 Etnologijos studijų kryptis Vadovas prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius ___________ ___________ (Moksl. laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data) Apginta doc. dr. Jonas Vaičenonis ___________ ____________ (Fakulteto dekanas) (Parašas) (Data) Kaunas, 2010 1. TURINYS 1. TURINYS ....................................................................................................................................... 1 2. SANTRAUKA................................................................................................................................ 2 3. SUMMARY.................................................................................................................................... 3 4. ĮVADAS ......................................................................................................................................... 4 5. DAMBRELIO ISTORIJA, ATSIRADIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE..................................... 7 5.1 Dambrelio raida pasaulyje ....................................................................................................... 7 5.2 Dambrelio istorinė raida .......................................................................................................... 9 5.3 Dambrelio istoriniai atradimai Europoje ir Jungtinėje karalystėje ......................................... -

Medium of Performance Thesaurus for Music
A clarinet (soprano) albogue tubes in a frame. USE clarinet BT double reed instrument UF kechruk a-jaeng alghōzā BT xylophone USE ajaeng USE algōjā anklung (rattle) accordeon alg̲hozah USE angklung (rattle) USE accordion USE algōjā antara accordion algōjā USE panpipes UF accordeon A pair of end-blown flutes played simultaneously, anzad garmon widespread in the Indian subcontinent. USE imzad piano accordion UF alghōzā anzhad BT free reed instrument alg̲hozah USE imzad NT button-key accordion algōzā Appalachian dulcimer lõõtspill bīnõn UF American dulcimer accordion band do nally Appalachian mountain dulcimer An ensemble consisting of two or more accordions, jorhi dulcimer, American with or without percussion and other instruments. jorī dulcimer, Appalachian UF accordion orchestra ngoze dulcimer, Kentucky BT instrumental ensemble pāvā dulcimer, lap accordion orchestra pāwā dulcimer, mountain USE accordion band satāra dulcimer, plucked acoustic bass guitar BT duct flute Kentucky dulcimer UF bass guitar, acoustic algōzā mountain dulcimer folk bass guitar USE algōjā lap dulcimer BT guitar Almglocke plucked dulcimer acoustic guitar USE cowbell BT plucked string instrument USE guitar alpenhorn zither acoustic guitar, electric USE alphorn Appalachian mountain dulcimer USE electric guitar alphorn USE Appalachian dulcimer actor UF alpenhorn arame, viola da An actor in a non-singing role who is explicitly alpine horn USE viola d'arame required for the performance of a musical BT natural horn composition that is not in a traditionally dramatic arará form. alpine horn A drum constructed by the Arará people of Cuba. BT performer USE alphorn BT drum adufo alto (singer) arched-top guitar USE tambourine USE alto voice USE guitar aenas alto clarinet archicembalo An alto member of the clarinet family that is USE arcicembalo USE launeddas associated with Western art music and is normally aeolian harp pitched in E♭. -

Gawai Dayak Festival and the Increase of Foreign Tourist Visits
Gawai Dayak Festival and the Increase of Foreign Tourist Visits Festival Gawai Dayak dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Elyta Universitas Tanjungpura Pontianak ABSTRAK Gawai Dayak adalah festival tahunan di Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia, yang memperlihatkan kekayaan seni budaya dan tradisi Suku Dayak yang berkembang baik di Kalimantan Barat maupun di Sarawak. Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di dalam memanfaatkan festival Gawai Dayak sebagai sarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Bagaimana langkah- langkah yang dapat dilakukan sehingga festival Gawai Dayak mampu menjadi sarana meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kalimantan Barat? Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dianalisis dalam artikel ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi yang terkait dengan penyelenggaraan Gawai Dayak. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam membenahi tata kelola wisata di Kalimantan Barat teridentifikasi dan berpotensi menjadi instrumen soft power memperkenalkan budaya dan sekaligus menjadi sarana daya tarik wisata bagi Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Gawai Dayak, pariwisata, soft power Gawai Dayak is an annual festival in West Kalimantan, Indonesia and Sarawak, Malaysia, which shows the richness of the arts and culture and traditions of the Dayak tribe that have developed both in West Kalimantan and in Sarawak. This article examines the efforts made by the West Kalimantan provincial government to utilize the Gawai Dayak festival as a means to increase foreign tourist visits. What steps can be taken so that the Gawai Dayak festival can be a means of increasing the number of foreign tourist visits to West Kalimantan? Using a descriptive method with a qualitative approach, the data analyzed in this article were collected through interviews and documentary studies related to organizing the Dayak Gawai event. -

Konference09 Matousek
Konference 2009 Hlas v kulturách světa Techniky ústní resonance v etnické hudbě Vlastimil Matoušek Ústní resonance , která se v evropské kultivované (vážné, artificiální atd.) hudbě prakticky neužívá, hraje naopak velice důležitou roli v celé řadě hudebních projevů v kategorii etnické hudby2, zejména v hudbě tzv. pří- rodních národů. Jsou to především některé hlasové „zpěvní“ projevy „imitující“, související často s magií a napodobováním zvuků přírody, hlasů zvířat atd., „hra“ na mluvící trubice (srov. dále) a hlasové modifiká- tory, hra na některé trubkové nástroje, hra na ústní hudební luk a na brumli. Zvláštním fenoménem je tzv. bifonický (také harmonický) zpěv. Hlasové projevy „imitující“ U přírodních národů, lidských společenství žijících na předliterárním stupni vývoje, se lze setkat s vokálními projevy, které se zpěvu v našem slova smyslu, ve kterém hrají klíčovou roli kultivované tóny konkrétních výšek, příliš nepodobají. Naopak, jejich „zpěv“ běžně zahrnuje i všemož- né další zvuky, které lze jen z hrdla vyloudit, ty pak často napodobují hla- sy zvířat, slouží k odhánění zlých duchů či jako hádanky atp.. Přitom se zpravidla také využívá rezonance ústní dutiny. Jako příklad mohou sloužit třeba tzv. vokální hry Inuitů-Eskymáků. ukázka 1. CD Canada – Jeux vocaux des Inuit, Ocora C 559071, Paris 1989, č. 24, 1:01, Qattipaartuk, „vyprávěcí“ hry Netsilik Inuit, Gjoja Haven, Ca- nada. Mluvící trubice a hlasové modifikátory Mluvící trubice (speaking tube, voice modifier, voice mask atd..) – bývá trubice z duté větve, bambusu, zvířecích rohů v délce cca 50cm až 200cm, www.hlasohled.cz 1 Konference 2009 Hlas v kulturách světa zpravidla o průměru od 3cm do 10cm, používaná pro zkreslení a modifi- kování hlasových projevů (tedy nikoliv k troubení!) s použitím ústní re- sonance.