I:\Zakiyuddin B\Jurnal\Ijtihad\
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK HASAN TIRO Oleh: Abrar Muhammad Yus Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh E-Mail: [email protected]
PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK HASAN TIRO Oleh: Abrar Muhammad Yus Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh e-mail: [email protected] Abstrak Pergolakan politik rakyat Aceh pada dasarnya bersifat kesinambungan perjuangan politik bagi rakyat dan bangsa Aceh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh pejuang politik Aceh yang lahir dan dikenal kegigihannya dalam memperjuangkan ide-ide perjuangannya. Untuk melakukan kajian terhadap tokoh-tokoh tersebut, dapat dilihat dari pendekatan ataupun pola serta periode perjuangan politik yang dilakukan oleh para tokoh tersebut. Hasan Tiro sebagai tokoh “pejuang-politik” disamping itu ia juga sebagai “pemikir- pejuang” misalnya, secara umum dapat dilihat dalam tiga periode perjuangannya yaitu: pertama, periode ketika ia masih muda dan sekaligus sebagai penerus perjuangan Tgk. Daud Beureueh, kedua, periode ketika mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan ketiga, periode penyesuaian perjuangan politik yang dalam periode ini Hasan Tiro mengalami pergeseran nilai ide-ide perjuangan politiknya, dari semangat nilai-nilai keagamaan berubah kearah yang kecenderungannya bersifat “sekuler”. Hal ini dapat dilihat dari perubahan tujuan perjuangan Hasan Tiro, serta pola perjuangan politiknya yang pada akhirnya harus berakhir di meja perundingan Helsinki. Kata Kunci: pemikiran politik, hasan tiro A. Sketsa Sosial-Politik Hasan Tiro Sejarah mencatat bahwa rakyat Aceh tidak dapat ditaklukkan oleh Belanda dengan cara yang militeristik, karena perang terhadap Belanda dalam pandangan rakyat Aceh merupakan perang suci “jihad fisabilillah,” yang bermakna jika mati akan disebut syahid karena didorong oleh semangat aqidah Islamiyah, yang sudah mengakar sangat kuat dalam pemahaman rakyat Aceh. Oleh karena itu, perang ini telah melibatkan semua lapisan masyarakat tidak terkecuali siapapun bahkan kaum perempuan sekalipun. Para ulama berperan penting dalam mengobarkan semangat jihad dalam perang tersebut. -

Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Simetris
Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA. PELAKSANAAN Syariat Islam DI ACEH SEBAGAI OTONOMI KHUSUS YANG ASIMETRIS (Sejarah Dan Perjuangan) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020 PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SEBAGAI OTONOMI KHUSUS YANG ASIMETRIS (SEJARAH DAN PERJUANGAN) Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA. Editor : DR. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Tata Letak Isi : Muhammad Sufri Desain Cover : Syahreza Diterbitkan oleh: Dinas Syariat Islam Aceh Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh Email : [email protected] Telp : (0651) 7551313 Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314 Bekerjasama dengan Percetakan: CV. Rumoh Cetak Jalan Utama Rukoh, Syiahkuala, Banda Aceh Email: [email protected] | Hp: 08116888292 Dinas Syariat Islam Aceh viii + 224 hlm. 14 x 21 cm. ISBN. 978-602-58950-5-0 Pengantar penulis BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. atas segala karunia dan rahmat yang dilimpahkan- Nya, shalawat dan salam penulis haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad Rasul penutup dan penghulu para nabi--yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, serta kepada semua keluarga dan Sahabat beliau. Dengan izin serta karunia Allah Swt. penulisn buku dengn judul PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SEBAGAI OTONOMI KHUSUS YANG ASIMETRIS (Sejarah Dan Perjuangan) telah dapat penulis rampungkan dan selesaikan penulisannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan caranya masing-masing, sehingga tulisan ini dapat penulis rampungkan. Terutama sekali kepada para mahasiswa, para peneliti dan para peminat yang sering mengajukan pertanyaan yang tajam dan menggelitik, kritik yang pedas, atau pujian berlebihan yang tidak menggembirakan, baik mengenai isi buku yang penulis tulis, atau juga mengenai kebijakan, dan kenyataan nyata pelaksanaan qanun- qanun yang berkaitan dengna syariat Islam selama ini. -

National Heroes in Indonesian History Text Book
Paramita:Paramita: Historical Historical Studies Studies Journal, Journal, 29(2) 29(2) 2019: 2019 119 -129 ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16217 NATIONAL HEROES IN INDONESIAN HISTORY TEXT BOOK Suwito Eko Pramono, Tsabit Azinar Ahmad, Putri Agus Wijayati Department of History, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang ABSTRACT ABSTRAK History education has an essential role in Pendidikan sejarah memiliki peran penting building the character of society. One of the dalam membangun karakter masyarakat. Sa- advantages of learning history in terms of val- lah satu keuntungan dari belajar sejarah dalam ue inculcation is the existence of a hero who is hal penanaman nilai adalah keberadaan pahla- made a role model. Historical figures become wan yang dijadikan panutan. Tokoh sejarah best practices in the internalization of values. menjadi praktik terbaik dalam internalisasi However, the study of heroism and efforts to nilai. Namun, studi tentang kepahlawanan instill it in history learning has not been done dan upaya menanamkannya dalam pembelaja- much. Therefore, researchers are interested in ran sejarah belum banyak dilakukan. Oleh reviewing the values of bravery and internali- karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau zation in education. Through textbook studies nilai-nilai keberanian dan internalisasi dalam and curriculum analysis, researchers can col- pendidikan. Melalui studi buku teks dan ana- lect data about national heroes in the context lisis kurikulum, peneliti dapat mengumpulkan of learning. The results showed that not all data tentang pahlawan nasional dalam national heroes were included in textbooks. konteks pembelajaran. Hasil penelitian Besides, not all the heroes mentioned in the menunjukkan bahwa tidak semua pahlawan book are specifically reviewed. -

PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH Konstribusi A
Dr. Syabuddin Gade, M.Ag PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH Konstribusi A. Hasjmy Menghadapi Multi Krisis di Aceh Penyunting: Prof. Madya Dr. Hj. Abdul Ghafar Don (Universiti Kebangsaan Malaysia) Diterbitkan Oleh: ArraniryPress - Lembaga Naskah Aceh (NASA) ~ i ~ PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT) PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH Konstribusi A. Hasjmy Menghadapi Multi Krisis di Aceh Edisi Pertama, Cet. 1 Tahun 2017 ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA) xx + 439 hlm. 13 cm x 20.5 cm ISBN : 978-602-7837-06-5 Hak Cipta Pada Penulis All rights Reserved Cetakan Pertama, Oktober 2017 Pengarang : Dr. Syabuddin Gade, M.Ag Penyunting : Prof. Madya Dr. Hj. Abdul Ghafar Don Layout/Tata letak : LKASGroup Diterbitkan atas kerjasama: ArraniryPress Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh 23111 Telp. (0651) - 7552921/Fax. (0651) - 7552922 E-mail: [email protected] Lembaga Naskah Aceh (NASA) JL. Ulee Kareng - Lamreung, Desa Ie Masen, No. 9A Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 23117 Telp./Fax. : 0651-635016 E-mail: [email protected] ~ ii ~ PENGANTAR PENULIS A. Hasjmy dikenali bukan sahaja sebagai sasterawan, poli- tikus, sejarawan dan ulama, tetapi juga sebagai tokoh pen- didikan dan dakwah di Aceh. Tambahan lagi, kepakaran A. Hasjmy dalam beberapa bidang keilmuan yang terkesan “en- siklopedik” bukanlah “isapan jempol belaka”, tetapi dibuktikan dengan karya tulis yang mencapai hampir 60 karya. Semua ini merupakan warisan berguna bagi generasi Aceh masa kini dan masa hadapan khususnya dan bagi umat manusia pada umumnya. Kajian terhadap pemikiran A. Hasjmy, setakat ini memang banyak mendapat perhatian dari pelbagai kalangan. Dalam buku Badruzzaman Ismail, et al., Delapan puluh tahun melalui jalan raya dunia A. -

Cover HABA-Kapita Selekta
Wacana PANGLIMA ABDUL WAHAB: PAHLAWAN TIGA ZAMAN Oleh: Sudirman Pendahuluan perjuangannya. Akan tetapi, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Selama penjajahan Belanda di khususnya generasi muda yang sering kali Aceh terjadi banyak perlawanan dari rakyat. tidak mengetahui sisi kehidupan dan Perlawanan-perlawanan terjadi dalam skala pengabdian para pejuang, sehingga mereka besar dan kecil serta dalam ruang lingkup kurang memahami nilai-nilai perjuangan dan waktu yang berbeda. Semua dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena perlawanan tersebut merupakan tindakan itu, kisah perjuangan Pang Hab dan nilai- dari rakyat sebagai reaksi dalam upaya nilai kejuangannya menjadi penting membebaskan diri dari cengkraman dipahami ketika kebanyakan orang penjajah. Meskipun dalam kadar dan bentuk menikmati hasil perjuangan dari para yang berbeda, perlawanan rakyat Aceh pendahulunya. terhadap kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan perang kemerdekaan dapat dijumpai hampir di setiap daerah. Silsilah Pang Wahab Pada permulaannya, rakyat Aceh Pahlawan Aceh yang masih hidup di bawah pimpinan sultan, uleebalang, dan sampai zaman setelah kemerdekaan ulama melakukan perang frontal terhadap Republik Indonesia dan mendapat piagam Belanda. Setelah itu, rakyat Aceh masih tanda kehormatan dan bintang jasa dari juga melakukan perang gerilya terhadap Presiden Republik Indonesia, Sukarno, Belanda. Namun, ketika banyak pemimpin ialah Pang Hab. Pang Hab berasal dari Aceh ditangkap, gugur atau diasingkan dan keturunan uleebalang XXII Mukim, perlawanan dapat dipatahkan -

Malik Mahmud Legal Strongmen? March 2019
Vol. 2 No. 1 Malik Mahmud Legal Strongmen? March 2019 ARIF AKBAR Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia [email protected] 38 ABSTRACT The Helsinki MoU agreed by the Indonesian Government, and the Free Aceh Movement provided Received: January 28, 2019 Revised: March 6, 2019 an opportunity for Aceh to have a customary institution called the Wali Nanggroe institution. This Accepted: March 13, 2019 opportunity was used by the DPRA which was dominated by the Aceh Party by confirming Malik Mahmud Alhaitar as the Naggroe Aceh Mayor, in the Aceh Party structure Malik Mahmud was one of the leaders of this local Party, so it was possible to have a dual role played by the figure of Wali Naggroe. The inauguration of Malik Mahmud as the Wali Nanggroe also indirectly gave rise to a local number of Strongmen within the structure of the Acehnese community, given the position of the Wali Nanggroe as a position that was highly respected in the construction of Acehnese people's lives. Moving on from the above problems, this study wants to see how the role of the State in giving birth to local Strongmen within the structure of Acehnese society. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. Data sources are obtained through interviews and observations and documentation. Data is processed through data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. This research borrows his theorist Jonh T Sidel and Migdal who have formulated how the formation of Local Strongmen or Bossism and the characteristics of both. Based on the results in the field, it shows that the Local Strongmen could emerge because of the involvement of the state in them, the participation of the country is not limited to allowing the birth of Local Strongmen but more than that, the state also provides legal standing for Local Strongmen Keywords: Local Strongmen, Wali Nanggroe. -

Type Your Uppercase Title Here Centered with No
THE ULAMA IN ACEH IN TIME OF CONFLICT, TSUNAMI AND PEACE PROCESS AN ETHNOGRAPHIC APPROACH A thesis presented to the faculty of the Center for International Studies of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Ezki Widianti June 2006 This thesis entitled THE ULAMA IN ACEH IN TIME OF CONFLICT, TSUNAMI AND PEACE PROCESS AN ETNOGRAPHIC APPROACH by EZKI WIDIANTI has been approved for the Center of International Studies by Elizabeth Fuller Collins Associate Professor, Classics and World Religions Drew McDaniel Interim Director, Center for International Studies Abstract WIDIANTI, EZKI T., M.A., June 2006. International Development Studies THE ULAMA IN ACEH IN TIME OF CONFLICT, TSUNAMI AND PEACE PROCESS AN ETHNOGRAPHIC APPROACH (71 pp.) Director of Thesis: Elizabeth Fuller Collins Aceh, the "Veranda of Mecca," has the reputation of being the most deeply Muslim region in Indonesia. Because of its traditional value system, ulama have had broad influence in Acehnese society. I describe the role of the ulama in Aceh as leaders of resistance to Dutch colonialism and show how their influence declined over the last thirty years. Since 1976 when the Free Aceh Movement (GAM) demanded independence from the Indonesian government, Aceh has been the site of a militarized conflict. During this time the role of the ulama declined as the authoritarian government of former president, Suharto (1967-1998) tried to co-opt their support and GAM demanded their allegiance. After a tsunami hit Aceh in December 2004, the government and GAM negotiated a peace accord. I describe the reemergence of ulama in post-tsunami Aceh and argue that they should be given a more significant role in reconstruction. -
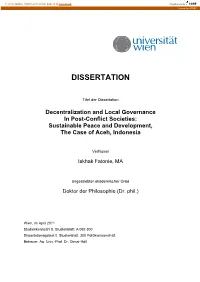
Dissertation
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DISSERTATION Titel der Dissertation Decentralization and Local Governance In Post-Conflict Societies: Sustainable Peace and Development, The Case of Aceh, Indonesia Verfasser Iskhak Fatonie, MA angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, im April 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 300 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: 300 Politikwissenchaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Otmar Höll Table of Contents Acknowledgements ………………………………………………………………... v List of Abbreviations .…….……………………………………………………….. vi List of Tables .……………….…………………………………………………….. viii List of Figures .……...……………..………………………………………………. ix Map of Aceh .………………………………………………………..…………….. x Abstract .……………………………………………..…………………………….. xi Chapter 1 - Introduction .......................................................................................... 1 1.1 Background ……... .……………………………………………………….. 1 1.2 Problem Statement ……..………………………………..………………… 4 1.3 Research Objectives and Research Questions……………...……………… 6 1.4 Research Hypothesis……………..………………………………………… 7 1.5 Research Methodology ……………………………………………………. 7 1.6 Research Paper Structure ………………………………………………….. 8 Chapter 2 - Decentralization and Conflict: Concepts, Theories and Debates ..... 9 2.1 Decentralization at Large……………………….. ……….……………………. 9 2.1.1 Definition and Concept ….……………………................................... 9 2.1.2 Objectives of Decentralization ………………………………………. 13 2.1.3 Autonomy, Self-Governance -

Modeling Aceh: Essays on Resource Management, Inflation, and Social Capital
MODELING ACEH: ESSAYS ON RESOURCE MANAGEMENT, INFLATION, AND SOCIAL CAPITAL A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Saiful Mahdi January 2011 © 2011 Saiful Mahdi MODELING ACEH: ESSAYS ON RESOURCE CURSE, INFLATION, AND SOCIAL CAPITAL Saiful Mahdi, Ph.D. Cornell University 2011 This dissertation is a collection of three papers that cover contemporary issues at centre stage in the development of Aceh, Indonesia. The first, ‗Testing the resource curse hypothesis in Aceh‘, empirically tests the resource curse hypothesis in this oil- and-gas rich region. Using data from 1975 to 2006, the model results reject the hypothesis of a resource curse. The empirical models indicate that the boom in the mining sector in Aceh from the late 1970s until the mid-1980s did not reduce the output of the non-mining manufacturing and agriculture sectors as predicted by the resource curse theory. On the contrary, the increase in mining output actually had a positive impact on the other two sectors‘ output. Conflict, on the other hand, although not being significant in the model, shows a negative relationship with output in non- mining manufacturing and in agriculture. The Asian economic crisis, interestingly, is also found to have had a positive impact on the non-mining manufacturing and agricultural sector. The second paper, ‗Determinants of inflation in Aceh‘, examines inflation behaviour in Aceh before and after the 2004 Indian Ocean tsunami. The wild increase in inflation in post-tsunami Aceh was assumed to be influenced by two ‗shocks‘: the tsunami and the nation-wide fuel price increase in 2005. -

War Strategy Done by Gayo and Alas People Against Dutch Colonial (1901-1912)
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume I, No 2, June 2018, Page: 25-39 e-ISSN: 2615-3076(Online), p-ISSN: 2615-1715(Print) www.birci-journal.com emails; [email protected] [email protected] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- War Strategy Done by Gayo and Alas People Against Dutch Colonial (1901-1912) 1 2 2 Hairul Masri , Suprayitno , Ratna 1Master Student in Faculty of Cultural Sciences, North Sumatra University (USU),Medan, Indonesia 2Lecturer in Faculty of Cultural Sciences, North Sumatra University (USU),Medan, Indonesia [email protected] Abstract: The arrival of Dutch troops with marsose troops into the Gayo and Alas areas while attempting to crush local fighters led to wars in the area. By fomenting the spirit of war sabil, the fighters with local residents made war against the Dutch as a form of jihad against the unbelievers in order to maintain the area and belief of Islam is embraced. In the face of Dutch troops, the fighters in the Gayo and Alas region used several strategies, among which were the implantation of the Sabil War Ideology, warfare, and guerrilla warfare. Through the implementation of the strategy, the fighters are able to provide fierce resistance and can survive for a long time against the attack of Dutch troops. The Gayo and Alas people's resistance has begun to dwindle since some of the leaders of the fight have been killed and captured by Dutch troops. This led to a decline in resistance because it was no longer well organized as the combatants lost their command. Keywords: war strategy; Gayo and Alas; Dutch colonial. -
F:\My Workproject\2012 01 01 Se
Partai Aceh: TRANSFORMASI GAM? Arya Budi Partai Aceh: TRANSFORMASI GAM? Partai Aceh: Transformasi GAM? Arya Budi Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All Right Reserved Penulis: Arya Budi Editor: Wigke Capri Arti Sampul dan Tata Letak: Oryza Irwanto Research Centre for Politics and Goverment Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Jl. Socio Yusticia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 www.jpp.fisipol.ugm.ac.id email: [email protected] Telp: +62 274 563365 ext.212 286 + xvi halaman 140 x 210 mm ISBN 978-602-96762-7-3 © 2012 Partai Aceh: Transformasi GAM? Daftar Isi Daftar Isi ........................................................................ v Daftar Gambar .............................................................. x Daftar Tabel ................................................................... xi Kata Pengantar Penerbit ............................................. xiii Dari Penulis ................................................................... xv Pendahuluan ................................................................. 1 Aceh: Struktur Peluang Politik ............................ 3 Problema Transformasi ......................................... 6 Teorisasi ................................................................... 9 Genealogi: Menanyakan “Mengapa” ............ 10 Alasan Kelahiran Partai Politik: Sebuah Genealogi .............................................. 12 Transformasi: Keniscayaan dalam Demokrasi ........................................................... 18 Gerakan Senjata, Perang dalam -

Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia
This page intentionally left blank Imperial Alchemy The mid twentieth century marked one of the greatest watersheds of Asian history, when a range of imperial constructs were declared to be nation-states, either by revolution or by decolonisation. Nationalism was the great alchemist, turning the base metal of empire into the gold of nations. To achieve such a transformation from the immense diversity of these Asian empires required a different set of forces from those that Europeans had needed in their transitions from multi-ethnic empires to culturally homogeneous nations. In this book Anthony Reid, one of the premier scholars of Southeast Asia, explores the mysterious alchemy by which new political identities have been formed. Taking Southeast Asia as his example, Reid tests contemporary theory about the relation between modernity, nationalism and ethnic identity. Grappling with concepts emanating from a very different European experience of nationalism, Reid develops his own typology to better fit the formation of political identities such as the Indonesian, Malay, Chinese, Acehnese, Batak and Kadazan. anthony reid is a Southeast Asian Historian now again based at the Australian National University, Canberra, but previously at the National University of Singapore (2002–9), where he established the Asia Research Institute, and University of California, Los Angeles (1999–2002). His other recent books include Southeast Asia in the Age of Commerce (2 vols, 1988–93), Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia (1999), An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra (2004), and, as [co]editor, Islamic Legitimacy in a Plural Asia (2007), Chinese Diaspora in the Pacific (2008) and Negotiating Asymmetry: China’s Place in Asia (2009).