Keraton Jawa 1755 - 1989
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
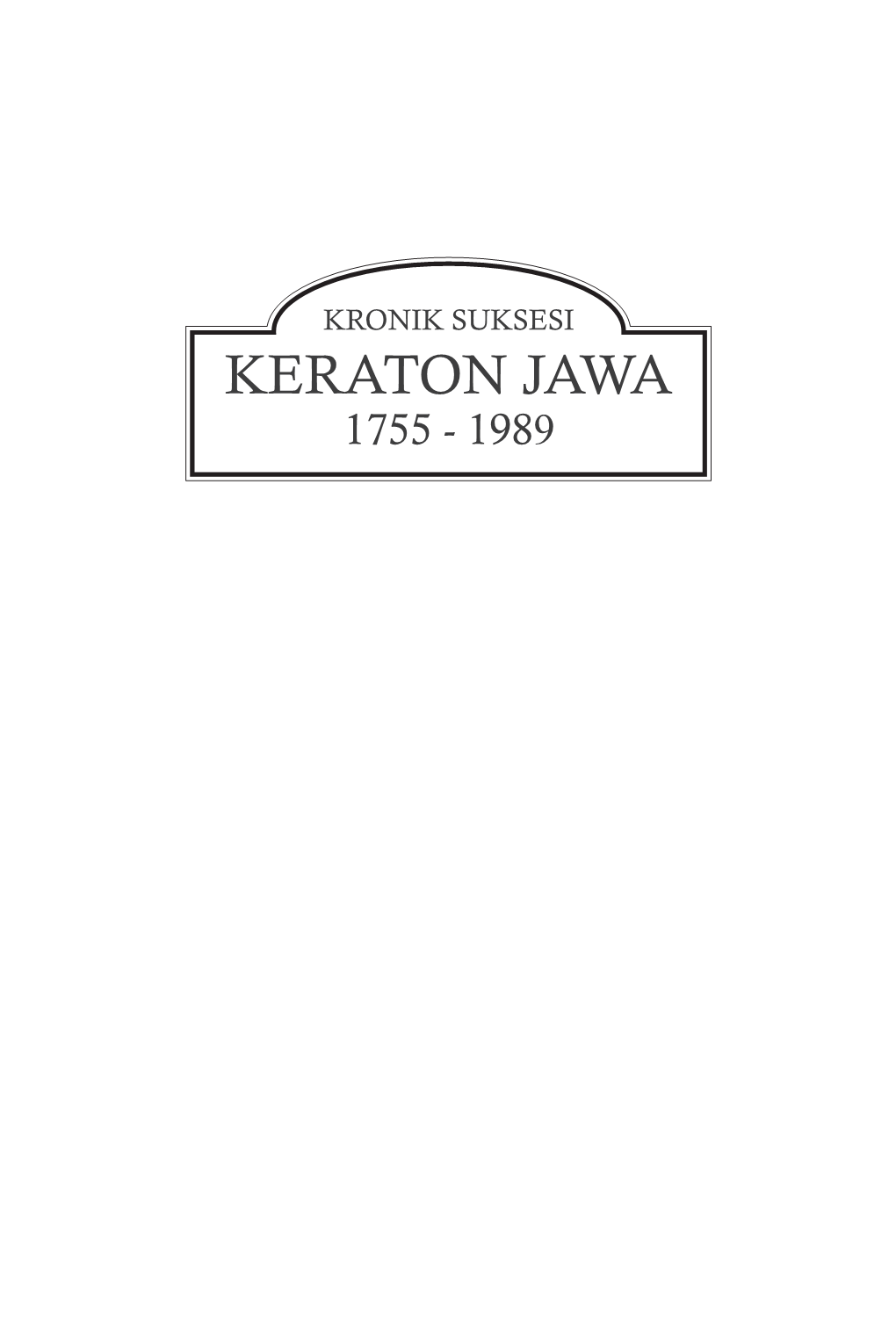
Load more
Recommended publications
-

Space and Myth in Surakarta Kasunanan Palace, Indonesia
SPACE AND MYTH IN SURAKARTA KASUNANAN PALACE, INDONESIA A PRELIMINARY INVESTIGATION OF SPATIAL AND MYTHICAL QUALITIES OF THE PALACE AND HOW THEY RELATE TO THE POWER AND AUTHORITY OF THE K1NG/DOM By WAHYU DEWANTO (Architect) SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UNIVERSITY OF TASMANIA LAUNCESTON U-S-T-R-A-L—I-A NOVEMBER 1997 STATEMENT OF AUTHENTICITY OF MATERIAL This dissertation contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any institution and to the best of my knowledge and belief, the research contains no material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text of the dissertation. ahyu Dewanto Launceston, 21 November 1997 STATEMENT OF AUTHORITY OF ACCESS TO LOAN AND COPYING The University of Tasmania and its approved officers and representatives are authorised to loan or make limited copies of this dissertation for general dispersal in the interests of academic research, subject to the Copyright act 1968. Signed Wahyu Dewanto Launceston, 21 November 1997 111 abstract Surakarta Kasunanan palace, in central Java, is an important part of the heritage of the Indonesian nation. It is regarded as a centre of Javanese culture. The architecture of the palace represents the complexity of Indonesian culture, where local tradition and external social, cultural and religious influences are manifested in the form and structure. Surakarta Kasunanan palace as a whole is considered a sacred place, gives a religious impression and reflects the characteristics of the kingdom. -

AGENDA REV 5 1.Indd
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA AGENDA KERJA DPD RI 2017 DATA PRIBADI Nama __________________________________________________________ No. Anggota ___________________________________________________ Alamat _________________________________________________________ _________________________________________________________________ Telepon/Fax ____________________________________________________ Nomor _________________________________________________________ KTP ____________________________________________________________ Paspor _________________________________________________________ Asuransi _______________________________________________________ Pajak Pendapatan ______________________________________________ SIM ____________________________________________________________ PBB ____________________________________________________________ Lain-lain _______________________________________________________ DATA BISNIS Kantor _________________________________________________________ Alamat _________________________________________________________ _________________________________________________________________ Telepon/Fax ____________________________________________________ Telex ___________________________________________________________ Lain-lain _______________________________________________________ NOMOR TELEPON PENTING Dokter/Dokter Gigi _____________________________________________ Biro Perjalanan _________________________________________________ Taksi ___________________________________________________________ Stasiun K.A -

Lampiran 1 : Matriks Berita 1 : Kemelut Putri Mahkota SINTAKSIS
Lampiran 1 : Matriks Berita 1 : Kemelut Putri Mahkota SINTAKSIS Headline Lead Latar Informasi Kutipan Sumber Penutup Kemelut Putri Demi tahta Keraton Paragraf 1 – 4 : Paragraf 5 : Sehubungan dengan konflik Mahkota untuk Mangkubumi, Pemberian gelar “Tadinya Pembayun tidak pemberian gelar Sri Sultan bahkan Mangkubumi kepada masalah, tapi setelah ada Mangkubumi pada dirinya, Kemelut (KBBI) = menjual harta keraton Pembayun menyebabkan sabda raja, kami ada batas.” Pembayun memilih untuk keadaan yang genting walau hal tersebut beberapa aktivitasnya tidak berbicara apa – apa atau berbahaya. ditentang oleh menjadi terganggu dan Yudhaningrat, adik tiri Sri dengan alasan bahwa ini sebagian anggota membuat ia hubungannya Sultan. belum waktunya bagi dia keluarga keraton. dengan orang – orang untuk berbicara. sekitar semakin terbatasi. Paragraf 5 & 6 : Paragraf 11 : Sri Sultan mengeluarkan “Saya gemeteran sampai dua dawuh (sabda), tidak lihat Ngarso Dalem pemberian gelar sudah jalan turun. Dua hari Mangkubumi kepada saya tidak bisa tidur,” Pembayun serta akunya (Pembayun). 113 penggantian namanya. Kedua dawuh tersebut menyebabkan polemik. Paragraf 7 : Paragraf 12: Gelar Mangkubumi yang Ia (Pembayun) merasa nama disandang Pembayun Mangkubumi sangat berat menyebabkan konflik karena bermakna pemangku tahta keraton. adat kekuasaan. Paragraf 8 – 11 : Paragraf 13: Pemberian gelar tersebut Ia (Siti Sutiyah) mengaku membuat Pembayun semua penari pun tidak merasa terbeban dan selalu hadir, yang penting tertekan. mereka menekuni tarian dengan latihan sendiri. Paragraf 12 & 13 : Paragraf 14 : Gelar Mangkubumi “H-1 dan H-2 itu datang. bukanlah alasan mengapa Kalau beberapa hari Pembayun menghadiri itu memang sempat tidak latihan. rawuh (datang). Tapi, 114 menjelang pentas, tetap datang kok,” jelasnya. Paragraf 14 – 16 : Paragraf 17 : Prosesi Pemberian gelar “Itu memang kursi putri Mangkubumi pada mahkota itu. -

Acoustic Parameter for Javanese Gamelan Performance in Pendopo Mangkunegaran Surakarta
Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 184 ( 2015 ) 322 – 327 5th Arte Polis International Conference and Workshop – “Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place”, Arte-Polis 5, 8-9 August 2014, Bandung, Indonesia Acoustic parameter for Javanese Gamelan Performance in Pendopo Mangkunegaran Surakarta a b b c Suyatno *, H. A. Tjokronegoro , IGN. Merthayasa , R. Supanggah aDepartment of Physics, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia bDepartment of Engineering Physics, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia cDepartement of Karawitan, Institut Seni Indonesia, Surakarta, Indonesia Abstract Pendopo Mangkunegaran Surakarta is a building that has a volume of 3000 m3, a pyramid form of roof, and no walls. The objective of the research in this paper is to explore the condition of Listening Level (LL), a sub-sequence Reverberation Time (Tsub), Clarity (C80, D50) and Inter-Aural Cross Correlation (IACC) at Pendopo Mangkunegaran Surakarta. To quantify the acoustic parameters of the Pendopo, microphones were located in the area of the King, distinguished guests, dancers, and audience. The source of sound is located at the corner of where the Gamelan is played. The sound of Gamelan at the corner of the Pendopo produces a diverse distribution of sound and reverberation time in the room, especially in the center of the room. It is concluded that the acoustic quality of Pendopo building is appropriate for Javanese Gamelan performances with a well-developed spatial effect. © 20152015 The The Authors. Authors. Published Published by by Elsevier Elsevier Ltd. Ltd This. is an open access article under the CC BY-NC-ND license (Peerhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-review under responsibility of the Scientific). -

Confirming the Existence of the Kingdom: the Efforts of Territorial Consolidation and Formation of Cultural Identity During
Indonesian Historical Studies, Vol. 1, No. 2, 103-116 © 2017 Confirming the Existence of the Kingdom: The Efforts of Territorial Consolidation and Formation of Cultural Identity During the Reign of Hamengku Buwana I, 1755 – 1792 Sutarwinarmo,1* Agustinus Supriyono,2 Dhanang Respati Puguh2 1Arsip Nasional Republik Indonesia 2Master Program of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University *Corresponding Author: [email protected] Abstract This article discusses the efforts of territorial Consolidation and formation of cultural identity during the reign of Hamengku Buwana I. This article is written using historical method and utilizing primary sources in the form of VOC archives stored in the National Archives of the Republic of Indonesia and Java manuscripts stored in Yogyakarta Sultanate, as well as secondary sources in the form of articles and books. After Giyanti Agreement in 1755, Sultan Hamengku Buwana I attempted to consolidate his territory through negotiation, dispute Received: settlement and law enforcement in order to preserve the sovereignity 30 November 2017 and territorial integrity of his kingdom. He also developed Ringgit Swargen, Yogyakarta style leather puppets that have different shape Accepted: 18 December 2017 from Surakarta style leather puppets developed by Surakarta Sunanate as one of the cultural identity of Yogyakarta Sultanate. Leather puppet show was used to control the areas that were in the territory of the Sultanate of Yogyakarta, as the leather puppet show performed outside the palace must obtain permission from the palace puppet master. The efforts of Sultan Hamengku Buwana I failed, due to the conflict that caused the war destroyed the boundaries and the peace agreement that had been made. -

Indonesia's Regional Representative Assembly
Indonesia’s Regional Representative Assembly: Democracy, Representation and the Regions A report on the Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Stephen Sherlock Centre for Democratic Institutions July 2005 About the Author ............................................................................................................ 3 About the Centre for Democratic Institutions .......................................................... 3 Introduction ..................................................................................................................... 4 What is the DPD?............................................................................................................ 6 Constitutional role and powers....................................................................................... 6 An advisory body not an upper house ............................................................................ 8 An assembly for the regions.......................................................................................... 10 Structure of the DPD ................................................................................................... 10 Leadership of the DPD.......................................................................................... 11 Ad‐Hoc Committees.............................................................................................. 12 Steering Committee ............................................................................................... 12 Legislation Committee ......................................................................................... -

Mapping Status and Roles of Javanese Women in Indonesian Literary Texts
PEMETAAN STATUS DAN PERAN PEREMPUAN JAWA DALAM TEKS SASTRA INDONESIA MAPPING STATUS AND ROLES OF JAVANESE WOMEN IN INDONESIAN LITERARY TEXTS Esti Ismawati Program Pascasarjana Universitas Widya Dharma Klaten [email protected] Abstract Status and roles of Javanese women in Indonesian literary text has been written in the form of short stories, novels, and romances, as seen in Umar Kayam, YB Mangunwijaya, Arswendo Atmowiloto, Nh Dini, and Ahmad Tohari, but until now no one has diccussed it scientifically. This paper describes status and roles of Javanese women in Indonesian literary texts from the colonial era, independence era, today’s era, and Javanese women in reality, because the literary texts are the reflection of the society. Are there changes within the status and roles of Javanese women in Indonesian literary texts and in the reality? The methods used in this research are descriptive method for the Javanese women in literary texts and survey for the Javanese women in the reality. The techniques used are bibliography technic (reading appreciation) for literary text and indepth interview and questionnaire. It can be concluded that the status and roles of Javanese women in Indonesian literary texts and in the reality changes from era to era. The changes includemindset and lifestyle change. There is no difference between the status and roles of Javanese women in Indonesian literary texts and in the reality. Keywords: Javanese women, status, roles, literary texts, reality Abstrak Status dan peran perempuan Jawa dalam teks sastra Indonesia telah banyak ditulis dalam bentuk cerpen, novel, dan roman, sebagaimana tampak dalam karya Umar Kayam, YB Mangunwijaya, Arswendo Atmowiloto, Nh Dini, dan Ahmad Tohari. -

73 Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur 73 Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur Wahyuni Choiriyati Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Jalan Margonda Raya No. 100 Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia. Email: [email protected] Abstract King declaration was delivered by Sultan Hamengkubuwono X exposing his princess for next in order to be crowned in Yogyakarta’s palace.This raised contentious among Sultan Hamengkubuwono and his brothers. This was wrapped in cultural communication practicess in high level of context that was not easy to understand especially for society in general. This writing is to focus signifying king declaration in society in line to deep structure and culture. By phenomenology approach with critical paradigm, data gathered by in depth interviews and observation. Results of research found that king decralation was perceived as high context communication practices. This tended to economic political nuances. Nowdays, King has not dedicated to serve the society yet, but he tended to want to be respected. Power structure was maintained to secure the power legitimation including reveneu of land taxes and royal familiy businesses in palace. Each of them played the significant roles to secure and maintain in inner cirlce of power in the palace. Keywords: succession of leadership, structure, power, culture and communication Abstrak Sabdaraja yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan bahwa putri sulungnya akan diangkat menjadi penerus tahta kraton Yogyakarta. Hal ini menimbulkan ketegangan antara sultan Hamengkubuwono X dengan adik-adiknya. Semua ini dikemas dalam praktik komunikasi budaya konteks tinggi yang tidak mudah diterjemahkan masyarakat awam. Fokus tulisan ini adalah menggambarkan pemakanaan masyarakat Yogyakarta terkait sabdaraja dan segala hal yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dan budaya yang melingkupinya. -

Batik, a Beautiful Cultural Heritage That Preserve Culture and Support Economic Development in Indonesia”
“BATIK, A BEAUTIFUL CULTURAL HERITAGE THAT PRESERVE CULTURE AND SUPPORT ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA” Evi Steelyana Accounting Departement, Faculty of Economics and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480 [email protected] ABSTRACT Batik is an icon nation for Indonesia. Batik has awarded as cultural heritage from UNESCO on October 2nd, 2009and it is significantly affected to batik industry afterward.The raising of batik industry caused some multiplier effects to economics and socio cultural in Indonesia. In many areas of industry, banking role has always beenthe man behind the scene. Banking role in Indonesia also gives some encouragement and be part of batik industry development. Many national event has been created by some banks to encourage SME in batik industry to market their product internationally. This paper will give a simple explanation how banking industry and batik industry get along together in Indonesia, especially in financial sector to enhance economics development and to preserve a nation culture.Research methodology in this paper is quantitative method. This paper will give a simple analysis through comparative analysis based on export value from batik industry, domestic use of batik,batik industry development and microcredit or loan from banking industry to SME in batik industry.Many people wearing batik to show how they do appreciate and belong to a culture.Batik also gives other spirit of nationalism which represent in Batik Nationalis.The role of batik in international diplomacy and in the world level gives significant meaning for batik as a commodity which preserve Indonesian culture. In a piece of batik cloth, embodied socio-cultural and economic values that maintain the dignity of a nation. -

SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY in the NEW ORDER a Thesis Presented to the Faculty of the Center for Inte
SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER A thesis presented to the faculty of the Center for International Studies of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Sony Karsono August 2005 This thesis entitled SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER by Sony Karsono has been approved for the Department of Southeast Asian Studies and the Center for International Studies by William H. Frederick Associate Professor of History Josep Rota Director of International Studies KARSONO, SONY. M.A. August 2005. International Studies Setting History Straight? Indonesian Historiography in the New Order (274 pp.) Director of Thesis: William H. Frederick This thesis discusses one central problem: What happened to Indonesian historiography in the New Order (1966-98)? To analyze the problem, the author studies the connections between the major themes in his intellectual autobiography and those in the metahistory of the regime. Proceeding in chronological and thematic manner, the thesis comes in three parts. Part One presents the author’s intellectual autobiography, which illustrates how, as a member of the generation of people who grew up in the New Order, he came into contact with history. Part Two examines the genealogy of and the major issues at stake in the post-New Order controversy over the rectification of history. Part Three ends with several concluding observations. First, the historiographical engineering that the New Order committed was not effective. Second, the regime created the tools for people to criticize itself, which shows that it misunderstood its own society. Third, Indonesian contemporary culture is such that people abhor the idea that there is no single truth. -

Memaknai Bentuk Rupa Lambang Keraton Mangkunegaran
MEMAKNAI BENTUK RUPA LAMBANG KERATON MANGKUNEGARAN Herliyana Rosalinda1, Umi Kholisya2 Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta. [email protected], [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Makna Simbolis Lambang Keraton Mangkunegaran Surakarta. Pmbahasannya digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode historis, untuk menafsirkan makna simbol yang ada pada lambang keraton Mangunegaran digunakan pendekatan hermeunitika. Objeknya Keraton Mangkunegaran Surakarta sedangkan subjek penelitian ini adalah Makna Simbolis Lambang Keraton. Penelitian juga difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Mangkunegaran Surakarta, selain itu pemaknaan lambang sebagai identitas legitimasi suatu pemerintahan dalam kerangka budaya juga menjadi kajian yang penting, terutama dari bentuk visual, rupa, maksud atau makna simbolik yang ada pada lambang kerajaan Mangkunegaran Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan: pada setiap periodesasi pemerintahan Mangkunegara, lambang Mangkunegaran memiliki bentuk rupa dan makna simbol yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik pemikiran, pemerintahan, maupun filosofis dari dalam diri raja Mangkunegaran yang sedang memerintah. Umumnya unsur gambar yang ada pada lambang Mangkunegaran berisi gambar mahkota, padi dan kapas, surya, dan logotype MN. Sedangkan untuk perbedaannya ddilihat dari perbedaan tampilan bentuk ataupun jumlah masing-masing jenis gambar tersebut. Kata Kunci : Bentuk rupa, Simbol, Lambang, Mangkunegaran INTERPRET SHAPE OF EMBLEM ON MANGKUNEGARAN PALACE Abstract This study aimed to describe the Meaning of Mangkunegaran Surakarta Symbol. The explanation of this study classed as a qualitative descriptive using historical methods, and then to interpret the meaning of the symbol on the emblem used Mangunegaran palace hermeunitika approach. The object is Kraton Mangkunegaran while the subject of this study was the Meaning of Symbol palace. -

Indo 37 0 1107019139 119
Nyai Bei Mardusari, a Wife of Mangkunegara VII and a famous Surakarta Dancer and Pesindhdn (1936) Singer-dancers ( talgdhek) with small gamelan at roadside warung (1955) Photographs by Claire Holt WHO IS TH E PESINDHEN? NOTES ON THE FEMALE SINGING TRADITION IN JAVA R. Anderson Sutton* Those who have attended performances of gamelan music in Central Java can be in no doubt that the solo female singer (pesindhen) is accorded a role of special prominence. Usually situated conspicuously in front of the gamelan, she is set off from the male instrumentalists for all to see. Amplifiers often blast her voice at peak volume over the full gamelan ensemble. In the performance of many pieces she is given solo passages (andhegan), which draw all attention exclusively to her. One of my teachers in Java, Suhardi, used to tell me that there was no sense in playing gamelan if there were no pesindhen. Although for some pieces he would adopt the "loud-playing" style, with no vocal or soft-sounding instruments of any kind, he was like most Javanese performers and listeners in his fondness for the "soft-playing" style— in which a pesindhen is an essential component. Commercial cassette recordings of gamelan music, almost without exception, feature the vocal line of the pesindhen at a much higher dynamic level than that of any instrumental part. On the covers of cassettes appear the names and often the photographs of the pesindhen (usually several)* 1 who sang in the recorded perform ance. The names of these singers are generally well known, and buyers often choose a particular cassette because it features one of their favorite pesindhen.