Al-Qur'an Dalam Okultisme Nusantara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Short History of Indonesia: the Unlikely Nation?
History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page i A SHORT HISTORY OF INDONESIA History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page ii Short History of Asia Series Series Editor: Milton Osborne Milton Osborne has had an association with the Asian region for over 40 years as an academic, public servant and independent writer. He is the author of eight books on Asian topics, including Southeast Asia: An Introductory History, first published in 1979 and now in its eighth edition, and, most recently, The Mekong: Turbulent Past, Uncertain Future, published in 2000. History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page iii A SHORT HISTORY OF INDONESIA THE UNLIKELY NATION? Colin Brown History Indonesia PAGES 13/2/03 8:28 AM Page iv First published in 2003 Copyright © Colin Brown 2003 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. The Australian Copyright Act 1968 (the Act) allows a maximum of one chapter or 10 per cent of this book, whichever is the greater, to be photocopied by any educational institution for its educational purposes provided that the educational institution (or body that administers it) has given a remuneration notice to Copyright Agency Limited (CAL) under the Act. Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest NSW 2065 Australia Phone: (61 2) 8425 0100 Fax: (61 2) 9906 2218 Email: [email protected] Web: www.allenandunwin.com National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry: Brown, Colin, A short history of Indonesia : the unlikely nation? Bibliography. -

Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Daftar Pustaka 265 DAFTAR PUSTAKA Abbas, Siradjuddin, 1984a, I‘tiqad Ahlussunnah wal Jama`ah , Jakarta: Pustaka Tarbiyah. ------------------------, 1984b, 40 Masalah Agama , Jil. IV, Jakarta: Pustaka Tarbiyah. Abduh, Muhammad, 1969, Ris>lah at-Tauh}i>d, Tkp: tp. Abdullah, Abdul Rahman Haji, 1997, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran , Jakarta: Gema Insani Press. Abdullah, H.W. Muhd. Shaghir, 1983, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam , Pontianak: al-Fathanah. Abdullah, Taufik dan Sharon Shiddique ( ed .), 1988, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara , Jakarta: LP3ES. Abdullah, Taufik, ( ed .), 1992, Sejarah Ummat Islam Indonesia , Jakarta: MUI. Abdullah, M. Amin, 2004, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Abdullah, Taufik, 1987, Islam dan Masyarakat: Pantuan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES. Abdulwahid, Idat, 1991. Kajian Semiotik Folklor (Mantra) di Jawa Barat. Laporan Penelitian. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Ahmad, Khursin, 1983, Pesan Islam , penerj. Achsin Mohammad, Bandung: Pustaka. Ahmad, M.M. Zuhuruddin, 1993, Mystic Tendencies in Islam: in the Light of the Qur’an and Traditions, Delhi: Low Price Publications. Amdjad Al-Hafidh, 1999, Keistimewaan dan Peranan Al-Asma Ul-Husna di Zaman Modern, Semarang: Yayasan Majelis Khidmah Al-Asma-Ul-Husna. Amin, M. Masyhur, 1995, Dinamika Islam: Sejarah Transformasi dan Kebangkitan , Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Amuli, Jawad, 2003, Hikmah dan Makna Haji , Bogor: Cahaya. Albanese, Cahtherine L., 1999, America Religions and Religion , 3rd Edition, Albany, NY: Wadsworth Publishing Company. Ali, Abdullah Yusuf, 1983, The Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary , Brentwood, Maryland: Amana Corp. Ali, Maulana Muhammad, 1991, Holy Qur’an: Arabic Text, English Translation and Com- mentary , Seventh Edition, U.S.A.: Ahmadiyah Anjuman Isha`at Islam, Lahore, Inc. -

Bentuk-Bentuk Mitos Dalam Cerita Rakyat Banjar the Myth Types in Banjar’S Folklore
Tuah Talino Volume 12 Nomor 1 Edisi Juli 2018 Balai Bahasa Kalimantan Barat BENTUK-BENTUK MITOS DALAM CERITA RAKYAT BANJAR THE MYTH TYPES IN BANJAR’S FOLKLORE Saefuddin Balai Bahasa Kalimantan Selatan [email protected] ABSTRAK Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk- bentuk mitos dalam cerita rakyat Banjar. Tujuan penelitian ini akan mengungkap bentuk-bentuk mitos dalam cerita rakyat Banjar. Cerita rakyat yang berbentuk mite ialah salah satu jenis sastra lama dan bersifat anonim. Cerita mitos bukan milik perseorangan, tetapi dihasilkan oleh masyarakat. Penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut. Mitos secara umum berhubungan dengan kisah-kisah tentang keajaiban dan erat hubungannya dengan kepercayaan terhadap dewa- dewa mendapat tempat luas dalam masyarakat. Kisah-kisah mitos dapat dilihat pada cerita rakyat Banjar, salah satunya ialah cerita Puteri Junjung Buih yang menceritakan tentang manusia yang lahir dari hasil pertapaan dan manusia lahir dari buih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif ialah suatu metode untuk memperoleh informasi tentang narasi dalam cerita mitos secara lebih terperinci. Hasil penelitian memberi gambaran tentang bentuk-bentuk mitos dalam cerita rakyat Banjar di Kalimantan Selatan. Kata kunci: Mitos, cerita rakyat Banjar ABSTRACT The problem which is discussed in this study is how the types of myth in Banjar’s foklore are. The aim of this study is to reveal the types of myth in Banjar’s folklore. The myth in folklore is one of old literatures and is anonymous. Myth is not belong to an individual, but it is produced by a society. The dissemination was done from mouth to mouth. -

Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden
INVENTORIES OF COLLECTIONS OF ORIENTAL MANUSCRIPTS INVENTORY OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF LEIDEN VOLUME 7 MANUSCRIPTS OR. 6001 – OR. 7000 REGISTERED IN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY IN THE PERIOD BETWEEN MAY 1917 AND 1946 COMPILED BY JAN JUST WITKAM PROFESSOR OF PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY OF THE ISLAMIC WORLD IN LEIDEN UNIVERSITY INTERPRES LEGATI WARNERIANI TER LUGT PRESS LEIDEN 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007. The form and contents of the present inventory are protected by Dutch and international copyright law and database legislation. All use other than within the framework of the law is forbidden and liable to prosecution. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the author and the publisher. First electronic publication: 17 September 2006. Latest update: 30 July 2007 Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007 2 PREFACE The arrangement of the present volume of the Inventories of Oriental manuscripts in Leiden University Library does not differ in any specific way from the volumes which have been published earlier (vols. 5, 6, 12, 13, 14, 20, 22 and 25). For the sake of brevity I refer to my prefaces in those volumes. A few essentials my be repeated here. Not all manuscripts mentioned in the present volume were viewed by autopsy. The sheer number of manuscripts makes this impossible. -
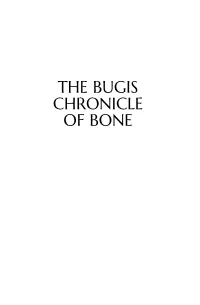
The Bugis Chronicle of Bone
THE BUGIS CHRONICLE OF BONE THE BUGIS CHRONICLE OF BONE TRANSLATED AND EDITED BY CAMPBELL MACKNIGHT, MUKHLIS PAENI AND MUHLIS HADRAWI Published by ANU Press The Australian National University Acton ACT 2601, Australia Email: [email protected] Available to download for free at press.anu.edu.au ISBN (print): 9781760463571 ISBN (online): 9781760463588 WorldCat (print): 1140933926 WorldCat (online): 1140933873 DOI: 10.22459/BCB.2020 This title is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). The full licence terms are available at creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Cover design and layout by ANU Press. Cover image: The rice fields of Bone display the agricultural basis of the kingdom, while the lontar palms provided the original medium for Bugis writing (photograph by Campbell Macknight). The sword, La Téariduni, an item in the regalia of Bone, indicates military might. The chronicle records its name being used to represent the kingdom in a treaty from the middle of the sixteenth century (image from Perelaer 1872, vol. 2, plate 1). This edition © 2020 ANU Press Contents Figures, maps and plates vii Acknowledgements ix Preface xi Introduction 1 1. The Chronicle of Bone in Bugis historiography 1 2. The definition of the work 5 3. The manuscript 6 4. The choice of this version of the work 7 5. Principles of transcription 10 6. Principles of translation 13 7. The nature of the work 14 8. The date of the work and the problem of the end 21 9. Early Western-language comment on the events of the chronicle 26 10. -

A JAWI SOURCEBOOK for the STUDY of MALAY PALAEOGRAPHY ∗ and ORTHOGRAPHY Introduction
Annabel Teh Gallop A JAWI SOURCEBOOK FOR THE STUDY OF MALAY PALAEOGRAPHY ∗ AND ORTHOGRAPHY Introduction This special issue of Indonesia and the Malay World was compiled by friends and col- leagues as a tribute to Professor E. Ulrich Kratz’s three decades of teaching Jawi and tra- ditional Malay literature at the School of Oriental and African Studies, University of London, and to mark his 70th birthday on 14 October 2014. Reflecting Ulrich’s deep inter- est in Malay manuscript texts and letters over many years (see the list of publications com- piled by Helen Cordell in this issue), this Festschrift takes the rather unusual form of a compilation of reproductions of Malay manuscripts in Jawi script, accompanied by commen- taries on the handwriting and spelling. Nearly all the manuscripts are dated or firmly date- able, and come from known locations. The hope is that this issue will be useful as a sourcebook for the study of the development of Jawi script, and in particular its palaeography and orthography, over the course of nearly three and a half centuries. The manuscripts pre- sented date from the end of the 16th century to the early 20th century, and originate from all corners of the Malay world, from Aceh to Aru and from Melaka to Mindanao, as well as from Malay communities in Sri Lanka and Mecca. Arabic script in Southeast Asia It is highly likely that there may have been an Islamic presence in Southeast Asia – in the form of individual traders and travellers of Muslim faith, as well as small groups of local converts – from the early centuries of the Hijra era, but it is generally accepted that the Downloaded by [Universiteit Leiden / LUMC] at 02:58 25 June 2016 institutionalisation of Islam which occurred with the formal conversion of the ruler of a state first took place in the Malay archipelago around the 13th century AD in north Sumatra. -

In Search of Asian Malagasy Ancestors in Indonesia Pradiptajati Kusuma
In search of Asian Malagasy ancestors in Indonesia Pradiptajati Kusuma To cite this version: Pradiptajati Kusuma. In search of Asian Malagasy ancestors in Indonesia. Social Anthropology and ethnology. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2017. English. NNT : 2017TOU30109. tel- 01914319 HAL Id: tel-01914319 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01914319 Submitted on 6 Nov 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE En vue de l’obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : Universite Toulouse III - Paul Sabatier Présentée et soutenue par : KUSUMA Pradiptajati Le 14 Septembre 2017 Titre : In search of Asian Malagasy ancestors in Indonesia ED Biologie, Santé, Biotechnologies: Anthropobiologie Unité de recherche : Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse (AMIS) UMR-5288 Directeur(s) de Thèse : RICAUT François-Xavier, Chargé de Recherche LETELLIER Thierry, Chargé de Recherche Rapporteurs : FORESTIER Hubert, Professeur, Paris, France KAYSER Manfred, Professeur, Rotterdam, Pays-Bas Autre(s) membre(s) du jury : -

Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden
INVENTORIES OF COLLECTIONS OF ORIENTAL MANUSCRIPTS INVENTORY OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF LEIDEN VOLUME 2 MANUSCRIPTS OR. 1001 – OR. 2000 REGISTERED IN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY IN THE PERIOD BETWEEN 1665 AND 1871 COMPILED BY JAN JUST WITKAM PROFESSOR OF PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY OF THE ISLAMIC WORLD IN LEIDEN UNIVERSITY INTERPRES LEGATI WARNERIANI TER LUGT PRESS LEIDEN 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007. The form and contents of the present inventory are protected by Dutch and international copyright law and database legislation. All use other than within the framework of the law is forbidden and liable to prosecution. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the author and the publisher. First electronic publication: 27 October 2006. Latest update: 13 August 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007 2 PREFACE The arrangement of the present volume of the Inventories of Oriental manuscripts in Leiden University Library does not differ in any specific way from the volumes which have been published earlier. For the sake of brevity I refer to my prefaces in those volumes. A few essentials my be repeated here. Not all manuscripts mentioned in the present volume were viewed by autopsy, but many were. The sheer number of manuscripts makes this impossible. At a later stage this may be achieved, but trying to achieve this at the present stage of inventorizing would seriously hamper the progress of the present project. -

Perut Hijau: Siam Dalam Jiwa Melayu
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repository@USM 1 PERUT HIJAU: SIAM DALAM JIWA MELAYU oleh Ahmad Murad Merican [email protected] Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang [Dibentangkan di Seminar Antarabangsa Sejarah Lisan 2016 dari Perspektif Sejarah, Warisan dan Kebudayaan Malaysia-Thailand, 2-4 Disember 2016, Pak Bara, Satun, Thailand] ABSTRAK Pemerhatian dan kajian mengenai imej dan paparan orang asing oleh orang Melayu merupakan satu pendekatan yang agak baru dalam menyelami interaksi Melayu dengan kaum asing, sekaligus dapat mengenali jiwa Melayu zaman berzaman. Kajian ini meninjau imej Siam dalam jiwa Melayu. Siam tidak pernah menjajah Melayu, walaupun negeri Kedah. Siam bernaung ke atas negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu berkurun lamanya. Perhubungan Melayu – Siam, khususnya Kedah-Siam ialah satu perhubungan yang kompleks. Terdapat detik peperangan, dan juga detik keamanan. Namun, umumnya dalam masyarakat Melayu, lanjutan dari pengalaman negeri Kedah, Siam diwajahkan sebagai kaum yang ganas dan memerah kudrat Melayu. Siam boleh diungkapkan juga sebagai “kacau daun” Melayu, khususnya Kedah. Ada masanya Siam diterima sebagai pelindung, dan ada masa sebagai pengacau. Hasil dari pertembungan itu, pelbagai imej orang-orang Siam telah di paparkan dalam sejarah. Paparan imej itu berubah-ubah mengikut jenis pertembungan dan perhubungan. Lazimnya kita dengar ungkapan ‘Siam perut hijau.’ Kertas kerja ini menggunakan beberapa visual, dan laman media baru seperti Facebook dan blog bagi memaparkan jiwa Melayu terhadap Siam. Cerita yang dapat dikutip memaparkan memori kolektif dan sentiment Melayu terhadap Siam – rakyat dan raja. Kita juga dapat perhatikan imej Siam dalam beberapa teks kasik terpilih serta pilihan Surat-Surat Francis Light dalam perhubungan dengan beberapa Sultan Kedah. -

Boat Symbolism and Political Systems in Insular Southeast Asia*
9 Shipshape Societies: Boat Symbolism and Political Systems in Insular Southeast Asia* Pierre-Yves Manguin Boat motives appearing in various Southeast Asian cultural contexts were first described in detail when the subject attracted the attention of scholars in the 1930's. On the one hand, Steinmann analysed the 11 motive in terms of the "cult ship : starting from the description of the Lampung ship-cloths, he compared their motives with those appear- ing in shamanistic death rituals among the Dayaks and with the famous Bronze Age canoes of the Dong-sdn drums. ,"On the other hand, Vroklage concentrated on Eastern Indonesia; except for the occasional comparison of the "death-ship" motive with the Greeks' crossing of the river Styx, for a brief outline analysis of the relationship of boat motives with the then popular "megalithic culture", or for the repeated mention of the ancient migratory voyage as the origin of the social patterns under discussion, his various articles are basically descriptive. [ 1] Scattered references to the subject appeared occasionally after the War, but it is only during this last decade that the two previous trends have clearly been revived. Art historians, particularly specialists of textiles, have devoted a fair amount of work to the Lampung ship-cloths and to their role in this Sumatran society. [2] The Eastern Indonesian "field of studies" has similarly been the object of renewed interest from a large number of well-trained anthropologists who have used sophisticated analytical tools to study boat symbolism and its meaning within the global social systems they dealt with. [3] However, to this point, little has been done to integrate in a broader geographical and chronological framework the multiple refer- ences to boat symbolism in Insular Southeast Asia. -

Dari Bugis Klasik Ke Bugis Islam: Studi Sastra Atas Bottinna I La D Ếwata Sibawa I W Ế Attaweq (Bda)
DARI BUGIS KLASIK KE BUGIS ISLAM: STUDI SASTRA ATAS BOTTINNA I LA D ẾWATA SIBAWA I W Ế ATTAWEQ (BDA) Classic to Islamic Buginess: Literary Study towards I La Dewata Sibawa I We Attaweq (BDA) Andi Muhammad Akhmar Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Jalan Perintis kemerdekaan, Km.10, Makassar Ponsel 081392121488 Pos-el: [email protected] Abstrak Para penyusun buku Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Sulawesi Selatan memasukkan sejumlah naskah yang berisi kisah perkawinan La Déwata dan Wé Attaweq ini dalam kelompok naskah La Galigo /sastra Galigosementara, Kern dan Matthes justru menganggap naskah –naskah tersebut bukan bagian dari siklus ( cyclus ) La Galigo . Perbedaan pandangan pendapat ini memunculkan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu bagaimana pergeseran bentuk-bentuk formula dan komposisi cerita dari kedua pandagan terasebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana pergeseran bentuk-bentuk formula dan komposisi cerita dalam BDA dalam kerangka pergeseran penciptaan teks dan tanggapan pembaca. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode resepsi sastra dalam analis datanya. Selain itu, kedua naskah BDA diperiksa dengan menggunakan teori rumus, semiotika, dan penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komposisi puisi, teks BDA versi klasik mengikuti sistem formula puisi La Galigo. Sementara itu, teks BDA versi islam memperlihatkan dua jenis kombinasi formula, yaitu kombinasi bersifat tetap dan kombinasi bersifat tidak tetap. Demikian pula struktur penceritaan pada kedua teks yang diamati memperlihatkan perbedaan yang menonjol. Pada teks BDA versi klasik hanya memuat memuat satu téreng (episode) yang isinya menceritakan satu peristiwa upacara perkawinan. Sementara itu, teks BDA versi Islam, memaut kisah yang luas, yaitu tujuh kali peristiwa perkawinan, dengan perluasan-perluasan cerita yang terdapat di dalamnya. -

Intertekstual Dekonstruktif Novel Lambung Mangkurat Atas Hikayat Banjar Dan Tutur Candi
ALINEA ::: JURNAL BAHASA SASTRA DAN PENGAJARAN P-ISSN: 2301 – 6345 I E-ISSN: 2614-7599 http://jurnal.unsur.ac.id/ajbsi INTERTEKSTUAL DEKONSTRUKTIF NOVEL LAMBUNG MANGKURAT ATAS HIKAYAT BANJAR DAN TUTUR CANDI Dewi Alfianti & Ahsani Taqwiem Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ______________ Abstrak : Riwayat artikel: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui interteksualitas dan dekonstruksi novel “Lambung Mangkurat”, dan dua hipogramnya, “Hikayat Banjar” dan “Tutur Dikirim: 6 Desember 2019 Candi”. Penelitian dilakukan menggunakan analisis intertekstual model Julia Direvisi: 6 Januari 2020 Kristeva dan dekonstruksi Jaqcues Derrida. Hasil analisis menunjukkan ada Diterima: 8 Februari 2020 sejumlah perbedaan pada bagian jalan cerita dan penokohan. Pada novel tidak Diterbitkan: 30 April 2020 ada hal-hal gaib, berbeda dengan dalam kedua hipogram. Tokoh Lambung Mangkurat dan Junjung Buih dalam novel diberi atribut serba sempurna sementara di dalam novel muncul dengan segala kekurangan dan kelemahan sebagaiman manusia biasa yang memiliki ambisi, kelemahan, dan ketakutana __________ yang di dalam dua hipogram tidak ada. Di dalam novel Lambung Mangkurat Katakunci: diceritakan berhasil menjadi Raja Nagara Dipa berkat bantuan Gajah Mada, juga dicerita terjadi pemberontakan Kerajaan Kuripan yang di dua hipogram dekonstruktif tidak. Perbedaan ini terjadi sebagai upaya pengarang untuk menafsirkan ulang intertekstual dan memaknai kembali cerita Lambung Mangkurat dalam perspektif yang lebih Lambung Mangkurat sesuai dengan zamannya. Abstract: This paper aims to find out the intertexuality and deconstruction of the novel _______________________ "Lambung Mangkurat", and two hypograms, "Hikayat Banjar" and "Tutur Alamat surat Candi". The study was conducted using intertextual analysis of Julia Kristeva's model and Jaqcues Derrida's deconstruction. The analysis shows that there are [email protected] a number of differences in the part of the storyline and characterizations.