Dermaga-Sastra-Indon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

And Bugis) in the Riau Islands
ISSN 0219-3213 2018 no. 12 Trends in Southeast Asia LIVING ON THE EDGE: BEING MALAY (AND BUGIS) IN THE RIAU ISLANDS ANDREW M. CARRUTHERS TRS12/18s ISBN 978-981-4818-61-2 30 Heng Mui Keng Terrace Singapore 119614 http://bookshop.iseas.edu.sg 9 789814 818612 Trends in Southeast Asia 18-J04027 01 Trends_2018-12.indd 1 19/6/18 8:05 AM The ISEAS – Yusof Ishak Institute (formerly Institute of Southeast Asian Studies) is an autonomous organization established in 1968. It is a regional centre dedicated to the study of socio-political, security, and economic trends and developments in Southeast Asia and its wider geostrategic and economic environment. The Institute’s research programmes are grouped under Regional Economic Studies (RES), Regional Strategic and Political Studies (RSPS), and Regional Social and Cultural Studies (RSCS). The Institute is also home to the ASEAN Studies Centre (ASC), the Nalanda-Sriwijaya Centre (NSC) and the Singapore APEC Study Centre. ISEAS Publishing, an established academic press, has issued more than 2,000 books and journals. It is the largest scholarly publisher of research about Southeast Asia from within the region. ISEAS Publishing works with many other academic and trade publishers and distributors to disseminate important research and analyses from and about Southeast Asia to the rest of the world. 18-J04027 01 Trends_2018-12.indd 2 19/6/18 8:05 AM 2018 no. 12 Trends in Southeast Asia LIVING ON THE EDGE: BEING MALAY (AND BUGIS) IN THE RIAU ISLANDS ANDREW M. CARRUTHERS 18-J04027 01 Trends_2018-12.indd 3 19/6/18 8:05 AM Published by: ISEAS Publishing 30 Heng Mui Keng Terrace Singapore 119614 [email protected] http://bookshop.iseas.edu.sg © 2018 ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore All rights reserved. -
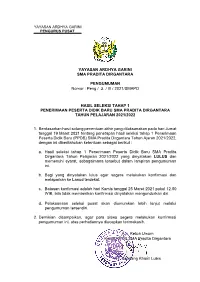
Pengumuman-Tahap-1-Ppdb
YAYASAN ARDHYA GARINI PENGURUS PUSAT YAYASAN ARDHYA GARINI SMA PRADITA DIRGANTARA PENGUMUMAN Nomor : Peng / 2 / III / 2021/SMAPD HASIL SELEKSI TAHAP 1 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA PRADITA DIRGANTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022 1. Berdasarkan hasil sidang penentuan akhir yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hasil seleksi tahap 1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Pradita Dirgantara Tahun Ajaran 2021/2022, dengan ini diberitahukan ketentuan sebagai berikut : a. Hasil seleksi tahap 1 Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Pradita Dirgantara Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dinyatakan LULUS dan memenuhi syarat, sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini. b. Bagi yang dinyatakan lulus agar segera melakukan konfirmasi dan melaporkan ke Lanud terdekat. c. Batasan konfirmasi adalah hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, bila tidak memberikan konfirmasi dinyatakan mengundurkan diri. d. Pelaksanaan seleksi pusat akan diumumkan lebih lanjut melalui pengumuman tersendiri. 2. Demikian disampaikan, agar para siswa segera melakukan konfirmasi pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. A.n. Ketua Umum Ketua PPDB SMA Pradita Dirgantara Ny. Sondang Khairil Lubis Lampiran Pengumuman Daftar Nama Peserta Lolos Seleksi Tahap 1 NO KODE DAFTAR NAMA JK ASAL PANDA 1 2 3 4 5 1 PRAK-83JQEKIC Az Zahra Leilany Widjanarka P Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang 2 PRAK-8TM1YQGC Glenn Emmanuel Abraham L Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang 3 PRAK-202101-0879 Kayana Nur Ramadhania P Lanud Abdul -

Peraturan Badan Informasi Geospasial
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan satuan harga lain selain standar biaya masukan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Badan Informasi Geospasial diberikan kewenangan untuk menetapkan satuan harga; - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang -

Negeri Sembilan: Rantau Minangkabau Di Semenanjung Tanah Melayu
HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, IX, 2 (Desember 2008) NEGERI SEMBILAN: RANTAU MINANGKABAU DI SEMENANJUNG TANAH MELAYU Rahilah Omar dan Nelmawarni ABSTRACT For a long time, the people of Minangkabaus have had strong inclination to leave their original village in search of new settlement besides seeking wealth. In the Minangkabau culture, this practice of leaving one’s home is known as merantau. This practice has caused a strong influence in terms of history, blood ties and cultural linkages especially between the Kingdom of Pagaruyung of Sumatra and Negeri Sembilan and in general the Minangkabaus. The existence of Negeri Sembilan began with the coming of the Minangkabaus perantau to the place. They explored the area and built settlements within these localities. Their roles as pioneer settlers and setting new localities are seen as one of the important aspects in the history of Negeri Sembilan. The Minangkabaus perantau did not only struggle to achieve a better living but had also successfully established a kingdom and instilled the Adat Pepatih as the cultural basis of Negeri Sembilan. Key words: the people of Minangkabaus, Minangkabau, the history of Negeri Sembilan. Rahilah Bt. Omar (Ph.D) adalah seorang Pensyarah di Jabatan Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lahir pada tanggal 8 Maret 1961. Memperoleh Bachelor of Arts in History, dari University Kebangsaan Malaysia (1992); Master of Arts in History, “The Regicide Of Sultan Mahmud III And The Claim Of Raja Kecik For The Throne Of Johore, 1718” – University Of Hull, England (1996); dan Ph.D. in History (South Sulawesi, Indonesia) dengan judul disertasi “The History Of Boné, A.D. -
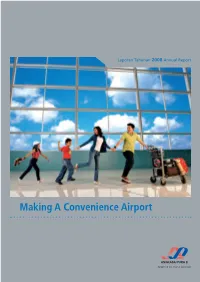
Making a Convenience Airport
Laporan Tahunan 2008 Annual Report Making A Convenience Airport Daftar Isi Table of Contents 2 Visi & Misi Vision & Mission 3 Strategi Perusahaan Company Strategy 4 Sekilas Perusahaan Company in Brief 5 Wilayah Kerja Working Area Introduction 7 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights 8 Peristiwa Penting 2008 2008 Important Events 10 Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners 18 Laporan Direksi Report from the Board of Directors 28 Jasa Aeronautika Aeronautical Services Our Services 32 Jasa Non-Aeronautika Non-Aeronautical Services 40 Pengembangan Usaha Business Development 44 Pengembangan Bandara Airport Development Operational Review 46 Sumber Daya Manusia Human Resources 54 Struktur Organisasi Organization Structure 56 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility 62 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Governance Report 92 Manajemen Risiko Risk Management 100 Diskusi & Analisis Manajemen Management Discussion & Analysis Management 113 Informasi Perusahaan Corporate Information Discussion & Analysis 114 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Responsibility for Financial Reporting 115 Laporan Keuangan Financial Statements Making A Convenience Airport Melalui upaya-upaya berkesinambungan dalam perluasan kapasitas serta peningkatan fasilitas di bandara-bandara yang dikelola, termasuk pencanangan program ‘Road to Clean Airport’ di 2008, Angkasa Pura II terus berfokus menampilkan citra bandara yang aman, nyaman dan efisien, dengan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta ekspektasi para pengguna jasa bandara. Through consistent and sustained efforts in capacity expansion and facility improvements in airports under its management, including through the launch of the ‘Road to Clean Airport’ program in 2008, Angkasa Pura II focuses on building an image of safe, comfortable and efficient airport, offering a level of service quality that can fulfill the needs and expectations of the various airport service users. -

Research Title
THE ROLE OF FEDERALISM IN MITIGATING ETHNIC CONFLICTS IN PLURAL SOCIETIES: NIGERIA AND MALAYSIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE CHUKWUNENYE CLIFFORD NJOKU DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AND STRATEGIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2015 THE ROLE OF FEDERALISM IN MITIGATING ETHNIC CONFLICTS IN PLURAL SOCIETIES: NIGERIA AND MALAYSIA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE CHUKWUNENYE CLIFFORD NJOKU AHA080051 THESIS SUBMITTED IN FULFULMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AND STRATEGIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2015 UNIVERSITY OF MALAYA ORIGINIAL LITERARY WORD DECLARATION Name of Candidate: Chukwunenye Clifford Njoku (I/C/Passport No. A06333058) Registration/Matric No: AHA080051 Name of Degree: Doctor of Philosophy Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis (“this Work”): The Role of Federalism in Mitigating Ethnic Conflicts in Plural Societies: Nigeria and Malaysia in Comparative Perspective Field of Study: International Relations I do solemnly and sincerely declare that: (1) I am the sole author/writer of this Work; (2) This Work is original; (3) Any use of work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any except or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and the title of the work and its authorship have been acknowledged in this -

Revisi Pantas Sejarah Tingkatan 3 © Chekgu Anas 1
BAB 1: KEDATANGAN KUASA BARAT • Bahasa melayu dan tulisan jawi Tidak Formal 1.1 KESTABILAN DAN KEMAKMURAN NEGARA • Kemahiran bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang 1. Apakah maksud kestabilan? • Ilmu agama, pekerti mulia • Pantun, syair, peribahasa berbentuk ✓ Sistem Pemerintahan tauladan • Sistem Pemerintahan Beraja • Matlamat; membolehkan berdikari • Hierarki Pemerintahan Negeri Sembilan • Amalan dan kepercayaan turun temurun • Sistem Pemerintahan Sarawak • Sistem Pemerintahan Sabah 1.2 FAKTOR KEDATANGAN KUASA BARAT ✓ Perundangan • Undang undang bertulis 3. Apakah faktor kedatangan kuasa barat abad • Contoh: Hukum Kanun Melaka ke 16? • Undang tidak bertulis ✓ Barangan Mewah • Contoh: Adat Perpatih • Rempah ratus, minyak wangi, emas, perak ✓ Hubungan luar • Dari China seperti teh, sutera, tembikar • Dengan negara luar ✓ Pusat Pengumpulan Barang • Politik, ekonomi, sosial • China mahukan emas, perak, bijih timah • Memanfaatkan hubungan dengan yang boleh dijumpai di Kepulauan Melayu pedagang ✓ Pelabuhan Persinggahan • Kebijaksanaan pemerintah • Angin monsun • Berlindung sementara perubahan angin 2. Apakah maksud kemakmuran? • Mengisi bekalan makanan, baiki kapal ✓ Hasil Bumi, Hasil Alam 4. Apakah faktor kedatangan abad ke-17-20? • Bijih timah, emas, perak • Hasil hutan; rempah ratus, damar, rotan ✓ Revolusi Perindustrian • Hasil hutan; kayu kayan, gaharu, cendana. • Abad 17,18- Membolehkan barangan • Hasil laut; sirip ikan yu, timun laut dikeluarkan secara besaran. Mencari ✓ Memanfaatkan Hasil Alam pusat untuk bekalkan bahan mentah -

N Nama Nip Baru Nip Lama Nupt Tempat Lahir Tgl Lahir Usia
REKAP PNS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN N NAMA NIP BARU NIP LAMA NUPT TEMPAT LAHIR TGL LAHIR USIA JK AGAMA STATUS PERNIKAHAN ALAMAT KTP ALAMAT KAB/KOTA ALAMAT PROVINSI SUMBER GAJI WILAYAH PEMBAYARAN STATUS PNS/CPNS STATUS HUKUM PEGAWAI JENIS KEPEGAWAIAN GOL. RUANG TMT PANGKAT MS PANGKAT JENJANG NAMA SEKOLAH PRODI THN JENIS JABATAN ESELON NAMA JABATAN TMT JABATAN STATUS JABATAN DIKLAT TMT PENSIUN UNIT KERJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - JL. PUNCAK INDAH NOMOR 4, RT 004 19721005 201001 1 47 Tahun 10 Bulan 20 PNS Daerah Propinsi yang bekerja 10 Tahun 7 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN Jabatan CABANG DINAS KELAUTAN DAN 1 Ir TRI SETIAWAN.HS, M.SI YOGJAKARTA ######### L Islam Menikah RW 008, Kel/Desa KEMBOJA, Kec. Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau APBD Provinsi KPPN Tanjung Pinang PNS Aktif III/c - Penata 01/04/2017 S-2 UNIVERSITAS ANDALAS 2005 IV.a - PENGAWAS KEPALA SEKSI 16/03/2018 Promosi Diklat Prajabatan Golongan III 01/11/2030 SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI 007 Hari pada Propinsi Bulan PEDESAAN Struktural PERIKANAN ANAMBAS - SEKSI Tanjungpinang Barat PENGAWASAN DAN KONSERVASI Jl.Kampung Suka Jaya No.31, RT 001 19770715 200803 1 43 Tahun 1 Bulan 10 PNS Daerah Propinsi yang bekerja 12 Tahun 5 Jabatan Pengawas Perikanan Keahlian Ahli DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 2 ABDUL RACHIM, S.Pi P20005955 Yogyakarta ######### L Islam Menikah RW 008, Kel/Desa Melayu Kota Piring, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau APBD Provinsi KPPN Batam PNS Aktif III/c - Penata 01/04/2016 S-1 UNIVERSITAS GADJAH MADA BUDIDAYA PERIKANAN 2005 28/12/2018 Sudah Diangkat Imphasing / Tanpa Diklat 01/08/2035 BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 001 Hari pada Propinsi Bulan Fungsional Muda (III/c) BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Kec. -

Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan
P-ISSN: 2339-0921 E-ISSN: 2580-5762 Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Pengaruh Bugis di Tanah Melayu dalam Perspektif Sejarah Sosial Politik Saepuddin Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur Corry Van Stenus, Perempuan dalam Perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar (1950-1965) Nurul Azizah Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika Herman Wicaksono Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme di Indonesia Soraya Rasyid, Annisa Tamara Bergerak dengan Dua Sayap: Fenomena Gerakan Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Reformasi Aksa Volume 8 Nomor 1 Januari-Juni 2020 P-ISSN 2339-0921 E-ISSN 2580-5762 RIHLAH Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Editor in Chief : Dr. Rahmat, M.Pd. Managing Editor : Mastanning, S.Hum, M.Hum. Editorial Board : Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum. : Nurhidayat, S.Hum, M.Hum. Desain Grafis : Nur Arifin, S.IP. Secretariat : Safaruddin, S.Hum. Reviewers : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Rahmawati, MA. : Dr. Nurhayati Syairuddin, M.Hum Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. -

Antropologi Melayu.Pdf
Pendahuluan 1 Antropologi Melayu ANTROPOLOGI MELAYU Penulis: Husni Thamrin Editor: Madona Khairunisa Desain sampul dan Tata letak: Yofie AF ISBN: 978-602-6827-87-6 Penerbit: KALIMEDIA Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta e-Mail: [email protected] Telp. 082 220 149 510 Bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau Cetakan, I 2018 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit 2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR PROF EMERITUS DATUK WIRA DR. MOHD. YUSUF HASHIM BIN HJ HASHIM (PRO CANSELOR KELEJ UNIVERSITI MELAKA) Buku yang berjudul Antropologi Melayu berakar sangat kuat terhadap nilai nilai ajaran Islam, yang berbeda dengan Buku buku Antropologi biasanya yang sangat kental pengaruh nilai nilai Barat dan animis. Konsepsi Antropologi Melayu ini, berasaskan bahwa kebudayaan melayu berlandaskankepada ajaran dan nilai nilai Islam. Hal tersebut telah banyak dibahas dalam kitab-kitab Jawi tentang kebuadayaan Melayu mempu- yai hubungan yang sismbiosis dengan Islam. Dalam konteks sistem politik orang Melayu Hubungan sitem kekuasaan bahkan dinyatakan sebagai hubungan sim- biotik belaka, hubungan timbal balik yang saling mempenga- ruhi. Sistem kekuasaan membangun solidaritas sosial dengan rakyatnya jika ingin kekuasaannya berlangsung baik dan langgeng. Dalam kitab Sulalat al-Salatin (1979), misalnya, Sultan Manshur Shah dari Malaka yang memberikan nasihat kepada putranya, Raja Ahmad, tentang hubungan simbiotik ini. Demikian pula dalam kitab Taj al-Salatin (1966) tercantum tentang kultur Melayu berkaitan syarat-syarat menjadi raja yang mencakup persyaratan jasmaniah dan ruhaniah, seperti laki-laki yang sudah akil balig, tampan, gagah, berani, ber- pengetahuan luas, pemurah, dan mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji. -

Sejarah Kejuangan Dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Hohor-Pahang (1761—1812)
SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAHLAWANAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH YANG DIPERTUAN BESAR KERAJAAN RIAU-LINGGA-HOHOR-PAHANG (1761—1812) PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN PEMERINRAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2012 SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAHLAWANAN SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH YANG DIPERTUAN BESAR KERAJAAN RIAU-LINGGA-JOHOR-PAHANG (1761—1812) 1 Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelaggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2 SEJARAH KEJUANGAN DAN KEPAHLAWANAN SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH YANG DIPERTUAN BESAR KERAJAAN RIAU-LINGGA-JOHOR-PAHANG (1761—1812) Tim Penulis dan Penyelaras Ketua: Drs. Haji Abdul Malik, M.Pd. Wakil Ketua: Drs. Haji Abdul Kadir Ibrahim, M.T. Anggota: Haji Rida K Liamsi Dr. Haji Azam Awang, M.Si. Drs. Al Azhar, M.Si. Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A. Drs. Suarman Raja Malik Hafrizal Tengku Moh. Fuad PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAIK-LINGGA 2012 3 Tim Perumus dan Penyusun: Keputusan Bupati Lingga, Nomor: 179/ KPTS/ 2012, 4 Mei 2012 Pelindung: H. Daria (Bupati Lingga) Penasehat: Drs. Abu Hasyim (Wakil Bupati Lingga) Drs. -

DISHUB LAKIP 2019.Pdf
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................... DAFTAR ISI..................................................................... DAFTAR TABEL ………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….. 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………… 1 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan …………… 2 1.3. Struktur Organisasi ……………………………………………….. 3 1.4. Isu Strategis ………………………………………………………….. 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................. 6 2.1. Indikator Kinerja Utama …………………………………………… 6 2.2. Rencana Strategis …………………………………………………….. 7 2.3. Perjanjian Kinerja …………………………………………………….. 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................ 9 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................ 9 3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 .............................................................. 9 3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019 ................................................................. 10 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah …………………….. 11 3.1.4. Analisa Pencapaian Kinerja …………………………… 12 3.2. Realisasi Anggaran ……………………………………………………….. 33 BAB IV PENUTUP …………………………………………………… 35 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama ....................................................... 6 Tabel 2.2. Rencana Strategis .................................................................. 7 Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja ................................................................