Film Sebagai Gejala Komunikasi Massa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kajian Naratif Atas Tema Nasionalisme Dalam Film-Film Usmar Ismail Era 1950-An
KAJIAN NARATIF ATAS TEMA NASIONALISME DALAM FILM-FILM USMAR ISMAIL ERA 1950-AN TESIS PENGKAJIAN SENI untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat magister dalam bidang Seni, Minat Utama Videografi Sazkia Noor Anggraini 1320789412 PROGRAM PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2017 UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi manapun. Tesis ini merupakan hasil pengkajian/penelitian yang didukung berbagai referensi dan sepengetahuan saya belum pernah ditulis dan dipublikasikan kecuali yang secara tertulis diacu dan disebutkan dalam kepustakaan. Saya bertanggungjawab atas keaslian tesis ini dan saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini. Yogyakarta, 10 Agustus 2017 Yang membuat pernyataan, Sazkia Noor Anggraini NIM. 1320789412 iii UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA KAJIAN NARATIF ATAS TEMA NASIONALISME DALAM FILM-FILM USMAR ISMAIL ERA 1950-AN Pertanggungjawaban Tertulis Program Penciptaan dan Pengkajian Seni Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2017 Oleh Sazkia Noor Anggraini ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari klaim bahwa film-film sebelum Darah dan Doa (1950) tidak didasari oleh sebuah kesadaran nasional dan oleh karenanya tidak bisa disebut sebagai film Indonesia. Klaim ini perlu dipertanyakan karena punya tendensi akan pengertian sempit etno nasionalis yang keluar dari elite budaya Indonesia. Penelitian ini mencoba membangun argumen secara kritis dengan memeriksa kembali proyeksi tema nasionalisme dalam naratif film-film Usmar Ismail pada era 1950-an. Gagasan nasionalisme kebangsaan oleh Benedict Anderson digunakan sebagai konsep kerja utama dalam membedah naratif pada film Darah dan Doa, Lewat Djam Malam (1954), dan Tamu Agung (1955). -

Sang Kyai” (Sebuah Analisis Semiotika Roland Barthes)
NILAI PERJUANGAN KEMERDEKAAN DALAM FILM “SANG KYAI” (SEBUAH ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Komunikasi Islam Disusun Oleh : Wawan Supriyanto NIM. 07210028 Dosen Pembimbing : Mohammad Zamroni, S.Sos.I.,M.Si. NIP. 19780717 200901 1 012 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014 i MOTTO “PERJUANGAN HENTI TATKALA IMAN TERGERUS KEDANGKALAN BERFIKIR, BIJAKLAH BERPERANGAI SEBAGAI WUJUD ABDI TUHAN DI MUKA BUMI” - KH. Hasyim Asy’ari (Dinukil dari Film “Sang Kiai”) - v HALAMAN DARMABAKTI Kudarmabaktikankan Karya Sederhana ini kepada Almamater Tercinta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta vi KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala sesuatu kepada para makhluk sesuai kadarnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Salallahu‘alaihi wasallam. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Diantaranya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Musa Asy’ari selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 3. Ibu Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 4. Bapak Saptoni, S.Ag., MA., sebagai Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih untuk tidak bosan-bosannya menanyakan kapan skripsi penulis selesai. 5. -

Revisiting Transnational Media Flow in Nusantara: Cross-Border Content Broadcasting in Indonesia and Malaysia
Southeast Asian Studies, Vol. 49, No. 2, September 2011 Revisiting Transnational Media Flow in Nusantara: Cross-border Content Broadcasting in Indonesia and Malaysia Nuurrianti Jalli* and Yearry Panji Setianto** Previous studies on transnational media have emphasized transnational media organizations and tended to ignore the role of cross-border content, especially in a non-Western context. This study aims to fill theoretical gaps within this scholarship by providing an analysis of the Southeast Asian media sphere, focusing on Indonesia and Malaysia in a historical context—transnational media flow before 2010. The two neighboring nations of Indonesia and Malaysia have many things in common, from culture to language and religion. This study not only explores similarities in the reception and appropriation of transnational content in both countries but also investigates why, to some extent, each had a different attitude toward content pro- duced by the other. It also looks at how governments in these two nations control the flow of transnational media content. Focusing on broadcast media, the study finds that cross-border media flow between Indonesia and Malaysia was made pos- sible primarily in two ways: (1) illicit or unintended media exchange, and (2) legal and intended media exchange. Illicit media exchange was enabled through the use of satellite dishes and antennae near state borders, as well as piracy. Legal and intended media exchange was enabled through state collaboration and the purchase of media rights; both governments also utilized several bodies of laws to assist in controlling transnational media content. Based on our analysis, there is a path of transnational media exchange between these two countries. -

( STUDI ANALISIS SEMIOTIKA JOHN FISKE) Oleh
REPRESENTASI POLIGAMI DALAM FILM ATHIRAH ( STUDI ANALISIS SEMIOTIKA JOHN FISKE) Oleh: Erik Pandapotan Simanullang [email protected] Pembimbing: Chelsy Yesicha, S.Sos, M.I.Kom Jurusan Ilmu Komunikasi – Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12, 5 Simpang Baru Pekanbaru Telp/Fax. 0761-63277 Abstract Athirah movie is a film that lifts the reality of polygamous life, polygamy is an issue that is still a debate in the community. This is quite interesting because polygamy is still something that causes pros and cons in Indonesian society. Different from previous polygamy- themed films, this film is a true story of a wife's struggle as well as the mother of Vice President Indonesia, Jusuf Kalla. In theory, many women have expressed disagreement on polygamous marriages, but in practice women are always in a cornered position, have no choice and are difficult to bid or even have no ability to reject men's desire for polygamy. Starting from this, some Indonesian filmmakers view the interesting polygamy phenomenon to be lifted into a film masterpiece. This study aims to determine the impact of polygamy for wives and children represented in Athirah films viewed from the level of reality, level of representation and ideology level. This study used qualitative methods analyzed by semiotic analysis of John Fiske. Subjects and objects in this study is the observation of the audio and visual display in the scenes of the film Athirah with data collection techniques used are observation, documentation, and literature study. The results of this study show there is a polygamy representation in the Athirah film. -

Identity, Minority, and the Idea of a Nation: a Closer Look at Frieda (1951) by Dr
Vol. 1 Journal of Korean and Asian Arts SPRING 2020 Identity, Minority, and the Idea of a Nation: a Closer Look at Frieda (1951) by Dr. Huyung Umi Lestari / Universitas Multimedia Nusantara 【Abstract】 The discourse on film nasional (national film) in Indonesia always started by bringing up Darah dan Doa (1950, Blood and Prayer) as the foundation of the Indonesian film industry. The prominent film historian, Misbach Yusa Biran, stated that Darah dan Doa was produced with national consciousness value. The legacy of Darah dan Doa was not only neglecting the role of filmmakers from pre-Independence in Indonesia but also the role of other filmmakers during the 1950s, including Dr. Huyung. Previously, Dr. Huyung (Hinatsu Eitaro /Hŏ Yŏng) came from Korea and became a supporter of Imperial Japan during World War II. After Indonesia gained her independence, Huyung joined Berita Film Indonesia and became a film teacher at the Cine Drama Institute and Kino Drama Atelier. It was there that they then went on to make Frieda (1951), Bunga Rumah Makan (1951, The Flower of the Restaurant), Kenangan Masa (1951, Memories of the Past), and Gadis Olahraga (1951, the Sportswoman). This article discusses 'unity in diversity', a concept in filmmaking that was started by Huyung in 1949. When discussing Darah and Doa as the first film nasional, people forget that the film is driven from the military perspective. Meanwhile, Huyung tried to represent an ethnic minority in Frieda and showing that the ordinary people and the intellectuals also shaped the nation. Based on his experience in the Japanese army and Berita Film Indonesia, Huyung understood that film was very useful in achieving the goals of the state apparatus, due to the cinema's ability to spread nationalism. -

Q&A PROGRAM KINEFORUM MARET 2011 SEJARAH ADALAH SEKARANG 5 Page 1
Q&A PROGRAM KINEFORUM MARET 2011 SEJARAH ADALAH SEKARANG 5 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 1 2 3 4 5 6 WARNA WARNI BUKAN SEKEDAR BOW: USMAR ISMAIL FESTIVAL 80-AN FILM ANAK INDONESIA FILM ANAK INDONESIA PEREMPUAN PROFESI BOW: USMAR ISMAIL GAMBAR TANGAN, LAYAR GAMBAR TANGAN, LAYAR TEREKAM, TERDENGAR, TEREKAM, TERDENGAR, PERAN PEMERAN LEBAR LEBAR TERLIHAT TERLIHAT FESTIVAL 80-AN WARNA WARNI PERAN PEMERAN GAMBAR TANGAN, LAYAR PEREMPUAN LEBAR kineforum 14.15: Perempuan Kedua 14.15: Raja Jin Penjaga 14.15: Red Cobex 14.15: Ira Maya Putri 14.15: Langitku, Rumahku 14.15: Djenderal Kantjil Pintu Kereta Api Cinderella 17.00: Darah dan Doa 17.00: Badut-badut Kota 17.00: Enam Djam di 17.00: Metamorfoblus 17.00: The Songstress and 17.00: Petualangan Sherina Djogdja the Seagull 19.30: Nakalnya Anak-anak 19.30: Sorga yang Hilang 19.30: Beranak Dalam 19.30: Kejarlah Daku, Kau 19.30: Tuan Tanah 19.30: Fiksi Kubur Kutangkap Kedawung 16:00 Diskusi Dari Gambar Acara Pendukung Tangan ke Layar Lebar GC III Pameran Sejarah Bioskop Pameran Sejarah Bioskop Pameran Sejarah Bioskop Pameran Sejarah Bioskop Pameran Sejarah Bioskop Pameran Sejarah Bioskop dan Kebijakan Film di dan Kebijakan Film di dan Kebijakan Film di dan Kebijakan Film di dan Kebijakan Film di dan Kebijakan Film di Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 7 8 9 10 11 12 13 FESTIVAL 80-AN SUPERHERO BUKAN SEKEDAR TEREKAM, TERDENGAR, SUPERHERO FILM ANAK INDONESIA FILM ANAK INDONESIA PROFESI TERLIHAT WARNA WARNI WARNA WARNI GAMBAR TANGAN, LAYAR BOW: USMAR ISMAIL BUKAN -

The Cultural Traffic of Classic Indonesian Exploitation Cinema
The Cultural Traffic of Classic Indonesian Exploitation Cinema Ekky Imanjaya Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia School of Art, Media and American Studies December 2016 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or extract must include full attribution. 1 Abstract Classic Indonesian exploitation films (originally produced, distributed, and exhibited in the New Order’s Indonesia from 1979 to 1995) are commonly negligible in both national and transnational cinema contexts, in the discourses of film criticism, journalism, and studies. Nonetheless, in the 2000s, there has been a global interest in re-circulating and consuming this kind of films. The films are internationally considered as “cult movies” and celebrated by global fans. This thesis will focus on the cultural traffic of the films, from late 1970s to early 2010s, from Indonesia to other countries. By analyzing the global flows of the films I will argue that despite the marginal status of the films, classic Indonesian exploitation films become the center of a taste battle among a variety of interest groups and agencies. The process will include challenging the official history of Indonesian cinema by investigating the framework of cultural traffic as well as politics of taste, and highlighting the significance of exploitation and B-films, paving the way into some findings that recommend accommodating the movies in serious discourses on cinema, nationally and globally. -

Ideologi Film Garin Nugroho
Ideologi Film Garin Nugroho Ahmad Toni Prodi S3 Pascasarjana Fikom Universitas Padjajaran Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinangor 45363 Fikom Universitas Budi Luhur Jalan Raya Ciledug Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12260 ABSTRACT This study is based on qualitative research with critical discourse analysis approach. The study presents the text of the fi lm as micro level of semiotic analysis. The purpose of the study is to uncover the ideology of Garin Nugroho fi lms which apply high aesthetic and anthropology construction of an exotic Indonesian culture. The result shows that the ideology resistance manifested in the fi lm of “Daun di Atas Bantal” is the philosophy reconstruction of art democratization as the power to sup- press the regime of Suharto and the new order. “Opera jawa” fi lm is the reconstruction of gender philosophy and Java femininity as well as the philosophy of the nature cosmology in the perspective of moderate Hindu Islam in presenting the greediness of human in the system of the nature ecology. The fi lm of ‘Mata tertutup’ is the philosophy reconstruction of moderate Islam to counter the power of radicalism and terrorism as the concept developed and related to the tenacity of nationalism system of the young generation in Indonesia. “Soegija” fi lm is the reconstruction of Christology philosophy and the values of minority leadership in the nationhood and statehood. The fi lm of “Tjokroaminoto Guru Bangsa” is the reconstruction of Islam philosophy to view the humanism values in the estab- lishment of the foundation of the nation as a moderate view. -

Bahasa Indonesia • Kelas XII SM A/M A/SMK/M AK
EDISI REVISI 2018 Bahasa Indonesia Buku ini dipersiapkan untuk mendukung kebijakan Kurikulum 2013 yang tidak sekadar secara AK konstitusional mempertahankan bahasa Indonesia dalam daftar mata pelajaran di sekolah. M Bahasa Namun, kurikulum terbaru ini mempertegaskan pentingnya keberadaan bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan. Berdasarkan Kurikulum 2013, buku siswa A/SMK/ kelas XII ini memuat enam pelajaran yang berisi materi pembelajaran teks cerita sejarah, berita, M iklan, opini/editorial, cerita ksi, dan teks dalam genre makro. Pada awal setiap pelajaran, siswa A/ M Indonesia diajak untuk membangun konteks sesuai dengan tema pelajaran. Setiap tema dibahas lebih lanjut dalam tiga kegiatan, yakni (1) pemodelan teks, (2) kerja bersama membangun teks, dan (3) kerja mandiri membangun teks. Kegiatan pembelajaran teks itu masing-masing dikembangkan dalam bentuk tugas-tugas yang beragam untuk menciptakan kegemaran belajar. Untuk itu, Kelas XII S pelaksanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk kegiatan proyek yang mencakupi penyusu- • nan proposal kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pelaporan (lisan dan/atau tulis). Melalui buku ini, diharapkan siswa mampu dan berpengalaman memproduksi serta menggunakan teks sesuai ndonesia dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Dalam pembelajaran bahasa yang berbasis teks, bahasa I Indonesia diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri dan mengembangkan budaya akademik. Bahasa ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 HET Rp15.800 Rp16.500 Rp17,200 Rp18.500 Rp23,700 SMA/MA/ SMK/MAK ISBN: KELAS 978-602-427-098-8 (jilid lengkap) 978-602-427-101-5 (jilid 3) XII Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. -

Download Thesis
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Have Decentralisation and Democratisation been Effective in Promoting an Inclusive Social Protection System in Indonesia? A Comparative Case Study of the Implementation of Social Protection Programmes in Central Java Wardhana, Dharendra Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate -

Transformasi Perjuangan Perempuan Dalam Ekranisasi Novel Athirah Karya Alberthiene Endah Ke Film Athirah Karya Riri Riza: Kajian Ekranisasi
TRANSFORMASI PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM EKRANISASI NOVEL ATHIRAH KARYA ALBERTHIENE ENDAH KE FILM ATHIRAH KARYA RIRI RIZA: KAJIAN EKRANISASI SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Indonesia oleh Etik Tarina 2111414021 JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2019 iii iv MOTO DAN PERSEMBAHAN Allah tidak akan memberikan keindahan yang sempurna tanpa didahului perjalanan terjal (Athirah) Persembahan: Skripsi ini saya persembahkan untuk: 1. Keluarga tercinta (Bapak, Mama, Arifin) 2. Almamater saya, Universitas Negeri Semarang v SARI Tarina, Etik. 2019. “Transformasi Perjuangan Perempuan dalam Ekranisasi Novel Athirah Karya Alberthiene Endah ke Film Athirah Karya Riri Riza: Kajian Ekranisasi”. Skripsi. Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Suseno, S.Pd., M.A. Kata Kunci: perjuangan perempuan, ekranisasi, feminis, novel, film Dalam perkembangan kesenian juga sangat lumrah satu jenis kesenian mengambil kesenian lain sebagai sumbernya atau dikenal dengan istilah transformasi. Pada proses transformasi, media yang digunakan berbeda, sehingga akan menimbulkan perubahan. Pengubahan dari novel ke film atau bias disebut ekanisasi diharapkan mampu memberikan kesan dan pesan yang positif kepada penikmatnya. Fenomena ekranisasi tentu tidak lepas dari keterkenalan awal suatu karya. novel yang sukses tidak jarang menjadi pijakan awal bagi lahirnya film yang sukses juga. Hal itu sering menjadi acuan lahirnya kesuksesan baru suatu bentuk pengalihan, -
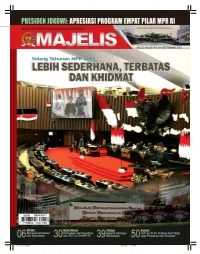
1630986333 File Mpr.Pdf
EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021 1 01-07 SEP.pmd 1 9/5/2021, 2:32 PM 2 EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021 01-07 SEP.pmd 2 9/5/2021, 2:32 PM Daftar Isi EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021 39 SELINGAN 76 Profil Sejarah Olahraga Bulutangkis Saadiah Uluputty Pengantar Redaksi ...................................................... 04 08 BERITA UTAMA Perspektif .......................................................................... 06 Sidang Tahunan MPR RI 2021 Diskusi Majelis ............................................................... 28 Digelar secara hybrid, yaitu daring dan luring, Sidang Tahunan MPR 2021 lebih sederhana dan terbatas, baik dari jumlah mereka yang Aspirasi Masyarakat ..................................................... 47 hadir secara fisik maupun dari aspek waktu, tapi tanpa mengurangi khidmat sidang paripurna MPR. Gema Pancasila ............................................................ 48 Kolom ................................................................................ 54 Varia MPR ....................................................................... 68 Wawancara ..................................................... 70 Figur .................................................................................... 72 Ragam ................................................................................ 74 Dari Rumah Kebangsaan ............................................. 78 Rehal ................................................................................ 82 30 Majelis Khusus Peringatan Hari Konstitusi dan