42 Bab Iii Penggabungan Laskar Putri Indonesia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960S
ROBERT M. CORNEJO When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960s ROBERT M. CORNEJO1 Robert M. Cornejo is a major in the US Army and a graduate of the United States Military Academy, West Point, New York. He recently earned an M.A. in National Security Affairs from the Naval Postgraduate School, Monterey, California, and is currently a student at the Singapore Command and Staff College. lthough Indonesia’s aspirations have been Sukarno’s successor, General Suharto, agreed to inter- largely forgotten today, in the mid-1960s, it national safeguards, thereby effectively ending concerns Asought to acquire and test nuclear weapons. In- that Indonesia might go nuclear. donesian government officials began publicizing their The purpose of this article is to tell the story of intent to acquire an atom bomb shortly after the People’s Indonesia’s nuclear aspirations, study Sukarno’s deci- Republic of China (PRC) exploded its first nuclear de- sion to support nuclear weapons, and identify variables vice in October 1964. By July 1965, Indonesian Presi- that may explain why he professed to seek the bomb. dent Sukarno was publicly vaunting his country’s future The article opens by tracing the evolution of Indonesia’s nuclear status. However, Indonesia did not have the in- nuclear aspirations, from a US Atoms for Peace pro- digenous capability necessary to produce its own nuclear gram of nuclear assistance that began in 1960, to weapon, and as a result, it would have had to secure Sukarno’s declared intention to acquire an atom bomb assistance from an established nuclear weapon state to in 1965. -

Masyumi Dalam Kontestasi Politik Orde Lama 159
Abdul Rahman / Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama 159 MASYUMI DALAM KONTESTASI POLITIK ORDE LAMA Abdul Rahman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Jl. A.P Pettarani, Kampus Gunungsari Timur, Makassar Email: [email protected] Abstrak - Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongancendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947. Kata Kunci: Masyumi, Politik, Orde -

Studia Islamika
Volume 24, Number 2, 2017 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢، ٢٠١٧ T R K S S O S S: E L, E G Achmad Ubaedillah ‘R’ N -S: A B B D Mehmet Özay E I S L C S T C اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻳﺦ Raihani واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻲ Priangan: P E C D ( I I U P (PSII اﻻﺗﺤﺎد اﻷﺧﻀﺮ ١٩٤٢-١٩٢٠ ﻧﻤﻮذﺟﺎ Valina Singka Subekti ﳏﻤﺪ ﺇﺳﻜﻨﺪﺭ E-ISSN: 2355-6145 STUDIA ISLAMIKA STUDIA ISLAMIKA Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 24, no. 2, 2017 EDITOR-IN-CHIEF Azyumardi Azra MANAGING EDITOR Oman Fathurahman EDITORS Saiful Mujani Jamhari Didin Syafruddin Jajat Burhanudin Fuad Jabali Ali Munhanif Saiful Umam Ismatu Ropi Dadi Darmadi Jajang Jahroni Din Wahid INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD M. Quraish Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA) Tauk Abdullah (Indonesian Institute of Sciences (LIPI), INDONESIA) M.C. Ricklefs (Australian National University, AUSTRALIA) Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS) John R. Bowen (Washington University, USA) M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA) Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA) Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY) Robert W. Hefner (Boston University, USA) Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientique (CNRS), FRANCE) R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE) Michael F. Laffan (Princeton University, USA) ASSISTANT TO THE EDITORS Testriono Muhammad Nida' Fadlan Endi Aulia Garadian ENGLISH LANGUAGE ADVISOR Dick van der Meij Daniel Peterson ARABIC LANGUAGE ADVISOR Tb. Ade Asnawi COVER DESIGNER S. Prinka STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. -

Indo 13 0 1107127212 183
DIVISIONS AND POWER IN THE INDONESIAN NATIONAL PARTY, 1965-1966* Angus McIntyre The principal division which split the PNI into two sharply opposed factions in 1965-1966 had its origins as far back as 1957, when the PKI made spectacular advances in large part at PNI expense in the 1957 regional elections in Java and South Sumatra. In Central Java, where the PKI supplanted the PNI as the region's strongest party (based on the 1955 general elections results) , the PNI reaction at the time was most outspoken. Hadisubeno, the regional party chairman, blamed the party's poor showing on its past association with the PKI1 and accordingly urged the party's central executive council to re view this relationship. He suggested that the party consider forming an alliance with the Masjumi (the modernist Islamic party) and the Nahdatul Ulama (NU, the traditional Islamic party).2 A conference of the Central Java PNI passed a resolution forbidding cooperation with the PKI.3 These acts were interpreted by many as a slap at President Sukarno,** who had made it increasingly clear in the preceding months that to oppose the PKI was to oppose him as well; however, the party's central leadership, no less hostile to the PKI, was unwilling to risk such an interpretation and thereby further impair its relations with Sukarno. Indeed, only a few months before, Sukarno had indicated strong displeasure with the PNI in his address to the party on the occasion of its thirtieth anniversary celebrations. He implied that PNI members had lost their commitment to the goal of a socialist or marhaenist5 society, the realization of which had been his very reason * The writer would like to express his gratitude to the Jajasan Siswa Lokantara Indonesia for providing him with the opportunity to con- duct research in Indonesia in 1966 and 1967 and to the Myer Founda tion for giving him financial assistance in 1967. -

Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa
NASKAH AKHIR TENTANG 1. Pergerakan Kebangsaan dan Gejolak Politik Lokal; 2. Kehidupan Sosial Budaya; 3. Merebut dan Mempertahankan Kemer- dekaan; 4. Pembangunan Semasa Bupati Dr. H. Don Murdono, S. H., M. Si. Untuk buku Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa kerja sama Pusat Kebudayaan Sunda (PKS), Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran Dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Sumedang Untuk memenuhi persyaratan bagi pengajuan kenaikan Golongan/ Pangkat ke IIIc/Penata pada jabatan fungsional Lektor. BAGIAN KEDUA MASA KERAJAAN HINGGA BERDIRINYA KABUPATEN SUMEDANG 4. Pergerakan Kebangsaan dan Gejolak Politik Lokal Eksploitasi kolonial yang terjadi pada abad ke-19 di Nusantara telah menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong rakyat untuk melakukan pergerakan sosial. Dominasi ekonomi, politik, dan budaya yang berlangsung terus menerus telah menimbulkan disorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga- lembaganya. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi Barat yang memiliki kekuatan disinteragtif, masyarakat tradisional mempunyai cara-cara tersendiri. Cara-cara tersebut dilakukan mengingat di dalam sistem pemerintahan kolonial tidak terdapat lembaga untuk menyalurkan rasa tidak puas ataupun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, satu- satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gerakan sosial sebagai bentuk proses sosial.1 Gerakan sosial yang menjadi fenomena dari gejolak politik tingkat lokal sejak akhir abad ke-19 pun terjadi di Sumedang. Gerakan sosial di Sumedang yang perlu dikemukakan di sini adalah Gerakan Nyi Aciah yang terjadi pada tahun 1870-1871 dan dikategorikan sebagai sebuah gerakan keagamaan.2 Gerakan Nyi Aciah terjadi ketika Pangeran Aria Suria Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih menjabat sebagai Bupati Sumedang (1834-1882). Ditulis oleh Miftahul Falah, S. S. sebagai bagian dari buku Sumedang dari Masa ke Masa. -

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ١٦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ T M M R Psii: a C B K.H
Volume 20, Number 1, 2013 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ١، ٢٠١٣ B M I : ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ Karel Steenbrink ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻮﺳﻨﺘﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ١٦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ T M M R PSII: A C B K.H. A A ﺇﺋﲔ ﺳﻮﺭﻳﺎﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ Kevin W. Fogg ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ : A P H I W K ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ Faizal Amin ﺗﺎﲰﺎﻥ STUDIA ISLAMIKA STUDIA ISLAMIKA Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 20, no. 1, 2013 EDITORIAL BOARD: M. Quraish Shihab (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Tauk Abdullah (LIPI Jakarta) Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara) M.C. Ricklefs (Australian National University, Canberra) Martin van Bruinessen (Utrecht University) John R. Bowen (Washington University, St. Louis) M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur) Virginia M. Hooker (Australian National University, Canberra) EDITOR-IN-CHIEF Azyumardi Azra EDITORS Saiful Mujani Jamhari Jajat Burhanudin Oman Fathurahman Fuad Jabali Ali Munhanif Saiful Umam Ismatu Ropi Dina Afrianty ASSISTANT TO THE EDITORS Testriono Muhammad Nida' Fadlan ENGLISH LANGUAGE ADVISOR Melissa Crouch Simon Gladman ARABIC LANGUAGE ADVISOR Nursamad COVER DESIGNER S. Prinka STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/ STT/1976). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. is journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. -

Kata Pengantar
KATA PENGANTAR Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengolahan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Pada tahun anggaran 2016 ini, salah satu program kerja Sub Bidang Pengolahan Arsip Pengolahan I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun Guide Arsip Presiden RI: Sukarno 1945-1967. Guide arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis bertema Sukarno sebagai Presiden dengan kurun waktu 1945-1967 yang arsipnya tersimpan dan dapat diakses di ANRI. Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, maka guide arsip ini tentunya belum sempurna dan masih ada kekurangan. Namun demikian guide arsip ini sudah dapat digunakan sebagai finding aid untuk mengakses dan menemukan arsip statis mengenai Presiden Sukarno yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip (user). Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Museum Kepresidenan, Yayasan Bung Karno dan semua pihak yang telah membantu penyusunan guide arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. -
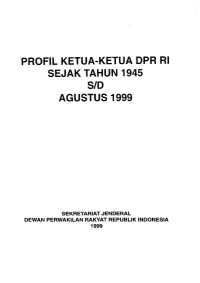
C:\Documents and Settings\Dd Cantik\Desktop\DPR Scan Anggit
PROFIL KETUA-KETUA DPR RI SEJAK TAHUN 1945 SID AGUSTUS 1999 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1999 KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Keterbatasan buku-buku me• ngenai Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah disadari, apalagi buku-buku yang dapat memberikan informasi mengenai mereka yang pernah duduk didalamnya. Padahal, buku semacam itu dapat bercerita banyak tentang . suatu zaman dan kita dapat menarik semangat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan melalui buku pula kita dapat memberikan penghargaan kepada mereka · yang memang pantas mendapatkannya. Oleh karena itu saya merasa gembira dengan hadirnya buku mengenai profil Ketua-ketua DPR dari periode 1945 sampai sekarang. Walaupun berupa sebuah buku kecil yang sederhana, namun setidaknya merupakan buku pertama oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang berusaha untuk mengkompilasikan informasi tentang sosok-sosok mereka 111 dari .berbagai sumber yang pernah mengetuai Lembaga Legislatif ini. Membaca buku ini, seperti mernutar film dalam benak, dengan kita sebagai sutradaranya dan petikan profil dalam buku kecil ini sebagai plotnya. B uku ini mencoba untuk jauh dari kesan menggurui ataupun mengkultuskan pribadi tertentu. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan buku ini dan saya berharap semoga di masa mendatang akan melimpah khasanah pustaka mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, tentunya yang bermutu dan dapat dipertanggung-j awabkan Wassalamu'alaikum Wr. Wb. SEKRETARIS JENDERAL. DPR RI, DRS. AFIF MA'R-OEF lV DAFTAR ISi Halaman I. Kata Pengantar Hl 2. MR. KASMAN SINGODIMEDJO I 3. SUTAN SYAHRIR 9 4. S U P E N O 19 5. MR. ASSAAT 25 6. MR. SARTO NO 33 7. K.H. ZAINUL ARIFIN 41 8. -

The Peta and My Relations with the Japanese: a Correction of Sukarno1s Autobiography*
THE PETA AND MY RELATIONS WITH THE JAPANESE: A CORRECTION OF SUKARNO1S AUTOBIOGRAPHY* Raden Gatot Mangkupradja I was lying in bed feeling the effects of the medicine re cently injected into my body by Dr. Sie Wie Boo. Suddenly there was the voice of a guest, and after knocking at the door Brother Rasiban came into my room. He took a seat near my bed, and after inquiring as to my health he said, holding up a volume, "Well, Pak Gatot, I !ve just received this book--Bung Karnofs autobiography— from my son Supena. Please read it, Pak Gatot, and see if what Mrs. Cindy Adams has written is correct. And . above all see if what Bung Karno has told her is true. Your name is often mentioned in the book." "Brother Rasiban," I said. "Ifve heard of this book before and of my name often being mentioned in it. But I ’ve never seen a copy, let alone read it. How could I possibly afford a book which costs two hundred and twenty-five rupiah?' Thank you for it anyway," I added, "I’ll read it." On that day, however, I did not feel at all like reading; only on the next did I begin. As usual, I skimmed through the book, skipping the pages which did not catch my attention, before I settled down to a more careful reading. From this superficial glance I was able to see that Bung Karno had not told the en tire truth. He had put forward as facts things he had only made up, and he had exaggerated in places. -

Dinamika Internal Kabinet Sjahrir Masa Revolusi Indonesia 1945-1947 Skripsi
UNIVERSITAS INDONESIA DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR MASA REVOLUSI INDONESIA 1945-1947 SKRIPSI Diajukan sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora Moch. Insan Pratama 0705040339 FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH KEKHUSUSAN SEJARAH INDONESIA DEPOK JANUARI 2010 Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010 SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi/tesis/disertasi* ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya. Jakarta, Moch. Insan Pratama *Pilih yang sesuai. ii Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010 HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Nama : Moch. Insan Pratama NPM : 0705040339 TandaTangan: Tanggal : iii Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010 iv Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010 KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah saya tujukan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya memberikan kesempatan kepada saya menjalani pendidikan terbaik di Universitas Indonesia. Selama empat tahun lebih, ilmu yang berguna dan pengalaman yang berharga saya dapatkan dalam lingkungan akademik yang -

19 PENDAHULUAN Partai Masyumi Merupakan Salah Satu Partai Politik
PASANG SURUT PERAN POLITIK MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN (1945-1960) Insan Fahmi Siregar -urusan SeMarah FIS - U11ES Abstract 0asyumi 3arty (Partai 0aMelis Syuro 0uslimin Indonesia) was a maMor Islamic political party in ,ndonesia. ,t was originally estaElished Ey the occupying -apanese in 1943 in an attempt to control ,slam in ,ndonesia. ,n 1952, 1ahdlatul 8lama seceded from 0asyumi and create the new party, Eased on traditional society. The party came second in the 1955 election with 20.9% of the popular vote. During the period of liberal democracy era, Masyumi members had seats in parliament and the party supplied prime ministers such as 0uhammad 1atsir and Burhanuddin Harahap. The group‘s leaders campaigned for an Islamic state in the 1950‘s not out of a real conviction, but mainly from fear of being outfianked by the larger and more aggressive 0asyumi. 8nder the dictatorships, the group withdrew from partisan politics, but with the restoration of democracy it formed a new party, 1ational Awakening, open to all religions and committed to a secular state. ,n 1958, some 0asyumi memEers Moined the 3RR, reEellion against SuNarno. Two years later in 1960, Sukarno banned 0asyumi and Socialist 3arty, and sent 0asyumi leaders to Mail. Key words: Masyumi Party, opposes, democracy, government PENDAHULUAN politik di Indonesia. Bahkan peran politik Masyumi sangat besar pengaruhnya terhadap Partai Masyumi merupakan salah satu perpolitikan Indonesia. Hal itu tidak terlalu partai politik yang lahir dari rahim proklamasi mengherankan karena Masyumi merupakan kemerdekaan Indonesia. Partai Masyumi salah satu partai besar di Indonesia. Selain didiriNan pada tanggal 7 1opemEer 1945 itu, Masyumi juga memiliki kader-kader melalui Muktamar Umat Islam di Gedung yang cukup cerdas dan ahli dalam bidangnya, Muallimin Yogyakarta. -

September 30Th Movement" and Its Epilogue
SELECTED DOCUMENTS RELATING TO THE "SEPTEMBER 30TH MOVEMENT" AND ITS EPILOGUE EDITORIAL NOTE: The editors wish to acknowledge from the outset that the collection of documents appended below is very far from providing a comprehensive coverage of the roles of the various important groups and individuals affected by, or involved in the events of October 1, 1965. But we are confident that this collection constitutes a reasonably representative sample of the positions taken publicly by the political elements most directly concerned. Priority has been given to material which has for one reason or another not yet been made readily accessible to students of Indonesian affairs. The chief criterion of selec tion has been, however, direct relevance to the actual events of October 1 and 2, in Djakarta and the regions most deeply affected. Each document is prefaced by a brief editorial com ment noting the time and place of issuance - where this is known. An attempt is also made - where necessary - to suggest the significance of some selections. INDEX OF DOCUMENTS I. STATEMENTS OF THE SEPTEMBER 30th MOVEMENT. 1. Initial Statement of Lieutenant Colonel Untung. 2. Decree No. 1 on the Establishment of the Indonesian Revolution Council. 3. Decision No. 1 Concerning the Composition of the Indonesian Revolution Council. 4. Decision No. 2 Concerning Demotion and Promotion in Rank. 5. Affiliations of Indonesian Revolution Council Members [compiled by the editors]. II. STATEMENTS OF THE INDONESIAN AIR FORCE. 1. Air Force Commander Dani's Order of the Day (October 1). 2. Air Force Commander Dani's Statement in Jogjakarta (October 2).