Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960S
ROBERT M. CORNEJO When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960s ROBERT M. CORNEJO1 Robert M. Cornejo is a major in the US Army and a graduate of the United States Military Academy, West Point, New York. He recently earned an M.A. in National Security Affairs from the Naval Postgraduate School, Monterey, California, and is currently a student at the Singapore Command and Staff College. lthough Indonesia’s aspirations have been Sukarno’s successor, General Suharto, agreed to inter- largely forgotten today, in the mid-1960s, it national safeguards, thereby effectively ending concerns Asought to acquire and test nuclear weapons. In- that Indonesia might go nuclear. donesian government officials began publicizing their The purpose of this article is to tell the story of intent to acquire an atom bomb shortly after the People’s Indonesia’s nuclear aspirations, study Sukarno’s deci- Republic of China (PRC) exploded its first nuclear de- sion to support nuclear weapons, and identify variables vice in October 1964. By July 1965, Indonesian Presi- that may explain why he professed to seek the bomb. dent Sukarno was publicly vaunting his country’s future The article opens by tracing the evolution of Indonesia’s nuclear status. However, Indonesia did not have the in- nuclear aspirations, from a US Atoms for Peace pro- digenous capability necessary to produce its own nuclear gram of nuclear assistance that began in 1960, to weapon, and as a result, it would have had to secure Sukarno’s declared intention to acquire an atom bomb assistance from an established nuclear weapon state to in 1965. -

Masyumi Dalam Kontestasi Politik Orde Lama 159
Abdul Rahman / Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama 159 MASYUMI DALAM KONTESTASI POLITIK ORDE LAMA Abdul Rahman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Jl. A.P Pettarani, Kampus Gunungsari Timur, Makassar Email: [email protected] Abstrak - Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongancendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947. Kata Kunci: Masyumi, Politik, Orde -
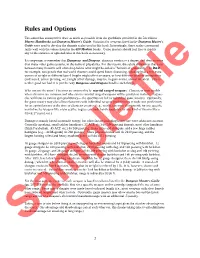
Rules and Options
Rules and Options The author has attempted to draw as much as possible from the guidelines provided in the 5th edition Players Handbooks and Dungeon Master's Guide. Statistics for weapons listed in the Dungeon Master's Guide were used to develop the damage scales used in this book. Interestingly, these scales correspond fairly well with the values listed in the d20 Modern books. Game masters should feel free to modify any of the statistics or optional rules in this book as necessary. It is important to remember that Dungeons and Dragons abstracts combat to a degree, and does so more than many other game systems, in the name of playability. For this reason, the subtle differences that exist between many firearms will often drop below what might be called a "horizon of granularity." In D&D, for example, two pistols that real world shooters could spend hours discussing, debating how a few extra ounces of weight or different barrel lengths might affect accuracy, or how different kinds of ammunition (soft-nosed, armor-piercing, etc.) might affect damage, may be, in game terms, almost identical. This is neither good nor bad; it is just the way Dungeons and Dragons handles such things. Who can use firearms? Firearms are assumed to be martial ranged weapons. Characters from worlds where firearms are common and who can use martial ranged weapons will be proficient in them. Anyone else will have to train to gain proficiency— the specifics are left to individual game masters. Optionally, the game master may also allow characters with individual weapon proficiencies to trade one proficiency for an equivalent one at the time of character creation (e.g., monks can trade shortswords for one specific martial melee weapon like a war scythe, rogues can trade hand crossbows for one kind of firearm like a Glock 17 pistol, etc.). -

Symbolism of the Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile
KUPAS SENI Jurnal Seni dan Pendidikan Seni ISSN 2289-4640 /eISSN 0127-9688 /Vol. 8 No.2 (2020) / (1-12) Article Info: Received Date: 05 May 2020 Accepted Date: 18 November 2020 Published Date: 27 November 2020 Corresponding Author: [email protected] Symbolism of The Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile Mohamad Azizie Nordin Saiful Akram Che Cob Faculty Art and Design, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, Malaysia To cite this article (APA): Nordin, M. A., & Che Cob, S. A. (2020). Symbolism of The Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 8(2), 1-12. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.2.1.2020 To link to this article: https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.2.1.2020 Abstract The research aims to analyse the motive of the traditional Bugis symbol and meaning in Tawau, Sabah (weapon & textile). The research is type is d descriptive qualitative approach with interviews, observation, document, and literature review. Data analysis techniques in this research are ethnography Clifford Geertz. The results of the research indicated that weapons and textiles have a philosophy and symbolic meaning of Bugis Sabah's motive. In this study, textile for Bugis Sabah has convinced symbolic meanings that are very dependent on the wearer for green color for nobility women, red color for teenager’s girl, red color for married women, purple color for widows, black color for elderly and white color for assistants and shaman. Lippa Sabbe’ cloth also has its meaning and philosophy. The motifs found in this Lippa Sabbe ’is Balo Tettong, Mallobang, Cobo, Balo dan Balo Renni. -

Studia Islamika
Volume 24, Number 2, 2017 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢، ٢٠١٧ T R K S S O S S: E L, E G Achmad Ubaedillah ‘R’ N -S: A B B D Mehmet Özay E I S L C S T C اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻳﺦ Raihani واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻲ Priangan: P E C D ( I I U P (PSII اﻻﺗﺤﺎد اﻷﺧﻀﺮ ١٩٤٢-١٩٢٠ ﻧﻤﻮذﺟﺎ Valina Singka Subekti ﳏﻤﺪ ﺇﺳﻜﻨﺪﺭ E-ISSN: 2355-6145 STUDIA ISLAMIKA STUDIA ISLAMIKA Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 24, no. 2, 2017 EDITOR-IN-CHIEF Azyumardi Azra MANAGING EDITOR Oman Fathurahman EDITORS Saiful Mujani Jamhari Didin Syafruddin Jajat Burhanudin Fuad Jabali Ali Munhanif Saiful Umam Ismatu Ropi Dadi Darmadi Jajang Jahroni Din Wahid INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD M. Quraish Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA) Tauk Abdullah (Indonesian Institute of Sciences (LIPI), INDONESIA) M.C. Ricklefs (Australian National University, AUSTRALIA) Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS) John R. Bowen (Washington University, USA) M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA) Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA) Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY) Robert W. Hefner (Boston University, USA) Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientique (CNRS), FRANCE) R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE) Michael F. Laffan (Princeton University, USA) ASSISTANT TO THE EDITORS Testriono Muhammad Nida' Fadlan Endi Aulia Garadian ENGLISH LANGUAGE ADVISOR Dick van der Meij Daniel Peterson ARABIC LANGUAGE ADVISOR Tb. Ade Asnawi COVER DESIGNER S. Prinka STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. -

1001 Years of Missing Martial Arts
1001 Years of Missing Martial Arts IMPORTANT NOTICE: Author: Master Mohammed Khamouch Chief Editor: Prof. Mohamed El-Gomati All rights, including copyright, in the content of this document are owned or controlled for these purposes by FSTC Limited. In Deputy Editor: Prof. Mohammed Abattouy accessing these web pages, you agree that you may only download the content for your own personal non-commercial Associate Editor: Dr. Salim Ayduz use. You are not permitted to copy, broadcast, download, store (in any medium), transmit, show or play in public, adapt or Release Date: April 2007 change in any way the content of this document for any other purpose whatsoever without the prior written permission of FSTC Publication ID: 683 Limited. Material may not be copied, reproduced, republished, Copyright: © FSTC Limited, 2007 downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way except for your own personal non-commercial home use. Any other use requires the prior written permission of FSTC Limited. You agree not to adapt, alter or create a derivative work from any of the material contained in this document or use it for any other purpose other than for your personal non-commercial use. FSTC Limited has taken all reasonable care to ensure that pages published in this document and on the MuslimHeritage.com Web Site were accurate at the time of publication or last modification. Web sites are by nature experimental or constantly changing. Hence information published may be for test purposes only, may be out of date, or may be the personal opinion of the author. Readers should always verify information with the appropriate references before relying on it. -

Indo 13 0 1107127212 183
DIVISIONS AND POWER IN THE INDONESIAN NATIONAL PARTY, 1965-1966* Angus McIntyre The principal division which split the PNI into two sharply opposed factions in 1965-1966 had its origins as far back as 1957, when the PKI made spectacular advances in large part at PNI expense in the 1957 regional elections in Java and South Sumatra. In Central Java, where the PKI supplanted the PNI as the region's strongest party (based on the 1955 general elections results) , the PNI reaction at the time was most outspoken. Hadisubeno, the regional party chairman, blamed the party's poor showing on its past association with the PKI1 and accordingly urged the party's central executive council to re view this relationship. He suggested that the party consider forming an alliance with the Masjumi (the modernist Islamic party) and the Nahdatul Ulama (NU, the traditional Islamic party).2 A conference of the Central Java PNI passed a resolution forbidding cooperation with the PKI.3 These acts were interpreted by many as a slap at President Sukarno,** who had made it increasingly clear in the preceding months that to oppose the PKI was to oppose him as well; however, the party's central leadership, no less hostile to the PKI, was unwilling to risk such an interpretation and thereby further impair its relations with Sukarno. Indeed, only a few months before, Sukarno had indicated strong displeasure with the PNI in his address to the party on the occasion of its thirtieth anniversary celebrations. He implied that PNI members had lost their commitment to the goal of a socialist or marhaenist5 society, the realization of which had been his very reason * The writer would like to express his gratitude to the Jajasan Siswa Lokantara Indonesia for providing him with the opportunity to con- duct research in Indonesia in 1966 and 1967 and to the Myer Founda tion for giving him financial assistance in 1967. -

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ١٦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ T M M R Psii: a C B K.H
Volume 20, Number 1, 2013 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ١، ٢٠١٣ B M I : ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ Karel Steenbrink ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻮﺳﻨﺘﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ١٦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ T M M R PSII: A C B K.H. A A ﺇﺋﲔ ﺳﻮﺭﻳﺎﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ Kevin W. Fogg ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ : A P H I W K ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ Faizal Amin ﺗﺎﲰﺎﻥ STUDIA ISLAMIKA STUDIA ISLAMIKA Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 20, no. 1, 2013 EDITORIAL BOARD: M. Quraish Shihab (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Tauk Abdullah (LIPI Jakarta) Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara) M.C. Ricklefs (Australian National University, Canberra) Martin van Bruinessen (Utrecht University) John R. Bowen (Washington University, St. Louis) M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur) Virginia M. Hooker (Australian National University, Canberra) EDITOR-IN-CHIEF Azyumardi Azra EDITORS Saiful Mujani Jamhari Jajat Burhanudin Oman Fathurahman Fuad Jabali Ali Munhanif Saiful Umam Ismatu Ropi Dina Afrianty ASSISTANT TO THE EDITORS Testriono Muhammad Nida' Fadlan ENGLISH LANGUAGE ADVISOR Melissa Crouch Simon Gladman ARABIC LANGUAGE ADVISOR Nursamad COVER DESIGNER S. Prinka STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/ STT/1976). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. is journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. -

The World from Malarrak: Depictions of South-East Asian and European Subjects in Rock Art from the Wellington Range, Australia
The world from Malarrak: Depictions of South-east Asian and European subjects in rock art from the Wellington Range, Australia Sally K May The Australian National University Paul SC Taçon Griffith University Alistair Paterson The University of Western Australia Meg Travers University of New England Abstract: This paper investigates contact histories in northern Australia through an analysis of recent rock paintings. Around Australia Aboriginal artists have produced a unique record of their experiences of contact since the earliest encounters with Southeast Asian and, later, European visitors and settlers. This rock art archive provides irreplaceable contemporary accounts of Aboriginal attitudes towards, and engagement with, foreigners on their shores. Since 2008 our team has been working to document contact period rock art in northwestern and western Arnhem Land. This paper focuses on findings from a site complex known as Malarrak. It includes the most thorough analysis of contact rock art yet undertaken in this area and ques tions previous interpretations of subject matter and the relationship of particular paintings to historic events. Contact period rock art from Malarrak presents us with an illustrated history of international relationships in this isolated part of the world. It not only reflects the material changes brought about by outside cultural groups but also highlights the active role Aboriginal communities took in respond ing to these circumstances. Introduction the rock art that documents this period of change Few changes would have been as dramatic and from an Aboriginal perspective. We argue that confronting as the early encounters between Aboriginal artists have produced a unique record Indigenous groups and strangers arriving in of their experiences of contact since the very earli- their country after having crossed the sea. -

Investment of Self-Confidence in Cingkrik Rawa Belong Pencak Silat for Elementary School Students
Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah p-ISSN: 2088-9801 | e-ISSN: 2597-937X Vol. 11, No. 1 (June 2021), PP. 10 – 18 INVESTMENT OF SELF-CONFIDENCE IN CINGKRIK RAWA BELONG PENCAK SILAT FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Sa'odah1* and Mamat Supriatna2 1,2Primary Education Department, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia *Email: [email protected] Website: https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/adzka Received: 2 October 2020; Accepted: 20 April 2021; Published: 23 June 2021 DOI: 10.18952/aladzkapgmi.v11i1.3983 ABSTRACT This article aims to describe thoroughly the value of self-confidence in Pencak Silat activities for elementary school students. The scope includes the value of self-confidence in Pencak Silat Cingkrik Rawa Belong. The research method used is a literature review and field visits that include observation and interviews. The research subjects were the head of the Lengkong Arts and Culture House Foundation and the research object was elementary school students who were active in Pencak Silat activities in elementary schools. The research sites are the Cingkrik Rawa Belong Lengkong Cultural Art House and the Primary School in Tangerang. The instruments used were interviews and observation. The result of this research is that the value of self-confidence in Pencak Silat activities is the value obtained by children from training or Pencak silat activities and then retrained through the experience of the championships that have been followed The use-value contained in the Cingkrik Pencak Silat activity can be used as learning to instill confidence in elementary school students. Keywords: cingkrik pencak silat; self-confidence values; elementary school INTRODUCTION Pencak Silat is the result of the culture of Indonesian people in terms of self-defense, self-defense, and the surrounding environment to achieve harmony in life to increase faith and piety (Pratama, 2018; Gristyutawati, Earrings Dien, 2012; and Mardotillah & Zein, 2017). -

Kata Pengantar
KATA PENGANTAR Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengolahan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Pada tahun anggaran 2016 ini, salah satu program kerja Sub Bidang Pengolahan Arsip Pengolahan I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun Guide Arsip Presiden RI: Sukarno 1945-1967. Guide arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis bertema Sukarno sebagai Presiden dengan kurun waktu 1945-1967 yang arsipnya tersimpan dan dapat diakses di ANRI. Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, maka guide arsip ini tentunya belum sempurna dan masih ada kekurangan. Namun demikian guide arsip ini sudah dapat digunakan sebagai finding aid untuk mengakses dan menemukan arsip statis mengenai Presiden Sukarno yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip (user). Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Museum Kepresidenan, Yayasan Bung Karno dan semua pihak yang telah membantu penyusunan guide arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. -
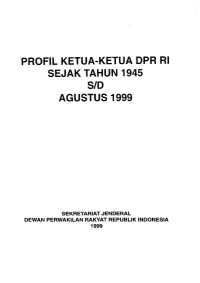
C:\Documents and Settings\Dd Cantik\Desktop\DPR Scan Anggit
PROFIL KETUA-KETUA DPR RI SEJAK TAHUN 1945 SID AGUSTUS 1999 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1999 KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Keterbatasan buku-buku me• ngenai Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah disadari, apalagi buku-buku yang dapat memberikan informasi mengenai mereka yang pernah duduk didalamnya. Padahal, buku semacam itu dapat bercerita banyak tentang . suatu zaman dan kita dapat menarik semangat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan melalui buku pula kita dapat memberikan penghargaan kepada mereka · yang memang pantas mendapatkannya. Oleh karena itu saya merasa gembira dengan hadirnya buku mengenai profil Ketua-ketua DPR dari periode 1945 sampai sekarang. Walaupun berupa sebuah buku kecil yang sederhana, namun setidaknya merupakan buku pertama oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang berusaha untuk mengkompilasikan informasi tentang sosok-sosok mereka 111 dari .berbagai sumber yang pernah mengetuai Lembaga Legislatif ini. Membaca buku ini, seperti mernutar film dalam benak, dengan kita sebagai sutradaranya dan petikan profil dalam buku kecil ini sebagai plotnya. B uku ini mencoba untuk jauh dari kesan menggurui ataupun mengkultuskan pribadi tertentu. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan buku ini dan saya berharap semoga di masa mendatang akan melimpah khasanah pustaka mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, tentunya yang bermutu dan dapat dipertanggung-j awabkan Wassalamu'alaikum Wr. Wb. SEKRETARIS JENDERAL. DPR RI, DRS. AFIF MA'R-OEF lV DAFTAR ISi Halaman I. Kata Pengantar Hl 2. MR. KASMAN SINGODIMEDJO I 3. SUTAN SYAHRIR 9 4. S U P E N O 19 5. MR. ASSAAT 25 6. MR. SARTO NO 33 7. K.H. ZAINUL ARIFIN 41 8.