Download (1MB)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
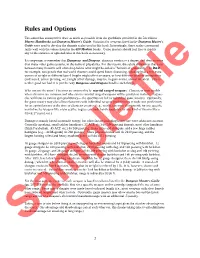
Rules and Options
Rules and Options The author has attempted to draw as much as possible from the guidelines provided in the 5th edition Players Handbooks and Dungeon Master's Guide. Statistics for weapons listed in the Dungeon Master's Guide were used to develop the damage scales used in this book. Interestingly, these scales correspond fairly well with the values listed in the d20 Modern books. Game masters should feel free to modify any of the statistics or optional rules in this book as necessary. It is important to remember that Dungeons and Dragons abstracts combat to a degree, and does so more than many other game systems, in the name of playability. For this reason, the subtle differences that exist between many firearms will often drop below what might be called a "horizon of granularity." In D&D, for example, two pistols that real world shooters could spend hours discussing, debating how a few extra ounces of weight or different barrel lengths might affect accuracy, or how different kinds of ammunition (soft-nosed, armor-piercing, etc.) might affect damage, may be, in game terms, almost identical. This is neither good nor bad; it is just the way Dungeons and Dragons handles such things. Who can use firearms? Firearms are assumed to be martial ranged weapons. Characters from worlds where firearms are common and who can use martial ranged weapons will be proficient in them. Anyone else will have to train to gain proficiency— the specifics are left to individual game masters. Optionally, the game master may also allow characters with individual weapon proficiencies to trade one proficiency for an equivalent one at the time of character creation (e.g., monks can trade shortswords for one specific martial melee weapon like a war scythe, rogues can trade hand crossbows for one kind of firearm like a Glock 17 pistol, etc.). -

Symbolism of the Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile
KUPAS SENI Jurnal Seni dan Pendidikan Seni ISSN 2289-4640 /eISSN 0127-9688 /Vol. 8 No.2 (2020) / (1-12) Article Info: Received Date: 05 May 2020 Accepted Date: 18 November 2020 Published Date: 27 November 2020 Corresponding Author: [email protected] Symbolism of The Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile Mohamad Azizie Nordin Saiful Akram Che Cob Faculty Art and Design, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, Malaysia To cite this article (APA): Nordin, M. A., & Che Cob, S. A. (2020). Symbolism of The Sabah Bugis Motive: Sign and Meaning: Weapon and Textile. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 8(2), 1-12. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.2.1.2020 To link to this article: https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.2.1.2020 Abstract The research aims to analyse the motive of the traditional Bugis symbol and meaning in Tawau, Sabah (weapon & textile). The research is type is d descriptive qualitative approach with interviews, observation, document, and literature review. Data analysis techniques in this research are ethnography Clifford Geertz. The results of the research indicated that weapons and textiles have a philosophy and symbolic meaning of Bugis Sabah's motive. In this study, textile for Bugis Sabah has convinced symbolic meanings that are very dependent on the wearer for green color for nobility women, red color for teenager’s girl, red color for married women, purple color for widows, black color for elderly and white color for assistants and shaman. Lippa Sabbe’ cloth also has its meaning and philosophy. The motifs found in this Lippa Sabbe ’is Balo Tettong, Mallobang, Cobo, Balo dan Balo Renni. -

1001 Years of Missing Martial Arts
1001 Years of Missing Martial Arts IMPORTANT NOTICE: Author: Master Mohammed Khamouch Chief Editor: Prof. Mohamed El-Gomati All rights, including copyright, in the content of this document are owned or controlled for these purposes by FSTC Limited. In Deputy Editor: Prof. Mohammed Abattouy accessing these web pages, you agree that you may only download the content for your own personal non-commercial Associate Editor: Dr. Salim Ayduz use. You are not permitted to copy, broadcast, download, store (in any medium), transmit, show or play in public, adapt or Release Date: April 2007 change in any way the content of this document for any other purpose whatsoever without the prior written permission of FSTC Publication ID: 683 Limited. Material may not be copied, reproduced, republished, Copyright: © FSTC Limited, 2007 downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way except for your own personal non-commercial home use. Any other use requires the prior written permission of FSTC Limited. You agree not to adapt, alter or create a derivative work from any of the material contained in this document or use it for any other purpose other than for your personal non-commercial use. FSTC Limited has taken all reasonable care to ensure that pages published in this document and on the MuslimHeritage.com Web Site were accurate at the time of publication or last modification. Web sites are by nature experimental or constantly changing. Hence information published may be for test purposes only, may be out of date, or may be the personal opinion of the author. Readers should always verify information with the appropriate references before relying on it. -

Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa
NASKAH AKHIR TENTANG 1. Pergerakan Kebangsaan dan Gejolak Politik Lokal; 2. Kehidupan Sosial Budaya; 3. Merebut dan Mempertahankan Kemer- dekaan; 4. Pembangunan Semasa Bupati Dr. H. Don Murdono, S. H., M. Si. Untuk buku Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa kerja sama Pusat Kebudayaan Sunda (PKS), Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran Dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Sumedang Untuk memenuhi persyaratan bagi pengajuan kenaikan Golongan/ Pangkat ke IIIc/Penata pada jabatan fungsional Lektor. BAGIAN KEDUA MASA KERAJAAN HINGGA BERDIRINYA KABUPATEN SUMEDANG 4. Pergerakan Kebangsaan dan Gejolak Politik Lokal Eksploitasi kolonial yang terjadi pada abad ke-19 di Nusantara telah menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong rakyat untuk melakukan pergerakan sosial. Dominasi ekonomi, politik, dan budaya yang berlangsung terus menerus telah menimbulkan disorganisasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga- lembaganya. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi Barat yang memiliki kekuatan disinteragtif, masyarakat tradisional mempunyai cara-cara tersendiri. Cara-cara tersebut dilakukan mengingat di dalam sistem pemerintahan kolonial tidak terdapat lembaga untuk menyalurkan rasa tidak puas ataupun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, satu- satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gerakan sosial sebagai bentuk proses sosial.1 Gerakan sosial yang menjadi fenomena dari gejolak politik tingkat lokal sejak akhir abad ke-19 pun terjadi di Sumedang. Gerakan sosial di Sumedang yang perlu dikemukakan di sini adalah Gerakan Nyi Aciah yang terjadi pada tahun 1870-1871 dan dikategorikan sebagai sebuah gerakan keagamaan.2 Gerakan Nyi Aciah terjadi ketika Pangeran Aria Suria Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih menjabat sebagai Bupati Sumedang (1834-1882). Ditulis oleh Miftahul Falah, S. S. sebagai bagian dari buku Sumedang dari Masa ke Masa. -

The World from Malarrak: Depictions of South-East Asian and European Subjects in Rock Art from the Wellington Range, Australia
The world from Malarrak: Depictions of South-east Asian and European subjects in rock art from the Wellington Range, Australia Sally K May The Australian National University Paul SC Taçon Griffith University Alistair Paterson The University of Western Australia Meg Travers University of New England Abstract: This paper investigates contact histories in northern Australia through an analysis of recent rock paintings. Around Australia Aboriginal artists have produced a unique record of their experiences of contact since the earliest encounters with Southeast Asian and, later, European visitors and settlers. This rock art archive provides irreplaceable contemporary accounts of Aboriginal attitudes towards, and engagement with, foreigners on their shores. Since 2008 our team has been working to document contact period rock art in northwestern and western Arnhem Land. This paper focuses on findings from a site complex known as Malarrak. It includes the most thorough analysis of contact rock art yet undertaken in this area and ques tions previous interpretations of subject matter and the relationship of particular paintings to historic events. Contact period rock art from Malarrak presents us with an illustrated history of international relationships in this isolated part of the world. It not only reflects the material changes brought about by outside cultural groups but also highlights the active role Aboriginal communities took in respond ing to these circumstances. Introduction the rock art that documents this period of change Few changes would have been as dramatic and from an Aboriginal perspective. We argue that confronting as the early encounters between Aboriginal artists have produced a unique record Indigenous groups and strangers arriving in of their experiences of contact since the very earli- their country after having crossed the sea. -

Investment of Self-Confidence in Cingkrik Rawa Belong Pencak Silat for Elementary School Students
Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah p-ISSN: 2088-9801 | e-ISSN: 2597-937X Vol. 11, No. 1 (June 2021), PP. 10 – 18 INVESTMENT OF SELF-CONFIDENCE IN CINGKRIK RAWA BELONG PENCAK SILAT FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Sa'odah1* and Mamat Supriatna2 1,2Primary Education Department, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia *Email: [email protected] Website: https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/adzka Received: 2 October 2020; Accepted: 20 April 2021; Published: 23 June 2021 DOI: 10.18952/aladzkapgmi.v11i1.3983 ABSTRACT This article aims to describe thoroughly the value of self-confidence in Pencak Silat activities for elementary school students. The scope includes the value of self-confidence in Pencak Silat Cingkrik Rawa Belong. The research method used is a literature review and field visits that include observation and interviews. The research subjects were the head of the Lengkong Arts and Culture House Foundation and the research object was elementary school students who were active in Pencak Silat activities in elementary schools. The research sites are the Cingkrik Rawa Belong Lengkong Cultural Art House and the Primary School in Tangerang. The instruments used were interviews and observation. The result of this research is that the value of self-confidence in Pencak Silat activities is the value obtained by children from training or Pencak silat activities and then retrained through the experience of the championships that have been followed The use-value contained in the Cingkrik Pencak Silat activity can be used as learning to instill confidence in elementary school students. Keywords: cingkrik pencak silat; self-confidence values; elementary school INTRODUCTION Pencak Silat is the result of the culture of Indonesian people in terms of self-defense, self-defense, and the surrounding environment to achieve harmony in life to increase faith and piety (Pratama, 2018; Gristyutawati, Earrings Dien, 2012; and Mardotillah & Zein, 2017). -

REPRESENTASI NILAI BUDAYA SIRI' DALAM FILM TELEVISI NASIONAL (Analisis Semiotik Pierce Film “Badik Titipan Ayah”)
REPRESENTASI NILAI BUDAYA SIRI’ DALAM FILM TELEVISI NASIONAL (Analisis Semiotik Pierce Film “Badik Titipan Ayah”) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Oleh: SRI YUSNIDAR NIM: 50500113074 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017 iii iv v KATA PENGANTAR . احلمد هلل الذي خلق اﻹنسان يف أحسن تقومي، وجعل احلياء من اﻹميان والصﻻة والسﻻم على خري خلقه سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم املبعوث إىل خري اﻷنام، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة . Assalamu’alaikum Wr.Wb Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk yang bernafas dimuka bumi. Dialah yang maha pengasih namun tak pilih kasih dan karena Dialah akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad swt. Keluarganya dan orang-orang yang masih mengikuti ajaran-Nya hingga hari pembalasan tiba. Selanjutnya penulis hanturkan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang terus mendukung dan mendoakan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini dan untuk pihak-pihak yang telah banyak berjasa dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini: 1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A, dan Wakil Rektor III Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D, serta Wakil Rektor IV Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar. -

Makna Simbolik Pusaka Tua Jenis Badik Di Museum La Galigo - Benteng Rotterdam Kota Makassar
MAKNA SIMBOLIK PUSAKA TUA JENIS BADIK DI MUSEUM LA GALIGO - BENTENG ROTTERDAM KOTA MAKASSAR SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Oleh ROSDAWIA NIM. 105381109216 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI 2020 i ii iii UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURAT PERJANJIAN Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : ROSDAWIA Nim : 105381109216 Jenjang : Strata Satu (S1) Program Studi : Pendidikan Sosiologi Judul : Makna Simbolik Pusaka Tua Jenis Di Museum La Galigo-Benteng Rotterdam Kota Makassar Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikutr: 1. Mulai daripenyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusunnya sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun). 2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas. 3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini. 4. Apabila saya melanggar perjanjian butir 1, 2 dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran. Makassar, November 2020 Yang membuat Pernyataan, ROSDAWIA Nim. 105381109216 iv UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : ROSDAWIA Nim : 105381115016 Jenjang : Strata Satu (S1) Program Studi : Pendidikan Sosiologi Judul : Makna Simbolik Pusaka Tua Jenis Badik Di Museum La Galigo-Benteng Rotterdam Kota Makassar Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan- bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya. -

Lawi Ayam : Aesthetic Experience and Design-User System Assesment of a Malay Weapon Artefact
LAWI AYAM : AESTHETIC EXPERIENCE AND DESIGN-USER SYSTEM ASSESMENT OF A MALAY WEAPON ARTEFACT Malaya SITI MASTURA BINTI MD ISHAK of INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES UniversityUNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2017 LAWI AYAM : AESTHETIC EXPERIENCE AND DESIGN-USER SYSTEM ASSESMENT OF A MALAY WEAPON ARTEFACT SITI MASTURA BINTI MD ISHAK Malaya of THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES UNIVERSITY OF MALAYA UniversityKUALA LUMPUR 2017 UNIVERSITY OF MALAYA ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION Name of Candidate: SITI MASTURA BINTI MD ISHAK Registration/Matric No: HHB 120007 Name of Degree: DOCTOR OF PHILOSOPHY Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis (“this Work”): LAWI AYAM : AESTHETIC EXPERIENCE AND DESIGN-USER SYSTEM ASSESMENT OF A MALAY WEAPON ARTEFACT Field of Study: AESTHETICS I do solemnly and sincerely declare that: (1) I am the sole author/writer of this Work; (2) This Work is original; Malaya (3) Any use of any work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any excerpt or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and theof title of the Work and its authorship have been acknowledged in this Work; (4) I do not have any actual knowledge nor do I ought reasonably to know that the making of this work constitutes an infringement of any copyright work; (5) I hereby assign all and every rights in the copyright to this Work to the University of Malaya (“UM”), who henceforth shall be owner of the copyright in this Work and that any reproduction or use in any form or by any means whatsoever is prohibited without the written consent of UM having been first had and obtained; (6) I am fully aware that if in the course of making this Work I have infringed any copyright whether intentionally or otherwise, I may be subject to legal action or any other action as may be determined by UM. -

Download Download
ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA Volume 4 Edisi 2, DESEMBER 2019 P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747 National Accredited SINTA 2. No. 10/E/KPT/2019 Manca': A Study of the Martial Arts' Symbol as Makassar Cultural Identity in Gowa, South Sulawesi Manca’: Kajian Tentang Simbol Seni Beladiri Sebagai Identitas Budaya Makassar di Gowa Sulawesi Selatan Mutahhar Syan1, Supriadi Hamdat2 1Universitas Negeri Makassar, Makassar Indonesia. Email: [email protected] 2Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: This study aims to describe and analyze the symbols of movements and Beladiri; budaya makassar; costumes used from martial arts as a cultural identity that is present symbol; identity. and attached to the Sulawesi Pencak Silat Association (IPS). The study used a qualitative descriptive approach with ethnographic methods. How to cite: This research was conducted in Padepokan Pencak Silat Sulawesi Syan, M., Hamdat, S. Association (IPS) in Taeng Village, Gowa Regency. The analysis (2019). Manca’: Kajian technique used is a symbolic interpretation, which sees symbols and Tentang Simbol Seni meanings going hand in hand from each movement used. This research Beladiri Sebagai Identitas shows that silat or manca is not talking about stance as a form of Budaya Makassar di Gowa organized movement, but rather on the functions, benefits, risks posed. Sulawesi Selatan. The parts of silat contain meanings and symbols that are understood ETNOSIA: Jurnal as cultural identity and forms of belief, namely: the fingers describe Etnografi Indonesia. 4(2): three in one form of respect, stepping with the right foot first, the foot 193 – 206. is always shaped like an easel. -

Ethnic Conflict in Indonesia Causes and Recommended Measures
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Calhoun, Institutional Archive of the Naval Postgraduate School Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2005-12 Ethnic Conflict in Indonesia causes and recommended measures Siddiq, Irfan. Monterey California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/1822 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS ETHNIC CONFLICT IN INDONESIA: CAUSES AND RECOMMENDED MEASURES by Irfan Siddiq December 2005 Thesis Advisor: Tuong Vu Second Reader: Edward A. Olsen Approve for public release; distribution is unlimited THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2.REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED December 2005 Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE: Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and 5. FUNDING NUMBERS Recommended Measures 6. AUTHOR(S) Irfan Siddiq 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING ORGANIZATION Naval Postgraduate School REPORT NUMBER Monterey, CA 93943-5000 9. -

The Shifting of Traditional Clothes Symbolic Means in the Bone District Community
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 6, Ser. 3 (June. 2019) 63-67 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org The Shifting of Traditional Clothes Symbolic Means in the Bone District Community Andi Nurmaida1, Andi Agustang2, Darman Manda3, Anshari4 1,2,3,4 Graduated Program, Universitas Negeri Makassar, South Sulawesi, Indonesia Corresponding Author: Andi Nurmaida Abstract: Culture is a part of every human life and it is a legacy that realized from various cultural elements in Indonesia. One of them is traditional clothes which have undergone a shift due to technological advances. This study aims to understand the process of the shifting meaning of traditional clothes to the people of Bone Regency with specific purposes, namely the form of shifting meaning of traditional clothes to the people of Bone Regency. This research location is in the Tanete Riattang Sub district Bone Regency with the data source is the Family of Royal Bone Regency, cultural observer, community leaders and the people of Bone Regency. The data collection techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing a conclusion and verifying. The result of the study found that the form of the shifting meaning of traditional clothes in the people of Bone Regency can be seen from its symbol, time of use, and the sacred value of traditional clothes. Keywords : shifting symbolic meaning, traditional clothes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Date of Submission: 30-05-2019 Date of acceptance: 15-06-2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- I. INTRODUCTION The social changes that occur include changes in various sectors, one of which is fashion.