Rumah Ulu Komering
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
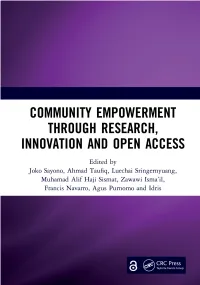
Community Empowerment Through Research, Innovation and Open Access
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH RESEARCH, INNOVATION AND OPEN ACCESS PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (ICHSS 2020), MALANG, INDONESIA, 28 OCTOBER 2020 Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access Edited by Joko Sayono & Ahmad Taufiq Universitas Negeri Malang, Indonesia Luechai Sringernyuang Mahidol University, Thailand Muhamad Alif Haji Sismat Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam Zawawi Isma’il Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia Francis M. Navarro Ateneo De Manila University, Philippines Agus Purnomo & Idris Universitas Negeri Malang, Indonesia CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2021 selection and editorial matter, the Editors; individual chapters, the contributors Typeset by MPS Limited, Chennai, India The Open Access version of this book, available at www.taylorfrancis.com, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license. Although all care is taken to ensure integrity and the quality of this publication and the information herein, no responsibility is assumed by the publishers nor the author for any damage to the property or persons as a result of operation or use of this publication and/or the information contained herein. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record has been requested for this book Published by: CRC Press/Balkema Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands e-mail: [email protected] www.routledge.com – www.taylorandfrancis.com ISBN: 978-1-032-03819-3 (Hbk) ISBN: 978-1-032-03820-9 (Pbk) ISBN: 978-1-003-18920-6 (eBook) DOI: 10.1201/9781003189206 Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access – Sayono et al (Eds) © 2021 Copyright the Editor(s), ISBN 978-1-032-03819-3 Table of contents Preface ix Acknowledgement xi Scientific committee xiii Organizing committee xv Empowering translation students through the use of digital technologies 1 M.A.H. -

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/44/2019 Tentang Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: HK.01.07/MENKES/44/2019 TENTANG TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1440 H/2019 M DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas - 2 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Bab 3 Kepurbakalaan Padang Lawas: Tinjauan Gaya Seni Bangun, Seni Arca Dan Latar Keaagamaan
BAB 3 KEPURBAKALAAN PADANG LAWAS: TINJAUAN GAYA SENI BANGUN, SENI ARCA DAN LATAR KEAAGAMAAN Tinjauan seni bangun (arsitektur) kepurbakalaan di Padang Lawas dilakukan terhadap biaro yang masih berdiri dan sudah dipugar, yaitu Biaro Si Pamutung, Biaro Bahal 1, Biaro Bahal 2, dan Biaro Bahal 3. Sedangkan rekonstruksi bentuk dilakukan terhadap unsur-unsur bangunan biaro-biaro di Padang Lawas yang sudah tidak berada dalam konteksnya lagi, atau masih insitu dan berada dengan konteksnya tetapi dalam keadaan fragmentaris. Rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan tulisan dan foto (gambar) para peneliti yang sudah melakukan penelitian di situs tersebut pada masa lalu. Tinjauan terhadap gaya seni arca dilakukan terhadap arca-arca logam untuk mengetahui bagaimana gaya seni arca tinggalan di Padang Lawas, apakah mempunyai kesamaan dengan gaya seni arca dari tempat lain baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Gaya seni arca juga dapat memberikan gambaran periodisasinya secara relatif. Adapun periodisasi situs secara mutlak didapatkan berdasarkan temuan prasasti-prasasti yang menuliskan pertanggalan. Prasasti- prasasti yang ditemukan di Padang Lawas sebagian besar berisi tentang mantra- mantra dalam melakukan suatu upacara keagamaan, oleh karena itu latar keagamaan situs dapat diketahui berdasarkan isi prasasti. Di samping itu latar keagamaan diketahui juga dengan melalui studi ikonografi terhadap arca dan relief. 3.1 Gaya Seni Bangun (Arsitektur) Menurut Walter Grophius arsitektur adalah suatu ilmu bangunan yang juga mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan biologi, sosial, teknik, dan artistik, oleh karena itu arsitektur dapat didefinisikan sebagai: (1) Seni ilmu bangunan, termasuk perencanaan, perancangan, konstruksi dan penyelesaian ornament; (2) Sifat, karakter atau gaya bangunan; (3) Kegiatan atau proses membangun bangunan; (4) Bangunan-bangunan; (5) Sekelompok bangunan Universitas Indonesia 114 Kepurbakalaan Padang..., Sukawati Susetyo, FIB UI, 2010. -

Tipologi Atap Pada Arsitektur Vernakular Di Sumatera Selatan
Prosiding Seminar Kearifan Lokal dan Lingkungan Binaan 25-26 Januari 2017 TIPOLOGI ATAP PADA ARSITEKTUR VERNAKULAR DI SUMATERA SELATAN Zuber Angkasa Wazir1* 1.Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang *Email: [email protected] ABSCTRACT The development of new urbanism paradigm in the world today, has been reminded of the importance of vernacular architecture in urban planning.. It would be advantageous for areas with high ethnic diversity as South Sumatra. This study aims to inventory the vernacular house typology in South Sumatra. Methods of study is to examine the vernacular houses of all ethnicities in South Sumatra (29 ethnicity) plus two ethnic from neighboring provinces (Kubu and Lambak). The study found 18 different types of houses, and also found that the typology of the roof consists of a limas roof, pelana roof, and a perisai roof. The variety of roof reflects the high ethnic mobilization in South Sumatra. Even so, as a result of acculturation that occurs in these dynamics, the variety is found only on the shape of the roof, while the other part of the building does not have a clear marker of difference. Implications of the New Urbanism presented in the design of contemporary urban planning in South Sumatra. Keywords: arsitektur vernakular, Sumatera Selatan, tipologi bentuk, tipologi atap, keanekaragaman etnik PENDAHULUAN Bangunan didefinisikan sebagai “wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air” [1]. Sebagai bagian dari habitat manusia, bangunan memiliki fungsi yang melayani berbagai kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga kebutuhan tersier dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. -

I Sejarah Rumah Ulu Di Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa Tahun 1992-2019
SEJARAH RUMAH ULU DI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN BALAPUTRA DEWA TAHUN 1992-2019 (SEBAGAI SUATU SUMBANGAN MATERI WISATA SEJARAH BUDAYA DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG) SKRIPSI OLEH RIKO RIANDA NIM 352016007 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH MARET 2021 i SEJARAH RUMAH ULU DI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN BALAPUTRA DEWA TAHUN 1992-2019 (SEBAGAI SUATU SUMBANGAN MATERI WISATA SEJARAH BUDAYA DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG) SKRIPSI Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk memenuhi salah satu persyaratan Dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Oleh Riko Rianda NIM 352016007 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH MARET 2021 i Skripsi oleh Riko Rianda ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji Palembang, 25 Februari 2021 Pembimbing I, Heryati, S.Pd., M.Hum. Palembang, 23 Februari 2021 Pembimbing II, Yuliarni, S.Pd., M.Hum. ii Skripsi oleh Riko Rianda ini telah di pertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Maret 2021 Dewan Penguji: Heryati, S.Pd., M.Hum., Ketua Yuliarni, S.Pd., M.Hum., Anggota Dr. Apriana, M.Hum., Anggota Mengetahui Mengesahkan Ketua Program Studi Dekan Pendidikan Sejarah, FKIP UMP, Heryati, S.Pd., M.Hum. Dr. H. Rusdy A Siroj, M.Pd. iii iv MOTTO dan PERSEMBAHAN Motto: . Cerdas dalam berfikir cermat dalam bertindak . “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian” (Q.S Al-Mujadila: 11) Kupersembahkan Kepada: Ayahanda Bajidin dan Ibundaku Siti Rohani tercinta yang selalu aku banggakan dan senantiaasa tiada henti mendo’akan, mendukung, dan mengharapkan kesuksesan dan keberhasilanku. -

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Arsitektur Tradisional
i PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL Disertasi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Raditya Permana NIM. B5A003018 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2011 ii PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL Disertasi Raditya Permana NIM. B5A003018 Semarang, 31 Maret 2011 Promotor Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. NIP : 194205051973022001 Mengetahui Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS. NIP. 195110211976032001 iii PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Raditya Permana NIM : B5A003018 Alamat : Villa Aster II, Blok O No. 1 A, Srondol, Semarang Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain. 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor. 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. Semarang, 31 Maret 2011 Yang membuat pernyataan, METERAI Rp. 6.000,- Raditya Permana NIM. B5A003018 iv KATA PENGANTAR Puji syukur promovendeus panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. -

Etnomatematika Pada Kebudayaan Rumah Adat Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
e-ISSN: 2549-5070 p-ISSN: 2549-8231 Journal of Medives Volume 2, No. 1, 2018, pp. 137-144 http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/matematika/article/view/557 ETNOMATEMATIKA PADA KEBUDAYAAN RUMAH ADAT OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN Eka Fitri Puspa Sari1, Somakim2, Yusuf Hartono2 1Universitas PGRI Palembang, 2Universitas Sriwijaya [email protected] Diterima: November 2017. Disetujui: Desember 2017. Dipublikasikan: Januari 2018 ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian kajian pendidikan matematika yang berhubungan dengan etnomatematika pada rumah adat ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya dengan kota-kota besar di Indonesia yang mempunyai budaya beragam, Ogan Komering Ulu mempunyai ragam kekayaan sejarah dan budaya yang sangat menakjubkan. Salah satu peninggalan tersebut adalah arsitektur tradisional rumah ogan komering ulu. Beberapa rumah tradisional tersebut telah berumur lebih dari 50 tahun serta menyimpan nilai sejarah, budaya dan arsitektur yang belum sepenuhnya terungkap dengan jelas. Rumah ogan komering ulu mempunyai bangunan tipe spesifik yaitu limas, kemudian ada beberapa motif hiasan rumah atau ukiran yang berbentuk geometri. Kata kunci: etnomatematika, rumah adat, geometri. ABSTRACT This is a literature study of mathematics education related to ethnomatematics in traditional house of Komering Ulu in southern sumatera province. Like the other big cities in indonesia that have diverse culture, Ogan Komering Ulu also has an incredible variety of historical and cultural riches. One such relic is the traditional architecture of the house ogan komering ulu. Some of the traditional houses are over 50 years old and store historical, cultural and architectural values that have not been fully revealed. Rumah ogan komering ulu has a specific type of building that is pyramid, then there are some motifs of home decoration or engraving in the form of geometry. -

1 Bab Iii Gambaran Umum Arsitektur Rumah Limas
1 BAB III GAMBARAN UMUM ARSITEKTUR RUMAH LIMAS PALEMBANG Rumah Limas adalah rumah adat yang dibangun dengan arsitektur tradisional dan sekaligus merupakan rumah adat yang cukup terkenal diantara berbagai bentuk rumah tradisional yang di jumpai di Palembang. Terkenal dengan corak, bentuk dan kepadataan seni ukir dan juga disertai dengan kemilauan warna cat warna peredo emas yang khusus di datangkan dari Negeri Siam serta penataan ruangan yang mencerminkan tingginya tingkatan budaya suku bangsa yang memilikinya. Rumah Limas di Palembang memiliki bentuk atau ciri tersendiri A. Ciri-ciri Khas Rumah Limas 1. Mempunyai lemari yang menempel langsung pada dinding yang berfungsi sebagai lemari penyimpanan barang-barang antik dan sekaligus menjadi hiasan dinding 2. Mempunyai tingkatan-tingkatan atau bengkilas dalam rumah, serta dibatasi dengan papan atau kekijing 3. Pemasangan Rumah Limas tidak mengunakan logam akan tetapi memakai paku pasa atau yang terbuat dari kayu 4. Terdapat lawang kipas yang bisa menjadi dinding rumah sekaligus menjadi atap dan gentengnya diberi nama genteng bela bolo seperti bambu yang dibelah dua 2 5. Kamar yang aslinya tidak mengunakan engsel 1. Ukuran Rumah Limas Palembang Rumah Limas Palembang diukur menurut kedudukannya didalam masyarakat Palembang yang mana Rumah Limas terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu ukuran besar, ukuran menengah, ukuran sedang, ukuran kecil dan ukuran biasa. Sedangkan penghuninya mulai dari golongan demang sampai dengan pangeran, anggota masyarakat biasa, cendikiawan, alim ulama dan kepala adat beserta pemuka lainnya.1 a. Ukuran-ukuran Rumah Limas Palembang 1. Ukuran Rumah Induk dari Rumah Limas yang besar sebagai berikut: 15 x 28 depe atau 22,5 x 42 M. 13 x 28 depe atau 19,50 x 42 M. -
Daftar Mutasi Dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sesuai Kep-208/Pj/2021
LAMPIRAN I Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-192/PJ/PJ.01/2021 Tanggal : 21 Mei 2021 DAFTAR MUTASI DAN PENGUKUHAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN SESUAI KEP-208/PJ/2021 JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN NO NAMA/NIP LAMA BARU 1 Nurmansyah Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Tata Laksana 19741127 199511 1 001 Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sekretariat Direktorat Jenderal Satu 2 Edy Setiawan Kepala Subbagian Kepegawaian Kepala Subbagian Perencanaan dan 19780227 200001 1 003 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Pengadaan Pegawai Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal 3 Adi Barata Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Mutasi 19760918 199903 1 003 Pimpinan Bagian Umum Sekretariat Kepegawaian I Bagian Mutasi dan Direktorat Jenderal Kepangkatan Sekretariat Direktorat Jenderal 4 Bombong Widarto Kepala Seksi Sinkronisasi Peraturan Kepala Subbagian Mutasi 19710813 199201 1 002 Perpajakan Direktorat Peraturan Kepegawaian III Bagian Mutasi dan Perpajakan II Kepangkatan Sekretariat Direktorat Jenderal 5 R. Akhmad Rival Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Administrasi Gaji 19771118 200001 1 001 Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan dan Tunjangan Bagian Keuangan Pajak Pratama Bengkulu Sekretariat Direktorat Jenderal 6 Agustinus Widiantoro Kepala Seksi Pengolahan Data dan Kepala Subbagian Pengadaan I Bagian 19750704 199602 1 001 Informasi Kantor Pelayanan -

Modus Bermukim Masyarakat Riparian Sungai Musi Palembang
SEMINAR NASIONAL SCAN#7:2016 “The Lost World” Historical Continuity for Sustainable Future MODUS BERMUKIM MASYARAKAT RIPARIAN SUNGAI MUSI PALEMBANG Bambang Wicaksono1), Susilo Kusdiwanggo2) Staf Pengajar Jurusan Arsitektur/Perencanaan Wilayah Kota Universitas IGM Palembang, Mahasiswa Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Teknik BKU Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya1) Co-promotor, Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya2) E-mail : [email protected]) E-mail : [email protected]) ABSTRACT There are three modes of settlement that have for centuries lived by the community in addressing Palembang Musi River. First, the settlement in the form of water raft houses on the Musi River, then the second settlement in the tidal area with houses stage, and three settlements on the mainland. Forms of settlement on the banks of the Musi River in the form of stilt houses on poles anchored on the banks of the Musi River with a pyramid roof which was then called Rumah Limas and Limas House Warehouse. But there are also houses built on the River Musi form rafts called Rakit. In the historical records, the first settlement in Palembang growth came from settlements on the banks of the Musi River. The pattern of settlement developments occurring elongated follows the flow of the Musi River, which is on the right and left sides of the river. The influence of the river for the people of Palembang expressed in the naming of their villages were always oriented to the river. The area north of the River Musi called Ilir, and the area south of the Musi River called Seberang Ulu. -

New Normal Arsitektur Tradisional Ulu Ogan, Sumatera Selatan
Seminar Nasional AVoER XII 2020 Palembang, 18 - 19 November 2020 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya NEW NORMAL ARSITEKTUR TRADISIONAL ULU OGAN, SUMATERA SELATAN A. Siswanto1* 1 Arsitektur, Universitas Sriwijaya, Palembang Corresponding author: [email protected] ABSTRAK: Rumah Ulu Ogan yang telah dihuni selama beberapa generasi memiliki penampilan new normal yang beradaptasi pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. New normal atau perubahan baru yang kemudian dianggap wajar merupakan diimplementasikan dari suatu tindakan praktis tanpa memperhatikan aspek langgam arsitektur tradisional yang selama ini dikenal secara umum termasuk arsitek karena memiliki filosofi, proporsi, dan karakter unik. Walaupun tindakan new normal dapat dimengerti tetapi sebenarnya dapat dianggap mengabaikan filosofi, proporsi dan karakter dari arsitektur tradisional. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji gejala new normal yang dihadapi berbagai tipe rumah tradisional. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang meliputi beberapa rumah tradisional di beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Partisipan adalah pemilik, penghuni dan pemuka masyarakat di desa terkait. Perubahan yang dilakukan memiliki banyak kesamaan dan pada elemen rumah yang relatif sama. New normal pada tampilan rumah Ulu Ogan telah memberikan proporsi dan penampilan baru dari rumah tradisional yang kemudian dianggap wajar dan bukan hal yang aneh atau janggal. Kesimpulan yang diperoleh adalah perubahan dan penyesuaian langgam arsitektur tradisional seiring dengan kebutuhan, kemampuan -

Kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Sumatera Selatan Bagi Pambangunan Lingkungan Binaan, Ari Siswanto
Volume: I, Nomor: 1, Halaman: 37 - 45, Nopember 2009. Kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Sumatera Selatan Bagi Pambangunan Lingkungan Binaan, Ari Siswanto KEARIFAN LOKAL ARSITEKTUR TRADISIONAL SUMATERA SELATAN BAGI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BINAAN Ari Siswanto Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UNSRI Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana UNSRI Email: [email protected] Abstrak Pembangunan yang sangat intensif dengan merubah bentuk fisik kawasan serta mengabaikan karakter lingkungan dapat mengancam lingkungan binaan dalam jangka panjang. Bencana banjir, tanah longsor dan gempabumi merupakan ancaman serius bagi lingkungan binaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerugian harta dan jiwa dalam jumlah besar. Lingkungan fisik Sumatera Selatan sangat bervariasi, meliputi wilayah perairan, pantai, daerah rawa pasang surut, dataran rendah, dataran tinggi termasuk kawasan rawan gempabumi di sebelah barat. Sumatera Selatan memiliki beragam arsitektur tradisional yang menakjubkan serta menunjukkan keharmonisan dan kesesuaian dengan lingkungan setempat. Di daerah rawa perkotaan terdapat rumah Limas yang memiliki perbedaan konstruksi dengan rumah limas di dataran tinggi, walaupun memiliki perbedaan tetapi tetap adaptif dengan lingkungannya. Selanjutnya, di kawasan perairan dan sungai terdapat rumah rakit, di daerah rawa dan dataran tinggi terdapat rumah panggung sedangkan di daerah rawan gempabumi terdapat rumah tradisional Lamban Tuha yang mampu meredam getaran akibat gempabumi.