Download (1MB)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strategi Pembelajaran Sejarah Berbasis Lagu-Lagu Perjuangan Dalam Konteks Kesadaran Nasionalisme
STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS LAGU………| 1 STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS LAGU-LAGU PERJUANGAN DALAM KONTEKS KESADARAN NASIONALISME Brigida Intan Printina* Abstrak Di masa-masa kebangkitan nasional lagu-lagu perjuangan menjadi sarana vital dalam membangkitkan kesadaran nasional para pemuda bangsa. Namun, mayoritas pemuda saat ini tidak mampu menunjukkan semangat nasionalismenya karena kurang mengerti akan makna lagu-lagu perjuangan. Maraknya lagu asing semakin menggerus nilai nasionalisme. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pembelajaran sejarah agar setiap pemuda dapat membangun diri dan mampu membentuk kesadaran nasionalisme dengan menyanyikan dan menghayati lagu-lagu perjuangan di setiap kesempatan. Kata Kunci : strategi pembelajaran sejarah, lagu perjuangan, nasionalisme Pendahuluan kepada etnis Jawa atau salah satu budaya Tumbuh dan berkembangnya etnis di Nusantara, melainkan harus bersifat nasionalisme di Indonesia tidak semata- universal seperti dalam kedudukan musik mata didasarkan pada persamaan- diatonis. (R.M. Soedarsono, 1998 : 39). persamaan primordialistik, akan tetapi Di samping memiliki kemampuan sudah bersifat terbuka. Diilhami oleh cita- dalam pengajaran, guru juga harus cita kebangkitan nasional dari tahun 1908, mengembangkan strategi belajar mengajar. pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Salah satu cara untuk membentuk karakter Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, peserta didik dalam pembelajaran sejarah yaitu -

Indonesian Heroic Songs in History Learning
2nd International Conference on History Education 2018 INDONESIAN HEROIC SONGS IN HISTORY LEARNING M. Maman Sumaludin, Didin Saripudin, Erlina Wiyanarti Post-Graduate Program of History Education, Indonesia University of Education, Bandung West Java, Indonesia [email protected] Abstract During the national movement until the revolutionary period in Indonesia, Indonesian heroic songs were created and became an important media in arousing the spirit of nationalism and patriotism in seizing and defending Indonesia's independence. However, recently, most of the students are not very familiar with it, and they have a lack of understanding of heroic songs that have historical values and the struggle of national values. The rise of contemporary songs that continue to erode the values of nationalism and patriotism, only prioritizing entertainment compared than the educational values. History learning has an important role in passing down the values of nationalism and patriotism, in this case, the use of Indonesian heroic songs in history learning. Thus, this research is descriptive qualitative research through literature study. It was conducted to develop history learning media. Also, it is hoped that it can be used as a material in implementing historical learning based on character/value so that the values of nationalism and patriotism can be embedded by singing and living the songs of heroic at every opportunity. Keywords: Indonesian heroic song, history learning, nationalism and patriotism Introduction should be passed down and embedded in every Nationalism and patriotism have been nation generation. However, as the times opened since the National movement period, changed, the sense of nationalism and around the beginning of the 20th century. -

SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY in the NEW ORDER a Thesis Presented to the Faculty of the Center for Inte
SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER A thesis presented to the faculty of the Center for International Studies of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Sony Karsono August 2005 This thesis entitled SETTING HISTORY STRAIGHT? INDONESIAN HISTORIOGRAPHY IN THE NEW ORDER by Sony Karsono has been approved for the Department of Southeast Asian Studies and the Center for International Studies by William H. Frederick Associate Professor of History Josep Rota Director of International Studies KARSONO, SONY. M.A. August 2005. International Studies Setting History Straight? Indonesian Historiography in the New Order (274 pp.) Director of Thesis: William H. Frederick This thesis discusses one central problem: What happened to Indonesian historiography in the New Order (1966-98)? To analyze the problem, the author studies the connections between the major themes in his intellectual autobiography and those in the metahistory of the regime. Proceeding in chronological and thematic manner, the thesis comes in three parts. Part One presents the author’s intellectual autobiography, which illustrates how, as a member of the generation of people who grew up in the New Order, he came into contact with history. Part Two examines the genealogy of and the major issues at stake in the post-New Order controversy over the rectification of history. Part Three ends with several concluding observations. First, the historiographical engineering that the New Order committed was not effective. Second, the regime created the tools for people to criticize itself, which shows that it misunderstood its own society. Third, Indonesian contemporary culture is such that people abhor the idea that there is no single truth. -

The Governments of Indonesia and Portugal- Recalling General
A/53/951 S/1999/513 English Page 4 Annex I Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor The Governments of Indonesia and Portugal- Recalling General Assembly resolutions 1514 (XV), 1541 (XV), 2625(XXV) and the relevant resolutions and decisions adopted by the Security Council and the General Assembly on the question of East Timor; Bearing in mind the sustained efforts of the Governments of Indonesia and Portugal since July 1983, through the good offices of the Secretary-General, to find a just, comprehensive and internationally acceptable solution to the question of East Timor; Recalling the agreement of 5 August 1998 to undertake, under the auspices of the Secretary-General, negotiations on a special status based on a wide-ranging autonomy for East Timor without prejudice to the positions of principle of the respective Governments on thefinal status of East Timor; Having discussed a constitutional framework for an autonomy for East Timor on the basis of a draft presented by the United Nations, as amended by the Indonesian Government; /... A/53/951 S/1999/513 English Page 5 Noting the position of the Government of Indonesia that the proposed special autonomy should be implemented only as an end solution to the question of East Timor with full recognition of Indonesian sovereignty over East Timor; Noting the position of the Government of Portugal that an autonomy regime should be transitional, not requiring recognition of Indonesian sovereignty over East Timor or the removal of East -

Nationalism and National Culture in Indonesian Art Music and Performances (1900-2018): Reflections from Postcolonial Perspectives
Nationalism and National Culture in Indonesian Art Music and Performances (1900-2018): Reflections from Postcolonial Perspectives Aniarani Andita 5837456 MA Thesis Musicology Utrecht University First Reader/Supervisor: Dr. Floris Schuiling Second Reader: Dr. Barbara Titus 2018 ABSTRACT Partha Chatterjee (1997) affirms that the attitude to modernity in formerly-colonized societies is always deeply ambiguous, because the modernity that the colonizers used as justification for colonialism also taught the colonized societies of its values. Indonesia is not an exception; having been colonized for centuries by a European nation, Indonesian nationalism arose from the desire for freedom from the colonizer. However, this nationalism, and the subsequent attempts for the creation of national culture has have always been replete with ambivalencies—with negotiations between the need to create a distinct national identity and the values of European cultures as imposed in the colonial time. This thesis looks at the discourses of nationalism, national culture, and national music in Indonesia since the beginning of the twentieth century to the present day, and examine its manifestations in the field of Indonesian art music and its performances by Indonesian symphony orchestras. I argue that these discourses and actions have always been embedded with a legacy of colonialism in the form of xenocentrism in its broad sense: the tendency among Indonesians to continue to concern about the Western others as they try to define their own identity and culture. Moreover, through case studies such as the compositions Varia Ibukota by Mochtar Embut and Suvenir dari Minangkabau by Arya Pugala Kitti, and the practices of contemporary symphony orchestras Gita Bahana Nusantara and Jakarta City Philharmonic, I employ postcolonial theories to view those works as reflections of the entanglement between colonial history and Indonesia-specific visions, as well as as endeavours to decolonize the knowledge of European classical music and performance form. -

Case Study on Bina Nusantara University Students of Alam Sutera Campus
Nationalism in the Perspective of Indonesia's Young Generation: Case Study on Bina Nusantara University Students of Alam Sutera Campus Petrus Hepi Witono1, Frederikus Fios2 1 Character Building Development Center, Industrial Engineering Department, School of Indutrial Engineering, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia, 11480 2 Character Building Development Center, Computer Science Department, School of Computer Science, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia, 11480 Keywords: Nationalism, young generation. Abstract: The discourse on nationalism is still interesting to discuss as it relates to the noble pride and dignity of the nation that we must accept in the reality of life. The concept of nationalism requires every individual as a citizen to have the attitude, perspective and firm belief in the future of young generation based on an understanding of what happened in the past and the present. Nationalism gives a distinct identity. When the younger generation does not care anymore about the future of the nation, the nation's nationalism is being eroded. The attitude of nationalism will encourage an individual to have a patriotic attitude as an expression of a high sense of love to his own homeland. The aim of this research is to know the quality of nationalism of Indonesian young generation and to reflect its concrete impact on the commitment of every individual as a young generation to live well as citizens of Indonesia. The research used qualitative method with interview and open question to 10 young generations (student of Bina Nusantara University of Alam Sutera Campus) as sample. The theoretical framework uses the thought of nationalism from Louis Snyder (1964). -

Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce
OnlineISSN:2249-4588 PrintISSN:0975-5853 DOI:10.17406/GJMBR EffectsoftheBankingSector FunctionsofStateCompanies FinancialSlack&FirmPerformance Privatization,FinancialLiberalization VOLUME18ISSUE7VERSION1.0 Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce Volume 18 Issue 7 (Ver. 1.0) Open Association of Research Society © Global Journal of Global Journals Inc. Management and Business (A Delaware USA Incorporation with “Good Standing”; Reg. Number: 0423089) Sponsors:Open Association of Research Society Research. 2018. Open Scientific Standards All rights reserved. This is a special issue published in version 1.0 Publisher’s Headquarters office of “Global Journal of Science Frontier Research.” By Global Journals Inc. Global Journals ® Headquarters All articles are open access articles distributed 945th Concord Streets, under “Global Journal of Science Frontier Research” Framingham Massachusetts Pin: 01701, Reading License, which permits restricted use. United States of America Entire contents are copyright by of “Global USA Toll Free: +001-888-839-7392 Journal of Science Frontier Research” unless USA Toll Free Fax: +001-888-839-7392 otherwise noted on specific articles. No part of this publication may be reproduced Offset Typesetting or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including Global Journals Incorporated photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without written 2nd, Lansdowne, Lansdowne Rd., Croydon-Surrey, permission. Pin: CR9 2ER, United Kingdom The opinions and statements made in this book are those of the authors concerned. Packaging & Continental Dispatching Ultraculture has not verified and neither confirms nor denies any of the foregoing and no warranty or fitness is implied. -

Eaton Dissertation
Governing Shōnan: The Japanese Administration of Wartime Singapore Clay Eaton Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2018 © 2018 Clay Eaton All rights reserved ABSTRACT Governing Shōnan: The Japanese Administration of Wartime Singapore Clay Eaton The Japanese military administration of Southeast Asia during the Second World War was meant to rebuild the prewar colonial system in the region under strong, centralized control. Different Japanese administrators disagreed over tactics, but their shared goal was to transform the inhabitants of the region into productive members of a new imperial formation, the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Shōnan, the wartime name for Singapore, was meant to be the center of this Co-Prosperity Sphere in Southeast Asia. It was the strategic fulcrum of the region, one of its most important ports, and a center of culture and learning for the wartime Japanese. Home to thousands of Japanese administrators during the war and a linguistically, ethnically, and religiously diverse local population, Shōnan was a site of active debates over the future of the Sphere. Three assumptions undergirded these discussions: that of Japanese preeminence within the Sphere, the suitability of “rule by minzoku (race)” for Southeast Asians, and the importance of maintaining colonial social hierarchies even as Japanese administrators attempted to put the region on a total war footing. These goals were at odds with each other, and Japanese rule only upended social hierarchies and exacerbated racial tensions. The unintended legacy of the wartime empire lay, not only in the new opportunities that Japanese rule afforded to Southeast Asian revolutionaries, but in the end of the politics of accommodation with imperial power practiced by prewar Asian elites. -
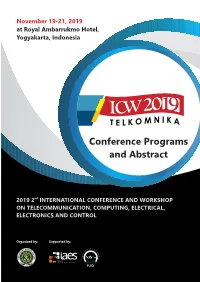
Conference Programs and Abstract
November 19-21, 2019 at Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia Conference Programs and Abstract 2019 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOP ON TELECOMMUNICATION, COMPUTING, ELECTRICAL, ELECTRONICS AND CONTROL Conference Programs And Abstract 2019 2nd International Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics, and Control (ICW-TELKOMNIKA 2019) 19-20 November 2019 YOGYAKARTA, INDONESIA Foreword from the Conference Chair Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To our distinguished guests, ladies, and gentlemen, Welcome to 2019 2nd International Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics, and Control (ICW-TELKOMNIKA 2019). We welcome all the attendees to Yogyakarta, the city of culture and education. ICW-TELKOMNIKA is an annual international conference and workshop where experts come to present and share their latest works in the field of telecommunication, computing, electrical, electronics, and control. This year’s conference theme is “Computational Intelligence Techniques in the Context of Industry 4.0: Present Findings & Future Directions for Living a Better Life”. In ICW-TELKOMNIKA 2019, only high quality selected papers are accepted to be presented. It was successfully held with the selected 173 papers among 475 submissions. Thus the acceptance rate was 36.4%. We would like to express our gratitude to all participants presenting your experiences in this vast conference. We are also thankful to all the international reviewers, steering committee, TPC members, and organizing a committee for their valuable work. We would like to give a compliment to all partners in publications and sponsorships for their valuable supports. We hope you enjoy your stay with us. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuryono Satya Widodo Anton Yudhana, Ph.D. -

Recollecting Resonances Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land En Volkenkunde
Recollecting Resonances Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde Edited by Rosemarijn Hoefte KITLV, Leiden Henk Schulte Nordholt KITLV, Leiden Editorial Board Michael Laffan Princeton University Adrian Vickers Sydney University Anna Tsing University of California Santa Cruz VOLUME 288 Southeast Asia Mediated Edited by Bart Barendregt (KITLV) Ariel Heryanto (Australian National University) VOLUME 4 The titles published in this series are listed at brill.com/vki Recollecting Resonances Indonesian–Dutch Musical Encounters Edited by Bart Barendregt and Els Bogaerts LEIDEN • BOSTON 2014 This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution‐Noncommercial 3.0 Unported (CC‐BY‐NC 3.0) License, which permits any non‐commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. The realization of this publication was made possible by the support of KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Cover illustration: The photo on the cover is taken around 1915 and depicts a Eurasian man seated in a Batavian living room while plucking the strings of his instrument (courtesy of KITLV Collec- tions, image 13352). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Recollecting resonances : Indonesian-Dutch musical encounters / edited by Bart Barendregt and Els Bogaerts. pages cm. — (Verhandelingen van het koninklijk instituut voor taal-, land en volkenkunde ; 288) (Southeast Asia mediated ; 4) Includes index. ISBN 978-90-04-25609-5 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-25859-4 (e-book) 1. Music— Indonesia—Dutch influences. 2. Music—Indonesia—History and criticism. 3. Music— Netherlands—Indonesian influences. -

CHAPTER 7 the Indonesian Massacres ROBERT CRIBB During
The Indonesian Massacres 289 CHAPTER 7 The Indonesian Massacres ROBERT CRIBB During the six-month period from October 1965 to March 1966, approximately half a million people were killed in a series of massacres in Indonesia. The victims were largely members of the Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia, PKI) which until that time had been the largest Communist Party in the non-Communist world. By 1965 it appeared to many observers inside and outside Indonesia that the Party was well-placed to come to power after President Sukarno‘s departure. The massacres followed an attempted coup d‘etat in the Indonesian capital, Jakarta, in which the PKI was implicated, at least in the public mind, by circumstance and vigorous military propaganda, and resulted in the Party‘s destruction. These massacres paved the way for the accession to power of a business-oriented and military-dominated government under General Suharto. Who Committed the Genocide? The Indonesian killings were the work of anti-Communist army units and civilian vigilantes, drawn especially, but by no means exclusively, from religious political parties. Both groups brought to the killing a long-standing hatred of Communism. The army‘s hostility dated from the years of armed struggle against the Dutch (1945–1949), when Communist influence had been strong both within army units and among independent irregular troops, or lasykar. The professional soldiers who soon struggled through and up into the top military positions resented both Party influence in the junior ranks and the independent Communist units that challenged their monopoly of armed force. Resentment had become alarm when the crypto- Communist Defense Minister Amir Syarifuddin attempted to introduce political commissars into army units in 1946. -

14415 Wijayanti 2020 E.Docx
International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 14, Issue 4, 2020 Nation Building in Southeast Asia: A Comparative Study Yeni Wijayantia, Yat Rospia Bratab, Hieronymus Purwantac, a,bDepartment of History Education, Galuh University, cDepartment of History Education, Sebelas Maret University, Email: c*[email protected] This article aims to compare the efforts among Southeast Asian countries in nation-building. Each country has its uniqueness in developing its national identity. Countries in Southeast Asia conducted several methods, such as cultural, linguistic, and educational approaches. This study uses the Critical Discourse Analysis (CDA). Data collection was carried out by a documentary study. Data analysis is implemented by interrelating the three-dimensional analysis process, namely analysing the text verbally and visually, analysing the process of the text production, and analysing the historical and social conditions that influence it. The findings show that countries in Southeast Asia carried out nation-building under different approaches, namely, cultural, linguistic, and educational approaches. Key words: Nation-building, Southeast Asia, comparison, culture, language, education. Introduction Nation-building is the process of developing citizenship, so there are many similarities, such as shared interests, goals, and preferences. The similarities become a power that can reduce dispute and develop civic life toward national integration (Alesina, & Bryony Reich, 2015; Blackburn, 2010). Historically, there was a similarity of fate that occurred during the emergence of nationalism in the early 20th century (Susanto, 2016). Various ethnicities had the same fate as colonised countries, which led them to fight colonialism and build independent and sovereign nation-states (Renan, 1882).