Cover Prosiding Acsj 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
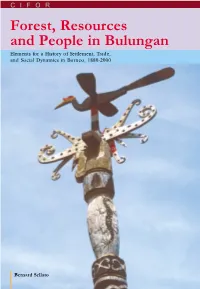
Forest, Resources and People in Bulungan Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000
CIFOR Forest, Resources and People in Bulungan Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000 Bernard Sellato Forest, Resources and People in Bulungan Elements for a History of Settlement, Trade and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000 Bernard Sellato Cover Photo: Hornbill carving in gate to Kenyah village, East Kalimantan by Christophe Kuhn © 2001 by Center for International Forestry Research All rights reserved. Published in 2001 Printed by SMK Grafika Desa Putera, Indonesia ISBN 979-8764-76-5 Published by Center for International Forestry Research Mailing address: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia Office address: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100 E-mail: [email protected] Web site: http://www.cifor.cgiar.org Contents Acknowledgements vi Foreword vii 1. Introduction 1 2. Environment and Population 5 2.1 One Forested Domain 5 2.2 Two River Basins 7 2.3 Population 9 Long Pujungan District 9 Malinau District 12 Comments 13 3. Tribes and States in Northern East Borneo 15 3.1 The Coastal Polities 16 Bulungan 17 Tidung Sesayap 19 Sembawang24 3.2 The Stratified Groups 27 The Merap 28 The Kenyah 30 3.3 The Punan Groups 32 Minor Punan Groups 32 The Punan of the Tubu and Malinau 33 3.4 One Regional History 37 CONTENTS 4. Territory, Resources and Land Use43 4.1 Forest and Resources 44 Among Coastal Polities 44 Among Stratified Tribal Groups 46 Among Non-Stratified Tribal Groups 49 Among Punan Groups 50 4.2 Agricultural Patterns 52 Rice Agriculture 53 Cash Crops 59 Recent Trends 62 5. -

Seeking the State from the Margins: from Tidung Lands to Borderlands in Borneo
Seeking the state from the margins From Tidung Lands to borderlands in Borneo Nathan Bond ORCID ID: 0000-0002-8094-9173 A thesis submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. December 2020 School of Social and Political Sciences The University of Melbourne i Abstract Scholarship on the geographic margins of the state has long suggested that life in such spaces threatens national state-building by transgressing state order. Recently, however, scholars have begun to nuance this view by exploring how marginal peoples often embrace the nation and the state. In this thesis, I bridge these two approaches by exploring how borderland peoples, as exemplars of marginal peoples, seek the state from the margins. I explore this issue by presenting the first extended ethnography of the cross-border ethnic Tidung and neighbouring peoples in the Tidung Lands of northeast Borneo, complementing long-term fieldwork with research in Dutch and British archives. This region, lying at the interstices of Indonesian Kalimantan, Malaysian Sabah and the Southern Philippines, is an ideal site from which to study borderland dynamics and how people have come to seek the state. I analyse understandings of the state, and practical consequences of those understandings in the lives and thought of people in the Tidung Lands. I argue that people who imagine themselves as occupying a marginal place in the national order of things often seek to deepen, rather than resist, relations with the nation-states to which they are marginal. The core contribution of the thesis consists in drawing empirical and theoretical attention to the under-researched issue of seeking the state and thereby encouraging further inquiry into this issue. -

Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically by Region
Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically by Region Region: Africa Egypt Location Place Alternative Name Cairo Saladin Citadel of Cairo Coordinates (lat/long):30.026608 31.259968 Accurate?Y Letters sent: 1 recieved:0 total: 1 Ethiopia Abyssinia Location Place Alternative Name Addis Ababa Coordinates (lat/long):8.988611 38.747932 Accurate?N Letters sent: 1 recieved:2 total: 3 Gondar Fasil Ghebbi Coordinates (lat/long):12.608048 37.469666 Accurate?Y Letters sent: 2 recieved:2 total: 4 South Africa Location Place Alternative Name Cape of Good Hope Castle of Good Hope Coordinates (lat/long):-33.925869 18.427623 Accurate?Y Letters sent: 9 recieved:0 total: 9 The castle was were most political exiles were kept Robben Island Robben Island Cape Town Coordinates (lat/long):-33.807607 18.371231 Accurate?Y Letters sent: 1 recieved:0 total: 1 Region: East Asia www.sejarah-nusantara.anri.go.id - ANRI TCF 2015 Page 1 of 44 Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically by Region China Location Place Alternative Name Amoy Xiamen Coordinates (lat/long):24.479198 118.109207 Accurate?N Letters sent: 8 recieved:3 total: 11 Beijing Forbidden city Coordinates (lat/long):39.917906 116.397032 Accurate?Y Letters sent: 11 recieved:7 total: 18 Canton Guagnzhou Coordinates (lat/long):23.125598 113.227844 Accurate?N Letters sent: 7 recieved:4 total: 11 Chi Engling Coordinates (lat/long):23.646272 116.626946 Accurate?N Letters sent: 1 recieved:0 total: 1 Geodata unreliable Fuzhou Coordinates (lat/long):26.05016 119.31839 Accurate?N Letters sent: 32 -

Multicultural Narratives in Indonesian Education Historiography: Study Discourse-Historical Approach History Textbook of Senior High School
The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) Multicultural Narratives in Indonesian Education Historiography: Study Discourse-Historical Approach History Textbook of Senior High School Akhmad Dwi Afiyadi, Leo Agung S, Sunardi Department of History Education, Sebelas Maret University, Solo, Indonesia Correspondence: [email protected] Abstract: This research tries to trace the multicultural narrations produced by government through textbooks of history lesson (high school) as compulsory subjects. This research is based on the theory of multiculturalism which states that multiculturalism is the recognition of cultural diversity including ethnic, religious, racial and intergroup diversity. On the other hand this articles attempts to look at the multicultural narrations produced by the government in the textbooks of historical pursuits and the political context of education in the production of multicultural narratives. The multicultural narratives described in the textbook of the history lessons ideally depict the territory of Indonesia which has a diversity of tribes, religions, race and groups. The result of this study are expected to find whether the narrative textbooks of history lessons have revealed historical facts that reflect the diversity of Indonesian society and see how the political context of education, whether to position the textbook as a way of controlling the official historical narratives that students, educators and policy makers education. Keywords: [Multicultural Narratives, History Textbook, Discourse-Historical Approach, Education Historiography] 1. INTRODUCTION not be separated from the political interests of the government. State political conditions The lesson of history is the lessons affect the curriculum and textbook material. taught at the school from the elementary to This is because history textbooks in schools the secondary level. -
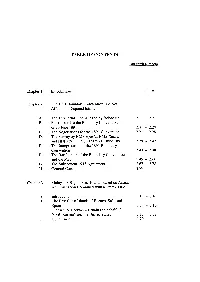
Table of Contents
TABLE OF CONTENTS Paragraoh numbers Chapter 1 Introduction 1.1 - 1.10 Chapter 2 The 1891 Boundary Convention Did Not Affect the Disputed Islands The Territorial Title Alleged by Indonesia Background to the Boundary Convention of 20 June 189 1 The Negotiations for the 189 1 Convention The Survey by HMS Egeria, HMS Rattler and HNLMS Banda, 30 May - 19 June 1891 The Interpretation of the 189 1 Boundary Convention The Ratification of the Boundary Convention and the Map The Subsequent 19 15 Agreement General Conclusions Chapter 3 Malaysia's Right to the Islands Based on Actual Administration Combined with a Treaty Title A. Introduction 3.1 - 3.4 B. The East Coast Islands of Borneo, Sulu and Spain 3.5 - 3.16 C. Transactions between Britain (on behalf of North Borneo) and the United States 3.17 - 3.28 D. Conclusion 3.29 Chapter 4 The Practice of the Parties and their Predecessors Confirms Malaysia's Title A. Introduction B. Practice Relating to the Islands before 1963 C. Post-colonial Practice D. General Conclusions Chapter 5 Officia1 and other Maps Support Malaysia's Title to the Islands A. Introduction 5.1 - 5.3 B. Indonesia's Arguments Based on Various Maps 5.4 - 5.30 C. The Relevance of Maps in Determining Disputed Boundaries 5.31 - 5.36 D. Conclusions from the Map Evidence as a Whole 5.37 - 5.39 Submissions List of Annexes Appendix 1 The Regional History of Northeast Bomeo in the Nineteenth Century (with special reference to Bulungan) by Prof. Dr. Vincent J. H. Houben Table of Inserts Insert Descri~tion page 1. -

CR 2002/30 International Court Cour Internationale of Justice De Justice
CR 2002/30 International Court Cour internationale of Justice de Justice THE HAGUE LA HAYE YEAR 2002 Public sitting held on Thursday 6 June 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding, in the case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) ____________________ VERBATIM RECORD ____________________ ANNÉE 2002 Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) ________________ COMPTE RENDU ________________ - 2 - Present: President Guillaume Vice-President Shi Judges Oda Ranjeva Herczegh Fleischhauer Koroma Vereshchetin Higgins Parra-Aranguren Kooijmans Rezek Al-Khasawneh Buergenthal Elaraby Judges ad hoc Weeramantry Franck Registrar Couvreur ¾¾¾¾¾¾ - 3 - Présents : M. Guillaume, président M. Shi, vice-président MM. Oda Ranjeva Herczegh Fleischhauer Koroma Vereshchetin Mme Higgins MM. Parra-Aranguren Kooijmans Rezek Al-Khasawneh Buergenthal Elaraby, juges MM. Weeramantry Franck, juges ad hoc M. Couvreur, greffier ¾¾¾¾¾¾ - 4 - The Government of the Republic of Indonesia is represented by: H. E. Dr. N. Hassan Wirajuda, Minister for Foreign Affairs, as Agent; H. E. Mr. Abdul Irsan, Ambassador of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands, as Co-Agent; Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, Member and former Chairman of the International Law Commission, Mr. Alfred H. A. Soons, Professor of Public International Law, Utrecht University, Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of International Law, Mr. Rodman R. -

Proposal Submit PHP2D 2021
Lampiran Surat Nomor : 2101/E2/KM.09.01/2021 Tanggal : 15 Mei 2021 Daftar Tim Lolos Seleksi Administrasi No Perguruan Tinggi Ketua Organisasi Mahasiswa Judul Proposal 1 Universitas Karyadarma Kupang JULIUS JOHNELDITH LADI UKM Undarma Kupang PERTANIAN TERPADU ZERO WASTE DI DESA PUKDALE KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 2 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu NABILA VERONIKA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Budidaya Lele dengan Keramba Jaring Menggunakan Inovasi Pakan dari Maggot Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat selama Pandemi Covid 19 di Desa Pendidikan Al Maksum Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat. 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nyoman Mega Fridayanti UKM Peduli Lingkungan DESA BINAAN BERBASISKAN EKOWISATA UNTUK MEWUJUDKAN DESA LEMUKIH MENJADI DESA WISATA ALAM SAPTA PESONA DENGAN Buleleng PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA DAN KELOMPOK SADAR WISATA (DARWIS) 4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ni Kadek Pebri Dwi Ariastuti UKM Catur DESA BINAAN BERBASISKAN WISATA BAHARI DENGAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN KREATIF DESA SANGSIT, KECAMATAN Buleleng SAWAN, KABUPATEN BULELENG 5 Universitas Dr Soetomo MUHAMMAD FAHRIZAL Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) PEMANFAATAN TERAS RUMAH MENJADI MEDIA PENANAMAN TOGA (TANAMAN OBAT RUMAH TANGGA) SEBAGAI TERAPI PSIKOLOGI BAGI KHOIRONI PENYINTAS COVID-19 PADA WARGA DESA SAWOTRATAP, KECAMATAN GEDANGAN, SIDOARJO 6 Universitas KH. Bahaudin Mudhary Musfik HMJ-MANAJEMEN UNIBA MADURA POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUKIT PAKES DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBUATAN BUSSINES AREA MENJADI Madura SUMENEP CAFE -

Socio-Cultural Structure of Transmigrant Communities in the Salimbatu Area for Accelerating Regional Development of Bulungan Regency, Indonesia
E3S Web of Conferences 211, 01006 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101006 The 1st JESSD Symposium 2020 Socio-cultural structure of transmigrant communities in the Salimbatu Area for accelerating regional development of Bulungan Regency, Indonesia Sindhung Wardana1, Hayati Sari Hasibuan1, and Herdis Herdiansyah1* 1School of Environmental Science, Universitas Indonesia, Central Jakarta 10430, Indonesia Abstract. Bulungan Regency as the capital of North Kalimantan Province needs accelerated development to realize its vision as an industrial-based food center. Among the aspects that still need to be worked out are the availability of human resources (HR) as the main driver of the regional economy. It is hoped that the presence of the Transmigrant Community with an agricultural background in the Salimbatu area can make a positive contribution to efforts to accelerate development in Bulungan Regency. By using a combination of literature review study methods reinforced with GIS analysis, this study seeks to reveal the socio-cultural structure of the people in the Salimbatu Transmigration Area and its contribution to improving the agricultural sector to accelerate regional development. The results obtained from this study indicate that the presence of the Transmigrant Community in the Salimbatu area has a proportion where 54.35% of them are native Bulungan people, while the remaining 45.65% are migrants through the Transmigration program. The socio-cultural proportion of the peasant community through the transmigration program to strengthen the regional economy in the agricultural sector in Bulungan Regency currently has not had an optimal impact. 1 Introduction Equitable development between rural and urban areas is very important in reducing inequality in Indonesia [1]. -
Environmental Factors Affect the Evolution of Linguistic Subgroups in Borneo
Environmental factors affect the evolution of linguistic subgroups in Borneo Alexander D. Smith1 and Taraka Rama1 1Department of Linguistics, University of North Texas, Denton, TX, USA Abstract This study investigates the relatedness and history of the Austronesian languages of Bor- neo, which is the third largest island in the world and home to significant linguistic diversity. We apply Bayesian phylogenetic dating methods to lexical cognate data based on four histor- ical calibration points to infer a dated phylogeny of 87 languages. The inferred tree topology agrees with the mid and lower-level subgrouping proposals based on the classical compara- tive method, but suggests a different higher-level organization. The root age of the dated tree is shallower than the archaeological estimates but agrees with a hypothesis of a past linguistic leveling event. The inferred homelands of the major linguistic subgroups from a Bayesian phylogeographic analysis agree with the homeland proposals from archaeology and linguistics. The inferred homeland for four of the eight subgroups support the riverine home- land hypothesis whereby the major linguistic subgroups developed initially in communities situated along Borneo's major rivers. Keywords: Bayesian Phylogenetics, Homeland, Austronesian, Borneo 1 Introduction Borneo lies at a cross-roads in Island Southeast Asia (ISEA). The island sits on the easternmost extension of the Sunda Shelf, a part of the Southeast Asian continental shelf that connects the large Greater Sunda Islands to Mainland Southeast Asia during periods of glacial expansion and low sea-levels. Although humans have occupied this area for tens of thousands of years, the current dominant ethno-linguistic group in ISEA only reached Borneo in the last 4,000 years as a result of the Austronesian expansion out of Taiwan, into the Philippines, and beyond [Bellwood, 2007, Blust, 1985-86]. -

Overview of Diplomatic Letters
Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically and Chronologically by Diplomat Region: Africa Egypt Location: Cairo Diplomat Name Alternative names Hekimo ğlu Ali Pasha Grand Vizier Hekimo ğlu Ali Pasha Period (from/to): 1756- 1757 Historically known?Y Number of letters: 1 Ethiopia Location: Addis Ababa Diplomat Name Alternative names Iyasu I Joshua I Period (from/to): 1682- 1706 Historically known?Y Number of letters: 3 Location: Gondar Diplomat Name Alternative names Yohannes I A'ilaf Sagad Period (from/to): 1667- 1682 Historically known?Y Number of letters: 1 South Africa Location: Cape of Good Hope Diplomat Name Alternative names Sultan Abdul Bashir (exile) Period (from/to): 1700- 1701 Historically known?Y Number of letters: 2 www.sejarah-nusantara.anri.go.id - ANRI TCF 2015 Page 1 of 224 Overview of Diplomatic Letters Listed Geographically and Chronologically by Diplomat Raden Suryakasuma Saloringpasar Period (from/to): 1722- 1726 Historically known?N Number of letters: 5 Not to be confused with the son of Pakubuwono I Son of Damala Daeng Mamongon Period (from/to): 1741- 1741 Historically known?N Number of letters: 1 Kaicili Putra Ahmad Period (from/to): 1786- 1786 Historically known?N Number of letters: 1 Location: Robben Island Diplomat Name Alternative names Raja Christofeel Manoppo Raja Bolaang Period (from/to): 1773- 1773 Historically known?N Number of letters: 1 Region: East Asia China Location: Amoy Diplomat Name Alternative names Bu Yuan of Xiamen Period (from/to): 1688- 1688 Historically known?N Number of letters: 2 -

AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 1, Maret 2017
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 1, Maret 2017 STRATEGI KESULTANAN BULUNGAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR 1945-1950 MENTARI Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya E-Mail: [email protected] Wisnu Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Abstrak Berita tentang kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah sampai di pemerintahan kesultanan Bulungan. Akan tetapi kesultanan Bulungan tidak bisa menentukan sikap, sebab segala bentuk keamanan baik sipil maupun militer telah dikuasai oleh NICA (Belanda). Pihak Belanda kembali menanamkan pengaruh kekuasaanya di wilayah Kesultanan Bulungan. Adapun upaya dari pihak NICA (Belanda) untuk menandingi negara Republik Indonesia dengan membentuk suatu bentuk tatanan pemerintahan baru yakni berbentuk federal yang terdiri atas wilayah Kalimantan dan Timur Besar bernama RIS (Republik Indonesia Serikat). Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengapa Sultan Bulungan lebih memilih bergabung dengan pihak Republik Indonesia dibandingkan pihak Belanda dan bagaimana strategi kebijakan politik Sultan Bulungan terhadap pemerintah RI dan pemerintah Belanda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan alasan mengapa Sultan Bulungan lebih memilih bergabung dengan Pemerintah RI dibandingkan pihak Belanda dan menjelaskan bagaimana strategi kebijakan politik yang diambil Sultan Bulungan terhadap pemerintah RI dan Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu, heuristik, kritik sumber, Interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah Kesultanan Bulungan memutuskan berpihak kepada RI sebab sikap kesewenang-wenangan Belanda dalam setiap pengambilan kebijakan lebih banyak merugikan Kesultanan Bulungan. Pungutan pajak memberatkan masyarakat, hingga menimbulkan pergolakan sebagai bentuk protes terhadap Belanda. -

International Court of Justice Year 2002 2002 17
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE YEAR 2002 2002 17 December General List No. 102 17 December 2002 CASE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN (INDONESIA/MALAYSIA) Geographical context ¾ Historical background ¾ Bases on which the Parties found their claims to the islands of Ligitan and Sipadan. * * Conventional title asserted by Indonesia (1891 Convention between Great Britain and the Netherlands). Indonesia’s argument that the 1891 Convention established the 4° 10' north parallel of latitude as the dividing line between the respective possessions of Great Britain and the Netherlands in the area of the disputed islands and that those islands therefore belong to it as successor to the Netherlands. Disagreement of the Parties on the interpretation to be given to Article IV of the 1891 Convention ¾ Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties reflect international customary law on the subject. Text of Article IV of the 1891 Convention ¾ Clause providing “From 4° 10' north latitude on the east coast the boundary-line shall be continued eastward along that parallel, across the Island of Sebittik . .” ¾ Ambiguity of the terms “shall be continued” and “across” ¾ Ambiguity which could have been avoided had the Convention expressly stipulated that the 4° 10' north parallel constituted the line separating the islands under British sovereignty from those under Dutch sovereignty ¾ Ordinary meaning of the term “boundary”. - 2 - Context of the 1891 Convention ¾ Explanatory Memorandum appended to the draft Law