Profil Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Katalog-Lontar-2019 Prev.Pdf
2019 LONTAR CATALOGUE 2019 THE LONTAR FOUNDATION Since its establishment in 1987, the Lontar Foundation of Jakarta has carried on its shoulders the mission of improving international awareness of Indonesian literature and culture, primarily throught the publication of Indonesian literary translations. Lontar’s Publications Division, the backbone of the organization, has the significant task of determining which literary works are to be translated so as to reflect Indonesia’s cultural wealth. The Lontar Foundation publishes books under four imprints: Lontar, BTW, Amanah, and Godown. All titles released prior to 2002 (when Godown and Amanah were established) carried the Lontar imprint. TABLE OF CONTENTS Titles released under the Lontar imprint are primarily translations of Indonesian literature. (Exceptions include large-format books that embody Lontar’s mission of enhancing international knowledge of Indonesian culture.) Most Lontar titles are intended for general THE LONTAR FOUNDATION AND ITS IMPRINTS i reading pleasure and for use in teaching courses on Indonesian literature and culture. Lontar TITLES 2 The Modern Library of Indonesia 2 Historical Anthologies 11 Titles in the BTW series—with “BTW” standing for “by the way,” as Other Literary Translations 13 in “by the way, have you heard about such and such an author?”— Special Publications 15 feature work by new and emerging Indonesian writers. This series of Wayang Educational Package 16 mini-books is aimed at publishers, editors, and literary critics. BTW BOOKS SERIES #1 18 Under its Amanah imprint, Lontar publishes Indonesian-language BTW BOOKS SERIES #2 23 titles that Lontar itself has put together in the course of developing an English-language publication. -

Makkunrai” Karya Lily Yulianti Farid
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” GENDER INEQUALITY DALAM ”MAKKUNRAI” KARYA LILY YULIANTI FARID Maria Josephine Mantik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia [email protected] Abstrak Pemahaman akan konsep gender sangatlah diperlukan dalam menganalisis suatu masyarakat atau kelompok etnis. Perspektif gender diperlukan untuk menggali persoalan-persoalan tentang ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam cerita pendek ”Makkunrai” karya Lily Yulianti Farid. Dalam analisis gender, terdapat kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequality) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Analisis gender yang dilakukan, pada umumnya berupaya untuk memahami pokok persoalan ketimpangan relasi gender, yakni pada sistem dan struktur sosial yang tidak adil yang merugikan kaum perempuan. Dalam cerpen yang berjudul Makkunrai (bahasa Bugis = perempuan) karya Lily Yulianti Farid, tokoh Aku yang adalah seorang perempuan merasakan perbedaan perilaku masyarakat (Bugis/Makasar) terhadap kaum laki- laki dan perempuan. Sejak lahir, tokoh Aku harus hidup dalam dominasi laki-laki. Sejak lahir, tokoh Aku sudah tidak dikehendaki oleh keluarga besar, ia adalah perempuan. Peran perempuan berada di bawah kekangan dominasi harta dan kekuasaan, sehingga ia harus menuruti keinginan masyarakat patrilineal di segala bidang, termasuk dalam penentuan teman hidup yang akan dijalaninya sampai mati. Perilaku kakek, yang merelakan istrinya menderita, bahkan harus mati karena menahan perasaan karena tidak mau diduakan, menjadi mercu suar bagi tokoh Aku yang akhirnya memberanikan diri untuk melepaskan diri dari masyarakatnya. Kata Kunci: gender inequality, masyakat Bugis, peran perempuan, dominasi laki-laki, kekuasaan. A. Pendahuluan Makkunrai. Perempuan. Pembahasan mengenai peran dan kedudukan perempuan seolah tidak ada habisnya. Meskipun Tuhan menciptakan makhluknya laki- laki dan perempuan dalam posisi yang sama, namun kenyataan berkata lain. -
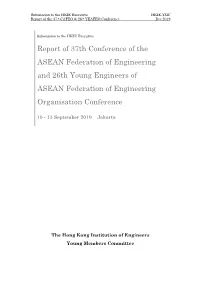
Report of 37Th Conference of the ASEAN Federation of Engineering and 26Th Young Engineers of ASEAN Federation of Engineering Organisation Conference
Submission to the HKIE Executive HKIE-YMC Report of the 37th CAFEO & 26th YEAFEO Conference Dec 2019 Submission to the HKIE Executive Report of 37th Conference of the ASEAN Federation of Engineering and 26th Young Engineers of ASEAN Federation of Engineering Organisation Conference 10 - 13 September 2019 Jakarta The Hong Kong Institution of Engineers Young Members Committee Submission to HKIE Executive HKIE-YMC Report of the 37th CAFEO & 26th YEAFEO Conference Dec 2019 Contents 1. Introduction ................................................................................................................. 1 1.1 Background ............................................................................................................. 1 1.2 Objectives ................................................................................................................ 3 2. YEAFEO Meeting ........................................................................................................ 4 2.1 Country Report ..................................................................................................... 4 2.2 YEAFEO Governing Board Meeting ................................................................. 5 3. Sustainability Forum ................................................................................................. 6 3.1 Energy ...................................................................................................................... 6 3.2 LinkAja ................................................................................................................... -

Time Project Event Unite the Nations 3 May 2011
Time Project Event 2011 May 3rd 2011 TIME PROJECT EVENT UNITE THE NATIONS 3 MAY 2011 Short instruction: 1) How many questions do I have to answer? There are 250 questions. Every Country has 25 questions. Every school HAS to answer 225 questions, which means you do not ANSWER THE 25 questions FROM YOUR OWN COUNTRY. For example: Russia: There are 25 questions about Russia. More than one school from Rusia contributed questions which means there may be some Russian questions some Russian students may not recognize (they came from the other school ). Schools from Russia do not answer the 25 questions about Russia regardless of who contributed the questions. You never answer the questions about YOUR OWN COUNTRY. 2) How do I find the answers? - Encyclopaedias, the Internet, the Library or other sources at school or in the community - Get in touch with other time participants to find answers to questions which are difficult for you. 3) Where and when do I send the answers? Questions have to answered on line at the ZOHO Challenge Site. https://challenge.zoho.com/unite_the_nations_2011 Test starts 00:00 GMT May 3rd 2011 - Deadline: 00:00 GMT/UTC 4 May 2011! Other questions?? Get in touch with Event Co-ordinator ! [email protected] phone: +01.519.452.8310 cellphone +01.519.200.5092 fax: +01.519.452. 8319 And now…the game! Time Project Event 2011 May 3rd 2011 ARTS Argentina 1) Who wrote the book "Martin Fierro"? a) Jose Hernandez b) Peschisolido miguel angel c) David vineyards d) Jorge Luis Borges 2) What is the typical dance of Argentina? a) quartet b) tango c) cumbia d) capoeira 3) Who was Carlos Gardel? a) a singer of cumbia b) a soccer player c) a singer of tango d) a former president 4) Who was Lola Mora? a) a model b) a sculptor c) an athlete d) a journalist 5) Which Argentine made and released the world's first animated feature film. -

Diplomasi Kebudayaan Indonesia Di Eropa Melalui Europalia 2017
DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA DI EROPA MELALUI EUROPALIA 2017 Disusun oleh: Bimo Aryo Wibowo 11141130000087 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2020 i iii PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI SKRIPSI DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA DI EROPA MELALUI EUROPALIA 2017 Oleh Bimo Aryo Wibowo 11141130000087 Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional. Ketua, Sekretaris, Muhammad Adian Firnas, S.IP, M.Si Irfan Hutagalung, SH, LLM NIDN. 0305077401 NIDN. 2024057002 Penguji I, Penguji II, Eva Mushoffa, MA Inggrid Galuh, MHSPS NIDN. 2016077702 NIDN. 9920112884 Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 24 Agustus 2020. Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta Muhammad Adian Firnas, S.IP, M.Si NIDN. 0305077401 ABSTRAK Skripsi ini menganalisa mengenai diplomasi kebudayaan dan kepentingan nasional Indonesia terhadap negara di kawasan Eropa terutama Brussel dengan diplomasi kebudayaan Indonesia melalui festival Europalia 2017. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepentingan nasional Indonesia dalam festival Europalia 2017 kemarin secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan mengapa Indonesia mau melakukan diplomasi kebudayaannya ke Eropa melalui festival pagelaran seni dan kebudayaan Europalia 2017.Penelitian ini, diambil pada masa Presiden Joko Widodo di periode pertamanya 2014-2019. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode kualitatif, dengan didukungnya pengumpulan data-data informasi yang berupa data primer, dan sumber data sekunder. -

Download The
CSEASPANORAMA2008 A (Balinese) Tempest Ian Falconer (MA, Asian Studies) starred as Prospero in the Department of Theatre and Dance’s version of the Bard’s lauded comedy, a performance infused with Balinese wayang and gamelan and Larry Reed’s famed shadowcasting. Center for Southeast Asian Studies University of Hawai‘i By Director Barbara Watson Andaya Dear friends and including the highlight of the Prospero, Miranda, Ariel and year, the Balinese shadow-play Caliban were given a new life as colleagues... version of Shakespeare’s The the shadows of human “puppets” In late July 2008, when I re- Tempest. Under the auspices of wearing specially made masks turned from twelve months’ the Department of Theatre and were projected onto a large sabbatical leave, I began to ask Dance, Kirstin invited Larry screen. And the “Southeast myself if my presence as director Reed, founder and artistic Asian” content was not merely was really necessary. So much had director of Shadowlight Produc- visual, for an important feature of CSEAS Panorama (Vol. XII) is published been accomplished in my absence tions and one of the few the production was the music annually by the Center Americans trained in wayang kulit, provided by the University of for Southeast Asian that I really felt quite dispensable! Studies at the or shadow puppetry, to spend a Hawai‘i Balinese Gamelan University of Hawai‘i. I would like to express my deep gratitude to Acting Director semester in Hawai‘i. Larry and Ensemble directed by a second For more information about the program, Kirstin Pauka (Professor, Asian Kirstin worked with students in artist-in-residence, Balinese please visit the Theatre and Dance to produce a puppet master, I Nyoman Center’s website at Theatre), Associate Director Paul www.hawaii.edu/cseas Rausch, and our graduate assis- memorable and innovative Sumandhi. -

Multimedia, Mobility and the Digital Southeast Asian Family a Two-Day Workshop 20-21 April 2017 Melbourne, Australia
Multimedia, Mobility and the Digital Southeast Asian Family A Two-Day Workshop 20-21 April 2017 Melbourne, Australia Funded by: . Migration and Mobilities Cluster, Transforming Human Societies Research Focus Area, La Trobe University, Australia . Social Sciences and Humanities Research Council of Canada . La Trobe Asia, La Trobe University, Australia . Centre for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria, British Columbia, Canada Program Southeast Asia is home to the largest number of social media users globally. Digital technology is shaping the way Southeast Asians interact, maintain contact, and express who they are, their family relationships. It is also a region known for its mobile population with high numbers of overseas workers, international students, refugees/asylum seekers, and migrants seeking permanent residency or citizenship in other countries. Online multimedia content is one way that migrants and mobile Southeast Asians express their sense of connectedness to their family members, belonging, multiple and varied identities, and cultural backgrounds. This two-day workshop of 13 presentations and 20 participants aims to provide a contemporary understanding of online multimedia expression of identity, belonging, and intergenerational family relationships of migrants and mobile subjects of Southeast Asian descent. What do these online multimedia production and stories tell us about the effects of migration and mobility on family intergenerational relationships, that of children, parents, grandparents, and extended kin networks? By focusing on online multimedia expression of Southeast Asians, we aim to comprehend social and cultural change in this region and beyond, that is shaped by digital technology, and particularly in relation to issues of identity, belonging and family relationships. In addition, we are interested in exploring the nuances of how technology shapes this process of change, including addressing a wider range of issues beyond connectedness such as power, conflict, and kinship relations. -
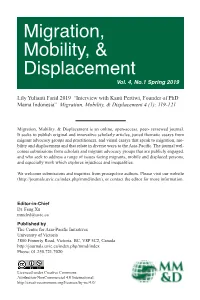
Migration, Mobility, & Displacement
Migration, Mobility, & Displacement Vol. 4, No.1 Spring 2019 Lily Yulianti Farid 2019 “Interview with Kanti Pertiwi, Founder of PhD Mama Indonesia” Migration, Mobility, & Displacement 4 (1): 119-121 Migration, Mobility, & Displacement is an online, open-access, peer- reviewed journal. It seeks to publish original and innovative scholarly articles, juried thematic essays from migrant advocacy groups and practitioners, and visual essays that speak to migration, mo- bility and displacement and that relate in diverse ways to the Asia-Pacific. The journal wel- comes submissions from scholars and migrant advocacy groups that are publicly engaged, and who seek to address a range of issues facing migrants, mobile and displaced persons, and especially work which explores injustices and inequalities. We welcome submissions and inquiries from prosepctive authors. Please visit our website (http://journals.uvic.ca/index.php/mmd/index), or contact the editor for more information. Editor-in-Chief Dr. Feng Xu [email protected] Published by The Centre for Asia-Pacific Initiatives University of Victoria 3800 Finnerty Road, Victoria, BC, V8P 5C2, Canada http://journals.uvic.ca/index.php/mmd/index Phone: 01.250.721.7020 Licenced under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Interview with Kanti Pertiwi, Founder of PhD Mama Indonesia Lily Yulianti Farid Lily Yulianti Farid interviewed Dr. Kanti Pertiwi, founder of the PhD Mama Indonesia online forum (www.phdmamaindonesia.com). Dr. Pertiwi received her PhD from the Faculty of Business and Economics at the University of Melbourne in 2017. She is a mother of three daughters and a lecturer in the Faculty of Economics at the University of Indonesia. -

A Message from the Festival Director
1 A Message from the Festival Director The Emerging Writers’ Festival has always been a festival for writers. Inspiring, informing and connecting writers of all kinds and at all stages of their career – that’s what we do. In our 2012 festival you will find events programmed with writers in mind. Our two-day Town Hall Writers’ conference continues to grow, with over 80 exciting writers ready to discuss the art and craft of being a writer. We have also introduced a new panel series aimed at demystifying the sometimes confusing publishing world, our Industry Insider discussion sessions. Page Parlour indie press fair will be complemented by Future Bookshop, an interactive exhibition at the National Gallery of Victoria. Plus there will be plenty of time for fun and frolics at our Revenge of the Nerds Slide Night, closing night Spelling Bee and atmospheric Fright Night storytelling event. This year our program features more ways than ever to come along and engage with the festival and network with other writers. Our Festival Hub Rue Bebelons will once again be the place to be – look out for the Late Night Book Clubs! – or you can write up a storm in our Rabbit Hole writing frenzy, join our first-ever Festival Open Mic, or jump online and explore our EWFdigital events. Yup, when we say we’re the festival for writers, we really mean it. Of course, the Festival is just one part in our broader mission to create opportunities for emerging writers. This year we are incredibly excited to present the Monash University Undergraduate Prize for Creative Writing, a prestigious new literary award with a Penguin publishing opportunity attached, and are tickled pink to be offering a writers’ residency program as part of the Future Bookshop. -

A GLOBAL / COUNTRY STUDY REPORT on “INDONESIA” Submitted to Gujarat Technological University in PARTIAL FULFILLMENT of the R
A GLOBAL / COUNTRY STUDY REPORT On “INDONESIA” Submitted to Gujarat Technological University IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT OF THE AWARD FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION S.R. LUTHRA INSTITUTE OF MANAGEMENT (Inst. Code: 750) MBA PROGRAMME Affiliated to Gujarat Technological University, Ahmedabad May 2013 1 Table of Contents Sr.No Particulars Page No. PART-I 1 International Trade & Trade Opportunities 2 2 Sectoral Composition & Growing Industries 11 3 Financial, Capital & Money Markets 22 4 History, Culture & Society 36 5 Manufacturing 47 6 IT, Services & Infrasructure 55 7 Geography, Topology & Natural Resources 64 8 Agriculture & Processed Foods Industry 73 9 Political & Economic Environment & Legal 80 Aspects of International Trade PART-II 1 Chemicals 91 2 Pharmacuticals 98 3 Textiles 109 4 Machinery and Equipment 128 5 Processed Food 137 6 Agricuitures 145 7 Automobiles 159 8 Petrolium 167 9 Metals 173 2 PART-I 1- International Trade & Trade Opportunities This report is designed to assist the Indian business community in intensifying bilateral trade, economic and investment relations with Indonesia. It provides basic information on Indonesia, the Indonesian economy, the profile of Indonesia’s foreign trade and major items traded between India and Indonesia. It also contains information for those intending to visit Indonesia or planning to set up business operations here through a representative office. Information related to investment is also included, together with contact details of Indonesian business entities. We hope this project will prove useful to Indian business. The Embassy of India will be happy to assist business endeavors to improve trade and investment between India and Indonesia in every way possible. -

Pola Lantai Panggung Un Dan Kompetensi Dasar Yang Tercantum Dalam Kurikulum
Alien Wariatunnisa Yulia Hendrilianti Seni Tari Seni Seni S e untukuntuk SSMA/MAMA/MA KKelaselas XX,, XXI,I, ddanan XXIIII n i Tari untuk SMA/MA Kelas X, XI, dan XII untuk SMA/MA u nt u Yulia Hendrilianti Yulia Alien Wariatunnisa PUSAT PERBUKUAN Kementerian Pendidikan Nasional Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. Dilindungi Undang-undang. Penulis Alien Wariatunnisa Seni Tari Yulia Hendrilianti untuk SMA/MA Kelas X, XI, dan XII Penyunting Isi Irma Rahmawati Penyunting Bahasa Ria Novitasari Penata Letak Irma Pewajah Isi Joni Eff endi Daulay Perancang Sampul Yusuf Mulyadin Ukuran Buku 17,6 x 25 cm 792.8 ALI ALIEN Wiriatunnisa s Seni Tari untuk SMA/MA Kelas X, XI, dan XII/Alien Wiriatunnisa, Yulia Hendrilianti; editor, Irma Rahmawati, Ria Novitasari.—Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. xii, 230 hlm.: ilus.; 30 cm Bibliograę : hlm. 228 Indeks ISBN 978-979-095-260-7 1. Tarian - Studi dan Pengajaran I. Judul II. Yulia Hendrilianti III. Irma Rahmawati IV. Ria Novitasari Hak Cipta Buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dari Penerbit PT Sinergi Pustaka Indonesia Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Diperbanyak oleh... Kata Sambutan Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009. -

ISSN: 2591-7064 Vol. 2, No. 6, Sep. 2018 Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts
ISSN: 2591-7064 Vol. 1, No. 3, Nov. 2017 ISSN: 2591-7064 Vol. 2, No. 6, Sep. 2018 Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts Funded by Joint Multidisciplinary Research Conferences Joint Multidisciplinary Research Conferences Plus Multidisciplinary Research Festivals Available at www.ascendensasia.com/ojs www.aaresearchindex.com/ojs Published by Ascendens Asia Pte. Ltd. AAJMRA Vol. 2, No. 6, September 2018 Page 2 of 203 https://aaresearchindex.com/ojs/index.php/AAJMRA Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts Volume 2 Number 6 September 2018 1st PUP-SIMP-AAG Joint International Multidisciplinary Research Conference Abstracts ISSN: 2591-7064 Recommended Citation (September 2018) "1st PUP-SIMP-AAG Joint International Multidisciplinary Research Conference Abstracts," Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts, Vol.2, No.6. Available at: "http://aaresearchindex.com/ojs/index.php/AAJMRA". The Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts(AAJMRA) is a collection of abstracts of research papers presented during Multidisciplinary Research Fests (MRFs) mainly organised by Ascendens Asia Singapore as well as other research conferences in collaboration with various institutions and learned societies. MRFs provide opportunities for collaboration with a common prime objective of creating platforms for students, faculty, staff, and researchers-alike from different institutions to interrelate/interact with their counterparts. MRFs are expected to aide and promote personality development and critical thinking as participants engage themselves in constructive discussions with other participating researchers. AAJMRAs are made available complimentary and for open access by Ascendens Asia Singapore. For more information, please contact [email protected]. AAJMRA Vol. 2, No.