Makkunrai” Karya Lily Yulianti Farid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Katalog-Lontar-2019 Prev.Pdf
2019 LONTAR CATALOGUE 2019 THE LONTAR FOUNDATION Since its establishment in 1987, the Lontar Foundation of Jakarta has carried on its shoulders the mission of improving international awareness of Indonesian literature and culture, primarily throught the publication of Indonesian literary translations. Lontar’s Publications Division, the backbone of the organization, has the significant task of determining which literary works are to be translated so as to reflect Indonesia’s cultural wealth. The Lontar Foundation publishes books under four imprints: Lontar, BTW, Amanah, and Godown. All titles released prior to 2002 (when Godown and Amanah were established) carried the Lontar imprint. TABLE OF CONTENTS Titles released under the Lontar imprint are primarily translations of Indonesian literature. (Exceptions include large-format books that embody Lontar’s mission of enhancing international knowledge of Indonesian culture.) Most Lontar titles are intended for general THE LONTAR FOUNDATION AND ITS IMPRINTS i reading pleasure and for use in teaching courses on Indonesian literature and culture. Lontar TITLES 2 The Modern Library of Indonesia 2 Historical Anthologies 11 Titles in the BTW series—with “BTW” standing for “by the way,” as Other Literary Translations 13 in “by the way, have you heard about such and such an author?”— Special Publications 15 feature work by new and emerging Indonesian writers. This series of Wayang Educational Package 16 mini-books is aimed at publishers, editors, and literary critics. BTW BOOKS SERIES #1 18 Under its Amanah imprint, Lontar publishes Indonesian-language BTW BOOKS SERIES #2 23 titles that Lontar itself has put together in the course of developing an English-language publication. -

Diplomasi Kebudayaan Indonesia Di Eropa Melalui Europalia 2017
DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA DI EROPA MELALUI EUROPALIA 2017 Disusun oleh: Bimo Aryo Wibowo 11141130000087 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2020 i iii PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI SKRIPSI DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA DI EROPA MELALUI EUROPALIA 2017 Oleh Bimo Aryo Wibowo 11141130000087 Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional. Ketua, Sekretaris, Muhammad Adian Firnas, S.IP, M.Si Irfan Hutagalung, SH, LLM NIDN. 0305077401 NIDN. 2024057002 Penguji I, Penguji II, Eva Mushoffa, MA Inggrid Galuh, MHSPS NIDN. 2016077702 NIDN. 9920112884 Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 24 Agustus 2020. Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta Muhammad Adian Firnas, S.IP, M.Si NIDN. 0305077401 ABSTRAK Skripsi ini menganalisa mengenai diplomasi kebudayaan dan kepentingan nasional Indonesia terhadap negara di kawasan Eropa terutama Brussel dengan diplomasi kebudayaan Indonesia melalui festival Europalia 2017. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepentingan nasional Indonesia dalam festival Europalia 2017 kemarin secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan mengapa Indonesia mau melakukan diplomasi kebudayaannya ke Eropa melalui festival pagelaran seni dan kebudayaan Europalia 2017.Penelitian ini, diambil pada masa Presiden Joko Widodo di periode pertamanya 2014-2019. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode kualitatif, dengan didukungnya pengumpulan data-data informasi yang berupa data primer, dan sumber data sekunder. -

Multimedia, Mobility and the Digital Southeast Asian Family a Two-Day Workshop 20-21 April 2017 Melbourne, Australia
Multimedia, Mobility and the Digital Southeast Asian Family A Two-Day Workshop 20-21 April 2017 Melbourne, Australia Funded by: . Migration and Mobilities Cluster, Transforming Human Societies Research Focus Area, La Trobe University, Australia . Social Sciences and Humanities Research Council of Canada . La Trobe Asia, La Trobe University, Australia . Centre for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria, British Columbia, Canada Program Southeast Asia is home to the largest number of social media users globally. Digital technology is shaping the way Southeast Asians interact, maintain contact, and express who they are, their family relationships. It is also a region known for its mobile population with high numbers of overseas workers, international students, refugees/asylum seekers, and migrants seeking permanent residency or citizenship in other countries. Online multimedia content is one way that migrants and mobile Southeast Asians express their sense of connectedness to their family members, belonging, multiple and varied identities, and cultural backgrounds. This two-day workshop of 13 presentations and 20 participants aims to provide a contemporary understanding of online multimedia expression of identity, belonging, and intergenerational family relationships of migrants and mobile subjects of Southeast Asian descent. What do these online multimedia production and stories tell us about the effects of migration and mobility on family intergenerational relationships, that of children, parents, grandparents, and extended kin networks? By focusing on online multimedia expression of Southeast Asians, we aim to comprehend social and cultural change in this region and beyond, that is shaped by digital technology, and particularly in relation to issues of identity, belonging and family relationships. In addition, we are interested in exploring the nuances of how technology shapes this process of change, including addressing a wider range of issues beyond connectedness such as power, conflict, and kinship relations. -
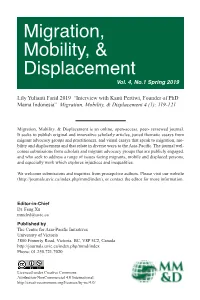
Migration, Mobility, & Displacement
Migration, Mobility, & Displacement Vol. 4, No.1 Spring 2019 Lily Yulianti Farid 2019 “Interview with Kanti Pertiwi, Founder of PhD Mama Indonesia” Migration, Mobility, & Displacement 4 (1): 119-121 Migration, Mobility, & Displacement is an online, open-access, peer- reviewed journal. It seeks to publish original and innovative scholarly articles, juried thematic essays from migrant advocacy groups and practitioners, and visual essays that speak to migration, mo- bility and displacement and that relate in diverse ways to the Asia-Pacific. The journal wel- comes submissions from scholars and migrant advocacy groups that are publicly engaged, and who seek to address a range of issues facing migrants, mobile and displaced persons, and especially work which explores injustices and inequalities. We welcome submissions and inquiries from prosepctive authors. Please visit our website (http://journals.uvic.ca/index.php/mmd/index), or contact the editor for more information. Editor-in-Chief Dr. Feng Xu [email protected] Published by The Centre for Asia-Pacific Initiatives University of Victoria 3800 Finnerty Road, Victoria, BC, V8P 5C2, Canada http://journals.uvic.ca/index.php/mmd/index Phone: 01.250.721.7020 Licenced under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Interview with Kanti Pertiwi, Founder of PhD Mama Indonesia Lily Yulianti Farid Lily Yulianti Farid interviewed Dr. Kanti Pertiwi, founder of the PhD Mama Indonesia online forum (www.phdmamaindonesia.com). Dr. Pertiwi received her PhD from the Faculty of Business and Economics at the University of Melbourne in 2017. She is a mother of three daughters and a lecturer in the Faculty of Economics at the University of Indonesia. -

A Message from the Festival Director
1 A Message from the Festival Director The Emerging Writers’ Festival has always been a festival for writers. Inspiring, informing and connecting writers of all kinds and at all stages of their career – that’s what we do. In our 2012 festival you will find events programmed with writers in mind. Our two-day Town Hall Writers’ conference continues to grow, with over 80 exciting writers ready to discuss the art and craft of being a writer. We have also introduced a new panel series aimed at demystifying the sometimes confusing publishing world, our Industry Insider discussion sessions. Page Parlour indie press fair will be complemented by Future Bookshop, an interactive exhibition at the National Gallery of Victoria. Plus there will be plenty of time for fun and frolics at our Revenge of the Nerds Slide Night, closing night Spelling Bee and atmospheric Fright Night storytelling event. This year our program features more ways than ever to come along and engage with the festival and network with other writers. Our Festival Hub Rue Bebelons will once again be the place to be – look out for the Late Night Book Clubs! – or you can write up a storm in our Rabbit Hole writing frenzy, join our first-ever Festival Open Mic, or jump online and explore our EWFdigital events. Yup, when we say we’re the festival for writers, we really mean it. Of course, the Festival is just one part in our broader mission to create opportunities for emerging writers. This year we are incredibly excited to present the Monash University Undergraduate Prize for Creative Writing, a prestigious new literary award with a Penguin publishing opportunity attached, and are tickled pink to be offering a writers’ residency program as part of the Future Bookshop. -

Struktur Kepribadian Dalam Antologi Cerpen Ayahmu Bulan Engkau Matahari Karya Lily Yulianti Farid: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM ANTOLOGI CERPEN AYAHMU BULAN ENGKAU MATAHARI KARYA LILY YULIANTI FARID: KAJIAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia Program Studi Sastra Indonesia Oleh Clarita Pranciska Simarmata NIM: 164114047 PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA Juli 2020 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM ANTOLOGI CERPEN AYAHMU BULAN ENGKAU MATAHARI KARYA LILY YULIANTI FARID: KAJIAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia Program Studi Sastra Indonesia Oleh Clarita Pranciska Simarmata NIM: 164114047 PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA Juli 2020 i PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI HALAMAN PERSEMBAHAN Skripsi sederhana ini saya persembahkan untuk: Tuhan Yang Maha Esa, keluarga besar Bapak Antonius Simarmata, Ibu Elisabeth S. Siboro, dan saudara/i penulis, Program Studi Sastra Indonesia USD, serta segenap pembaca. vi PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI MOTTO “Cobalah dua metode, yaitu berdoa dan bersastra. Maka kau akan menemukan jawaban. Doa adalah sumber kekuatan dan Sastra adalah salah satu terapi penenang” capas vii PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI ABSTRAK Simarmata, Clarita Pranciska. 2020. “Struktur Kepribadian dalam Antologi Cerpen Ayahmu Bulan Engkau Matahari Karya Lily Yulianti Farid: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud”. Skripsi Strata Satu (S-1). Yogyakarta: Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini membahas struktur kepribadian dalam antologi cerpen Ayahmu Bulan Engkau Matahari. Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan tokoh dan penokohan dan (2) mendeskripsikan struktur kepribadian dalam beberapa tokoh dalam cerpen “Ayahmu Bulan Engkau Matahari”, “Maiasaura”, dan “Dapur” karya Lily Yulianti Farid. -

Book of Abstracts Here
Page 1 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia Abstracts 22nd Biennial Conference of the ASAA The University of Sydney sydney.edu.au/events/asaa2018 Area Studies and Beyond – Abstracts 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA) 3 - 5 July 2018 Contents Welcome from the ASAA President ii Welcome from the Conference Convenor iii Sub-Regional Keynote Abstracts 1 Roundtable Abstracts 3 Speaker Abstracts (alphabetical by last name) Abdullah – Asad 4 Bacon – Bytheway 12 Campbell – Curato 21 Da-Anoy – Dutta 37 Edwards – Erlina 44 Fabrizio – Fushiki 46 Galang – Gupta 53 Hack – Hyslop 62 Inwald – I-Ying 73 Jacka – Jung 74 Kam – Kwek 77 Lahiri-Dutt - Luzzu 86 Ma – Myutel 98 Abstracts Nagesh – Nur 112 O’Brien – Oshiro 120 Pak – Putra 121 Rahim – Rungmanee 132 Saito – Swinbank 139 Tadem – Twomey 155 Uabumrungjit – Utama 164 Vanderstaay – Vu 164 Wahyuningrum – Wu 167 Xiaoxuan – Xu 179 Yadav – Yusuke 179 Zabrovskaia – Zhou 186 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia Association of Asian Studies 22nd Biennial Conference of the i Page i2 Welcome from the ASAA President Welcome to the 22nd biennial Asian Studies Association of Australia Conference Since 1976, ASAA and its conferences have been at the centre of Asian engagement in Australia. Over these 42 years, Asian Studies and Asian engagement have moved from the periphery of the Australian academy and public discourse to the very heart. We stand on the shoulders of those who have presented before us and brought their insight to the attention of policy makers and the next generation of students. -
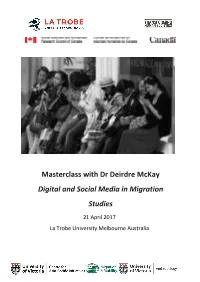
Masterclass with Dr Deirdre Mckay Digital and Social Media in Migration Studies
Masterclass with Dr Deirdre McKay Digital and Social Media in Migration Studies 21 April 2017 La Trobe University Melbourne Australia Masterclass Details VENUE: Viz Lab, Research Commons, Level 2, Borchardt Library, Bundoora Campus TIME: 12.00pm – 5.00pm (lunch and afternoon tea provided) DATE: Friday 21 April 2017 CONVENORS: Dr Monika Winarnita [email protected] and Alex Lloyd [email protected] PRESENTER: Dr Deirdre McKay, Keele University, UK About Dr McKay Dr Deirdre McKay is a Senior Lecturer in Social Geography and Environmental Politics at Keele University, UK. As a Research Fellow Dr McKay has presented her work at La Trobe University’s Philippines Australia Studies Centre. Dr McKay does fieldwork in the global South and also with migrant communities from developing areas who have moved into the world's global cities. Much of her work has been conducted with people who originate in indigenous villages in the northern Philippines. Her latest book is: ‘An Archipelago of Care Filipino Migrants and Global Networks’ (2016) Indiana University Press. For more on Dr McKay’s work you can listen to her interview podcast: https://soundcloud.com/listener1984/phone-home-a-welfare-investment-by-refugees Overview Ten early career researchers, graduate, and postgraduate students have been accepted to attend this masterclass to explore current digital and social media research in migration studies led by Dr Deirdre McKay from the University of Keele, UK. Participants will present a short five (5) minute description of their current research for feedback from Dr McKay who will also facilitate an interactive discussion about the topic. -

Universitas Hasanuddin Update June 2018
UNIVERSITAS HASANUDDIN UPDATE JUNE 2018 Universitas Hasanuddin UPDATE Unhas Presentation at QS Conference Moscow, (May 21st - 23rd, 2018) She delivered her thoughts on Unhas also has a presentation - Unhas participated in the QS how UNHAS build its “brand” on “The Challenges of Hasanud- Worldwide 2018 held at RUDN within the competition of din University within the Global University Moscow. Unhas joined world universities and the Perspective” delivered by M. Iqbal the exhibition & Rector of Unhas emergence of 4.0 industry. Djawad, Ph.D, Director of delivered a presentation in front of International Partnership. QS Conference participants. International Office www.unhas.ac.id/intnews Universitas Hasanuddin 1 UNIVERSITAS HASANUDDIN UPDATE JUNE 2018 Universitas St. Petersburg State Univ Office of Vice Rector for (May 23rd, 2018) - International Affairs & Svetlena Hasanuddin - Unhas delegates, including Banit, Senior Lecturer of the Rector, Prof. Dwia Aries Oriental Faculty, Indonesian Dept. St. Petersburg Tina Pulubuhu, MA and State University Members of Trustee, Prof. dr. The meeting focused on the plans Idrus Paturusi & Prof. Razak for educational & research Cooperation in Thaha had a discussion at cooperation, especially in St. Petersburg State Univ Medicine & Social Sciences. Medicine & Social with Prof. Sergey Andryshin, Sciences Vice-Rector for International Both sides agreed to have an MoU Affairs, Anastasia Yanush- and hold a long-distance meeting kevich, Ph.D., Head of the using video conferencing facilities. UNHAS - Institut Français Indonesia (IFI) agreement for Centre for DELF Examination & French Corner Monday, May 14th, 2018 - UNHAS, Ms. Masdiana had be made to have UNHAS as one Director of International a meeting with officials from of the centres for DELF exam & to Partnership, Mr. -

IEAA Annual Report 2015–16
International Education Association of Australia (IEAA) Annual Report 2015–16 CONTENTS 04 President’s Report 05 Policy and Advocacy 10 Relations with Stakeholders 12 Research 15 Major Projects 16 Professional Development 18 Excellence Awards 20 Tony Adams Fund 21 Special Interest Groups ■ Admissions and Compliance ■ Internationalisation of the Curriculum ■ Marketing, Recruitment and Communication ■ Pathways ■ Sponsored Students ■ Student Mobility ■ Transnational Education 29 Membership and Sponsorship 30 Governance and Administration 31 Financial Report 41 Appendix 1: Standing Committees 42 Appendix 2: Sponsors and Charter Members 44 Appendix 3: Professional Development 50 Appendix 4: AIEC Pre-conference Workshops 52 Appendix 5: IEAA in the Media PRESIDENT’S REPORT The past year Over many years IEAA has fostered an was a very organisational culture that supports and positive time for encourages active participation of our international members. This is very evident in the work of our education in Special Interest Groups (SIGs), which are integral Australia – there in providing professional development forums in was continued which we share expertise and ideas across the strong demand sector. Our SIG conveners play an important role from international in shaping the focus of the association, and we students seeking have sought over the past year to draw on their Professor to study here, and expert communities to shape the Association’s from Australian research and advocacy. Christopher Ziguras students seeking IEAA also relies on generous support, both IEAA President to study abroad. financial and in-kind, from our many institutional Education sponsors and corporate affiliates. The real providers and governments, more than ever, strength of the Association, I believe, results are seeing internationalisation as a key plank in from the shared investment on the part of their strategic thinking. -

Profil Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2018
Profil Penerima PROFIL PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN TAHUN 2018 Anugerah Kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni Tradisi TAHUN 2018 1 Anugerah Kebudayaan dan penghargaan 2 Maestro Seni Tradisi TAHUN 2018 ANUGERAH KEBUDAYAAN 2018 Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 Anugerah Kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni Tradisi TAHUN 2018 3 TIM PENYUSUN PROFIL PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN TAHUN 2018 Pengarah Nadjamuddin Ramly Penanggung Jawab Yayuk Sri Budi Rahayu Penulis Aan Rukmana Dewi Nova Dita Darfiyanti Mohamad Atqa Rizky Ernandi Willy Hangguman Kameramen/Fotografer Leon Desata Marbun M. Rully A. P. I. Simbul Sagala Rachmat Gunawan Editor Binsar Simanullang Kenedi Nurhan Pengolah Data Dede Semiawan Desy Wulandari Retno Raswaty Desain Cover & Layout Yoki Rendra Priyantoko Sekretariat Djatmiko Liza Ariesta M Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anugerah Kebudayaan dan penghargaan 4 Maestro Seni Tradisi TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Kebudayaan yang didalamnya berisi cipta, rasa dan karsa manusia adalah indentitas sebuah kelompok masyarakat. Indonesia yang merupakan negara multikultur mempunyai kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah bahkan UNESCO menjuluki sebagai “Adidaya di bidang Kebudayaan”. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah sebuah identitas bangsa Indonesia, keunikan dan ciri khas Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Eksistensi kebudayaan bergantung pada peran serta dan kepedulian masyarakat. Salah satu aspek terjaganya eksistensi kebudayaan adalah proses belajar. Melalui proses belajar akan muncul kedinamisan budaya. Proses pembelajaran membutuhkan seorang guru atau pengajar dan murid yang ingin belajar dan alat penunjang yang mendukung. Tidak sembarang orang yang dapat menjadi guru karena guru adalah seorang teladan yang digugu dan ditiru. -

Seminar Series
MONASH ARTS MONASH INDIGENOUS STUDIES CENTRE, CABAH AND GLOBAL ENCOUNTERS LAUREATE PROGRAM SEMINAR SERIES Trading Culture - A closer look into Macassan - Yolgnu Artists' Interactions in Celebrating the Shared History ABSTRACT Trade between the Makassan people and the the Indigenous people in northern part of Australia that took place in 1700s or earlier as suggested by new evidence has inspired considerable artistic collaborations between Australian and Indonesian artists. For instance, Andrish Saint-Clare’s Indigenous Opera, Trepang (1997) and Julie Janson’s play The Crocodile Hotel (2003) which brought the little-known history to light and presented fascinating cultural experiences to the contemporary public. In 2018, another project entitled Trading Culture was also launched to strengthen the cultural relationship. It was a creative practice research project that was inspired by the shared history of Makassan and Yolgnu people consisting of four key elements: artist exchange; international symposium; exhibition and documentary film. In this seminar, Dr Lily Yulianti Farid will discuss the close interactions of six Makassan and Yolgnu artists who participating in the project and how they engaged with themes of identity, culture and DATE traditions in contemporary settings. Friday 28 August, 2020 PRESENTER TIME 2.00pm-3.30pm (AEST) Dr Lily Yulianti Farid is a post-doctoral research fellow at the Global Encounters & First Nation People: 1000 Year of Australia History research project, Monash ZOOM LINK Indigenous Studies Centre. She hails from Makassar, Indonesia and has been go to https://monash.zoom.us/join and enter actively promoting Australia – Indonesia’s people to people connections though meeting ID: 970 0233 3099 and password: art and culture in the last 15 years.