Congratulations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indonesia's Sustainable Development Projects
a INDONESIA’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS PREFACE Indonesia highly committed to implementing and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Under the coordination of the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Indonesia has mainstreamed SDGs into National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and elaborated in the Government Work Plan (RKP) annual budget documents. In its implementation, Indonesia upholds the SDGs principles, namely (i) universal development principles, (ii) integration, (iii) no one left behind, and (iv) inclusive principles. Achievement of the ambitious SDGs targets, a set of international commitments to end poverty and build a better world by 2030, will require significant investment. The investment gap for the SDGs remains significant. Additional long-term resources need to be mobilized from all resources to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. In addition, it needs to be ensured that investment for the SDGs is inclusive and leaves no one behind. Indonesia is one of the countries that was given the opportunity to offer investment opportunities related to sustainable development in the 2019 Sustainable Development Goals Investment (SDGI) Fair in New York on April 15-17 2019. The SDGI Fair provides a platform, for governments, the private sectors, philanthropies and financial intermediaries, for “closing the SDG investment gap” through its focus on national and international efforts to accelerate the mobilization of sufficient investment for sustainable development. Therefore, Indonesia would like to take this opportunity to convey various concrete investment for SDGs. The book “Indonesia’s Sustainable Development Project” shows and describes investment opportunities in Indonesia that support the achievement of related SDGs goals and targets. -

PT. Kereta Api Indonesia and Statens Järnvägar (SJ) AB, Sweden
ANALYSIS OF TRAIN PASSENGER RESPONSES ON PROVIDED SERVICE Case study: PT. Kereta Api Indonesia and Statens Järnvägar (SJ) AB, Sweden ABADI DWI SAPUTRA Supervisor: Lars Haglund Service Science Program Karlstad University Spring 2010 ABSTRACT Railway is one of public transport mode on land transportation. Railways, as mass public transport modes, have unique characteristics. It has large capacity, high safety level, and free from traffic jam. Those characteristics make railway a primary public transportation. In fact, even railway transportation has a lot of benefits for society life but they still faced by the problem. Service quality level of Railways transportation is still low compared with other transportation modes. At present railways operation is still colored with the delay, limited condition vehicle, and unclear train travel information that often disadvantage passengers, and many other services offered fail to attract passengers. These conditions result in decreasing the quality of services and insufficient railways operation. The objective of this research is to analyze the relationship between customer satisfaction towards provided service with the desire to do a complaint and to find the factor from service quality that has significant influences to customer satisfaction towards PT KAI services. From that data, and also comparison study between PT Kereta Api Indonesia and Statens Järnvägar (SJ) AB, Sweden, we can recommend the service standards design, service guarantee and complaint handling system that need to be adjusted -

ICRD Paper Template
P-ISSN: 2087-9733 E-ISSN: 2442-983X Journal Homepage: http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijpd Volume 4 No 1, February 2019, 19-28 http://dx.doi.org/10.14710/ijpd.4.1.19-28 Strengthening Rural and Regional Economic Competitiveness Triggering Purworejo Regency Economic Growth through Tourism-Based Kutoarjo Transit Node Development Submitted: 22 December 2018 Accepted: 31 January 2019 Available Online: 28 February 2019 Ibtidah Triyani1, Khalid Adam2, Diana Kristina3 1,2,3Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University, Semarang, Indonesia [email protected] Abstract The railway transport node in Kutoarjo, serving the southern route of Java, is an excellent opportunity for Kutoarjo's economic growth. Kutoarjo, located in the administrative area of Purworejo Regency in RTRW of Central Java Province belongs to Purwomanggung regional system covering Purworejo Regency, Wonosobo Regency, Magelang Regency, Magelang City, and Temanggung Regency. An international airport is also being built in Kulonprogo Regency, Special Region of Jogjakarta Province, which will be integrated with the existing stations in Purworejo Regency, explicitly located in Kutoarjo sub-district, Kutoarjo Station. The construction of NYIA (New Yogyakarta International Airport) in Kulon Progo is an excellent opportunity for the rise and trigger for Kutoarjo. However, the current condition of the existing Kutoharjo station is not optimal and does not significantly give added value to the economy either in Kutoarjo or Purworejo. Kutoharjo Station is only a temporary transit point, and there is no other object which can make visitors want to stop longer in Kutoharjo. This study aims to formulate a management development of Kutoarjo as a transit city that can contribute to mobilizing the economy in Purworejo Regency and its surrounding areas. -

Ex-Ante Evaluation 1. Name of Project Country: the Republic of Indonesia
Ex-Ante Evaluation 1. Name of Project Country: The Republic of Indonesia Project: Railway Double Tracking on Java South Line Project (III) Loan Agreement: March 28, 2008 Loan Amount: 18,819 million yen Borrower: The Republic of Indonesia 2. Necessity and Relevance of JBIC’s Assistance In Java, one of the world’s highest population density areas, the number of passengers riding on long-distance railways increased by an average of 7% during the 10-year period from 1991 to 2000 despite a temporal decline in the period of the Asian currency crisis, excluding the Jabotabek region served by suburban railways. Since that time, however, ridership has leveled off. The principal factors behind this decrease are fare increases, a decline in confidence due to inadequate maintenance owing to a lack of financial resources and technology, the construction of expressways and increasing motorization. Another reason relates to the fact that because the government has set economy class fares low as a policy measure, the railway operator Indonesia Railway Company (Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero); hereinafter referred to as “PT.KAI”) has systematically reduced the operation of unprofitable economy class trains. To stimulate passenger demand, it is necessary to improve operation and maintenance through measures such as formulating and implementing appropriate fare policies and increasing the number of train runs. Ridership on the Java South Line also tended to decline up to 2004 for the above reasons, but since 2005, it has shown an uptrend. Although airlines and road transport compete with railways for passengers, air transport between Jakarta and Surabaya, Yogyakarta, and Solo, the major cities in the eastern district of Java, is expected to reach the saturation point in a few years since the airport facilities are expected to reach capacity. -

Contemporary Indonesian Film: Spirits of Reform and Ghosts from the Past Heeren, C.Q
Contemporary Indonesian film: spirits of reform and ghosts from the past Heeren, C.Q. van Citation Heeren, C. Q. van. (2009, June 9). Contemporary Indonesian film: spirits of reform and ghosts from the past. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/13830 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in License: the Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/13830 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). Contemporary Indonesian film: Spirits of Reform and ghosts from the past Katinka van Heeren Contemporary Indonesian film: Spirits of Reform and ghosts from the past Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op dinsdag 9 juni 2009 klokke 16.15 uur door Catherine Quirine van Heeren Geboren te Jakarta in 1973 III Promotiecommissie Promotor: Prof. dr. B. Arps Referent: Prof. dr. H. Schulte Nordholt (Vrije Universiteit Amsterdam) Leden: Prof. dr. K. van Dijk Prof. dr. B. Meyer (Vrije Universiteit Amsterdam) Prof. dr. P. Nas Prof. dr. I. Smits Prof. dr. P. Spyer . The research for this dissertation was carried out under the auspices of the Indonesian Mediations Project, part of the Indonesia in Transition programme (2001-2005), funded by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). I would like to thank the School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS), and the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) for their financial support. -

Contemporary Indonesian Film Indonesian
This highly informative book explores the world of Post- film Indonesian Contemporary Soeharto Indonesian audio-visual media in the exiting era of Reform. From a multidisciplinary approach it considers a wide variety of issues such as mainstream and alternative Contemporary film practices, ceremonial and independent film festivals, film piracy, history and horror, documentary, television soaps, and Islamic films, as well as censorship from the state Indonesian film and street. Through the perspective of discourses on, and practices of film production, distribution, and exhibition, this book gives a detailed insight into current issues of Indone- Spirits of Reform and ghosts from the past sia’s social and political situation, where Islam, secular reali- ties, and ghosts on and off screen, mingle or clash. Dr. Katinka van Heeren was born on 7 January 1973 in Jakarta Indonesia. She has been a student of Indonesian Languages and Cultures since 1995. Over the years she built up a specialization in Javanese culture, Indonesian Islam, and contemporary audio-visual media. In 2000 she obtained her Masters degree at the University of Leiden with a thesis on media, identity politics and socio-political influences of New Order rule in Indonesian culture in the analysis of two Katinka van Heeren van Katinka Indonesian films. From 2001 to 2005 she was member of the Indonesian Mediations research project. This project was part of a larger Dutch KNAW research project of Indonesia in Transition. In June 2009 she obtained her doctorate. Between 2001 and 2010 she has organized several film screenings in the Netherlands and Indonesia, as well as took part at different film festivals as a member of the jury. -

Recycling Militants in Indonesia
RECYCLING MILITANTS IN INDONESIA: DARUL ISLAM AND THE AUSTRALIAN EMBASSY BOMBING Asia Report N°92 – 22 February 2005 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... i I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 II. THE DEFEAT OF DARUL ISLAM AND ITS CONSEQUENCES ......................... 2 A. ACENG KURNIA AND THE PRTI ............................................................................................3 B. THE MAHONI MEETING.........................................................................................................5 C. RELEVANCE FOR TODAY .......................................................................................................5 III. KOMANDO JIHAD ....................................................................................................... 6 A. THE LEAD-UP TO MILITARY ACTION.....................................................................................6 B. THE EMERGENCE OF MUSA WARMAN...................................................................................8 C. RELEVANCE FOR TODAY .......................................................................................................9 IV. POWER STRUGGLE IN JAVA................................................................................. 10 A. ADAH DJAELANI BECOMES IMAM .......................................................................................10 -

Chapter 4 Analyses on Present Railway Facility and Operation
Chapter 4 Analyses on Present Railway Facility and Operation Chapter 4 Analyses on Present Railway Facility and Operation 4.1 Present Condition of Railway System in Central Java Region 4.1.1 Railway Infrastructure (1) Railway Network The network layout is shown in the map below consists of the following segments: • North Line (Jakarta - Semarang - Surabaya) • South Line (Bandung - Yogyakarta - Surabaya) • Kroya - Cirebon Line • Solo - Gundih - Semarang Line • Solo - Wonogiri Line Gundih Wonogiri Kroya Yogyakarta Source: Based on Each DAOP Report Figure 4.1.1 Railway Network in Java Island The operated network (shown in Figure 4.1.2) is 894 km (58.9%) and non-operated network (also shown in Figure 4.1.2) is 624 km (41.1%). (2) Operating Route and Railway Station There are a total of 127 stations in the Central Java Region, of which 16 are large stations (class 1) and 7 (class 2). They are controlled and maintained by three Railway Management Bureaus, or DAOP (or Daerah Operasi), which are under the control of PT. Kerata Api (Persero). 4 - 1 The Study on Development of Regional Railway System of Central Java Region Final Report N Tayu Java Sea Rembang Cirebon Bakalan Pati Kudas Juwana Tegal Brebes Pemalang Pekalongan Demak Batang Kendal SEMARANG West Java Slawi Brumbung Puruwodadi Blora Province DAOP 4 Prupuk Cepu Kedungjati Central Java Province Gundih Ambarawa Parakan DAOP 5 Wonosobo Tuntang Magelang Purwokerto Sragen SuraKarta(Solo) Madiun Kroya Purworejo Sukoharjo Cilacap Kebumen Klaten Kutoarjo Wonogiri YOGYAKARTA Wates Baturetno Indian Ocean Sea Bantul DAOP 6 Legend East Java Province : Operated Line Yogyakarta Province : Non-operated Line : Boundary of Province Figure 4.1.2 Segmentation of DAOP Regions (3) Track 1) Rail There are seven types of rails depending on its unit weight (54 kg, 50.4 kg, 42.59 kg, 41.5 9 kg, 38kg, 33.4 kg, 25.7 kg). -
The Study on Development of Regional Railway System of Central Java Region in the Republic of Indonesia
No. Ministry of Transportation The Republic of Indonesia The Study on Development of Regional Railway System of Central Java Region in The Republic of Indonesia Final Report (Main Report) February 2009 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD. EID JR 09-034 Ministry of Transportation The Republic of Indonesia The Study on Development of Regional Railway System of Central Java Region in The Republic of Indonesia Final Report (Main Report) February 2009 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD. The foreign exchange rates applied in this study are: USD$1.00 = Rp. 11,500 Yen 1 = Rp. 118.2 (As of November 12, 2008) PREFACE In response to a request from the Government of the Republic of Indonesia, the Government of Japan decided to conduct “The Study on Development of Regional Railway System in Central Java Region” and entrusted to the study to Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA selected and dispatched a study team headed by Mr. Tomokazu Wachi of Oriental Consultants Co., Ltd. between January and December, 2008. The team held discussions with the officials concerned of the Government of the Republic of Indonesia and conducted field surveys at the study area. Upon returning to Japan, the team conducted further studies and prepared this final report. I hope that this report will contribute to the promotion of this project and to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Government of the Republic of Indonesia for their close cooperation extended to the study. -

(Drpphln) 2008
List of Priority External Loans and Grants (DRPPHLN) 2008 Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency Foreword In the context of endeavours to increase efficiency and effectiveness of the utilization of External Loans and Grants, the government of Indonesia has initiated various reforms in the process of the planning and preparation of projects that are funded by External Loans and Grants. One of such reforms is the annual compilation of the List of Planned Priority External Loans and Grants known (DRPPHLN), and also known as the Green Book. The Green Book is one of the planning documents in the process of planning projects that are funded by external loans/grants, that comprise RKPLN (Borrowing Strategy), the DRPHLN‐JM (List of Project Proposal funded by External Loans/Grants for Medium‐Term), the DRPPHLN, and the RPK‐PHLN (Planned Implementation of External Loans/Grants Activities). The Green Book contains the list of proposed projects that are eligible for being funded by external loans and/or grants. Thereby, the projects in the Green Book are the projects that are contained in the DRPHLN‐JM, that have already met most of the readiness criteria and that have already obtained the indicated commitment from the prospective development partners. The DRPPHLN is to become the guideline for preparing the subsequent Annual Government Work Plan. The 2008 Green Book contains 139 proposed projects in the total amount of USD 4.97 billion, consisting of 56 proposed projects totalling USD 4.59 billion and 83 proposed technical assistance projects totalling USD 0.38 billion. These proposals originate from ministries/government agencies (128 projects), regional governments (5 projects), and state‐owned enterprises (6 projects). -

Corporate Brochure
DAFAM | hotels collections January 2021 edition Dafam Hotel Management is a hotel management that stands in quality with international standard. It designs four inspiring brands to accommodate wide range of market segments in various locations. These brands are diversely created specically with each style of service and facilities which guests will enjoy best. S I G N A T U R E by DAFAM A signature brand with its A brand that shows its Our mid-scale brand, Young and dynamic hotel No frills and to the point beyond expected luxury of service and spread across archipelago with retro concept at style, reduce time wasted experience in personal facilities. Stands tall in the offers a homy service and economic scale. National of guest’s valuable time, services and hi-end capital city of province yet pleasant tranquility where vintage legend and simple make them move products and facilities. metropolis. Equals to its business are well taken service, brought our guest independently to savor Stands majestically at modern style for upscale care of within outstanding travel in time, explore its the hotel. More than just a Central Business District or market. service and facilities. unique style. budget, fulll guest basic metropolitan area. Equals needs in smart way. to the next style for savvy customers. Brand that mounted to our partner’s Our hotel collection with a natural Our hotel collection which adopted genuine marks assure its constant setting of environment and located the Syariah management system and quality of service which bring by our away from crowded area or procedure, according to Halal service culture. -
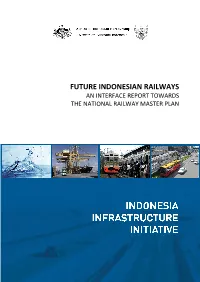
Future Indonesian Railways : an Interface Report Towards ...; PDF Copied from the Internet by Library of Congress Jakarta Office
FUTURE INDONESIAN RAILWAYS AN INTERFACE REPORT TOWARDS THE NATIONAL RAILWAY MASTER PLAN FUTURE INDONESIAN RAILWAYS AN INTERFACE REPORT TOWARDS THE NATIONAL RAILWAY MASTER PLAN INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE August 2010 INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE This document has been published by the Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), an Australian Government funded project designed to promote economic growth in Indonesia by enhancing the relevance, quality and quantum of infrastructure investment. The views expressed in this report do not necessarily reflect the views of the Australia Indonesia Partnership or the Australian Government. Please direct any comments or questions to the IndII Director, tel. +62 (21) 230‐6063, fax +62 (21) 3190‐2994. Website: www.indii.co.id. ACKNOWLEDGEMENTS This report has been prepared by Dr. Suyono Dikun, who was engaged under the Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), funded by AusAID, as part of its initiative to assist the Ministry of Transport (MoT), Directorate General of Railways (DGR) in the development of a National Railway Master Plan. The support provided by the Directorate General of Railways (Ministry of Transportation) is gratefully acknowledged. Any errors of fact or interpretation are solely those of the author. Dr. Suyono Dikun Jakarta, 23 August 2010 © IndII 2010 All original intellectual property contained within this document is the property of the Indonesia Infrastructure Initiative (IndII). It can be used freely without attribution by consultants and IndII partners in preparing IndII documents, reports designs and plans; it can also be used freely by other agencies or organisations, provided attribution is given. Every attempt has been made to ensure that referenced documents within this publication have been correctly attributed.