Ricikan Struktural Salah Satu Indikator Pada Pembentukan Gending Dalam Karawitan Jawa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gamelan-Performance-II.Pdf
PERFORMANCE Module Handbook Kayo Kimura, Nami Higuchi(Javanese Gamelan ensembles) Suguri Hariu (Javanese dance) Term: Fall Semester Numbering MMA102 Credits 1 SYNOPSIS: The aim of this subject is to help students understand the structure and instrumentation of each part of Indonesian and Central Javanese gamelan ensembles and to teach them “communication through music” which is a distinctive feature of gamelan. Students will also have the opportunity to learn Javanese dance deeply connected to music. OUTLINE SYLLABUS Week Synopsis 1 Beginner: 4 Lancaran Ensemble Intermediate: Irama and Instrumentation 1 (Irama Types) Advanced: Structures 2 Beginner: 5 Introduction to Other Arrangements Intermediate: 2 Changes in Tempo Advanced: Irama and Instrumentation 3 Beginner: 6 Irama Variations Intermediate: 3 Instrumentation Seminar Advanced: Ensemble Rules 4 Beginner: Music Used during Royal Ceremonies 1 (Outline) Intermediate: Nursery Rhymes 1 (Outline) Advanced: Introduction to Lagu Instruments 5 Beginner: 2 Colotomic Instrument Techniques Intermediate: 2 Colotomic Instruments, Saron Advanced: Mutual Relationship of Lagu Instruments 6 Beginner: 3 Bonang and Saron Techniques Intermediate: 3 Bonang Barung Advanced: Song Request Seminar (Beginner) 7 Beginner: 4 Kecer and Kendang Techniques Intermediate: 4 Kendang and Rhythms Advanced: Song Request Seminar (Intermediate) 8 Beginner: 5 Ensemble Seminar Intermediate: 5 Song and Ensemble Seminar Advanced: Song Request Seminar (Advanced) 9 Beginner: Contemporary Music Seminar 1 (Scores and Music) Intermediate: -
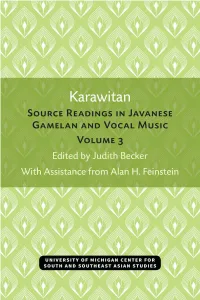
Source Readings in Javanese Gamelan and Vocal Music, Volume 3
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN CENTER FOR SOUTH AND SOUTHEAST ASIAN STUDIES MICHIGAN PAPERS ON SOUTH AND SOUTHEAST ASIA Editorial Board A. L. Becker Peter E. Hook Karl L. Hutterer John K. Musgrave Nicholas B. Dirks, Chair Ann Arbor, Michigan USA KARAWITAN SOURCE READINGS IN JAVANESE GAMELAN AND VOCAL MUSIC Judith Becker editor Alan H. Feinstein assistant editor Hardja Susilo Sumarsam A. L. Becker consultants Volume 3 MICHIGAN PAPERS ON SOUTH AND SOUTHEAST ASIA Center for South and Southeast Asian Studies The University of Michigan Number 31 Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/ Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program. Library of Congress Catalog Card Number: 82-72445 ISBN 0-89148-034-X Copyright ^ by © 1988 Center for South and Southeast Asian Studies The University of Michigan Publication of this book was assisted in part by a grant from the Publications Program of the National Endowment for the Humanities. Additional funding or assistance was provided by the National Endowment for the Humanities (Translations); the Southeast Asia Regional Council, Association for Asian Studies; The Rackham School of Graduate Studies, The University of Michigan; and the School of Music, The University of Michigan. Printed in the United States of America ISBN 978-0-89148-041-9 (hardcover) ISBN 978-0-472-03820-6 (paper) ISBN 978-0-472-12770-2 (ebook) ISBN 978-0-472-90166-1 (open access) The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS vii APPENDIX 1: Glossary of Technical Terms Mentioned in the Texts 1 APPENDIX 2: Javanese Cipher Notation (Titilaras Kepatihan) of Musical Pieces Mentioned in the Texts 47 APPENDIX 3: Biographies of Authors 429 APPENDIX 4: Bibliography of Sources Mentioned by Authors, Translators, Editors, and Consultants 447 GENERAL INDEX 463 INDEX TO MUSICAL PIECES (GENDHING) 488 This work is complete in three volumes. -

Fungsi Serta Makna Simbolik Gamelan Sekaten Dalam Upacara Garebeg Di Yogyakarta �� A.M
Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI - Tesis S2 Fungsi Serta Makna Simbolik Gamelan Sekaten dalam Upacara Garebeg di Yogyakarta A.M. Susilo Pradoko Deskripsi Dokumen: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81580 ------------------------------------------------------------------------------------------ Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fungsi serta makna-makna simbolik gamelan sekaten bagi masyarakat pendukungnya dalam upacara Garebeg Mulud di Yogyakarta. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan holistik. Pengumpulan data diperoleh melalui: studi literatur, wawancara dan observasi partisipasi serta perolehan data melalui camera video dan foto. Teknik analisa data dengan interpretasi makna, fungsional, dan causal serta analisis isi dari permainan musik gamelan serta teknik garap gendhingnya hingga menemukan inferensi-inferensi. Hasil inferensi-inferensi ini kemudian divalidasikan dengan para tokoh masyarakat pendukungnya serta key informan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Ternyata gamelan berfungsi bagi raja, ulama serta bagi masyarakat. Fungsi gamelan bagi Raja adalah: 1. Sebagai pengakuan atas kebesaran dan kekuasaan raja. 2. Sarana memperkokoh kerajaan serta kolektifitas sosial. Sedangkan fungsi gamelan sekaten bagi Ulama adalah: Sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam, syiar Islam. Fungsi bagi masyarakat adalah: 1. Mendapatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan badan dan jiwanya. 2. Sarana untuk hiburan dan rekreasi. Gamelan sekaten merupakan sub sistem simbol yang mewujudkan gambaran kolektif masyarakat pendukungnya yang memiliki makna proyektif tentang ajaran-ajaran untuk berperilaku dalam masyarakatnya. Gamelan sekaten memiliki makna ajaran-ajaran tentang: Ketuhanan, asal dan tujuan hidup manusia (sang/can paraning dumadi), harmonis , rukun, olah kanurasan, sabar, tepo seliro, go tong royong serta tatanan sopan santun yang sesuai dengan cara pandangan masyarakat pendukungnya untuk berperilaku dalam menanggapi kehidupannya. . -

University of Oklahoma Graduate College
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE JAVANESE WAYANG KULIT PERFORMED IN THE CLASSIC PALACE STYLE: AN ANALYSIS OF RAMA’S CROWN AS TOLD BY KI PURBO ASMORO A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF MUSIC By GUAN YU, LAM Norman, Oklahoma 2016 JAVANESE WAYANG KULIT PERFORMED IN THE CLASSIC PALACE STYLE: AN ANALYSIS OF RAMA’S CROWN AS TOLD BY KI PURBO ASMORO A THESIS APPROVED FOR THE SCHOOL OF MUSIC BY ______________________________ Dr. Paula Conlon, Chair ______________________________ Dr. Eugene Enrico ______________________________ Dr. Marvin Lamb © Copyright by GUAN YU, LAM 2016 All Rights Reserved. Acknowledgements I would like to take this opportunity to thank the members of my committee: Dr. Paula Conlon, Dr. Eugene Enrico, and Dr. Marvin Lamb for their guidance and suggestions in the preparation of this thesis. I would especially like to thank Dr. Paula Conlon, who served as chair of the committee, for the many hours of reading, editing, and encouragement. I would also like to thank Wong Fei Yang, Thow Xin Wei, and Agustinus Handi for selflessly sharing their knowledge and helping to guide me as I prepared this thesis. Finally, I would like to thank my family and friends for their continued support throughout this process. iv Table of Contents Acknowledgements ......................................................................................................... iv List of Figures ............................................................................................................... -

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta Kesenian-Keseniat Rakyat Dan Selama Menjalani Studi Di Dunia Seni
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Karya Tari Obah Mosik adalah sebuah karya tari ciptaan baru yang merupakan hasil penuangan ide serta kreativitas penata tari, yang dilatarbelakangi Reog Prajuritan yang menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Karya tari ini disajikan dalam bentuk koreografi kelompok, didukung enam penari putra. Instrumen pengiringnya menggunakan beberapa instrumen meliputi Gambang berlaras pelog, Kempul dan Slentem berlaras slendro. Serta menggunakan instrumen asli pada Reog Prajuritan meliputi Bendhe, Kecer, Angklung, dan Bedug. Ada beberapa penambahan instrumen seperti suling dan senar drum untuk memvisualisasikan prajurit kraton. Dalam karya tari ini, dimunculkan spirit tari Reog Prajuritan dengan pijakan gerak yang muncul berdasarkan dari motif gerak lampah macak dengan mengambil esensi-esensi yang ada di dalamnya meliputi ayunan dan pengulangan, serta memunculkan beberapa motif gerak yang sudah ada pada tari Reog Prajuritan dengan pengembangan dalam berbagai unsur yang penata lakukan. Karya tari Obah Mosik merupakan karta Tugas Akhir studi di program Studi S-1 Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karya tugas akhir ini dapat dipandang sebagai ungkapan berbagai pengalaman selama berada di lingkungan yang dekat dengan 49 UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta kesenian-keseniat rakyat dan selama menjalani studi di dunia seni pertunjukan. Evaluasi dari penikmat dan pengamat seni baik dari akademisi atau non akademisi sangat dibutuhkan untuk memacu semangat dan meningkatkan kemampuan berkarya selanjutnya. Penyajian karya dilengkapi dengan naskah berupa skripsi tari. Skripsi karya tari ini sebagai keterangan tertulis karya tari Obah Mosik. B. Saran Belajar untuk menciptakan suatu karya tari adalah hal yang sangat berharga. Dari semula melihat berbagai macam pertunjukan, lalu mencoba menganalisis dan memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam karya tari yang diajikan dan bagaimana proses yang dilakukan. -

Bab Ii Tinjauan Pustaka A
- - www.lib.umtas.ac.id BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Media Pembelajaran Kokami (Kotak Kartu Misterius) a. Pengertian Media Media memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi dari pendidik agar dapat diterima oleh siswa/peserta didik. Media pembelajaran adalah salah satu hal yang penting karena akan sangat membantu dalam proses pembelajaran dan juga peserta didik akan lebih memahami apa yang disampaikan pendidik sehingga peserta didik tidak kesulitan. Contohnya yaitu jika pendidik ingin menunjukkan contoh hewan singa, pendidik hanya perlu menunjukkan gambar singa tersebut atau dapat juga dalam bentuk film maupun video hewan tanpa harus membawa hewan yang dalam bentuk asli. Sehingga peseta didik menjadi lebih paham dan juga memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Daryanto (2016: 4) kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Maksud dari medium yaitu sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari pembawa pesan kepada penerima pesan dalam suatu komunikasi. Pembelajaran yaitu suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dilakukan secara sengaja guna mencapai terjadinya proses belajar. 6 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya - - - - www.lib.umtas.ac.id 7 Sedangkan menurut Miarso dalam Suryani (2018:3) Pembelajaran merupakan suatu keadaan yang digunakan untuk menunjukkan suatu usaha pelaksanaan pendidikan yang dilakukan secara sengaja, dengan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta yang pelaksanaannya terkendali. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana penyampaian informasi yang dipergunakan agar mencapai tujuan pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang pelaksanaanya terkendali. -
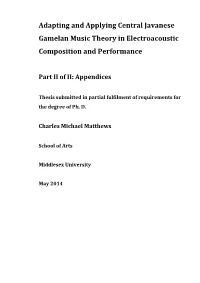
Adapting and Applying Central Javanese Gamelan Music Theory in Electroacoustic Composition and Performance
Adapting and Applying Central Javanese Gamelan Music Theory in Electroacoustic Composition and Performance Part II of II: Appendices Thesis submitted in partial fulfilment of requirements for the degree of Ph. D. Charles Michael Matthews School of Arts Middlesex University May 2014 Table of contents – part II Table of figures ....................................................................................................................... 121 Table of tables ......................................................................................................................... 124 Appendix 1: Composition process and framework development ..................... 125 1.1 Framework .............................................................................................................................. 126 1.2 Aesthetic development ........................................................................................................ 127 1.3 Idiomatic reference .............................................................................................................. 128 1.3.1 Electroacoustic music references .......................................................................................... 129 1.3.2 Musical time .................................................................................................................................... 130 1.3.3 Electronic cengkok and envelopes ........................................................................................ 132 1.4 Instruments and interfaces .............................................................................................. -

Angklung Badeng Learning for Junior High School Students in Malangbong Garut
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 255 1st International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2018) The Model of Angklung Badeng Learning for Junior High School Students in Malangbong Garut Dody Mohamad Kholid Pendidikan Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia [email protected] Abstract—Traditional art is one of the characteristics of a actually had the next generation consisting of students from particular ethnic and region, so it must be preserved. Its various schools [2]. However, their next generation has limited existence concerns the identity and sovereignty of a region practice time, limited songs played, and lack of equipment because traditional art usually contains philosophy and meanings available. Some of the equipment have been damaged so that of life that must be preserved and applied by the students. It also the training process is not maximum. In addition, some new shapes the characteristics of human being as well. One of the members are still constrained by the training time so that efforts in preserving the culture of traditional art is to include the sometimes the training time does not match the time held by its art in schools’ extracurricular activities. The target covers junior members. It is caused by the condition and circumstances of high school students in the environment around the traditional each member (school students). arts. To overcome these problems, an appropriate model of learning must be designed in accordance with the situation and At this time, the existence of angklung badeng in condition and the character of region and students where the Malangbong has a little demand, especially from the young learning takes place. -

Gamelan Sekaten Fenomena Penuh Makna.Pdf (Caver, Artikel, Review)
Gamelan Sekaten Merupakan Fenomena Penuh Makna dan Multi Perspektif Suatu Kajian Kebudayaan Materi A.M.Susilo Pradoko [email protected] Universitas Negeri Yogyakarta Materi merupakan budaya manusia karena dengan obyek materi tersebut manusia mengalami perjumpaan, berinteraksi dengan materi tersebut, Ian Woodward menyatakan sebagai berikut: “ Object are commonly spoken of as material culture. The term material culture emphasis how apparently inanimate things within the environment act on people, and are acted upon by people, for the purposes of carrying out social fungtions, regulating social relations and giving symbolic meaning to human activity.” (Woodward, 2007:4). Terjemahan: “Obyek biasanya dibicarakan sebagai kebudayaan material. Istilah kebudayaan material menekankan bagaimana benda-benda mati di antara tindakan lingkungan orang-orang, dan diperlakukan orang-orang, bertujuan untuk membawa fungsi sosial, mengatur hubungan- hubungan sosial dan memberikan arti simbolis pada aktivitas manusia” (Woodward, 2007:4). Kebudayaan material menurut Woodward tersebut berarti bahwa benda-benda mati obyek budaya tersebut mampu bermakna dan selanjutnya berinteraksi secara sosial dengan masyarakat pendukungnya sebagai sarana simbolis dalam berbagai keperluan memenuhi fungsi sosial. Kebudayaan materi tangible selain dipelajari bentuknya yang mencakup ukuran benda itu, warna benda itu, materi bahan untuk membuat benda itu, komposisi benda itu, juga dipelajari hubungan benda itu dengan manusia tatkala benda itu digunakan dalam interaksi sosial masyarakat. Woodward Ian mengungkapkan sebagi berikut : “ Material culture is no longer the sole concern of museum scholars and archeologist-resercher from a wide range of fields have now colonized study of object. …. Material culture studies can provide a useful vehicle for synthesis of macro and micro or structural and interpretative approach in the social sciences“ (Idem). -

Gamelan Sekaten Dan Penyebaran Islam Di Jawa
GAMELAN SEKATEN DAN PENYEBARAN ISLAM DI JAWA Joko Daryanto Universitas Sebelas Maret Abstrak Penyebaran Islam di Jawa menggunakan berbagai cara ataupun metode dakwah penyebaran Islam. Salah satu sarana pendukung penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah gamelan Sekaten. Perangkat gamelan ini merupakan perangkat gamelan yang dibunyikan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dibunyikan selama satu minggu di Bangsal Pagongan depan Masjid Agung Surakarta.Sebelum orang Jawa mengenal dan memeluk agama Islam, masyarakat Jawa telah memeluk agama Hindu dan Budha. Kondisi sosial psikologis masyarakat Jawa semacam itu rupanya menjadi hambatan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Pada akhirnya Sunan Kalijaga mengusulkan agar menggunakan gamelan sebagai daya tarik awal bagi penyebaran agama Islam. Gamelan Sekaten yang digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam di Jawa diduga kuat memiliki nilai-nilai atau unsur-unsur Islam dalam perangkat tersebut.Setting masyarakat Jawa pada saat itu masih memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap agama Hindu dan Budha sehingga diperlukan alat bantu dalam hal ini gamelan Sekaten untuk memudahkan para wali menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah dengan menggunakan gamelan Sekaten ternyata sangat menarik dan efektif untuk mengumpulkan orang. Diawali dengan ketertarikan terhadap bunyi gamelan Sekaten akhirnya masyarakat Jawa mengenal dan akhirnya memeluk Islam sebagai keyakinan. ProsesIslamisasi seperti itu selanjutnya disebutsebagai dakwah dengan menggunakan pendekatan kultural. Kata kunci: gamelan, sekaten, Islam, Jawa Abstract The spreading of Islamic faith in Java uses many ways or methods to propagate Islamic faith. One of the medium which is support the spreading of Islam in Java is ‘Gamelan Sekaten’. It is kind of an ensemble which is played on the occasion of Muhammad’s birthday and played as long as 1 week in ‘Bangsal Pagongan’ in front of the Great Mosque Surakarta. -

Sunan Kali Jaga
Sunan Kali Jaga Sunan Kali Jaga is one of the Wali Sanga,1 and remains an important figure for Muslims in Java because of his work in spreading Islam and integrating its teachings into the Javanese tradition. Throughout his time proselytizing, he used art forms that, at the time, were both amenable to and treasured by the people of Java. Sunan Kali Jaga is thought to have been born in 1455, with the name Raden Syahid (Raden Sahid) or Raden Abdurrahman. He was the son of Aria Wilatikta, an official in Tuban,2 East Java, who was descended from Ranggalawe, an official of the Majapahit Kingdom during the time of Queen Tri Buwana Tungga Dewi and King Hayam Wuruk. Sunan Kali Jaga’s childhood coincided with the collapse of the Majapahit Kingdom recorded in the sengkalan “Sirna Ilang Kertaning Bhumi,”3 referring to the year 1400 Caka4 (1478). Seeing the desperate situation of the people of Majapahit, Raden Syahid decided to become a bandit who would rob the kingdom’s stores of crops and the rich people of Majapahit, and give his plunder to the poor. He became well known as Brandal5 Lokajaya. One day when Raden Syahid was in the forest, he accosted an old man with a cane, which he stole, thinking it was made from gold. He said that he would sell the cane and give the money to the poor. The old man was Sunan Bonang,6 and he did not approve of Raden Syahid’s actions. Sunan Bonang advised Raden Syahid that God would not accept such bad deeds; even though his intentions were good, his actions were wrong. -

Table of Contents Provided by Blackwell's Book Services and R.R
Preface p. v Acknowledgements p. vi Using the book p. vii List of illustrations p. x List of locations of instruments illustrated p. xiii List of tips and tricks p. xiii Introduction Encountering the gamelan p. 2 Gamelan at home p. 7 Where? p. 7 When? p. 8 What? p. 11 Who? p. 16 Gamelan abroad p. 19 Where? p. 19 When? p. 20 What? p. 20 Music Karawitan - the art of music p. 22 General principles p. 22 Roles of instruments p. 34 Character of music p. 37 Notation p. 38 Principles of Kepatihan notation p. 38 Other forms of notation p. 43 Laras - 'tuning' p. 45 Slendro vs. pelog p. 45 Embat p. 50 Pathet - 'mode' p. 52 Irama - rhythm p. 58 Bentuk - form p. 63 Overview p. 63 Lancaran and bubaran p. 64 Ketawang p. 67 Langgam p. 69 Ladrang p. 70 Gati/mares p. 72 Gangsaran p. 72 Gendhing p. 73 Editable forms p. 85 Other instrumental forms p. 90 Vocal forms p. 91 Combinations and suites p. 95 Drama and dance p. 96 Review p. 101 Instruments Instruments-an overview p. 104 Playing style: general p. 109 Balungan instruments p. 111 Saron family p. 113 Saron barung p. 114 Demung, saron demung p. 121 Peking, saron panerus p. 124 Saron wayangan p. 133 Slenthem p. 133 Other instruments p. 134 Decorating instruments-introduction p. 136 Bonang family p. 138 Bonang barung and bonang panerus p. 140 Bonang panembung p. 183 Soft-style decorating instruments p. 184 Rebab p. 184 Gender family p. 188 Gender barung p.