Prosiding Prosiding Seminar Dan Lokakarya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
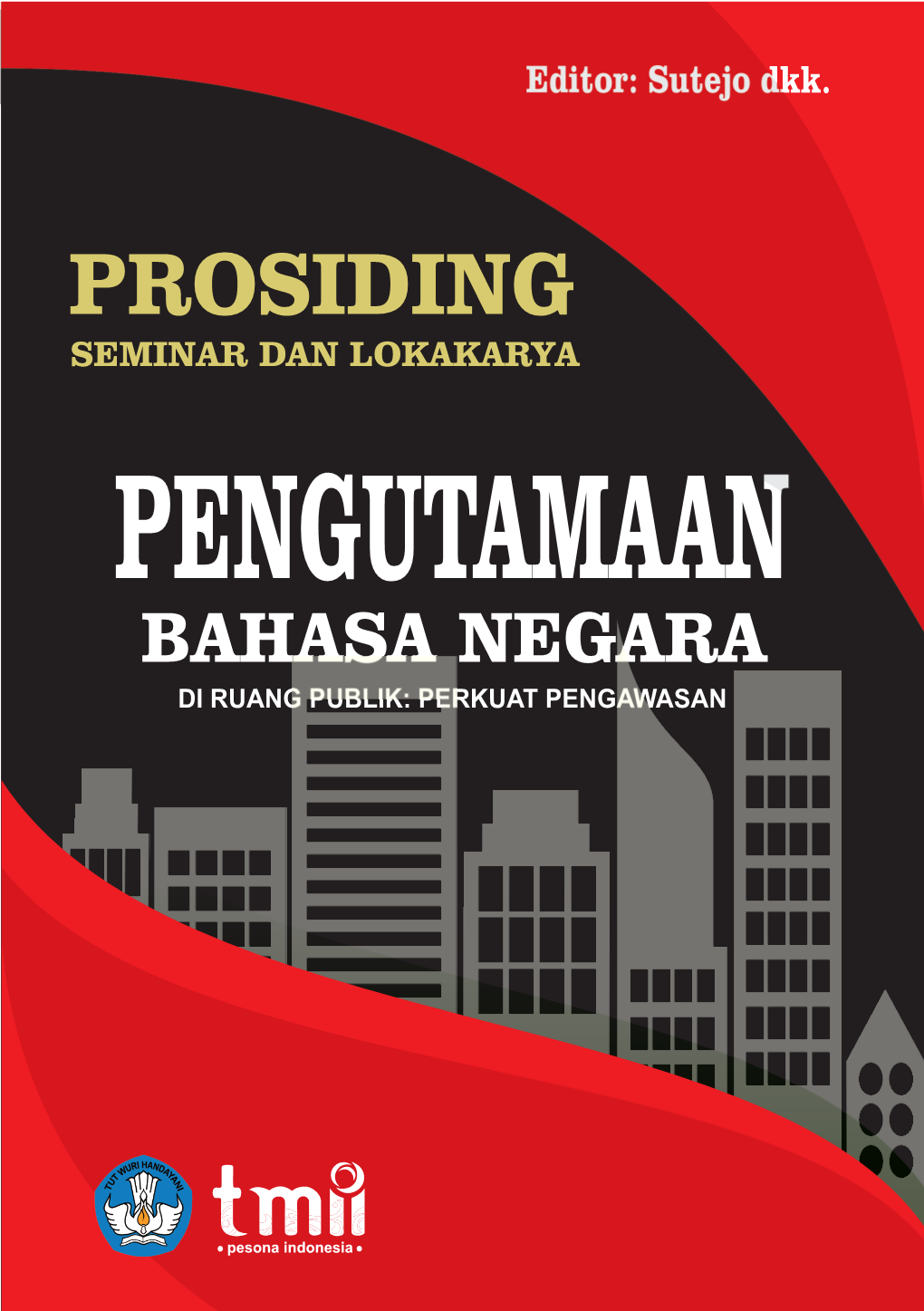
Load more
Recommended publications
-

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Istilah Intelektual Di Indonesia Ketika “ Bahasa” Ditemukan Atau Ketika “Bahasa “
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Istilah Intelektual di Indonesia ketika “ bahasa” ditemukan atau ketika “bahasa “ menemukan penuturnya, maka saat itulah dengan sendirinya hadir seorang Intelektual atau sekelompok orang intelegensia yang bisa disebut cendikiawan, artinya sebelum masuknya istilah Intelektual di Indonesia pada dasarnya di Indonesia sudah ada Intelektual. Istilah intelektual Muslim mulai di kenal sejak Syarekat Dagang Islam (SDI) muncul pada tahun 1905 dan SI pada 1911. Kehadiran Intelektual Muslim Indonesia dapat di rasakan pada era tahun 60-an, saat itu Indonesia mengalami booming para sarjana Muslim yang berasal dari alumni Jong Islamieten Bond ( JIB), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII). Sehingga kehidupan intelektual seperti tradisi diskusi, kepenulisan buku, seminar mulai berkembang di indonesia. Lafran pane terilhami oleh hasrat intelektual Muslim generasi terdahulu yang telah mendirikan organisasi-organisasi seperti Jong Islamieten Bond atau JIB pada 1925 dan Student Islamieten Studiclub atau SIS pada 1934. Lafran Pane berasal dari kampung Pangurabaan, kecamatan Sipirok- Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lafran Pane adalah anak keluarga Sutan Pangurabaan Pane, ayahnya Sutan Pangurabaan Pane termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di Spirok pada 1921. Kakeknya adalah seorang ulama bernama Syekh Badurrahman. Lafran adalah adik dari sastrawan dan seniman terkenal yaitu 1 Sanusi Pane dan Armijn Pane. Lafran yang saat itu merupakan mahasiswa ketua III Senat di sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, dan pada saat itu Lafran masih bersatus sebagai pengurus Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY). Kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dikenal dengan “kota Pelajar”. Namun akibat dari penjajahan Belanda dunia pendidikan dan kemahasiswaan di Indonesia telah dipengaruhi unsur-unsur dan sistem pendidikan Barat yang mengarah kepada kurangnya ilmu agama pada setiap kehidupan manusia. -

Page : Date : Time : 02/04/2018 15:20:43 1 AS AT
PT CAPITALINC INVESTMENT TBK REGISTER OF SHAREHOLDERS Date : 02/04/2018 MENARA JAMSOSTEK, MEN.SELATAN LT.10 DAFTAR PEMEGANG SAHAM Time : 15:20:43 SORT BY : NAME Page : 1 JL.JEND. GATOT SUBROTO NO. 38 AS AT : 31/03/2018 Total Share Issued : 31,842,082,852 Seq. Ledger Shareholder Name & GroupTotal Share Participant Name Persentase No. No. Shareholder Address Status Total SKS Citizenship 1 80002546-7 A DANOL DEWANTOJ9 65,000 YJ 0.0002 JL.KELAPA TIGA NO.22 IND 0 PT Lotus Andalan Sekuritas RT004/006 KEL.LENTENG AGUNG INA KEC.JAGAKARSA 2 80003142-0 A TIE J9 100,000 YU 0.0003 JL.SETIABUDI NO.21 IND 0 PT. CIMB SECURITIES INDONESIA RT008 RW004 KEL. LUBUK PAKAM PEKAN INA KEC. LUBUK PAKA 3 80000670-1 A YOSPANTOROJ9 85,000 CP 0.0003 CITRA VILLA BLOK K 18 NO.13 RT.007 IND 0 PT VALBURY ASIA SECURITIES RW.028 KEL.MANGUNJAYA KEC.TAMBUN INA SELATAN 4 00004882-4 A'AN HERNAWANJ2 30 0.0000 JL. SAWAH LIO II DLM RT.010/008 IND 6 JAKARTA BARAT INA 5 80001906-8 A. HARRISUSANTOJ9 30,030 OD 0.0001 JL. KEAMANAN NO 32 RT 002 RW 005 IND 0 PT DANAREKSA SEKURITAS KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT INA 6 80001968-8 A. SAWERIGADINGJ9 100 PC 0.0000 JL. A. MAKKASAU, RT.002/RW.001 IND 0 PT PAC SEKURITAS INDONESIA INA 7 80000540-7 A. ZAENAL ABIDINJ9 681,900 CC 0.0021 DS. PEKALONGAN RT 003 RW 002, IND 0 PT MANDIRI SEKURITAS PEKALONGAN, WINONG INA 8 80000078-9 A.A GEDE ARI SUDHANA DALEMJ9 20,000 AI 0.0001 JL.PADANG GALERIA II/123 DPS PADANG IND 0 PT UOB KAY HIAN SECURITIES SUMBU TENGAH KEL.PADANGSAMBIAN INA KELOD KEC.DENPASAR 9 80001723-1 A.A ISTRI MANIK NOVITA DEWIJ9 20,000 NI 0.0001 LINGK./BR UMA KAPAL IND 0 PT BNI SECURITIES KAPAL MENGWI INA 10 80002018-5 A.K.PRAHASTA SAMIAJI, ST.MSCJ9 200,000 PD 0.0006 JLN AGUNG JAYA 3 BLOK D ID/5 RT. -

Indonesian Authors in Geneeskundige Tijdschrift Voor Nederlands Indie As Constructors of Medical Science
Volume 16 Number 2 ISSN 2314-1234 (Print) Page October 2020 ISSN 2620-5882 (Online) 123—142 Indonesian Authors in Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlands Indie as Constructors of Medical Science WAHYU SURI YANI Alumny History Department, Universitas Gadjah Mada Email: [email protected] or [email protected] Abstract Access to the publication Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (GTNI), Keywords: a Dutch Indies medical journal, was limited to European doctors. Although Stovia Bahder Djohan; (School ter Opleiding van Inlandsche Artsen) was established to produce indigenous Constructor; (Bumiputra) doctors, its students and graduates were not given access to GTNI. In GTNI; response, educators at Stovia founded the Tijdschrift Voor Inlandsche Geneeskundigen Leimena; (TVIG) as a special journal for indigenous doctors. Due to limited funds, TVIG – Stovia; Pribumi the only scientific medical publication for indigenous doctors – ceased publication Doctors; TVIG in 1922. The physicians formed Vereeniging van Inlandsche Geneeskundigen (VIG) an association for pribumi (native) doctors to express various demands for equal rights, one of which was the right to access GTNI. The protests and demands of the bumiputra doctors resulted not only in being granted reading access rights but also being able to become writers for GTNI. Bumiputra doctors who contributed to GTNI included Bahder Djohan and Johannes Leimena. However, they were not the only authors who contributed to GTNI during the Dutch East Indies era. After Indonesia became independent, both doctors played major roles in laying the foundation for Indonesia’s health education system and implementing village-based health policies. This article is part of a research project on Indonesia’s health history using the archives of the GTNI, TVIG and books written by doctors who contributed to GTNI which were published from the early twentieth century onwards. -

BAB U SEII\YAI\G PAI{DANG TENTANG HMI Kemerdekaan Yang
BAB U SEII\YAI\G PAI{DANG TENTANG HMI A. Sejereh ewal berdirinye ttMt ditengah kancah revolusi fisik l. Situasi Ncgara Republik Indonesia Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai jembatan emas untuk mewujudkan cita-citanya membangun bangsa yang adil, makmur, maju dan modern sejajar dengan bangsa-bangsa modern lainnya di dunia ini. di peroleh dengan harga yang sangst mahal. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang mahal itu, tidaklah diperoleh dengan mudah, apalagi sebagai hadiah Jepang. tetapi ia merupakan usaha yang sangat meletihkan setelah melewati rentang waktu + 350 tahun terjajah. Setelah kemerdekaan itu diperoleh. Perjuangan untuk mempertahankan dan mengisinya justru jauh lebih berat. Sebab, setelah itu, Belanda datang lagi dan hendak melanjutkan dinasti penjajahannya; menguras habis kekayaan bangsa Indonesia , seraya membawa Missi Zending, di samping peradaban barat yang liberalis itu. Sebenarny4 kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilihat secara terpisalt dengan situasi internasional, dimana pada saat itu gelombang perang kemerdekaan 12 13 relatif terjajah, terutama dunia dari segenap bangsa-bangsa dunia ketiga yang masing-masing, yaitu upaya Islam untuk merebut dan menunutut kemerdekaannya serta ikut membebaskan diri untuk menentukan nasib dan kedaulatannya menentukan peradaban dunia umunnya' yang.tak Kemerdekaan bagi bangsa ini dirasakan sebagai karunia Allah panjang rakyat yang tertandingkan -

Tesis Implikasi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia
TESIS IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA Dosen Pembimbing: Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si. Hj. Ni’matul Huda, SH, M.HUM. Disusun oleh NAMA : LUTHFI AJI ASMORO NIM : 03 M 00 36 BKU : HTN/HAN Program Studi : Ilmu Hukum PROGRAM MAGISTER (S-2) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2009 I LEMBAR PENGESAHAN IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA Disusun oleh NAMA : LUTHFI AJI ASMORO NIM : 03 M 00 36 BKU : HTN/HAN Program Studi : Ilmu Hukum TELAH DISETUJUI OLEH: Pembimbing I Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M,Si. Tanggal …………………… Pembimbing II Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum Tanggal …………………… Mengetahui, Ketua Program II DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H Tanggal …………………….. LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA TESIS Oleh: LUTHFI AJI ASMORO Nomor Mahasiswa : 03 M 00 36 BKU : HTN/HAN Program Studi : Ilmu Hukum Telah dipertahankan di hadapan Dewan penguji Pada tanggal 07 Januari 2009 dan dinyatakan LULUS Tim Penguji: Ketua, Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M,Si. Tanggal ……………… Anggota Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum. Tanggal ……………… Anggota, Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. Tanggal ……………… Mengetahui, Direktur Program III Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal ……………… ABSTRAKSI IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA Pasca jatuhnya Orde Baru, terjadi dua perubahan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya adalah kebebasan berpolitik masyarakat dan adanya perubahan UUD 1945. Perubahan kebebasan politik memunculkan lahirnya partai-partai politik peserta pemilu dan perubahan UUD 1945 menguatkan sistem pemerintahan presidensiil. Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sistem kepartaian dan sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasi dari kombinasi sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia serta untuk mencari model sistem pemerintahan yang sesuai dengan negara Indonesia. -

Laporandekandiesnatal Iske 5 4 , Fakultasilmusosialuny , 1
L A P O R A N D E K A N D I E S N A T A L I S K E 5 4 , F A K U L T A S I L M U S O S I A L U N Y , 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 9 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua o Yang saya hormati, Rektor UNY, Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. o Yang saya hormati, Bapak/Ibu sesepuh/Dekan Senior, Fakultas Ilmu Sosial UNY ke 10. Bapak Sardiman AM, M.Pd. o Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Irwan Abdullah, yang akan memberikan pidato ilmiah pada hari ini dengan tema “I Don’t Care: The Lost of Social Engagement in Post-Truth Era of Indonesia” o Yang saya hormati, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat UNY o Yang saya hormati, Bapak-bapak Wakil Rektor UNY o Yang saya hormati, Bapak Ketua/Sekretaris Dewan Pertimbangan UNY o Yang saya hormati, Ibu Ketua BPPU UNY o Yang saya hormati, Bapak Ketua Satuan Pengawas Internal o Yang saya hormati, Bapak Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat FIS UNY o Yang saya hormati, para Dekan se lingkungan UNY o Yang saya hormati, Direktur Pascasarjana UNY o Yang saya hormati, Ketua Lembaga (LPPM dan LPPMP) o Yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan PT Mitra FIS UNY o Yang saya hormati, para Wakil Dekan FIS dan FE UNY o Yang saya hormati, Bapak Ibu Kajur/Kaprodi FIS UNY o Yang saya hormati, Bapak/Ibu dosen, Ibu Kabag FIS dan FE, dan Bapak/Ibu Kasubag FIS dan FE, serta tendik FIS UNY o Yang saya hormati, Bapak/Ibu Muspika Kec. -

The Case Political Crime “Papa Asking Stock of PT. Freeport Indonesia”
26 International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 26-36 Corruption Culture on Managing Natural Resources: The Case Political Crime “Papa asking Stock of PT. Freeport Indonesia” Bambang Slamet Riyadi1,2,* and Muhammad Mustofa2 1Lecture of Law at Faculty of Law, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; Student of Doctoral Criminology, Departement of Criminology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Indonesia, Campus Universitas Indonesia Depok, Depok City, West Java, Indonesia; Student of Law Program Doctoral, Faculty of Law, Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia 2Profesor of Criminolgy at Departement Criminology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Indonesia, Campus Universitas Indonesia Depok, Depok City, West Java, Indonesia Abstract: This research is the result criminology study on corruption culture of abusing the office and power involved the political elite and state officials in case of 'papa asking the stock’ related to the extension of mining contract of PT. Freeport Indonesia. This research is based on the concept of corruption culture, criminological theories and views of some economic and political observers. The research findings revealed the existence of corruption culture on political crime agreement scenario in case of “Papa Asking The Stock” that are provoking the extension of concentrates export license, diversion of issues and political lobbying to suppress stock divestment and smelter development. The nature of social structures and socio-cultural situations, responses to social situations and relationships with the perpetrators affecting individuals and groups crime behavior. A previous social culture behavior encourages learning in behavior at the society afterwards. State creates the crime laws to protect and maintain its power. The perpetrators rationalize the criminal act on securing and save their interests. -

Indonesia - Jilid 3 3 Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia • Institusi Dan Gerakan •
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3 3 Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia • Institusi dan Gerakan • i Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Institusi dan Gerakan JILID 3 Editor Jilid 3 Azyumardi Azra Jajat Burhanuddin Taufik Abdullah Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM INDONESIA Jilid 3 Pengarah: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2. Direktur Jenderal Kebudayaan Penanggung Jawab: Endjat Djaenuderadjat Amurwani Dwi Lestariningsih Penulis: Muhammad Iskandar Azyumardi Azra Muhammad Hisyam Zulkifli Setyadi Sulaiman Ahmad Najib Burhani Jajat Burhanudin Yon Machmudi Didi Ahmadi Moeslich Hasbullah MUhammad Wildan Asep Saepudin Jahar M. Dien Madjid Riset Ilustrasi: Isak Purba, Agus Widiatmoko, Siti Sari, Hermasari Ayu Kusuma, Tirmizi, Budi Harjo Sayoga, Maemunah, Esti Warastika, Dian Andika Winda, Bariyo, Haryanto, Rina Pujiarti, Wastilah, Putri Arum Setyawati, Suniarti, Mulyadi Amir, Mawanto Tata Letak & Desain: Iregha Kadireja Martina Safitry Keterangan Cover: Kiai sedang mengajar kitab kepada para santri di lingkungan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Sumber Cover: Dokumentasi Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Sumber Peta: KITLV Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 9, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270 Tel./Fax.: 021-572 5044 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG: Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari penerbit CETAKAN 2015 ISBN: 978-602-1289-00-6 ISBN: 978-602-1289-12-9 ii Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3 BAB X Gerakan Islam Kampus: Sejarah dan Dinamika Gerakan Mahasiswa Muslim alam sejarah Indonesia, tercatat ada tiga periode penting menyangkut Tiga periode penting gerakan Islam oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. -

LAPORAN AKADEMIK HASIL PENELITIAN Klaster Pembinaan Kapasitas/ Penelitian Pemula
No. Reg : 191140000018068 ID Peneliti : 200512870207000 LAPORAN AKADEMIK HASIL PENELITIAN Klaster Pembinaan Kapasitas/ Penelitian Pemula Judul : PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN; SUATU ANALISIS TERAHADAP PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Oleh Peneliti HENDRA GUNAWAN, MA NIDN. 2005128702 ID Peneliti 200512870207000 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019 PENELITIAN INI DIDUKUNG / DIBIAYAI OLEH DANA DIPA BOPTN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019 DAFTAR ISI Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------------- i Daftar Isi ------------------------------------------------------------------------------------------------- ii Bab I Penadahuluan A. Latar Belakang----------------------------------------------------------------------------- 1 B. Batasan Istilah------------------------------------------------------------------------------ 3 C. Rumusan Masalah-------------------------------------------------------------------------- 3 D. Tujuan Penelitian--------------------------------------------------------------------------- 3 E. Kontribusi----------------------------------------------------------------------------------- 3 F. Tinjauan Pustaka--------------------------------------------------------------------------- 3 G. Hipotesis------------------------------------------------------------------------------------ 7 H. Metode Penelitian-------------------------------------------------------------------------- -

Perjuangan Pemuda Sunda Masa Pergerakan Nasional (1919-1931)
HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4 (2). 2021. 159-172. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.32045 Available online at HISTORIA; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah website: https://ejournal.upi.edu/index.php/historia HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4 (2). 2021. 159-172 RESEARCH ARTICLE PERKUMPULAN SEKAR RUKUN: PERJUANGAN PEMUDA SUNDA MASA PERGERAKAN NASIONAL (1919-1931) Mohammad Refi Omar Ar Razy1 1Departemen Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia [email protected] To cite this article: Ar Razy, M.R.O. (2021). Perkumpulan sekar rukun: perjuangan pemuda sunda masa pergerakan nasional (1919-1931). HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4 (2). 2021. 159-172, DOI: https://doi.org/10.17509/ historia.v4i2.32045. Naskah diterima : 9 Februari 2021, Naskah direvisi : 15 April 2021, Naskah disetujui : 20 April 2021 Abstract This study aims to analyze the work of the Sekar Rukun Association during the National Movement (1919-1931), which includes the formation, form of struggle, and the process of its fusion with the Young Indonesia organization. The research method used is the historical method which consists of heuristic, source criticism, interpretation, and historiography stages. This research shows that the Sekar Rukun Association was first formed by Sundanese figures who attended school in Batavia, such as Doni Ismail, Iki Adiwidjaja Djuwariah Hilman, Moh. Sapii, Mangkudiguna, Soetisna Sendjaja and Iwa Kusumasumantri before finally Dr. Husein Djajadiningrat was involved in the Sekar Rukun Association. Second, the form of struggle for the Sekar Rukun Association is by working with youth organizations similar to during the National Movement such as Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Bataks, and so on. -

Download Download
P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754 Yupa: Historical Studies Journal Vol. 4 No. 1, 0000 (29-39) http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa Developing Digital Book Based on Lafran Pane' Thought for Increasing State Defend Attitude of Students Umi Azizah1, Djono2, Akhmad Arif Musaddad3 1Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 3Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 1 2 3 [email protected], [email protected], [email protected] Received Accepted Published 14/07/2020 02/09/2020 10/09/2020 Abstract In the globalization era, technology development grows rapidly. The development of technology accompanied with the decreasing of states defend attitude among Indonesian. This phenomenon evidenced by development of life that has been influenced by foreign culture, of sectarian solidarity, individualism, primordial, and the moral degradation of Indonesian which can threaten the integration of the nation. Education has an important role to deal with these problems. Teachers must be able to find instructional innovations that can be used to improve state defend attitude of students, because very important for future of the nation. Instructional innovation can be used by revive characters which it contains the values of state defend in the form of digital books. Lafran Pane is one of the Indonesian heroes who have thoughts about an intellectual's attitude towards the progress of the nation and state, especially students. Lafran Pane emphasized that student must be able to love their homeland, be hold on their beliefs, reform of thought in all fields, create harmony between religions, and be aware of their obligations as a fighter to elevate national dignity. -

Sejarah Paket C Indonesia Merdeka Modul 9 Awal.Indd
MODUL TEMA 9 MODUL 9 Indonesia Merdeka i Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang Kata Pengantar Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA/MA Modul Tema 9 : Indonesia Merdeka endidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang Penulis: Sulaiman Hasan karena kondisi geografi s, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengiku- ti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan Diterbitkan oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- P dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi iv+ 36 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari. Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip fl exible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Kon- sekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri. Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompe- tensi 2 (kelas 4 Paket A).