Prinsip Toleransi Sunan Kalijaga Dan Kontribusinya Dalam Islamisasi Masyarakat Jawa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Islamic Education and Linguistic Issues: Indonesian Experience
ISLAMIC EDUCATION AND LINGUISTIC ISSUES: INDONESIAN EXPERIENCE Anis Malik Thoha Susiyanto [email protected] ABSTRACT Some languages have played an important role as the medium for the revelation of God to mankind. The existence of such language is to bridge the communication of the Prophet who was sent to his people. Thus, the existence of language as a medium of communication in propaganda is desperately needed between mad’u (object of da'wah) and preachers (actor of da'wah). It is understood that a language other than Arabic, serves as an introduction to preaching to the local non-Arab community. The local non-Arabic language as the language of propaganda has not been used as the way it was. There is a process to be followed, namely what is called by S.M.N. Al-Attas as the concept of Islamisation of Language. Linguistic aspects and translation of Islamic values by using the local language of instruction at least prove that Islam is not synonymous with Arab, although the Arabic is used as the language of science. Even here it appears that Islam tends to appreciate the various expressions of culture, including the linguistic aspects. Local and regional languages, when Islam has been embedded in the hearts of non-Arab nations, have not necessarily been lost and destroyed. On the contrary, these languages have increased in terms of the aspects of ethics, morality, and enrichment of terminological. In this very section, the Islamic education plays an important role in the development of linguistics and literacy, both in terms of the scientific language and medium of introduction for propaganda. -

Religious Leader and Charismatic Leadership in Indonesia:The Role of Kyai in Pesantren in Java
KAWISTARA VOLUME 3 No. 2, 17 Agustus 2013 Halaman 117-226 RELIGIOUS LEADER AND CHARISMATIC LEADERSHIP IN INDONESIA:THE ROLE OF KYAI IN PESANTREN IN JAVA Ferry Muhammadsyah Siregar Inter-Religious Study Universitas Gadjah Mada Email:[email protected] Nur Kholis Setiawan Universitas Islam Negeri Sunan .alijaga <ogyaNarta Robert Setio Universitas Nristen 'uta :acana <ogyaNarta ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang peran kyai di pesantren di Jawa dengan fokus pada peran-peran pemimpin agama (kyai) di pesantren serta menggunakan konsep dan teori Max Weber tentang kepemimpinan agama dan karisma. Tulisan ini menggunakan data kualitatif untuk analisis bahan yang dikumpulkan dari pengamatan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa struktur dan pola kepemimpinan kyai dalam pesantren yang masih kuat di mana kyai diposisikan sebagai tokoh utama. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin non- formal dalam masyarakat melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Karisma kyai juga memperoleh dukungan rakyat karena stabilitas moral dan kualitas keimanan. Proses ini pada awalnya dimulai dari kelompok terdekat sekitar pesantren dan kemudian menyebar secara luas. Kata Kunci: Pemimpin Agama, Kepemimpinan Karismatik, Karisma, Peran kyai, Pesantren. ABSTRACT This paper discusses on the role of the kyai in pesantren in Java. It addresses on the roles of religious leader in pesantren. It applies Max Weber’s concept on religious leadership and charisma. It uses qualitative data for analysis of materials collected from observations and library research. This research Ànds that the structures and patterns of leadership and power of Kyai within pesantren are strong in which kyai is positioned as the main Àgure. -

The Closer Bridge Towards Islamic Studies in Higher Education in Malaysia and Indonesia
Creative Education 2012. Vol.3, Special Issue, 986-992 Published Online October 2012 in SciRes (http://www.SciRP.org/journal/ce) http://dx.doi.org/10.4236/ce.2012.326149 The Closer Bridge towards Islamic Studies in Higher Education in Malaysia and Indonesia Abd. Rachman Assegaf1, Abd. Razak Bin Zakaria2, Abdul Muhsein Sulaiman2 1State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 2Faculty of Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia Email: [email protected], [email protected], [email protected] Received June 25th, 2012; revised July 28th, 2012; accepted August 14th, 2012 The transformations of Islamic higher education in Indonesia have occurred since the establishment of STI to PTAIN, then IAIN and UIN. It has tremendous impact on the implementation of models of Islamic studies. At early stage of development, Islamic higher education in this country tends to follow a norma- tive-idealistic approach of Islamic studies due to the huge influences of many Middle Eastern graduates. However, changes of Islamic studies approach come to exist when the Western graduates bring non- scriptualistic methodologies and multidisciplinary approach in Islamic studies. If compared to Malaysia, the two poles of Eastern or Western and Islamic or non-Islamic higher education types have been inte- grated with the paradigm of Islamization of knowledge. Recent development indicates that Malaysian and Indonesian universities have intensified their mutual cooperation through U to U or G to G Memorandum of Understanding. There are several ways of encounters, namely teacher (or lecturer) and student ex- changes, literature line, bilateral cooperation, and informal factors. With the closer link between the two people of these countries, the bonds between Islamic studies connecting the two countries have become closer. -

Representasi Pendidikan Karakter Dalam Film Surau Dan Silek (Analisis Semiotik Ferdinand De Saussure)
REPRESENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM FILM SURAU DAN SILEK (ANALISIS SEMIOTIK FERDINAND DE SAUSSURE) Putra Chaniago, S. Sos Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 e-mail : [email protected] Abstrak : Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam ranah komunikasi Islam pada Film Surau dan Silek. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis semiotika Ferdinan de Saussure. Dalam metodenya ia mengembangkan dua sistem yaitu penanda, pertanda serta makna yang terkandung dan yang ingin disampaikan di dalamnya. Film ini merupakan film budaya berbahasa Minangkabau yang mengandung tutur nasihat. Film ini bercerita tentang kehidupan tiga remaja Minang yang sedang semangat berlatih silat, namun mereka ditinggalkan oleh Mak Rustam sang guru silat yang memutuskan untuk pergi merantau. Penelitian ini menemukan terdapat representasi pendidikan karakter dalam film surau dan silek, yaitu silek mengajarkan kesimbangan antara emosional question (kecerdasan emosional), spiritual question (kecerdasan spritual), intelegens question (kecerdasan intelejen) dan heart question (kecerdasan hati). Film Surau dan Silek mengandung banyak pesan moral, nilai-nilai agama dan budaya, sehingga mampu merubah persepsi tentang silat di Minang yang tak hanya sebagai aktifitas pemuda nagari untuk berkelahi, namun juga sebagai pendidikan karakter dari perspektif Islam dan adat Minang, yaitu mengamalkan agama Islam sebagai ajaran, dan melestarikan budaya surau dan silat sebagai aktifitas pemuda Minang. Abstract : This study discusses the value of character education values in the realm of Islamic communication studies in Surau and Silek films. This type of research is descriptive qualitative using the semiotic analysis method of Ferdinand de Saussure. In his method, he developed two systems, namely the signifier, the sign and the meaning that is contained and what is intended to be conveyed in it. -

Out of a Crocodile's Mouth, Enter a Tiger's Snout
Out of A Crocodile’s Mouth, Enter A Tiger’s Snout: Kingship in Cirebon and the Dutch East India Company’s Intervention in the Late Seventeenth Century M.A. Thesis Satrio Dwicahyo Supervisor: Dr. Lennart Bes Table of Contents Table of Contents.................................................................................................................................................... 1 List of Pictures, Maps, and Tables .......................................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................................ 3 Cirebon as A Sovereign ..................................................................................................................................... 4 Cirebon between Major Powers ........................................................................................................................ 8 Research Question ........................................................................................................................................... 11 Previous Related Studies ................................................................................................................................. 12 Sources and Challenges .................................................................................................................................. 14 Structure of the Study..................................................................................................................................... -

Chapter Iii Sunan Muria and Relationship Before
CHAPTER III SUNAN MURIA AND RELATIONSHIP BEFORE MARRIAGE A. SUNAN MURIA 1. Sunan Muria’s Lineage According to folklore, and the prevailing view in the literature of Java, Islam came and spread in Java is thanks to nine islamic spreaders who are members of a council called Walisongo.1 One of Walisongo is Sunan Muria. Sunan Muria’s personal name is Raden Prawoto some say, others say he is Raden Umar Said. He called Sunan Muria because it relates to the name of the mountain where he was buried mount muria, because Sunan Muria was classified as members of Walisongo who younger generation than Sunan Kalijaga and Sunan Kudus, insufficient life story written in full by the author except in the story said historiography with a number of differences, including regarding the pedigree of which actually originated Sunan Muria.2 According to the first version, as written Solihin Salam in Sekitar Wâlî Sanga (1974) and AM Noertjahjo in Cerita Sekitar Wali Sanga (1974), Sunan Muria is mentioned as the eldest son of Sunan Kalijaga from his marriage with Dewi Sarah Maulana Ishaq’s daughter. Sunan Muria was born with the name Raden Umar Said.He has two younger sisters, they are Dewi Rukayah and Dewi Sofiyah. When an adult, Raden Umar Said married with Dewi Sujinah, Ja'far Sadiq’s younger sister, or Sunan Kudus, Raden Usman Haji’s son or Sunan Ngudung.3 Meanwhile, according to the second version that is based on the manuscript of Pustoko Agung compiled and summarized by R. Darmowasito and 1 Ridin Sofwan,e.t Op.Cit., p. -
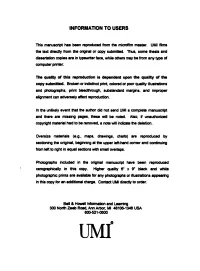
Information to Users
INFORMATION TO USERS Thil m8l1uscript ha. been repraduced from the microfilm m.ter. UMI film. the tut directly tram the original or copy submitted. Thul, some "Ii. and dillertation copie••re in typewriter face, while otherIlTI8Y be tram any type ~ computer printer. The qu.11ty of thls Nproctuctlon 1. dependent upon .... quallty of .. copy submitted. Broken or indistinct prim, c:aIor8d orpoor quality illustrations and photogl1lphs, print bIIedthrough, lubstandllrd margina, and improper alignment can adversely 8ffect reproduction. ln the W1likely event that the 8Uthor did not send UMI a comple. manuscript and there are miuing pages, theIe will be noteel. Allo, if unauthorized copyright materi81 had to be removed, a note will indieate the deletion. Oversize materials (•.g., mapl, drawingl, charls) are reproduced by sectioning the original, begiming 8t the upper 1eft-tw1d corner and continuing from Ieft ta right in equal sections with small overlaps. Photographs inclucted in the original manulCripl h8ve been repraducect xerographically in thi. ccpy. Higher quelity e- x r bI8ck and white photognlPhic printl are ••il8b1e for MY photogripM or illustnltionl .ppearing in thil capy for ... Mklitionai chIrge. Contact UMI directly ta orcier. Bell & Howell Information and Lelming 300 North Z8eb Rœd, Ann Arbor, MI 481C&1348 USA 800-521-œoo ISLAM ABD JAVAlŒSB ACCULTURATION: TEXTUAL AND CONTEXTUAL AlfALYSIS OF THB sz..tJImTANRlTUAL A thesis submitted ta the Faculty of Graduate Studies and Research In partial fulfillment ofthe requirements ofthe degree of Master ofArts by Masclar HUmy Institute ofIslamic Studies McGill University Montreal Canada CMasdar Hilmy 1999 National Ubrary Bibliothèque nationale 1+1 otCanada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 385 WIIIingIon Street 385. -

23 Bab Ii Biografi Sunan Kalijaga Dan Kidung
BAB II BIOGRAFI SUNAN KALIJAGA DAN KIDUNG RUMEKSO ING WENGI A. Biografi Sunan Kalijaga Kisah tentang kiprah kewalian Sunan Kalijaga yang penuh dengan bumbu mistik mempunyai beberapa ragam versi. Sebab sumber orisinil dari kisah tersebut tidak tersedia. Menurut Ricklefs, sebelum ada catatan Belanda, kisah tentang Sunan Kalijaga memang tidak memiliki data yang dapat dipercaya mengenai sejarah Jawa. Kemungkinan keragaman versi kisah tersebut terjadi sebab disampaikan secra tutur oleh juru pamekas lalu sedikit demi sedikit terdistorsi setelah para pengagum dan penentangnya.1 1. Nama dan Asal-usul Raden Sahid merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga putra seorang bupati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta, yang memiliki istri bernama Dewi Nawangrum.2 Selain nama Raden Sahid (atau dieja dengan Raden Said menurut beberapa literatur), Sunan Kalijaga juga dikenal dengan dengan sejumlah nama, yaitu Syaikh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama-nama 1 Hariwijaya, Islam Kejawen, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), 282. 2Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 147. 23 24 tersebut memiliki jalinan erat dengan perjalanan kisah hidupnya sejak bernama Raden Sahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga.3 Dalam Babad Tanah Jawi menyebutkan bahwasanya Tumenggung Wilatikta adalah nama ayah dari Raden Sahid, yang dikatakan dalam Babad Tuban sebagai anak dari seseorang yang bukan asli pribumi jawa yakni Arya Teja.4 Nama aslinya adalah Abdurrahman merupakan orang keturunan Arab sekaligus Ulama yang berhasil mengislamkan Bupati Tuban, Arya Dikara dan menjadi menantunya. Ketika Abdurrahman menggatikan mertuanya menjadi Bupati Tuban dan mengubah namanya menjadi Arya Teja. Dari pernikahannya dengan putri Arya Dikara inilah, ia dikarunia seorang anak bernama Arya Wilatikta.5 Sebelum menikahi putri Arya Adikara, Arya Teja telah menikah dengan dengan putri bupati Surabaya, Arya Lembu Sura. -

Original Research Articleoriginal Research Article Open Access
Available online at http://www.journalijdr.com ISSN: 2230-9926 International Journal of Development Research Vol. 09, Issue, 02, pp.25569-25573, February, 2019 ORIGINAL RESEARCH ARTICLEORIGINAL RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS ESTABLISHING SPACE UNITY BETWEEN TRADITIONAL AND RELIGIOUS RITUALS AT KADILANGU-DEMAK *1Marwoto, 2Sugiono Soetomo, 2Bambang Setioko and 2Mussadun 1Departement of Architecture Kebangsaan University, Bandung Indonesia 2Departement of Architecture Diponegoro University, Semarang, Indonesia ARTICLE INFO ABSTRACT Article History: In general, tradition is a culture of society who cling to the norms that have been outlined by its Received 29th November, 2018 predecessors. This form of tradition concerns the important ritual of the human being upon Received in revised form entering a special stage of life which involves ritual and prayer. The case of traditions and rituals 27th December, 2018 space that occurred in Kadilangu Demak illustrates the element of religious submission that does Accepted 01st January, 2019 not eliminate the tradition that has been running before. While the Islamic religion introduced by th Published online 27 February, 2019 the Wali does not necessarily change the Hindu tradition into Islam in total. Kadilangu community even has a tradition that comes from Hindu culture and adapted to the teachings of Key Words: Islam. The question is to what extent do these two aspects affect the structure of cultural space Cultural Space, and religious rituals use? It takes a descriptive observational approach to the phenomenon that Spiritual Space, occurs based on cultural space and religious rituals so that it can explain its development and Slametan, Kliwonan, characteristics of cultural messages to be conveyed. -

The Role of Chinese in Coming of Islam to Indonesia: Teaching Materials Development Based on Multiculturalism
Paramita:Paramita: Historical Historical Studies Studies Journal, Journal, 27 (2),27(2), 2017: 2017 238 -248 ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v27i2.8660 THE ROLE OF CHINESE IN COMING OF ISLAM TO INDONESIA: TEACHING MATERIALS DEVELOPMENT BASED ON MULTICULTURALISM Hendra Kurniawan Department of History Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta ABSTRACT ABSTRAK The aim of this research was to describe the Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan role of Chinese in coming of Islam to Indone- peran Tionghoa dalam masuknya Islam ke sia in XV-XVI century and developed it into a Indonesia pada abad XV-XVI dan mengem- history teaching materials based on multicul- bangkannya menjadi bahan ajar sejarah ber- turalism. It was a library research with histori- basis multikulturalisme. Penelitian ini merupa- cal approach. Data that were obtained from kan penelitian kepustakaan dengan pendeka- various sources analyzed by qualitatively de- tan historis. Data yang diperoleh dari berbagai scriptive into teaching materials integrated sumber dianalisis secara kualitatif deskriptif into curriculum. The results showed that there menjadi bahan ajar untuk diintegrasikan ke were some historical facts, strengthen the role dalam kurikulum. Hasil penelitian menunjuk- of Chinese in the coming of Islam to Indonesia kan bahwa terdapat berbagai fakta sejarah in the XV-XVI centuries. The study compiled yang menguatkan peran Tionghoa dalam ma- into teaching materials that can be integrated suknya Islam ke Indonesia pada abad XV- into curriculum 2013 on Indonesian History XVI. Kajian tersebut disusun menjadi bahan subjects for high school class X. Developed ajar yang dapat diintegrasikan ke dalam Ku- teaching materials can disseminated multicul- rikulum 2013 pada mata pelajaran Sejarah turalism values in students to realize a harmo- Indonesia untuk SMA kelas X. -

Perkembangan Arsitektur Mesjid Walisongo Di Jawa (Ashadi)
Perkembangan Arsitektur Mesjid Walisongo di Jawa (Ashadi) PERKEMBANGAN ARSITEKTUR MESJID WALISONGO DI JAWA : PERUBAHAN RUANG DAN BENTUK Ashadi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta [email protected] ABSTRAK. Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan- kebutuhan masyarakat muslim, arsitektur mesjid sebagai sarana tempat ibadah umat Islam cenderung pula mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi pula pada mesjid-mesjid awal perkembangan Islam di Jawa yang pada umumnya disangkutpautkan dengan para mubaligh Wali Songo. Dengan pendekatan historis, tulisan ini berusaha memperlihatkan perubahan-perubahan ruang dan bentuk dalam arsitektur mesjid Wali Songo melalui tema-tema keruangan dan modernitas. Kata kunci : Keruangan memusat, tradisionalitas, modernitas ABSTRACT. As period of time changes all the time and as the needs of moslem community had increased, an architecture of mosque as a prayer facility for moslem has tend to be changed as well. Those changes had happened to mostly mosques within early Islam development in Java, which generally had been related to “Wali Songo”. By using historicalcopyright approach, this paper is trying to seek the changes of architectural space and form within architecture of Wali Songo’s mosque through spatial themes and modernity. Keywords : centered space, traditionality, modernity 143 NALARs Volume 11 No 2 Juli 2012 : 143-160 PENDAHULUAN Perkembangan Islam pada periode awal di pulau Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo (Wali yang jumlahnya sembilan), yakni sembilan mubaligh Islam yang dianggap sebagai kepala dari sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas menyiarkan agama Islam di daerah-daerah di pesisir utara pulau Jawa. Mereka adalah Maulanan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. -

Stream Politics in the Transfer of Power from Demak to Pajang
REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ISSN: 2146-0353 ● © RIGEO ● 11(2), SPRING, 2021 www.rigeo.org Research Article Stream Politics in the Transfer of Power from Demak to Pajang Imam Sukardi1 Anang Harris Himawan2 Faculty of Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Department of History Education, Faculty of Surakarta, Indonesia. Education and Teacher Training, Sebelas Maret [email protected] University. [email protected] Abstract The current historical theme concerning the transfer of power from Demak to Pajang was chosen because it has remained a discourse among scholars, particularly of history, to this day. Historians have opposing views regarding the background of the establishment of the Sultanate of Pajang. First, the founding of Pajang in the 16th century was, consequently, due to the Sultanate of Demak’s inability to prevent the fall of Melaka and Maluku, serving as wealth “repository” areas for Java (Demak), into the hands of the Portuguese, which resulted in a political and economic crisis in Demak, thus forcing the coastal political power house to relocate further inland to Pajang. Second, the founding of Pajang was the result of an internal political conflict within the Demak Sultanate reaching its peak, and it had transpired since the death of the First Sultan of Demak, Raden Patah. Third, the founding of Pajang signified the return of Majapahit Empire’s “throne” to its rightful heir, namely the descendants of Andayaningrat, Brawijaya’s son-in-law from the empress Dyah Annarawati. Fourth, the founding of Pajang was the culmination of a political struggle between two major religious streams championed by their respective Wali (saint of Islam in the archipelago), wherein the Walis of the coast, who adhered to genuine Islamic teachings (conservative, puritan, muti’ah) and represented by Sunan Kudus, faced the Walis of the inland (moderate, aba’ah) who were represented by Sunan Kalijaga.