In Search of Peace: Ahmadi Women's Experiences in Conflict Transformation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia
This article was downloaded by: [Ahmad Najib Burhani] On: 20 December 2013, At: 14:15 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Islam and Christian–Muslim Relations Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/cicm20 The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences Ahmad Najib Burhania a Research Center for Society and Culture (PMB), Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia Published online: 18 Dec 2013. To cite this article: Ahmad Najib Burhani , Islam and Christian–Muslim Relations (2013): The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences, Islam and Christian–Muslim Relations, DOI: 10.1080/09596410.2013.864191 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09596410.2013.864191 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

Tuan Guru and Ahmadiyah in the Redrawing of Post-1998 Sasak-Muslim Boundary Lines in Lombok
CONTESTED IDENTITIES: TUAN GURU AND AHMADIYAH IN THE REDRAWING OF POST-1998 SASAK-MUSLIM BOUNDARY LINES IN LOMBOK BY SITTI SANI NURHAYATI A thesis submitted to Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Victoria University of Wellington 2020 i Abstract This study examines what drives the increasing hostility towards Ahmadiyah in post- Suharto Lombok. Fieldwork was undertaken in three villages – Pemongkong, Pancor and Ketapang – where Ahmadiyah communities lived and experienced violent attacks from 1998 to 2010. The stories from these villages are analysed within the context of a revival of local religious authority and the redefinition of the paradigm of ethno-religious identity. Furthermore, this thesis contends that the redrawing of identity in Lombok generates a new interdependency of different religious authorities, as well as novel political possibilities following the regime change. Finally, the thesis concludes there is a need to understand intercommunal religious violence by reference to specific local realities. Concomitantly, there is a need for greater caution in offering sweeping universal Indonesia-wide explanations that need to be qualified in terms of local contexts. ii iii Acknowledgements Alhamdulillah. I would especially like to express my sincere gratitude and heartfelt appreciation to my primary supervisor, Professor Paul Morris. As my supervisor and mentor, Paul has taught me more than I could ever give him credit for here. My immense gratitude also goes to my secondary supervisors, Drs Geoff Troughton and Eva Nisa, for their thoughtful guidance and endless support, which enabled me, from the initial to the final stages of my doctoral study, to meaningfully engage in the whole thesis writing process. -

Masyarakat Indonesia Edisi XXXVII / No
Masyarakat Indonesia Edisi XXXVII / No. 2 / 2011 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA MASYARAKAT INDONESIA MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA Edisi XXXVII No. 2, 2011 DAFTAR ISI Hlm. MINORITISASI AHMADIYAH DI INDONESIA ........................ 1 Amin Mudzakkir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia KASUS MULTIKULTURALISME BELANDA SEBAGAI KRITIK ATAS UTOPIA MULTIKULTURALISME INDONESIA ....................... 25 Ibnu Nadzir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PEMETAAN SOSIAL-POLITIK KELOMPOK ETNIK CINA DI INDONESIA ....................................................... 47 Amri Marzali Akademi Pengajian Melayu-Universiti Malaya REISLAMIZING LOMBOK: CONTESTING THE BAYANESE ADAT ..................................... 85 Erni Budiwanti Indonesian Institute of Sciences DINAMIKA KEHIDUPAN MINORITAS MUSLIM DI BALI .... 115 Indriana Kartini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia EDISI XXXVII / NO.2 / 2011 | iii NASIONALISME ETNIK DI KALIMANTAN BARAT ............... 147 Kristianus Universitas Kebangsaan Malaysia STREET CHILDREN AND BROKEN PERCEPTION ................. 177 A Child’s Right Perspectives Lilis Mulyani Indonesian Institute of Sciences BAHASA MINORITAS DAN KONSTRUKSI IDENTITAS ETNIK PADA KOMUNITAS BAHASA KUI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR .............. 199 Katubi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TINJAUAN BUKU UPAYA MENGELOLA KERAGAMAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI .....................................................................221 Muhammad Fakhry Ghafur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PEMIKIRAN PEMBARUAN DALAM ISLAM: PERTARUNGAN ANTARA MAZHAB -

131066 Sukmono 2020 E.Docx
International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020 Multicultural Communication and Survival Strategy of Ahmadiyya in Tawangmangu, Indonesia Filosa Gita Sukmonoa, Fajar Junaedib, Ali Maksumc, a,bDepartment of Communication, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, cDepartment of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmadiyya community in Indonesia often receive physical attacks from other Islamic communities that accused Ahmadiyya as not-Islam. For some Indonesians, Ahmadiyya holds a contentious Islamic identity, which for some people adulterates the cardinal canon of Islam. However, the Ahmadiyya community in Tawangmangu, Indonesia, experiences a reasonably inverse condition. By smartly managing cultural relations with local citizens (non-Ahmadiyya), Ahmadiyya’s people seem to live in harmony with the residents. The empirical study revealed that the Ahmadiyya community in Tawangmangu established multicultural relations in daily life by carrying out cultural approaches. The cultural approaches were intensive acculturation and integration with the host community. The Ahmadiyya community even used a football academy to attract the local community to engage indirectly in a social activity. Under this strategy, Ahmadiyya successfully maintains its original identity without disturbing local identities, cultures, and wisdom. Key words: Ahmadiyya, local community, multicultural communication, integration, Indonesia. Introduction In the post-1998 reformation, the sectarian-based multicultural conflict has become one of the crucial issues in community life in Indonesia. Minority groups, in general, are often targeted by both physical attacks and other forms of persecution. Generally, these attacks and persecutions were carried out by the majority groups in the local area. The issue that often becomes the trigger for the conflict is related to the alleged deviation of religious rituals. -

Religious Violence in the Indonesian Democratic Era1
RELIGIOUS VIOLENCE IN THE INDONESIAN DEMOCRATIC ERA1 Hasse J & Mega Hidayati [email protected] & mhidyati.gmail.com Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstract The Indonesian democratic era has provided hope for the growth of mutual social practices established upon diversity of ethnicity, religions, race, and inter-group relations. Yet, in the last decade, various forms of violence were often carried out on behalf of religion instead. These acts of violence were not only physical but psychological (cultural) as well, in the form of discrimination, abuse, expulsion, insult, and threat. The Ahmadiyya sect and Shia cases, for instance, provide an outlook regarding the prevalence of violence within social practices in the community in response to differences. Why does such violence remain to occur in Indonesia? Aside from a ‘failed understanding of religious texts’, excessive truth claim also triggers acts of religious violence in the current era of Indonesian democracy. It is of utmost importance that people’s understanding and interpretation of differences be set straight so that any response to differences can be considered as an embryo of national power that serves as an instrument employed for uniting the people of this nation instead of disuniting them. Keywords: religious violence, democratic era, Indonesia. INTRODUCTION The reality of diverse ethnicities, races, and religions found in Indonesia is a blessing that makes for more complete and dynamic order in life. The diversity of this nation has evolved and developed into the strong pillar that it is until this day. During the pre-independence era, the diverse entities above became united to fight against the colonialists. -

Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship (A Case Study of Ahmadiyya Community in Tasikmalaya)
Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship (A Case Study of Ahmadiyya Community in Tasikmalaya) Ach. Fatayillah Mursyidi1*, Zainal Abidin Bagir2, Samsul Maarif3 1 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; e-mail: [email protected] 2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; e-mail: [email protected] 3 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia; e-mail: [email protected] * Correspondence Received: 2020-08-27; Accepted: 2020-11-30; Published: 2020-12-30 Abstract: Citizenship is among the notions mostly contested after the collapse of a long-standing authoritarian regime in 1998. The reform era – after 1998 - radically transformed Indonesia into a democratic country and brought many other issues including minority issues into the forefront. Unlike other countries that draw their citizenship on a clear formula between religious and secular paradigm, Indonesia, due to ambivalence of its religion-state relation, exhibits fuzzy color of citizenship that leaves space for majority domination over the minority. In consequence, the status of Ahmadiyya for instance, as one of an Islamic minority group, is publicly questioned both politically and theologically. Capitalized by two Indonesian prominent scholars, Burhani (2014) and Sudibyo (2019), I conducted approximately one-month field research in Tasikmalaya and found that what has been experienced by Ahmadiyya resembles Homo Sacer in a sense that while recognised legally through constitutional laws, those who violate their rights are immune to legal charges. This leads to nothing but emboldening the latter to persistently minoritise the former in any possible ways. Keywords: Ahmadiyya; Citizenship; Homo Sacer; Minority; Tasikmalaya. Abstrak: Kewarganegaraan termasuk di antara istilah yang kerap diperdebatkan pasca peristiwa runtuhnya rezim otoriter yang lama berkuasa pada tahun 1998. -

Freedom of Religion and Belief in the Southeast Asia
FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF IN THE SOUTHEAST ASIA: LEGAL FRAMEWORK, PRACTICES AND INTERNATIONAL CONCERN FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF IN THE SOUTHEAST ASIA: LEGAL FRAMEWORK, PRACTICES AND INTERNATIONAL CONCERN Alamsyah Djafar Herlambang Perdana Wiratman Muhammad Hafiz Published by Human Rights Working Group (HRWG): Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy 2012 1 Freedom of Religion and Belief in the Southeast Asia: ResearchLegal Framework, team Practices and International Concern : Alamsyah Djafar Herlambang Perdana Wiratman EditorMuhammad Hafiz Expert: readerMuhammad Hafiz : Ahmad Suaedy SupervisorYuyun Wahyuningrum : Rafendi Djamin FirstMuhammad edition Choirul Anam : Desember 2012 Published by: Human Rights Working Group (HRWG): Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy Jiwasraya Building Lobby Floor Jl. R.P. Soeroso No. 41 Gondangdia, Jakarta Pusat, Indonesia Website: www.hrwg.org / email: [email protected] ISBN 2 CONTENTS FOREWORD INTRODUCTION BY EDITOR Chapter I Diversities in Southeast Asia and Religious Freedom A. Preface ChapterB.IIHumanASEAN Rights and and Guarantee Freedom for of ReligionFreedom of Religion A. ASEAN B. ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) C. Constitutionalism, Constitutions and Religious Freedom ChapterD.IIIInternationalThe Portrait Human of Freedom Rights Instruments of Religion in in ASEAN Southeast StatesAsia A. Brunei Darussalam B. Indonesia C. Cambodia D. Lao PDR E. Malaysia F. Myanmar G. Philippines H. Singapore I. Thailand ChapterJ. IVVietnamThe Attention of the United Nations Concerning Religious Freedom in ASEAN: Review of Charter and Treaty Bodies A. Brunei Darussalam B. Indonesia C. Cambodia D. Lao PDR E. Malaysia F. Myanmar G. Philippines H. Singapore I. Thailand J. Vietnam 3 Chapter IV The Crucial Points of the Guarantee of Freedom of Religion in Southeast Asia A. -

A Pseudo-Secular Space, Religious Minority and Reasons for Exclusion: the Ahmadiyya Minority Group in Contemporary Indonesia
© 2019 Authors. Center for Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, Serbia.This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License Max Regus1 Review article STKIP ST. Paulus Ruteng UDC 321.7:28.284.5(594) Indonesia A PSEUDO-SECULAR SPACE, RELIGIOUS MINORITY AND REASONS FOR EXCLUSION: THE AHMADIYYA MINORITY GROUP IN CONTEMPORARY INDONESIA Abstract This paper examines the intersection of religion and politics and its conse- quences on religious minorities in Indonesia. This paper is based on a case study of the current position of the Ahmadiyya minority group in the Indonesian Is- lamic majority. The tension arises from a specific circumstance: This large Muslim country uses democracy as a political system, but the involvement of religious politics is evident. This situation directly endangers the presence of the Ahmadi- yya group. Keywords: Indonesia, Democracy, Islam, Ahmadiyya, Pseudo-Secular, Mi- norities, Exclusion Introduction This article—by considering the intersection of social-political spaces and the exclusion of religious minorities in Indonesia based on the current situation of the Ahmadiyya—aims to spread and emerge the discipline of ‘the politology of religion’.2 It is important first to introduce the profile of the Ahmadiyya mi- nority group. The group itself was founded in 1889 by Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) in the village of Qadian, Punjab, India. Several key factors encour- aged Mirza Ghulam Ahmad to initiate a new Islamic movement and therefore to build the Ahmadiyya. These include British colonialism in the South Asia region, degradation of Muslim culture in many areas, and the Christianization process undertaken by the western missionaries. -

Reclaiming Minority's Freedom of Religion Or Belief in Indonesia
Reclaiming Minority’s Freedom of Religion or Belief in Indonesia Evaluating State Response to the Ahmadiyya Conflict in Lombok, Indonesia Candidate number: 9003 Submission deadline: 15/05/2014 Number of words: 19,999 Abstract This study reveals a horizontal conflict in Indonesian society involving violation of the rights of a religious minority group and studies the state’s response to the conflict. The case to be analyzed in this study is the conflict between Nahdlatul Wathan and Ahmadiyya in Lombok, Indonesia. The Indonesian government undertook to resolve the conflict by establishing a Joint Ministerial Decree that prohibits the Ahmadis to believe in a new prophet and prohibits them to manifest their belief. Although freedom to manifest religion might be limited under certain clauses provided in article 18 (3) of the ICCPR, this study finds that the Joint Ministerial Decree does not satisfy most of criteria of the limitation clauses. Moreover, the decree also violates freedom of religion provided for by article 18 of the ICCPR (freedom of the internal forum that may not be derogated from under any circumstances) as well as the rights of persons belonging to a minority to practice their own religion under article 27 of the ICCPR. This study furthermore proposes alternative mechanisms for resolving the conflict as well as reclaiming the Ahmadis’ rights, using both a legal and a non-legal approach. Keywords: Freedom of religion, Minority, Conflict resolution. I TABLE OF CONTENT Abstract .................................................................................................................................. -
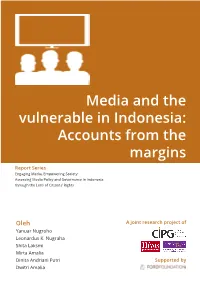
Media and the Vulnerable in Indonesia
Media and the vulnerable in Indonesia: Accounts from the margins Report Series Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens’ Rights Oleh A joint research project of Yanuar Nugroho Leonardus K. Nugraha Shita Laksmi Mirta Amalia Dinita Andriani Putri Supported by Dwitri Amalia Media and the vulnerable in Indonesia: Accounts from the margins. Published in Indonesia in 2013 by Centre for Innovation Policy and Governance Jl. Siaga Raya (Siaga Baru), Komp BAPPENAS No 43. Pejaten Barat, Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12130 Indonesia. www.cipg.or.id Cover designed by FOSTROM (www.fostrom.com); all rights reserved. Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License Some rights reserved. How to cite this report: (Nugroho, et al., 2012) - Nugroho, Y., Nugraha, LK., Laksmi, S., Amalia, M., Putri, DA., Amalia, D., 2012. Media and the vulnerable in Indonesia: Accounts from the margins. Report Series. Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Research collaboration of Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS Regional Office Southeast Asia, funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and HIVOS. Centre for Innovation Policy and Governance i Media and the vulnerable in Indonesia: Accounts from the margins Acknowledgements The research was funded by the Ford Foundation Indonesia Office and undertaken by the Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Jakarta and HIVOS Regional Office Southeast Asia Principal Investigator : Dr. Yanuar Nugroho, University of Manchester Co-investigator (CIPG), Coordinator : Mirta Amalia Co-investigator (HIVOS) : Shita Laksmi Researchers (CIPG) : Leonardus Kristianto Nugraha Dinita Andriani Putri Dwitri Amalia Academic Advisors : Dr. -

(FPI; Islamic Defenders Front) – Ahmadiyya – Mixed Marriages
Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research Response Number: IDN34570 Country: Indonesia Date: 26 March 2009 Keywords: Indonesia – Front Pembela Islam (FPI; Islamic Defenders Front) – Ahmadiyya – Mixed marriages This response was prepared by the Research & Information Services Section of the Refugee Review Tribunal (RRT) after researching publicly accessible information currently available to the RRT within time constraints. This response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. This research response may not, under any circumstance, be cited in a decision or any other document. Anyone wishing to use this information may only cite the primary source material contained herein. Questions 1. Please provide some general background about the Front Pembela Islam (FPI). Please also provide information on the relationship between the FPI and the police. 2. Please provide information on the relationship between the FPI and the Ahmadiyya. Please also provide information on the situation of the Ahmadiyya in Indonesia more generally. 3. What is the situation in Indonesia with regard to inter-faith marriages? Specifically: what information is available on the marriage of a Muslim man to a Christian female? RESPONSE 1. Please provide some general background about the Front Pembela Islam (FPI). Please also provide information on the relationship between the FPI and the police. The Front Pembela Islam (FPI; Islamic Defenders Front) is an Indonesian Islamist movement which has advocated for the implementation of conservative laws and whose activists have been involved in militant attacks upon groups, institutions and practices deemed un-Islamic and immoral by the FPI leadership. -

UPR13, Amnesty International Submission for the UPR Of
INDONESIA Stalled Reforms: Impunity, discrimination and security force violations in Indonesia Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May-June 2012 CONTENTS Introduction................................................................................................................. 3 Follow up to the previous review..................................................................................... 4 Normative and institutional framework of the State .......................................................... 5 Criminal Code and Criminal Procedure Code ................................................................ 5 Impunity .................................................................................................................. 5 Human rights and decentralized legislation.................................................................. 5 Promotion and protection of human rights on the ground.................................................. 6 Human rights violations by the security forces.............................................................. 6 Maternal health and sexual and reproductive rights....................................................... 6 Domestic workers ...................................................................................................... 6 Freedom of expression and human rights defenders ...................................................... 6 Discrimination and freedom of religion .......................................................................