Download This PDF File
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chinese Big Business in Indonesia Christian Chua
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ScholarBank@NUS CHINESE BIG BUSINESS IN INDONESIA THE STATE OF CAPITAL CHRISTIAN CHUA NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 CHINESE BIG BUSINESS IN INDONESIA THE STATE OF CAPITAL CHRISTIAN CHUA (M.A., University of Göttingen/Germany) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF SOCIOLOGY NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 i ACKNOWLEDGEMENTS Throughout the years working on this study, the list of those who ought to be mentioned here grew tremendously. Given the limited space, I apologise that these acknowledgements thus have to remain somewhat incomplete. I trust that those whose names should, but do not, ap- pear here know that I am aware of and grateful for the roles they played for me and for this thesis. However, a few persons cannot remain unstated. Most of all, I owe my deepest thanks to my supervisor Vedi Hadiz. Without him, I would not have begun work on this topic and in- deed, may have even given up along the way. His patience and knowledgeable guidance, as well as his sharp mind and motivation helped me through many crises and phases of despair. I am thankful, as well, for the advice and help of Mary Heidhues, Anthony Reid, Noorman Ab- dullah, and Kelvin Low, who provided invaluable feedback on early drafts. During my fieldwork in Indonesia, I was able to work as a Research Fellow at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Jakarta thanks to the kind support of its direc- tor, Hadi Soesastro. -

Social Justice at Bay
Social justice at bay The Dutch role in Jakarta’s coastal defence and land reclamation Colophon Social justice at bay. The Dutch role in Jakarta’s coastal defence and land reclamation project. April 2017 Authors: Maarten Bakker (SOMO), Satoko Kishimoto (TNI), Christa Nooy (Both ENDS) Language editor: Vicky Anning Cover and layout: Margo Vlamings Cover photo: Save the Jakarta Bay Coalition ISBN: 978-94-6207-115-5 This publication is made possible with financial assistance from the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The content of this publication is the sole responsibility of the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Both ENDS and the Transnational Institute (TNI) and can in no way be taken to reflect the views of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. ACKNOWLEDGEMENTS: This report is the result of a research collaboration between SOMO, Both ENDS and TNI. Thanks are due to the following people for their extensive comments and reviews: Ahmad Marthin Hadiwinata (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia – KNTI), Nila Ardhianie (Amrta Institute), Niels Hazekamp & Giacomo Galli (Both ENDS), Roos van Os (SOMO), Bart Teeuwen (institutional and legal expert for water resources), Bosman Batubara & Michelle Kooy (Department of Integrated Water Systems & Governance, UNESCO-IHE Institute for Water Education) and Santy Kouwagam (Indonesian lawyer and researcher at Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society). This document is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You may copy and distribute the document, in its entirety or separate full chapters, as long as it is attributed to the authors and the publishing organisations, cites the original source for the publication on their website, and is used for noncommercial, educational, or public policy purposes. -

Analisis Kebijakan Jembatan Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Oleh
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN PESISIR Studi Kasus: Analisis Kebijakan Jembatan Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Oleh : Alim Bathoro1 Abstract The process of development are two sides of the same coin, one side is the physical development and the other side is human development. However, in the development process, usually prefer the physical development, and less attention to human development. Therefore, people as objects, not subjects of development. The political authorities see development only in terms of economic benefits, the development of socio-political side ignored. Therefore, the development has a problem. Maritime development in the coastal areas and archipelago are also experiencing the same dilemma. In order to obtain an understanding of maritime development, this study will analyze the policy of the Sunda Strait bridge. Therefore, this study will analyze, who benefited from the Sunda Strait Bridge project, and who was defeated in the Sunda Strait Bridge project. If we read Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 related to the Sunda Strait Bridge, the actors had been found, they are government officials (local and central) and national enterprises. This research found that conflicts of interest between the central and local elite, has resulted in making the Sunda Strait bridge construction was delayed several times. Clearly, national enterprises seems to be the main actor in the local policy, both in Lampung and Banten. That is in local policies, local governments easily become part of the national enterprises interests. Keywords : Policy, Actor, Elite, Government Pendahuluan hal itu berhasil, maka boleh jadi jembatan yang Pembangunan di Indonesia memasuki babak baru menghubungkan Sumatera dengan Malaysia akan ketika Perpres 86 Tahun 2011 digulirkan, perpres menyusul, sehingga menghubungkan Indonesia tersebut mengatur tentang pembangunan Jembatan bagian barat dengan Benua Asia. -

Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era
Kyoto University Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era Wu-Ling Chong* This article examines the relationships between the changes and continuities of Indonesian local politics and Chinese Indonesian business practices in the post- Suharto era, focusing on Chinese Indonesian businesses in two of the largest Indo- nesian cities, Medan and Surabaya. The fall of Suharto in May 1998 led to the opening up of a democratic and liberal space as well as the removal of many dis- criminatory measures against the Chinese minority. However, due to the absence of an effective, genuinely reformist party or political coalition, predatory political- business interests nurtured under Suharto’s New Order managed to capture the new political and economic regimes. As a result, corruption and internal mis- management continue to plague the bureaucracy in the country and devolve from the central to the local governments. This article argues that this is due partially to the role some Chinese businesspeople have played in perpetuating corrupt busi- ness practices. As targets of extortion and corruption by bureaucratic officials and youth/crime organizations, Chinese businesspeople are not merely passive and powerless victims of corrupt practices. This article argues, through a combination of Anthony Giddens’s structure-agency theory as well as Pierre Bourdieu’s notion of habitus and field, that although Chinese businesspeople are constrained by the muddy and corrupt business environment, they have also played an active role in shaping such a business environment. They have thus played an active role in shaping local politics, which is infused with corruption and institutionalized gang- sterism, as well as perpetuating their increasingly ambivalent position. -

NO ROOM for JUSTICE? When the Court Is Used to Attack Journalism in Decentralised Indonesia
Human Rights and Peace in Southeast Asia Series 4: 12 CHALLENGING THE NORMS NO ROOM FOR JUSTICE? WHEN THE court IS USED to attacK journalism IN DECENTRALISED INDONESIA R. Herlambang P. Wiratraman Freer situation in post Soeharto’sdecentralised Indonesia does not automatically affect local journalists and press who have been facing brutal attacks or violence. The court for justice is still far away from reaching and protecting journalists. Yet, the internal pressure from media owners or editors to withdraw the case leaves frustrated journalists alone to get more legal protection. Injustices situation are caused by two major problems, which are the weak judicial protection system and the pressure from political-economy power alliances who secure their vested interest by deploying hired gangsters in attacking the press. Therefore, avoiding the court is a serious matter for journalists to consider whether or not they bring justice before the judicial system. This is not always related to distrust over the judicial system, but it is more a ‘forced situation’(situasi keterpaksaan), and it might lead to the systematic of impunity governance. The paper dissects to what extent avoiding the court could be fairly considered as possible justice for journalist in the context of decentralised Indonesia. No Room for Justice? When the Court is Used to Attack Journalism 13 in Decentralised Indonesia 1. Introduction: Decentralisation as Context Journalists in Indonesia often opt to avoid the court while seeking justice as a form of limitation on their freedom of press. This is happening despite all the talksabout increasing press freedom since the end of the Suharto regime in 1998. -
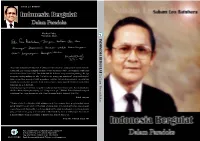
Indonesia Bergulat Dalam Paradoks Problem Etika
Sabam Leo Batubara Mochtar Lubis Wartawan Jihad INDONESIA BERGULAT “Saya ingin mengapresiasi sikap Sdr. Leo Batubara. Dia adalah tipe orang yang mengusasi masalah. Ketika Sdr. Leo menjadi pengurus Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), ia menguasai seluk beluk urusan kertas koran secara detil. Dan kalau kini dia berbicara mengenai undang-undang, dia juga Paradoks Dalam menguasai undang-undang itu. Sdr. Leo bukan tipe orang yang superficial, yang cetek-dangkal, tetapi orang yang mencoba untuk memahami masalah. Ia bersedia membaca, mencatat dan mendalami serta belajar agar tahu betul duduk perkara sesuatu masalah. Indonesia memerlukan orang macam Leo Batubara. Sekarang saya ingin berbicara mengenai kebebasan atau kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah sebuah perjuangan panjang. It’s a long way to go.” (Diskusi Pakar Nasional mengenai Kebebasan Pers, yang diprakarsai SPS, Hotel Sheraton Media, Jakarta 14|10|1998) Jakob Oetama “Membaca buku Leo Batubara tidak ubahnya seperti kita memutar kaset pergulatan hati nurani para pemimpin kita dari tahun 1945 sampai sekarang dalam menentukan pilihannya atas persoalan negara yang penuh kontradiksi. Leo berpendapat bahwa dalam menghadapi ini semua pemimpin yang pernah memegang pemerintahan telah berpaling dari pertimbangan hati nurani kemanusiaannya dalam menegakkan demokrasi dan kemerdekaan pers.” Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3521488, 3452030 / Faks. 021-3452030 DEWANPERS Email: [email protected] / Website: www.dewanpers.org Diterbitkan oleh Dewan Pers, 2009 Indonesia Bergulat Dalam Paradoks Problem Etika Buku ini saya tulis sebagai tanda kasih kepada isteri tersayang Lintong br. Tambunan, puteri dan menantu serta cucu saya Lucy Marintan, Pirton R Hutagalung, B.S., MBA., dan Patricia Hutagalung serta putera saya Choky A Batubara, S.E., dan Ir. -

Indonesia Media and Telecoms Landscape Guide November 2012
1 Indonesia Media and Telecoms Landscape Guide November 2012 2 Index Introduction…………………………………………………………….……….3 Media overview……………………………………………………………….16 Media groups………………………………………………………………….30 Radio overview………………………………………………………………..39 Radio networks………………………………………………….…………….44 Television overview……………………………………………….…………..66 Television networks…………………………………………………………...74 Print overview………………………………………………………………….98 Newspapers…………………………………………………………………..103 Magazines…………………………………………………………………….121 Online media………………………………………………………………….124 News weBsites………………………………………………………………..128 Traditional and informal channels of communication……………………..131 Media resources………………………………………………………………133 Telecoms overview…………………………………………………………...141 Telecoms companies…………………………………………………………145 3 Introduction Indonesia is the largest and most populous country in Southeast Asia. It has become an economic and political powerhouse in the region, with a growing international profile. This chain of more than 6,000 inhabited islands had an estimated population of 242 million people in 2011, according to the World Bank. More than half the population lives on the island of Java, where the capital Jakarta is situated. This large island of 140 million people is one of the most densely populated places on earth. The overthrow of President Suharto in 1998 ended six decades of authoritarian rule. It ushered in a new era of democracy, freedom of speech and economic prosperity. The local media has blossomed in this environment. Over 1,500 private radio stations and more than -

Annual Report 01 Opening 02 Business and Functional Review 03 Financial Review 04 Good Corporate Governance
2018 Annual Report 01 Opening 02 Business and Functional Review 03 Financial Review 04 Good Corporate Governance Table of Content 01 02 03 Opening Business and Financial Functional Review Review 6 Key Performance 2018 42 Loan 84 Management Discussion and Analysis 8 Vision, Mission, Core Beliefs & 46 Treasury, FI and International Core Values Banking 10 Overview of CCB Indonesia 48 Human Capital 12 Company Profile 51 Information Technology 14 Shareholders Information 52 Risk Management • Company Group Structure, Subsidiaries and Associated Entities • Capital and Risk Management – Parent Entity 19 Shares Highlights 22 Financial Highlights 24 Milestones 30 Awards 32 Strategic Direction 34 Report of Board of Commissioners 37 Report of Board of Directors 05 Corporate Information 06 Financial Statement 04 05 06 Good Corporate Corporate Financial Governance Information Statement 94 Corporate Social Responsibility 158 Organization Structure 192 Responsibility for Financial Reporting 98 Good Corporate Governance 160 Board of Commissioners’ Profile 193 Audited financial report 2018 154 Committees Report 164 Board of Directors’ Profile 170 Committees Profile 176 Executive Officers 178 Product, Services, rate information 180 Sustainability Report 184 Offices Network 01 Opening 02 Business and Functional Review 03 Financial Review 04 Good Corporate Governance 05 Corporate Information 06 Financial Statement Opening Buketan Pattern Batik Buketan pattern is using plants and flowers as decorative ornament. The word “buketan” was originated from French “bouquet”, which means flower arrangement. Along with European influence during the colonial era, especially from the Dutch, this pattern is widely developed in Java coastal area during the 19th century. 01 Opening 02 Business and Functional Review 03 Financial Review 04 Good Corporate Governance Key Performance 2018 With the support of stakeholders, CCB Indonesia managed to increase business volume and performance continuously from year to year and provided better quality services, through 95 offices by the end of 2018. -

Indonesia: Press Freedom Under Threat
Public amnesty international Indonesia Press freedom under threat October 2003 AI Index: ASA 21/044/2003 Legal cases recently brought against media professionals highlight continuing flaws in the Indonesian legal system and indicate disturbing attempts to restrict fundamental rights to freedom of expression and opinion and the public’s right to access to information. Amnesty International believes that these cases represent the most serious threat to press freedom in Indonesia for almost a decade and is urging the Indonesian government to take the steps necessary to uphold fundamental rights and avert a backsliding into a more restrictive environment1. Greater media freedom has been one of the most promising aspects of the post- Suharto era. This freedom has been enthusiastically embraced as demonstrated by the birth of hundreds of new print and broadcast media throughout the country during the past five years. At present, in Indonesia the media is able to report and encourage lively debate on a range of topics previously off limits for fear of government recrimination. The passing into law of Press Law No. 40/1999 represented a positive move away from the formerly restrictive legislation governing the Indonesian media [see Appendix for selected extracts]. As such, it has been welcomed as a positive effort to regulate the media while simultaneously protecting the fundamental rights of freedom of expression and opinion and the public’s right to information. The positive aspects of greater media freedom have been countered to some extent by irresponsible reporting, and there have been examples of partisan, sensationalist and inaccurate reporting which has rightly led to criticism and calls for greater media accountability. -

Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era
http://englishkyoto-seas.org/ Wu-Ling Chong Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era Southeast Asian Studies, Vol. 4, No. 3, December 2015, pp. 487-532. How to Cite: Chong, Wu-Ling. Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era. Southeast Asian Studies, Vol. 4, No. 3, December 2015, pp. 487-532. Link to this article: http://englishkyoto-seas.org/2015/12/vol-4-no-3-chong/ View the table of contents for this issue: http://englishkyoto-seas.org/2015/12/vol-4-no-3-of-southeast-asian-studies-2/ Subscriptions: http://englishkyoto-seas.org/mailing-list/ For permissions, please send an e-mail to: [email protected] u.ac.jp Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era Wu-Ling Chong* This article examines the relationships between the changes and continuities of Indonesian local politics and Chinese Indonesian business practices in the post- Suharto era, focusing on Chinese Indonesian businesses in two of the largest Indo- nesian cities, Medan and Surabaya. The fall of Suharto in May 1998 led to the opening up of a democratic and liberal space as well as the removal of many dis- criminatory measures against the Chinese minority. However, due to the absence of an effective, genuinely reformist party or political coalition, predatory political- business interests nurtured under Suharto’s New Order managed to capture the new political and economic regimes. As a result, corruption and internal mis- management continue to plague the bureaucracy in the country and devolve from the central to the local governments. -
Gridlock Over Suharto's Legacy in Indonesia (Part I)
Volume 6 | Issue 3 | Article ID 2679 | Mar 03, 2008 The Asia-Pacific Journal | Japan Focus "Corruption Ruins Everything": Gridlock over Suharto's Legacy in Indonesia (Part I) Peter King “Corruption Ruins Everything”: Gridlock and struggles initiated outside the over Suharto’s Legacy in Indonesia (Part I) parliamentary arena. Peter King Part II can be read here. Indonesia since the fall of Suharto in 1998 under reformasi remains subject to powerful Recent surveys suggest that there is much less tendencies for disintegrasi—both province- concern now about Indonesian disintegration in based “separatism” and general socio-political the usual sense—provincial defection-- than in decay. These tendencies are greatly aggravated the early days of reformasi under Presidents by the failure of democratically electedJusuf Habibie (1998-9) and Abdurrahman presidents and parliaments to effectively tackle Wahid/Gus Dur (1999-2001). At that time both endemic corruption or reform the armed Acehnese and Papuan civil society mobilized forces, which continue to enjoy near-total strongly for independence and East Timor immunity as a major practitioner, guarantor managed to achieve it.[2] Aceh since early and enforcer of corrupt business practice and 2005 has enjoyed a ceasefire and disarmament extortion. This article notes the activism of civil agreement between the Free Aceh Movement society and liberal media on the corruption (GAM) and Jakarta in which referendum and issue and the commendable new array of anti- independence demands have been put aside corruption institutions. But it argues that and any immediate danger of secession reform efforts have been virtually nullified by averted. But Papua has remained restive and broad collusion of Indonesia’s political,the special autonomy deal of 2001 has clearly bureaucratic, military and business elites in failed to bring reconciliation or peace, sustaining—while “democratizing” andundermined as it has been at every turn by decentralizing—the system of corruption nationalists and corruptors —and the military inherited from Suharto. -
2010 Bearable Lightness of Democracy-C
Downloaded from <arielheryanto.wordpress.com> eltaj;teJtJoe The bearable lightness of democracy Ariel Heryanto Now that Indonesia is entering the second decade of the post-New Order era, under the Susilo Bambang Yudhoyono government (2004-09), Indonesians and analysts ofIndonesia should have a better sense of what democracy might mean and entail than they had in 1998. Analysts may differ on the question of whether or not contemporary Indonesia is a democracy and on what basis this term can be defined. Rather than performing another round of conceptual debates on what constitutes a democracy in the abstract, this chapter proceeds with the a priori assumption that Indonesia is a democracy' in order to offer two paradoxical observations. First, in contrast to the generally pessimistic view among Indonesians and their observers alike, I wish to propose that Indonesia is more liberated and democratic than has been generally acknowledged.' Second, in what may seem contradictory to the first point, I wish to argue that Indonesia's Iiberalisation and democratisation does not necessarily mean that all is or will be good. This argument will be presented in a section below in response to the widespread an.d uncritical valorisation of democracy in academic and non academic analyses of contemporary Indonesia. Because I have been an academic and have grown up under the heavy weight of the New Order authoritarian government, I see Indonesia as having achieved more than is generally recognised by Indonesians and foreigners alike. Who should be credited with this achievement is a different question and one that can only be partially answered in this chapter.