BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi): an Urban Ecology Analysis
2nd International Conference on Electrical, Electronics and Civil Engineering (ICEECE'2012) Singapore April 28-29, 2012 Transport Mode Choice by Land Transport Users in Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi): An Urban Ecology Analysis Sutanto Soehodho, Fitria Rahadiani, Komarudin bus-way, monorail, and Waterway [16]. However, these Abstract—Understanding the transport behaviour can be used to solutions are still relatively less effective to reduce the well understand a transport system. Adapting a behaviour approach, congestion. This is because of the preferences that are more the ecological model, to analyse transport behaviour is important private vehicles- oriented than public transport-oriented. because the ecological factors influence individual behaviour. DKI Additionally, the development of an integrated transportation Jakarta (the main city in Indonesia) which has a complex system in Jakarta is still not adequate to cope with the transportation problem should need the urban ecology analysis. The problem. research will focus on adapting an urban ecology approach to analyse the transport behaviour of people in Jakarta and the areas nearby. The Understanding the transport behaviour can be used to well research aims to empirically evaluate individual, socio-cultural, and understand a transport system. Some research done in the environmental factors, such as age, sex, job, salary/income, developed countries has used the behaviour approach to education level, vehicle ownership, number and structure of family encourage changes in behaviour to be more sustainable such members, marriage status, accessibility, connectivity, and traffic, as the use of public transport, cycling, and walking as a mode which influence individuals’ decision making to choose transport of transportation (to be described in the literature review). -

SEAJPH Vol 3(2)
Access this article online Original research Website: www.searo.who.int/ publications/journals/seajph Clustered tuberculosis incidence Quick Response Code: in Bandar Lampung, Indonesia Dyah WSR Wardani,1 Lutfan Lazuardi,2 Yodi Mahendradhata,2,3 Hari Kusnanto2 ABSTRACT 1Department of Public Health, Background: The incidence of tuberculosis (TB) in the city of Bandar Lampung, Faculty of Medicine, University of Indonesia, increased during the period 2009–2011, although the cure rate for TB Lampung, Jl. S. Brojonegoro No. 1 cases treated under the directly observed treatment, short course (DOTS) strategy Bandar Lampung, Indonesia, in the city has been maintained at more than 85%. Cluster analysis is recognized 2Department of Public Health, as an interactive tool that can be used to identify the significance of spatially Faculty of Medicine, Gadjah Mada grouping sites of TB incidence. This study aimed to identify space–time clusters of University, Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta, Indonesia, TB during January to July 2012 in Bandar Lampung, and assess whether clustering 3 co-occurred with locations of high population density and poverty. Centre for Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Gadjah Mada Methods: Medical records were obtained of smear-positive TB patients who were University, Yogyakarta, Indonesia receiving treatment at DOTS facilities, located at 27 primary health centres and one hospital, during the period January to July 2012. Data on home addresses Address for correspondence: from all cases were geocoded into latitude and longitude coordinates, using global Dr Dyah WSR Wardani, Department of Public Health, positioning system (GPS) tools. The coordinate data were then analysed using Faculty of Medicine, SaTScan. -

Reconnaissance Study Of
(a) Large Reservoir and Small Pump Capacity In most drainage areas, a pumping station is characterized by storage of flood in a large reservoir placed at the pumping station so as to minimize pump capacity, thus initial cost and operation cost. Table 3.18 includes data of pump capacity and area of reservoir attached. However, as explained in the 1973 Master Plan Study Report, if pumps are small, the reservoir may not yet empty before the next rainstorm. (b) Complicated Network of Drainage System The pump drainage areas in the DKI Jakarta have complicated network of drains with a lot of gates. Flood water is so controlled by gates to distribute optimum discharge to downstream in consideration of flow capacity of main drain, pump capacity as well as down stream water level including Sea Level. (c) Planning without Consideration of Secondary and Tertiary Drains The other characteristics of drainage system in the DKI Jakarta is that existing pump capacity and starting water level of a reservoir of a pump drainage area are so determined that highest water level or the Design Flood Level along the main drain is lower than the existing bank elevation for one day flood with 25-year return period, assuming that most of rainfall can be drained to the main drain. However, there are a lot of flood prone areas in pump drainage areas. One cause of inundation in flood prone areas may be improper installation/maintenance of secondary/tertiary drains, though gravity drain can be attained. Also high Design Flood Level of main drain may be other causes why rainwater is difficult to be drained. -

Violent Extremism in Indonesia: Radicalism, Intolerance
VIOLENT EXTREMISM IN INDONESIA: RADICALISM, INTOLERANCE WINTER 2017 AND ELECTIONS A PROJECT FROM THE INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE Violent Extremism in Indonesia: Radicalism, Intolerance and Elections Copyright © 2018 International Republican Institute. All rights reserved. Permission Statement: No part of this work may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without the written permission of the International Republican Institute. Requests for permission should include the following information: • The title of the document for which permission to copy material is desired. • A description of the material for which permission to copy is desired. • The purpose for which the copied material will be used and the manner in which it will be used. • Your name, title, company or organization name, telephone number, fax number, e-mail address and mailing address. Please send all requests for permission to: Attn: Department of External Affairs International Republican Institute 1225 Eye Street NW, Suite 800 Washington, DC 20005 [email protected] VIOLENT EXTREMISM IN INDONESIA: RADICALISM, INTOLERANCE AND ELECTIONS WINTER 2017 International Republican Institute IRI.org @IRI_Polls © 2018 All Rights Reserved 2 IRI | WINTER 2017 EXECUTIVE SUMMARY Approach hardship and its defense of free expression. • In late 2017, the International Republican However, members of the nationalist parties, Institute (IRI) conducted a series of focus group which control government, were less critical of discussions (FGDs) to gain insight into the the government and its overall representation of local political dynamics in West Java that are constituents and ability to address the country’s contributing to radicalism and intolerance, with primary challenges. -

Studi Kasus : Kereta Api (Ka) Sukabumi-Bogor
KAJIAN PERJALANAN KOMUTER MODA KERETA API (STUDI KASUS : KERETA API (KA) SUKABUMI-BOGOR) Arman Maulana 1), Andi Rahmah 2), Budi Arief 3) ABSTRAK Kereta Api (KA) Pangrango Suikabumi-Bogor ataupun Bogor-Sukabumi diresmikan pada 9 November 2013, KA ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pergerakan pada kedua wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini, mendapat gambaran pola dan karakteristik perjalanan penumpang komuter KA, menganalisis besaran tingkat pertumbuhan perjalanan penumpang komuter KA, dan upaya penanganan/konsep perbaikan Kereta Api (KA) Sukabumi-Bogor ataupun Bogor-Sukabumi. Digunakan dasar utama UU RI No.23 Tahun 2007, dan Permenhub RI No.110 Tahun 2017 dalam pengamatan survei secara langsung. Metode penelitian menggunakan data primer dari hasil kuesioner kepada pengguna jasa kereta api (KA) tentang pelayanan dan kepentingan, dan analisis data sekunder dari PT.KAI menjadi data yang informatif pada kajian perjalanan komuter moda kereta api (KA), serta mengunakan metode furness pada pemodelan transportasi, penyajian data statistik, dan ramalan permintaan (demand forecast). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kereta Api (KA) Pangrango memenuhi 80,72 % pada lintas Sukabumi-Bogor, dan 79,86 % pada lintas Bogor-Sukabumi berdasarkan kuesioner jenis atribut pelayanan terhadap pengguna jasa kereta api (KA) Pangrango, hal ini sudah memenuhi standar pelayan minimal dan menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat. Tetapi kinerja PT.KAI Kereta Api (KA) Pangrango masih belum optimal dikarenakan sarana, prasarana, dan frekuensi perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango masih terbatas. Oleh karena itu diharapkan pada masa yang akan datang adanya penambahan armada kereta api, frekuensi perjalanan, dan jalur track sehingga dapat terciptanya angkutan massal yang layak dan handal. Kata Kunci : Metode Furness, Perjalanan Komuter, Ramalan Permintaan. -

Analisis Kinerja Operasional Kereta Api Pangrango Bogor – Sukabumi
Analisis Kinerja Operasional Kereta Api Pangrango - Sukabumi CESD Vol 02, No 2 Desember 2019 E-ISSN : 2621-4164 Vol. 02 No 2 Desember 2019 Analisis Kinerja Operasional Kereta Api Pangrango Bogor – Sukabumi *Dika Saputra1, Prima Jiwa Osly1, Wita Meutia1 1Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila Abstract Kota Bogor dan Kota Sukabumi dua wilayah penting di Jawa Barat yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Sehingga terdapat kebutuhan pergerakan yang besar pada kedua wilayah tersebut. Keterbuhungan antar kedua wilayah tersebut, difasilitasi oleh kereta api Pangrango Bogor – Sukabumi. Kereta api Pangrago yang diresmikan pada November 9, 2013 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pergerakan pada kedua wilayah tersebut. Kereta api Pangrango digunakan untuk perjalanan kerja, berdagang maupun berlibur.. Maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi waktu henti dan waktu tempuh serta menganalisa kenyamanan kereta api Pangrango Bogor – Sukabumi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kinerja dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisa jumlah responden dan analisis metode Importance Performance Analysis (IPA). Hasil dari kinerja rata – rata waktu tempuh dari stasiun Bogor Paledang – Sukabumi selama suvei sebesar 121 menit dan hasilnya sama sesuai GAPEKA 2017 yaitu 121 menit. Rata – rata waktu tempuh dari stasiun Sukabumi – Bogor Paledang selama survei sebesar 122.66 dan hasilnya hampir mendekati GAPEKA 2017 yaitu 123 menit. Rata – rata waktu henti dari stasiun Bogor Paledang – Sukabumi selama survei sebesar 23 menit dan hasilnya sesuai GAPEKA 2017 yaitu 23 menit. Rata – rata waktu henti dari stasiun Sukabumi – Bogor Paledang selama survei sebesar 23 menit dan hasilnya sesuai GAPEKA 2017 yaitu 23 menit. Hasil dari metode Importance Performance Analysis (IPA) diperoleh rata – rata nilai tingkat kepuasan dan kepentingan dari keseluruhan atribut pelayanan kereta api Pangrango Bogor Paledang – Sukabumi sebesar 6603 dan 8275. -

The Case of Central Kalimantan Province, Indonesia
Quarterly Journal of International Agriculture 54 (2015), No. 1: 77-100 Governance, Decentralisation and Deforestation: The Case of Central Kalimantan Province, Indonesia Aritta Suwarno and Lars Hein Wageningen University, The Netherlands Elham Sumarga Wageningen University, The Netherlands, and School of Life Sciences and Technology, ITB Bandung, Indonesia Abstract The implementation of the decentralisation policies in Indonesia, which started in 2000, has fundamentally changed the country’s forest governance framework. This study investigates how decentralisation has influenced forest governance, and links the forest governance to deforestation rates at the district level. We measure and compare the quality of forest governance in 11 districts in Central Kalimantan province in the periods 2000-2005 and 2005-2010 and relate forest governance to deforestation rate. This study shows that decentralisation has led to marked differences in forest govern- ance between districts and that deforestation rates is strongly related to the change of forest governance. We recommend revisiting the Indonesian forest governance framework to ensure more checks and balances in decision making, better monitoring and increased transparency, with particular support for Forest Management Units as a new tool for forest management, and government support to facilitate the design and implementation of REDD+ projects. Keywords: Indonesia, decentralisation, deforestation, forest governance JEL: H110 1 Introduction Indonesian forests account for around 2.3% of global forest cover (FAO, 2010) and represent 44% of the Southeast Asian forested area (KOH et al., 2013). According to the Indonesian Ministry of Forestry (MOF, 2011), the total designated forest area in Indonesia was about 131 million ha. In 2009/2010, approximately 98 million ha of the designated forest area was still forested (MOF, 2011). -

Urbanization, Distancing and Food Waste in Bogor, Indonesia
URBAN AND REGIONAL FOOD SYSTEMS Wasted Infrastructures: Urbanization, Distancing and Food Waste in Bogor, Indonesia TAMARRA SOMA Applying the conceptual frameworks of ‘food distancing’ (Clapp, 2012) and ‘waste distancing’ (Clapp, 2002), this paper investigates the issues of food consumption and food waste inin urbanurban Indonesia.Indonesia. TheThe paperpaper arguesargues thatthat thethe ‘distancing” ‘distancing’ of food production via long-distance modern supply chains is connected to the growing issue of food waste in rapidly urbanizing areas. Another impact of distancing in Bogor, Indonesia is the environmental impact of modern food packaging in comparison to traditional food packaging. The paper concludes by emphasizing that rapid urbanization enables distancing and produces an unjust system whereby the impact of food waste and its associated packaging is distanced from those who are privileged and brought nearer to those who are marginalized. On the 21 February 2005, 143 people from fession to understand how urban develop- two villages predominantly inhabited by ment priorities can lead to increased inequali- waste pickers and their families were killed ties. The lives of the informal waste pickers after being buried by a garbage avalanche (many of whom were youths) killed across at the Leuwigajah open dump in Indonesia Indonesia (Humaeni and Widjaya, 2010), (Lavigne et al., 2014). The fatal garbage tsunami the environmental degradation caused by was the result of an explosion caused by an immense amount of non-biodegradable trapped methane gas (resulting from de- food packaging waste, and the stench of composing organic/food waste). Methane is a rotting organic waste represents the ‘col- greenhouse gas estimated to have a warming lateral damage’ of modern industrial food pro- potential twenty- ve times more than carbon duction and consumption. -

Case Study : Old Mosques in the City of Palembang, South Sumatra)
BANDUNG CREATIVE MOVEMENT 2015 2nd International Conference on Creative Industries “Strive to Improve Creativity“ 8 – 9 September 2015 TYPOLOGY OF TRADITIONAL MOSQUE IN PALEMBANG (Case Study : Old Mosques In The City of Palembang, South Sumatra) Rangga Firmansyah S.Sn., M.Sc.1*, Irwan Sudarisman ST., MT.2 1 School of Creative Industries, Telkom University, [email protected], 2 School of Creative Industries, Telkom University,[email protected] Abstract: Currently the design and architecture of Islamic thought was born of a duplication and imitation of the typology of the building which is considered as a product of the Muslim community. This approach is often limited by the use of symbols or physical form that is considered to represent Islam and usually come from the Middle East. This can be seen from the development of the mosque construction and rehabilitation of traditional mosques tend to forget the local aspect as well as the values and the basic principles of Islam. Traditional Mosque of Palembang is one of the local identity of people in Palembang as well as a dedicated and have a special law as buildings of worship of Muslims (madaniyah typical). The purpose of this research is to be able to see the typology of the traditional mosque in Palembang viewed from different aspects findings in the field, as well as determine the factors that influence in its formation. This research used a case study and the basic theory of the interior in the aspects of forming the typology of Palembang traditional mosque. The results showed the typology of the traditional mosque in the city of Palembang were influenced by values and basic principles of Islam and cultural values locally based. -

2018 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Indonesia
Indonesia MODERATE ADVANCEMENT In 2018, Indonesia made a moderate advancement in efforts to eliminate the worst forms of child labor. The government substantially increased its labor inspectorate funding from $2.1 million in 2017 to $10.2 million with specific funds allocated to enforcing child labor regulations. It also conducted 19,792 labor inspections and continued working with the International Organization for Migration to establish a comprehensive integrated Trafficking in Persons database. However, children in Indonesia engage in the worst forms of child labor, including in commercial sexual exploitation, sometimes as the result of human trafficking. Children also perform dangerous tasks in plantation agriculture, including in palm oil and tobacco production. The Ministry of Manpower continued to lack the financial resources and personnel necessary to adequately enforce child labor laws throughout the country. In addition, the Domestic Workers Protection Bill, which has been under consideration since 2010, continued to languish in parliament. I. PREVALENCE AND SECTORAL DISTRIBUTION OF CHILD LABOR Children in Indonesia engage in the worst forms of child labor, including in commercial sexual exploitation, sometimes as the result of human trafficking. Children also perform dangerous tasks in plantation agriculture, including in palm oil and tobacco production. (1-10) Table 1 provides key indicators on children’s work and education in Indonesia. Although the government collects national data on working children ages 5 through 14, it does not publish the data. Table 1. Statistics on Children’s Work and Figure 1. Working Children by Sector, Education Ages 10-14 Children Age Percent Working (% and population) 10 to 14 3.7 (816,363) Attending School (%) 10 to 14 92.4 Combining Work and School (%) 10 to 14 2.1 Services 26.5% Primary Completion Rate (%) 99.2 Source for primary completion rate: Data from 2017, published by UNESCO Agriculture Institute for Statistics, 2019. -
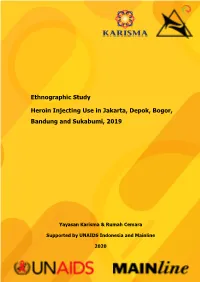
Ethnographic Study Heroin Injecting Use in Jakarta, Depok, Bogor
Ethnographic Study Heroin Injecting Use in Jakarta, Depok, Bogor, Bandung and Sukabumi, 2019 Yayasan Karisma & Rumah Cemara Supported by UNAIDS Indonesia and Mainline 2020 Ethnography Study Heroin Injecting Use in Jakarta, Depok, Bogor, Bandung and Sukabumi, 2019 Research Team: Arif Rachman Iryawan (Principal Investigator) Wahyu Khresna (Researcher 1) Sahrul Syah (Researcher 2) Faisyal Sjahrial (Researcher 3) Ignatius Praptoraharjo (Researcher 4) Rizza Auli Shava (Data Analyst) Puji Lestari (Research Assistant Jakarta) Nawawi Hermawan (Research Assistant Depok) Lucky Pramitasari (Research Assistant Bogor) Mahbub Alpariji (Research Assistant Sukabumi) Vika Nurdian (Research Assistant Bandung) Aris Mawardi (Research Assistant Purwakarta) Translator: Aditia Taslim This research was conducted by the Yayasan Karisma and Rumah Cemara through the support of partnership between UNAIDS Indonesia and the Mainline Netherland in 2019 Executive Summary An Ethnographic Study on Opioid Injecting Use in Bandung, Bogor, Jakarta and Sukabumi, 2019 Heroin, as a common drug injected by people who use drugs, was not available in the market in the last few years in Indonesia. Based on reports and observations from the field, it was noted that heroin made a came back in mid-2019. Therefore, this study was made to identify the different context on injecting drug use based on the current heroin market availability among the community of people who inject drugs. Specifically, this study aims to illustrate the current situation on drug use, identify any changing trends, map the social and risk network, identify key barriers and enablers, capture the perspective of service providers, and provide recommendations to inform policy reform. The study used an ethnography method to develop in-depth/thick description. -

Conservation of Underground Water with the Ecosystem Approach to the Development of the New Towns in Bogor, Tangerang, Bekasi (Botabek) Region
Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 227 ( 2016 ) 720 – 727 CITIES 2015 International Conference, Intelligent Planning Towards Smart Cities, CITIES 2015, 3-4 November 2015, Surabaya, Indonesia Conservation of underground water with the ecosystem approach to the development of the New towns in Bogor, Tangerang, Bekasi (Botabek) Region Parino Rahardjoa*, Djoko. M. Hartonob, Emirhadi Sugandac, Hadi Susilo Arifind aDoctoral Student of Environmental Science Study Program, University of Indonesia/Faculty of Urban & Regional Planning Department, Faculty of Engineering, University of Tarumanagara, Jakarta, Indonesia. b Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Indonesia cArchitecture Department, Faculty of Engineering University of Indonesia dLandscape Architecture Department, Faculty of Agriculture. Bogor Agricultural University Abstract The limited supply of clean water led to some residents in the city, as well as business and trade areas using underground water. Optimization of land used in the development of new towns and expanded impervious land surface, thus reducing infiltration capacity, resulting in an increased volume of runoff. The use of underground water and the reduced infiltration of rainwater resulted in a decrease in the underground water table. To maintain the underground water table and preventing land subsidence resulted from the use of underground water as raw material for clean water. The effort required is how doing underground water conservation. This paper discusses the development of new towns to assess the natural landscape as underground water conservation efforts on the development of the new town. The research method uses a quantitative approach to calculate the potential runoff using a soil conservation service, while to analyze the trend of changes in land cover using temporal spatial analysis, using descriptive analysis.