18 Bab Ii Struktur Dan Makna Pada Mantra Perepi Dalam
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Struktur, Makna, Dan Fungsi Mantra Berattep Masyarakat Melayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
STRUKTUR, MAKNA, DAN FUNGSI MANTRA BERATTEP MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS ARTIKEL PENELITIAN OLEH RIZKA MUNA NIM F11411036 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK 2018 1 STRUKTUR, MAKNA, DAN FUNGSI MANTRA BERATTEP MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS Rizka Muna, Antonius Totok Priyadi, Agus Wartiningsih Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan Pontianak E-mail: [email protected] Abstract: This study was conducted based on the interest on Mantra Berattep of Malay People in Teluk Keramat District which is still used from generation to generation during traditional ceremonies prior to rice cultivation. The research problems are the structure (rhyme and rhythm), the function, and the meaning of Mantra Berattep. The research aims to describe those problems. Based on the data analysis on Mantra Berattep of Malay People in Teluk Keramat District Sambas Regency, there are rhyme according to their sounds in words such as full rhyme, absolute rhyme, half rhyme, alliteration rhyme, assonant rhyme, and pararhyme (MBB2). Rhymes according to their location in the lines such as initial rhyme (MBB1 and MB), middle rhyme, and tail rhyme. Rhymes according to the location of the rhyme in the line such as internal rhyme and cross rhyme. Rhymes according to their matches in a verse such as broken rhyme and free rhyme. Overall the reading of Mantra Berattep by Malay People in Teluk Keramat has flat intonation. The function of Mantra Berattep includes recreative function, didactic function, aesthetic function, moral function, and religious function. -

Wellness Schedules Ages 14 and Above*
GROUP EXERCISE SCHEDULE SEPT 2019 Wellness Schedules Ages 14 and Above* AOA KEY Aqua Exercise WS Wellness Studio Cardio & Strength RR Reflection Room Cycle CR Cycle Room Dance Fitness Ages 8-13 Can Attend w/Adult Yoga * Ticket Required $ Fees Associated Barre, Pilates & Tai Chi Class Change/New Class Net Sports Updated 7/19/2019 ACTIVE OLDER ADULTS MON TUES WED THURS FRI SAT SUN AOA Step AOA Circuit AOA Step & 7:00-8:00AM 8:00-9:00 AM Strength Sue Sue 7:00-8:00 AM WS Gym 2 Bill WS AOA Chair AOA Yoga AOA Chair AOA Yoga AOA Chair Strength 8:15-9:15 AM Strength 8:15 –9:15 AM Strength 8:00 – 9:00 AM Tara 8:00 – 9:00 AM Jessica 8:00 – 9:00 AM Maria RR Sue RR Sue Gym 1 Gym 1 Gym 1 Zumba ® Gold Zumba ® Gold 9:30-10:30 AM 9:30-10:30 AM Kristin Holly Gym 2 Gym 2 AOA Strength AOA Strength Moving for Tai Chi 11:00-12:00 PM 11:00-11:45 AM Better Living 11:45-12:45 PM Sue/Stephanie Jo 11:00-12:00 AM Stefanie Gym1/WS WS Deborah WS Gym 2 AOA Yoga Stretching AOA Yoga* Meditation Tai Chi - 12:15 - 1:30 PM 12:30 - 1:30 PM 11:00 - 12:00 PM 11:30 - 12:45 PM First Section Laurel Laurel Yella Carrie P 1:00-2:00 PM RR RR RR RR Stefanie WS Zumba® Gold Tai Chi - Tai Chi Tai Chi - 12:30-1:15 PM All Sections 2:15 - 3:25 PM Third Section Joan 2:15 - 3:15 PM Richard 2:00 - 3:00 PM WS Stefanie WS Stefanie WS Prior Experience WS All Levels Recommended Prior experience is recommended. -

LSGC Adlahat University Registration No MA-I Serial Registration No
LSGC Adlahat University Registration No MA-I Serial Registration No. Name Father Mother Class / Subject 1 403202000421 KM ARTI LAKSHMI KUMAR SUDAMA DEVI M.A. Economics I-Semester 2 403202000392 KM ARTI MAURYA GULAB SINGH CHINTA DEVI M.A. Economics I-Semester 3 403202000442 KM CHANDRAKALA VISHVAKARMA KANHAIYA LAL VISHVAKARMA SHYAMKUMARI DEVI M.A. Economics I-Semester 4 403202000415 KM NEETU KUMARI KRISHNA BIHARI BINDU DEVI M.A. Economics I-Semester 5 403202000433 KM PUJA PATEL PARAMESHWAR SINGH SITABI DEVI M.A. Economics I-Semester 6 403202000443 KM SAPANA MAURYA PARAS NATH SINGH LAKSHMEENA DEVI M.A. Economics I-Semester 7 403202000376 ARCHANA SINGH MUNNA PRASAD SINGH ASHA DEVI M.A. English I-Semester 8 403202000434 KARISHMA MAURYA CHANDRA PRAKASH MAURYA VINDO DEVI M.A. English I-Semester 9 403202000512 KM ANITA PATEL KESH NATH SINGH RAJ KUMARI DEVI M.A. English I-Semester 10 403202000384 KM KANCHAN PREMANATH SEETA DEVI M.A. English I-Semester 11 403202000529 KM MAHIMA SINGH SURESH SINGH RAM DULARI M.A. English I-Semester 12 403202000550 KM NANDINI GUPTA MUNNA GUPTA SHAKUNTALA DEVI M.A. English I-Semester 13 403202000509 KM NIKITA RAY DASHARATH RAY URMILA RAY M.A. English I-Semester 14 403202000399 KM PRIYA VISHWAKARMA TILAKDHARI SUSHAMA DEVI M.A. English I-Semester 15 403202000450 KM RUPA KUMARI BASANT LALA YADAV KISMAT DEVI M.A. English I-Semester 16 403202000418 KM SARITA YADAV SANT RAM YADAV SHANTI DEVI M.A. English I-Semester 17 403202000453 KM SUDHA MAURYA SATYA NARAYAN SUSHILA DEVI M.A. English I-Semester 18 403202000422 KM SUMAN MAURYA UDAY NATH MAURYA GAYATRI DEVI M.A. -

Summer 1 - What Do You Need to Know About Hinduism? Printing
Enlarge to A3 when Summer 1 - What do you need to know about Hinduism? printing Some important Hindu beliefs about God Some important facts about Hindu worship. Hindus believe there is one God, whom they call Brahman. They like to think Hindus worship at home (puja) and in the mandir (temple). But Hindus believe that everything they about him in different ways to help them understand him. Each way they think do is an act of worship. about Brahman takes the form of a deity and reminds them of something in particularThese aboutthree what deities God is like. are known as the Worship at home (puja) In a Hindu home there will be a shrine for their favourite deities and they will worship every day. Hindus will make sure they wash before they start their worship. The shrine will contain a picture or statue of the deities and will be decorated nicely. A bell is rung before they start to worship, so that the deity will notice that they are there; be woken up. Brahma – the creator Hindus like to use all 5 of their senses when they worship. Vishnu – the preserver of life Hindus will light candles and burn incense when they worship. They will bring an offering such as food or flowers. Shiva – the destroyer of ignorance and evil. They will touch the picture or statue with special coloured powder and with ghee, which is melted butter. These three deities are known as the Trimurti Hindus believe that God has visited the world many times in the form of different deities (gods) to help us to know how to be good and to resist evil. -

Yajur Veda Avani Avittam Or Upakarma and Gayathri Japam
Om Sree Vigneswaraya Namaha Yajur Veda Avani Avittam/Upakarma (Japa Vidhi) TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION ...................................................................................................................... 4 2 THINGS REQUIRED FOR AVANI AVITTAM/UPAKARMA ................................................... 7 3 AVANI AVITTAM/UPAKARMA STEPS ................................................................................ 10 1.1. Kshowaram/Vapanam .......................................................................................... 10 1.2. Snanam (Nithya Karma) ...................................................................................... 10 1.3. Sandhya Vandanam (Nithya Karma - Prathas Sandhyam) .......................... 11 1.4. Samidaa Dhaaanam (Nithya Karma – Brahmachari‟s only) ........................ 37 1.5. Owpasanam and Vaisvathevam (Nithya Karma – Gruhasta‟s Only) .......... 48 1.6. Yajnopaveeta Dhaaranam ................................................................................... 49 1.7. Kamoka Rishith Japam (Not for Brahmachari‟s doing first Avani Avittam/Upakarma) .............................................................................................. 59 1.8. Kshowaram/Vapanam and Snanam (Brahmachari‟s Only) .......................... 68 1.9. Sandhya Vandanam (Nithya Karma - Madhyanikam) ................................... 69 1.10. Brahma Yajnam (Nithya Karma) ........................................................................ 95 1.11. Maha Sankalpam ................................................................................................ -

The Hindu'saugust 15, 1947 Issue
COLLECTOR'S EDITION The Hindu’s August 15, 1947 issue From its birth as a weekly in September 1878, The Hindu became a powerful instrument of the Indian national movement that sought to overthrow British rule. It was hence tting that when freedom dawned, The Hindu welcomed it with characteristic aplomb, deep thought, and skillful penmanship. The Hindu's edition on August 15, 1947, along with a 32-page supplement, was a tribute to the freedom struggle, with articles by some of the greatest names of that age including V.K. Krishna Menon, India’s rst woman legislator Muthulakshmi Reddi, and the great educationist K.M. Munshi. It also carried striking images of the arrival of Independence, and riveting news from that tempestuous time. The Hindu's leading article on the historic day was characteristically pithy and powerful. Titled "Red letter day'', it said: "By the grace of Providence India enters the comity of free nations today, an equal among equals. It is an occasion for rejoicing not only for her people but for all who value human freedom as an end in itself. So long as this country with her hoary civilisation and many-sided culture, her wealth of resources and matchless opulence of spirit remained in political bondage, that very fact constituted an implicit denial of those values to which the dominant nations of the West were wont to pay lip service." Now, we are proud to share with our loyal subscribers, those very pages, articles, and images from which our readers got to know about the advent of freedom on August 15, 1947. -

Shri Amritwaani Paath & Satsang with Swami Nalinanand Giri Ji
THE HINDU TEMPLE OF METROPOLITAN WASHINGTON 10001 RIGGS ROAD, ADELPHI, MD 20783 PHONE #s 301-445-2165, 301-434-1000; http://www.hindutemplemd.org; E-mail: [email protected] December 2014 Scheduled Events Month Date Day Time Event Description December 1 MONDAY Shiv Pooja December 2 TUESDAY AMAVASYA GEETA JAYANTI December 2 TUESDAY 7:30 PM to 8:30 PM Hanuman Chalisa Paath & with Pandit Pitamber Dutt Sharm ji -reading, bhajans, kirtan, katha Sunderkaand Paath December 3 WEDNESDAY Laxmi Narayana Pooja December 4 THURSDAY PRADOSHA December 4 THURSDAY 7:00 PM to 9:00 PM Sai Baba Group Bhajans, Reading & Arti; Followed by Prasad December 5 FRIDAY 8:00 PM Santoshi Mata Arti Service December 6 SATURDAY PURNIMA DATTATREYA JAYANT December 6 SATURDAY Serva Deva Pooja December 6 SATURDAY 9:00 AM to 10:00 AM Jain Pooja "New Program" Every Saturday Morning - 10 am to 11:30 am December 6, 13, 20, & 27, 2014 Shri Amritwaani Paath & Satsang With Swami Nalinanand Giri Ji December 7 SUNDAY 8:00 AM to 10:00 AM Yoga Classes December 7 SUNDAY 9:00 AM to 10:00 AM Jain Pooja December 7 SUNDAY 5:00 PM to7:00 PM Hari & Ram Katha Katha, bhajans, Kirtan Evening; Prasad & Priti Bhoj December 8 MONDAY Shiv Pooja December 9 TUESDAY 7:30 PM to 8:30 PM Hanuman Chalisa & Sunderkaand with Pandit Pitamber Dutt Sharm ji -reading, bhajans, kirtan, katha Paath December 10 WEDNESDAY Laxmi Narayana Pooja December 11 THURSDAY 7:00 PM to 9:00 PM Sai Baba Group December 12 FRIDAY 8:00 PM Santoshi Mata Arti Service Bhajans, Reading & Arti; Followed by Prasad December 13 SATURDAY -
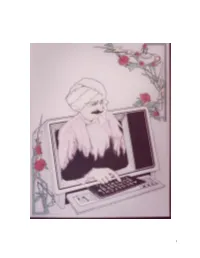
Clicking Here
1 The Alphabet Board A Collection of Sayings of AVATAR MEHER BABA Compiled by Chris Maier This collection © 2014 by Chris Maier. See pp. 2-4 for further copyright information. 2 Preface Words can clarify or confuse; they’ve always had this dual identity, but in this “Information Age” words have proliferated to such an extent that mankind seems in danger of drowning in a sea of verbiage. Inasmuch as we depend on words, we need those which give meaning to our lives; we need, ideally, words defined by God! And—thank God!—we have them. For although He kept silent for forty-four years, Avatar Meher Baba spoke to us through His alphabet Board, His flying fingers giving the true meaning of everything from Art to Zero—all the while pointing us away from words, towards His silence and the unnamable mystery of His Love. Note: When “you” is referred to in a quote from Meher Baba, it is sometimes a general and at other times a specific “you,” but if the gist of the message seemed generally applicable, it is quoted without indicating who was being addressed. Omissions are noted by ellipsis points (…), paragraph breaks are omitted, editor’s interpolations are enclosed in brackets, and spellings and capitalization are rendered as in the source text: thus, for instance, Baba is sometimes “me” and sometimes “Me,” God is “he” or “He,” and so on. SOURCES The words of Meher Baba are copyright by the Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust (AMBPPCT), Kings Road, Ahmednagar, M.S. 414001, India. -

Shri Vishwakarma Skill University Dudhola, Palwal
SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY (Enacted by the Act 25 of 2016, State of Haryana) DUDHOLA, PALWAL Minutes of the 13th Executive Council Meeting (Emergent) held on 20.01.2020 at 03:00 PM Venue: CONFERENCE ROOM SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY TRANSIT OFFICE, GURUGRAM, SECTOR-44 SVSU SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY (Enacted Under Government of Haryana, Act No. 25 of 2016) Temporary Office: Plot No. 147 Sector- 44 Gurugram (Haryana) Phone: 0124-6525001 E-Mail: [email protected] Visit us at: www.hvsu.ac.in Ref. No. SVSU/EC/2020/Acad. Br/89 Date: 20/01/2020 To All the members of Executive Council Shri Vishwakarma Skill University Dudhola, Palwal Subject: Minutes of the 13th meeting of the Executive Council (Emergent) held on 20th January, 2020. Sir, Kindly find enclosed herewith minutes of the 13th meeting of the Executive Council (Emergent) held on 20th January, 2020 at 03:00 PM in the Conference Room, SVSU transit office Gurugram. The discrepancies if any, in recording of minutes may be intimated to this office within 07 days from the date of receipt of the minutes. Your faithfully (Registrar) D.A: as above Endst. No. SVSU/EC/2020/Acad. Br /90-93 Dated: 20/01/2020 A Copy is forwarded to the following for information and necessary action: 1. The Secretary to Governor, Haryana Raj Bhawan, Chandigarh for kind information of his Excellency, the Governor & Chancellor, SVSU Dudhola, Palwal 2. The Director Skill Development and Industrial Training Department Haryana 3. PS to Vice-Chancellor for kind information of the Vice-Chancellor, Shri Vishwakarma Skill University. -

HINDUISM Part 1 Unit 2: Living As a Hindu
HINDUISM Part 1 Unit 2: Living as a Hindu What this unit contains What does it mean to be a Hindu? Respect for other people (shown through namaste) and respect for all living things because God is in everything. Understanding more about God and Hindu values through the stories of the birth of Krishna, Krishna and Sudhama and Murugan and Ganesh. Values: The importance of caring for others and respect for parents. Belief that God is seen in different ways and represented through different forms. Worship in the home: The shrine; The Arti ceremony; Prasad (food offered, blessed and served after prayer). Where the unit fits and how it builds This is the second Unit of Hinduism in the Primary phase. It develops pupils' knowledge and upon previous learning understanding of Hindu beliefs about God from unit 1 by introducing them to a second avatar of Vishnu. Extension activities and further thinking Think of a time when you won a competition and how you behaved towards the losers. Vocabulary SMSC/Citizenship Hinduism Shiva worship prasad Worship of God Hindu Murugan shrine prayer Sportsmanship God Ganesh adoption respect Respect for all people. belonging Krishna foster honesty Respect for all living things. namaste Sudhama Arti truthfulness Concept of God being in all creation. Agreed Syllabus for Religious Education Teaching unit HINDUISM Part 1 Unit 2:1 HINDUISM Part 1 Unit 2: Living as a Hindu Unit 2 Session 1 A A Learning objectives T T Suggested teaching activities Sensitivities, points to 1 2 note, resources Pupils should: √ Explore & demonstrate greetings known by the class, celebrating the languages Resources and cultures represented. -

Moorty Sthapana Ceremonies
THE HINDU TEMPLE OF METROPOLITAN WASHINGTON 10001 RIGGS ROAD, ADELPHI, MD 20783 PHONE 301‐445‐2165, 301‐434‐1000 http://www.hindutemplemd.org June 2011 SCHEDULED EVENTS MONTH DATE DAY TIME SERVICE PROGRAM June 1 WEDNESDAY AMAVASYA Laxmi Narayana Pooja June 2 THURSDAY 8:00 PM to 9:00 PM Sai Baba Group Bhajans, Reading, Arti & Prasad June 3 FRIDAY 8:00 PM Santoshi Mata Arti Service 3 DAYS OF CELEBRATIONS - Each Event Followed by Prasad & Priti Bhoj From Friday JUNE 3 to Sunday June 5, 2011 For SHIV PARIVAR MOORTY PRATHISHTA & RUDRA MAHA YAGNA MAHOTSAVA Friday June 3 & Saturday 4, 2011 Morning & Evening Programs: From 10:00 AM TO 1:00 PM: POOJA & HAVAN CEREMONIES From 7:00 PM TO 9:00 PM: BHAJAN/ KIRTAN/KATHA MOORTY STHAPANA CEREMONIES SUNDAY JUNE 5, 2011: 10:00 AM to 2:00 PM & From 5:00 PM TO 7:00 PM: BHAJAN/ KIRTAN/KATHA Please contact Pandit Pitamber Dutt Sharma and Ram Kumar Shastri to Participate in these auspicious ceremonies: (301)-445-2165 or (301)-434-1000 ; See Attached Flyer for Details June 4 SATURDAY Ajaa Ekadashi Serva Deva Pooja June 4 SATURDAY 9:00 am to 10:30 am Jain Pooja SPECIAL PROGRAM 2 Days of Special Sai Baba Devotees Program By: Saturday JUNE 4, 2011 Babuji (Shri Vijay Kumar Varma) of Sri Saikalp Adhyam KAAMKAAJ & Sanstha, "Sai Niketan", 9:00 AM to 1:00 PM Babuji (Shri Vijay Kumar Varma) of Sri Saikalp Adhyam Sunday, JUNE 5, 2011 9:00 AM to 6:00 PM Sanstha, "Sai Niketan", New Delhi, performed the Pran SEMINAR Pratishtha of Shirdi Saibaba murti sthapna at the Hindu Temple of Metropolitan Washington in 2007. -

Semiotika Mantra Petapa Alas Purwo: Kajian Semiotika
SEMIOTIKA Volume 20 Nomor 2, Juli 2019 Halaman 108—119 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/SEMIOTIKA/index E-ISSN: 2599-3429 P-ISSN: 1411-5948 MANTRA PETAPA ALAS PURWO: KAJIAN SEMIOTIKA RIFFATERRE THE ASCETIC SPELL IN ALAS PURWO: RIFFATERRE SEMIOTIC ANALYSIS M. Fawaid Al Fikry1, Sunarti Mustamar2*, Christanto Pudjirahardjo3 1Alumni Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember 2,3Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember *Corresponding Author: [email protected] Informasi Artikel: Dikirim: 1/02/2019; Direvisi: 10/03/2019; Diterima: 5/04/2019 Abstract Mantra (spell) is the oldest poem in oral literature used as a kind of prayer and hope to God through His creation. This research goals to describe the structure and meaning of the text found in Alas Purwo spells entitled "Restoring magic" using Riffaterre's semiotic theory. Qualitative methods and descriptive analysis are used as research method. The analysis is focused on structural analysis of themes and diction, followed by Riffaterre's semiotic analysis to discuss four things, namely the unsustainability of expression, heueristic and hermeneutic readings, matrices or keywords, and hypograms or intertexts. The results showed that the theme of the mantra is the wish from spell practitioner delivered to the Lord of the universe, while the diction is denotative and connotative. The unsustainable expression in the form of replacement of meaning is found in the use of the synecdoche; deviation of the meaning of the spell, found in the nonsense language style; while the creation of the meaning of spell is dominated by homologues. Heuristic reading uses Indonesian conventions, while hermeneutic reading shows the hope of the spell reader to return the evil magic to its owner.