PASAR TERAPUNG Dalam Perspektif Pengembangan Pariwisata
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Floral Biology and Pollination Strategy of Durio (Malvaceae) in Sarawak, Malaysian Borneo
BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X Volume 21, Number 12, December 2020 E-ISSN: 2085-4722 Pages: 5579-5594 DOI: 10.13057/biodiv/d211203 Floral biology and pollination strategy of Durio (Malvaceae) in Sarawak, Malaysian Borneo NG WIN SENG1, JAYASILAN MOHD-AZLAN1, WONG SIN YENG1,2,♥ 1Institute of Biodiversity and Environmental Conservation, Universiti Malaysia Sarawak. 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia. 2Harvard University Herbaria. 22 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138, United States of America. ♥ email: [email protected]. Manuscript received: 25 September 2020. Revision accepted: 4 November 2020. Abstract. Ng WS, Mohd-Azlan J, Wong SY. 2020. Floral biology and pollination strategy of Durio (Malvaceae) in Sarawak, Malaysian Borneo. Biodiversitas 21: 5579-5594. This study was carried out to investigate on the flowering mechanisms of four Durio species in Sarawak. The anthesis started in the afternoon (D. graveolens and D. zibethinus), evening (D. kutejensis) or midnight (D. griffithii); and lasted between 11.5 hours (D. griffithii) to 20 hours (D. graveolens). All four Durio species are generalists. Individuals of a fruit bat (Eonycteris spelaea, Pteropodidae) are considered as the main pollinator for D. graveolens, D. kutejensis, and D. zibethinus while spiderhunter (Arachnothera, Nectariniidae) is also proposed as a primary pollinator for D. kutejensis. Five invertebrate taxa were observed as secondary or inadvertent pollinators of Durio spp.: honeybee, Apis sp. (Apidae), stingless bee, Tetrigona sp. (Apidae), nocturnal wasp, Provespa sp. (Vespidae), pollen beetle (Nitidulidae), and thrip (Thysanoptera). Honey bees and stingless bees pollinated all four Durio species. Pollen beetles were found to pollinate D. griffithii and D. graveolens while nocturnal wasps were found to pollinate D. -

Collection and Evaluation of Under-Utilized Tropical and Subtropical Fruit Tree Genetic Resources in Malaysia
J]RCAS International Symposium Series No. 3: 27-38 Session 1-3 27 Collection and Evaluation of Under-Utilized Tropical and Subtropical Fruit Tree Genetic Resources in Malaysia WONG, Kai Choo' Abstract Fruit tree genetic resources in Malaysia consist of cultivated and wild species. The cul tivated fruit trees number more than 100 species of both indigenous and introduced species. Among these fruits, some are popular and are widely cultivated throughout the country while others are less known and grown in small localized areas. The latter are the under-utilized fruit species. Apart from these cultivated fruits, there is also in the Malaysian natural forest a diversity of wild fruit tree species which produce edible fruits but are relatively unknown and unutilized. Many of the under-utilized and unutilized fruit species are known to show economic potential. Collection and evaluation of some of these fruit tree genetic resources have been carried out. These materials are assessed for their potential as new fruit trees, as sources of rootstocks for grafting and also as sources of germplasm for breeding to improve the present cultivated fruit species. Some of these potential fruit tree species within the gen era Artocarpus, Baccaurea, Canarium, Dimocarpus, Dialium, Durio, Garcinia, Litsea, Mangif era, Nephelium, Sa/acca, and Syzygium are highlighted. Introduction Malaysian fruit tree genetic resources comprise both cultivated and wild species. There are more than 100 cultivated fruit species of both major and minor fruit crops. Each category includes indigenous as well as introduced species. The major cultivated fruit crops are well known and are commonly grown throughout the country. -

Review Article Phytochemicals and Medicinal Properties of Indigenous Tropical Fruits with Potential for Commercial Development
Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2016, Article ID 7591951, 20 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/7591951 Review Article Phytochemicals and Medicinal Properties of Indigenous Tropical Fruits with Potential for Commercial Development Hock Eng Khoo,1,2 Azrina Azlan,1,2,3 Kin Weng Kong,4 and Amin Ismail1,2,3 1 Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia (UPM), 43400Serdang,Selangor,Malaysia 2Research Centre of Excellence for Nutrition and Non-Communicable Diseases, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia (UPM), 43400 Serdang, Selangor, Malaysia 3Laboratory of Halal Science Research, Halal Products Research Institute, Universiti Putra Malaysia (UPM), 43400Serdang,Selangor,Malaysia 4Department of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia Correspondence should be addressed to Azrina Azlan; [email protected] Received 28 December 2015; Revised 29 April 2016; Accepted 4 May 2016 Academic Editor: Daniela Rigano Copyright © 2016 Hock Eng Khoo et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Hundreds of fruit-bearing trees are native to Southeast Asia, but many of them are considered as indigenous or underutilized. These species can be categorized as indigenous tropical fruits with potential for commercial development and those possible for commercial development. Many of these fruits are considered as underutilized unless the commercialization is being realized despite the fact that they have the developmental potential. This review discusses seven indigenous tropical fruits from 15 species that have been identified, in which their fruits are having potential for commercial development. -
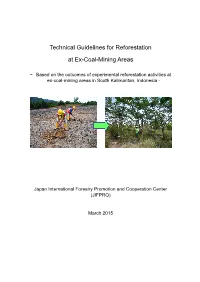
Technical Guidelines for Reforestation at Ex-Coal-Mining Areas
Technical Guidelines for Reforestation at Ex-Coal-Mining Areas - Based on the outcomes of experimental reforestation activities at ex-coal-mining areas in South Kalimantan, Indonesia - Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center (JIFPRO) March 2015 Technical Guidelines for Reforestation at Ex-Coal-Mining Areas - Based on the outcomes of experimental reforestation activities at ex-coal-mining areas in South Kalimantan, Indonesia - Eiichiro Nakama, Seiichi Ohta, Yasuo Ohsumi, Tokunori Mori and Satohiko Sasaki Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center Fakhrur Razie, Hamdani Fauzi and Mahrus Aryadi Lambung Mangkurat University, Indonesia Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center March 2015 Foreword During the past decades, deforestation and forest degradation continues especially in developing countries. According to the report of the Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), approximately 13 million hectors of global forests have been lost annually due to forest land conversion to other land uses, forest fires and natural disasters, while reforestation and natural regeneration account for an increase of approx. 7.8 million hectors of forest cover. This means the net loss of global forest is estimated at 5.2 million hectors. Adverse impacts of forest conversion to farmland can be minimized as far as the land is properly used and managed in a sustainable manner. However, in some cases, problem soils are exposed and abandoned as degraded land. Deforestation by mining is a big issue these years. Problem soils such as strong acid soils and/or too much heavy metal soils appear at the ex-mining areas. In some cases it is too difficult to reforestate. -

Isolasi Flavonoid Dari Daun Durian (Durio Zibethinus Murr., Bombacaceae)
Isolasi Flavonoid dari Daun Durian (Durio Zibethinus Murr., Bombacaceae) Muhamad Insanu*, Komar Ruslan, Irda Fidrianny, Sienny Wijaya Kelompok Keilmuan Biologi Farmasi, Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung, 40132 Abstrak Daun durian (Durio zibethinus Murr., Bombacaceae) secara tradisional banyak digunakan untuk menurunkan demam. Penelitian dan publikasi mengenai kandungan kimia daun durian masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah kandungan kimia daun durian. Simplisia daun durian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut berturut-turut n-heksana, etil asetat dan etanol. Ekstrak etanol difraksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan menggunakan pelarut eter, etil asetat dan butanol. Fraksi butanol dimurnikan secara kromatografi kertas preparatif. Sedangkan fraksi eter dimurnikan secara kromatografi lapis tipis preparatif. Isolat dikarakterisasi dengan penampak bercak spesifik, spektrofotometri ultraviolet - sinar tampak dan pereaksi geser. Dari ekstrak etanol diperoleh isolat S yang menunjukkan dua puncak pada 257 tim, 357 nm dan isolat W yang menunjukkan puncak pada 268 nm dan 313 nm. Isolat S merupakan golongan senyawa ilavonol 3-OH tersubstitusi dengan gugus OH pada atom C-5, C-7, C-3’ dan C-4’. Isolat W merupakan senyawa golongan flavon dengan gugus OH pada atom C-5, C-77 dan C-4'. Kata Kunci : Durio zibethinus, Durian, Flavonoid, Ilavonol, Flavon Abstract Durian (Durio zibethinus Murr., Bombacaceae) leaves was traditionally used for reducing fever. The researches of its chemical compounds were still limited. The aim of this research is to isolate the chemical compounds from durian leaves. Crude drug of durian leaves were consecutively extracted by maceration using n-hexane, ethyl acetate and ethanol. The ethanol extract was fractionated by liquid-liquid extraction using ether, ethyl acetate and butanol. -

Restoration Planning of Degraded Tropical Forests for Biodiversity and Ecosystem Services
Restoration planning of degraded tropical forests for biodiversity and ecosystem services Sugeng Budiharta Bachelor of Forestry Master of Science in Conservation Biology A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland in January 2016 School of Biological Sciences Abstract Forest restoration has the potential to mitigate the impact of deforestation and forest degradation. Various global policies have been sought to put restoration into the mainstream agenda including under the Convention on Biological Diversity (CBD) and the program for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+). The Aichi Target of the CBD set a target for at least 15% of degraded ecosystems to be restored by 2020 for key goals including biodiversity conservation, carbon enhancement and the provision of livelihoods. A theoretical framework to underpin decision- making for landscape-scale restoration has been slow to emerge, resulting in a limited contribution from science towards achieving such policy targets. My thesis develops decision frameworks to guide the restoration of degraded tropical forests to enhance biodiversity and the delivery of ecosystem services. In this thesis, three critical questions on how to make better decisions for landscape-scale restoration are addressed by: (a) considering landscape heterogeneity in terms of degradation condition, restoration action and cost, and temporally-explicit restoration benefits; (b) leveraging restoration within competing land uses using emerging policy for offsetting; and (c) enhancing feasibility by accounting for the social and political dimensions related to restoration. I use Kalimantan (Indonesian Borneo) as a case study area, as it represents a region that is globally important in terms of biodiversity and carbon storage. -

Natural Antioxidant Properties of Selected Wild Mangifera Species in Malaysia
J. Trop. Agric. and Fd. Sc. 44(1)(2016): 63 – 72 Mirfat, A.H.S., Salma, I. and Razali, M. Natural antioxidant properties of selected wild Mangifera species in Malaysia Mirfat, A.H.S.,1 Salma, I.2 and Razali, M.1 1Agrobiodiversity and Environmental Research Centre, Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia 2Gene Bank and Seed Centre, MARDI Headquarters, Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia Abstract Many wild fruit species found in Malaysia are not well known and are underutilised. Information on their health benefits is critical in efforts to promote these fruits. This study was conducted to evaluate the antioxidant potential of seven species of wild Mangifera (mango) in Malaysia: M. caesia (binjai), M. foetida (bacang), M. pajang (bambangan), M. laurina (mempelam air), M. pentandra (mempelam bemban), M. odorata (kuini) and M. longipetiolata (sepam). The results were compared to those obtained from a popular mango, M. indica. Among the mangoes, M. caesia was found to be the most potential source of antioxidant as evidenced by its potent radical scavenging activity (92.09 ± 0.62%), ferric reducing ability (0.66 ± 0.11 mm) and total flavonoid content (550.67 ± 19.78 mg/100 g). Meanwhile, M. pajang showed the highest total phenolic (7055.65 ± 101.89 mg/100 g) and ascorbic acid content (403.21 ± 46.83 mg/100 g). In general, from the results obtained, some of the wild mango relatives were found to have strong antioxidant potential that is beneficial to health. This study provides a better understanding of the nutraceutical and functional potential of underutilised Mangifera species. -

International Journal of Modern Pharmaceutical
IJMPR 2021, 5(4), 39-46 ISSN: 2319-5878 IJMPR Amandeep et al. International Journal International of Journal Modern of Modern Pharmaceutical Research 39 Review Article Pharmaceutical Research SJIF Impact Factor: 5.273 www.ijmpronline.com REVIEW ARTICLE ON MANILKARA HEXANDRA (KHIRNI) Amandeep Kaur* and Dr. Naresh Singh Gill Department of Pharmaceutical Chemistry, Rayat Institute of Pharmacy, Railmajra. Received on: 25/05/2021 ABSTRACT Revised on: 15/06/2021 Manilkara hexandra commonly known as Rayan and Khirni is an evergreen tree Accepted on: 05/07/2021 species with a long history of traditional medicinal uses in South Asia chiefly in western and central India, belongs to family Sapotaceae. The genus Manilkara includes *Corresponding Author 135 plants that are distributed Worldwide. Sapotaceae family consists of 58 genus and Amandeep Kaur just about 1250 species with morphological variation, ranging from shrubs to medium and giant trees. Brazil comprises of 11 genera, and 231 species, covering 1 endemic Department of genus, and 104 endemic species. The plant has been famous for its curative properties Pharmaceutical Chemistry, and has been put to use for treatment of various ailments suchlike ulcer, bronchitis, Rayat Institute of Pharmacy, jaundice, fever, hyper dyspepsia, arthritis and alimentary disorders. A record of the Railmajra. literature show extracts and metabolites from this plant having pharmacological properties such as anti–inflammatory, antiulcer, aphrodisiac, alexipharmic, anthelmintic, antibacterial, and free radical scavenging activity. Apart from medicinal uses, plant has high scale value because of its edible and nutritive fruit, useful wood, latex and bark and contributes substantial livelihood support to local inhabitants. KEYWORDS: Khirni, Manilkara hexandra, Sapotaceae, Rayan, Pharmacological properties. -

Mangifera Indica (Mango)
PHCOG REV. REVIEW ARTICLE Mangifera Indica (Mango) Shah K. A., Patel M. B., Patel R. J., Parmar P. K. Department of Pharmacognosy, K. B. Raval College of Pharmacy, Shertha – 382 324, Gandhinagar, Gujarat, India Submitted: 18-01-10 Revised: 06-02-10 Published: 10-07-10 ABSTRACT Mangifera indica, commonly used herb in ayurvedic medicine. Although review articles on this plant are already published, but this review article is presented to compile all the updated information on its phytochemical and pharmacological activities, which were performed widely by different methods. Studies indicate mango possesses antidiabetic, anti-oxidant, anti-viral, cardiotonic, hypotensive, anti-infl ammatory properties. Various effects like antibacterial, anti fungal, anthelmintic, anti parasitic, anti tumor, anti HIV, antibone resorption, antispasmodic, antipyretic, antidiarrhoeal, antiallergic, immunomodulation, hypolipidemic, anti microbial, hepatoprotective, gastroprotective have also been studied. These studies are very encouraging and indicate this herb should be studied more extensively to confi rm these results and reveal other potential therapeutic effects. Clinical trials using mango for a variety of conditions should also be conducted. Key words: Mangifera indica, mangiferin, pharmacological activities, phytochemistry INTRODUCTION Ripe mango fruit is considered to be invigorating and freshening. The juice is restorative tonic and used in heat stroke. The seeds Mangifera indica (MI), also known as mango, aam, it has been an are used in asthma and as an astringent. Fumes from the burning important herb in the Ayurvedic and indigenous medical systems leaves are inhaled for relief from hiccups and affections of for over 4000 years. Mangoes belong to genus Mangifera which the throat. The bark is astringent, it is used in diphtheria and consists of about 30 species of tropical fruiting trees in the rheumatism, and it is believed to possess a tonic action on mucus fl owering plant family Anacardiaceae. -

Download the Full Paper
J. Bio. & Env. Sci. 2019 Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) Vol. 14, No. 4, p. 54-64, 2019 http://www.innspub.net RESEARCH PAPER OPEN ACCESS Habitat’s biodiversity of endemic and introduction fruit trees in Samboja District Kutai Kartanegara Regency Rustam Baraq Noor1, Marjenah2, Arifien Bratawinata2, Paulus Matius2 1Forestry Science Doctoral Program, Forestry Faculty of Mulawarman University, Jl. Ki Hajar, Dewantara, Gunung Kelua Campus,Samarinda, East Kalimantan, Indonesia 2Forestry Faculty of Mulawarman University, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gunung Kelua Campus, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia Article published on April 28, 2019 Key words: Adaptation, Habitat, Species biodiversity, Fruit plants, Endemic, Exotic. Abstract Rustam Baraq Noor, Habitat’s biodiversity of endemic and exotic fruit trees in Samboja District Kutai Kartanegara Regency. Endemic and Exotic fruit biodiversity studied was situated in Salok Api Darat Village and Amborawang Laut Village Samboja District. This research aimed to identify the biodiversity and adaptation capabilities. The execution was in July 2015 to December 2016. The data was collected using survey, exploration, field observation and an interview for the plantation’s owner. Fruit species in the habitat of Samboja shore studied were 54 species and what was found in the field was 39 species endemic fruit trees and 21 exotic fruit trees. Species of endemic fruit trees were Durio zibethinus, Mangifera odorata, Durio kutejensis, Lansium domesticum, Nephelium lappaceum, Mangifera kemanga, Artocarpus champaden, and eksotik namely Artocarpus integra, Artocarpus altilis. Adaptation capabilities on the new habitat for Mangifera indica exotic fruit tree, it was fond that the grafting was prone to stem drill pest. -

11Th Flora Malesina Symposium, Brunei Darussalm, 30 June 5 July 2019 1
11TH FLORA MALESINA SYMPOSIUM, BRUNEI DARUSSALM, 30 JUNE 5 JULY 2019 1 Welcome message The Universiti Brunei Darussalam is honoured to host the 11th International Flora Malesiana Symposium. On behalf of the organizing committee it is my pleasure to welcome you to Brunei Darussalam. The Flora Malesiana Symposium is a fantastic opportunity to engage in discussion and sharing information and experience in the field of taxonomy, ecology and conservation. This is the first time that a Flora Malesiana Symposium is organized in Brunei Darissalam and in the entire island of Borneo. At the center of the Malesian archipelago the island of Borneo magnifies the megadiversity of this region with its richness in plant and animal species. Moreover, the symposium will be an opportunity to inspire and engage the young generation of taxonomists, ecologists and conservationists who are attending it. They will be able to interact with senior researchers and get inspired with new ideas and develop further collaboration. In a phase of Biodiversity crisis, it is pivotal the understanding of plant diversity their ecology in order to have a tangible and successful result in the conservation action. I would like to thank the Vice Chancellor of UBD for supporting the symposium. In the last 6 months the organizing committee has worked very hard for making the symposium possible, to them goes my special thanks. I would like to extend my thanks to all the delegates and the keynote speakers who will make this event a memorable symposium. Dr Daniele Cicuzza Chairperson of the 11th International Flora Malesiana Symposium UBD, Brunei Darussalam 11TH FLORA MALESINA SYMPOSIUM, BRUNEI DARUSSALM, 30 JUNE 5 JULY 2019 2 Organizing Committee Adviser Media and publicity Dr. -

Biblioasia Jan-Mar 2021.Pdf
Vol. 16 Issue 04 2021 JAN–MAR 10 / The Mystery of Madras Chunam 24 / Remembering Robinsons 30 / Stories From the Stacks 36 / Let There Be Light 42 / A Convict Made Good 48 / The Young Ones A Labour OF Love The Origins of Kueh Lapis p. 4 I think we can all agree that 2020 was a challenging year. Like many people, I’m looking Director’s forward to a much better year ahead. And for those of us with a sweet tooth, what better way to start 2021 than to tuck into PRESERVING THE SOUNDS OF SINGAPORE buttery rich kueh lapis? Christopher Tan’s essay on the origins of this mouth-watering layered Note cake from Indonesia – made of eggs, butter, flour and spices – is a feast for the senses, and very timely too, given the upcoming Lunar New Year. The clacking of a typewriter, the beeping of a pager and the Still on the subject of eggs, you should read Yeo Kang Shua’s examination of Madraschunam , the plaster made from, among other things, egg white and sugar. It is widely believed to have shrill ringing of an analogue telephone – have you heard these been used on the interior walls of St Andrew’s Cathedral. Kang Shua sets the record straight. sounds before? Sounds can paint images in the mind and evoke Given the current predilection for toppling statues of contentious historical figures, poet and playwright Ng Yi-Sheng argues that Raffles has already been knocked off his pedestal – shared memories. figuratively speaking that is. From a familiar historical figure, we turn to a relatively unknown personality – Kunnuck Mistree, a former Indian convict who remade himself into a successful and respectable member of society.