Skripsi Oki Libriyanto (0303060416)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reconnaissance Study Of
NO. RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT JANUARY 2006 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD GE JR 05-060 RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT JANUARY 2006 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION .............................................................. 1 1.1 BACKGROUND ................................................................ 1 1.2 OBJECTIVES....................................................................... 1 1.3 STUDY AREA..................................................................... 2 2. PRESENT CONDITIONS................................................. 3 2.1 SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS.................................. 3 2.1.1 Administration........................................................ 3 2.1.2 Population and Households.................................... 6 2.2 NATURAL CONDITIONS.................................................. 7 2.2.1 Topography and Geology ....................................... 7 2.2.2 Climate ................................................................... 7 2.2.3 River Systems........................................................ -

Hutan Di Banten Rusak Parah
Hutan Di Banten Rusak Parah Oleh : Atep Afia Hidayat – Staf Pengajar Teknik komponen lingkungan yang dikorbankan, Industri Universitas Mercu Buana, Jakarta termasuk hutan. Di bagian selatan Banten, yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang, kerusakan hutan tidak separah di bagian utara. Namun eksploitasi terus berlangsung, sebagai gambaran di kawasan hutan Gunung Halimun dan Gunung Kendeng, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, jawa Barat, areal yang tertutup vegetasi hutan tinggal 75-80 persen, dengan kata lain 20-25 persen areal hutan Propinsi Banten memiliki hutan tropis yang luas, sudah gundul. Sementara di perbatasan namun bersamaan dengan peningkatan jumlah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, penduduk kualitas dan kuantitas hutan terus seperti di Gunung Karang (meliputi perbatasan mengalami penurunan. Dari sekitar 250 ribu wilayah Kecamatan Ciomas, Keduhejo, hektar hutan yang ada di Banten, 90 ribu hektar Pandeglang dan Cadasari) 60 persen areal hutan atau 36 persen di antaranya dalam kondisi gundul dan di Gunung Aseupan (perbatasan rusak parah. Tekanan terhadap ekosistem hutan wilayah Kecamatan Menes, Mandalawangi, di bagian utara Banten jauh lebih besar Jiput dan Padarincang) 45 persen gundul. dibandingkan bagian selatan. Bagian utara Sedangkan di kawasan hutan Gunung Pulosari, Banten yang meliputi Kota dan kabupaten perbatasan antara Kecamatan Mandalawangi Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan Saketi, Kabupaten Pandeglang 65 persen memiliki tingkat kepadatan penduduk yang gundul. sangat tinggi, sehingga eksploitasi sumberdaya Eksploitasi ternyata tidak hanya terjadi di hutan alam termasuk hutan, berlangsung cepat dan pegunungan, tetapi juga di kawasan hutan boros. lainnya, seperti hutan yang ada di sekitar Tak dapat dipungkiri, keberadaan kawasan daerah aliran sungai (DAS) Ci Danau, Ci industri dan pemukiman yang terkonsentrasi di Beureum, Ci Simeut, Ci Ujung, Ci Baliung, Ci bagian utara menyebabkan degradasi kualitas Banten, Ci Bogor, Ci Durian, Ci Manceuri dan lingkungan sulit dihindari. -

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); - 2 - 2. -

Laporan Individu
LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGAJARAN LAPANGAN (PPL) SEMESTER KHUSUS TAHUN 2015/2016 SD NEGERI KARANGJATI, PLOSOKUNING, MINOMARTANI KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DWI NUR SETIYANINGSIH 12108244011 PGSD PUSAT PENGEMBANGAN PRAKTIK PENALAMAN LAPAGAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ( PP PPL dan PKL ) LPPMP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2015 i ii KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kehadirat Alah SWT, yang telah memberikan bimbingan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan di SD Negeri Karangjati ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat paa wakunya, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Perlu disadari bahwa terselesaikannya pembuatan laporan ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oeh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 1. Orang tua yang telah memberikan bantuan dan dorongan secara material. 2. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd, M.A selaku rektor UNY, 3. Drs. Ngatman Soewito selaku ketua pelaksana PP PPL dan PKL UNY, 4. Drs. Dwi Yuniarifi, M.Si. selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan banyak memberikan penggarahan, 5. Jumadi, S.Pd. SD selaku kepala SD Negeri Karangjati yang telah bersedia menerima kami mahasiswa praktikan PPL di sekolah tersebut, 6. Suwaji, S.Pd selaku koordinator PPL di sekolah, 7. Sri Murwaningsih, S.Pd selaku Guru Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya, mohon maaf jika selama proses mengajar masih banyak kesalahan. 8. Bapak dan Ibu guru dan seluruh karyawan SD Negeri Karangjati, 9. Siswa- siswi SD Negeri Karangjati tahun ajaran 2015/ 2016, 10. Sahabat perjuangan PPL UNY SD Negeri Karangjati ( Sari, Nourma, Ima, Anisa, Anna, Atika, Desi, Arsyad, Boma, Wahet, Ferry, Wahyu, Dayat ), dan 11. -

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. -

Rationalization of Rain Stations in the Ciliwung Cisadane River Basin
International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 0974-3154, Volume 12, Number 12 (2019), pp. 2957-2963 © International Research Publication House. http://www.irphouse.com Rationalization of Rain Stations in the Ciliwung Cisadane River Basin Fisnu Yudha Pramono1, Suripin2, Suharyanto3 and Widada Sulistya4 1 Doctoral Student, Universitas Diponegoro, Indonesia. 2 Professor, Universitas Diponegoro, Indonesia. 3 Lecturer, Universitas Diponegoro, Indonesia. 4 Deputy Official, BMKG, Indonesia. Abstract destructive power of water resources need accurate, timely and sustainable rainfall. Its data needs to be adequately recorded Hydrological calculations to support the development, because it is used in creating basic plans. research, management, conservation, and control of the destructive power of water resources need accurate, timely and Hydrological station data are expected to be produced properly sustainable rainfall. The accuracy of the hydrological base is using appropriate methods and competent human resource dependent on the station’s location for accurate monitoring of quality. Its accuracy greatly depends on the capability of the its flow characteristics. Therefore, further studies are required station in monitoring the condition of the hydrological to determine the placement of hydrological stations in the characteristics of a flow area accurately and correctly. Ciliwung Cisadane River Basin. The approach to obtain a reliable data network is by This rationalization is an approach to produce a reliable rationalizing the hydrological station [10] [5]. Besides that, it is hydrological station network with accurate, effective and also able to produce accurate, effective and efficient rainfall efficient data. It also describes and analyses the hydrological data used to describe or represent the hydrological conditions conditions of the study area. -
Penentuan Koefisien Imbuhan (Rc) Air Tanah Sungai Cisadane Hulu – Sub Das Cisadane
PENENTUAN KOEFISIEN IMBUHAN (RC) AIR TANAH SUNGAI CISADANE HULU – SUB DAS CISADANE Oleh : Muhammad Agus Karmadi ABSTRAK Imbuhan air tanah alami yang dimanifestasikan oleh lengkung penyusutan (recession curve) aliran dasar (base flow) adalah komponen yang sangat penting dari aliran sungai yang dihasilkan oleh aliran masuk melalui proses infiltrasi curah hujan menjadi perkolasi dan akhirnya menyumbang ke simpanan air tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran tentatif Koefisien Imbuhan Air Tanah Alami Sub DAS Cisadane hulu dengan luas 842.69 Km², di mana besaran imbuhan ini bisa dipakai sebagai dasar untuk penetapan pengambilan air tanah yang di izinkan pada daerah yang bersangkutan berbasis lingkungan yang bersifat sustainable/berkelanjutan, agar pemanfaatan air tanah tetap lestari. Selain itu nilai koefisien imbuhan ini juga dapat dipakai untuk menetapkan secara tak langsung besarnya imbuhan air tanah di DAS sekitarnya dalam proses regionalisasi. Karakteristik DAS yang paling umum yang mempengaruhi besar imbuhan yang meliputi curah hujan, variabel geologi, tingkat infiltrasi tanah, faktor aliran dasar, dan tutupan lahan. Kajian yang dilaksanakan untuk mendapatkan estimasi rata rata nilai imbuhan menggunakan Kurva Resesif (lengkung penyusutan/recession curve) dari data debit harian periode tahun 1980 – 2015 yang diperoleh dari Pusat Litbang Sumber Daya Air, Bandung. Nilai curah hujan rata-rata dicari dengan metode Isohyet kemudian dapat ditentukan nilai koefisien imbuhan (Recharge Coefficien) yakni besar nilai imbuhan dibagi dengan curah hujan rata-rata serta di bagi luas wilayah DAS maka diperoleh N ilai Koefisien Imbuhan (RC) yang di peroleh berdasarkan perhitungan sebesar 0.14 %. Sedangkan berdasarkan perhitungan Imbuhan yang terjadi pada Formasi Batuan di dapatkan N ilai Koefisien Imbuhan (RC) sebesar : 742.11 x 106 m3/tahun. -
IPS Paket a Final Modul 1 TAK KENAL MAKA TAK SAYANG-Awal
TINGKATAN II MODUL TEMA 1 TINGKATAN II MODUL TEMA 1 Tak Kenal Maka Tak Sayang i Kata Pengantar Daftar Isi HALAMAN JUDUL endidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang Kata Pengantar ...................................................................................... ii karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti Daftar Isi ................................................................................................. iii pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan P Petunjuk Penggunaan Modul .................................................................. 1 dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul ............................ 2 peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari. Unit 1 SAYANGI ALAM INDONESIA Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik A. Keterangan Antar Ruang ................................................................... 2 peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran B. Letak Wilayah di Kab/Kota/Propinsi ................................................. -
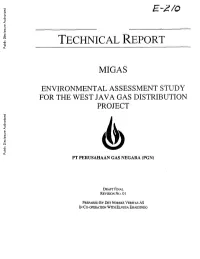
TECHNICAL REPORT Public Disclosure Authorized
E -/ A TECHNICAL REPORT Public Disclosure Authorized MIGAS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY FOR THE WEST JAVA GAS DISTRIBUTION Public Disclosure Authorized PROJECT Public Disclosure Authorized PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) DRAFT FINAL REVISION No. 01 PREPARED BY DET NORSKE VER1TAS AS IN CO-OPERAnON WITH ELNUSA EHAESINDO Public Disclosure Authorized t DRAFT FINAL TECHNICAL REPORT * Table of Contents Page I EXECUTIVE SUMMARY ..............................................1 1.1 Abstract 1 1.2 Introduction 1 1.3 Policy, Legal and Administrative Framework I ,I 1.4 Description of the Gas Distribution Project 2 i 1.5 Environmental Baseline Description 2 ,, 1.6 Safety Baseline Description 3 1.7 Social and Economic Baseline Description 3 1.8 Communities and Cultural Baseline Description 3 1.9 Pollution Baseline 4 1.10 Environmental Impacts on Land Use 4 1.11 Environmental Impacts from Pollution 4 A 1.12 Accidental Events - Assessment of Safety and Environmental Risks 4 ; 1.12.1 Safety risks 4 1.12.2 Environmental risks 4 1.13 Impacts on Social and Economic Conditions 5 1.14 Impacts on Communities and Culture 5 * 1.15 Analysis of Alternative Options 5 - 1.16 Environmental and Safety Mitigation Plan 6 s 1.17 Environmental and Safety Management within PGN 6 1.17.1 PGN organisation 6 1.17.2 Gas distribution project 6 1.17.3 Contractors 6 1.17.4 Environmental and Safety Monitoring Programme 7 Q 1.18 PGN Commitments on Environment and Safety 7 2 INTRODUCTION ............. 8 2.1 Purpose of This Report 8 2.2 Overview of the Trans South Sumatera - West Java Gas Development Project 8 2.3 Brief Description of the PGN Gas Distribution System 9 2.4 Methodology of the Environmental Assessment Study 10 2.5 Report Structure 12 3 POLICY, LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK............................... -
Water Resources Management in the 6 Cis River Basin Territory
POLA SUMMARY WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE 6 CIS RIVER BASIN TERRITORY YEAR 2012 DIRECTORATE GENERAL WATER RESOURCES MINISTRY OF PUBLIC WORKS TABLE OF CONTENTS Page 1. Background 3 2. Problems 4 2.1. WR Conservation 4 2.2. WR Utilization 4 2.3. Control of Water Destructive Power 5 2.4. Water Resource Information System 5 2.5. Empowerment and Improvement of Community and Private Sector Participation 5 3. Scenario - Strategy 9 4. Conclusion And Recommendation 11 5. Effort – Operational Policy 15 5.1. CONSERVATION 15 5.1.1 Protection and Preservation of Water Resource 15 5.1.2 Water Preservation 15 5.1.3 Water Quality Management and Pollution Control 15 5.2. WATER RESOURCES UTILIZATION 16 5.2.1 Water Resources Allocation 16 5.2.2 Water Resources Provision 16 5.2.3 WR Utilization 17 5.2.4 WR Development 17 5.3. CONTROL OF WATER DESTRUCTIVE POWER 17 5.3.1 Prevention of Disaster 17 5.3.2 Mitigation 17 5.3.3 Recovery from Disaster 18 5.4. WATER RESOURCE INFORMATION SYSTEM 18 5.5. EMPOWERMENT / IMPROVEMENT OF COMMUNITY, PRIVATE SECTOR AND GOVERNMENT PARTICIPATION 18 5.5.1 WRM Institution 18 5.5.2 Funding 18 5.5.3 Governance 18 5.5.4 Coordination Forum for PSDA (WRM) 19 5.5.5 Empowerment & Improvement of Community and Private Sector Participation 19 5.6. SPATIAL PLANNING 19 page i LIST OF FIGURES Figure 2.1. Map of critical land in 6 Cis RBT 6 Figure 2.2. Map of water distribution scheme in 6 Cis RBT 7 Figure 2.3. -

Morfometri Das Di Jawa Bagian Barat Skripsi
UNIVERSITAS INDONESIA MORFOMETRI DAS DI JAWA BAGIAN BARAT SKRIPSI UTUT RARA PUTRA 0806328801 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN GEOGRAFI DEPOK 2012 Morfometri das..., Utut Rara Putra, FMIPA UI, 2012 UNIVERSITAS INDONESIA MORFOMETRI DAS DI JAWA BAGIAN BARAT SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana UTUT RARA PUTRA 0806328801 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN GEOGRAFI DEPOK JUNI, 2012 i Morfometri das..., Utut Rara Putra, FMIPA UI, 2012 SALAMAN PER$YARATAN *RI$INALITA$ Skripsi iri ruerupaican hasil karya sesdiri ribn semua sumberyaag diktitip araupirn dirujuk telah saya nyatakandengan benar aT^-^ LaittfitL NPA4 TaadaTaagan Tanggal 27 luni 2412 Morfometri das..., Utut Rara Putra, FMIPA UI, 2012 HALAMAN PENGESAHAN Skripsi ini diajukan oleh : Nama : Utut RaraPutra NPM : 0806328801 Program Studi : Geografi Judul Skripsi : Morfometri DAS di Jawa Bagian Barat Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geografr, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia Dewan Penguji Ketua Sidang Dr. Ir. Tarsoen Waryono M.Si nlp- Pembimbing I Dr. Rer Nat Eko Kusratrnoko M.S Pembimbing II Drs. Tjiong Giok Pin, M.Si Penguji II Drs. Sobirin M.Si Penguji III Drs. Hari Kartono,M.S Ditetapkan di : Depok Tanggal : 27 Jvri2012 llr Morfometri das..., Utut Rara Putra, FMIPA UI, 2012 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “ Morfometri DAS di Jawa Bagian Barat” ini telah berhasil diselesaikan. Penulisan tugas akhir dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains Ilmiah Departemen Geografi , Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. -

Pusat Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2014
MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI KREATIF (Studi Kasus di Enam Sentra Wisata di Jawa Barat) Laporan Penelitian Kelompok Mendapat Bantuan Dana dari BOPTN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2014 Peneliti: Ketua: Endah Ratna Sonya, M.Si. Anggota: M. Taufiq Rahman, Ph.D. Anggota: Dr. Muhammad Zuldin, M.Si. Anggota: Kustana, M.Si. Pusat Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2014 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan akan banyaknya potensi kreatif masyarakat yang harus digali secara optimal melalui pengembangan masyarakat berbasis budaya dan lingkungan hidup. Penelitian ini mengambil kasus di Saung Angklung Udjo Bandung, Kawasan Sentra Bunga Cihideung Lembang-Bandung Barat, Keraton Kasepuhan Cirebon, Sentra Golok Galonggong Tasikmalaya, Sentra Ikan Rancapanggung Cililin, dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Melalui berbagai aktivitas tersebut, masyarakat di sekitar kawasan tersebut semakin meningkat kehidupan ekonominya dan juga turut aktif menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan budaya. Penelitian ini mengidentifikasi pengembangan potensi yang belum digarap secara optimal harus menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengoptimalkan manfaat untuk masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari enam lokasi penelitian dapat dirinci bahwa empat lokasi yaitu Saung Angklung Udjo, Wisata Bunga Cihideung, Sentra Golok Galonggong, dan Sentra Ikan Rancapanggung itu masuk dalam model pembangunan masyarakat lokal. Karakteristik utamanya adalah aktor utama yang merintis arena tersebut adalah berdasarkan inisiatif masyarakat lokal. Dalam terminologi pembangunan sosial, itu disebut sebagai pembangunan model bottom up. Sementara itu, Keraton Kasepuhan Cirebon dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak berada pada ranah perencanaan sosial. Model ini tidak lagi berbasiskan inisiatif lokal, tetapi dibangun atas perencanaan sosial yang dilakukan oleh berbagai kekuatan formal maupun informal.