Kajian Sosial-Budaya Masyarakat Pada Lanskap Riparian Sungai Ciliwung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Pb) Pollution in the River Estuaries of Jakarta Bay
The Sustainable City IX, Vol. 2 1555 Analysis of lead (Pb) pollution in the river estuaries of Jakarta Bay M. Rumanta Universitas Terbuka, Indonesia Abstract The purpose of this study is to obtain information about the level of Pb in the sediment of the estuaries surrounding Jakarta Bay and to compare them. Samples were taken from 9 estuaries by using a grab sampler at three different location points – the left, right and the middle sides of the river. Then, samples were collected in one bottle sample and received drops of concentrated HNO3. The taking of samples was repeated three times. In addition, an in situ measurement of pH and temperature of samples was taken as proponent data. The Pb concentration of the river sediment was measured using an AAS flame in the laboratory of Balai Penelitian Tanah Bogor. Data was analyzed statistically (one way ANOVA and t-test student) by using SPSS-11.5 software. The results show that Pb concentration in the sediment of the estuaries surrounding Jakarta was quite high (20–336 µg/g). The sediment of Ciliwung River in the rainy season was the highest (336 µg/g). Pb concentration of sediment in the dry season was higher than that in the rainy season, except in Ciliwung River. It was concluded that all rivers flowing into Jakarta Bay make a significant contribution to the Pb pollution in Jakarta Bay, and the one with the largest contribution was Ciliwung River. Keywords: Pb, sediment, estuaries, dry season, rainy season, AAS flame. 1 Introduction Jakarta Bay (89 km of length) is formed as a result of the extension of Karawang Cape in the eastern region and Kait Cape in the western region into the Java Sea (Rositasari [1]). -
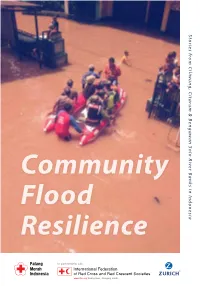
Community Flood Resilience
Stories from Ciliwung, Citarum & Bengawan Solo River Banks in Indonesia Community Flood Resilience Stories from Ciliwung, Citarum & Bengawan Solo River Banks in Indonesia Community Flood Resilience Stories from Ciliwung, Citarum & Bengawan Solo River Banks Publisher Palang Merah Indonesia (PMI) in partnership with Stories from Ciliwung, Citarum & Bengawan Solo River Banks in Indonesia International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Zurich Insurance Indonesia (ZII) Palang Merah Indonesia National Headquarter Disaster Management Division Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 96 - Jakarta 12790 Phone: +62 21 7992325 ext 303 Fax: +62 21 799 5188 www.pmi.or.id First edition March 2018 CFR Book Team Teguh Wibowo (PMI) Surendra Kumar Regmi (IFRC) Arfik Triwahyudi (ZII) Editor & Book Designer Gamalel W. Budiharga Writer & Translator Budi N.D. Dharmawan English Proofreader Daniel Owen Photographer Suryo Wibowo Infographic Dhika Indriana Photo Credit Suryo Wibowo, Budi N.D. Dharmawan, Gamaliel W. Budiharga & PMI, IFRC & ZII archives © 2018. PMI, IFRC & ZII PRINTED IN INDONESIA Community Flood Resilience Preface resilience/rɪˈzɪlɪəns/ n 1 The capacity to recover quickly from difficulties; toughness;2 The ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity. https://en.oxforddictionaries.com iv v Preface hard work of all the parties involved. also heads of villages and urban Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, The program’s innovations have been villages in all pilot program areas for proven and tested, providing real their technical guidance and direction Praise for Allah, that has blessed us so that this solution, which has been replicated for the program implementors as well Community Flood Resilience (CFR) program success story in other villages and urban villages, as SIBAT teams, so the program can book is finally finished. -

Economic Impacts of Sanitation in Indonesia
Research Report August 2008 Economic Impacts of Sanitation in Indonesia A five-country study conducted in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, the Philippines, and Vietnam under the Economics of Sanitation Initiative (ESI) Water and Sanitation Program East Asia and the Pacifi c (WSP-EAP) World Bank Offi ce Jakarta Indonesia Stock Exchange Building Tower II/13th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Tel: (62-21) 5299-3003 Fax: (62-21) 5299-3004 Printed in 2008. The volume is a product of World Bank staff and consultants. The fi ndings, interpretations, and conclusions expressed herein do not necessarily refl ect the views of the Board of Executive Directors of the World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of the World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement of acceptance of such boundaries. Research Report August 2008 Economic Impacts of Sanitation in Indonesia A fi ve-country study conducted in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, the Philippines, and Vietnam under the Economics of Sanitation Initiative (ESI) EXECUTIVE SUMMARY Executive Summary At 55% in 2004, sanitation coverage in Indonesia is below the regional average for Southeast Asian countries of 67%. Nationwide, sanitation coverage has increased by 9 percentage points since 1990, representing signifi cant progress towards the target of 73% set by the Millennium Development Goal joint water supply and sanitation target. -

Reconnaissance Study Of
NO. RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT JANUARY 2006 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD GE JR 05-060 RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT JANUARY 2006 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD RECONNAISSANCE STUDY OF THE INSTITUTIONAL REVITALIZATION PROJECT FOR MANAGEMENT OF FLOOD, EROSION AND INNER WATER CONTROL IN JABOTABEK WATERSHED FINAL REPORT TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION .............................................................. 1 1.1 BACKGROUND ................................................................ 1 1.2 OBJECTIVES....................................................................... 1 1.3 STUDY AREA..................................................................... 2 2. PRESENT CONDITIONS................................................. 3 2.1 SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS.................................. 3 2.1.1 Administration........................................................ 3 2.1.2 Population and Households.................................... 6 2.2 NATURAL CONDITIONS.................................................. 7 2.2.1 Topography and Geology ....................................... 7 2.2.2 Climate ................................................................... 7 2.2.3 River Systems........................................................ -

Heavy Metal Concentration in Water, Sediment, and Pterygoplichthys Pardalis in the Ciliwung River, Indonesia 1Dewi Elfidasari, 1Laksmi N
Heavy metal concentration in water, sediment, and Pterygoplichthys pardalis in the Ciliwung River, Indonesia 1Dewi Elfidasari, 1Laksmi N. Ismi, 2Irawan Sugoro 1 Department of Biology, Faculty of Science and Technology University Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia; 2 The Center of Isotope and Radiation Application (PAIR), The National Agency of Nuclear Energy (BATAN), Jakarta, Indonesia. Corresponding author: D. Elfidasari, [email protected] Abstract. Ciliwung River is one of the most polluted freshwaters in Indonesia, shown by its color, smell, and the wastes. Generally, the presence of heavy metals is an indicator of pollution in any river. Furthermore, the survival of waters biota is determined by the pollution levels of the water and sediment, including the Pterygoplichthys pardalis fish dominating the river. The purpose of this study therefore was to record the concentration of heavy metals in water, sediment, and P. pardalis in the Ciliwung River from upstream in Bogor to its downstream in Jakarta. The X-Ray Fluorescence (XRF) spectrometer was used to analyze the metals. The results showed that the concentrations of heavy metals such as Cd, Hg, and Pb were relatively high in the water and sediment of the river, exceeding the threshold of Indonesian Government Regulation. The highest concentration of these metals was found in the samples from Ciliwung River Jakarta area. The concentrations of these metals were quite high in the P. pardalis flesh exceeding the threshold set through the provisions of National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and Indonesia National Standard (SNI). On analysis, there was a strong correlation between the metal content of fish flesh and sediment. -

The Pollution Index and Carrying Capacity of the Upstream Brantas River
International Journal of GEOMATE, Sept., 2020, Vol.19, Issue 73, pp. 26 – 32 ISSN: 2186International-2982 (P), 2186-2990 Journal (O), Japan, of GEOMATE,DOI: https://doi.org/10.21660/2020.73.55874 Sept., 2020, Vol.19, Issue 73, pp. 26 – 32 Geotechnique, Construction Materials and Environment THE POLLUTION INDEX AND CARRYING CAPACITY OF THE UPSTREAM BRANTAS RIVER Kustamar1 and *Lies Kurniawati Wulandari1 1Faculty of Civil Engineering and Planning, National Institute of Technology (ITN) Malang, Indonesia *Corresponding Author, Received: 28 July 2019, Revised: 13 Jan. 2020, Accepted: 17 March 2020 ABSTRACT: River is one of the surface water resources that is often polluted by various human activities. With its dynamic characteristics, a river must be periodically examined to determine its water quality. This study aims to investigate the carrying capacity of the Brantas river in East Java, Indonesia. The observation was done by measuring TSS (Total suspended solid), TDS (Total dissolved solid), and oil and grease in the upstream zone of the Brantas river. This research used a descriptive method. The determination of the research stations was based on the condition of the watershed and its surroundings, assuming that there was a decrease in water quality. The sampling points include Pendem Bridge (1), DAM (local water company) Sengkaling (2), Simpang Remujung Bridge (3), and Samaan District (4). The results demonstrated that the upstream Brantas river at each sampling point had different pollution levels. Generally, the sampling point 1 (Pendem Bridge) was the cleanest zone compared to other sampling points. On the other hand, sampling point 4 (Samaan District) was the most polluted site of the upstream zone. -

Water Environment Issues in Indonesia: Challenges and Opportunities
1 Water Environment Issues in Indonesia: Challenges and Opportunities Prof. Tjandra Setiadi Centre for Environmental Studies Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Indonesia [email protected] 2 Presentation Outline Water Challenges and Examples of Opportunities Colalboration in Indonesia Case Studies Water Environment In Indonesia 3 Water Environment in Indonesia 4 Introduction Indonesia water resource: . 6 % of world water resource . 21% of asia pasific water resource 5 6 7 Four Water Classes (Quality) (Government Regulation No 82 Year 2001 • Class I : Best Quality designated for raw water for water supply; and include Class II till IV (BOD < 2 mg/L) • Class II : designated for water sport activities (not a direct contact) and include Class III and IV (BOD < 3 mg/L) • Class III: designated for fishery (aquaculture) and include Class IV (BOD < 6 mg/L) • Class IV : designated for irrigation (BOD < 12 mg/L) • For most of the rivers in Indonesia: intended to be Class II. 8 River Quality Monitoring 2009 (based on class II designated, MoE lab. data) Province River Name Province River Name Province River Name NAD Krueng Aceh Sulut Tondano Province River Name Province River Name Batu Gajah Deli Gorontalo Bone Banten Kali Angke Kalbar Kapuas Maluku Sumut Batu Merah Percut Sulteng Palu Jakarta Ciliwung Kalteng Kahayan Mal-Utara Tabobo Riau Kampar Tallo Jabar Citarum Kalsel Martapura Sulsel Papua Anafre Sumbar Batang Agam Kaltim Mahakam Jeneberang Jateng Progo Province River Name Jambi Batang Hari Sultra Konaweha DIY Progo Bali T. Badung Bengkulu A. Bengkulu Jatim Brantas NTT Dendeng Sumsel Musi NTB Jangkok Lampung W.Sekampung Babel Rangkui Light pollution Medium pollution Heavy pollution Light to medium pollution Medium to heavy pollution Light to heavy pollution 9 River Quality Monitoring 2009 (based on class II designated, MoE lab. -

JICA Data Collection Survey on Water Environment Improvement Through Low-Cost Wastewater Treatment System in Jakarta
City of Jakarta (DKI JAKARTA) Ministry of Public Works (PU) Wastewater Management Enterprize (PD PAL JAYA) JICA Data Collection Survey on Water Environment Improvement through Low-Cost Wastewater Treatment System in Jakarta Final Report October 2010 Japan International Cooperation Agency Hiroshima University Currency rate (monthly from 2006 to present) Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2006 USD1=JPY 116.47 114.58 112.17 116.32 114.66 116.94 117.63 117.45 116.07 118.8 121.77 119.78 IDR1=JPY 0.01235 0.01307 0.01219 0.01247 0.01272 0.01289 0.01279 0.0129 0.01265 0.01314 0.01338 0.01324 2007 USD1=JPY 117.38 119.03 121.59 123 118.53 115.73 115.55 114.67 109.98 114.21 106.98 106.18 IDR1=JPY 0.01286 0.01312 0.01381 0.01357 0.01299 0.0123 0.01266 0.01261 0.01172 0.01213 0.01159 0.01174 2008 USD1=JPY 99.29 104.05 105.1 106.17 108.05 109.33 105.9 98.23 95.37 90.44 90.02 97.95 IDR1=JPY 0.01079 0.01119 0.01126 0.01157 0.01185 0.01196 0.01116 0.00923 0.0076 0.00812 0.00789 0.00819 2009 USD1=JPY 97.29 96.87 96.47 95.55 95.25 93.13 89.98 90.87 86.66 91.45 90.14 89.25 IDR1=JPY 0.00842 0.00905 0.00914 0.0093 0.00959 0.00928 0.00925 0.00946 0.00922 0.00969 0.00969 0.00952 2010 USD1=JPY 92.7 94.06 91.1 88.66 87.05 IDR1=JPY 0.01022 0.01044 0.00986 0.00975 0.00969 (Source: JICA rate table) Jakarta Bay Area : 661.52 km2 32 km Located at Low lying area Crossed by 13 rivers Population 12 million South China Sea Jabodetabek Pacific Ocean Indian Ocean Jakarta Bay Jakarta Ciliwung river Cisadane river Depok Jatilihur dam Bogor Cirata dam Bandung Saguling -

Elucidating Flood Disaster Problems in the World Capital Cities: Analyzing the Role of Humantrain Supply Chain
712 Int. J Sup. Chain. Mgt Vol. 9, No. 3, June 2020 Elucidating Flood Disaster Problems in the World Capital Cities: Analyzing the Role of Humantrain Supply Chain Muzani' ' Geography Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220 [email protected] Abstract-Jakarta is one of the cities that is often hit by Dutch government built 3 dams. Jago Dam and Udik floods. The problem of flooding in Jakarta is actually not a Dam, both of which are located at the top of the river and new thing. Many factors make Jakarta city vulnerable to Bendungan Hilir which are located downstream of the flooding. These factors are natural and anthropogenic Ciliwung river (Jakarta) [10]. As a result of a massive factors. These natural factors are: (1) Jakarta is located in flood in 1876, the Dutch government rebuilt the Flood the lowlands near the coast, (2) there are 13 rivers flowing Canal which stretched from the Manggarai area in the through Jakarta, and (3) the high annual rainfall in the center of the city to the Muara Angke area in the coastal Ciliwung watershed (> 3000 mm). While anthropogenic factors are: (1) landscape changes due to high competition area of Jakarta. The existence of this canal is intended to in land-based economic activities, (2) poor urban and rural prevent flooding in Jakarta. It is hoped that through this spatial planning, and (3) lack of integrated institutional canal, flood water will flow faster to the Java Sea on the capacity and arrangements, especially in cross-border coast of Jakarta. -

Short-Term Water Level Prediction Using Fuzzy Adaptive System and Artificial Neural Networks Approaches
Short-term Water Level Prediction Using Fuzzy Adaptive System and Artificial Neural Networks Approaches 1R. Erinawati and 2J. Fenton 1Civil and Environmental Engineering Department, The University of Melbourne, 2School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, The University of Melbourne, E-Mail: [email protected] , [email protected] Keywords: Neural Networks, Fuzzy Adaptive System, River Flow Forecasting EXTENDED ABSTRACT (MAE), and coefficient determination (R2). To allow direct comparisons for four rivers, unit free This paper presents a comparative study on short- formulas from RMSE and MAE are also employed. term water level prediction using fuzzy adaptive These are known as root mean square percentage systems (FAS) and artificial neural networks error (RMSPE) and mean absolute percentage error (ANNs). The short-term water prediction (three (MAPE). days or less prediction) is crucial for flood warning system. This prediction is usually ANNs and FAS produced similar pattern results. calculated using conceptual or physical-based However, ANNs gave slightly better results for models. almost all rivers. Out of four rivers, only the Bengawan Solo performed very well up to three Although conceptual or physical-based models days ahead predictions (RMSPE < 25%). The can lead to better understanding of hydraulic and model of the Ciliwung River could perform hydrological processes, these types of models are relatively well. For ANN models, both the often constrained by data availability, funding Bogowonto and Telomoyo River could actually limitation and human resources. In this paper, the gave reasonable results with RMSPE < 25% for one ANNs and FAS methods are applied to handle day ahead. Their performance decreased such situations where data are limited, such as in significantly for a longer period. -

Ciliwung River in Jakarta, Indonesia
CILIWUNG RIVER IN JAKARTA, INDONESIA Della Permata –08R12105 YSEP 2008 Civil Engineering Department Tokyo Institute of Technology INDONESIA Government Official name : Republic of Indonesia Capital: Jakarta Form of government : Presidential, unitary form • Geography – Location : south eastern Asia, archipelago between the indian ocean and the pacific ocean – Total area : 1,919,440 sq km (5x Japan) – Archipelago of more than 17,500 islands (6,000 inhabited); straddles Equator – Climate: tropical; hot, humid; more moderate in highlands • People – Population: 237,512,352 (July 2008 est.) – Religions: Muslim 88%, Protestant 5%, Roman Catholic 3%, Hindu 2%, Bu ddhis t 1%,other 1% – Languages: Bahasa Indonesia (official, modified form of Malay), English, Dutch, local dialects, the most widely spoken of which is Javanese JAKARTA Asthecapilital city and largest city of IdIndones ia, Jakarta has a greater population than any other city in ShSoutheast AiAsia. Jakarta has an area of 750.28 square kilo metres and a population of 8,489,910 people (2008 census). Jakarta is the twelfth-largest city in the world; the metropolitan area, called Jabodetabek, is the sixth-largest in the world. Jakarta is located on the northwestern coast of Java, at the mouth of the Ciliwung River on Jakarta Bay, which is an inlet of the Java Sea. ENVIRONMENTAL ISSUES Water pollution Air Environmen pollution tal problems Solid waste disposal Soil pollution WATER POLLUTION Sea River Laaeke Water pollution Groundwater Bay etc RIVER CONDITION IN JAKARTA RIVER POLLUTION IN JAKARTA Approximately is about 64 rivers from 470 rivers in Indonesia has critical condition. An d it spreads in many ciiities. -

Water Quality Impacts of the Citarum River on Jakarta and Surrounding Bandung Basin
Water Quality Impacts of the Citarum River on Jakarta and Surrounding Bandung Basin Senior Thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Science Degree At The Ohio State University By Coleman Quay The Ohio State University 2018 Table of Contents Abstract .......................................................................................................................................................... i Acknowledgements ....................................................................................................................................... ii Introduction ................................................................................................................................................... 1 Physical Setting ............................................................................................................................................. 2 Location of the Study Area ....................................................................................................................... 2 Climate ...................................................................................................................................................... 3 Hydrology ................................................................................................................................................. 7 Geology ..................................................................................................................................................... 8 Water Resources