PENDIDIKAN BERBASIS NILAI-Nllai KEBANGSAAN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tourism Sector Development Strategy in North Maluku: a Case Study of Tidore Islands
Tourism Sector Development Strategy in North Maluku: A Case Study of Tidore Islands Prince Charles Heston Runtunuwu Faculty of Economics and Business, Khairun University Jl. Yusuf Abdulrahman, Gambesi, Ternate 97719, Indonesia Correspondence Email: [email protected] ABSTRACT Tourism is one of the important things for a country, with tourism, a country or more specifically the Regional Government where the tourist object is located, receives income from the income of each tourist attraction. This study aims to identify and determine tourism objects that need to get a priority scale as a leading tourism to be developed; how the strategies that need to be formulated in the context of developing tourist objects in the City of Tidore Islands. The number of research samples was 70 people. The test tools used are analysis weighted product, simple linear regression, SWOT analysis. The results showed that: (1) the leading tourist attraction in the City of Tidore Archipelago is the Kie Kedaton Kie tourist attraction in the Tidore Sultanate, which is ranked 1; (2) service quality on visitor satisfaction shows that the level of service quality has a significant effect of 73.3% on visitor satisfaction at the Kie Kedaton Kie Sultanate of Tidore; (3) The strategy for developing the leading tourism objects in the City of Tidore Islands is as follows: (i). Improve the quality and quantity of human resources (HR) so that managers of tourist attractions are more optimal, (ii). Development of supporting facilities to build vacant land, which is governed by policies and development of investment marketing and tourism marketing, (iii). Collaborating with third parties (private) or community self-help parties, (iv). -

Sultan Zainal Abidin Syah: from the Kingdomcontents of Tidore to the Republic of Indonesia Foreword
TAWARIKH:TAWARIKH: Journal Journal of Historicalof Historical Studies Studies,, VolumeVolume 12(1), 11(2), October April 2020 2020 Volume 11(2), April 2020 p-ISSN 2085-0980, e-ISSN 2685-2284 ABDUL HARIS FATGEHIPON & SATRIONO PRIYO UTOMO Sultan Zainal Abidin Syah: From the KingdomContents of Tidore to the Republic of Indonesia Foreword. [ii] JOHANABSTRACT: WAHYUDI This paper& M. DIEN– using MAJID, the qualitative approach, historical method, and literature review The– discussesHajj in Indonesia Zainal Abidin and Brunei Syah as Darussalam the first Governor in XIX of – WestXX AD: Irian and, at the same time, as Sultan of A ComparisonTidore in North Study Maluku,. [91-102] Indonesia. The results of this study indicate that the political process of the West Irian struggle will not have an important influence in the Indonesian revolution without the MOHAMMADfirmness of the IMAM Tidore FARISI Sultanate, & ARY namely PURWANTININGSIH Sultan Zainal Abidin, Syah. The assertion given by Sultan TheZainal September Abidin 30 Syahth Movement in rejecting and the Aftermath results of in the Indonesian KMB (Konferensi Collective Meja Memory Bundar or Round Table andConference) Revolution: in A 1949, Lesson because for the the Nation KMB. [103-128]sought to separate West Irian from Indonesian territory. The appointment of Zainal Abidin Syah as Sultan took place in Denpasar, Bali, in 1946, and his MARYcoronation O. ESERE, was carried out a year later in January 1947 in Soa Sio, Tidore. Zainal Abidin Syah was Historicalas the first Overview Governor of ofGuidance West Irian, and which Counselling was installed Practices on 23 inrd NigeriaSeptember. [129-142] 1956. Ali Sastroamidjojo’s Cabinet formed the Province of West Irian, whose capital was located in Soa Sio. -

Otoritas Dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional Di Loloda Maluku-Utara (1808-1958)
Sosiohumaniora, Volume 15, No. 1, Maret 2013 : 64 – 72 OTORITAS DAN LEGITIMASI KEDUDUKAN PEMIMPIN TRADISIONAL DI LOLODA MALUKU-UTARA (1808-1958) Mustafa Mansur, Kunto Sofianto, dan Dade Mahzuni Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate Email:[email protected] ABSTRAK. Studi mengenai kedudukan kepemimpinan tradisional di Loloda Maluku Utara`pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan Indonesia (1945-1958) merupakan studi untuk melihat aspek-aspek perubahan terhadap kedudukan pemimpin di Loloda sebagai akibat dari politik kolonial dan pengaruh Kesultanan Ternate. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang diangkat adalah bagaimana kedudukan pemimpin tradisional di Loloda pada masa kolonial dan masa kemerdekaan Indonesia (1945-1958)? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sementara konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah konsep kekuasaan, stratifikasi sosial dan legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemimpin tradisional di Loloda pada masa kolonial (1808-1909) mengalami degradasi dengan diubahnya status Kerajaan Loloda menjadi distrik oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemimpinnya tetap memakai gelar raja (kolano) karena didukung oleh otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik serta sistem pewarisan kekuasaan (assigned status) dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kolonial juga mengakui gelar raja (kolano) sebagai strategi membangun kekuasaanya di Loloda. Pengakuan -

Program – IEOM 2018 Washington DC
Organizer INTERNATIONAL Third North American International Conference IEOMon Industrial Engineering and Operations Management, Washington, DC SEPTEMBER 27–29, 2018 Host University IEOM Washington DC Conference September 27-29, 2018 Sponsors and Partners Organizer IEOM Society International Welcome to the Third North American IEOM Conference in Washington, DC To All Conference Attendees: On behalf of the IEOM Society International, we would like to welcome you to Washington, DC, USA, the University of the District of Columbia (UDC) and the Third North American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. This unique international conference provides a forum for academics, researchers and practitioners from many industries to exchange ideas and share recent developments in the field of industrial engineering and operations management. This diverse international event provides an opportunity to collaborate and advance the theory and practice of major trends in industrial engineering and operations management. There were close to 550 papers/abstracts submitted from 60 countries and after a thorough peer review process, approximately 350 have been accepted .The program includes many cutting edge topics of industrial engineering and operations management. This conference will address many of the issues concerning continuous improvement for quality and service. Our keynote speakers will address some of these issues: • Ronald Mason, Jr., J.D., President, University of the District of Columbia, Washington, DC • Dr. Bruce Kramer, Senior Advisor, NSF • John H. James, Jr., Executive Director, Missile Defense Agency • Dr. Claudia Rankins, Program Officer, Directorate for Education and Human Resources, NSF • Dr. Pamela McCauley, Program Director, Innovation Corps-National Innovation Network Sites Program, NSF and Professor and Director of the Ergonomics Laboratory, Department of Industrial Engineering and Management Systems, University of Central Florida • Dr. -
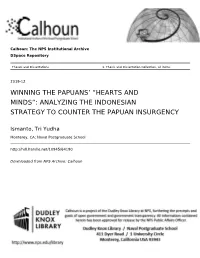
Analyzing the Indonesian Strategy to Counter the Papuan Insurgency
Calhoun: The NPS Institutional Archive DSpace Repository Theses and Dissertations 1. Thesis and Dissertation Collection, all items 2019-12 WINNING THE PAPUANS’ “HEARTS AND MINDS”: ANALYZING THE INDONESIAN STRATEGY TO COUNTER THE PAPUAN INSURGENCY Ismanto, Tri Yudha Monterey, CA; Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/64190 Downloaded from NPS Archive: Calhoun NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS WINNING THE PAPUANS’ “HEARTS AND MINDS”: ANALYZING THE INDONESIAN STRATEGY TO COUNTER THE PAPUAN INSURGENCY by Tri Yudha Ismanto December 2019 Thesis Advisor: Douglas A. Borer Second Reader: Robert E. Burks Approved for public release. Distribution is unlimited. THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK Form Approved OMB REPORT DOCUMENTATION PAGE No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington, DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED (Leave blank) December 2019 Master’s thesis 4. TITLE AND SUBTITLE 5. FUNDING NUMBERS WINNING THE PAPUANS’ “HEARTS AND MINDS”: ANALYZING THE INDONESIAN STRATEGY TO COUNTER THE PAPUAN INSURGENCY 6. AUTHOR(S) Tri Yudha Ismanto 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. -

The Emergence of Papuan Tribal Governance: a Case Study of Societal Knowledge Creation
The Emergence of Papuan Tribal Governance: A Case Study of Societal Knowledge Creation by Totok Hari Wibowo Submitted to Japan Advanced Institute of Science and Technology In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Dr. Katsuhiro Umemoto School of Knowledge Science Japan Advanced Institute of Science and Technology June 2005 Copyleft 2005 by Totok Hari Wibowo STATEMENT BY AUTHOR This dissertation has been submitted in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at Japan Advanced Institute of Science and Technology and is deposited in the Institute Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Quotations from this manuscript in whole or in part are allowable without special permission, provided that accurate acknowledgment of the copyleft holder is made. It is the Author’s hope that this work will spawn new ideas for research. ii ACKNOWLEDGMENTS It has been an exceptional journey - one that I had never dreamed of before. My research track was started right after I became a graduate student in 2001, when I was accepted by Dr. Katsuhiro Umemoto at the Japan Advanced Institute of Science and Technology in Tatsunokuchi, Ishikawa. I am deeply indebted to Dr. Umemoto for his encouragement, advice, mentoring, and research support throughout my doctoral studies. I also truly appreciate his patience and tolerance during my numerous mishaps. This dissertation is part of the research carried out through his vision throughout the last four years. I regard myself fortunate to have the opportunity to work with a group of enthusiastic people in Dr. -

The Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia
The impact of migration on the people of Papua, Indonesia A historical demographic analysis Stuart Upton Department of History and Philosophy University of New South Wales January 2009 A thesis submitted to the Faculty of Arts and Social Sciences in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy 1 ‘I hereby declare that this submission is my own work and to the best of my knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the award of any other degree or diploma at UNSW or any other educational institution, except where due acknowledgement is made in the thesis. Any contribution made to the research by others, with whom I have worked at UNSW or elsewhere, is explicitly acknowledged in the thesis. I also declare that the intellectual content of this thesis is the product of my own work, except to the extent that assistance from others in the project’s design and conception or in style, presentation and linguistic expression is acknowledged.’ Signed ………………………………………………. Stuart Upton 2 Acknowledgements I have received a great deal of assistance in this project from my supervisor, Associate-Professor Jean Gelman Taylor, who has been very forgiving of my many failings as a student. I very much appreciate all the detailed, rigorous academic attention she has provided to enable this thesis to be completed. I would also like to thank my second supervisor, Professor David Reeve, who inspired me to start this project, for his wealth of humour and encouragement. -

Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua
Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua DISERTASI Diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam oleh : Toni Victor M. Wanggai 02.3.00.1.04.01.0070 Promotor : Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. Dr. Uka Tjandrasasmita SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/1429 H ii PERSETUJUAN Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka). Jakarta, November 2008 Ketua Sidang / merangkap Promotor, Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. iii PERSETUJUAN Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka). Jakarta, November 2008 Promotor/ merangkap Penguji, Dr.Uka Tjandrasasmita iv PERSETUJUAN Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. Wanggai, NIM. 02.3.00.1.04.01.0070, telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar dari Tim Penguji pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal 31 Agustus 2008, dapat disetujui untuk dibawa ke Sidang Promosi Doktor (Ujian Terbuka). Jakarta, November 2008 Penguji, Prof. Dr. Badri Yatim, M.A. v PERSETUJUAN Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua” yang ditulis oleh Toni Victor M. -

JAIST Repository
JAIST Repository https://dspace.jaist.ac.jp/ 創発するパプア部族統治 ~社会的知識創造の事例研 Title 究 Author(s) Totok, Hari Wibowo Citation Issue Date 2005-06 Type Thesis or Dissertation Text version author URL http://hdl.handle.net/10119/825 Rights Supervisor:Katsuhiro Umemoto, 知識科学研究科, 博 Description 士 Japan Advanced Institute of Science and Technology The Emergence of Papuan Tribal Governance: A Case Study of Societal Knowledge Creation by Totok Hari Wibowo Submitted to Japan Advanced Institute of Science and Technology In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Dr. Katsuhiro Umemoto School of Knowledge Science Japan Advanced Institute of Science and Technology June 2005 Copyleft 2005 by Totok Hari Wibowo STATEMENT BY AUTHOR This dissertation has been submitted in partial fulfillment of the requirements for an advanced degree at Japan Advanced Institute of Science and Technology and is deposited in the Institute Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Quotations from this manuscript in whole or in part are allowable without special permission, provided that accurate acknowledgment of the copyleft holder is made. It is the Author’s hope that this work will spawn new ideas for research. ii ACKNOWLEDGMENTS It has been an exceptional journey - one that I had never dreamed of before. My research track was started right after I became a graduate student in 2001, when I was accepted by Dr. Katsuhiro Umemoto at the Japan Advanced Institute of Science and Technology in Tatsunokuchi, Ishikawa. I am deeply indebted to Dr. Umemoto for his encouragement, advice, mentoring, and research support throughout my doctoral studies. -

Walikota Tidore Kepulauan
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT HUKUM ADAT KESULTANAN TIDORE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kesultanan Tidore serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI; b. bahwa Kesultanan Tidore merupakan salah satu kesultanan yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara hingga kini masih hidup dan diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa adat istiadat dan budaya masyarakat adat kesultanan Tidore sampai kini masih terpelihara dengan baik, sehingga membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Tidore; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 5. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 6. -

Competition and Cooperation in Social and Political Sciences
COMPETITION AND COOPERATION IN SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES AACHWAN7_Book.indbCHWAN7_Book.indb i 111/15/20171/15/2017 99:06:36:06:36 AAMM AACHWAN7_Book.indbCHWAN7_Book.indb iiii 111/15/20171/15/2017 99:06:36:06:36 AAMM PROCEEDINGS OF THE ASIA PACIFIC RESEARCH IN SOCIAL AND HUMANITIES, DEPOK, INDONESIA, 7–9 NOVEMBER 2016: TOPICS IN SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Competition and Cooperation in Social and Political Sciences Editors Isbandi Rukminto Adi & Rochman Achwan Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, Indonesia AACHWAN7_Book.indbCHWAN7_Book.indb iiiiii 111/15/20171/15/2017 99:06:36:06:36 AAMM Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2018 Taylor & Francis Group, London, UK Typeset by V Publishing Solutions Pvt Ltd., Chennai, India Although all care is taken to ensure integrity and the quality of this publication and the information herein, no responsibility is assumed by the publishers nor the author for any damage to the property or persons as a result of operation or use of this publication and/or the information contained herein. The Open Access version of this book, available at www.tandfebooks.com, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license. Published by: CRC Press/Balkema Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands e-mail: [email protected] www.crcpress.com – www.taylorandfrancis.com ISBN: 978-1-138-62676-8 (Hbk) ISBN: 978-1-315-21362-0 (eBook) AACHWAN7_Book.indbCHWAN7_Book.indb iivv 111/15/20171/15/2017 99:06:36:06:36 AAMM Competition and Cooperation in Social and Political Sciences – Adi & Achwan (Eds) © 2018 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-62676-8 Table of contents Preface ix Organizing committee xi Keynote speech Reconciliation after recognition? Indigenous-settler relations in Australia 3 A. -

The Impact of Migration on the Province of Papua, Indonesia
The impact of migration on the people of Papua, Indonesia A historical demographic analysis Stuart Upton Department of History and Philosophy University of New South Wales January 2009 A thesis submitted to the Faculty of Arts and Social Sciences in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy 1 ‘I hereby declare that this submission is my own work and to the best of my knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the award of any other degree or diploma at UNSW or any other educational institution, except where due acknowledgement is made in the thesis. Any contribution made to the research by others, with whom I have worked at UNSW or elsewhere, is explicitly acknowledged in the thesis. I also declare that the intellectual content of this thesis is the product of my own work, except to the extent that assistance from others in the project’s design and conception or in style, presentation and linguistic expression is acknowledged.’ Signed ………………………………………………. Stuart Upton 2 Acknowledgements I have received a great deal of assistance in this project from my supervisor, Associate-Professor Jean Gelman Taylor, who has been very forgiving of my many failings as a student. I very much appreciate all the detailed, rigorous academic attention she has provided to enable this thesis to be completed. I would also like to thank my second supervisor, Professor David Reeve, who inspired me to start this project, for his wealth of humour and encouragement.