Pertimbangan Hakim Yang Bias Rasial Dalam
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SIDANG TILANG TGL, 12 Oktober 2018 P O L R E S T a B E S S E M a R a N G No
SIDANG TILANG TGL, 12 Oktober 2018 P O L R E S T A B E S S E M A R A N G No. Reg. NAMA ALAMAT PASAL BB BB Denda Bia perk 1 4393936 SUGIONO LINGK GANDEK MAGETAN287 UULAJ STNK B-1891-KYB 79000 1000 2 4393937 SUNARDI NGESAL KAB SMG 287 UULAJ SIM BI U 79000 1000 3 4393938 WAHYU AGUNG S BULU SRAGEN 287 UULAJ SIM BI 79000 1000 4 4393939 IMAM SUBANDI SILIREJO PEKALONGAN 287 UULAJ SIM A 79000 1000 5 4393940 YAFI YAHYA PS CANDI PRAMBANAN SMG 281 UULAJ STNK H-2684-AQG 79000 1000 6 4396386 EKO WDODO DS TLOGOREJO DEMAK 288 UULAJ STNK H-5130-CS 79000 1000 7 4396387 LIS SETYANINGRUM CANDI MUTIARA SMG 281 UULAJ STNK H-4118-AEW 69000 1000 8 4396388 SRI LESTARI KARANGGAWANG SMG 281 UULAJ STNK H-4174-ARG 79000 1000 9 4396389 YOPI ZERKANATO WONOBOYO KEBUMEN 281 UULAJ STNK AA-2990-HM 59000 1000 10 4396390 DHONNY EKA SA DURIAN SMG 281 UULAJ SIM C 79000 1000 11 4396191 KASRONI KARANG DEMAK 281 UULAJ SIM C 79000 1000 12 4396192 M KHAFID KEMBANGARUM DEMAK 281 UULAJ STNK H-4368-BCS 59000 1000 13 4396193 M SEPTIAN DWI B KOBER GG AMIN JAKTIM 281 UULAJ SIM C 79000 1000 14 4396194 DUWI SUPRIYANTO DSN KEDNUNGWUNGU GROBOGAN281 UULAJ STNK H-2546-TP 79000 1000 15 4396195 ZAENAL MUHTAROM GONDOSSARI SMG 281 UULAJ STNK H-1434-LW 149000 1000 16 4396421 AMMAR FIKRI S BLIMBING PEMALANG 287 UULAJ SIM C 79000 1000 17 4396422 HINDHAR PRIYO U CEMARA TMR SMG 287 UULAJ SIM C 79000 1000 18 4396423 NUR HAKIM PASIGITAN KENDAL 281 UULAJ STNK H-5486-GW 79000 1000 19 4396424 CAKYANTO DUKUH LO BREBES 287 UULAJ SIM C 79000 1000 20 4396425 ALFIAN YUSUF SS KARANGANYAR DEMAK 281 UULAJ STNK -

DONG JIONG WITHDRAWS from MALAYSIAN OPEN (Bernama 04
04 JUL 1997 Badminton-Open DONG JIONG WITHDRAWS FROM MALAYSIAN OPEN By: Hamdan Saaid KUALA LUMPUR, July 4 (Bernama) -- Olympic silver medalist and world number one Dong Jiong of China has withdrawn from the US$180,000 (RM450,000) Malaysian Open badminton championships in Kota Kinabalu from July 9 to 13. The Chinese Badminton Association has informed the organisers that Dong, who had also pulled out from the World Championships in Glasgow due to high fever, was unable to compete due to injury. It was another set back for the championships which had earlier seen the withdrawal of reigning world champion Peter Rasmussen of Denmark while Malaysia's top doubles champ Yap Kim Hock pulled out due to shoulder injury, forcing his partner Cheah Soon Kit to find a new partner. In Dong's absence, former world champion Joko Suprianto of Indonesia has been seeded first in the six-star tournament while defending champion Ong Ewe Hock has been drawn to meet Joko in the final. According to the seedings released by the International Badminton Federation (IBF), Ewe Hock is in the same half with third seed Peter-Gade Christensen of Denmark. Christensen, who became the first European since Morten Frost Hansen to win a title in Asia when he won the Taiwan Open this year, is expected to clash with the Malaysian in the semifinal. Three-time champion Rashid Sidek has been seeded fourth and is likely to come up with Joko in the last four. Rashid beat him in the quarterfinals in the Olympi c Games in Atlanta. -

Individuaalne MM 1977-2019
Dan Lin Vasakult paremale: Dan Lin (Hiina), Jong-Bong Park (Lõuna-Korea), Nan Zhang (Hiina), Haifeng Fu (Hiina), Yun Cai (Hiina), Dong-Moon Kim (Lõuna-Korea) INDIVIDUAALSED MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED. MEHED. MEDALID MEDALID KOKKU MS MD XD Riik Võistleja M K H P K H P K H P K H P CHN Dan LIN 7 5 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 KOR Joo-Bong PARK 7 5 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 CHN Nan ZHANG 7 4 0 3 0 0 0 1 0 1 3 0 2 CHN Haifeng FU 6 4 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 CHN Yun CAI 6 4 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 KOR Dong-Moon KIM 6 3 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 KOR Yong-Dae LEE 6 0 3 3 0 0 0 0 3 2 0 0 1 INA Hendra SETIAWAN 5 4 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 INA Mohammad AHSAN 5 3 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 DEN Thomas LUND 5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 MAS Chong Wei LEE 5 0 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 CHN Chen XU 5 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 ENG Mike TREDGETT 5 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2 DEN Peter Høeg GADE 5 0 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 CHN Bingyi TIAN 4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 CHN Yongbo LI 4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 INA Christian HADINATA 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 CHN Long CHEN 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 CHN Yang SANG 4 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 INA Tontowi AHMAD 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 CHN Cheng LIU 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 INA Taufik HIDAYAT 4 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 DEN Jon HOLST-CHRISTENSEN 4 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 DEN Jens ERIKSEN 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 MAS Kien Keat KOO 4 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 CHN Siwei ZHENG 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 INA Nova WIDIANTO 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 INA Ricky SUBAGJA 3 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 JPN Kento MOMOTA 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 KOR Moon-Soo KIM 3 2 0 1 0 0 0 2 0 1 -

FORZA Verdens Vel Nok Hårdeste Smash, SUPER POWER-SERIEN Har FZ Super Power 8000 Givet FORZA® Ham Endnu Mere Fart I Smashen
BADMINTON »Badminton« markerer sæsonstar Ring til os på tlf. 98 43 0092 og bestil de Og gevinst er der hver gang til dem, der ► ten ved at udsende bladet i etstort tre ekstra numre eller send kuponen her benytter sig af »Badmintons« rabataftaler oplag på 100.000 eksemplarer, der markerer, nederst på siden - eller tag en fotokopi, hvis med DSB og Hotel Triton i København. at badminton er Danmarks familieidræt num du ikke vil klippe i bladet. De 75 kr. henter du Aftalen med DSB indebærer, at alle klub mer et. Dermed når »Badminton« ud til man hjem igen, hvis du bruger blot nogle af »Bad ber kan rejse med en ekstra rabat på 15% - ge nye læsere denne gang - og både til dem mintons« mange abonnomentsfordele. oven i alle andre rabatordninger. Man skal og til de faste abonnenter ønsker vi velkom blot tilmelde sig ordningen ved at bestille men til en ny og spændende sæson med Gevinst hver gang rekvisitioner hos DSB, passagerdivisionen på »Badminton«. Vi udkommer frem til årsskif En af dem er en stor konkurrence om tlf. 33 14 04 00. tet med tre ekstra numre for baggrund og præmier for 100.000 kr., som vi fortæller Hotel Triton, der ligger fem minutters debat om badmintonsporten i ind- og udland. nærmere om inde i bladet. Alle er medi kon gang fra Hovedbanegården tilbyder »Badmin Det koster naturligvis, og derfor skal vi kurrencen, for er de abonnementsnummer tons« abonnenter overnatning for blot 200 opfordre alle læsere - både nye og gamle - til trukket ud har du vundet en af de mange kr. -

Daftar Nama Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Kualifikasi Pendidikan
DAFTAR NAMA PELAMAR LULUS SELEKSI ADMINISTRASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SARJANA JABATAN AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO NOMOR REGISTER NAMA 1 10100192010103026 CANDRA RANI MAHARDIKHA 2 10100194032627021 BOY APRISANTO GURNING 3 10100197002102116 SABIRIN 4 10100298076319233 ISNANUR KHUROTUL AINI 5 10100398030604763 JEFRY MONANG MANALU 6 10100491076301716 VIDIA LESTARI, S.PSI 7 10100493011627021 ARIZALDI AHNAN LUBIS 8 10100496031805723 LAKSAMANA ARDHIAN ALUN SAMUDERA 9 10100590121701781 VIRANDHI OCKTA WIJAYA 10 10100594015601761 NOVITA APRIYANTI 11 10100595060106723 OSEP SUPRIATNA 12 10100599085601761 NYIMAS SOPHIA SAHDINI 13 10100691054503713 EVELINE NURHAYATI 14 10100692032111731 DEDE TRI WAHYU KOTAMA 15 10100692094905713 NAOMI FRICILLA 16 10100692166305723 DESY SARI PUSPITANINGRUM 17 10100696005203015 NI PUTU YUNIATI SUCI DEWI 18 10100783025411737 NURHIKMAH JAYA 19 10100790154903041 DESYANA GULTOM 20 10100791065106723 AZZAHRA NABILA PUTRI 21 10100792044408041 THESSA INDRIYANTI 22 10100792122905713 CIPTO ALDI 23 10100793026417123 SHELVIANA RIZKIANI S 24 10100796040306731 ANDIKA RIZKY PRATAMA 25 10100797015329023 INTAN 26 10100797031604763 FRIDHO INDRAYASA 27 10100888080511761 MAWRIS 28 10100983074201736 LISA ADMIYANTI 29 10100991045405713 ALYA ZHARIFA RAHMADHANI 30 10200091051105723 MUHAMMAD NURHIDAYATULLAH 31 10200691180606123 ADRIAN DEARDO 32 10200792052205723 MOHAMMAD CAHYO KRESNO 33 10200794014305723 DITHA PUSPITA DIENENGSARI 34 11000001045304015 KOMANF DESY MEDYANTI PUSPANINGRUM 35 11000002065201711 FEBRIZKI PUTRI ARESY 36 -

Svjetska Prvenstva (1977-2007)
SVJETSKA PRVENSTVA (1977-2007) Malmo– 1977 M - Flemming Delfs (DEN) Ž - Lene Koppen (DEN) MM - Tjun Tjun/Johan Wahjudi (INA) ŽŽ - Etsuko Toganoo/Erniko Ueno (JPN) MŽ - Steen Skovgaard/Lene Koppen (DEN) Jakarta– 1980 M - Rudy Hartono (INA) Ž - Verawaty Wiharjo (INA) MM - Ade Chandra/Christian Hadinata (INA) ŽŽ - Nora Perry/Jane Webster (ENG) MŽ - Christian Hadinata/Imelda Wiguno (INA) Kopenhagen– 1983 M - Icuk Sugiarto (INA) Ž - Li Lingwei (CHN) MM - Steen Fladberg/Jesper Helledie (DEN) ŽŽ - Lin Ying/Wu Dixi (CHN) MŽ - Thomas Kihlstrom/Nora Perry (SWE/ENG) Calgary– 1985 M - Han Jian (CHN) Ž - Han Aiping (CHN) MM - Park Joo Bong/Kim Moon Soo (KOR) ŽŽ - Han Aiping/Li Lingwei (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Yoo Sang Hee (KOR) Peking– 1987 M - Yang Yang (CHN) Ž - Han Aiping (CHN) MM - Li Yongbo/Tian Bingyi (CHN) ŽŽ - Lin Ying/Guan Weizhen (CHN) MŽ - Wang Pengren/Shi Fangjing (CHN) Jakarta– 1989 M - Yang Yang (CHN) Ž - Li Lingwei (CHN) MM - Li Yongbo/Tian Bingyi (CHN) ŽŽ - Lin Ying/Guan Weizhen (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Chung Myung Hee (KOR) Kopenhagen– 1991 M - Zhao Jianhua (CHN) Ž - Tang Jiuhong (CHN) MM - Park Joo Bong/Kim Moon Soo (KOR) ŽŽ - Guan Weizhen/Nong Qunhua (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Chung Myung Hee (KOR) Birmingam– 1993 M - Joko Suprianto (INA) Ž - Susi Susanti (INA) MM - Ricky Subagja/Rudy Gunawan (INA) ŽŽ - Nong Qunhua/Zhou Lei (CHN) MŽ - Thomas Lund/Catrine Bengtsson (DEN/SWE) Lausanne– 1995 M - Heryanto Arbi (INA) Ž - Ye Zhaoying (CHN) MM - Rexy Mainaky/Ricky Subagja (INA) ŽŽ - Gil Young Ah/Jang Hye Ock (KOR) MŽ - Thomas Lund/Marlene -
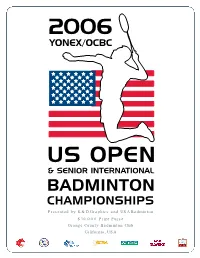
Presented by K & D Graphics and USA Badminton $30,000 Prize
06_US_Open_program 8/4/06 12:40 PM Page 1 Presented by K & D Graphics and USA Badminton $30,000 Prize Purse Orange County Badminton Club California, USA 06_US_Open_program 8/4/06 12:40 PM Page 2 2006 OCBC/YONEX US OPEN ORGANIZING COMMITTEE SANCTIONING ORGANIZATIONS TITLE SPONSORS International Badminton Federation (IBF) Yonex Corporation Pan American Badminton Confederation (PABC) K & D Graphics United States Badminton Association (USAB) Southern California Badminton Association (SCBA) EQUIPMENT SPONSOR Yonex Corporation HONORARY CHAIRPERSON Dr. Kang Young Joong, President (IBF) OFFICIAL HOTEL DoubleTree Hotel - Anaheim/Orange ORGANIZING COMMITTEE CHAIR Don Chew, President/CEO (K&D Graphics/OCBC) UMPIRES David Carton TOURNAMENT DIRECTOR Ian Counter Paisan Rangsikitpho, Vice President (USAB) Manfred Giehl (Germany) Elaine Kong REFEREE Catharine Lee Ian Lagden (CAN) David Lee Lynn Maund DEPUTY REFEREE Mrs. Ali Nanning (Netherland) Charlotte Ackerman Christina Orita Chris Phillips TOURNAMENT COMMITTEE Arthur Schwartz Bob Cook - Assistant Tournament Director Dudley Chen, Terry Lira - Match Control LINE JUDGES Dale Crawford, Jeff Yau - Tournament Desk Ron Blanchard Carol Bryan - Results/Draws Victor Liu Ana Cook, Tim Mangkalakiri, Panita Phongasavithas, Gisele Nguyen Jeff Yau - Registration/Credentials/Information Leslie Nguyen Ed Barnes, Calvin Blocker - Court Manager Linda Shen Carol Bryan, Tom Wilmhurst - Line Judge Coordinator Peni Subhandi Oraphan Chansawangpuvana - Awards and Presentation Dudley Chen, Dale Crawford, Glenn Crawford, Terry -

Svetska Prvenstva
SVJETSKA PRVENSTVA (1977-2010 ) Malmo– 1977 M - Flemming Delfs (DEN) Ž - Lene Koppen (DEN) MM - Tjun Tjun/Johan Wahjudi (INA) ŽŽ - Etsuko Toganoo/Erniko Ueno (JPN) MŽ - Steen Skovgaard/Lene Koppen (DEN) Jakarta– 1980 M - Rudy Hartono (INA) Ž - Verawaty Wiharjo (INA) MM - Ade Chandra/Christian Hadinata (INA) ŽŽ - Nora Perry/Jane Webster (ENG) MŽ - Christian Hadinata/Imelda Wiguno (INA) Kopenhagen– 1983 M - Icuk Sugiarto (INA) Ž - Li Lingwei (CHN) MM - Steen Fladberg/Jesper Helledie (DEN) ŽŽ - Lin Ying/Wu Dixi (CHN) MŽ - Thomas Kihlstrom/Nora Perry (SWE/ENG) Calgary– 1985 M - Han Jian (CHN) Ž - Han Aiping (CHN) MM - Park Joo Bong/Kim Moon Soo (KOR) ŽŽ - Han Aiping/Li Lingwei (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Yoo Sang Hee (KOR) Peking– 1987 M - Yang Yang (CHN) Ž - Han Aiping (CHN) MM - Li Yongbo/Tian Bingyi (CHN) ŽŽ - Lin Ying/Guan Weizhen (CHN) MŽ - Wang Pengren/Shi Fangjing (CHN) Jakarta– 1989 M - Yang Yang (CHN) Ž - Li Lingwei (CHN) MM - Li Yongbo/Tian Bingyi (CHN) ŽŽ - Lin Ying/Guan Weizhen (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Chung Myung Hee (KOR) Kopenhagen– 1991 M - Zhao Jianhua (CHN) Ž - Tang Jiuhong (CHN) MM - Park Joo Bong/Kim Moon Soo (KOR) ŽŽ - Guan Weizhen/Nong Qunhua (CHN) MŽ - Park Joo Bong/Chung Myung Hee (KOR) Birmingam– 1993 M - Joko Suprianto (INA) Ž - Susi Susanti (INA) MM - Ricky Subagja/Rudy Gunawan (INA) ŽŽ - Nong Qunhua/Zhou Lei (CHN) MŽ - Thomas Lund/Catrine Bengtsson (DEN/SWE) Lausanne– 1995 M - Heryanto Arbi (INA) Ž - Ye Zhaoying (CHN) MM - Rexy Mainaky/Ricky Subagja (INA) ŽŽ - Gil Young Ah/Jang Hye Ock (KOR) MŽ - Thomas Lund/Marlene -

Kontribusi Koni Dalam Sistem Keolahragaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional
i UNIVERSITAS INDONESIA KONTRIBUSI KONI DALAM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M Si) Pada Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Oleh Drs. SUNARJO SLAMET WIDODO NPM : 0806449456 FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL JAKARTA JUNI 2011 Kontribusi koni..., Sunarjo Slamet Widodo, Pascasarjana UI, 2011 UNIVERSITAS INDONESIA KONTRIBUSI KONI DALAM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M Si) Pada Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Oleh Drs. SUNARJO SLAMET WIDODO NPM : 0806449456 FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL JAKARTA Juni 2011 Kontribusi koni..., Sunarjo Slamet Widodo, Pascasarjana UI, 2011 ii PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL HALAMAN PERSETUJUAN NAMA : Drs. Sunarjo Slamet Widodo NPM : 080 644 9456 JUDUL TESIS : KONTRIBUSI KONI DALAM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL Telah disetujui untuk diuji PEMBIMBING I PEMBIMBING II DR. Zairyanto DR. Abdul Rivai Ras MM,MS.M Si Kontribusi koni..., Sunarjo Slamet Widodo, Pascasarjana UI, 2011 iii HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh : Nama : Drs. Sunarjo Slamet Widodo NPM : 0806449456 Program Studi : Pengkajian Stratejik Ketahanan Nasional Judul Tesis : KONTRIBUSI KONI DALAM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M Si) pada Program Studi Pengkajian Stratejik Ketahanan Nasioanal Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. DEWAN PENGUJI Ketua : Prof.DR.T.Ronny R Nitibaskara.MA (..………………...) Anggota :1. -

Our Badminton Greats
Our Badminton Greats The sport is believed to have been invented around 1873 in England and named after the country estate, Badminton, of the Duke of Beaufort whose guests called it "the Badminton game." The Bath Badminton Club, organized in 1877, developed the first written rules and in 1893, the Badminton Association of England was founded as the first national governing body and the first All-England championship was held in 1899. Popularized by British army officers in India, badminton eventually made its way to Malaya. ccording to school records, the game was first introduced to the V.I. in 1911 by the Headmaster, Mr. B. E. Shaw. Perhaps it was at the V.I. that the first badminton matches were played in Malaya but we cannot be absolutely sure of this. What we can be sure of is that these humble beginnings beside the Klang River and later on Petaling Hill helped spawn some of the great shuttlers who put Malaya and Malaysia on the badminton map of the world. Two gravel courts were initially made by Mr Shaw for the use of the Senior Cambridge classes and another court was added later on for the juniors. In 1921, three other courts became available for the use of the Lower School boys and Chua Chong Kwee was appointed the V.I.’s first badminton captain in 1923. As the sport gained popularity, Mr Shaw’s successor, Mr Richard Sidney, appointed Mr Yap Swee Hin as the badminton master in 1925 and added eight more new gravel courts for inter-house matches. -

Ji Vom Videomarkt • ANGEBOTE Erschienen Ist Jetzt Bei Uwe Nuttelmann, Siil Schläger-Rahmen Besp
Badminton Rundschau Neues .,•• , •• , •• , •• ,.Ji vom Videomarkt • ANGEBOTE Erschienen ist jetzt bei Uwe Nuttelmann, SIil Schläger-Rahmen besp. mit Ashaway Mühlenstraße 27, 2933 Jade 2, DM/Stck. oder Yonex BG 65 Tel. O44 55/13 33 oder Fax O44 55/13 11 . Kennex Carbonpro 747 85- 99 - D ..._ Kennex Boran 900 109:- 119:- iiill1 „ Victor Adventure 149,- 159,- Der erste Teil einer Badminton Lehrfilmreihe, Victor Discovery der eine Hilfe für die Trainingsarbeit (alte Farbe:grün) 99,- 119,- Carlton Powerflow GR 89,- 99,- sein wird. Das Video gibt Einblick in die Schlag Carlton Powerflow BR 139,- 149,- und Lauftechnikn, in die Spielregeln und geht .91 ll Yonex Cab 7 59,- 79,- auf die Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed Yonex Blacken II 49, 69,- • Yonex Graphlex 160 (besp. BG 43) 65,- ein. Der Film ist geeignet für Anfänger und Fort 109,- 129,- geschrittene aller Altersstufen. SII\ ;;;;;;: :,mbo Tasche 59,- Das Lernen wi rd in diesem Film zum spannen Victor Tasche XL-Size 59,- Kennex Badminton-Netz 29,- den und interessanten Prozeß, mit Hilfe einer D .... Kennex Griffband: dick, selbstklebend 3,- Methode, die den wesentlichsten Bestandteil iiill1 ab 24 Stck. 2,50 „ des Freizeitsports zum Inhalt hat: Spielen. Angebote solange Vorrat reicht! In Kürze erscheint ein zweiter Teil, so daß eine SPORT-KL.AUER kontinuierliche Trainingsmöglichkeit mit Hilfe .,. Kessenicher Straße 3 • 5300 Bonn 1 dieser Methode möglich ist. Tel. (02 28) 23 63 57 Montag - Freitag 10.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr Titel des Films: BADMINTON - im Spiel ver .,. Samstag 9.30 - 14.00 Uhr gessen -, Preis: 49,- DM. -

Aus Dem Inhalt
Aus dem Inhalt Berichte 'Seite , - Internationale Turnierergebnisse •' 3 - 1 . Bundesliga ' 4 - 2. Bundesliga, Gruppe West 5 - Oberliga Nord und Süd 6 - German Open 8 - Chiemsee-Cup 9 - Verschiedenes · 10-13 AMTLICHE NACHRICHTEN - Wechsel der Startberechtigung und Schiedsrichtermeldungen 14-15 - Ballzulassung ·.• 15 - Änderungen von Staffeleinteilungen 16 - Turnierauschreibungen und Ranglistenturniere 17-19 - Anschriften- bzw. Namens- korrekturen 19 Titelfoto: Andrea Findhammer vom 1. BV Mülheim. Siegerin beim Chiemsee-Cup 1989. Foto: Jörg Sterling Das größte Deutsche Badminton-Turnier! Kontaktanschrift: Hartmut Kühler Fast 250 Teilnehmer aus über 20 Nationen! Kronprinzenstraße 19 Die weltbesten Badminton-Spieler sind am Start! 4000 Düsseldorf 1 Im Vorjahr kamen über 12 000 Zuschauer! Telefon 0211/309416 Rundfunk, Fernsehen und Presse berichten! Düsseldorf! - Eine Messe für den Badminton-Sport! - Sponsoren! - Nutzen Sie unser Werbeangebot! - Badminton Internationale Turnierergebnisse Rundschau IM Malaysia ( 5. - 9.7.89 in Kuala Lumpur) Vorstand BLV NRW e.V. Ergebnisse jeweils ab Halbfinale Präsident: Herreneinzel: Eddy Kurniawan (INA) - Zhao Jianhua (CHN) 15:18/13:15; Dr. Hans-Richard Lange Joko Suprianto (INA) - Xiong Guobao (CHN) :15/8:15; Celsiusstr. 31 , 5300 Bonn 1 11 Finale: Xiong Guobao 15: / 15:8 Telefon (0228) 25 41 44 11 Vizepräsidenten: Dameneinzel: Han Aiping (CHN) - Huang Ying (CHN) 11 :2/11 :6; Dr. Wolfgang Bochow Lou Yun (TAi) - Huang Hua (CHN) 11 :3/ 11 :7; Albatrosweg 32, 5024 Pulheim Finale: Han Aiping 6:11 / 11 :6/ 11 :7 Telefon (02238) 5 58 95 Herrendoppel: Li Yongbo/Tian Bingyi (CHN) - Joo Bong Park/Moon Soo Kirn (KOR) Horst Boldt 12:15/17:18; Sidek/SDoo (MAL) - Sidek/Sidek (MAL)15:12/15:7/15:9; Mellinghofer Str.