Peta Jawa Tengah
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Influence of Hindu, Buddhist, and Chinese Culture on the Shapes of Gebyog of the Javenese Traditional Houses
Arts and Design Studies www.iiste.org ISSN 2224-6061 (Paper) ISSN 2225-059X (Online) Vol.79, 2019 The Influence of Hindu, Buddhist, and Chinese Culture on the Shapes of Gebyog of the Javenese Traditional Houses Joko Budiwiyanto 1 Dharsono 2 Sri Hastanto 2 Titis S. Pitana 3 Abstract Gebyog is a traditional Javanese house wall made of wood with a particular pattern. The shape of Javanese houses and gebyog develop over periods of culture and government until today. The shapes of gebyog are greatly influenced by various culture, such as Hindu, Buddhist, Islamic, and Chinese. The Hindu and Buddhist influences of are evident in the shapes of the ornaments and their meanings. The Chinese influence through Islamic culture developing in the archipelago is strong, mainly in terms of the gebyog patterns, wood construction techniques, ornaments, and coloring techniques. The nuance has been felt in the era of Majapahit, Demak, Mataram and at present. The use of ganja mayangkara in Javanese houses of the Majapahit era, the use of Chinese-style gunungan ornaments at the entrance to the Sunan Giri tomb, the saka guru construction technique of Demak mosque, the Kudusnese and Jeparanese gebyog motifs, and the shape of the gebyog patangaring of the house. Keywords: Hindu-Buddhist influence, Chinese influence, the shape of gebyog , Javanese house. DOI : 10.7176/ADS/79-09 Publication date: December 31st 2019 I. INTRODUCTION Gebyog , according to the Javanese-Indonesian Dictionary, is generally construed as a wooden wall. In the context of this study, gebyog is a wooden wall in a Javanese house with a particular pattern. -
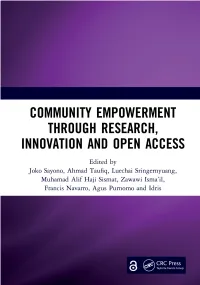
Community Empowerment Through Research, Innovation and Open Access
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH RESEARCH, INNOVATION AND OPEN ACCESS PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (ICHSS 2020), MALANG, INDONESIA, 28 OCTOBER 2020 Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access Edited by Joko Sayono & Ahmad Taufiq Universitas Negeri Malang, Indonesia Luechai Sringernyuang Mahidol University, Thailand Muhamad Alif Haji Sismat Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam Zawawi Isma’il Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia Francis M. Navarro Ateneo De Manila University, Philippines Agus Purnomo & Idris Universitas Negeri Malang, Indonesia CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2021 selection and editorial matter, the Editors; individual chapters, the contributors Typeset by MPS Limited, Chennai, India The Open Access version of this book, available at www.taylorfrancis.com, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license. Although all care is taken to ensure integrity and the quality of this publication and the information herein, no responsibility is assumed by the publishers nor the author for any damage to the property or persons as a result of operation or use of this publication and/or the information contained herein. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record has been requested for this book Published by: CRC Press/Balkema Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands e-mail: [email protected] www.routledge.com – www.taylorandfrancis.com ISBN: 978-1-032-03819-3 (Hbk) ISBN: 978-1-032-03820-9 (Pbk) ISBN: 978-1-003-18920-6 (eBook) DOI: 10.1201/9781003189206 Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access – Sayono et al (Eds) © 2021 Copyright the Editor(s), ISBN 978-1-032-03819-3 Table of contents Preface ix Acknowledgement xi Scientific committee xiii Organizing committee xv Empowering translation students through the use of digital technologies 1 M.A.H. -

Islamic Shari'a Configuration of Buka Luwur Tradition In
Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume 8, Number 1, 2020 DOI: 10.21043/qijis.v8i1.7999 ISLAMIC SHARI’A CONFIGURATION OF BUKA LUWUR TRADITION IN KUDUS Mundakir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia [email protected] Aat Hidayat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia [email protected] Abstract Buka Luwur combines Islamic law teaching and Javanese tradition. As an empirical religious phenomenon, its events have meaning and symbol that overlaps the local community traditions with the adopted Islamic Shari’a implementation. However, formalist and rational religious understandings view Buka Luwur tradition as a bid’ah, with no basis in Islamic law. Using grounded research models and Fazlur Rahman’s double movement theory, this article portraits noumena from a series of Buka Luwur of the Islamic Shari’a implementation in the tradition. The community traditional believes rituals. thatIt describes the tradition the configuration symbolizes love for guardians by hoping for a blessing on work and remembering their struggle in preaching Islamic values. Also, the Buka Luwur tradition’s implementation is a symbol of social solidarity that needs to be appreciated in a plural society. It is a form of harmony and cooperation QIJIS, Vol. 8, No. 1, 2020 201 Mundakir and Aat Hidayat in holding ceremonies and rituals among believers. The results show that Buka Luwur events’ symbolizes a blessing for prayer to be quickly answered, refuse calamity, teach tolerance values preached and practiced by Sunan Kudus, and solidarity in helping one another. the Javanese tradition are found in the election on the 10th ofThe Muharam, configuration as the and top internalizationof the Buka Luwur of Islamic rituals series.law in tradition is found in the teaching of respecting ancestors. -

Tourist Attraction Potential Around the Cemetery of Sunan Kudus Based on Social Media Analysis
Published by : International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) http://www.ijert.org ISSN: 2278-0181 Vol. 8 Issue 07, July-2019 Tourist Attraction Potential Around the Cemetery of Sunan Kudus based on Social Media Analysis Wahyu Septiana Eko Budi Santoso Department of Architecture Department of Urban and Regional Planning Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia Surabaya, Indonesia Haryo Sulistyarso Department of Urban and Regional Planning Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia Abstract— The Old Town of Kudus area has a main tourist Langgardalem Village. Geographically, this old city borders attraction, the Menara Minaret and al-Aqsa Mosques and the Sungai Gelis to the east, Jl. Kiai Haji Asnawi in the west, Jl. Sunan Kudus Tomb, which is one of the destinations of the JH Ahmad Dahlan in the north, Jl. Sunan Kudus in the south community pilgrimage. However, at this time only the Menara and in the central part of this area is divided by Jl. Menara. Minaret and al-Aqsa Mosques and Sunan Kudus Tombs that This Menara Minaret and al-Aqsa Mosques is the center of the have been developed to be the tourist attractions. To identify environment in the area of the Old Town. potential tourist attractions around this area, it can be done by This area of the Old Town of Kudus has a great potential looking at the traces of visitor activity seen from social media. for cultural tourism attraction to be developed because it has This social media use can reveal tourists' attitudes and interests interesting attractions. The Menara Kudus Mosque or Al-Aqsa in a tourist location. -

Region Kabupaten Kecamatan Kelurahan Alamat Agen Agen Id Nama Agen Pic Agen Jaringan Kantor
REGION KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN ALAMAT AGEN AGEN ID NAMA AGEN PIC AGEN JARINGAN_KANTOR NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA DEWANTARA ULEE PULO GAMPONG ULEE PULO 213IB0107P000076 INDI CELL INDIRA MAYA RISWADANA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA SEUNUDDON ALUE CAPLI DUSUN MATANG ARON 213IB0115P000048 DUA PUTRA MANDIRI RATNA JELITA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET DUSUN KRUENG CUT 213IA0115P000031 KIOS NASI IBU BETA SURYANI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000039 KIOS WARKOP PAYONG 1903 HERI DARMANSYAH PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005130 MOCHY CELL ERNI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010046 KIOS ARRAHMAN ARAHMAN KAUNUS PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000026 KIOS ZAIMAN ZAIMAN NURDIN S.PT PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010008 ARITA NEW STEEL MASRI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005091 USAHA HIJRAH SYAIF ANNUR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL MALAHAYATI 213IA0115P005080 USAHA BARU T ISKANDAR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL. LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000004 PUTRA MAMA ANWARDI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH -

Ethnic Architectural Ornaments As Character of Joglo Traditional House
EasyChair Preprint № 4014 Ethnic Architectural Ornaments as Character of Joglo Traditional House Sultan Arya Manarul Hidayat, Aliya Jauhari Hildayanti and Rifqi Cahya Mahendra EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair. August 9, 2020 ETHNIC ARCHITECTURAL ORNAMENTS AS CHARACTER OF JOGLO TRADITIONAL HOUSE Sultan Arya MH, Aliya Jauhari H, Rifqi Cahya M 1 D epartment of Architecture, Universitas Islam Indonesia 1 E mail: [email protected] ABSTRACT: This paper aims to explain and compare the ornamentations of Joglo traditional house along with the function of the Joglo houses itself. The background of this paper is to give knowledge and consciousness about Joglo traditional house ornamentations which we often ignore. The discussion using the comparison tables showing the ornamentations of joglo houses precedents, categorized as a traditional and modern joglo house. The research findings produced an idea of how and why the ornamentation is used in either one or both of the precedents that have already been chosen. And the conclusion started with the reason for the use of ornamentation in Joglo traditional house and Joglo house with a new adaptation of the modern building. Keywords: Joglo, ornamentation, traditional, modern INTRODUCTION The physical building always marks the level of development of human life so that each building is loaded with intrinsic values about local wisdom (Ahimsa-Putra, 2008: 7). From time immemorial we can find many relics such as inscriptions and artifacts which can reconstruct the mentality of life in humans at that time as well as the physical buildings that show relics also represent the human life that built it. -

Mempertahankan Tradisi: Studi Budaya Di Kampung Kauman Menara Kudus Maintaining Tradition: a Cultural Study of Kudus Kauman Village
Mempertahankan Tradisi…(Moh. Rosyid) 297 MEMPERTAHANKAN TRADISI: STUDI BUDAYA DI KAMPUNG KAUMAN MENARA KUDUS MAINTAINING TRADITION: A CULTURAL STUDY OF KUDUS KAUMAN VILLAGE Moh Rosyid Institut Agama Islam Negeri Kudus email: [email protected] Naskah Diterima:21 Maret 2019 Naskah Direvisi:18 Juni 2019 Naskah Disetujui: 28 Juni 2019 DOI: 10.30959/patanjala.v11i2.516 Abstrak Artikel ini memotret tradisi di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Kampung Kauman Menara yang terdiri hanya 3 RT dan 1 RW. Data penduduk Desember 2017 ada 413 jiwa, 127 KK. Data riset ini diperoleh dengan wawancara dan observasi, dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tradisi khas dilestarikan berupa khoul (perayaan hari wafat) Sunan Kudus tiap 10 Asyura oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) dan warga Kauman dan temu rutin berkala antarwarga. Tata letak kampung padat hunian dan penduduk, bangunan rumah rata-rata ditembok tinggi. Kampung ini tidak dijamah bangunan kolonial Belanda sehingga masuk kategori kampung kuno Islam dengan kekhasan adanya Masjid al-Aqsha Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Warganya memiliki kegiatan rutin dalam forum temu warga dalam ikatan kebersamaan berdasarkan usia dan jenis kegiatan yang menu acaranya islami. Warga mempertahankan pantangan terkait penghormatan pada Sunan Kudus. Kata kunci: Kauman, desa, tradisi islami. Abstract This article portrays Kauman Village of Kudus. The village is the smallest in Kudus city consisting of three RT (neighborhood units) and one RW (community units). The population is 413 people and 127 families. This paper is based on interviews and observations and applying qualitative approach. The special tradition is preserved in the form of khoul (commemoration of Sunan Kudus) every Muharram 10th (Ashura) by the Masjid Menara and Makam Sunan Kudus Foundation (YM3SK) and residents of Kauman. -

Traditional Architecture of Kalang, Limasap (ETHNOGRAPHIC APPROACH)
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 04, APRIL 2020 ISSN 2277-8616 Traditional Architecture Of Kalang, Limasap (ETHNOGRAPHIC APPROACH) Prabani Setio Hastorahmanto, Sugiono Soetomo, Agung Budi Sardjono Abstract : Javanese traditional architecture has several forms that can be specifically identified from the shape of the roof. This form symbolizes the strata of its owner and has the function of following the traditional activities and domestic activities of its inhabitants. Research on Javanese-Indonesian homes in general has been widely carried out, but specifically for various sub-ethnic groups is still relatively limited, including for the Kalang sub-ethnic. namely a group of people who still adhere to the Kalang tradition which is an acculturation of ancient Javanese culture with Hindu-India. Through ethnographic methods, the physical meaning of the form of the Limasap roof is found, namely five sap (parts), traditional contradictory patterns of the kiwo-tengen (left-right) and the obong (burn) tradition which are still preserved and only carried out in Kalang Village. This research contributes to the preservation of ethnic or sub-ethnic groups in traditional settlements and additional knowledge about traditional Javanese houses in Indonesia. Keywords: Limasap Roof, Pole Tungko, Kiwo Room, Mantenan Room ———————————————————— 1. INTRODUCTION Javanese traditional architecture is a treasure that can be The tradition is known as the Obong tradition. A tradition learned and has a certain meaning for Javanese society. which is a ritual to take the spirits/souls of people who have The meaning shows that Javanese people have a culture passed away to Nirvana. Based on the results of the study that is realized in the form of a house. -

Rumah Joglo Sebagai Identitas Visual Konsep Bangunan Kuliner Kontemporer
Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Media Baru Vol. 1 No.2. Februari 2019 Rumah Joglo Sebagai Identitas Visual Konsep Bangunan Kuliner Kontemporer Christian Moniaga; Alvina Gunawan Arsitekturl, Fakultas Arsitektur dan Desain, Unika Soegijapranata Semarang Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235 [email protected] Abstrak Rumah Joglo merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang terdapat di Jawa Tengah. Rumah Joglo mempunyai kerangka bangunan utama yang terdiri dari soko guru berupa empat tiang utama penyangga serta tumpang sari yang berupa susunan balok yang disangga soko guru. Rumah Joglo yang pada awalnya hanya dimiliki oleh kalangan terpandang saja, seiring perkembangan jaman Joglo dapat dimiliki oleh siapapun yang ingin membangun Rumah Joglo. Tak heran banyak Joglo yang dibangun dengan fungsi yang berbeda sehingga berdampak pada susunan ruang Joglo. Dengan dasar pengetahuan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkapkan sejauh mana citra visual Rumah Joglo mampu mempengaruhi konsep identitas sebuah bangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi literatur serta dilakukannya sebuah observasi. Hasil identifikasi karakteristik Rumah Joglo menunjukkan bahwa Rumah Joglo merupakan perwujudan nilai kebudayaan lokal yang melahirkan seni arsitektur khas Jawa Tengah yang menarik. Kata kunci: Rumah Joglo, Identitas Visual, Konsep Bangunan Abstract Joglo House is one of the Indonesian cultural heritages found in Central Java. The Joglo house has a main building framework consisting of Soko Guru in the form of four main pillars supporting and intercropping in the form of blocks arranged by Soko Guru. Joglo house which was originally only owned by prominent people, along with the development of the Joglo era can be owned by anyone who wants to build a Joglo House. -

Viewing the Cultural Trace of the Mosque Building in the Cirebon Sultanate
Research on Humanities and Social Sciences www.iiste.org ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484 (Online) Vol.8, No.14, 2018 Viewing the Cultural Trace of the Mosque Building in the Cirebon Sultanate Nyai Kartika 1* Yasraf Amir Piliang 2 Imam Santosa 2 Reiza D. Dienaputra 3 1. Doctoral student on Art and Design Studies, Faculty of Art and Design Bandung Institute of Technology 2. Faculty of Art and Design Bandung Institute of Technology 3. Faculty of Cultural Sciences, Padjadjaran University Abstract Indonesian nation has a long historical record, not only about the physical resistance in the struggle for Indonesian independence, but also the culture of its dynamic society and continues to evolve with the changing times. The history of the past brings Indonesian culture into contact with and against the outside culture which then affects various aspects of people's lives. Acculturation, assimilation, and even shock culture also coloring the cultural changes caused by external cultural influences. Included in the field of building architecture, one of which is building a mosque located in the Sultanate of Cirebon, which will provide many interpretations of cultural forms through visual media. The emergence of ports in Cirebon become entrance of various cultures in Cirebon such as Arab and Chinese, in addition to Hindu culture, Buddhism which is already much more rooted in public life. Therefore, studying the development of culture through building a mosque becomes an interesting thing to do.The method used in this study is the historical method. This method uses four stages of work namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. -

Pendhapa Natabratan: Symbolic Meaning of the Javanese House in Demak, Indonesia
International Journal of Architecture, Arts and Applications 2020; 6(3): 39-46 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijaaa doi: 10.11648/j.ijaaa.20200603.12 ISSN: 2472-1107 (Print); ISSN: 2472-1131 (Online) Pendhapa Natabratan: Symbolic Meaning of the Javanese House in Demak, Indonesia Ashadi Ashadi Department of Architecture, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia Email address: To cite this article: Ashadi Ashadi. Pendhapa Natabratan: Symbolic Meaning of the Javanese House in Demak, Indonesia. International Journal of Architecture, Arts and Applications. Vol. 6, No. 3, 2020, pp. 39-46. doi: 10.11648/j.ijaaa.20200603.12 Received: June 18, 2020; Accepted: June 30, 2020; Published: July 17, 2020 Abstract: Pendhapa Natabratan At Kadilangu, Demak, Central Java, Indonesia was one of the Javanese noble houses which had very strong Javanese symbols. Javanese house contained symbolic meaning, socio-cultural values as well as architectural value, together with a unique structure that was adapted to the environmental and cultural conditions. Javanese houses, as a result of the traditional culture from the Javanese ethnic, had become Javanese cultural heritage that could not be changed. Javenese culture was heavily influenced by the noble power system. This study aimed to reveal the symbolic meaning of the Pendhapa Natabratan, especially those related to the Javanese traditional ceremonies held in this place, namely the Garebeg Besar and Ruwatan Sukerta. The study used an analytical framework that relied on the process of symbolic meaning in the relation of form-function-meaning within the framework of Javanese culture. The result of study showed that Pendhapa Natabratan had a domestic and cultural function. -

Region Kabupaten Kecamatan Kelurahan Alamat Agen Agen Id Nama Agen Pic Agen Jaringan Kantor Jabo Inner Jakarta Barat Cengkareng
REGION KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN ALAMAT AGEN AGEN ID NAMA AGEN PIC AGEN JARINGAN KANTOR JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. MELATI IV NO. 14 RT/RW 010/001 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0116P000002 WARUNG MAKAN DEVI DEVI WIDIASTUTI BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. SLANTAN RT/RW 010/001 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0116P000005 PRIMA ABADI LAUNDRY YUNIARTI KURNIAWATI BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. CC I NO. 18 A RT/RW 005/004 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0110P000056 KETUA RT IRFAIH IRFA'IH BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. RAWA BENGKEL NO. 19 RT/RW 005/007 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0109P000059 GALAXY CELL RUDY SANTOSO BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. UTAMA RAYA NO. 47 RT/RW 009/004 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0109P000061 RAFI CELL IRWAN SUSILO BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. KAMAL RAYA FLAMBOYAN NO. 12 RT/RW 002/008 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0116P000087 NEW HARPENS CELL SUHARDI BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT JL. JAYA RAYA RT/RW 001/009 NO. 52 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0116P000093 TOKO SRI WIJAYA ABDUL RAHMAN BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT RUSUN DINAS KEBERSIHAN RT/RW 014/005 KEL. CENGKARENG BARAT KEC. CENGKARENG 213BB0109P000060 AHMAD YANI AHMAD YANI BTPN PURNABAKTI DAAN MOGOT JABO INNER JAKARTA BARAT CENGKARENG CENGKARENG BARAT RUSUN FLAMBOYAN ELT RT/RW 014/010 KEL.