(Qadariyah) Oleh
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Islamic Traditions of Cirebon
the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims A. G. Muhaimin Department of Anthropology Division of Society and Environment Research School of Pacific and Asian Studies July 1995 Published by ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia Email: [email protected] Web: http://epress.anu.edu.au National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Muhaimin, Abdul Ghoffir. The Islamic traditions of Cirebon : ibadat and adat among Javanese muslims. Bibliography. ISBN 1 920942 30 0 (pbk.) ISBN 1 920942 31 9 (online) 1. Islam - Indonesia - Cirebon - Rituals. 2. Muslims - Indonesia - Cirebon. 3. Rites and ceremonies - Indonesia - Cirebon. I. Title. 297.5095982 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher. Cover design by Teresa Prowse Printed by University Printing Services, ANU This edition © 2006 ANU E Press the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims Islam in Southeast Asia Series Theses at The Australian National University are assessed by external examiners and students are expected to take into account the advice of their examiners before they submit to the University Library the final versions of their theses. For this series, this final version of the thesis has been used as the basis for publication, taking into account other changes that the author may have decided to undertake. In some cases, a few minor editorial revisions have made to the work. The acknowledgements in each of these publications provide information on the supervisors of the thesis and those who contributed to its development. -
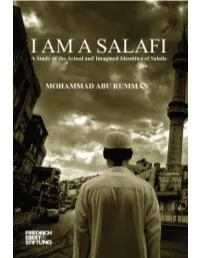
I Am a Salafi : a Study of the Actual and Imagined Identities of Salafis
The Hashemite Kingdom Jordan The Deposit Number at The National Library (2014/5/2464) 251.541 Mohammad Abu Rumman I Am A Salafi A Study of The Actual And Imagined Identities of Salafis / by Mohammad Abu Rumman Amman:Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 Deposit No.:2014/5/2464 Descriptors://Islamic Groups//Islamic Movement Published in 2014 by Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq FES Jordan & Iraq P.O. Box 941876 Amman 11194 Jordan Email: [email protected] Website: www.fes-jordan.org Not for sale © FES Jordan & Iraq All rights reserved. No part of this publication may be reprinted, reproduced or utilized in any form or by any means without prior written permission from the publishers. The views and opinions expressed in this publication are solely those of the original author. They do not necessarily represent those of the Friedrich-Ebert Stiftung or the editor. Translation: Dr. Hassan Barari Editing: Amy Henderson Cover: YADONIA Group Printing: Economic Printing Press ISBN: 978-9957-484-41-5 2nd Edition 2017 2 I AM A SALAFI A Study of the Actual and Imagined Identities of Salafis by Mohammad Abu Rumman 3 4 Dedication To my parents Hoping that this modest endeavor will be a reward for your efforts and dedication 5 Table of Contents DEDICATION ........................................................................................................ 5 FOREWORD .......................................................................................................... 8 ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................ -

Civilisations from East to West
Civilisations from East to West Kinga Dévényi (ed.) Civilisations from East to West Corvinus University of Budapest Department of International Relations Budapest, 2020 Editor: Kinga Dévényi Tartalomjegyzék Szerkesztette: Authors: LászlóDévényi Csicsmann Kinga (Introduction) Kinga Dévényi (Islam) Szerzők: Csicsmann László (Bevezető) Előszó �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Mária DévényiIldikó Farkas Kinga (Japan) (Iszlám) (Japán) BernadettFarkas Lehoczki Mária (Latin Ildikó America) Lehoczki Bernadett (Latin-Amerika) Tamás Matura (China) Matura Tamás (Kína) 1. Bevezetés a regionális–civilizációs tanulmányokba: Az új világrend és a ZsuzsannaRenner Renner Zsuzsanna (India) (India) paradigmák összecsapása – Csicsmann László������������������������������������������� 15 Sz. Bíró Zoltán (Oroszország) Zoltán Sz. Bíró (Russia) 1.1. Bevezetés .............................................................................................. 15 Szombathy Zoltán (Afrika) 1.2. Az új világrend és a globalizáció jellegzetességei ................................ 16 ZoltánZsinka Szombathy László (Africa) (Nyugat-Európa, Észak-Amerika) 1.3. Az új világrend vetélkedő paradigmái ....................................................... 23 LászlóZsom Zsinka Dóra (Western (Judaizmus) Europe, North America) 1.4. Civilizáció és kultúra fogalma(k) és értelmezése(k) .................................. 27 ....................................................... 31 Dóra Zsom (Judaism) 1.5. -

Philosophy 103
Philosophy 103 PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF AbU MANSUR AL-MATURIDI’S TEACHING AND ITS INFLUENCE ON THE SPIRITUAL KNOWLEDGE OF KAZAKHS Karatyshkanova K.R., Myrzabekov M.M. Kh.A. Yasawi International Kazakh-Turkish University, Turkistan, e-mail: [email protected], [email protected] The article outlines the prerequisites for the formation of religious views of the great scientist Abu Mansur al-Maturidi and the role of the environment, the time and space where he lived, and where various religions and cultures coexisted. Special attention is paid to the comparative analysis of the text of Abu Mansur al-Maturidi’s book “Kitab al-Tawhid” and the dogmas of such religions as Zoroastrism, Manichaeism, Christianity, Judaism, Buddhism, Tengrianism. The characteristics of various debates and ideological discussions aimed at forming the principles of the teachings of Abu Mansur al-Maturidi are given. It is claimed that the source of the worldview of Kazakh thinkers is the teaching of Abu Mansur al-Maturidi, who was able to synthesize issues of religion and morality. Keywords: ideological environment, murgia, scholars of Hanafi, Abu Mansur al-Maturidi, morality, spiritual knowledge, madrasah, Kazakh thinkers Abu Mansur al-Maturidi, popularly known great importance to these religions by devot- as “Imam-l-Mutakallimin Alamu-l-Huda”, ing a separate chapter to them, analyzing their “Raisu-s-Sunnah”, “Musakhihu Ahadi-l-Mus- creeds and dogmas. limin”, “Imamu Zahid”, “Raisu Aһli-s-Sunna”, By the way, even supporters of the dualism “Mahdiu-l-Umma” [1, s. 94] is a great theolo- of Zoroastrianism and Manichaeism left a deep gian, born in the city of Maturid, near Samar- impression on the territory Maverannahr. -

Pemikiran Qadariyah Dan Jabariyah Yang Bersandar Dibalik Legitimasi Al-Qur’An
INTEGRASI ALIRAN PEMIKIRAN KEISLAMAN: PEMIKIRAN QADARIYAH DAN JABARIYAH YANG BERSANDAR DIBALIK LEGITIMASI AL-QUR’AN Suhaimi Universitas Madura Pamekasan Email: [email protected] Abstrak: Artikel ini sengaja penulis angkat dalam rangka untuk memperdalam khasanah keilmuan yang berkaitan dengan persoalan aliran- aliran pemikiran yang pernah berkembang pada masa pasca-wafatnya Rasulullah saw., khususnya Qadariyah dan Jabariyah. Disamping itu penulis juga tertarik terhadap pemikiran kedua aliran tersebut yang saling bertentangan secara ekstrim. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan melakukan perbuatan, tidak ada sangkut- pautnya dengan kehendak Allah. Namun justru Jabariyah berpendapat lain, bahwa manusia tidak mempunyai daya dan kehendak apapun, semuanya karena atas kehendak Allah. Oleh karenanya dua pendapat yang berseberangan ini perlu adanya integrasi pemikiran agar dapat ditemukan titik temu keduanya. Adapun metode yang dipakai dalam artikel ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan sejarah pemikiran Qadariyah dan Jabariyah yang kemudian dilakukan semacam interpretasi baik secara objektif maupun subjektif. Kata kunci: Qadariyah, Jabariyah dan Integrasi Pemikiran. Abstract: This article is deliberately adopted by the author in order to deepen the scientific treasures related to the problems of thought of schools that have developed in the post-Prophet Muhammad era, especially Qadariyah and Jabariyah. Besides that, the writer is also interested in the thoughts of the two schools that are in extreme conflict. The Qadariyah sect argues that humans have the freedom to desire and do deeds, nothing to do with God's will. But instead Jabariyah argues differently, that humans do not have any power and will, all because of God's will. Therefore, these two opposing opinions need integration of ideas so that they can be found at the meeting point. -

Bektashi Order - Wikipedia, the Free Encyclopedia Personal Tools Create Account Log In
Bektashi Order - Wikipedia, the free encyclopedia Personal tools Create account Log in Namespaces Views Article Read Bektashi OrderTalk Edit From Wikipedia, the freeVariants encyclopedia View history Main page More TheContents Bektashi Order (Turkish: Bektaşi Tarikatı), or the ideology of Bektashism (Turkish: Bektaşilik), is a dervish order (tariqat) named after the 13th century Persian[1][2][3][4] Order of Bektashi dervishes AleviFeatured Wali content (saint) Haji Bektash Veli, but founded by Balim Sultan.[5] The order is mainly found throughout Anatolia and the Balkans, and was particularly strong in Albania, Search BulgariaCurrent events, and among Ottoman-era Greek Muslims from the regions of Epirus, Crete and Greek Macedonia. However, the Bektashi order does not seem to have attracted quite as BektaşiSearch Tarikatı manyRandom adherents article from among Bosnian Muslims, who tended to favor more mainstream Sunni orders such as the Naqshbandiyya and Qadiriyya. InDonate addition to Wikipedia to the spiritual teachings of Haji Bektash Veli, the Bektashi order was later significantly influenced during its formative period by the Hurufis (in the early 15th century),Wikipedia storethe Qalandariyya stream of Sufism, and to varying degrees the Shia beliefs circulating in Anatolia during the 14th to 16th centuries. The mystical practices and rituals of theInteraction Bektashi order were systematized and structured by Balım Sultan in the 16th century after which many of the order's distinct practices and beliefs took shape. A largeHelp number of academics consider Bektashism to have fused a number of Shia and Sufi concepts, although the order contains rituals and doctrines that are distinct unto itself.About Throughout Wikipedia its history Bektashis have always had wide appeal and influence among both the Ottoman intellectual elite as well as the peasantry. -

Demazhabization of Islam, Divinity Economy and Narratives of Conflict of the Tablighi Followers in Samarinda East Kalimantan
AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies (BJRS) Volume 4 Number 2 December 2015 DEMAZHABIZATION OF ISLAM, DIVINITY ECONOMY AND NARRATIVES OF CONFLICT OF THE TABLIGHI FOLLOWERS IN SAMARINDA EAST KALIMANTAN Saipul Hamdi Samarinda State Polytechnic of Ugriculture Abstract Tablighi Jamaat is one of the world’s largest and most successful transnational Is- lamic movements with established branches built on the business of dakwa (pros- elytization) in approximately 180 countries. Tablighi’s strong commitment to a style of dakwa based on their reformist attitude and ő exible practice of mazhab (schools of thought) through a process of ‘demazhabizasi’ (demahzhabization), has attracted interest from a range of people. Tablighi guarantees the freedom for its members to embrace their choice of mazhab, and prefers its proselytizers to follow the mazhab of the communities in which they preach in order to avoid religious debates. is article aims to understand the concept of ‘demazhabisasi’ that has developed in Tablihgi and the ways in which Tablighi members work to overcome and prevent conő ict due to the diff erent understandings of each mazhab. e material sacriŇ ces Tablighi proselytizers make together with their reliance on and submission to God for their economy, has led this research to examine the concept of a ‘divine economy’ that has developed in Tablighi com- munities. Yet, behind Tablighi’s apparent success, conő ict has emerged internally among Tablighi members, as well as externally among locals in the communi- ties in which Tablighi proselytizers work. is research uses an ethnographic ap- proach to explore narratives of conő ict that have emerged as a result of Tablighi proselytizing practices in Samarinda, East Kalimantan. -

Jihadist Website Posts Al-Libi's 'Guidance on the Ruling of the Muslim Spy' GMP20090708342001 Jihadist Websites -- OSC Summary in Arabic 30 Jun 09
UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY This product may contain copyrighted material; authorized use is for national security purposes of the United States Government only. Any reproduction, dissemination, or use is subject to the OSC usage policy and the original copyright. Show Full Version Jihadist Website Posts Al-Libi's 'Guidance on the Ruling of the Muslim Spy' GMP20090708342001 Jihadist Websites -- OSC Summary in Arabic 30 Jun 09 [Corrected version: removed multiple hyperlinks from text] Terrorism: Jihadist Website Posts Al-Libi's 'Guidance on the Ruling of the Muslim Spy' On 30 June, "Murasil al-Fajr" posted to the Islamic Al-Fallujah Forums website several links to a 149-page book entitled "Guidance on the Ruling of the Muslim Spy." The book discusses in detail the religious rulings concerning Muslim spies working for "the vicious Crusader campaign that is launched by the United States and its allies against Muslims and Islamic countries." The book contains an introduction by Ayman al-Zawahiri, Al-Qa'ida's second in command, who emphasizes the importance of the topic of the book and praises Al-Libi's "valuable, serious, scientific, and practical research on the Islamic judgment on spying." In the book, Al- Libi discusses in extensive detail all religious rulings concerning Muslim spies, emphasizing that they are "apostates" and therefore should be killed as they disclose "the shortcomings of Muslims." He also warns of their danger, saying: "One single piece of information transmitted to them, by one of their spies, is able to exasperate spirits, honor, and possessions in a way that thousands of their mobilized soldiers cannot do." The book was released and published by the Al-Fajr Media Center. -

Ulu Al Amr & Authority
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 10-2014 Ulu Al Amr & Authority: The Central Pillars of Sunni Political Thought Hisseine Faradj Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/347 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Ulu Al Amr & Authority: The Central Pillars of Sunni Political Thought by Hisseine Faradj A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Political Science in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy, The City University of New York 2014 © 2014 (year degree awarded) Hisseine Faradj All Rights Reserved iii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Political Science in satisfaction of the dissertation requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Susan Buck-Morss ________________ ________________________________ Date Chair of Examining Committee Alyson Cole ________________ ________________________________ Date Acting Executive Officer Jillian Schwedler ________________________________ John R. Wallach ________________________________ Supervisory Committee THE GRADUAE CENTER THE CITY UNIVERSITY OF NEW YOR iv Abstract ULU AL AMR & AUTHORITY: THE CENTRAL PILLARS OF SUNNI POLITICAL THOUGHT by Hisseine Faradj Advisor: Susan Buck-Morss This dissertation evaluates the political history of Islam through the prism of the Sunni conception of authority. It finds an historical red thread that explains the legal and political evolution of different types of Islamic government that have, instead of a European-type sovereign, the Ulu Al Amr (those in authority). -

The Contribution of Harun Nasution's Thoughts in Islamic Reform In
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 8, Ver. II (August. 2017) PP 66-74 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org The Contribution of Harun Nasution’s Thoughts in Islamic Reform in Indonesia *Adenan1,2, Prof. Ilhamuddin2, Prof. Amroeni Drajat2 1Ph.D Student at State Islamic University of North Sumatra (UINSU), Medan, Indonesia 2Lecturer at State Islamic University of North Sumatra (UINSU), Medan, Indonesia Corresponding Author: Adenan ABSTRACT: Harun Nasution is commonly known as a very rational and liberal Muslim intellectual. In his lecture, Harun always insisted that Indonesian Muslims should think rationally. He also suggests that we should imitate the Shi'ah who has thought rationally. Because of his thinking, many people refuse him, but there are some appreciate him. According to him, the qat'iyah teachings of Islam are not many, as God exists and the one, the prohibition of riba and eating pork as well as khamr. Meanwhile the rests are verses that are still zanny dilalah. Harun Nasution is a theologian, philosopher, reformer, Sufi expert, political expert and actualizes the today international issues. This is proved by the scientific works produced in accordance with the field. According to him Muslims in Indonesia need to improve their quality through the way of rational thinking. He states that Asy’ariyah that tends to Jabariyyah has flourished in Indonesia as one of the causes of stagnant dynamics of Islamic thought. For that reason, Harun gives a solution in the form of rebuilding the rational thought of Mu'tazilah so that Muslims in Indonesia can advance in the modern era. -

Contribution of Al-Ash^Arf to Islamic Thought His Influence on the Later
Contribution of al-Ash^arf to Islamic Thought & His Influence on the Later ^Ilm al-Kal9m ABSTRACT THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF IN PHILOSOPHY BY ATAUR RAHMAN Under the Supervision of DR. TASADDUQ HUSAIN Reader (Muslim Philosophy) DEPARTMENT OF PHILOSOPHY ALiGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH (INDIA) December 2002 Abstract c/n ine jCame of^ffan ABSTRACT This is the abstract of my thesis entitled 'Contribution of al- Ash'ari to Islamic Thought and His Influence on the later Ilm al- Kalam'. I have mentioned in my thesis, in its preface, a short account of Asha'ri's biography. In his biographic account I have mentioned about his life and works and how he converted to his own school of thought, named after his name, from M'utazilism. Abu Ali al-Jubbai was his teacher and he acquired education from him and remained with him for about forty years of his life. Abu Ali al-Jubbai, being a M'utazilite, stressed more on reason than revelation. Asha'ri also had followed his path, but he was not satisfied. He again and again put his perplexity and anxiety before him, especially when he was defeated by his opponents in any assembly discussion (munazara). He, ultimately, decided to abandon M'utazilism, or the attitude of giving more importance to reason Abstract than revelation. God helped al-Ash'ari, as He always does, by sending His Prophet in his dream who guided him to follow the path of righteousness. Ultimately Ash'ari decided to defend orthodoxy. He posed the question of three brothers (for details see the thesis), where he wanted to justify that reason is not enough to solve every problem. -

Akal, Wahyu, Dan Kasb Manusia Menurut Jabariyahdan
AKAL, WAHYU, DAN KASB MANUSIA MENURUT JABARIYAH DAN QADARIYAH Edi Sumanto Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Bengkulu Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email: [email protected] Abstract: Reason, Revelation, And Human Efforts According to Jabarites And Qadarites. This article describes the views of Qadarites and Jabarites about the revelation, reason, and human efforts. The method used is based on a literature library from books, magazines and articles related. The study concluded: first, for Jabarites, reasoning has no meaning, because reasoning is of no use to humans, they are more dominant subject to revelation or the provision of God in their every activities, so human just only accept anything that has been given by The Creator. While according to Qadarites, Reasoning is to proportionate the provisions that God has made for man, to contribute to the act of doing, good or bad. In connection with the concept of revelation, for Jabarites that the revelation is a source of important and basic to those that must be followed, because the verses they are using is a verse to support the argument they use. While revelation in according to Qadarites is considered as to proportionate their opinion, because God disposes all human actions, but humans have a stake in it in order to try and select it.Finally, in Human efforts, for Jabarites that no efforts, because everything he does has been determined by God. There is no human power to do in doing something. however, according to Qadarites that human effort is depend on human beings themselves and the result depends according what he has done without any intervention from God.