BANTENESIA-Jadi.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Islamic Political Parties and Democracy: a Comparative Study of Pks in Indonesia and Pas in Malaysia (1998-2005)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ScholarBank@NUS ISLAMIC POLITICAL PARTIES AND DEMOCRACY: A COMPARATIVE STUDY OF PKS IN INDONESIA AND PAS IN MALAYSIA (1998-2005) AHMAD ALI NURDIN S.Ag, (UIN), GradDipIslamicStud, MA (Hons) (UNE), MA (NUS) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY SOUTHEAST ASIAN STUDIES PROGRAM NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2009 Acknowledgements This work is the product of years of questioning, excitement, frustration, and above all enthusiasm. Thanks are due to the many people I have had the good fortune to interact with both professionally and in my personal life. While the responsibility for the views expressed in this work rests solely with me, I owe a great debt of gratitude to many people and institutions. First, I would like to express my gratitude to Dr. Priyambudi Sulistiyanto, who was my principal supervisor before he transferred to Flinders University in Australia. He has inspired my research on Islamic political parties in Southeast Asia since the beginning of my studies at NUS. After he left Singapore he patiently continued to give me advice and to guide me in finishing my thesis. Thanks go to him for his insightful comments and frequent words of encouragement. After the departure of Dr. Priyambudi, Prof. Reynaldo C. Ileto, who was a member of my thesis committee from the start of my doctoral studies in NUS, kindly agreed to take over the task of supervision. He has been instrumental in the development of my academic career because of his intellectual stimulation and advice throughout. -

Daya Tarik Baru Untuk Mahasiswa Diklasifikasikan Atas Jenisnyanya
SENIN, 26 APRIL 2021 || SENIN, 14 RAMADHAN 1442 H EDISI 567 TAHUN || Rp. 4500 Jakarta, Khazanah-- Dalam mengatakan kepingan dan bagian yang luar atau terjadi keretakan di peluncur pelumasan naik-turunnya periskop Mimbar Ramadhan keterangan kepada media pada Sabtu diyakini bagian atau komponen kapal torpedo." kapal selam. Kemudian alas yang (24/04), Kepala Staf TNI Angkatan selam "tidak akan terangkat ke luar Barang-barang yang ditemukan biasanya dipakai ABK untuk salat. Mengenal 8 Kategori Laut, Laksamana Yudo Margono, kapal apabila tidak ada tekanan dari antara lain, botol oranye berisi grease Menurut Laksamana Yudo Masjid di Indonesia BACA HAL-7 Padang, Khazanah – Sepintas kita lihat PEKAN IMUNISASI DUNIA FK UNP DI BUKITTINGGI DAN PADANG masjid sama saja, sebagai sebuah bangunan untuk beribadah bagi umat Islam. Tapi Pemprov ternyata di Indonesia masjid dapat Daya Tarik Baru untuk Mahasiswa diklasifikasikan atas jenisnyanya. Sumbar Padang, Khazanah – Bukittinggi BACA HAL-7 dan Padang akan memiliki daya tarik Syiar Islam Prakarsai baru lagi bagi mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air untuk menuntut ilmu karena di dua kota itu Universitas SUCI, MENYUCIKAN Vaksin Gratis Negeri Padang akan menyenggarakan program studi kedokteran olahraga DAN SOK SUCI untuk Lansia Fakultas Kedokteran yang baru saja Oleh: Prof. Duski Samad dibuka. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) “Pada kedua kota ini kita sudah Provinsi Sumatera Barat siapkan sejak 2018, sejalan dengan pendirian Fakultas Kedokteran,” kata Judul di atas dimaksudkan untuk batu Rektor UNP Prof. Ganefri hari Sabtu ujian dan parameter bagi pengukuran di Padang. kualitas jiwa hamba yang sedang tekun Pendirian prodi kedokteran UNP berjuang mendapatkan jiwa yang suci di sebenarnya sudah ada MoU dengan bulan suci Ramadhan dengan ibadah yang Universitas Indonesia dan Universitas jumlahnya meningkat dibanding hari-hari Andalas yang bertujuan membina dan biasa. -

DAFTAR PUSTAKA Akdon, Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik Untuk Manajemen Pendidikan), ALFABETA
DAFTAR PUSTAKA Akdon, Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategik Untuk Manajemen Pendidikan), ALFABETA, Bandung, 2006. Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Claudia Vanesha Pitoy, Altje Tumbel dan Maria Tielung, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03, Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, TBK Manado), 2016. Edi Aquino dan Ratih Indriyani, Jurnal: “Evaluasi Strategi Bersaing pada PT. Triyuda Perkasa”, Vol. 2, No. 1, pdf, diakses pada tanggal 17 April 2018, 08:24 Etika Sabariah, Manajemen Strategis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016. Florencia Felia Sugiarto, AGORA Vol. 4, No. 2, Analisis Strategi Bersaing PT. Surya Cipta Mandiri, 2016. Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep, Terj. Dono Sunardi, Salemba Empat, Jakarta, 2010. Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Strategis, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2012. Kevin Ryan Prathama, AGORA Vol. 1, No. 3, Analisis Strategi Bersaing PT. Mitra Agro Lestari Bersama, 2013. Michael A.Hitt, dkk, Manajemen Strategis : Daya Saing dan Globalisasi, Konsep, Salemba Empat, Jakarta, 2001. Michael Porter, Strategi Bersaing (Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing), Terj. Agus Maulana, Erlangga, Jakarta, 1980. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000. Muhammad Husni Mubarok, Strategi Korporat & Persaingan Bisnis dalam Meraih Keunggullan Kompetitif, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009. Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013. Rahardjo Susilo dan Gudnanto, Pemahaman Individu : Teknik Non Tes, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2012. Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2009. Rusadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001. Sapmaya Wulan dan Widyaningsih, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.2 No.1, Analisis Strategi Bersaing Penjualan Sepeda Motor Kawasaki PT. -

Monitoring Berita Pandemi Covid-19
Monitoring Berita Pandemi Covid-19 Pantauan Media Massa 18-20 Mei 2020 Metode & Sumber Data Intelligence Media Management 01 Laporan ini disusun dengan bantuan sistem Intelligence Media Management (IMM), yang memuat berita dari 6.296 media online, termasuk media luar negeri. IMM menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kata dan membantu analisis sentimen. Penyaringan Bahasa dan Kata 02 Seluruh berita yang masuk ke sistem IMM disaring berdasarkan bahasa, yakni bahasa Indonesia, dan kata, yakni variasi kata atau penyebutan Covid-19 oleh wartawan, seperti Virus Corona, Virus Korona, Coronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19, dll. 79.351 Berita 03 Dari seluruh berita yang tersaring, terdapat 79.351 berita selama 18-20 Mei 2020. Laporan ini disusun berdasarkan sejumlah berita tersebut, dibantu dengan fitur-fitur dalam sistem IMM. Ragam Berita Nasional Kasus Terbaru, Pelaksanaan Tes Cepat Pengajuan, Penerapan dan Wacana dan Uji Swab Covid-19 Relaksasi Status PSBB Pelaksanaan dan Masalah Penyaluran Penerapan dan Pelanggaran Protokol Bantuan Sosial Kesehatan di Pasar dan Pertokoan Kebijakan Pelaksanaan Salat dan Kontroversi dan Wacana Penerapan Perayaan Idul Fitri di Sejumlah Daerah Skenario “The New Normal” Kepulangan WNI dan Pemeriksaan Pelaksanaan dan Penundaan Penumpang di Bandara dan Pembayaran THR saat Pandemi Pelabuhan Langkah Pemerintah Pusat SIAPKAN TRANSFORMASI ANTISIPASI KEKERINGAN DIGITAL UMKM SAAT PANDEMI Menkop UKM tengah menyiapkan Kementerian PUPR mengoptimalkan langkah transformasi digital -
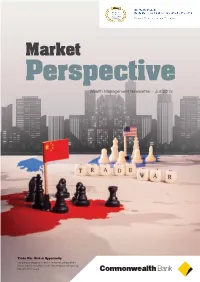
Rev8 Market Perspective-Juli 2018
Market Perspective Wealth Management Newsletter - Juli 2018 Trade War: Risk or Opportunity Isu perang dagang masih mewarnai pergerakan pasar namun diyakini tidak berpengaruh langsung kepada Indonesia. Greetings Nasabah yang terhormat, Terima kasih atas kepercayaan Anda dan menjadi Nasabah setia Bank Commonwealth. Pada Market Perspective e-Newsletter edisi Juli tahun 2018, kami membahas pergerakan pasar keuangan dan faktor- faktor yang mempengharuhinya sepanjang bulan Juni dan Juli 2018. Sepanjang bulan Juni, investor terlihat lebih berhati-hati seiring dengan kembali meningkatnya ketegangan mengenai perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, dan Uni Eropa. Pada bulan Juni juga, untuk pertama kalinya dalam Rustini Dewi sejarah, berlangsung pertemuan antara pemimpin Director of Retail Banking Amerika Serikat dan Korea Utara yang membahas mengenai denuklirisasi di semenanjung Korea. Sementara, di saat yang hampir bersamaan, The Fed menaikkan suku bunga acuan yang kedua di tahun 2018. Sepanjang bulan Juni, investor Dari domestik, pasar saham Indonesia terkoreksi cukup dalam setelah selesai libur panjang Lebaran terlihat lebih berhati-hati yang disebabkan oleh sentimen negatif akibat isu seiring kembali meningkatnya perang dagang. Sentimen positif dari Pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang berlangsung ketegangan mengenai perang dengan lancar dan aman terbukti tidak mampu dagang yang melibatkan menahan sentimen negatif tersebut. Di akhir bulan Amerika Serikat, Tiongkok, Bank Indonesia kembali menaikan suku bunga 7D reverse repo rate sebanyak 50bps untuk menahan Kanada, dan Uni Eropa. pelemahan Rupiah yang berkelanjutan. Di bulan Juli 2018 investor masih menunggu kelanjutan dari kesepakatan antara Amerika Serikat dengan partner dagangnya terutama Tiongkok, Kanada, dan Uni Eropa terkait defisit perdagangan yang dialami Amerika Serikat. Selain itu investor menanti hasil laporan keuangan emiten kuartal II-2018, yang diharapkan momentum Lebaran masih dapat menopang pertumbuhan laba emiten pada kuartal tersebut. -

Revisiting the Inclusion-Moderation Thesis in the Context Of
Special issue article Party Politics 19(2) 210–229 Revisiting the ª The Author(s) 2012 Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav inclusion-moderation DOI: 10.1177/1354068812462933 thesis in the context ppq.sagepub.com of decentralized institutions: The behavior of Indonesia’s Prosperous Justice Party in national and local politics Michael Buehler Northern Illinois University, Dekalb, IL, USA Abstract Institutions figure prominently in explanations for why radical parties forego their agendas and subject themselves to democratic principles when included in politics. Analyzing the Prosperous Justice Party’s political trajectory across Indonesia’s multi- level government structures between 1999 and 2009, I show that the Islamist party has gradually adopted more moderate behavior not only in national politics, where institu- tional incentives are conducive to moderation, but also in local politics, where institu- tional incentives for moderation are weaker. The absence of a strong pattern of invariant association between institutional incentives and the moderation of party behavior points to the importance of party internal mechanisms in moderation processes. Based on primary sources and in-depth interviews with party members, I argue that socio-structural factors shape a party’s internal power dynamics and thereby its long-term capacity to adopt more moderate behavior. Corresponding author: Michael Buehler, Northern Illinois University, 415 Zulauf Hall, Dekalb, IL 60115, USA. Email: [email protected] Buehler 211 Keywords Decentralization, democratization, Islamic Law, Indonesia, party formation, party institu- tionalization, Prosperous Justice Party, PKS, religious parties, shari’a Paper submitted 22 August 2012; accepted for publication 26 August 2012 Introduction Institutions figure prominently in explanations for why radical parties successfully inte- grate into the mainstream when included in politics. -

Gender, Progressive Islam and Islamism in Indonesia Analysing the Political Attitudes of PKB and PKS
Gender, Progressive Islam and Islamism in Indonesia Analysing the Political Attitudes of PKB and PKS Nunik Nurjanah A sub-thesis submitted for the degree of Masters of Arts (Asia-Pacific Studies) of the Australian National University, the College of Asia and the Pacific, the School of Culture, History and Language, July 2013 This thesis is my own original work. To the best of my knowledge, it contains no material previously published or written by another person, except where due reference is made in the text. Signed ......... Table of Contents Acknowledgements .......................................................................................................... v Abstract .......................................................................................................................... vii Glossary and Abbreviations ........................................................................................ viii Chapter I: Introduction .................................................................................................. 1 A. Background ..................................................................................................................... 1 B. Aim and Scope of Study.................................................................................................. 3 C. Key Questions .................................................................................................................. 6 D. Research Methodology .................................................................................................. -

Fires, Urban Environments and Politics in Contemporary Jakarta in : Bankoff G
f 18',,' __________iJ' r.·~F ,~~ '~l). Fires, Urban Environments, and Politics in ContemporaryJakarta JEROME TADIE estroying the city's neighborhoods in violent ways, sometimes putting D thousands ofpeople on the street, fires have been part ofthe common urban landscape ofJakarta since colonial times. I Their unchallenged strength makes them part ofthe everyday lifeof the metropolis, suggesting thatJakarta is doomed to experience them repeatedly. They reveal not only the transforma tions ofthe urban landscape but also the manner in which the cityhas developed as a whole. This essayquestions the relationships between fires and governance in the city. Fires afford a vantage point from which to view the transformations ofthe structures ofcityplanningand management over time. They expose how urban environments are controlled, both from a physical angle and with respect to their more political and social aspects. As they are complex phenomena, whose causes and reasons can range from mere accidents to arson, they involve different types of actors and practices (formal, informal, and occult) in the urban arena. Focusing on the fires that have taken place during the period of great transformation ofthe Indonesia's capital city-- since the mid-rqfios up to the twenty-first century-this essay seeks to address the links between the evolving physical urban environment and the political means ofgoverning a metropolis." 372 Fires, Urban Environments, and Politics in ContemporaryJakarta 373 It will fust analyze the extent offires in the city in connection with the modemiza tion ofthe city, then the chronology ofneighborhood fires since the 1970s; this will then lead to an assessment of the proposed solutions and reconstruction schemes. -

Kajian Kebijakan Pilkada 2018 @2018, the Indonesian Institute
Adinda Tenriangke Muchtar Arfianto Purbolaksono Endah Setyaningsih Fadel Basrianto Riski Wicaksono Umi Lutfiah Yossa Nainggolan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia. Kajian Kebijakan Pilkada 2018 @2018, The Indonesian Institute TIM PENULIS Peneliti The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar Arfianto Purbolaksono Endah Setyaningsih Fadel Basrianto Riski Wicaksono Umi Lutfiah Yossa Nainggolan Desain Cover : PrimeDesign Desain Layout : Harhar Muharam Ukuran 210 x 297 mm Diterbitkan oleh : The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telepon : 021-7203844 Faksimili : 021-7203439 Email : [email protected] Website : www.theindonesianinstitute.com iii Kata Pengantar Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun 2018 juga menjadi tahun yang hangat mengingat tahun ini menjadi pijakan penting sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pilkada serentak sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dinamika Pilkada serentak yang melibatkan beragam aktor dan kepentingan, serta aspek dan kebijakan yang mendasarinya juga menjadi alasan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) untuk menjadikan Pilkada serentak 2018 sebagai topik kajian kebijakan kami tahun ini dan menggarapnya dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial. -

Term of Reference Pertemuan Pemerintah Provinsi Dengan
Term of Reference Pertemuan Pemerintah Provinsi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Mitra OXFAM “Kolaborasi Pemerintah dan Aktor Non Pemerintah dalam Pembangunan Partisipatif untuk Mendukung Pencapaian SDGs” Perkumpulan PRAKARSA dan Oxfam di Indonesia Bogor, 14 Maret 2019 Pendahuluan Pasca reformasi, demokratisasi mengalami kemajuan. Relasi negara dengan warga membaik, hak sipil politik warga lebih terjamin, pelayanan publik makin baik, dan kesejahteraan meningkat. Pemerintah menjadi aktor kunci dalam upaya memajukan kepentingan publik, baik secara langsung maupun dengan cara membuat kebijakan yang bersinergi dengan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga memiliki kontribusi positif dalam menyuarakan kepentingan publik dan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pendekatan kolaboratif antara aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah perlu diperkuat. Namun, sejumlah tantangan masih tetap ada. Di Indonesia, partisipasi publik yang memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam politik termasuk dalam dialog perencanaan serta pelaksanaan kebijakan publik masih sebatas formalitas. Partisipasi publik di Indonesia belum memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik dan sumber daya yang dimiliki oleh negara meski dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan partisipasi publik. Sebagai contoh, Musrenbang yang merupakan ruang partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan paling masif masih belum menjamin akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan OMS di beberapa kelompok kerja di K/L juga masih kurang efektif dalam mengagregasi dan mengakomodasi suara-suara OMS. Pun, posisi OMS juga masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan-penganggaran sampai implementasi-evaluasi. -

DAFTAR PUSTAKA Aedy, Hasan. Teori Dan
DAFTAR PUSTAKA Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011. Agustianto, Percikan Pemikirn Ekonomi Islam, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002. Ahyari, Agus. Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002. Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-dasar Ekonomi Islam , (Solo: PT. Era Audicitra Intermedia, 2011), h. 381. Alma, H. Buchari. Kewirausahaan, Bandung: ALFABETA, 2005. Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Amin, Ridwan. Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management, Jakarta: Salemba Empat, 2010. Anoraga, Pandji. Manajemen Bisnis, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2004. Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan, Jakarta: Tazkia Islami dan BI, 1999. Arifin MBA, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-9,1993. Ascary. Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Asnaini, Evan Setiawan dan Windi Asriani, Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Teras, 2012. Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2010. Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V, Surabaya: Bina Ilmu, 1988. Chapra, Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Chapra, Umer. Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam), Jakarta: gema Insani Press, 2001. Danupranata, Gita. Ekonomi Islam, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006. Departemen Agama RI. AL-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahny, Bandung: CV. -

Islamising Indonesia
Chapter 7: A Vision of Shariah–Led Prosperity: PKS Attitudes to the Implementation of Islamic Law Political openings and opportunities, particularly after the end of Soeharto's New Order regime, have allowed activists of Jemaah Tarbiyah to promote their agenda of Islamisation with a broader target in view. Under the New Order they had remained outside the formal system and kept their distance from political activities, but after the resignation of Soeharto in 1998 they found a way to participate in the democratic system, transforming Jemaah Tarbiyah from an underground religious movement into a legal political party. The issue of the implementation of Islamic law in Indonesia has become an integral part of PKS's agenda to make Indonesia more religious in nature. The question often arises about PKS's attitude towards shariah. What exactly is the party's stance towards its implementation in Indonesia? PKS has made no plain statement in its political platform but this does not mean that it has no desire to implement shariah. PKS has been ambivalent in responding to this sensitive issue. On the one hand PKS has tried to deny allegations that it has a hidden agenda to Islamise the state and on the other hand it also has insisted its commitment to the struggle of Islam, including to applying shariah. This chapter analyses the broad question the formalisation of shariah in Indonesia. PKS's understanding of the issue has a significant place in this discourse; however, explaining it is not an easy task, since we must deal with political rhetoric and PKS's strategy for achieving broad support.