Tuanku Nan Renceh (1762-1832)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ulakan
Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 1, No. 2 (2020). 122-136 P-ISSN: 2722-8940; E-ISSN: 2722-8934 SEJARAH ISLAMISASI MINANGKABAU: STUDI TERHADAP PERAN SENTRAL SYEKH BURHANUDDIN ULAKAN Ridwan Arif Universitas Paramadina, Jakarta Email: [email protected] Abstract Sheikh Burhanuddin is known as a prominent Minangkabau scholar. The Islamization of Minangkabau is commonly associated with him. He is seen as a scholar succeeded in islamizing the Minang community. This study examines the role of Sheikh Burhanuddin in the process Islamization of Minangkabau. It examined the approaches and methods applied by Sheikh Burhanuddin in his efforts to Islamization. This study is a qualitative research, namely library research using the document analysis method. The results indicate that Syekh Burhanuddin was successful in his efforts to Islamize Minangkabau because he used the Sufism approach in his preaching, namely da'wah bi al-hikmah. This approach is implemented in the da'wah method, namely being tolerant of, and adopting local culture (Minangkabau customs and culture). Even further, Sheikh Burhanuddin succeeded in integrating Minangkabau customs with Islamic teachings. Keywords: Syekh Burhanuddin; da'wah; Islamization of the Minangkabau Abstrak Syekh Burhanuddin dikenal sebagai seorang ulama besar Minangkabau. Islamisasi Minangkabau sering dikaitkan dengan dirinya. Ini karena ia dipandang sebagai ulama yang sukses mengislamkan masyarakat Minang. Studi ini mengkaji peran Syekh Burhanuddin dalam islamisasi menangkabau. Ia meneliti pendekatan dan metode-metode yang digunakan Syekh Burhanuddin dalam upaya islamisasi. Kajian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan metode dokumen analisis. Hasil kajian ini menunjukkan Syekh Burhanuddin berhasil dalam upaya islamisasi Minangkabau karena menggunakan pendekatan tasawuf dalam dakwahnya yaitu da’wah bi al-hikmah. -

THE TRANSFORMATION of TRADITIONAL MANDAILING LEADERSHIP in INDONESIA and MALAYSIA in the AGE of GLOBALIZATION and REGIONAL AUTONOMY by Abdur-Razzaq Lubis1
THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL MANDAILING LEADERSHIP IN INDONESIA AND MALAYSIA IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY by Abdur-Razzaq Lubis1 THE NOTION OF JUSTICE IN THE ORIGIN OF THE MANDAILING PEOPLE The Mandailing people, an ethnic group from the south-west corner of the province of North Sumatra today, went through a process of cultural hybridization and creolization centuries ago by incorporating into its gene pool the diverse people from the archipelago and beyond; adopting as well as adapting cultures from across the continents. The many clans of the Mandailing people have both indigenous as well as foreign infusions. The saro cino or Chinese-style curved roof, indicates Chinese influence in Mandailing architecture.(Drs. Z. Pangaduan Lubis, 1999: 8). The legacy of Indian influences, either direct or via other peoples, include key political terms such as huta (village, generally fortified), raja (chief) and marga (partilineal exogamous clan).(J. Gonda, 1952) There are several hypotheses about the origin of the Mandailing people, mainly based on the proximity and similarity of sounds. One theory closely associated with the idea of governance is that the name Mandailing originated from Mandala Holing. (Mangaraja Lelo Lubis, : 3,13 & 19) Current in Mandailing society is the usage 'Surat Tumbaga H(K)oling na so ra sasa' which means that the 'Copper H(K)oling cannot be erased'. What is meant is that the adat cannot be wiped out; in other words, the adat is everlasting. Both examples emphasises that justice has a central role in Mandailing civilization, which is upheld by its judicial assembly, called Na Mora Na Toras, the traditional institution of 1 The author is the project leader of The Toyota Foundation research grant on Mandailing migration, cultural heritage and governance since 1998. -

AS{HA<B AL-JAWIYYIN DI HARAMAIN: Aktivisme Sosiso-Religius Islam Nusantara Pada Abad 17 Dan 18
Asha{ b< al-Jawiyyin di Haramain M. Fazlurrahman H. – UMS Surabaya ASHA{ B< AL-JAWIYYIN DI HARAMAIN: Aktivisme Sosiso-Religius Islam Nusantara pada Abad 17 dan 18 M. Fazlurrahman H. University of Muhammadiyah Surabaya, East Java, Indonesia [email protected] Abstraks: Berangkat dari pernyataan, penyebaran Islam merupakan proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga yang paling tidak jelas. Maka merasa perlu untuk mengkaji kembali diskursus yang selalu meresahkan para sejarawan, yaitu dibawa oleh para wirausahawan atau para guru-guru tasawuf; wilayah mana di antara nusantara yang luas, sebagai daerah pertama yang menerima ajaran Islam; jaringan ulama’ dengan pusat Islam di Makkah dan Madinah; lalu korelasi seperti apa yang terjadi antara religi-intelektualisme Islam dengan pembaharuan Islam Nusantara di abad ke- 17 dan 18. Sehingga dari makalah ini diharapkan dapat menekankan sejarah-sosial serta intelektual yang kemudian dapat mereformulasi tradisi, sehingga tak lagi terabaikan seperti studi- studi terdahulu tentang peran para ulama’ di Nusantara untuk menjaga NKRI. Kajian ini merupakan pengkajian pustaka (library research), menggunakan jenis kualitatif dengan model historis faktual. Dari diskursus ini ditemukan, bahwa ulama’ atau kaum cendekiawan Muslim dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena meletakkan dasar agama bagi sentimen anti-kolonial yang kemudian ditransformasi menjadi sebuah ideologi jihad yang berada dibalik pemberontakan melawan kolonial. Akhirnya dapat ditarik sebuah konklusi, yaitu para pelajar yang kembali dari Haramain tampaknya ada dua jenis, yakni mereka yang menentang ide-ide para reformis-Muslim dan mereka yang mendukung. Kata Kunci: al-Jawi, Haramain, Sosio-Religius dan Aktivisme. PENDAHULUAN Suatu paradigma yang memandang pengetahuan manusia (human sciences) sebagai gerak berkemajuan tak lepas dari ajaran subyek yang otonom, yaitu Renaissance. -
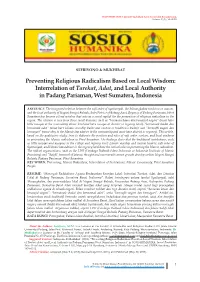
Preventing Religious Radicalism Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adat, and Local Authority in Padang Pariaman, West Sumatera, Indonesia
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 11(1), Mei 2018 SEFRIYONO & MUKHIBAT Preventing Religious Radicalism Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adat, and Local Authority in Padang Pariaman, West Sumatera, Indonesia ABSTRACT: The integrated relation between the sufi order of Syattariyah, the Minangkabau tradition or custom, and the local authority of Nagari Sungai Buluah, Sub-District of Batang Anai, Regency of Padang Pariaman, West Sumatera has become a local wisdom that acts as a social capital for the prevention of religious radicalism in the region. The relation is seen from three social domains, such as “bersurau kaum dan bemasjid nagari” (must have little mosque at the community ethnic level and have mosque at district or regency level); “bermamak ibadat dan bermamak adat” (must have Islamic worship leader and custom or tradition’s leader); and “bermufti nagari dan bernagari” (must obey to the Islamic law adviser in the community and must have district or regency). This article, based on the qualitative study, tries to elaborate the position and roles of sufi order, custom, and local wisdoms in preventing the Islamic radicalism in West Sumatera. The findings show that the traditional institutions, such as little mosque and mosques in the village and regency level; Islamic worship and custom leaders; sufi order of Syattariyah, and Islamic law adviser in the regency level have the critical roles in preventing the Islamic radicalism. The radical organizations, such as the LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia or Indonesia Institute of Islamic Preaching) and “Salafi” (renewel of Islamic thought and movement) cannot growth develop well in Nagari Sungai Buluah, Padang Pariaman, West Sumatera. -

The Influence of Religious Purification Tuanku Nan Renceh Movement Against Minangkabau Culture in the Sub-District of Agam District Tilatang Kamang 1803-1838
1 THE INFLUENCE OF RELIGIOUS PURIFICATION TUANKU NAN RENCEH MOVEMENT AGAINST MINANGKABAU CULTURE IN THE SUB-DISTRICT OF AGAM DISTRICT TILATANG KAMANG 1803-1838 Ifni Aulia Nisa TM *, Isjoni **, Bunari*** Email:[email protected] (085356611275), [email protected], [email protected] Faculty History Education Study Program FKIP-University of Riau Abstrak : The district Tilatang Kamang there are various traditions that deviate from religion norms. Customs and traditions have clung so hard so to be abolished. The ulama seeks to advise the public to follow the Islmanic Shari’a, but the fact is many people who do not want to listen to that advice, until a religious figure Tuanku Nan Renceh initiate new ideas to change people’s traditions with harsh and radical teachings.This study aims to determine the background (biography) Tuanku Nan Renceh, to know the culture and traditions of Tilatang Kamang society before and after the entry of the renewal, to know the cultures deviant who eradicated by Tuanku Nan Renceh, to know mindset Tuanku Nan Renceh about the culture to deviate, to find out what Tuanku Nan Renceh efforts in making changes to the system and habits of the people who have strayed of religious norms and customs norms prevailing in society.The theory used in this study is religious purification movement theory, the theory of religion, forms of movement of religious purification, and cultural theory. This study uses historical and documentary research. Data collection techniques in this study is the literature, documentation, comparative studies will then be deduced.The results showed that Tuanku Nan Renceh is known as the man who led a religious movement in Tilatang Kamang to change the tradition and culture of the people who deviate. -

Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban ISSN: 0216-5945 DOI
Available online: at https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban ISSN: 0216-5945 DOI: https://doi.org/10.15548/hadharah DINAMIKA PERKEMBANGAN TAREKAT SYATTARIYAH DAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI MINANGKABAU Chairullah Ahmad Suluah Community1 [email protected] Abstrak Artikel ini mendiskusikan problematika perkembangan dua tarekat yang populer di Minangakabu, Tarekat Syattariyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Sumber data dari penelitian ini menggunakan sejumlah naskah yang berisi ajaran kedua tarekat, dan naskah-naskah ijazah dari kedua tarekat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial intelektual. Sedangkan untuk mengungkap kandungan naskah menggunakan metode Filologi dan Kodikologi. Berdasarkan penelaahan mendalam dari sumber-sumber dimaksud diperoleh temuan bahwa dari aspek kajian dan ajaran-ajarn, kedua tarekat ini pada dasarnya tidak memiliki banyak perbedaan. Perubahan pada ajaran tarekat Naqsyabandiyah terutama sedikit terlihat pada akhir abad IX. Kata kunci: Tarekat, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Minangkabau. Abstract This article discusses the problematic of dynamic of two popular orders in Minangakabu, the Syattariyah and the Naqsyabandiyah. The data source of this research is a number of texts containing the teachings material of both tarekat, and degree documents from both tarekat. The research method uses qualitative methods with intellectual social history approach. Meanwhile, to explore the contents of the text, this research use the philology and kodikologi. Based on an in-depth study of the sources referred to, it was found that from the aspect of study and teachings, both of tarekat, basically did not have much differences. Changes to the teachings of the Naqshbandiyah order were particularly slight in the late IX century. -

SEJARAH MASUKNYA HABAIB KE INDRAMAYU Shaleh Afif : Guru SMA-IT Madinatul Ulum Email :[email protected]
Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam Vol. 15 No.2, Desember 2018, hlm. 283-302 ISSN (Cetak): 0216-5937 SEJARAH MASUKNYA HABAIB KE INDRAMAYU Shaleh Afif : Guru SMA-IT Madinatul Ulum Email :[email protected] Abstrak Penelitian terkait Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramyu yang dilakukan oleh habaib yang berada di Kabupaten Indramayu serta perannya dalam dakwah agama Islam dalam kurun waktu 1998 sampai 2014. Adapun mayoritas habaib yang berada di Nusantara didominasi berasal dari Hadralmaut dan cukup besar penyebarannya, sementara itu penelitian ini lebih khusus hanya membahas habaib di wilayah Indramayu.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kondisi keagamaan di Indramayu serta sejarah masuknya habaib di Indramayu yang tentunya memiliki beragam kegiatan untuk mensyiarkan dakwah Islam, juga menguatkan keislaman masyarakat di Indramayu.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang dihasilkan, melalui empat tahap yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik (kritik intern dan kritik ektern), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: pertama, kondisi keagaman di Indrmayu sama halnya dengan kondisi keagamaan yang lain yaitu memgang teguh agama Hindu-Budha Kedua, komunitas habaib ini datang dari Hadhramaut (Yaman) pada abad ke 18. Awalnya komunitas habaib yang ada di Indramayu masih tergolong komunitas Arab di Cirebon, akan tetapi pada tahun 1872 komunitas Indramayu memisahkan diri dari komunitas Arab Cirebon, dan menyebar ke seluruh daerah di Indramayu. Meskipun komunitas Arab-Indramayu lebih muda daripada komunitas Arab Cirebon, tetapi komunitas Arab di Indramayu lebih berkembang daripada komunitas Arab di Cirebon. Kata kunci : Habib, Dakwah Islam, Ulama, Indramayu A. -

The Genealogy of Muslim Radicalism in Indonesia A
The Genealogy of Muslim Radicalism in Indonesia THE GENEALOGY OF MUSLIM RADICALISM IN INDONESIA A Study of the Roots and Characteristics of the Padri Movement Abd A’la IAIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Abstract: This paper will trace the roots of religious radicalism in Indonesia with the Padri movement as the case in point. It argues that the history of the Padri movement is complex and multifaceted. Nevertheless, it seems to be clear that the Padri movement was in many ways a reincarnation of its counterpart in the Arabian Peninsula, the Wahhabi> > movement, even though it was not a perfect replica of the latter. While the two shared some similarities, they were also quite different in other respects. The historical passage of the Padris was therefore not the same as that of the Wahhabi> s.> Each movement had its own dimensions and peculiarities according to its particular context and setting. Despite these differences, both were united by the same objective; they were radical in their determination to establish what they considered the purest version of Islam, and both manipulated religious symbols in pursuit of their political agendas. Keywords: Padri movement, fundamentalism, radicalism, Minangkabau, Wahhabism.> Introduction Almost all historians agree that Islam in the Malay Archipelago – a large part of which subsequently became known as Indonesia – was disseminated in a peaceful process. The people of the archipelago accepted the religion of Islam wholeheartedly without any pressure or compulsion. To a certain extent, these people even treated Islam as belonging to their own culture, seeing striking similarities between the new religion and existing local traditions. -

Ave At: SEJARAH KONFLIK KEBANGKITAN ISLAM DI MINANGKABAU
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Rumah jurnal Fakultas Adab dan Humaniora UIN IB Ave at: Available online at: https://ejournal.fah.uinib.ac.id/index.php/khazanah Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam ISSN: 2339-207X (print) ISSN: 2614-3798 (online) DOI: https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0. 13 SEJARAH KONFLIK KEBANGKITAN ISLAM DI MINANGKABAU: Sebuah Tinjauan Awal Terhadap Proses Kemunculannya Ihsan Sanusi Peradaban Islam Melayu Pascasarjana Universitan Islam Negeri Raden Fatah Palembang email: [email protected] Abstract This article in principle wants to examine the history of the emergence of the conflict of Islamic revival in Minangkabau starting from the Paderi Movement to the Youth in Minangkabau. Especially in the initial period, namely the Padri movement, there was a tragedy of violence (radicalism) that accompanied it. This study becomes important, because after all the reformation of Islam began to be realized by reforming human life in the world. Both in terms of thought with the effort to restore the correct understanding of religion as it should, from the side of the practice of religion, namely by reforming deviant practices and adapted to the instructions of the religious texts (al- Qur'an and sunnah), and also from the side of strengthening power religion. In this case the research will be directed to the efforts of renewal by the Padri to the Youth towards the Islamic community in Minangkabau. To discuss this problem used historical research methods. Through this method, it is tested and analyzed critically the records and relics of the past. -

INDO 16 0 1107129329 39 80.Pdf (6.209Mb)
Roadside village between Malang and Selecta NOTES ON CONTEMPORARY INDONESIAN POLITICAL COMMUNICATION Benedict R. OfG. Anderson With the appearance in 1970 of Indonesian Political Thinking, students of Indonesian society and politics were for the first time presented with a wide-ranging collection of writings and speeches by important Indonesian politicians and intellectuals in the post-1945 period.1 The timing of its publication was not fortuitous: it clearly reflected a steadily growing scholarly interest in Indonesian ideology and political discourse.2 Recent work by Dahm, Weatherbee, Legge and Mortimer has been devoted to pioneering analysis of important segments of Indonesian political thought.3 Their writings show not only how rich this field of enquiry is, but also how much m m m research still needs to be done. At the same time it is useful to recognize that the materials used in this genre of research haewsssa specialized represent a particular type of political communication. In general, they take the form of more or less studied, quasi-literary and printed 1. Herbert Feith and Lance Castles, eds., Indonesian Political Thinking, 1945-1965 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970). For a useful critique, see Alfian, "Indonesian Political Thinking’: A Review," Indonesia, 11 (April 1971), pp. 193-200. 2. In addition, a number of translations of important individual texts by Indonesian political leaders have been published. These include: Sutan Sjahrir, Out of Exile, trans. Charles Wolf, Jr. (New York: John Day, 1949); Mohammad Hatta, Past and Future (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, 1960); Sukarno, Mar- haen and Proletarian, trans. -

State and Religion: Considering Indonesian Islam As Model of Democratisation for the Muslim World
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by eDoc.VifaPol OccasionalPaper 122 State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World Syafi q Hasyim If you wish to support our work: Commerzbank Berlin BIC 100 400 00 Donations account: 266 9661 04 Donations receipts will be issued. Imprint: Published by the Liberal Institute Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Reinhardtstraße 12 D–10117 Berlin Phone: +49 30.28 87 78-35 Fax: +49 30.28 87 78-39 [email protected] www.freiheit.org COMDOK GmbH Office Berlin First Edition 2013 STATE AND RELIGION: CONSIDERING INDONESIAN IsLAM AS MODEL OF DEMOCRATISATION FOR THE MUSLIM WORLD Syafiq Hasyim Paper prepared for the Colloquium on Models of Secularism, hosted by the Friedrich Naumann Stiftung, Berlin, July 31, 2013. Contents Introduction 5 Compatibility between Islam and Modern State 6 History of Indonesian Islam 10 Pancasila State 13 Indonesian Islam in Public Sphere and the State 16 Islam in the Political Sphere 19 Reform Era: Revitalisation of Islamic Ideology? 21 Indonesian Salafi-Wahhabi Groups and their Question on the Pancasila State 25 Conclusion 27 Bibliography 27 About the author 32 4 5 Introduction Since the fall of Suharto in 1998, Indonesia has been noticed by the interna- tional community as the largest Muslim country in the world (Mujani & Liddle 2004, pp. 110-11; Ananta et al. 2005). This recognition is because Indonesia has hinted more progress and improvement in democracy and human rights than other Muslim countries such as Turkey, Egypt and Pakistan. Freedom of press, the implementation of fair general elections, the distribution of power among the state institutions (trias politica) and some many others are main indicators depicting the rapid democratisation of Indonesia. -

Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao Di Sumatera Tengah (1820-1833)
NEGOSIASI ISLAM KULTUR DALAM GERAKAN PADERI RAO DI SUMATERA TENGAH (1820-1833) Safwan Rozi STAIN Bukit Tinggi [email protected] Abstrak Gerakan Paderi di Sumatera Tengah adalah revolusi intelektual dan sebuah batas sejarah yang menentukan perkembangan Minangkabau. Di dalamnya ada elemen-elemen fanatisme, kesalehan, resistensi terhadap kolonialisme, dan juga negosiasi budaya. Tulisan ini mengkaji tipologi gerakan keagamaan dalam gerakan Paderi melalui pendekatan sejarah sosial. Pembahasan difokuskan pada sejarah gerakan Paderi, dialektika agama dan budaya lokal, serta negosiasi kaum adat dan kaum agama dalam gerakan Paderi di tanah Rao. Negosiasi adat dan Islam tersebut terjadi pada tahun 1833. Golongan adat dan golongan Paderi bersatu bahu-membahu melawan Belanda. Persatuan bukan hanya dalam bentuk kekuatan saja tapi juga dalam bentuk visi yang kemudian dikenal dengan konsensus Plakat Puncak Pato di Tabek Patah Tanah Datar yang berbunyi “Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dan syarak mangato adat mamakai”. Ikrar ini mengikat golongan adat dan golongan Paderi yang mengakui eksistensi adat dan eksistensi agama Islam dalam pranata sosial. Kesepakatan tersebut kemudian memperkokoh posisi kelembagaan agama dalam masyarakat Minang. Abstract THE NEGOTIATIONS OF THE CULTURAL ISLAM IN THE PADERI RAO MOVEMENT IN CENTRAL SUMATRA (1820-1833). Padri movement is a revolution in Central Sumatra and intellectual history that determines a boundary for the Minangkabau. In it there is fanaticism, coloniality resistance, piety, heroic, history of a very gradual and cultural negotiation. With the use of social history through a heuristic approach, critic and sintetict method, this paper will examine some of the typology of religious Volume 6, Nomor 1, Juni 2012 85 Safwan Rozi movements in Padri movement.