Perpustakaan.Uns.Ac.Id Digilib.Uns.Ac.Id Commit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dead Men Tell No Lies: Using Martyr Data to Expose the PKK's Regional
Dead Men Tell No Lies: Using Martyr Data to Expose the PKK’s Regional Shell Game Jared Ferris and Andrew Self May 05, 2015 1 Table of Contents • List of Figures in Appendix 3 • Acknowledgments 4 • Introduction 5 o Terms and Usage 7 o Literature Review 8 o Methodology/Data 12 o Background 14 • Beginning of the PJAK and PKK Franchise Era 16 • The PKK in Syria 21 o The PYD and Syrian Kurds 2003-2011 23 o The Syrian Civil War 27 • New Opportunities: ISIS, Kobani, and Sinjar 31 • Conclusion 37 • Appendix I- Figures 38 • Appendix II- PKK Military Organizational Structure Chart 46 • Appendix III- Sample “Marty” Announcements 47 • Appendix IV-Acronyms 48 • Bibliography 49 2 List of Figures in Appendix I • Figure 1: Total HPG Deaths by Country of Birth 38 • Figure 2: % of Total HPG Deaths by Country of Birth 38 • Figure 3: HPG Syrian Fighters City of Birth 39 • Figure 4: % of HPG Deaths Country of Birth: Iran vs Syria 39 • Figure 5: HPG Fighter Year of Join by % of Country of Birth 40 • Figure 6: Total Number of HPG Fighters by Year Joined 40 • Figure 7: Total HPG Deaths by Country of Birth 2001-2015 41 • Figure 8: % of HPG Combat Deaths by Country of Death 2001-2015 41 • Figure 9: % of HPG Combat Deaths by Country of Death 42 • Figure 10: YPG Combat Deaths by Country of Birth: Oct 2013-June 2014 43 • Figure 11: YPG Combat Deaths by Country of Birth: July 2014-Feb 2015 43 • Figure 12: YPG Combat Deaths by Country of Birth: Nov 2013-Feb 2015 44 • Figure 13: Map of HPG Combat Deaths in Iran 45 3 Acknowledgements We would like to thank our advisor Dr. -

Kaakkois-Turkin Turvallisuustilanne Syyskuussa 2019
Raportti MIG-1917423 06.03.00 22.10.2019 MIGDno-2019-205 Kaakkois-Turkin turvallisuustilanne syyskuussa 2019 Tässä tilannekatsauksessa tarkastellaan Kaakkois-Turkin turvallisuustilannetta sekä erityisesti Kaakkois-Turkin alueella vuoden 2015 puolivälissä Turkin turvallisuusjoukkojen ja aseellisen kurdijärjestö Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) välillä uudelleenkärjistynyttä aseellista konfliktia (ns. PKK-konflikti). Konfliktiin liittyvät aseelliset yhteenotot jatkuvat tämän raportin kirjoittamishetkellä monissa Kaakkois-Turkin maakunnissa edelleen, joskin vuosien 2015–2016 intensiivisintä taisteluvaihetta vähäisempinä. Tilannekatsauksessa keskitytään Diyarbakırin, Hakkârin, Mardinin ja Şırnakin maakuntien vuosien 2018 ja 2019 turvallisuustilanteeseen ja kyseisten maakuntien alueella raportoituihin, PKK:n toimintaan ja/tai konfliktin eri osapuolten välisiin aseellisiin yhteenottoihin liittyviin turvallisuusvälikohtauksiin. Lisäksi raportissa käsitellään laajemmin myös PKK-konfliktin vaikutuksia kurdiliikkeen poliittisiin toimintamahdollisuuksiin Turkissa. Raportin kokoamisessa on käytetty erilaisia julkisia lähteitä, kuten kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten tuottamia raportteja ja näitä täydentävää uutismateriaalia, joka on ollut Maahanmuuttoviraston saatavilla raportin kirjoittamishetkellä (15.10.2019). Tilannekatsaus päivittää Maahanmuuttoviraston 22.6.2017 julkaiseman raportin1 Kaakkois-Turkin turvallisuustilanteesta. This situation report concerns the security situation in Southeast Turkey and, especially, -

Targeting the Minority: a New Theory of Diversionary Violence
Wright State University CORE Scholar Browse all Theses and Dissertations Theses and Dissertations 2020 Targeting the Minority: A New Theory of Diversionary Violence Nathaniel M. Arnold Wright State University Follow this and additional works at: https://corescholar.libraries.wright.edu/etd_all Part of the International Relations Commons Repository Citation Arnold, Nathaniel M., "Targeting the Minority: A New Theory of Diversionary Violence" (2020). Browse all Theses and Dissertations. 2323. https://corescholar.libraries.wright.edu/etd_all/2323 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at CORE Scholar. It has been accepted for inclusion in Browse all Theses and Dissertations by an authorized administrator of CORE Scholar. For more information, please contact [email protected]. TARGETING THE MINORITY: A NEW THEORY OF DIVERSIONARY VIOLENCE A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts By NATHANIEL M. ARNOLD B.A., Old Dominion University, 2014 2020 Wright State University WRIGHT STATE UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL April 29, 2020 I HEREBY RECOMMEND THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY Nathaniel M. Arnold ENTITLED Targeting the Minority: A New Theory of Diversionary Violence BE ACCEPTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF Master of Arts. ______________________________ Liam Anderson, Ph.D. Thesis Director ______________________________ Laura M. Luehrmann, Ph.D. Director, Master of Arts Program in International and Comparative Politics Committee on Final Examination: ___________________________________ Liam Anderson, Ph.D. School of Public and International Affairs ___________________________________ Carlos Costa, Ph.D. School of Public and International Affairs ___________________________________ Vaughn Shannon, Ph.D. -

Theorising Women and War in Kurdistan. a Feminist and Critical Perspective
Theorising Women and War in Kurdistan. A feminist and critical perspective. Nazand Begikhani, Wendelmoet Hamelink and Nerina Weiss Abstract In this introductory article to the special issue Women and War in Kurdistan, we connect our topic to feminist theory, to anthropological theory on war and conflict and their long-term consequences, and to theory on gender, nation and (visual) representation. We investigate Kurdish women´s victimisation and marginalisation, but also their resistance and agency as female combatants and women activists, their portrayal by media and scholars, and their self- representation. We offer herewith a critical perspective on militarisation, women´s liberation, and women´s experiences in times of war and peace. We also introduce the five articles in this issue and discuss how they contribute to the study of women and war in two main areas: the wide- reaching effects of war on women’s lives, and the gendered representation and images of war in Kurdistan. Keywords: female combatants, feminism, feminist theory, gender and nation, human rights, militarism, representation, sexual violence, victimhood, visualisation, war, women’s activism, women´s movements Introduction This special issue contributes to critical and empirical-based analyses of the present realities of Kurdish women in all parts of Kurdistan and explores the multiple effects and affects of war on women in the Kurdish regions. In doing so, we follow feminist and intersectional approaches to the study of violence and war. Readers might need to be reminded that Kurdistan is not a geographical entity with defined borders and Kurds are straddling the present state boundaries of Turkey, Syria, Iraq, Iran (Dahlman, 2002). -

Kurdistan Workers' Party (PKK)
Kurdistan Workers’ Party (PKK) Name: Kurdistan Workers’ Party (PKK) Type of Organization: Armed insurgent group political party and popular-mobilization group Ideologies and Affiliations: Kurdish Nationalism Apoism Marxist-Leninism Jineology Democratic Confederalism Place of Origin: Southeast Turkey Year of Origin: 1978 Founder(s): Abdullah Öcalan, Cemal Bayik, Murat Karayilan, Kemal Pir, Mahzum Korkmaz, Mazlum Dogan, Riza Altun Places of Operation: Turkey, Iraq, Syria, and Europe Overview Also Known As: Freedom and Democracy Congress of Kurdistan1 Kurdistan Halk Kongresi (Kurdistan People’s Congress)9 Hezan Parastina Gel2 Kurdish Liberation Hawks10 Kongra-Gel (KGK)3 Kurdistan Labor Party11 Kongra Gele Kurdistan4 Kurdistan Ozgurluk Sahinleri12 Kongreya Azadi u Demokrasya Kurdistan (KADEK)5 Kurdistan People’s Congress13 Kurdistan Freedom Falcons6 Partiya Karkeren Kurdistan14 Kurdistan Freedom Brigade7 People’s Defense Force (HPG)15 Kurdistan Freedom Hawks8 Teyrbazên Azadiya Kurdistan16 Executive Summary Abdullah Öcalan founded the Kurdistan Workers’ Party (PKK) in Turkey in 1978.17 While the PKK’s manifesto “…explicitly called for the creation of an independent Kurdish state,” the group embraced Marxism to justify its Kurdish-separatist war as part of a global class struggle and revolution.18 The PKK also utilizes violence to destroy or subsume any other Kurdish nationalist movement that opposes it or deviates from its specific goals.19 The PKK uses car bombs, suicide bombings, abductions, and assassinations against civilians, foreign -
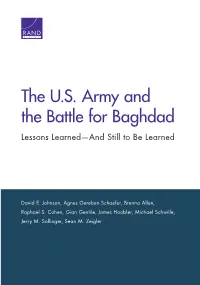
The US Army and the Battle for Baghdad: Lessons Learned
C O R P O R A T I O N The U.S. Army and the Battle for Baghdad Lessons Learned—And Still to Be Learned David E. Johnson, Agnes Gereben Schaefer, Brenna Allen, Raphael S. Cohen, Gian Gentile, James Hoobler, Michael Schwille, Jerry M. Sollinger, Sean M. Zeigler For more information on this publication, visit www.rand.org/t/RR3076 Library of Congress Control Number: 2019940985 ISBN: 978-0-8330-9601-2 Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif. © Copyright 2019 RAND Corporation R® is a registered trademark. Limited Print and Electronic Distribution Rights This document and trademark(s) contained herein are protected by law. This representation of RAND intellectual property is provided for noncommercial use only. Unauthorized posting of this publication online is prohibited. Permission is given to duplicate this document for personal use only, as long as it is unaltered and complete. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any of its research documents for commercial use. For information on reprint and linking permissions, please visit www.rand.org/pubs/permissions. The RAND Corporation is a research organization that develops solutions to public policy challenges to help make communities throughout the world safer and more secure, healthier and more prosperous. RAND is nonprofit, nonpartisan, and committed to the public interest. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions of its research clients and sponsors. Support RAND Make a tax-deductible charitable contribution at www.rand.org/giving/contribute www.rand.org Preface This report documents research and analysis conducted as part of a project entitled Lessons Learned from 13 Years of Conflict: The Battle for Baghdad, 2003–2008, spon- sored by the Office of Quadrennial Defense Review, U.S. -

Turkey's Kurdish Conflict: 2015-Present
Turkey's Kurdish Confict: 2015-Present BACKGROUNDER - December 2016 Summary Introduction to Turkey’s Kurd- ish confict • The Suruç bombing in July 2016 fared up Turkey’s most signifcant Turkey’s Kurdish confict has dominated the intra-state confict. headlines of Europe throughout 2016. In- creasingly, Turkey, has turned into an author- • Since July 2015, more than 2,300 itarian state by suppressing critical voices people have been killed in violent and crushing an elected opposition party. The detention of high-ranking ofcials of the clashes. People’s Democratic Party (HDP) at the start of November 2016 atracted international • Western Turkish cities such as Istan- atention. Over time, the political situation of bul and Ankara have been hit hard Turkey’s Kurds has deteriorated into military by terror atacks allegedly conduct- confrontations between the Turkish central ed by the PKK and its afliates. state and Kurdish nationalist groups. • The confict feeds from the Syrian Origins of the confict war where both belligerents are The origins of this confict can be traced back involved and fght intensely with to the fragmentation of Kurdish populations each other. into several states at the breakup of the Ot- toman Empire. The Kurdish fragmentation • This ISDP Backgrounder gives an into the states of Turkey, Syria, Iraq, and Iran overview to the confict, identifes took its course afer the Treaties of Sèvres the actors involved, details a time- and Lausanne established new boundaries line of events, the casualties of the between Middle Eastern states. However, confict so far and identifes trends despite the promises of major Colonial pow- ers, no separate nation-state emerged for the in warfare. -

Turkish Foreign Policy Towards the Kurdistan Regional Government (2003-2013) a Globalist Analysis
This work is protected by copyright and other intellectual property rights and duplication or sale of all or part is not permitted, except that material may be duplicated by you for research, private study, criticism/review or educational purposes. Electronic or print copies are for your own personal, non- commercial use and shall not be passed to any other individual. No quotation may be published without proper acknowledgement. For any other use, or to quote extensively from the work, permission must be obtained from the copyright holder/s. TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS THE KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (2003-2013) A GLOBALIST ANALYSIS by Mustafa Demir A Thesis Submitted in accordence with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Politics and International Relations July 2015 2 3 ABSTRACT Despite the shadows cast by their history, Turkey has developed relations with the Kurdish government to the level of a strategic partnership within the last decade, following the 2003 invasion of Iraq. This thesis contextualizes this unexpected rapprochement from a globalist perspective. To do so, the research first identifies and analyses important developments taking place during 2003- 2013, then it seeks the motives that led to the emergence of this strategic partnership between these two regional actors, first at regional, then at global level. In conclusion, it argues that it was mainly the power shift in global political system that led Turkey to abandon its traditional policy towards the Kurdish Region of Iraq. 4 Table of -

Turkey: the Pkk and a Kurdish Settlement
TURKEY: THE PKK AND A KURDISH SETTLEMENT Europe Report N°219 – 11 September 2012 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS ................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. MEANS OR END? THE PKK’S ARMED STRUGGLE .............................................. 7 A. THE ORGANISATION .................................................................................................................... 7 B. THE LEADERSHIP ......................................................................................................................... 9 C. COMPETING LEADERSHIP FACTIONS .......................................................................................... 11 D. THE INSURGENT FORCES ............................................................................................................ 12 E. FINANCING ................................................................................................................................ 13 F. IDEOLOGY .................................................................................................................................. 13 III. THE PKK OUTSIDE TURKEY .................................................................................... 15 A. THE PKK IN THE MIDDLE EAST ................................................................................................. 15 B. SYRIA ....................................................................................................................................... -

Turkey's Kurdish Conflict: 2015-Present
Turkey's Kurdish Confict: 2015-Present BACKGROUNDER - December 2016 Summary Introduction to Turkey’s Kurd- ish confict • The Suruç bombing in July 2016 fared up Turkey’s most signifcant Turkey’s Kurdish confict has dominated the intra-state confict. headlines of Europe throughout 2016. In- creasingly, Turkey, has turned into an author- • Since July 2015, more than 2,300 itarian state by suppressing critical voices people have been killed in violent and crushing an elected opposition party. The detention of high-ranking ofcials of the clashes. People’s Democratic Party (HDP) at the start of November 2016 atracted international • Western Turkish cities such as Istan- atention. Over time, the political situation of bul and Ankara have been hit hard Turkey’s Kurds has deteriorated into military by terror atacks allegedly conduct- confrontations between the Turkish central ed by the PKK and its afliates. state and Kurdish nationalist groups. • The confict feeds from the Syrian Origins of the confict war where both belligerents are The origins of this confict can be traced back involved and fght intensely with to the fragmentation of Kurdish populations each other. into several states at the breakup of the Ot- toman Empire. The Kurdish fragmentation • This ISDP Backgrounder gives an into the states of Turkey, Syria, Iraq, and Iran overview to the confict, identifes took its course afer the Treaties of Sèvres the actors involved, details a time- and Lausanne established new boundaries line of events, the casualties of the between Middle Eastern states. However, confict so far and identifes trends despite the promises of major Colonial pow- ers, no separate nation-state emerged for the in warfare. -

3 HDP Supporters Murdered by Counter Forces Laid to Rest
3 HDP supporters murdered by counter forces laid to rest IDENTY ABOUT US COPYRIGHT KURDÎ TÜRKÇE ENGLISH MAIN PAGE NEWS POLITICS WOMEN YOUTH ECOLOGY WORK LİFE ALL NEWS LOGIN CULTURE INTERNATIONAL ECONOMY SPOR LOCAL AGENDA OF ELECTION NEWS ⌂ BACK TO HOMEPAGE + 24 3 HDP supporters murdered by counter forces laid to rest - View More Articles 21 20.06.2015 15:55 YPG continue to attack ISIS in rural Girê Spî 1 15:50 'I'm sorry that I couldn't look at Demirel's dirty face' 1 14:39 Father asking for his children killers sued as perpetrator! 1 14:12 Dayiken Şemiyê: Missing and disappearances suffered at Demirel's term 1 14:03 Girê Spî: Life turning back to normal 1 13:25 Condolence tent for MLKP fighter Akdaş 1 11:00 IHD to apply to Supreme Court for imprisoned PYD members 1 10:42 Mexico beer centre attack leaves 10 dead 13:37 Save with Photos Print 10 June 2015 Save 10:41 Majority of victims of Charleston church shooting women DİYARBAKIR (DİHA) - The three persons murdered by counter forces in Diyarbakır last night, Bayram Dağtan, 10:26 Women take to the streets for Bayram Özelçi and Emin Ensen, have been laid to rest following a ceremony attended by thousands of people. Cansu Kaya 1 10:13 IHD reports on refugees’ problems HDP (Peoples' Democratic Party) supporters Bayram Özelçi, Bayram Dağtan and Emin Ensen lost their lives in 1 hospital last night after they were shot by members of HUDA-PAR who randomly opened fire on people in the streets 10:13 YPG forces continue to advance of Diyarbakır yesterday evening. -

The Invisible War in North Kurdistan
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto The Invisible War in North Kurdistan Kristiina Koivunen 2 The right to healthy living is an essential and non-transferrable basic human right which is guaranteed by our constitution. The utilisation of our health care services by every citizen when he/she needs them, the elimination of regional inequalities, and recognising and raising the health level of our people are some of our basic aims. Through the establishment and management of health information as required, health care services can be directed and monitored in line with our aims. (Dr. H. Ibrahim Öksöy, Minister of Health, 1995) The reason for diseases is poverty, but not only poverty; it is simply the policy of the Turkish state to destroy a nation. Not only to go and shoot and kill them - there are also other methods.(a Kurdish woman) 3 Kristiina Koivunen [email protected] ISBN: 952-10-0644-7 (Internet, PDF) 952-91-4994-8 (Publication) 4 The Invisible War in North Kurdistan List of Abbreviations / List of Tables Acknowledgement 1. Introduction: the scarcity of information about the health of the Kurds 12 Civil war in North Kurdistan(12) / Ethnocide and low-intensity warfare(13) Ethics of studying civilians under armed conflicts(15) 2. Theoretical approach 19 2.1. Ethnic identity People, nation and nationalism(21) / Ethnic revival(24) 2.2. Genocide and ethnocide 27 Ethnocide(32) / Linguistic human rights and linguicide(36) 2.3. Low-intensity warfare 40 3. Ethics of research about war 47 3.1.