JAHI7211-B5bb7d18e1fullabstract
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Upaya Jepang Dalam Menyebarkan Budaya Populer Di Indonesia Menggunakan Diplomasi Publik Melalui Anime Festival Asia Indonesia (AFAID)
Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 Upaya Jepang dalam Menyebarkan Budaya Populer di Indonesia Menggunakan Diplomasi Publik Melalui Anime Festival Asia Indonesia (AFAID) Skripsi Oleh Ainun Zidni Ilma 2011330168 Bandung 2018 Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 Upaya Jepang Dalam Menyebarkan Budaya Populer di Indonesia Menggunakan Diplomasi Publik Melalui Anime Festival Asia Indonesia (AFAID) Skripsi Oleh Ainun Zidni Ilma 2011330168 Pembimbing Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D. Bandung 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Tanda Pengesahan Skripsi Nama : Ainun Zidni Ilma Nomor Pokok : 2011330168 Judul : Upaya Jepang Dalam Menyebarkan Budaya Populer di Indonesia Menggunakan Diplomasi Publik Melalui Anime Festival Asia Indonesia (AFAID) Telah Diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana Pada Rabu, 8 Agustus 2018 Dan Dinyatakan LULUS Tim Penguji Ketua Sidang Merangkap Anggota Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. : Sekretaris Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D. : Anggota Dr. Paulus Yohanes Nur Indro : Mengesahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ainun Zidni Ilma NPM : 20111330168 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional Judul : Upaya Jepang Dalam Menyebarkan Budaya Populer di Indonesia Menggunakan Diplomasi Publik Melalui Anime Festival Asia Indonesia (AFAID) Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. -
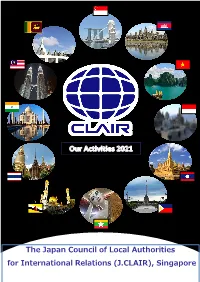
(JET) Programme 【Objective】 to Increase Cross-Cultural Understanding As Well As Contribute to Internationalization Efforts Within Japan
The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR), Singapore About CLAIR The Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) was established in July 1988 in response to rising concerns for local-level internationalization in Japan. CLAIR was created as a joint organization of local governments to promote and provide support for local internationalization. CLAIR’s headquarters are located in Tokyo with seven representative offices in Singapore, New York, London, Paris, Seoul, Sydney and Beijing. J.CLAIR Singapore J.CLAIR Singapore was set up in October 1990 and conducts activities in the 10 ASEAN countries (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) , India as well as Sri Lanka. Main Activities 1. International cooperation efforts at local government level 2. Promoting local level exchange 3. Conducting research on local administration and finance systems as well as the various policies 4. Supporting Japanese local governments’ overseas activities Sri Lanka Organizational Structure Our office consists of 19 staff dispatched from Japan and 6 local staff. No. Dispatched from Executive Director 1 Ministry of Internal Affairs & Communications Deputy Executive 1 Kyoto Director Senior Deputy Director 1 Hyogo Akita, Tochigi, Oyama City (Tochigi), Tokyo, Adachi City (Tokyo), Ota City (Tokyo), Nagano, Aichi, Ichinomiya City (Aichi), Deputy Director 14 Yamaguchi, Kitakyushu City (Fukuoka),Miyazaki, Kagoshima, Kagoshima City (Kagoshima) Division Director 2 Nagano, Kumamoto Local Staff 6 - 1 International Cooperation Efforts at Local Government Level Seminars and Exchange Sessions on Local Administration 【Objective】 With an aim to enhance cooperation and exchange in the area of local administration, J.CLAIR Singapore actively conducts seminars and exchange sessions with local government officials and related organizations in ASEAN countries, India as well as Sri Lanka. -

Penyebaran Pop Culture Jepang Oleh Anime Festival Asia (Afa) Di Indonesia Tahun 2012-2016
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (3): 729 -744 ISSN 2477-2623(online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017 PENYEBARAN POP CULTURE JEPANG OLEH ANIME FESTIVAL ASIA (AFA) DI INDONESIA TAHUN 2012-2016 Putri Safariani1 NIM. 1002045235 Abstract The spread of Japanese pop culture by Anime Festival Asia in Indonesia shows the advantages of a cultural element by utilizing the use of soft power diplomacy. The purpose of this research is to determine the Anime Festival Asia's efforts in the spread of Japanese pop culture in Indonesia.This issue would be analyzed with the theory of diplomacy to analyze the spread of Japanese pop culture by Anime Festival Asia (AFA). The result showed Japan as a country using Soft Power Diplomacy in a cultural context has succeeded in establishing better cooperation and providing a culture of Japanese pop culture and has big interest especially among teenagers, and that success can be seen in Anime Festival Asia activities that show success and profit between the two countries that have cooperation. Key words : Anime Festival Asia, Indonesia, Japanese Pop Culture Pendahuluan Pop Culture adalah budaya yang dibuat oleh masyarakat untuk dirinya sendiri kemudian diproduksi oleh media massa sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang dari kalangan manapun dan penyebarannya pun menjadi lebih luas dengan tujuan untuk menyenangkan diri mereka. Menurut Kato, pop culture disebut budaya massa (konsumen/rakyat). Budaya yang dipasarkan kepada konsumen secara komersial dan berorientasi pada keuntungan yang besar dan membuat budaya tersebut diproduksi secara besar dan menarik hingga tidak hanya disukai oleh masyarakat Jepang tetapi juga masyarakat dari negara lain (John Storey, 1993. -

Jlopplus0528 Afa.Pdf
アジア中の日本ポップカルチャーファンが集まるイベント UNITING J-POP CULTURE FANS THROUGHOUT ASIA 12 過去 7年間で 12回開催 TOTAL AFA HELD IN LAST 7 YEARS バンコク (Bangkok) 2015年 753,000 2008年からの総集客数 TOTAL ENGAGED AUDIENCE SINCE 2008 クアラルンプール (Kuala Lumpur) 年 145,000 2012 2014年の総集客数 TOTAL ENGAGED AUDIENCE IN 2014 シンガポール (Singapore) 2008年 ~ 2014年 (7回 ) 581,868 AFAFacebook「いいね」数 TOTAL AFA FACEBOOK FANS $4,000,000 ジャカルタ (Jakarta) 2014年イベント開催規模 2012年 ~ 2014年 (3回 ) (シンガポール/ジャカルタ) TOTAL INVESTMENT FOR AFA 2014 (Singapore & Jakarta) KEY MARKETS HAVE DEMONSTRATED SOLID GROWTH! 毎年、着実な成長を記録! 90,000 82,000 83,000 85,000 71,000 53,000 55,000 52,000 40,000 27,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 AFA SG ATTENDANCE GROWTH AFA ID ATTENDANCE GROWTH AFAシンガポール 来場者 AFAインドネシア 来場者 ANIME FESTIVAL ASIA EVENT REPORT 2014 - INDONESIA イベントレポート 55,000 Attendance over 3 Days 3⽇間の来場者 ¥800 Starting price of Entry 最低 ⼊場料 123 Total Exhibitors & Sponsors 出展社&スポンサー ¥8,000 Average spend at Event 平均⽀出額 ANIME FESTIVAL ASIA EVENT REPORT 2014 - SINGAPORE イベントレポート 90,000 Attendance over 3 Days 3⽇間の来場者 ¥1,000 Starting price of Entry 最低 ⼊場料 152 Total Exhibitors & Sponsors 出展社&スポンサー ¥15,000 Average spend at Event 平均⽀出額 ご協賛/ご出展パートナー PAST SPONSORS AND PARTNERS ODEX Genesis Frontier 他多数 And many more… AFAの独⾃メディア AFA MEDIA ANIME FESTIVAL ASIA - OFFICIAL FACEBOOK PAGE AFA公式 FACEBOOK #1 SE ASIA - OFFICIAL SOURCE FOR AFA & POP CULTURE UPDATES 東南アジア No.1のポップカルチャー情報源 OVER 580,000 Likes 58万以上の「いいね!」数 AFA CHANNEL - OFFICIAL NEWS SITE AFAチャンネル(ニュースサイト) #1 SE ASIA - JAPAN POP CULTURE NEWS SITE 東南アジア No.1の⽇本ポップカルチャーニュースサイト -

New Wins & Re-Appointments for Asia PR Werkz
The fourth edition of Singapore’s biggest annual yuletide fair will be held in December at Gardens by the Bay, with bigger, brighter and more magical experiences. Nov 22, 2017 13:00 +08 New Wins & Re-appointments for Asia PR Werkz New Wins & Re-appointments for Asia PR Werkz 22 November 2017 Within three months of setting up a new practice group for fintech and new age start-up companies, Asia PR Werkz announced today that they have secured several clients, including budget hotel platform RedDoorz, mobile wallet solution company MatchMove, and omni-channel commerce solutions provider Ace Turtle. All three accounts require Asia PR Werkz to cover media relations work beyond the Singapore market, including Malaysia, Indonesia, India and other parts of Southeast Asia. These accounts are led by Associate Director Ms Anu Gupta, and Manager Mr Joachim Leong, who re-joined Asia PR Werkz in September this year. Asia PR Werkz has also been re-appointed by Blue Sky Events to manage public relations and media relations matters for Christmas Wonderland 2017, and by SOZO to manage public relations and media relations matters for C3 Anime Festival Asia Singapore 2017. Christmas Wonderland 2017: The fourth edition of Singapore’s biggest annual yuletide fair will be held in December at Gardens by the Bay, with bigger, brighter and more magical experiences. The team, led by Director Ms Lim Wee Ling, will work closely with the organisers to promote the event in Singapore, as well as reach out to key opinion leaders in markets including Malaysia, Thailand, and Indonesia. (See attached past event photo for your usage.) C3 Anime Festival Asia Singapore 2017 is the region’s top Japanese Popular Culture and anime festival. -

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Dalam Tatanan Dunia
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Dalam tatanan dunia internasional, negara menggunakan beragam cara dalam pencapaian kepentingan nasionalnya. Salah satunya adalah penggunaan soft power. Menurut Nye, negara harus mampu menggunakan kekuatan soft power-nya untuk mencapai kepentingannya.1 Ada beberapa bidang yang menjadi kekuatan bagi suatu negara dalam melakukan soft power yakni budaya, politik dan sosial ekonomi. Jepang sebagai negara yang kaya akan budaya terkhususnya budaya tradisional populer memiliki potensi dalam pemaksimalan budaya tersebut sebagai alat penerapan kepentingan negaranya. Dalam konsep diplomasi budaya, budaya atau tradisi mampu menjadi jalan atau alat untuk melakukan komunikasi atau mengajak, mempengaruhi khalayak banyak dengan tujuan national branding dan penerapan kepentingan.2 Jepang mulai melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia setelah disepakatinya perjanjian perdamaian antara pihak Jepang dan Republik Indonesia pada april 1958.3 Setelah dilakukan perjanjian tersebut peningkatan demi peningkatan hubungan diplomatis terus dilakukan dengan serangkaian kerjasama dan juga 1 Joseph Jr Nye."Soft Power and American Foreign Policy." Political Science Quaterly Academy of Political Science, 2004. 2 Tulus Warsito, dan Wahyuni Kartikasari. Diplomasi Kebudayaan. yogyakarta: Ombak, 2007. 3 Rod Fisher. Japan Country Report. Country Report, Preparatory Action "Culture in The EU's External Relations", 2014. 1 pertukaran nota kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam berbagai bidang meliputi investasi, pariwisata dan pertukaran budaya.4 Di Indonesia, pengembangan kebijakan Cool Japan mulai gencar dilakukan sejak tahun 2008 setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia.5 Pengembangan yang dilakukan menggunakan strategi promosi budaya populer yang dikembangkan oleh Jepang dengan dukungan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan The Japan Foundation. Pengembangan kebijakan ini dianggap sebagai suatu usaha bagi Jepang dalam merevitalisasi negaranya. -
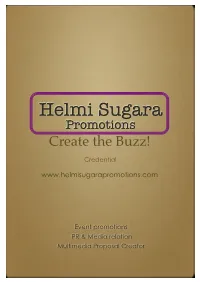
Media Relation Multimedia Proposal Creator Personal Background Name : Helmi Sugara! Born : Dec 19, 1976!
Helmi Sugara! Promotions" Create the Buzz!! Credential www.helmisugarapromotions.com Event promotions PR & Media relation Multimedia Proposal Creator Personal Background" Name : Helmi Sugara! Born : Dec 19, 1976! Professional experience:! •Warner Music Indonesia 1999 – 2003! International label promotion! •Nepathya int’l Promoter 2003 – 2004! Media Relation! •Java Festival Production 2004 – 2006! Media Relation! •Activate Media Nusantara 2006 – 2010! Media Relation, line producer, Chief of Creative! •Various Event Promotion, PR and! Media Relation (Media specialist) 2006 - Present! PR & Media Relation Coordinator! •Event’s proposal creator 2009 – present! Multimedia Creative proposal & sponsorship organizer! Various International event" 1. JAKARTA MOVEMENT 2003 – as Media Relation/promotion! 2. LINKIN PARK- METEORA WORLD TOUR 2004 as Media Relation/ promotion! 3. JAKARTA MOVEMENT 2004 – as Media Relation/promotion! 4. JAKARTA MOVEMENT 2005 – as Media Relation/promotion! 5. JAKARTA MOVEMENT 2006 – as Media Relation/promotion! 6. JIFFEST 2006 – as Media Relation/ promotion & Sponsorship agency! 7. JAKARTA INTERNATIONAL JAVA JAZZ FESTIVAL 2005 – Media Relation & Promotion! 8. JAKARTA INTERNATIONAL JAVA JAZZ FESTIVAL 2006 – Media Relation & Promotion! 9. JAKARTA INTERNATIONAL JAVA JAZZ FESTIVAL 2007 – Sponsorship agency! 10. JAKARTA INTERNATIONAL JAVA JAZZ FESTIVAL 2008 - Sponsorship agency! 11. TIESTO IN SEACH OF SUNRISE WORLD TOUR 2006 as Media Relation / PR & Promotion! 12. JADE 2007 – as Media Relation /PR & Promotion! 13. EMBASSY PLAYGROUND 2007 as Media Relation / PR & promotion! 14. TIESTO ELEMENTS OF LIFE TOUR 2008 as Media Relation & promotion! 15. JADE 2008 – as Media Relation/ PR & promotion! 16. EMBASSY PLAYGROUND 2008 / as Media Relation / PR & promotion! 17. BEYONCE EXPERIENCE TOUR 2007 / as Media Relation & Promotion! 18. DURAN – DURAN WORLD TOUR 2008 as Media Relation & Promotion! 19. -

Anime and Manga As Japanese Cultural Diplomacy Towards Indonesia (2012-2016)
THE ROLE OF CULTURE IN DIPLOMACY: ANIME AND MANGA AS JAPANESE CULTURAL DIPLOMACY TOWARDS INDONESIA (2012-2016) By ANDI RACHMAN ID no. 016201300167 A thesis presented to the Faculty of Humanities President University In partial fulfilment of the requirements for Bachelor Degree in International Relations Concentration Diplomacy Studies 2017 THESIS ADVISER RECOMMENDATION LETTER This thesis entitled “The Role of Culture in Diplomacy: Anime and Manga as Japanese Cultural Diplomacy towards Indonesia (2012- 2016)” prepared and submitted by Andi Rachman in partial fulfilment of the requirement for the degree of Bachelor of Arts in International Relations from the Faculty of Humanities has been reviewed and found to have satisfied the requirements for a thesis fit to be examined. I therefore recommend this thesis for Oral Defense. Cikarang, Indonesia, January 25th 2017 Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D. ii DECLARATION OF ORIGINALITY I declare this thesis, entitled “The role of Culture in Diplomacy: Anime and Manga as Japanese Cultural Diplomacy towards Indonesia (2012-2016)” is, to the best of my knowledge and belief, an original piece of work that has not been submitted, either in whole or in part, to another university to obtain a degree. Cikarang, Indonesia, January 25th 2017 Andi Rachman iii PANEL OF EXAMINER APPROVAL SHEET The Panel of Examiner declare the thesis entitled “The Role of Culture in Diplomacy: Anime and Manga as Japanese Cultural Diplomacy towards Indonesia (2012-2016)” that was submitted by Andi Rachman majoring in International Relations from Faculty of Humanities was assessed and approved to have passed the Oral Examination on March 6th, 2017. -

Anime Festival Asia Kembali Di Selenggarakan Untuk Tahun Ke-5 Mengumumkan Pengisi Konser I Love Anisong Dan Kegiatan Pameran Anime Yang Lebih Seru!
Anime Festival Asia kembali di selenggarakan untuk tahun ke-5 Mengumumkan pengisi konser I Love Anisong dan Kegiatan Pameran Anime yang lebih seru! Jakarta, 15 Juni 2016 – Anime Festival Asia Indonesia (AFAID16), Festival budaya Jepang dan Anime terbesar di Asia akan kembali di selenggarakan dan akan menghadirkan kembali konser I Love Aninsong, konser yang banyak ditunggu oleh penggemarnya serta telah mengumumkan artis/pengisi acara konsernya. AFAID16 akan kembali diselenggarakan hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 16, 17 dan 18 September 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran (JIExpo), AFAID16 mempersembahkan 8 Artis dari Jepang untuk menghibur para penggemarnya di Jakarta Indonesia. Tahun 2016 ini menjadi tahun ke-5 bagi Anime Festival Asia di Jakarta. Dengan semakin berkembangnya budaya Pop Jepang, diharapkan festivalnya nanti akan mengulang kesuksesannya di tahun 2015 yang telah berhasil mendatangkan lebih dari 60.000 pengunjung. Arena Konser yang Baru Para pengunjung dan penggemar AFAID akan semakin seru menikmati konser pilihannya tahun ini, dimana dengan ruang konser yang lebih besar dengan dilengkapi tata suara dan ruang akustik yang lebih baik di area konser Hall C3. Dengan tempat konser baru ini guna memenuhi animo dari para penggemar yang menginginkan tempat konser yang lebih baik dari tahun sebelumnya. “Konser I Love Aninsong adalah acara yang sangat penting dan memberikan pengalaman yang istimewa bagi para penggemarnya, maka dari itu kami sangat memperhatikan masukan dan usulan dari para penggemar secara serius. Seperti halnya kami telah memindahkan ruang konser ke area yang lebih baik guna memastikan setiap penggemar dapat menonton konser yang lebih maksimal. Bagi kami pengunjung festival AFAID adalah prioritas utama kami, dan kami selaku penyelenggara ingin memberikan acara festival dan pelayanan yang terbaik bagi pengunjungnya. -

The Role of Anime and Manga in Indonesia-Japan Cultural Diplomacy
筑波学院大学紀要第13集 41 ~ 47 ページ 2018年 <招待論文> The Role of Anime and Manga in Indonesia-Japan Cultural Diplomacy Wahyuni Kartikasari * Abstract In diplomacy we recognize the term of public diplomacy. Because public diplomacy uses media related to modern technology, then the development of communication technology also affects the forms of public diplomacy. Meanwhile, the most familiar to the development of communication technology is the young people. And one of the phenomena that are growing rapidly today among young people, is popular culture, shortly, pop culture. The Pop culture that emerging popularly in the world now such as anime, manga and cosplay come from Japan, and that media can be used to popularize Japanese culture and knowledge about Japan. This paper explores how the Japanese pop culture as public diplomacy and its influence in In- donesia. Key words: pop culture, anime, public diplomacy. 1. Diplomacy in International Relations Diplomacy is one part of the International Relations studies. In the sense of a traditional approach, diplomacy is understood as the art of negotiating with other countries. Diplomacy can also be interpreted as the art of promoting national interests to the international relations or other countries in various ways. In diplomacy we recognize the term of public diplomacy. The international relations dictionary mentions the definition of public diplomacy as a state’s attempt to influence public opinion in other countries by using instruments such as film, cultural exchange, radio, and television. E.H. Carr writes that the power of opinion is also important in the achievement of political objectives, just like military and economic power and has close ties to both. -

DEC 2019 43805SIAG Awdstrat19 Awd Serv 148X210 Insiderguide Apr19 Inc.Indd 1 27/2/19 5:02 PM Contents
A Visitor’s Guide to OCT - DEC 2019 43805SIAG_AwdStrat19_Awd_Serv_148x210_InsiderGuide_Apr19_Inc.indd 1 27/2/19 5:02 PM contents WHAT’S ON TAKE ME HOME 04 Look out for these exciting events. 20 Take your pick from unique keepsakes that pay tribute to Singaporean culture. PARK LIFE 10 Explore green sanctuaries that are SHOPPING TRAILS easily accessed from the city centre. 22 Don't miss out on the best buys in town. TREASURES OF LITTLE INDIA EYE-OPENING TOURS 12 Teeming with traditional sights, 24 Sign up for these immersive tours to sounds and scents, Little India experience a very different side of invites you to browse a wide range Singapore. of heritage and modern souvenirs. JUST KIDDING AROUND MAKAN TIME 26 Here are some ideas of how you and 14 Tuck into our city’s best your young ones can explore Singapore local dishes. together. THE EAT LIST ACTION & ADVENTURE 16 Indulge in new epicurean experiences 28 Be part of the action. at these modern restaurants. NEON NIGHTS ART IN THE CITY 30 Dive into new after-dark experiences 18 Be inspired by different forms that you won't forget. of art. Editor Andre Frois Contributing Editor Darren Chua Sub Editor Chai Tze Yuen Art Director Nor Hamimah www.mongoosepublishing.sg DC 001 05 19 Q4 STB is not responsible for the accuracy, For general enquiries, contact completeness or usefulness of this SINGAPORE TOURISM BOARD publication and shall not be liable for any damage, loss, injury or inconvenience arising Tourism Court, from or in connection with the content of 1 Orchard Spring Lane, this publication. -
Chapter Iv Manga and Anime As the Tools of Japanese
CHAPTER IV MANGA AND ANIME AS THE TOOLS OF JAPANESE PUBLIC DIPLOMACY Japan was considered to have violated human right and caused devastation in other countries during the World War II. Japanese invasion in World War II was so great that Japan had destabilized the World and Japan was a country considered cruel as destroyer to other countries. Because Japan was such an ambitious country and did the brutal things in international world, it made Japan become a country feared by others. However, after the defeat of Japan in World War II Japan got such bad image post World War II. Asian countries especially, that have been colonized by Japan did not respect anymore to Japan and also the international view about Japan has changed because there were so many countries that felt being effected of the Japanese atrocities. Thus, it made Japan had a bad image post World War II. The way Japan rebuilt their image is by using two of their soft diplomacy. They are anime and manga. The factors which led Japan to improve and to rebuild the national image post World War II that had been described above. Then, this section discusses the effort of Japan to rebuild the image and how Japan did national branding. The analysis of the efforts of Japan will eventually provide the result of analysis about international respond towards Japan post Japan national branding image. 50 A. The Cultural Values of Japan in Manga and Anime Cultural diplomacy is a part of public diplomacy. Diplomacy itself is an effort to struggle the national interest in international society and to have foreign relations.