Garap Tabuhan Bonang Panembung Dalam Gendhing Soran Karawitan Gaya Yogyakarta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

7'Tie;T;E ~;&H ~ T,#T1tmftllsieotog
7'tie;T;e ~;&H ~ t,#t1tMftllSieotOg, UCLA VOLUME 3 1986 EDITORIAL BOARD Mark E. Forry Anne Rasmussen Daniel Atesh Sonneborn Jane Sugarman Elizabeth Tolbert The Pacific Review of Ethnomusicology is an annual publication of the UCLA Ethnomusicology Students Association and is funded in part by the UCLA Graduate Student Association. Single issues are available for $6.00 (individuals) or $8.00 (institutions). Please address correspondence to: Pacific Review of Ethnomusicology Department of Music Schoenberg Hall University of California Los Angeles, CA 90024 USA Standing orders and agencies receive a 20% discount. Subscribers residing outside the U.S.A., Canada, and Mexico, please add $2.00 per order. Orders are payable in US dollars. Copyright © 1986 by the Regents of the University of California VOLUME 3 1986 CONTENTS Articles Ethnomusicologists Vis-a-Vis the Fallacies of Contemporary Musical Life ........................................ Stephen Blum 1 Responses to Blum................. ....................................... 20 The Construction, Technique, and Image of the Central Javanese Rebab in Relation to its Role in the Gamelan ... ................... Colin Quigley 42 Research Models in Ethnomusicology Applied to the RadifPhenomenon in Iranian Classical Music........................ Hafez Modir 63 New Theory for Traditional Music in Banyumas, West Central Java ......... R. Anderson Sutton 79 An Ethnomusicological Index to The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Part Two ............ Kenneth Culley 102 Review Irene V. Jackson. More Than Drumming: Essays on African and Afro-Latin American Music and Musicians ....................... Norman Weinstein 126 Briefly Noted Echology ..................................................................... 129 Contributors to this Issue From the Editors The third issue of the Pacific Review of Ethnomusicology continues the tradition of representing the diversity inherent in our field. -
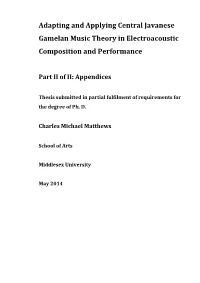
Adapting and Applying Central Javanese Gamelan Music Theory in Electroacoustic Composition and Performance
Adapting and Applying Central Javanese Gamelan Music Theory in Electroacoustic Composition and Performance Part II of II: Appendices Thesis submitted in partial fulfilment of requirements for the degree of Ph. D. Charles Michael Matthews School of Arts Middlesex University May 2014 Table of contents – part II Table of figures ....................................................................................................................... 121 Table of tables ......................................................................................................................... 124 Appendix 1: Composition process and framework development ..................... 125 1.1 Framework .............................................................................................................................. 126 1.2 Aesthetic development ........................................................................................................ 127 1.3 Idiomatic reference .............................................................................................................. 128 1.3.1 Electroacoustic music references .......................................................................................... 129 1.3.2 Musical time .................................................................................................................................... 130 1.3.3 Electronic cengkok and envelopes ........................................................................................ 132 1.4 Instruments and interfaces .............................................................................................. -

Representasi Konsep Patet Dalam Tradisi Garap Gamelan Bali
Vol. 21 No. 1, April 2020: 11-28 Representasi Konsep Patet dalam Tradisi Garap Gamelan Bali I Ketut Ardana1 Prodi Seni, Program Pascasarjana, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ABSTRACT The Representation of Patet Concept in the Working Tradition of the Balinese Gamelan. Patet is an actual problem because it has diversity in the working tradition of the Balinese gamelan. Unfortunately, this diversity is not published and formulated comprehensively into a theory that can explain the patet of the Balinese gamelan. One of the unique patet works raised in this study is the representation of patet in Gamelan Gong Suling. This gamelan is one of the gamelans that does not exist in society. It has flexibility in the concept of gamelan works, especially the problem of patet, which is different from other Balinese gamelan. Therefore, the formulation of the situation in this study is implementing the patet in Gamelan Gong Suling. The research methodology is based on the descriptive analysis method through garap theory. There are two main analysis aspects concerning the work of Gamelan Gong Suling: (1) the tungguhan (instrumens) grouping, and (2) the musical conception. As for the instrumentation, Gamelan Gong Suling is composed of Balinese flutes, kendang, cengceng ricik, kajar, klenang, and gong pulu. Regarding the function of the instruments, Balinese flutes play the melody (bantang gending, bon gending, payasan gending), kendang plays the payasan gending, cengceng ricik plays the pengramen, and gong pulu plays the pesu mulih. The musical concept of Gamelan Gong Suling concerns: garap material, prabot garap or piranti garap, and penentu garap. Regarding the works, Gamelan Gong Suling has a fundamental melody called Bantang Gending; for what concerns to Piranti Garap, Gamelan Gong Suling has five tetekep: tetekep deng, dang, dong, dung, and ding; as for what regards as Penentu Garap, there are four garap styles in Gamelan Gong Suling: garap tabuh petegak, garap prosesi, garap kreasi, and garap dolanan. -

Rwa Bhinneda the Aestetics of Balinese Traditional Music
Arts and Design Studies www.iiste.org ISSN 2224-6061 (Paper) ISSN 2225-059X (Online) DOI: 10.7176/ADS Vol.74, 2019 RWA BHINNEDA THE AESTETICS OF BALINESE TRADITIONAL MUSIC Pande Made Sukerta, I Nyoman Sukerna , Nanik Sri Prihatini Faculty of Performing Art, Indonesia Institute of the Arts Surakarta. Ki Hajar Dewantara Road, No.19 Kentingan, Jebres, Surakarta, Central Java, Indonesia Abstract Karawitan aesthetics was the "spirit" of art which was manifested in the form of three components, namely tungguhan, garap, and jengah . These three components could be regarded as aesthetic forming media which was covered by the concept of rwa bhinneda . Rwa bhinneda were two different things and functioned as elements of balance used in Balinese culture and/or Hinduism which could be used as an umbrella in studying Balinese musical aesthetics. The concept of balance could be interpreted as things that were opposite and always came in pairs. Balinese karawitan aesthetics that were opposite and always came in pairs were related to tungguhan, garap, and jengah . The aesthetic manifestations of Balinese music related to tungguhan were pemade and kantil , pengede and barangan , lanang and wadon , and ngumbang-ngisep (these terms were related to sound). The concept of balance associated with garap were polos-nyangsih, pesu-mulih, galak-manis , and ngumbang-ngisep (these terms were related to dynamics), and aesthetics that were associated with the concept jengah was the number and size of the type of tungguhan used. Jengah was a trait possessed by humans who did not want to be outdone by others. Balinese musical aesthetics could be expressed by its supporters, so that it became an aesthetic statement. -

The Perception and Cognition of Time in Balinese Music
Empirical Musicology Review Vol. 3, No. 2, 2008 The Perception and Cognition of Time in Balinese Music ANDREW CLAY MCGRAW[1] University of Richmond ABSTRACT: This article describes experiments designed to determine the perception and cognition of time-in-music among Balinese gamelan musicians. Three topics are discussed. First, the proposed connections between cultural/religious concepts of time and the construction of (time in) gamelan music are explored. Here a novel and experimental use of the Implicit Association Test is incorporated to explore potential implicit (unconscious) connections between concepts of time-in-music and time-in- general. Only weak associations are found. Second, the author explores music’s influence in subjects’ ability to gauge objective durations. Other than a tendency for Balinese subjects to consistently underestimate actual timings, and the potential for tempo changes to influence response patterns in specific ways, few strong patterns are found. Third, previously proposed models for the performance of tempo changes (here, rallentandos) are explored in the context of gamelan music. Results from perceptual tasks and an analysis of performance suggests that previous idealized models are too simplistic to describe the Balinese case. Submitted 2007 December 18; accepted 2007 February 2. KEYWORDS: Bali, gamelan, time, perception, cognition THE conflation, common in musicology and anthropology, of time-in-music with time-in-general (or, time in cosmological senses) invites all sorts of well-documented problems and paradoxes (see Rowell, 1979, 1985; Mayr, 1985). Given too much time to ponder it, we are easily over-stimulated by certain eccentric truths concerning time: Definitions of time are impossible as nothing resembles it. -

59. Gong Kebyar De Sebatu (Bali) Baris Melampahan
59. Gong Kebyar de Sebatu (Bali) Baris Melampahan (For Unit 6: Further Musical Understanding) Background information and performance circumstances Gamelan Music is deeply embedded in Indonesian (or Javanese) culture. Evidence of the existence of ensembles dates to the eighth-century BCE but it is believed that the Gamelan may have been in use 500 years earlier. In Javanese mythology, a god, Sang Hyang Guru, used a gong to summon other gods and, for more complex messages, he added extra gongs, thereby inventing the Gamelan. There are now three main types of Gamelan music: Javanese, Balinese and Sundanese; it is Balinese Gamelan (from the Indonesian island of Bali) of which Baris Melampahan is an example. Although Gamelan music on Bali is now regularly performed for tourists, it is vital to remember that the principal and original performing circumstances of the music were for ritual and ceremonial purposes. It is also worth noting that Gamelan belongs to the oral (or perhaps more appropriately ‘aural’) tradition of folk music – notation is a tool for analysing the music but the musicians themselves learn by ear and are taught by an instructor (called a sekaha). The term ‘Baris’ means a line or military formation and, in this context, refers to a traditional male war dance of which there are a great many types. The differing titles usually refer to the weapons used in the dance: for example, Baris Bedil uses rifles and Baris Bajra uses clubs. Baris Melampahan, which developed in the early twentieth-century, is an elaborate exception to the norm of Balinese Baris dances. -

VOCABULARY and CONCEPTS Balungan
VOCABULARY AND CONCEPTS Balungan: Melodic outline of a piece, literally refers to the “skeleton” of the melody, and is what is generally notated by musicians and teachers Bubaran: Compositional form of the Central Javanese court city of Yogyakarta, signaling the end of a concert, which uses 16 beats to the gong Buka: Opening phrase of a piece, played by a solo instrument or voice Gatra: Unit of four beats or tones of the balungan, with the last being the “goal” tone Gembyang: Technique in which octaves are sounded simultaneously on one instrument, most often used by the bonang Imbal: Technique where two similar instruments play interlocking parts which form one composite part, most often used by paired saron or demung Irama: Tempo, but also refers to the relationship of the beats of the elaborating instruments to those of the balungan (e.g., 1:1, 2:1, 4:1, etc.) Kepatihan: Cipher system of notation generally used for gamelan music Ladrang: Compositional form which uses 32 beats to the gongan Lagu: Melody, also known as the “inner melody” as it is never directly stated by any one instrument, but is a result of all parts acting together Lancaran: Compositional form which uses 8 balungan beats to the gongan Laras: Tuning system (see slendro and pelog) Mipil: Technique in which an instrument alternates on pairs of notes based on the balungan, most often used by the bonang Ngencot: Technique of striking a key at the same time as damping it Pathet: Mode Pelog: Seven-tone tuning system with small and large intervals Plesedan: Technique for the -

Aspects of Regionalism in Java and Bali by Mike Burns
i Gambang Techniques: Aspects of Regionalism in Java and Bali by Mike Burns A project prepared for a Masters Degree in Ethnomusicology, at the University of New England under the supervision of Drs David Goldsworthy and Andrew Alter Fig 1: Pak Kurnadi playing gambang at Hotel Bentani, Cirebon Prologue He sits at the gambang. The beaters in his hands travel up and down the wooden keys. It is a sound you hear outside the bungalows of Bali, in the wayang kulit of Java, in Sundanese wayang golek, and during the tourist oriented angklung shows. The music is in perpetual motion, but with frequent bounces and syncopations. The tuning is called slendro, the scale with no semitones. Is he making it all up? What patterns are evident, and are the choices his, his cultures or both? Why does this instrument carry so much melody and rhythm? ii Abstract This thesis investigates the use of wood and bamboo keyed xylophones, often known by the name gambang, throughout the islands of Java and Bali; analysing playing styles in the dominant cultural centres of Java (Solo and Yogyakarta), Sunda (Bandung), and of the gambang areas of Bali (Negara and Tenganan), and thus to create broad divisions within the thesis; examining playing patterns from lessons and transcriptions and placing those variations and developments in an historico-cultural context; and examining in particular the xylophone practices of the border regions of Banyuwangi and Cirebon, comparing them with general models for the regions surrounding them, thus seeking signatures distinctive to each area. In so doing the thesis investigates issues of local, regional and national identity, and questions in what ways these have affected the distinctive styles of each area, and whether any dominant cultures (including the West) have changed the old and new traditions of Indonesian gambang playing. -

Cengkok Slendro Manyura Seleh 1
Cengkok Slendro Manyura Seleh 1................................................................................................................................................. 1 Gantung .................................................................................................................................... 1 1/2 Gantung 1 ( 3 5 ) (Sriyatno, Srikaton, Wilujeng)........................................................ 1 Gantung 1 from 1 (Sriyatno)........................................................................................... 1 1/2 Ketuk Kuning 1 gby from 1 ( 6 1 ) (Sriyatno).............................................................. 1 1 gembyang from 2 kempyung..................................................................................................... 1 Dualolo Besar 1 gby from 2 ( 6 3 2 1 ) (Sriyatno) .............................................................. 1 1 gembyang from 3 gembyang ..................................................................................................... 1 Ayu Kuning 1 gby from 3 (. 3 2 5 3 2 1 ) (Puspawarna, Sriyatno)...................................... 1 Dualolo Besar 1 from 3 ( . 2 . 1 ) (Srikaton)..................................................................... 1 1 gembyang from 3 kempyung..................................................................................................... 2 Dualolo Besar 1 gby from 3 ( . 2 . 1 ) (Puspawarna) (tanggung).......................................... 2 Dualolo Besar 1 gby from 3 ( . 2 . 1 ) (Puspawarna, Wilujeng).......................................... -
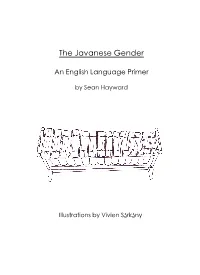
Primer for Javanese Gender
The Javanese Gender An English Language Primer by Sean Hayward Illustrations by Vivien Sárkány The Javanese Gender An English Language Primer by Sean Hayward Illustrations by Vivien Sárkány Foreward This primer is intended to serve as a brief introduction to the Central Javanese gender barung, one of the more complex and important instruments of the gamelan. It will focus specifically focusing on the Solonese style. When I first began learning gender, I did not speak Indonesian. Due to this, I found information about basic technique and patterns to be essentially inaccessible outside of my direct contact with my instructor. My motivation in writing this book is to hopefully relieve some of these difficulties for other students in the same position. This primer is nowhere close to a complete description of the instrument, but I hope it will be helpful nonetheless. Pursuing the serious study of gender is best approached by working directly with a Javanese musician. THE BASICS OF GAMELAN This book will assume some preexisting knowledge about gamelan, and this section will offer a brief review of the necessary terminology and concepts for playing the gender. Javanese gamelan is written using cipher notation called kepatihan. The numbers 1-7 represent pitches. 1 (siji), 2 (loro), 3 (telu), 4 (papat), 5 (lima), 6 (enem), 7 (pitu) These Javanese syllables in underlined italics will be used any time a tone is referred to in the text, exclusing kepatihan examples. This is the common solfege practice in Java. Dots above or below the number indicate the octave (higher and lower respectively), lines over the top of numbers divide the length of the note in half. -

JAVANESE GAMELAN TERMINOLOGY Barry Drummond Gamelan Laras Tentrem
JAVANESE GAMELAN TERMINOLOGY Barry Drummond Gamelan Laras Tentrem Instruments of the Gamelan Gamelan Generic term for ensembles of predominantly percussion instruments of Indonesia, especially in Java and Bali. Bronze is the preferred material for the gongs and metallophones, but brass and iron are used as well. The instruments constituting a complete gamelan in present-day Central Java are: Gong Ageng The largest of the hanging gongs, approximately 80-100 cm in diameter. Gong Suwukan Sometimes called Siyem. Mid-size hanging gongs, approximately 50-60 cm in diameter. Gamelan Terminology 2 Kempul The smallest hanging gongs, approximately 30-40 cm in diameter. Kenong The largest of the horizontal gongs resting on racks. Kethuk and Kempyang Two small horizontal gongs which form a pair. The above instruments form the gong structure in gendhing (musical compositions, see below) with the gong ageng marking the largest sections, called gongan, and the kenong usually dividing these into either two or four sections called kenongan. The kempul, in forms that use them, usually divide a kenongan in half while the kethuk and kempyang mark the pulse of the structure in between stronger beats. In addition, some gamelan have two small hanging gongs (± 25 cm), engkuk and kemong, which, in certain sections and irama (tempo/density level, see below) of slendro pieces, replace the kempyang. Slenthem Sometimes called Gender Panembung since its construction is like the gender described below, i.e., keys suspended over individual tuned resonators. Saron Demung Commonly shortened to Demung. Pitched an octave above the slenthem, its keys, like the other saron, lie atop a trough resonator. -

Musical Genres in Music of Karawitan
Musical Genres in Music of Karawitan Crosswords Between Tradition and New Music Géneros en la música del karawitan Confluencias entre la tradición y la nueva música Bambang Sunarto Indonesia Institut of Arts of Surakarta. (Institut Seni Indonesia Surakarta). Jl. Ki Hajar Dewantara, nº 19. Surakarta, Indonesia. [email protected]. Musical Genres in Music of Karawitan Crosswords Between Tradition and New Music Bambang Sunarto This research ontologically elaborates Este artículo pretende llevar a cabo una on categories of artistic on musical categorización de los modos de composition of karawitan music, composición de la música karawitan, characterized by particular styles. This siendo nuestra intención principal writing is intended to describe musical describir las formas musicales en la vida forms in everyday life in Javanese music diaria de la cultura de Java. La culture. This elaboration was done by identificación y análisis de los identifying and taking apart the componentes de cada uno de los components of any term and musical términos y conceptos musicales, concept as a manifestation of the entendidos como manifestación cultural statements. The outcome of cultural, ha sido uno de nuestros this explanation is a new conception principales objetivos. La investigación and perception of artistic categories ha resultado en una nueva concepción y related to the medium and musical percepción de las categorías artísticas construction. In new creations of relacionadas con el medio y la karawitan music, one can distinguish a construcción musical. De hecho, en las new karawitan with classic/traditional nuevas creaciones de la música nuances, another with popular nuances, karawitan se puede distinguir: un nuevo with reinterpretation, and with an género con características clásico- experimental or explorative nature.