ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev.2 (M) Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve, West Java Indonesia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Detailed Final Report
An urgent conservation call from endemic plants of Mount Salak, West Java, Indonesia I Robiansyah* and S U Rakhmawati Research Center for Plant Conservation and Botanic Gardens - LIPI. Jl.Ir.H. Juanda 13 Bogor 16003, West Java, Indonesia *[email protected] Abstract. Mount Salak is part of Mount Halimun-Salak National Park in West Java, Indonesia. It is home to five endemic plant species that are very susceptible to human interference due to their close proximity to human settlements. The deforestation rate of the area was 1,473 ha or 1.3% of the total area each year. Using eleven line transects with a total length of 44.76 km, the present study aims at providing data on current population and conservation status of these five endemic plant species. The results showed that there was an urgent conservation call from Mount Salak as all five targeted species were unable to be located. Furthermore, two invasive species that might possess serious threat to the endemic plants were observed during the survey: markisa (Passiflora sp.; Passifloraceae) and harendong bulu (Clidemia hirta; Melastomataceae). Based on these results, the present study assigned all the endemic species as Critically Endangered according to the IUCN Red List Category and Criteria. To conserve all the endemic plant species in Mount Salak, several recommendations were given and discussed. 1. Introduction Plants are fundamental part of terrestrial ecosystem and provide support systems for life on earth. For human, plants provide many essential services that underpin human survival and well-being, such as source of food, clothes, timber, medicines, fresh air, clean water, and much more. -

Howcompany Manage Stakeholder Engagement for Sustainable Tourism Development in Indonesia?
The Journal of Society and Media 2019, Vol. 3(2) 237-260 https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index DOI:10.26740/jsm.v3n2.p237-260 HowCompany Manage Stakeholder Engagement For Sustainable Tourism Development In Indonesia? Gayatri Atmadi1* 1Department of Communication Science, Universitas Al-Azhar, Jakarta Selatan, Indonesia Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan, Indonesia Email: [email protected] Abstract The background of this research is that in the past, the increasing trend of mountain climbing in Indonesia has reportedly raised environmental problems, especially regarding the tremendous volume of rubbish left behind mountain climbers. Plastic waste threatens the Indonesia tourism industry in mountain areas. The government stated that the continuously increasing plastic waste threatens to ruin Indonesia's tourism sector. The mineral water industry is one of the government's primary focuses in its plastic waste reduction. As Indonesia's largest plastic-bottled mineral water brand, Aqua is pledging to remove more plastic from the environment than it uses by 2025. The purpose of the research is to get a descriptive analysis of how the company can manage its stakeholder engagement for reducing plastic waste in Indonesia. This research employed a qualitative narrative analysis method with a case study around Aqua’s efforts for reducing plastic waste in Indonesia and data collected from digital media. The principal results of the research show that Aqua made good collaboration between the Trashbag Community Indonesia, The Ministry of Environment and Forestry, and media journalists on the program “Sapujagad 2017" by removing 5 tons of rubbish from Indonesia's mountains. In conclusion, a successful company must do stakeholder engagement and corporate social responsibility activities for supporting sustainable tourism development in Indonesia. -

Final Report
ACKNOWLEDGEMENTS This research is funded by UNESCO/MAB Young Scientist Award grant number SC/EES/AP/565.19, particularly from the Austrian MAB Committee as part of the International Year of Biodiversity. I would like to extend my deepest gratitude to the Man and Biosphere-LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) which was led by Prof. Endang Sukara (President of the MAB National Committee) and at present is substituted by Prof. Dr. Bambang Prasetya, Dr. Yohanes Purwanto (MAB National Committee) for endorsing this research, and Sri Handayani, S.Si. (MAB National Staff), also especially to the Mount Gede Pangrango National Park for allowing to work at Selabintana and Cisarua Resort, and the Carbon team members: Ahmad Jaeni, Dimas Ardiyanto, Eko Susanto, Mukhlis Soleh, Pak Rustandi and Pak Upah. Dr. Didik Widyatmoko, M.Sc., the director of Cibodas Botanic Garden for his encouragement and constructive remarks, Wiguna Rahman, S.P., Zaenal Mutaqien, S.Si. and Indriani Ekasari, M.P. my best colleagues for their discussions. Prof. Kurniatun Hairiah and Subekti Rahayu, M.Si. of World Agroforestry Center, M. Imam Surya, M.Si. of Scoula Superiore Sant’ Anna Italy also Utami Dyah Syafitri, M.Si. of Universiteit Antwerpen Belgium for intensive discussion, Mahendra Primajati, S.Si. of the Burung Indonesia for assisting with the map and Dr. Endah Sulistyawati of School of Life Sciences and Technology - Institut Teknologi Bandung for the great passion and inspiration. i TABLE OF CONTENTS Page LIST OF TABLES iii LIST OF FIGURES iv EXECUTIVE SUMMARY vi -

Formulation of Criminal Provisions in Establishment of Regional Regulation Design in Cianjur Regency
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 21, Special Issue, 2018 FORMULATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATION DESIGN IN CIANJUR REGENCY Kuswandi, Suryakancana University Tanti Kirana Utami, Suryakancana University ABSTRACT Legal development of laws and regulations, especially regional regulations, is marked by the formulation or formulation of criminal provisions. Therefore, the regional regulation is one of the law products, so in order to be binding in general and having effectiveness in the imposition of sanction of criminal law formulation policy should refer to the principles of criminal provisions in general. This paper examines how the procedures for drafting local regulations in Cianjur regency and the formulation of criminal provisions. This research uses normative juridical approach method with descriptive analytical research specification. The result of this research is the formation of the draft of regulation in Cianjur regency in accordance with Law no. 12 of 2011 on the establishment of legislation starting from the preparation of academic texts, public hearings and FGDs and the preparation of substantial draft of local regulations, especially the formulation of criminal provisions that refer to the provisions of criminal law. Keyword: Criminal Provisions, Legal Drafting, Local Regulations. INTRODUCTION Indonesia as a constitutional state is described in the 1945 Constitution. As a State of law, in the administration of the State government is certainly not independent of laws and regulations as a positive law prevailing in Indonesia. Law is a set of rules of conduct prevailing in society (Martosoewignjo, 1992). Cianjur Regency is geographically located in the centre of West Java Province, with a distance of approximately 65 km from the Capital of West Java Province (Bandung) and 120 Km from the State Capital (Jakarta), and is located between 6021-7025 South Latitude and 106042- 107025 east longitude. -
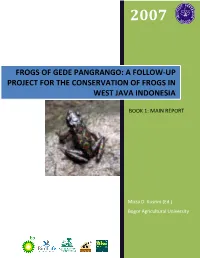
Frogs of Gede Pangrango: a Follow-Up Project for the Conservation of Frogs in West Java Indonesia
2007 FROGS OF GEDE PANGRANGO: A FOLLOW-UP PROJECT FOR THE CONSERVATION OF FROGS IN WEST JAVA INDONESIA BOOK 1: MAIN REPORT Mirza D. Kusrini (Ed.) Bogor Agricultural University Citation: Kusrini, M D. (Ed) 2007. Frogs of Gede Pangrango: A Follow up Project for the Conservation of Frogs in West Java Indonesia. Book 1: Main Report. Technical report submitted to the BP Conservation Programme. Cover photographs: Front cover: The bleeding toad Leptophryne cruentata from Cibeureum, Gede Pangrango Mountain. (Photo: Mirza D. Kusrini) Photo credits: Anisa Fitri: Fig 2-2 below right (p. 14), Fig 2-8 (p. 26), Fig 3-4 (p. 36),Fig 5-1 (p. 51), Fig 5-3 top (p. 53), Fig 6-3 (p. 65) Wempy Endarwin: Fig 2-2 top right & below left (p. 14), Fig 2-10 (p. 28), Fig 3-8 middle & below (p. 41), Fig 4-3 (p. 46) M. Yazid: Fig 3-8 top left (p. 41), Fig 6-3 (p. 65) Adininggar U. Ul-Hasanah: Fig 2-2 top left (p. 14), Fig 3-5 (p. 37), Fig 6-1 top (p. 59), Fig 6-2 (p. 64) Neneng Sholihat: Fig 3-8 top right (p. 41), Fig 4-1 (p. 45), Fig 5-3 below (p. 53), Hijrah Utama: Fig 6-1 below (p. 59) Bogor Agricultural University 2007 – Frogs of Mount Gede Pangrango National Park 1 Contents Acknowledgments 7 Executive Summary 8 Project Fact Sheet 9 Chapter 1. Introduction 10 Chapter 2. The amphibian of Mount Gede Pangrango National Park 11 I. Introduction 11 II. Methods 11 III. -

West Java Geothermal Update
PROCEEDINGS, Thirty-Eighth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 11-13, 2013 SGP-TR-198 WEST JAVA GEOTHERMAL UPDATE Achmad FADILLAH, Tubagus NUGRAHA and Jemmi GUMILAR Energy and Mineral Resources Office, West Java Gov Soekarno Hatta Street, Bandung, West Java, 40286, Indonesia e-mail: [email protected] priority in phase geological survey to prelimenary. ABSTRACT This paper give us image of geothermal growth in Almost 30 years since Kamojang, the first West Java since his early exploration until now. geothermal power plant in Indonesia located in West Beside that, it will explain the regulation that support Java, had produced 30 MWe electricity that makes geothermal development and investment opportunity. West Java become “the oldest brother” for INTRODUCTION geothermal development in Indonesia. Geothermal energy is one of the biggest energy Now after 30 years, West Java geothermal source that used in West Java. It is because development had been advanced with total Energy geothermal energy in West Java make the important Sales Contract reach 2.295 MWe in 8 location and role for that potential in resources or reserves. We have been produce 47% or approximately 1.075 MW know that when Indonesia located along the from Kamojang (200 MW), Darajat (271 MW), Salak legendary Ring of Fire, the Pacific Islands are host to (377 MW) and Wayang Windu (227 MW). The rest some of the largest resources of geothermal energy in 1.222 MW were still develop like Kamojang V, the world. As much as 40% of the world's geothermal Darajat III, Wayang Windu II, Patuha, and Karaha potential is found in Indonesia alone. -
Peta-Pendakian-Tnggp
106o56’30”E 106o57’00”E 106o57’30”E 106o58’00”E 106o58’30”E 106o59’00”E 106o59’30”E 107o00’00”E 107o00’30”E 107o01’00”E 107o01’30”E 715000 716000 717000 718000 719000 720000 721000 722000 723000 Camping Ground Camping Ground Mandalawangi Mandalakitri A MANDALAWANGI 1200 9255000 9255000 Kantor Balai Besar Taman Nasional (CIBODAS) National Park Head Office (Lihat Lembar Peta “Cara Mencapai Lokasi” See Map Page “How To Get To The Location”) Gerbang Mandalawangi Pondok Volunteer Mandalawangi Gate 1300 Kelompok monyet ekor panjang sering terlihat pada ketinggian 1-3 m diatas tanah Long tailed macaque often seen at 1-3 m above the ground 00 01 02 1400 Jam 44’30”S 1 03 o 4 Hour / 44’30”S 06 Cibodas Golf Park 04 Kebun Raya Cibodas o n 05 06 06 Cibodas Botanical Garden e Kadang terlihat Surili 07 Silver leaf monkey often spotted here l Tarentong 08 PETA PENDAKIAN a 09 Air Terjun/ 1430 Curug Ciwalen w 1 Jam 10 9254000 Ciwalen Waterfall 9254000 /4 Hour Habitat Konyal i Konyal habitat VegetasiJamuju Pohon trees Jamuju 12 C Sumber Air: Sungai 13 1500 Letak: Pertemuan antara jalur pengamatan burung dan 1 Jam jalur interpretasi tumbuhan Air Terjun/ /4 Hour Water Source: River Curug Ciismun TREKKING MAP Location: meeting point of birdwatching route and flora 1413 19 18 17 16 interpretation route Ciismun Waterfall 20 Telaga Biru Jembatan | Bridge 1525 Rawa Gayonggong 21 Blue Lake 22 Sumber Air: Sungai Vegetasi Hutan transisi dari Sub-Montana ke Montana 45’00”S o Sumber Air: Sungai 23 1 Water source: River Vegetation transition from Sub-Montane to Montane -

Commodification of Mount Gede Pangrango National Park
The 2nd ICVHE The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 “The Importance on Advancing Vocational Education to Meet Contemporary Labor Demands” Volume 2018 Conference Paper Commodification of Mount Gede Pangrango National Park Khaerul Amri and Awan Sandi Pungkas Department of Literature, Faculty of Humanities, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Abstract Mount Gede Pangrango National Park (TNGGP) is an area of conservation administrator of natural resources and ecosystem located in Bogor, Cianjur, and Sukabumi District, West Java. One of its functions is the development and utilization of environmental service and natural tourism. Commodification of Mount Gede Pangrango was conducted by the government with the intention of increasing country’s income as well as maintaining natural preservation. Concomitant rise of technology and media, especially after the presence of ‘5 cm’ film and social-media activism, mountaineering activity has transformed into a popular activity resulting in a new Corresponding Author: meaning. Its implication is the emergence of new commodification conducted Khaerul Amri by several actors behind TNGGP with a capital accumulation motive in the end Received: 8 June 2018 being to stabilize the new meaning of mountaineering activity. Those actors are Accepted: 17 July 2018 Published: 8 August 2018 private (agencies of mountaineering tourism, volunteer/ranger, product brand), local society, and government – that keep on negotiating and contesting in order to Publishing services provided by Knowledge E commodify the meaning of mountain and mountaineering activity. Then, what are new commodification forms conducted by those actors? How TNGGP is interpreted by Khaerul Amri and Awan Sandi Pungkas. This article is those actors? And what are the kind of negotiation and contestation among them? distributed under the terms of Those questions will be answered in this article. -

Seed Availability Assessment and Seed Collection of Wild Plants in Selabintana Forest, Mount Gede Pangrango National Park, West Java
https://publikasikr.lipi.go.id/ Buletin Kebun Raya 23(1): 36–45, April 2020 e-ISSN: 2460-1519 | p-ISSN: 0125-961X DOI: https://doi.org/10.14203/bkr.v23i1.4 Scientific Article SEED AVAILABILITY ASSESSMENT AND SEED COLLECTION OF WILD PLANTS IN SELABINTANA FOREST, MOUNT GEDE PANGRANGO NATIONAL PARK, WEST JAVA Penilaian ketersediaan biji dan pengoleksian biji tumbuhan dari hutan Selabintana, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat Musyarofah Zuhri*1, Dian Latifah1, Siti Roosita Ariati1, Sudrajat Rahdiana2, Emus2, Cahyadi2 1Research Center for Plant Conservation and Botanic Gardens, Indonesian Institute of Sciences Jl. Ir. H. Juanda No.13 Bogor 16003 West Java, Indonesia. 2Cibodas Botanic Garden PO Box 19 Sindanglaya, Cipanas, Cianjur 43253 West Java, Indonesia *Email: [email protected] Diterima/Received: 15 Januari 2020; Disetujui/Accepted: 30 Maret 2020 Abstrak Banyak kebun raya telah berkontribusi pada pencapaian Target 8 Strategi Global untuk Konservasi Tumbuhan (GSPC) melalui bank biji untuk jenis liar. Bank biji Kebun Raya Cibodas (KRC) sebagai bagian dari Kemitraan Millenium Seed Bank Kew juga mengumpulkan dan menyimpan biji jenis tumbuhan asli Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menilai ketersediaan biji di alam dan mengumpulkan biji yang ada di Hutan Selabintana, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, untuk disimpan di fasilitas penyimpanan biji dalam jangka panjang di bank biji KRC. Jenis yang ditargetkan untuk pengumpulan biji difokuskan pada jenis pohon asli dengan biji ortodok atau mendekati ortodok berdasarkan daftar Database Informasi Biji (SID). Penilaian pra-pengumpulan dan pengambilan sampel individu dalam suatu populasi menggunakan sampling acak. Empat puluh jenis tumbuhan penghasil biji dilaporkan. Karena keterbatasan jumlah biji di lapangan (kurang dari 250 biji), hanya 33 jenis yang dikumpulkan. -

Implementasi Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Sebagai Sumber Belajar Geografi Sma Negeri Di Kabupaten Cianjur
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI SMA NEGERI DI KABUPATEN CIANJUR Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Oleh: Ahmad Hambali NIM : 1111015000068 JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018 KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penulis menyadari, bahwa pengetahuan, pemahaman, pengalaman, kemampuan dan kekuatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu berusaha untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga penyusunan skripsi berjalan lancar. Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 2. Bapak Dr. Iwan Purwanto, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 3. Bapak Drs. Syaripulloh M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 4. Bapak Dr. Teuku Ramli Zakaria, MA., selaku Dosen Penasehat Akademik. 5. Ibu Dr. Jakiatin Nisa, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk dan nasehat kepada penulis dengan ikhlas demi keberhasilan penulis. 6. Seluruh Dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 7. Pemimpin Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam penggunaan sarana perpustakaan. -

First Report on Fungal Symbionts of Lycopodiaceae Root from Mount Gede Pangrango National Park Indonesia
First Report on Fungal Symbionts of Lycopodiaceae Root from Mount Gede Pangrango National Park Indonesia 著者 Takashima Yusuke, Narisawa Kazuhiko , Hidayat Iman, Rahayu Gayuh journal or Journal of Developments in Sustainable publication title Agriculture volume 9 number 2 page range 81-88 year 2014 URL http://hdl.handle.net/2241/00125616 Journal of Developments in Sustainable Agriculture 9: 81-88 ( 2014) First Report on Fungal Symbionts of Lycopodiaceae Root from Mount Gede Pangrango National Park Indonesia Yusuke Takashima1, 2, Kazuhiko Narisawa2, Iman Hidayat3 and Gayuh Rahayu1* 1 Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Bogor Agricultural University, Dramaga Campus, Bogor 16680, Indonesia 2 Graduate School of Agriculture, Ibaraki University, 3-21-1 Chuo, Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki, 300-0393, Japan 3 Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jl. Raya Jakarta-Bogor km 46, Cibinong 16911, West Java, Indonesia Association of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) with plant roots is often stated as critical to the successful establishment and diversification of terrestial plants. Information on AMF associations with Lycopodiaceae, ancient lineages of terrestrial plants, contributes to the understanding of terrestrial colonization of plants. While diversity of AMF and other fungal endophytes of some agricultural plants in Indonesia is extensively studied, terresterial Lycopodiaceae are not well documented. In this study, colonization status of AMF and root endophytic fungi (REF) in sporophytes of terresterial Lycopodiaceae (Huperzia selago, H. serrata and Lycopodium clavatum) inhabiting Mt. Pangrango at different altitudes were investigated on the basis of root microscopic observations and culture-dependent methods, respectively. As results, AMF colonization was observed in H. -

Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penata Kelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur
......... / ILMU ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN AKHIR TAHUN PENELITIAN PRODUK TERAPAN Tahun Anggaran 2017 (Tahap I ) KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATA KELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI CIANJUR SELATAN KABUPATEN CIANJUR Tahun ke 1 dari Rencana 2 Tahun Ketua Tim Peneliti Dr. Yaya Mulyana, A. Aziz NIDN 0429076401 Anggota Tim Peneliti Drs. Abu Huraerah, M.Si NIDN 0404026201 DRS. Ediyanto, M.Si NIDN 0023095901 LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2017 Dibiayai oleh : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Abstrak Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor yang terus-menerus dikembangkan pemerintah sebagai sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait. Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan