Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Potensi Penelitian Etnobotani Di Sulawesi Tengah Indonesia (Potencial of Ethnobotanical Studies in Central Sulawesi Indonesia)
Online Journal of Natural Science Vol 5(2) :111-131 ISSN: 2338-0950 Agustus 2016 Potensi Penelitian Etnobotani Di Sulawesi Tengah Indonesia (Potencial of Ethnobotanical Studies in Central Sulawesi Indonesia) Ramadhanil Pitopang1) dan Pandji Anom Ramawangsa2) 1)Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, Kampus Bumi Tadulako Palu Sulawesi Tengah 2)Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah . Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Trans Sulawesi km 9 Palu ABSTRACT Central Sulawesi is one of the provinces in Indonesia which is located in the "heart" of Wallacea biogeography region, an area that has the potential of unique biological resources rich in endemic flora and fauna. However, this potential especially plant biodiversity has not been revealed from various aspects of knowledge, especially from the aspect of ecology, taxonomy, conservation and utilization of plants by the local for their daily need. The province is inhabited by 19 ethnic groups different in cultures, languages and traditional knowledge system. Based on number studies that have been conducted showed that each ethnic group has local knowledge systems in using plants to meet their daily i.e. for building materials, food and beverages, pharmaceuticals and cosmetics, condiments and spices, natural coloring, forage, ornamental plants, ropes, as a complement to the traditional rituals, hunting, agriculture, household utensils and other necessities. This paper discusses the potential of plant biodiversity and ethnobotany research in Central Sulawesi Keywords: Potencial, Ethnobotanical studies, Central Sulawesi. ABSTRAK Sulawesi Tengah adalah salah satu propinsi di Indonesia yang secara biogeografi terletak di “jantung”nya Wallacea, sebuah kawasan yang memiliki potensi sumberdaya alam biologi yang unik kaya dengan flora-fauna endemik. -

W Orking P Aper Sa Jogyo Ins Titute N O. 1 | 20
5 1 o. 1 | 20 e N titut o Ins jogy Cagar Alam, Modal, dan Adat “Konsesionalisasi” dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah aper Sa Andika orking P W Working Paper Sajogyo Institute No. 1 | 2015 Cagar Alam, Modal, dan Adat “Konsesionalisasi” dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah Oleh: Andika Tentang Sajogyo Institute Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita- cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan bangunan rumah beserta isinya. Sajogyo Institute’s Working Paper No. 1 | 2015 © 2015 Sajogyo Institute Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial. Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka: Andika. 2015. “Cagar Alam, Modal, dan Adat: “Konsesionalisasi” dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali Suawesi Tengah”. Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 1/2015. Sajogyo Institute, Bogor. ISSN Digital : 977-2338-0700-17 ISSN Cetak : 977-2338-1116-35 Sumber foto sampul depan: Masyarakat Adat Tau Taa Wana. Gambar diambil dari: kotahujan.com Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini. -

Sfafe, in Addition to Explaining the Maintenance and Development of the Sub-National Citizenship Identity of Tau Taa Vana
PENGAKUAN HAK.HAK KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAU TAAVANA DI TOJO UNA.UNA SULAWESI TENGAH CITIZENSHIP R'GHTS OF INDEGENOUS PEOPLES "TAU TAAUANA" IN TOJO UNA-TJNA, CENTRAL SULAWESI M. Alie Humaedil Naskah diterima tanggal 28 Agustus 2012, disetujui tanggal 12 Oktober 2012 Abstract The indigenous people's of Tau Taa Vana in CentralSulawesi hold customary law ctubbed to death, which is replaced with fines they relate to the mythology of Kaiu Marangkaa. Through this mythology, the customary lawthatwas oiginally composed of the power of kingdom of the Temate centuries ago remain present. While, the power of lndonesia, as the reflection of state formally eliminated, especially the recognition of social and culturat life, for example, KTP (lD cards) are not given to them. With so many cases of "illegal" citizenship and its socla/ and cultural specificity, the Tau Taa Vana communities, lndonesia is only imaginary.Ihis rarses the question what is the concept of citizen for them. Through in-depth interuiews and participatory obseruations from 2009-201 2, periodically, 2 months a year, conducted, this ethnographic researches attemptto explainsthe growth of loyalty and ideals of the nation sfafe, in addition to explaining the maintenance and development of the sub-national citizenship identity of Tau Taa Vana. Keywords: tndigenous people, citizenship, Tau Taa Vana, Toio Una-Una, Central Su/awesi lmaginary lndonesia. 1 peneliti Bidang Kajian Budaya dalam persoalan kemiskinan, kebencanaan dan masyarakat adat terpencil (dan terpinggirkan), Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, email: [email protected]; dan [email protected]. Citizenship Rights of....... 329 Abstrak Komunitas Adat TerpencilTau Taa Vana di Sulawesi Tengah memegang hukum adat sakumpuli dan diganti dengan givu ada bayar yang dihubungkannya dengan mitologi Kaiu Marangkaa. -

Prosiding Seminar Nasional Ekosistem Unggul
PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKOSISTEM UNGGUL MEMBANGUN HUTAN SEBAGAI EKOSISTEM UNGGUL BERBASIS DAS: JAMINAN PRODUKSI, PELESTARIAN, DAN KESEJAHTERAAN YOGYAKARTA, 23 AGUSTUS 2018 DILAKSANAKAN OLEH : FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 MEMBANGUN HUTAN SEBAGAI EKOSISTEM UNGGUL BERBASIS DAS: JAMINAN PRODUKSI, PELESTARIAN, DAN KESEJAHTERAAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKOSISTEM UNGGUL YOGYAKARTA, 23 AGUSTUS 2018 DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 2 DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA MEMBANGUN HUTAN SEBAGAI EKOSISTEM UNGGUL BERBASIS DAS: JAMINAN PRODUKSI, PELESTARIAN, DAN KESEJAHTERAAN Penyunting: Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc. Dr. Ir. Lies Rahayu Wijayanti Faida, M.P. drh. Subeno, M.Sc. Dr. Much. Taufik tri Hermawan, S.Hut., M.Si. Ir. Retno Nur Utami, M.P. Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.ES. Dr. Soewarno Hasan Bahri, M.S. Hero Marhaento, S.Hut., M.Si Kristiani Fajar Wianti, S.Hut., M.Si. Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Si Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si. Sandy Nurviannto, S.Hut., M.Si Frita Kusuma Wardhani, S.Hut., M.Sc. Ferrieren Curassavica Arfenda, S,Hut., M.Sc. Desain Layout dan Sampul: Muhammad Chrisna Satriagasa, S.Si., M.Sc., M.Ec.Dev. Ikhwanudin Rofii, S.Hut. Penerbit: Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 612102, 550641, Faks (0274) 550641 Cetakan -
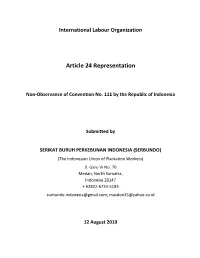
Ompu Ronggur ILO111 Submission
International Labour Organization Article 24 Representation Non-Observance of Convention No. 111 by the Republic of Indonesia Submitted by SERIKAT BURUH PERKEBUNAN INDONESIA (SERBUNDO) (The Indonesian Union of Plantation Workers) Jl. Garu VI No. 70 Medan, North Sumatra, Indonesia 20147 + 62822-6733-5183 [email protected]; [email protected] 12 August 2019 CONTENTS PAGE I. INTRODUCTION 1 II. FACTS 12 A. The Ompu Ronggur Indigenous Community 12 1. History, Social Organization and Customary Land Tenure 12 2. Traditional Occupations 17 B. Discriminatory disregard for Ompu Ronggur’s Rights in Favour of TPL 18 1. The TPL Concession 21 2. Ongoing Encroachment on and Destruction of Community Lands and Resources 22 3. Long-Standing and Persistent Disregard for Complaints made by Ompu Ronggur 23 4. Permanent Insecurity and Impunity 24 C. Discriminatory Impairment and Nullification of the Ompu Ronggur’s Traditional and “Particular” Occupations 25 1. Agro-forestry 26 a. Benzoin Resin Harvesting 26 b. Rice Farming 29 c. Timber Harvesting and Woodcarving 29 2. Hunting 30 3. Floor mat and tandok manufacture and sale 32 4. Traditional governance occupations 33 D. Indonesian Law Discriminates against Indigenous Peoples and their Rights 36 1. The Constitution 39 2. Land Laws 42 a. The Basic Agrarian Law 42 b. The 1999 Forestry Law 44 4. Constitutional Court Decision No. 35: Unfulfilled Promise 45 III. VIOLATIONS 47 A. Preliminary 47 1. Temporal Jurisdiction 47 2. Interdependent and Interconnected Rights 49 B. Specific Violations 55 1. Article 1 55 a. Indonesia’ treatment of Ompu Ronggur is consistent with the definition of discrimination in C111, Article 1 56 b. -

Givu As Criminal Sanctions Tau Taa Wana Indigenous People and Its Relevance to the National Criminal Justice Reform
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by International Institute for Science, Technology and Education (IISTE): E-Journals Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.23, 2014 Givu as Criminal Sanctions Tau Taa Wana Indigenous People and its Relevance to The National Criminal Justice Reform M. Hatta Roma Tampubolon 1 Moch. Munir 2, I Nyoman Nurjaya 3, Suhariningsih 4 email: [email protected] Abstract Givu are implemented in traditional law society Tau Taa Wana is customary reaction in order to create balance and harmony between the living world and the unseen world, between human groups and individuals, as well as the fellowship (community) and society at large. Givu is a nature of mind of the basis traditional and customary law community legal awareness Tau Taa Wana. Such ceremonies clean village (village) with the aim to restore balance and perceived disruptive magical powers such rituals in the criminal justice system palampa customary Tau Taa Wana. The basic ideas of the customary criminal sanctions have not been studied in depth and accommodated to the maximum in the national legislation. Indigenous groups implement criminal sanctions customary law is not merely to uphold the image of the customary criminal law and maintain social harmony, but also to show, that the indigenous peoples still exist with cultural pluralism, in particular legal pluralism. Keywords : Customary Law, Indigenous People, Givu, Tau Taa Wana, the National Criminal Justice Reform. 1 . INTRODUCTION Philosopher Cicero called the " ubi Societas, Ibi ius", where there are people, there is a law. -

Antimicrobial Effect of Medicinal Plants Used in Traditional Indonesian Medicine
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE Faculty of Tropical AgriSciences Department of Crop Sciences and Agroforestry Antimicrobial effect of medicinal plants used in traditional Indonesian medicine DOCTORAL THESIS Author: Andreas Romulo Supervisor: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 2018 ACKNOWLEDGMENT I would like to express my gratitude towards my exceptional supervisor prof. Ladislav Kokoška, Ph.D. for his sincere guidance, encouragement, and patience over the last three years. Thank you for giving me the opportunity to do research in the Laboratory of Ethnobotany and Ethnopharmacology. Your continuous support, insightful comments, suggestion, and critical analysis of the research and writing of this dissertation were essential for completion of my study and the success of my future career. I would like to thank Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D. for the support and helpful assistance in laboratory research and academic background, as well as to my fellow labmates, Ing. Markéta Houdková and Ing. Marie Netopilová who helped and contributed in the experiment. My special thanks to Ing. Klára Urbanová, Ph.D. and Ing. Pavel Nový, Ph.D. for their sincere help, guidance, and suggestion during the analysis of the essential oil. Finally, I would like to thank to my beloved parents and friends for their continues support, encouragement, and pray. I am so grateful to have you all. This research was financially supported by Erasmus Mundus project ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) [55207], Czech University of Life Sciences Prague Grant Agency project CIGA [20175001] and Internal Grant Agency project IGA [20175020]. II CERTIFICATION I, Andreas Romulo, submitted this dissertation for Ph.D. -

Buku PRAKTIK CERDAS
Kiat Praktis Identifikasi, Dokumentasi danPromosi Praktik Cerdas pelampung, botol bekas ini sangat kuat, elastis, ringan, mudah diperoleh, terjangkau serta dapat digunakan berulang-ulang. 3. Inovasi pada pembenihan tanaman jati lokal dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan. Secara teori, benih yang akan disemai terlebih dahulu ditabur pada bedengan kemudian dibakar, namun cara tersebut memiliki tingkat keberhasilan hanya 40% untuk tumbuh. Praktik pembenihan yang dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan adalah melalui pemberian perlakuan terhadap benih sebelum disemai. Benih terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung yang berongga dan mudah menyerap air. Kemudian benih di dalam karung direndam ke dalam pembuangan penampungan air atau ke dalam air berlumpur selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Keesokan harinya benih ditaburkan ke bedeng yang telah disiapkan. Teknik lain yang juga biasa dilakukan yakni perendaman benih dengan air panas selama minimal tiga hari tiga malam, di mana setiap pagi benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari dan di sore hari dilakukan lagi perendaman sampai esok hari untuk penjemuran. Proses dilakukan selama tiga berturut-turut. Metode bertujuan untuk memudahkan pertumbuhan kecambah pada benih jati tersebut. Cara ini memiliki 85% tingkat keberhasilan tumbuh. Praktik persemaian yang dilakukan oleh para kelompok perempuan petani jati sudah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun. Di tahun ketiga, kegiatan persemaian jati kelompok perempuan sudah mempunyai kebun benih sendiri dengan 31 Buku Panduan usia bibit jati yang dimiliki kelompok perempuan di kebun benih sudah berumur kurang lebih 3 tahun dan tinggi pohon bibit Jati tersebut sudah mencapai sekitar 6 meter. Kebun benih milik kelompok ini adalah sebanyak 4 buah yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa, yakni Kecamatan Laynea yang terdiri dari Desa Aoreo dan Desa Pamandati, serta Kecamatan Laeya yang terdiri dari Desa Lambakara dan Desa Ambalodangge di Kabupaten Konawe Selatan. -

Dynamics of Legal Recognition in Indigenous Peoples Under Law of Forestry Construction
Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44, 2015 Dynamics of Legal Recognition in Indigenous Peoples Under Law of Forestry Construction M. Hatta Roma Tampubolon Doctor and Lecturer of Law Faculty, Tadulako University, Research fields: legal antropology. Abstract Political developments and the struggle of indigenous peoples and indigenous as well as supporters in the national and international levels, created the ILO Convention No. 169 commonly known as the "Convention on Indigenous People Right", namely the convention on indigenous peoples and indigenous people in independent countries. The Convention was approved by 328 countries, one State against and 49 countries abstained, which underlines the implementation of human rights in general for the community customary law, also establishes the right to determine the identity, as well as determining the appropriate education of their values. They are entitled to decide the shape and development priorities, including the right to refuse development. ILO Convention 169 states customary law communities have the right to land and natural resources. Recognition of indigenous peoples, especially the juridical recognition is inseparable from the political dynamic, both in the context of national politics, cultural and political development in general. Therefore, some rules legislation issued sometimes showing obscurity recognition, or even to the efforts denial to the existence of indigenous peoples. State law and local law is the legal system that in reality there is. The state does have the right to make the adjustment to its citizens, but it does not mean that the existing legal system in the community should be replaced in its entirety by the legal system of the country. -

Use Style: Paper Title
Volume 5, Issue 2, February – 2020 International Journal of Innovative Science and Research Technology ISSN No:-2456-2165 The Culture of Resistance of the Indigenous People of Wana Posangke Zaiful, Sulaiman Mamar, Surahman Cinu, Roslinawati Universistas Tadulako, Palu, Central Sulawesi, Indonesia Abstract:- This research aims to explain the structural geographical isolation of the Wana to be an administration pressures that have led to the emergence of resistance problem, the Dutch tried eo ease the task government by movement of the Tau Taa Wana against out-groups and moving the Wana population into coastal settlements, just also to explain the culture of resistance of Tau Taa as the Indonesia government much leter attempted to do I Wana as a result of structural pressure. This research refer here to the suku terasing project development in the uses a qualitative methode with a case study approach. 1970s under the auspices of the social department” This research was carried out in the Tau Taa Wana Posangke indigenous community in North Morowali In line with that, the study of Alvard also found that Regency, Central Sulawesi-Indonesia. Informants or unilateral decisions by the Indonesian government caused resources persons were selected purposively. Data Tau Taa Wana to be exluded by state policy from collection is carried out through activities such as generation to generation. Alvard [2] stated that “The observation, indepth interview, focus group discussion lowlands have historically been an area of unsettled and library study. To see structural pressure and political animosities. It is unclear for how many years the resistance patterns, descriptive analysis are used to Wana have inhabited the area, although it has probably obtain inductive conclusions. -

Tradisi Pelestarian Hutan Masyarakat Adat Tau Taa
TRADISI PELESTARIAN HUTAN MASYARAKAT ADAT TAU TAA VANA DI TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH (The Forest Conservation Tradition of Indigenous People of Tau Taa Vana in Tojo Una-Una Central Sulawesi)* M. Alie Humaedi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha Lantai 6/9 Jalan Gatot Subroto 10 Jakarta 12190; e-mail: [email protected] *Diterima : 7 Februari 2012; Disetujui : 21 Agustus 2013 Bismark; Kuntadi; Wayan; Hesti ABSTRACT Forests, as an important part of biodiversity is known to have the value of direct benefits, indirect benefits value, and non-use value, which is not simply interpreted as commercial use only. The last value includes the value of civilization heritage, cultural and environmental existence and its people. This study aims to uncover the values and philosophy of life inherent in the social and culture system that gave birth to the tradition of environmental preservation from indigenous peoples of Tau Taa Vana in Tojo Una-una, Central Sulawesi. The results showed that forest conservation is closely linked with their view of the sick, and their illnesses healing practices. Forests are not only oriented towards the fulfillment of the necessities of life, but the forest also is an expression of the balance of God, nature and human, and keep the existence of life, especially in bakum valia and mobolong medical practice who use medicinal plants and healing rituals. Forest, besides perceived as a source of disease, also as the center of healing sickness and disease. Keywords: Indigeneous people, Tau Taa Vana, the practice of medicine tradition, bakum valia, mobolong ABSTRAK Hutan, sebagai bagian terpenting biodiversitas dikenal memiliki nilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung, dan nilai lain yang tidak sekedar diartikan secara komersial. -

Kawistara AGUSTUS 2020.Indd
ISSN 2088-5415 (Print) ISSN 2355-5777 (Online) https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index https://doi.org/10.22146/kawistara.58018 JURNAL KAWISTARA VOLUME 10 No. 2, 22 Agustus‑ 2020 Halaman 221—233 HYBRID INTERNAL MIGRATION: THE FACTORS OF MIGRATION FOR EDUCATION AMONG WANA TRIBE COMMUNITY IN CENTRAL SULAWESI MIGRASI INTERNAL HIBRID: FAKTOR-FAKTOR MIGRASI UNTUK PENDIDIKAN DI KALANGAN MASYARAKAT SUKU WANA, SULAWESI BARAT (1)Kim Yong Chan dan Titi Susilowati Prabawa (2)* Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Submitted:22-07-2020; Revised: 29-09-2020; Accepted:29-09-2020 ABSTRAK Berdasarkan wawancara dengan warga desa yang bermigrasi dari suku Wana yang tinggal di Sulawesi Tengah di Indonesia, penelitian ini membahas tentang faktor yang mendorong migrasi ke kota untuk tujuan pendidikan. Kami menemukan bahwa orang tua mengarahkan anaknya pindah ke kota untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari orang tua maupun generasi angkatan mereka secara langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan untuk migrasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa migrasi generasi muda di daerah asal ditentukan oleh tiga faktor pendorong terkait dengan pengalaman migrasi orang tua di kota. Keputusan untuk migrasi suku Wana ke kota besar di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya untuk meningkatkan status sosial mereka, tetapi dalam rangka mengupayakan perubahan status ekonomi, peningkatan pendidikan, dan fasilitas di daerah asal. Secara umum, artikel ini menggambarkan alasan psikologis dan tantangan generasi orang tua suku Wana ketika berjuang mendorong anak-anak mereka untuk pergi ke kota besar dengan tujuan memperoleh pendidikan. Kata Kunci: Migrasi pendidikan; Pengambilan keputusan; Proses migrasi; Pengembangan masyarakat; Suku Wana. *Corresponding author: [email protected] Copyright© 2020 THE AUTHOR (S).