RESPONS ULAMA ACEH TERHADAP AL-QUR'a>N AL-KARI
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![Bernama[8April2013]Saifuddin Nasution Antara Empat Muka](https://docslib.b-cdn.net/cover/3902/bernama-8april2013-saifuddin-nasution-antara-empat-muka-3902.webp)
Bernama[8April2013]Saifuddin Nasution Antara Empat Muka
Saifuddin Nasution Antara Empat Muka Baharu PKR Bertanding Di Kedah Bernama 8 April, 2013 SUNGAI PETANI, 8 April (Bernama) -- Parti Keadilan Rakyat (PKR) menyenaraikan empat muka baharu dan seorang penyandang bagi mempertahankan lima kerusi parlimennya di Kedah pada pilihan raya umum ke-13 ini. Mereka termasuk Setiausaha Agungnya Datuk Saifuddin Nasution Ismail yang akan bertanding di kerusi Parlimen Kulim/Bandar Baharu. Saifuddin merupakan penyandang kerusi Parlimen Machang, Kelantan. Ketika berucap pada satu ceramah di Bandar Laguna Merbok dekat sini malam tadi, Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan Naib Presiden parti N. Surendran sebagai calon di kerusi Parlimen Padang Serai. Dua lagi muka baharu ialah Ketua Wanita Cabang Sungai Petani Nor Azrina Surip @ Nurin Aina Abdullah (Parlimen Merbok) dan Ketua PKR Cabang Kuala Kedah Dr Azman Ismail (Kuala Kedah), manakala Datuk Johari Abdul kekal bagi mempertahankan kerusi Parlimen Sungai Petani. Pada pilihan raya umum 2008, PKR menang di lima daripada tujuh kerusi parlimen yang ditandinginya. Mereka tewas di kawasan Parlimen Alor Setar dan Langkawi. Di kerusi Parlimen Merbok, PKR menang menerusi Datuk Rashid Din yang menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Tajul Urus Mat Zain dengan majoriti 3,098 undi. Kerusi Parlimen Kulim/Bandar Baharu dan Padang Serai pula masing-masing dimenangi menerusi Datuk Zulkifli Noordin dan N. Gobalakrishnan namun kedua-duanya bertindak keluar parti selepas itu dan menjadi Anggota Parlimen Bebas. Bagi kerusi Parlimen Sungai Petani, Johari menewaskan bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin manakala kawasan Parlimen Kuala Kedah dimenangi oleh Ahmad Kasim. Anwar baru-baru ini mengumumkan Ketua Biro Perundangan PKR Gooi Hsiao Leung sebagai calon di kerusi Parlimen Alor Setar tetapi mendapat bantahan DAP Kedah yang turut mahu bertanding di kerusi itu. -
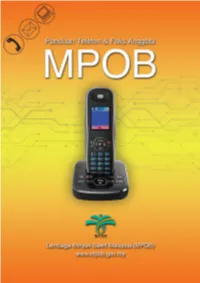
Buku-Telefon-2019.Pdf
Nama E-mel Talian Sambungan Terus i Nama E-mel Talian Sambungan Terus ii Nama E-mel Talian Sambungan Terus KANDUNGAN Pejabat Ketua Pengarah; Pejabat Timbalan Ketua Pengarah; 1 Unit Audit Dalam; IMPAC; Unit Pelestarian, Pemuliharaan & Pensijilan Bahagian Teknologi Maklumat & Khidmat Korporat 4 Bahagian Pengurusan Kewangan & Pembangunan 8 Bahagian Penyelidikan Biologi 15 Bahagian Pusat Kemajuan Bioteknologi & Biakbaka 24 Bahagian Penyelidikan Integrasi & Pengembangan 29 Bahagian Ekonomi & Pembangunan Industri 33 Bahagian Pelesenan & Penguatkuasaan 36 Bahagian Penyelidikan Pembangunan Produk & Khidmat Nasihat 39 Bahagian Penyelidikan Kejuruteraan & Pemprosesan 44 Bahagian Kemajuan Teknologi Oleokimia 48 Stesen Penyelidikan 51 Pejabat Wilayah 52 Talian Utama Pejabat 54 Sambungan Lain di Ibu Pejabat 55 Panggilan Kecemasan 57 Nombor Telefon Bimbit Pegawai Utama MPOB 58 iii Nama E-mel Talian Sambungan Terus PANDUAN PENGGUNAAN TELEFON 1. Operator: Dail 0 @ (03-8769 4400) 2. Pindahan Panggilan: Tekan butang FLASH diikuti no. sambungan. 3. Sila beritahu operator apabila membuat panggilan jauh persendirian. 4. Pohon rancang dan ringkaskan semua percakapan telefon. Semua maklumat telah disemak oleh Bahagian/Unit masing-masing dan tepat semasa percetakan. Diterbitkan pada April 2019. iv Nama E-mel Talian Sambungan Terus Pej. KP Pej. PEJABAT PENGERUSI • IBU PEJABAT (Faks: 8925 9446) Mohd Bakke Salleh mohdbakke@ 4401 8769 4401 / 8925 8464 (Tan Sri Dato’ Seri) Nurul Hanis Abd Rahman nurulhanis@ 4228 PEJABAT KETUA PENGARAH • IBU PEJABAT (Faks: 8925 9446) -

3Rd ISME International Colloquium 2016
• colloquium Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Heritage 2016 Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Heritage 3rd ISME International Colloquium 2016 proceeding book 27&28 Universiti December Teknologi MARA, 2016 Melaka, Malaysia. • Empowering Loesl Mind In Art DfJSlgn & CuffulBl H.rlttJg8 2016 Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Heritage 3rd ISME International Colloquium 2016 EDITORS AND COMPILERS: Dr. Azahar Harun Dr. Rosli Zakaria Dr. Abd Rasid Pn. Haslinda Abd Razak Pn. Liza Marziana Mohammad Noh En Nadzri Mohd Sharif En. Shaleh Mohd Mujir Pn Fatrisha Mohamed Yussof Pn Anith Liyana Amin Nudin Pn lIinadia Jamil Cik Fazlina Mohd Radzi Cik Aidah Alias Cik Nurkhazilah Idris COVER DESIGN: Norsharina Samsuri PUBLISHED BY: Faculty of Art & Design, UiTM Melaka KM26 Jalan lendu. 78000 Alor Gajah, Melaka Tel: +606 - 55820941 +60655821901 +6065582113 Email: [email protected] Web: http://isme2016.weebly.com ISBN: 978-967-0637-26-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted In any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder. • Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Heritage 2016 Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Heritage 3rd ISME International Colloquium 2016 Copyright © 2016 Faculty of Art & Design, UiTM Melaka KM26 Jalan Lendu, 78000 Alor Gajah Melaka http://isme2016.weebly.com Content 1 Personification in Marketing Communication: Case Study of Malaysian Brands 9 Azahar Harun, Mohamed Razeef Abd Razak, Russlan Abd Rahim, Lili Eliana Mohd Radzuan, Amina Syarfina Abu Bakar 2 The Image of Man after September 11 21 Mohd. -

Transparency & Integrity Form Strong Economy
www.selangorkini.my Media_Selangor MediaSelangor selangortv.my FREE ENGLISH EDITION MARCH 2017 #SmartSelangor At the State Assembly TRANSPARENCY & INTEGRITY FORM STRONG 2 - 4 ECONOMY I am very glad that the Selangor and Taipei sign MoU principles, which I mentioned earlier, underlies the State Government’s administration and inject confidence in investors to maintain Selangor as an 7 investment destination HRH Sultan of Selangor Selangor vital to Malaysia's economy 12 FULL REPORT PAGE � FULL REPORT PAGE � First Session, �th Term of the ��th Selangor State Assembly � Report by: Hafizan Taib, Nazli Ibrahim, Afix Redzuan, Lizawati Madfa, Norhayati Umor, Syasya Sufian, Ermizi Muhamad Photo by : Asri Sapfie, Raheemie Arifin & Shuaib Ayob Selangor main GDP contributor SHAH ALAM - His Royal Highness the Sultan of Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah praised the State Government’s commitment to improve the economic level of the state in line with the Membangun Bangsa dan Memakmur Negeri agenda. He said that as the main contributor to Malay- sia’s Gross Domestic Product (GDP), Selangor is vital in ensuring that Malaysia achieves the sta- tus of a high-income nation come 2020. “Selangor’s economy is a main indicator of Malaysia’s economic performance as the state dominates the manufacturing, construction and service sectors,” he said. The Sultan also praised the State Govern- ment’s efforts of successfully lifting Selangor from the poverty line, and recording a 0.2% pov- erty incidence compared to the country’s rate of 0.6%. The Sultan said that the situation reflects Selangor’s economic achievement and its resil- ience even when faced with challenges. -

February 11, 2016 the Honorable Mr. Barack Obama President of The
February 11, 2016 The Honorable Mr. Barack Obama President of the United States of America The White House 1600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20500 Dear Mr. President, As members of parliament from Southeast Asia, dedicated to the promotion and protection of human rights, we write to express our desire for you to make discussion of human rights and the democratic aspirations of the people of ASEAN a priority during the upcoming summit at the Sunnylands estate in California on 15-16 February 2016. As you are surely aware, democracy is struggling in Southeast Asia. Many countries in our region have taken dramatic steps backward in the past two years. While Southeast Asia appeared to be on the cusp of a genuine political transformation only a few years ago, more recently the region has instead witnessed military takeovers, the rollback of fundamental rights, intensifying government-sponsored discrimination against ethnic and religious minorities, and the increasing persecution of activists and opposition voices, including fellow parliamentarians. These setbacks constitute a fundamental threat to the future of the ASEAN Community and the US relationship with it. While we recognize and understand your administration’s desire to strengthen trade and security cooperation with Southeast Asian governments, we urge you to proceed with caution. Human rights, democracy, and basic dignity cannot take a backseat to economic or security prerogatives. Open dialogue on fundamental political and rights-based questions is vital to ensuring the sustainability of bilateral relationships and promoting broad-based benefits of trans-Pacific cooperation. When you sit down with ASEAN leaders in California, we urge you to press them on unfulfilled human rights commitments and to directly raise specific concerns with them. -

Selamat Datang Ke
Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke- VIII 2013 JADUAL PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERKEM VIII 2013 Sesi 1A – Bilik Pontian, Aras 7 (3.30 – 5.30 pm | 7 Jun 2013) EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM Pengerusi Sesi: Dr. Mohd Adib Ismail 1A-1 Penjanaan Semula Ekonomi Asnaf: Cadangan Perniagaan Sosial Najwa Mohd Khalil, Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad 1A-2 Muzara'ah Muntahiyah Bittamlik (MUMBIT): Produk Pembiayaan Hartani kepada Usahawan Tani Kecil Mohd Danial Mohd Razali @ Busu, Sanep Ahmad 1A-3 Kadar Sewaan dalam Instrumen Pembiayaan bagi Kontrak Ijarah di Perbankan Islam Nurfarhana Mohd. Daud, Abdul Ghaffar Ismail 1A-4 Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad 1A-5 Pengurusan Hutang Lapuk di Perbankan Islam Merentasi Kitaran Ekonomi Nur Ainina Mohd Fauzi, Abdul Ghaffar Ismail Sesi 1B – Bilik Muar, Aras 7 (3.30 – 5.30 pm | 7 Jun 2013) EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM Pengerusi Sesi: Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai 1B-1 Perbandingan Kaedah Penyelesaian Kemungkiran (Default) dalam Pembiayaan Rumah di Perbankan Islam Siti Saidatul Akmal Arishin, Abdul Ghaffar Ismail 1B-2 Keperluan Kecairan di Perbankan Islam di Malaysia Nur Amalina Saidan, Abdul Ghaffar Ismail 1B-3 Pengurusan Dana Unit Amanah Islam MAAKL Mutual dan Public Mutual: Suatu Perbandingan Suhailah Jaafar 1B-4 Analisis Perkembangan Produk Sukuk Korporat Islam di Malaysia pada Tahun 2000 hingga Tahun 2012 Ima Ibrahim, Sanep Ahmad, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai 1B-5 Kaitan antara Latihan Pengurusan Bakat dengan Prestasi Kerja dalam Sektor Perbankan Islam Siti Zarina Mohd Ghazali, Azman Ismail 10 Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke- VIII 2013 Sesi 1C – Bilik Mersing, Aras 7 (3.30 – 5.30 pm | 7 Jun 2013) PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI Pengerusi Sesi: Dr. -

EDISI 50 •7 MEI - 13 MEI 2017 • Amanah Pakatan Harapan Sedia Hadapi PRU 14 ELEPAS Pas Meninggalkan Umum Nanti Untuk Melawan BN
Pilih pemimpin atas semangat Putus hubungan dengan Jahanam PAN fastabikul khairat - Presiden Keadilan cuma acah-acah 7 12 dan ribut: BIL 50 7 - 13 MEI 2017 PP18978/03/2016(034450) Maafkan mereka, doakan mereka UNTUK AHLI SAHAJA Jangan 'kebuloq' sayangkan jawatan Umno/Pas kempen ms2 guna kaum dan agama ms2 ms9 Para pemimpin Pakatan Harapan dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Presiden baru-baru ini. Kini mereka bersedia gunakan 1 logo, 1 manifesto dan 1 calon melawan BN. Tulisan penuh muka 2 PAKATAN HARAPAN akan didaftar segera bagi membuat persediaan menghadapi pilihan raya umum ke 14 dengan menggunakan satu logo, satu manifesto dan satu calon. Ia dibuat ketika Pas membuat keputusan rasmi keluar dari kumpulan pembangkang melalui mukta- marnya yang ke 63 hujung minggu lalu. 2 NASIONALNASIONAL EDISI 50 •7 MEI - 13 MEI 2017 • Amanah Pakatan Harapan sedia hadapi PRU 14 ELEPAS Pas meninggalkan umum nanti untuk melawan BN. penasihat dan Datuk Seri Dr Wan bebas memegang jawatan politik Azmin Ali, Nurul Izzah Anwar dan blok pembangkang secara PH akan didaftarkan sebagai Azizah Ismail sebagai pengerusi nanti. Saifuddin Nasution Ismail manakala rasmi melalui keputusan- gabungan PKR, DAP, Amanah dan manakala Mohamad Sabu, Tan Sri Mesyuarat juga telah memilih Bersatu pula diwakili oleh Datuk nya dalam Muktamar ke Bersatu minggu depan apabila logo Muhyidin Yassin dan Lim Guang Eng Saifudin Abdullah sebagai setiausa- Seri Mukhriz Mahathir, Tan Sri Abdul S63 hujung minggu lalu, Pakatan yang sesuai dipilih selepas peme- pula dinamakan sebagai naib-naib ha agung gabungan itu manakala Rashid Abdul Rahman dan Dr Shah- Harapan (PH) kini bersedia untuk gang jawatan dan perlembagaan pengerusi. -

Edisi 101 • 6 - 12 Mei 2018 •
BIL 101 6 - 12 MEI 2018 Gagasan Sejahtera Sarawak Report: Husam pecah, calon Berjasa Mahkamah London anak butir lawan Pas tetap bicara penuh sebenar Tok Guru Nik Aziz, kata Nik Omar ms2 ms2 ms8 Kalau Tun Mahathir hasilkan gelombang sokongan di kalangan Melayu luar bandar, Nik Omar hasilkan gelombang sokongan di kalangan Melayu yang pro Islam dan menggegar Pas GELOMBANG sokongan terhadap Pakatan Harapan yang dihasilkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad kini ditambah lagi oleh gelombang yang dihasilkan oleh anak Tok Guru Nik Aziz, Nik Omar. Kalau Tun Mahathir hasilkan gelombang sokongan di kalangan Melayu luar bandar, Nik Omar hasilkan gelombang PENYERTAAN Nik sokongan di kalangan Melayu yang pro Omar sebagai calon Pakatan Harapan Islam dan menggegar Pas, kata pengkaji seolah-olah meletakkan politik, Dr Mazlan Ali. logo 'halal' kepada AMANAH di kalangan pengundi pro Islam. Beliau kini menjadi Laporan penuh tumpuan media. muka 9 2 NASIONALNASIONAL EDISI 101 • 6 - 12 MEI 2018 • Kajian Invoke: Undi Melayu BN jatuh merudum AJI selidik terbaharu Invoke membuang undi. di India kepada PH lebih tinggi berbanding akan mengundi PH dalam senyap. mendapati Undi Melayu Barisan Nasi- Manakala Undi Cina kepada BN juga jatuh sokongan kepada BN, jelasnya. “Kesimpulannya, perbezaan sokongan Konal (BN) jatuh merudum dari 41.1% merudum ke paras 9.3% dalam bulan April “Angka menunjukkan peralihan undi yang antara BN, PH dan PAS dalam kalangan (Disember) kepada hanya 18.1% (April) dan 2018. besar kepada PH dalam kalangan pengundi pengundi Melayu yang telah membuat ia membayangkan berlaku peralihan besar “66.3% pengundi Cina menyatakan mere- India berbanding sokongan kepada BN di keputusan adalah tidak besar iaitu sekitar pengundi Melayu. -

Proceedings of the International Food Research Conference 2017
Proceedings of the International Food Research Conference 2017 Date: 25-27 July 2017 Venue: Complex of the Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation), Universiti Putra Malaysia i © Universiti Putra Malaysia 2017 All rights reserved. No part of this publication may be produced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the copyright owner. Published by: Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan MALAYSIA ii Table of Content Page Foreword by the Vice Chancellor, Universiti Putra Malaysia xiv Foreword by the Dean, Faculty of Food Science and Technology xv Foreword by the IFRC 2017 Chairman xvi IFRC 2017 Proceedings Plenary 2 1 Supercritical Fluid Technology for Food Processing Masaki Ota and Hiroshi Inomata Food Safety and Quality 1. IFRC 2017: 035-049 5 Toxigenic Campylobacter jejuni in Vegetables Farms and Retail Outlets in Terengganu Tang, J.Y.H., Khalid, M.I. and Radu, S. 2. IFRC 2017: 037-024 9 Molecular Typing of Bacillus cereus Isolated from Sago Processing Mills in Sarawak. Jaraee J., Bilung M. L., Nolasco C. H. and Vincent M. 3. IFRC 2017: 071-051 13 Variation of Microbial and Chemical Quality of Two Major Food Fishes in Sri Lanka with Gamma Irradiation. Surendra, I.H.W., Edirisinghe, E.M.R.K.B. and Rathnayake, R.M.N.P. 4. IFRC 2017: 138-096 17 Shiga Toxin Escherichia coli Survival in Different Blending Ratio of Fresh Pineapple-Mango Juice Blends. Kamarul, Zaman, A.A., Shamsudin, R., Mohd Adzahan, N. -

Penggunaan Mekanisasi Di Ladang Sawit
Tidak Disunting POSTER Prosiding Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit 2016 Tajuk Ringkas: Pros. Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit 2016 © Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), 2016 Hak cipta terpelihara. Penerbitan ini tidak dibenarkan dikeluarkan semula, disimpan dalam keadaan yang boleh dicetak semula atau dipindah dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang kaedah elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit. Diterbitkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) pada 2016. Kandungan 6 Kawalan Biologi Penyakit Ganoderma Menggunakan EMBIOTM actinoPLUS Shariffah Muzaimah Syed Aripin, Idris Abu Seman, Madihah Ahmad Zairun, Ahmad Kushairi Din, Norman Kamarudin, Hamirin Kifli dan Wan Ismail Wan Hamat 12 Formulasi Baja Organik dan Baja Kimia untuk Kawalan Penyakit Ganoderma Sawit Mohd Shukri Ibrahim, Idris Abu Seman, Norman Kamarudin, Ahmad Kushairi Din, Mohamed Hanafi Musa, Nuranis Idris, Mohd Nawawi Wahab dan Zaafar Mohd Dahlan 21 Pengesanan Penyakit Ganoderma pada Pokok Sawit Menggunakan Teknologi Spektroskopi Hiperspektral Lapangan Mohamad Izzuddin Anuar, Idris Abu Seman dan Nisfariza Mohd Nor 35 Amalan Pengurusan Terbaik Penanaman Sawit di Tanah Gambut: Penggunaan Zeolite sebagai Pembaikpulih Tanah Hasnol Othman 43 SureSawitTMSHELL – Kit Diagnostik untuk Meramal Jenis Buah Sawit Rajinder Singh, Leslie Ooi Cheng Li, Leslie Low Eng Ti, Meilina Ong Abdullah, Mohd Arif Abd Manaf dan Ravigadevi Sambanthamurthi 48 Kumbang Merah Palma Norsiyenti Othman 59 Penggunaan Mekanisasi -

Nombor Telefon 222 Pusat Khidmat Ahli Parlimen
KENYATAAN MEDIA 12 Julai 2021 Bendera Putih dan Kegagalan Kerajaan: Wanita Keadilan Siap Siaga Membantu Negara merekodkan purata 2 kes bunuh diri setiap hari bagi tempoh 2019 hingga Mei 2021. Bagi tempoh lima bulan pertama dari Januari hingga Mei 2021, sebanyak 468 kes bunuh diri telah direkodkan. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga mendedahkan 91.2 peratus daripada 100,000 panggilan yang diterima oleh talian bantuan sokongan dan psikososial, memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Kes keganasan rumahtangga juga dilaporkan mencecah 23% berbanding tahun lalu. Terkini Perintah Kawalan Pergerakan yang Diperketatkan juga tidak menampakkan hasil. Bloomberg dalam artikel terbarunya yang bertajuk “Malaysia Is Staggering Down the Road to Failed Statehood” mengisahkan bagaimana rakyat Malaysia disaat pandemik menaikkan bendera putih demi sesuap makanan atau memerlukan pertolongan dalam bentuk kewangan untuk membayar sewa rumah. Cetusan idea bendera putih telah mendapat sambutan orang ramai termasuklah disokong oleh sebahagian ahli politik. Pada masa yang sama, inisitatif ini juga dipandang enteng oleh segelintir wakil rakyat yang melihat ia sebagai satu simbol menyerah kalah dan bukanlah suatu budaya yang diterima oleh sesetengah masyarakat. Tidak kurang juga pengibar bendera putih yang diganggu oleh pihak penguatkuasa dan diugut untuk tidak diberikan bantun oleh kerajaan, MP, Adun atau agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Inisiatif bendera putih kini telah diluaskan kepada aplikasi mudahalih yang dinamakan Sambal SOS. Aplikasi tersebut menolong golongan yang memerlukan dengan menyediakan lokasi ‘foodbank’ dan juga lokasi dimana bendera putih dikibarkan bagi memudahkan proses menjejaki mereka untuk menghantar bantuan yang diperlukan. Perlu diingat, bendera putih bukanlah menandakan rakyat sudah mengalah, namun merupakan tekad mereka untuk meneruskan kehidupan seharian. -

Effect of Management of Performance Reward Systems on Subordinates’ Satisfaction with Job in Malaysian Fire and Rescue Department
Binus Business Review, 8(2), August 2017, 115-123 P-ISSN: 2087-1228 DOI: 10.21512/bbr.v8i2.1947 E-ISSN: 2476-9053 Effect of Management of Performance Reward Systems on Subordinates’ Satisfaction with Job in Malaysian Fire and Rescue Department Azman Ismail¹; Yusniati Ishak²; Anis Anisah Abdullah³ ¹Faculty of Economics & Management, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia ²Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia ³Institute of Islam Hadhari (HADHARI), Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Received: 18th January 2017/ Revised: 30th March 2017/ Accepted: 14th April 2017 How to Cite: Ismail, A., Ishak, Y., & Abdullah, A. A. (2017). Effect of Management of Performance Reward Systems on Subordinates’ Satisfaction with Job in Malaysian Fire and Rescue Department. Binus Business Review, 8(2), 115-123. http://dx.doi.org/10.21512/bbr.v8i2.1947 ABSTRACT This research was to measure the correlation between management of performance reward systems on subordinates’ satisfaction towards the job. A survey method was utilized to collect data from subordinates who worked at the headquarters of fire and rescue departments in Malaysia. The outcomes of SmartPLS path model analysis display two important findings. First, the implementation of information delivery and performance assessment in handling performance reward systems have enhanced subordinates’ intrinsic job satisfaction, but the implementation of involvement hypothesized performance reward systems has not enhanced subordinates’ intrinsic job satisfaction. Second, implementation of information delivery, involvement and performance assessment in handling performance reward systems have also enhanced subordinates’ extrinsic job satisfaction.