Kehidupan Multi Etnik Di Kota Padang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
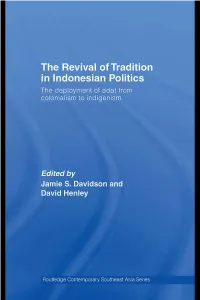
The Revival of Tradition in Indonesian Politics
The Revival of Tradition in Indonesian Politics The Indonesian term adat means ‘custom’ or ‘tradition’, and carries connotations of sedate order and harmony. Yet in recent years it has suddenly become associated with activism, protest and violence. Since the resignation of President Suharto in 1998, diverse indigenous communities and ethnic groups across Indonesia have publicly, vocally, and sometimes violently, demanded the right to implement elements of adat in their home territories. This book investigates the revival of adat in Indonesian politics, identifying its origins, the historical factors that have conditioned it and the reasons for its recent blossoming. The book considers whether the adat revival is a constructive contribution to Indonesia’s new political pluralism or a divisive, dangerous and reactionary force, and examines the implications for the development of democracy, human rights, civility and political stability. It is argued that the current interest in adat is not simply a national offshoot of international discourses on indigenous rights, but also reflects a specifically Indonesian ideological tradition in which land, community and custom provide the normative reference points for political struggles. Whilst campaigns in the name of adat may succeed in redressing injustices with regard to land tenure and helping to preserve local order in troubled times, attempts to create enduring forms of political order based on adat are fraught with dangers. These dangers include the exacerbation of ethnic conflict, the legitimation of social inequality, the denial of individual rights and the diversion of attention away from issues of citizenship, democracy and the rule of law at national level. Overall, this book is a full appraisal of the growing significance of adat in Indonesian politics, and is an important resource for anyone seeking to understand the contemporary Indonesian political landscape. -

Representasi Politik Opini Publik Terhadap Pemilukada Sumatra Barat 2010 Pada Koran Singgalang Dan Program Sumbar Satu
Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 9, Nomor 1, Oktober 2014 Representasi Politik Opini Publik terhadap Pemilukada Sumatra Barat 2010 pada Koran Singgalang dan Program Sumbar Satu Muhammad Thaufan A Prodi Komunikasi, Universitas Andalas, Padang (Mahasiswa doctoral GSID-Nagoya University Japan) Abstract This paper aims to discover political representation of the lokal media namely Harian Singgalang regarding public opinion during the election in West Sumatra Indonesia. Furthermore, the complexity of media power will be discussed through such television program and the newspaper`s headline and special report. By using case study approach and critical discourse analysis of Norman Fairclough in analyzing text, discoursive practice, and socio-cultural practice, it can be noted that political public opinion had been fully articulated in such lokal media representing collaboration actors and institution among media, politicians and lokal people. Political opinion could be sensed in the program “Menuju Sumbar Satu Padang TV” and located in the headlines and special report of Harian Singgalang during April-August 2010. Representation of political opinion in both Padang TV and Singgalang indicated media logic and also vested interested among such media and elites in order to maintain lokal democracy by spreading politically strategic information, persuading the audience, making the myth of good impression in order to win the election. Menuju Sumbar Satu Padang TV has depicted campaign strategy of some governors candidates while headlines and special report of Singgalang have extremely covered all candidates and transformed those dynamic public sphere for political consensus among media, politicians and the audience in promoting lokal democracy in West Sumatra 2010. Key Words : Mass Media, Media Power, Public Opinion, Representation, Democracy Abstrak Tulisan ini menyingkap tabir representasi politis media lokal yaitu Padang TV dan Harian Singgalang terkait opini public dalam proses Pemilukada Sumatera Barat 2010. -

Hasan Basri Perjalanan Birokrat Sejati
HASAN BASRI PERJALANAN BIROKRAT SEJATI Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). HASAN BASRI PERJALANAN BIROKRAT SEJATI Erniwati Azmi Fitrisia Ofianto Aisiah Rahmuliani Fithriah Firza Penerbit NAMS Pusat Studi Etnisitas dan Konflik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Solok Pemerintah Kabupaten Solok HASAN BASRI: Perjalanan Birokrat Sejati Copyright © Erniwati, dkk., 2017 Hak cipta dilindungi Undang-undang All rights reserved Cetakan pertama: 2017 Editor: Wendi Ahmad Wahyudi Tata letak: Wendi Ahmad Wahyudi Desain sampul: Rober Bastian Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit NAMS Redaksi: CV. Najaah Abadi Mitra Sejahtera (NAMS) Jl. Selat Sunda IV/D4-55. Jl. Raya Tlogowaru 88 Kota Malang, Jawa Timur Telp. 082230294393. Email: [email protected] Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) HASAN BASRI: Perjalanan Birokrat Sejati Malang: Penerbit NAMS, 2017 (xx + 199 hlm.; 15,5 x 23 cm) ISBN: 978-602-0959-13-9 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............................................................................................. -

Michael Malley
T he 7th D evelopment Cabinet: Loyal to a Fault? Michael Malley Five years ago, amid speculation that B. J. Habibie and his allies in the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI) would gain a large number of seats in the cabinet, State Secretary Moerdiono announced that "expertise" would be Soeharto's chief criterion for choosing ministers. This year, despite the economic crisis that enveloped the country, few people even thought to suggest that Soeharto sought the most technically qualified assistants. As the outgoing cabinet's term wore to a close, the jockeying for influence among ministers and their would-be successors emphasized the most important qualification of any who would join the new cabinet: loyalty. As if to diminish any surprise at the lengths he would go to create a cabinet of loyalists, Soeharto fired his central bank chief, Soedradjad Djiwandono, in mid- February, just two weeks before the 6 ^ Development Cabinet's term expired. Together with the finance minister, Mar'ie Muhammad, Soedradjad had worked closely with the International Monetary Fund to reach the reform-for-aid agreements Soeharto signed in October 1997 and January this year. Their support for reforms that would strike directly at palace-linked business interests seems to have upset the president, and neither were expected to retain their posts in the 7 ^ Cabinet. But Soedradjad made the further mistake of opposing the introduction of a currency board system to fix the rupiah's value to that of the US dollar. The scheme's main Indonesian proponents were Fuad Bawazier, one of Mar'ie's subordinates, and Peter Gontha, the principal business adviser to Soeharto's son Bambang Trihatmodjo. -

INDO 97 0 1404929731 1 28.Pdf (1.010Mb)
PUNCAK ANDALAS: Fu n c tio n al Regions, Territorial Co alitio ns, a n d the U nlikely Story of O ne W o u l d - be Province Keith Andrew Bettinger1 Since the fall of President Suharto and his authoritarian New Order government in 1998, Indonesia has experienced significant political and administrative transformation. Among the most conspicuous changes are those that have affected the geography of government. The decentralization reforms enacted in the wake of Suharto's forced resignation have not only altered the physical locus of a large spectrum of political and administrative powers, shifting them from Jakarta to outlying regions, but they have also allowed for the redrawing of Indonesia's political-administrative map. Redefining boundaries has been driven by a proliferation of administrative regions, a phenomenon known in Indonesia as pemekaran.2 By late 2013, 202 new districts (kabupaten) and administrative municipalities (kota) had been created, raising the 11 express my gratitude to two anonymous reviewers who provided comments and suggestions that greatly improved this essay. I also gratefully acknowledge the US-Indonesia Society and Mellon Foundation, without whose support this research would not have been possible. Lastly, I gratefully acknowledge comments and suggestions from Ehito Kimura, Krisnawati Suryanata, and Wendy Miles, all at the University of Hawaii. 2 Literally, "blossoming" or "flowering." Indonesia 97 (April 2014) 2 Keith Andrew Bettinger national total to 500. In addition, eight new provinces were created, raising the total to thirty-four. According to the decentralization laws governing pemekaran,3 there are several official justifications that allow for the creation of new regions. -

Regime Change, Democracy and Islam the Case of Indonesia
REGIME CHANGE, DEMOCRACY AND ISLAM THE CASE OF INDONESIA Final Report Islam Research Programme Jakarta March 2013 Disclaimer: The authors gratefully acknowledge financial support from the Islam Research Programme – Jakarta, funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. The views presented in this report represent those of the authors and are in no way attributable to the IRP Office or the Ministry CONTENTS INTRODUCTION 1 Kees van Dijk PART 1: SHARIA-BASED LAWS AND REGULATIONS 7 Kees van Dijk SHARIA-BASED LAWS: THE LEGAL POSITION OF WOMEN AND CHILDREN IN BANTEN AND WEST JAVA 11 Euis Nurlaelawati THE ISLAMIC COURT OF BULUKUMBA AND WOMEN’S ACCESS TO DIVORCE AND POST-DIVORCE RIGHTS 82 Stijn Cornelis van Huis WOMEN IN LOCAL POLITICS: THE BYLAW ON PROSTITUTION IN BANTUL 110 Muhammad Latif Fauzi PART 2: THE INTRODUCTION OF ISLAMIC LAW IN ACEH 133 Kees van Dijk ALTERNATIVES TO SHARIATISM: PROGRESSIVE MUSLIM INTELLECTUALS, FEMINISTS, QUEEERS AND SUFIS IN CONTEMPORARY ACEH 137 Moch Nur Ichwan CULTURAL RESISTANCE TO SHARIATISM IN ACEH 180 Reza Idria STRENGTHENING LOCAL LEADERSHIP. SHARIA, CUSTOMS, AND THE DYNAMICS OF VIGILANTE VIOLENCE IN ACEH 202 David Kloos PART 3: ISLAMIC POLITICAL PARTIES AND SOCIO-RELIGIOUS ORGANIZATIONS 237 Kees van Dijk A STUDY ON THE INTERNAL DYNAMICS OF THE JUSTICE AND WELFARE PARTY (PKS) AND JAMA’AH TARBIYAH 241 Ahmad-Norma Permata THE MOSQUE AS RELIGIOUS SPHERE: LOOKING AT THE CONFLICT OVER AL MUTTAQUN MOSQUE 295 Syaifudin Zuhri ENFORCING RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA: MUSLIM ELITES AND THE AHMADIYAH CONTROVERSY AFTER THE 2001 CIKEUSIK CLASH 322 Bastiaan Scherpen INTRODUCTION Kees van Dijk Islam in Indonesia has long been praised for its tolerance, locally and abroad, by the general public and in academic circles, and by politicians and heads of state. -

Backlash Against Foreign Investment Regime: Indonesia’S Experience
Backlash against Foreign Investment Regime: Indonesia’s Experience Herliana A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2017 Reading Committee: Dongsheng Zang, Chair John O. Haley Melissa Durkee Program Authorized to Offer Degree: School of Law ©Copyright 2017 Herliana ii University of Washington Abstract Backlash against Foreign Investment Regime: Indonesia’s Experience Herliana Chair of the Supervisory Committee: Professor Dongsheng Zang School of Law This study investigates Indonesia’s changing attitude from embracing to repudiating foreign direct investments. Opened its door for foreign investment in the late of 1960s and enjoyed significant economic growth as the result, the country suddenly changed its foreign investment policy in 2012 to be more protectionist towards domestic investors and skeptical towards foreign investors. The essential issues to be discussed in this research are: what motivates Indonesia to move away from global investment regime; what actions the country has taken as manifestation of resentment against the regime; and who are the actors behind such a backlash. This is a qualitative study which aims at gaining a deep understanding of a legal development of Indonesia’s foreign investment. It aims to provide explanation of the current phenomenon taking place in the country. Data were collected through interviews and documents. This research reveals that liberalization of foreign investment law has become the major cause of resentment towards the foreign investment. Liberalization which requires privatization and openness toward foreign capital has failed to deliver welfare to the Indonesian people. Instead, foreign investors have pushed local business players, especially small and medium enterprises, out of the market. -

West Sumatra and Jambi Natural Disasters
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized West Sumatra and Jambi Natural Disasters andJambi Natural Sumatra West A joint report by the BNPB, Bappenas, and the Provincial and District/City Governments andthe Provincial Bappenas, reportA joint theBNPB, by Damage, Loss and Preliminary LossandPreliminary Damage, of West Sumatra and Jambi and international partners, andJambi andinternational October Sumatra 2009 West of Needs Assessment : Damage, Loss and Preliminary Needs Assessment BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA The two consecutive earthquakes that hit the provinces of West Sumatra and Jambi on 30 September and 1 October caused widespread damage across the provinces killing over 1,100 people, destroying livelihoods and disrupting economic activity and social conditions. Resulting landslides left scores of houses and villages buried, whilst disrupting power and communication for days. The first of these events was felt throughout Sumatra and Java, in Indonesia, and in neighboring Malaysia, Singapore and Thailand. The Government of Indonesia responded immediately by declaring a one-month emergency phase, providing emergency relief funds with a promise of more to follow, and indicating that it welcomed international assistance. In addition, tents, blankets, food, medical personnel, emergency clean water facilities and toilets were provided during the immediate response. The armed forces were also engaged in search and rescue operations and delivering relief aid. National partners, including the Indonesian Red Cross, engaged immediately in emergency response efforts. This report describes the human loss, assessment of the damage to physical assets, the subsequent losses sustained across all economic activities, and the impact of the disaster on the provincial and national economies. -
Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy
Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Djayadi Hanan, M.A. Graduate Program in Political Science The Ohio State University 2012 Dissertation Committee: R. William Liddle, Adviser Richard Paul Gunther Goldie Ann Shabad Copyright by Djayadi Hanan 2012 i Abstract This study explores the phenomenon of executive – legislative relations in a new multiparty presidential system. It seeks to understand why, contrary to arguments regarding the dysfunctionality of multi-party presidential systems, Indonesia’s governmental system appears to work reasonably well. Using institutionalism as the main body of theory, in this study I argue that the combination of formal and informal institutions that structure the relationship between the president and the legislature offsets the potential of deadlock and makes the relationship work. The existence of a coalition-minded president, coupled with the tendency to accommodative and consensual behavior on the part of political elites, also contributes to the positive outcome. This study joins the latest studies on multiparty presidentialism in the last two decades, particularly in Latin America, which argue that this type of presidential system can be a successful form of governance. It contributes to several parts of the debate on presidential system scholarship. First, by deploying Weaver and Rockman’s concept of the three tiers of governmental institutions, this study points to the importance of looking more comprehensively at not only the basic institutional design of presidentialism (such as dual legitimacy and rigidity), but also the institutions below the regime level which usually regulate directly the daily practice of legislative – executive relations such as the legislative organizations and the decision making process of the legislature. -
“I Wanted to Run Away” Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia WATCH
HUMAN RIGHTS “I Wanted to Run Away” Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia WATCH “I Wanted to Run Away” Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia Copyright © 2021 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 978-1-62313-895-0 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice. Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all. Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich. For more information, please visit our website: http://www.hrw.org MARCH 2021 ISBN: 978-1-62313-895-0 “I Wanted to Run Away” Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia Glossary ........................................................................................................................... i Summary ......................................................................................................................... 1 From Pancasila to “Islamic Sharia” .......................................................................................... -

Contesting Knowledge of Land Access Claims in Jambi, Indonesia
ii Contesting Knowledge of Land Access Claims in Jambi, Indonesia Dissertation zur Erlangung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Doktorgrades "Doctor rerum naturalium" der Georg-August-Universität Göttingen im Promotionsprogramm Geowissenschaften / Geographie der Georg-August University School of Science (GAUSS) vorgelegt von Rina Mardiana Aus Bandung, Indonesien Göttingen 2017 Betreuungsausschuss: Prof. Dr. Heiko Faust Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, Geographisches Institut, Abteilung Humangeographie Prof. Dr. Christoph Dittrich Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, Geographisches Institut, Abteilung Humangeographie Mitglieder der Prüfungskommission Referent: Prof. Dr. Heiko Faust, Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, Geographisches Institut, Abteilung Humangeographie Korreferent: Prof. Dr. Christoph Dittrich, Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, Geographisches Institut, Abteilung Humangeographie Weitere Mitglieder der Prüfungskommission Prof. Dr. Endriatmo Soetarto Bogor Agricultural University, the Faculty of Human Ecology, Department of Communication and Community Development Sciences Prof. Dr. Daniela Sauer Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Physische Geographie Dr. Soeryo Adiwibowo Bogor Agricultural University, the Faculty of Human Ecology, Department of Communication and Community Development Sciences Dr. Stefanie Steinebach Georg-August-Universität -

Tilburg University Understanding Human Rights Culture in Indonesia
Tilburg University Understanding Human Rights Culture in Indonesia Regus, Max Publication date: 2017 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in Tilburg University Research Portal Citation for published version (APA): Regus, M. (2017). Understanding Human Rights Culture in Indonesia: A Case Study of the Ahmadiyya Minority Group. [s.n.]. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 26. sep. 2021 Understanding Human Rights Culture in Indonesia: A Case Study of the Ahmadiyya Minority Group Understanding Human Rights Culture in Indonesia: A Case Study of the Ahmadiyya Minority Group PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University op gezag van de rector magnificus, prof. dr. E.H.L. Aarts, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het college voor promoties aangewezen commissie in de Ruth First zaal van de Universiteit op maandag 18 december 2017 om 10.00 uur door Maksimus Regus, geboren op 23 september 1973 te Todo, Flores, Indonesië Promotores: Prof.