Bab I Pendahuluan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HRWF Human Rights in the World Newsletter Bulgaria Table Of
Table of Contents • EU votes for diplomats to boycott China Winter Olympics over rights abuses • CCP: 100th Anniversary of the party who killed 50 million • The CCP at 100: What next for human rights in EU-China relations? • Missing Tibetan monk was sentenced, sent to prison, family says • China occupies sacred land in Bhutan, threatens India • 900,000 Uyghur children: the saddest victims of genocide • EU suspends efforts to ratify controversial investment deal with China • Sanctions expose EU-China split • Recalling 10 March 1959 and origins of the CCP colonization in Tibet • Tibet: Repression increases before Tibetan Uprising Day • Uyghur Group Defends Detainee Database After Xinjiang Officials Allege ‘Fake Archive’ • Will the EU-China investment agreement survive Parliament’s scrutiny? • Experts demand suspension of EU-China Investment Deal • Sweden is about to deport activist to China—Torture and prison be damned • EU-CHINA: Advocacy for the Uyghur issue • Who are the Uyghurs? Canadian scholars give profound insights • Huawei enables China’s grave human rights violations • It's 'Captive Nations Week' — here's why we should care • EU-China relations under the German presidency: is this “Europe’s moment”? • If EU wants rule of law in China, it must help 'dissident' lawyers • Happening in Europe, too • U.N. experts call call for decisive measures to protect fundamental freedoms in China • EU-China Summit: Europe can, and should hold China to account • China is the world’s greatest threat to religious freedom and other basic human rights -

COVID-19: Make It the Last Pandemic
COVID-19: Make it the Last Pandemic Disclaimer: The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response concerning the legal status of any country, territory, city of area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Report Design: Michelle Hopgood, Toronto, Canada Icon Illustrator: Janet McLeod Wortel Maps: Taylor Blake COVID-19: Make it the Last Pandemic by The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response 2 of 86 Contents Preface 4 Abbreviations 6 1. Introduction 8 2. The devastating reality of the COVID-19 pandemic 10 3. The Panel’s call for immediate actions to stop the COVID-19 pandemic 12 4. What happened, what we’ve learned and what needs to change 15 4.1 Before the pandemic — the failure to take preparation seriously 15 4.2 A virus moving faster than the surveillance and alert system 21 4.2.1 The first reported cases 22 4.2.2 The declaration of a public health emergency of international concern 24 4.2.3 Two worlds at different speeds 26 4.3 Early responses lacked urgency and effectiveness 28 4.3.1 Successful countries were proactive, unsuccessful ones denied and delayed 31 4.3.2 The crisis in supplies 33 4.3.3 Lessons to be learnt from the early response 36 4.4 The failure to sustain the response in the face of the crisis 38 4.4.1 National health systems under enormous stress 38 4.4.2 Jobs at risk 38 4.4.3 Vaccine nationalism 41 5. -

Dokumentation Des COVID-19-Ausbruchs: Zeitleiste
Dokumentation des COVID-19-Ausbruchs: Zeitleiste JOURNALISMUS MEIN BERICHT https://web.archive.org/web/20210611015902/https://www.jenniferzengblog.com/home/2021/6/1 0/documentary-of-covid-19-outbreak-timeline (Anmerkung von Jennifer: Dieses Dokument enthält hauptsächlich chinesische Nachrichtenberichte über COVID-19, die zu Beginn des Ausbruchs (vom 1. Dezember bis 31. Januar) veröffentlicht wurden. Einige davon wurden von chinesischen Nachrichtenmedien und lokalen chinesischen Regierungen veröffentlicht Hinweise auf die mögliche Absicht der chinesischen Regierung, die Epidemie zum Schweigen zu bringen und zu vertuschen. Viele Artikel wurden später aus dem Internet gelöscht, aber eine Gruppe von Interessierten hat sie auf GitHub gespeichert. Sie organisieren die Archive in einer Zeitleiste mit dem Zweck, "zu bewahren". Geschichte, damit die Wahrheit im Laufe der Zeit nicht verborgen oder vergessen wird. Die ursprüngliche Zeitleiste ist auf Chinesisch. Dies ist eine englische Übersetzung, damit westliche Leser auch die Wahrheit hinter dem Covid-19-Ausbruch erfahren können. Dies ist ein übersetztes Dokument. Das Originaldokument ist in (Chinesisch): https://web.archive.org/web/20200419085730/https://github.com/Pratitya /COVID-19-timeline/blob/master/TIMELINE.md 1. Dezember 2019 · Der erste Einwohner von Wuhan hatte Symptome einer ungeklärten Lungenentzündung (nach der Diagnose war es zu diesem Zeitpunkt eine unbekannte Lungenentzündung mit unbekannter Ursache und kein Arzt gefunden und gemeldet). Laut Wu Wenxuan, Direktor der Intensivstation (ICU) des Jinyintan Krankenhauses, war der Patient ein Mann in den 70ern mit einem leichten Hirninfarkt und Alzheimer. Nachdem er krank wurde, wurde er in ein anderes Krankenhaus in Wuhan eingeliefert, aber als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er am 29. Dezember in das Jinyintan-Krankenhaus verlegt. -

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a Review 1
IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 7 Issue 7, July 2020 ISSN (Online) 2348 – 7968 | Impact Factor (2020) – 6.72 www.ijiset.com Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A review 1. Aanchal Arora, Department of Quality assurance, Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, M.B Road, Pushp Vihar, New Delhi, India. 2. Amrita Parle, Department of Pharmaceutical Chemistry, Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, M.B Road, Pushp Vihar, New Delhi, India. ABSTRACT Existence of human race has come into trouble due to the coronavirus disease 19 (COVID-19) which is highly contagious viral infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The virus initially emerged in Wuhan, China and spread across the globe. Genomic analysis disclosed that SARS-CoV-2 is phylogenetically related to severe acute respiratory syndrome-like (SARS-like) bat viruses, therefore bats could be the possible primary reservoir. Though point of origin and path of transmission is not clearly known, human to human transmission is confirmed through analysis. Due to spread of the disease in about 215 countries around the world, WHO has declared COVID-19 as public health emergency of international concern. There is no clinically approved drug or vaccine available for COVID-19 till date. Scientists are in search of effective and quick cure. Various clinical trials of different antiviral drugs, either alone or in combination with antibiotics, are being conducted worldwide. As -

COVID-19 and China: a Chronology of Events (December 2019-January 2020)
COVID-19 and China: A Chronology of Events (December 2019-January 2020) Updated May 13, 2020 Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov R46354 SUMMARY R46354 COVID-19 and China: A Chronology of Events May 13, 2020 (December 2019-January 2020) Susan V. Lawrence In Congress, multiple bills and resolutions have been introduced related to China’s Specialist in Asian Affairs handling of a novel coronavirus outbreak in Wuhan, China, that expanded to become the coronavirus disease 2019 (COVID-19) global pandemic. This report provides a timeline of key developments in the early weeks of the pandemic, based on available public reporting. It also considers issues raised by the timeline, including the timeliness of China’s information sharing with the World Health Organization (WHO), gaps in early information China shared with the world, and episodes in which Chinese authorities sought to discipline those who publicly shared information about aspects of the epidemic. Prior to January 20, 2020—the day Chinese authorities acknowledged person-to-person transmission of the novel coronavirus—the public record provides little indication that China’s top leaders saw containment of the epidemic as a high priority. Thereafter, however, Chinese authorities appear to have taken aggressive measures to contain the virus. The Appendix includes a concise version of the timeline. A condensed version is below: Late December: Hospitals in Wuhan, China, identify cases of pneumonia of unknown origin. December 30: The Wuhan Municipal Health Commission issues “urgent notices” to city hospitals about cases of atypical pneumonia linked to the city’s Huanan Seafood Wholesale Market. The notices leak online. -

《中国学术期刊文摘》赠阅 《中国学术期刊文摘》赠阅 CHINESE SCIENCE ABSTRACTS (Monthly, Established in 2006) Vol.10 No.1, 2015 (Sum No.103) Published on January 15, 2015
《中国学术期刊文摘》赠阅 《中国学术期刊文摘》赠阅 CHINESE SCIENCE ABSTRACTS (Monthly, Established in 2006) Vol.10 No.1, 2015 (Sum No.103) Published on January 15, 2015 Chinese Science Abstracts Competent Authority: China Association for Science and Technology Contents Supporting Organization: Department of Society Affairs and Academic Activities China Association for Science and Technology Hot Topic Sponsor: Science and Technology Review Publishing House Ebola Virus………………………………………………………………………1 Publisher: Science and Technology Review Publishing House High Impact Papers Editor-in-chief: CHEN Zhangliang Highly Cited Papers TOP5……………………………………………………11 Chief of the Staff/Deputy Editor-in-chief: Acoustics (11) Agricultural Engineering (12) Agriculture Dairy Animal Science (14) SU Qing [email protected] Agriculture Multidisciplinary (16) Agronomy (18) Allergy (20) Deputy Chief of the Staff/Deputy Editor-in-chief: SHI Yongchao [email protected] Anatomy Morphology (22) Andrology (24) Anesthesiology (26) Deputy Editor-in-chief: SONG Jun Architecture (28) Astronomy Astrophysics (29) Automation Control Systems (31) Deputy Director of Editorial Department: Biochemical Research Methods (33) Biochemistry Molecular Biology (34) WANG Shuaishuai [email protected] WANG Xiaobin Biodiversity Conservation (35) Biology (37) Biophysics (39) Biotechnology Applied Microbiology (41) Cell Biology (42) Executive Editor of this issue: WANG Shuaishuai Cell Tissue Engineering (43) Chemistry Analytical (45) Director of Circulation Department: Chemistry Applied (47) Chemistry Inorganic -

Orchestra Piece for Wuhan Medics Engineers Answer a Call of Help
CHINA DAILY | HONG KONG EDITION Thursday, February 13, 2020 | 17 LIFE n Dec 26, 2019, 54year among their patients. old Zhang Jixian, director After the six patients were trans of the Department of Res ferred to Jinyintan, more patients piratory and Critical Care with similar symptoms came, so OMedicine of Hubei Provincial Hospi that, on Jan 1, the isolation ward tal of Integrated Chinese & Western was full. During the New Year holi Medicine, received an elderly cou day, patients at respiratory and criti ple. Both of them had a high fever cal care departments increased and coughed, looking like they had drastically, from 100 per day to 230 been hit by a normal case of the flu. per day. More patients shared the However, when she checked the CT same symptoms as the first seven scans of their lungs, she found cases. something unusual. On Jan 17, the inpatient depart Normally, pneumonia causes a ment was transformed into an isola pathological change to one of the tion area. Two weeks later, the lungs, but the scans showed that the hospital was designated as one of two elderly people each had ground those specifically equipped to treat glass opacity in both, which was the pneumonia caused by the novel something Zhang had never seen coronavirus. The hospital was divid before. ed into six parts, with a total of 160 Examinations ruled out common beds. viruses such as influenza A and B, As the director of her department, mycoplasma, chlamydia, and adeno Zhang looked after the most severe virus. Zhang’s thoughts turned to patients, but would help her col SARS, or severe acute respiratory leagues during busy periods. -
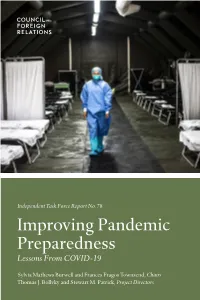
Improving Pandemic Preparedness: Lessons from COVID-19
Independent Task Force Report No. 78 Improving Pandemic Preparedness Lessons From COVID-19 Sylvia Mathews Burwell and Frances Fragos Townsend, Chairs Thomas J. Bollyky and Stewart M. Patrick, Project Directors Independent Task Force Report No. 78 Improving Pandemic Preparedness Lessons From COVID-19 Sylvia Mathews Burwell and Frances Fragos Townsend, Chairs Thomas J. Bollyky and Stewart M. Patrick, Project Directors The Council on Foreign Relations (CFR) is an independent, nonpartisan membership organization, think tank, and publisher dedicated to being a resource for its members, government officials, business executives, journalists, educators and students, civic and religious leaders, and other interested citizens in order to help them better understand the world and the foreign policy choices facing the United States and other countries. Founded in 1921, CFR carries out its mission by maintaining a diverse membership, with special programs to promote interest and develop expertise in the next generation of foreign policy leaders; convening meetings at its headquarters in New York and in Washington, DC, and other cities where senior government officials, members of Congress, global leaders, and prominent thinkers come together with Council members to discuss and debate major international issues; supporting a Studies Program that fosters independent research, enabling CFR scholars to produce articles, reports, and books and hold roundtables that analyze foreign policy issues and make concrete policy recommendations; publishing Foreign Affairs, the preeminent journal on international affairs and U.S. foreign policy; sponsoring Independent Task Forces that produce reports with both findings and policy prescriptions on the most important foreign policy topics; and providing up-to- date information and analysis about world events and American foreign policy on its website, CFR.org. -

Monday 12/28/20 This Material Is Distributed by Ghebi LLC on Behalf
Received by NSD/FARA Registration Unit 12/29/2020 10:24:42 AM Monday 12/28/20 This material is distributed by Ghebi LLC on behalf of Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency, and additional information is on file with the Department of Justice, Washington, District of Columbia. Lori Loughlin Released From Prison After Serving 2 Months for Role in College Admissions Scandal by Mary F. Lori Loughlin is an American actress and producer best known for her role as Rebecca Donaldson-Katsopolis on the ABC sitcom "Full House." Loughlin and her husband Mossimo Giannulli in 2020 pleaded guilty to conspiracy to commit fraud in relation to a college admissions bribery scandal. Loughlin was released from the Federal Correctional Institution in Dublin, California, on Monday after serving two months behind bars for her role in a US college admissions scandal, which was busted in 2019 by an FBI investigation code-named Operation Varsity Blues. According to a source who spoke to People, the actress had a tearful reunion with her daughters Olivia Jade Giannulli, 20, and Isabella Rose Giannulli, 21. “It’s the end of a very long ordeal,” the source told the outlet. Another insider said that Loughlin, 56, “seems beyond relieved that she can put her prison sentence behind her." "It's the most stressful thing she has ever dealt with. She plans on spending New Year's with Olivia and Bella". The “Full House” alum was given a two-month prison term in August after she and her husband pleaded guilty to paying the scheme’s mastermind, William “Rick” Singer, $500,000 to get her two daughters recruited onto the University of Southern California’s rowing team, despite their having no experience with the sport. -

From the Conference Chair
2008 International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2008) Wuhan, China 12 – 14 December 2008 Volume 1 Pages 1-621 IEEE Catalog Number: CFP08CSA-PRT ISBN: 978-1-4244-3902-7 TABLE OF CONTENTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE HMM-Based-Correlations in Infrared Remote-Image ....................................................................................1 Rui Yang, Bo Li A Fuzzy Interactive Approach for Decentralized Bilevel Programming Problem with a Common Decision Variable................................................................................................................................5 Guangmin Wang, Zhongping Wan The Research about Integration of Process Planning and Production Scheduling Based on Genetic Algorithm...............................................................................................................................................9 Wang Zhanjie, Tian Ju Water Quality Assessment Using Artificial Neural Network........................................................................13 Ma Huiqun, Liu Ling A Hybrid Multi-user Receiver Based on Parallel Interference Cancellation and Improved Genetic Algorithm.............................................................................................................................................16 Lili Lin Query-Focused Multi-document Summarization Using Keyword Extraction ............................................20 Liang Ma, Tingting He, Fang Li, Zhuomin Gui, Jinguang Chen Weak Biosignal Processing Using Adaptive Wavelet Neural -
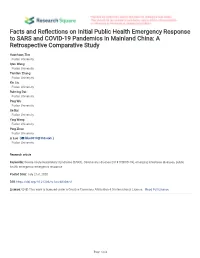
Facts and Re Ections on Initial Public Health
Facts and Reections on Initial Public Health Emergency Response to SARS and COVID-19 Pandemics in Mainland China: A Retrospective Comparative Study Huanhuan Zhu Fudan University Qian Wang Fudan University Tiantian Zhang Fudan University Xin Liu Fudan University Ruiming Dai Fudan University Ping Wu Fudan University Ge Bai Fudan University Ying Wang Fudan University Ping Zhou Fudan University Li Luo ( [email protected] ) Fudan University Research article Keywords: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Coronavirus disease-2019 (COVID-19), emerging infectious diseases, public health emergency, emergency response Posted Date: July 21st, 2020 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-40308/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Page 1/11 Abstract Background: Since December 2019, 2019-nCoV has emerged in Wuhan, China, the fast pace of transmission is wreaking global public health crisis. Country’s reaction speed is critical for the control of public health emergency (PHE), especially in the early stage of an outbreak. Compared with SARS pandemic, whether has the eciency of initial public health emergency response to COVID-19 in mainland China been improved? And whether is there still existing vulnerabilities in current PHE system? Studies on this topic are relatively few. We tried to nd the answers, evidences and alternatives. Methods: We conducted a retrospective comparative study. The speed of hospital reporting, pathogen identication and government decision-making between SARS and COVID-19 were compared by selecting 5 critical events from initial public health emergency response timeline. Besides, combining with the two pandemics' progress curves, we discussed the characteristics of their peak time. -

COVID-19 and China: a Chronology of Events (December 2019-January 2020)
COVID-19 and China: A Chronology of Events (December 2019-January 2020) Updated May 13, 2020 Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov R46354 SUMMARY R46354 COVID-19 and China: A Chronology of Events May 13, 2020 (December 2019-January 2020) Susan V. Lawrence In Congress, multiple bills and resolutions have been introduced related to China’s Specialist in Asian Affairs handling of a novel coronavirus outbreak in Wuhan, China, that expanded to become the coronavirus disease 2019 (COVID-19) global pandemic. This report provides a timeline of key developments in the early weeks of the pandemic, based on available public reporting. It also considers issues raised by the timeline, including the timeliness of China’s information sharing with the World Health Organization (WHO), gaps in early information China shared with the world, and episodes in which Chinese authorities sought to discipline those who publicly shared information about aspects of the epidemic. Prior to January 20, 2020—the day Chinese authorities acknowledged person-to-person transmission of the novel coronavirus—the public record provides little indication that China’s top leaders saw containment of the epidemic as a high priority. Thereafter, however, Chinese authorities appear to have taken aggressive measures to contain the virus. The Appendix includes a concise version of the timeline. A condensed version is below: Late December: Hospitals in Wuhan, China, identify cases of pneumonia of unknown origin. December 30: The Wuhan Municipal Health Commission issues “urgent notices” to city hospitals about cases of atypical pneumonia linked to the city’s Huanan Seafood Wholesale Market. The notices leak online.