Iva-Buddha Indonesia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
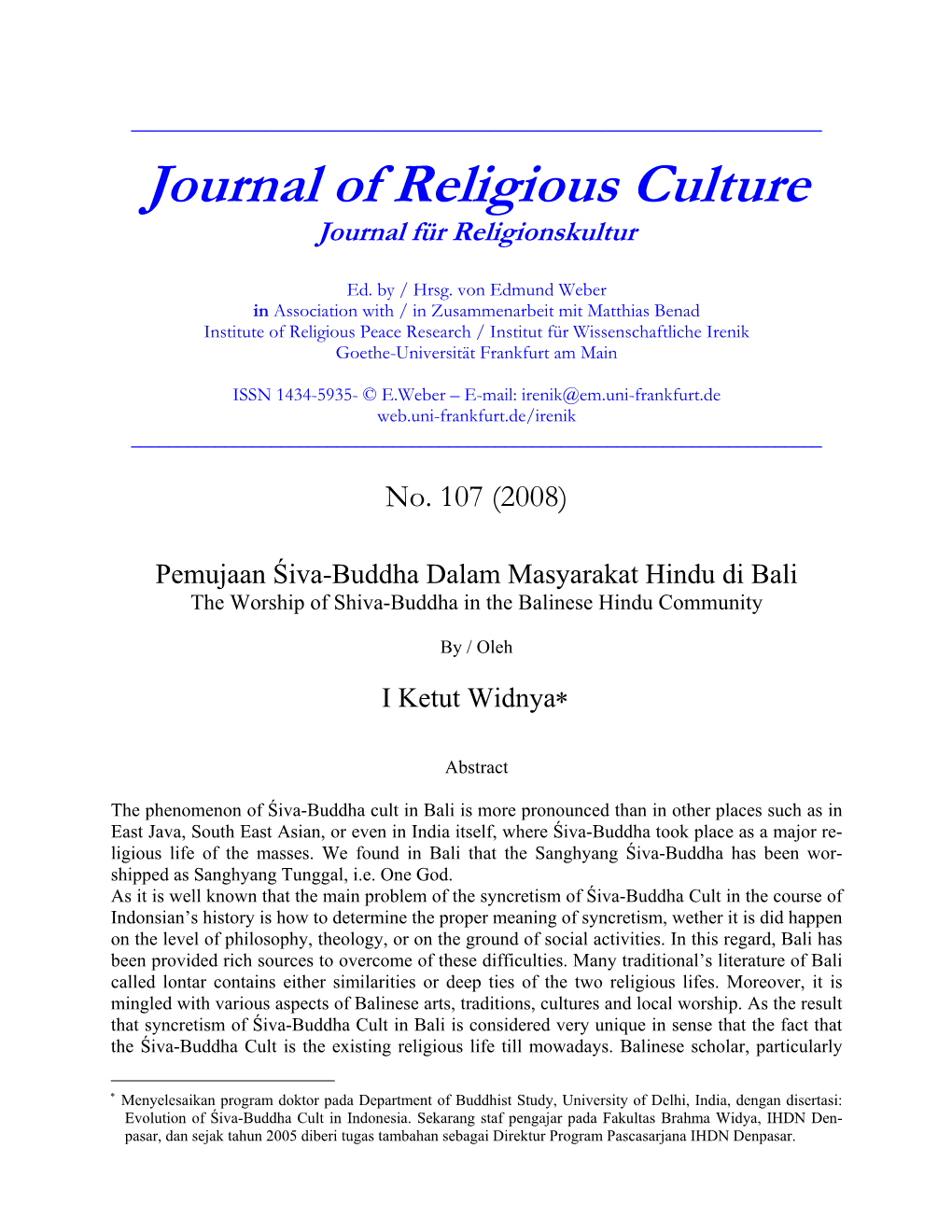
Load more
Recommended publications
-

The Era of Uncertainty and Ethical Arrangement In
Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 56, no. 2 (2018), pp.461-493, doi: 10.14421/ajis.2018.562.461-493 THE ERA OF UNCERTAINTY AND ETHICAL ARRANGEMENT IN JAVANESE CLASSICAL TEXTS Disseminating Ranggawarsita’s Works as Source of Islamic Ethics in Islamic Higher Education Zumrotul Mukaffa Sunan Ampel State Islamic University (UIN) Surabaya Email: [email protected] Abstract: This paper investigates the era of uncertainty and ethical arrangement as formulated in the Javanese classical text written by Ranggawarsita (1802-1873 M). Most of his works, especially Serat Kalatidha, Serat Sabdapranawa, and Serat Sabdatama, was situated during the era of uncertainty and the era of zaman edan (age of insanity), kalabendu (age of anger), owah or pakewuh (age of strangeness). The social structure in this era was seen the apparent rise of unethical behavior. Elite communities were seen to be lacking in self-respenct, meanwhile the general population were regarded as ignoring basic public morality. New ethical notion emerged to set society free from ‘uncertainty’ through the implementation of four ethical doctrines in social life, namely monotheism, purba wasesa ing astane Gusti (submission to God’s predestination), muhung mahas ing asepi (self-contemplation), and eling lan waspada (self-awareness and mindfulness). The current situation of the Indonesian nation is very similar to the age of kalabendu. Thus it is necessary to disseminate and transform of ethical doctrines in the Islamic Higher Education through Islamic Ethic, in the form of textbooks. [Artikel ini membahas zaman ketidakpastian dan respon etisnya di dalam naskah Jawa klasik karya pujangga Ranggawarsita. -

Pluralisme Agama Dalam Kakawin Sutasoma
48 PLURALISME AGAMA DALAM KAKAWIN SUTASOMA Hasan Irsyad; M. Ridlwan; Pheni Cahya Kartika Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya [email protected] ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada pluralisme agama dalam Kakawin Sutasoma serta Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks asli Kakawin Sutasoma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan konsep pluralisme agama yang diajarkan Kakawin Sutasoma dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan konteks asli Kakawin Sutasoma. Untuk menemukan pluralisme agama dalam Kakawin Sutasoma, digunakan tiga prinsip pluralisme agama Coward. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara diskriptif. Dokumen yang digunakan adalah Kakawin Sutasoma terjemahan Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo yang diterbitkan Komunitas Bambu pada 2009. Penelitian berhasil mengidentifikasi adanya pluralisme agama Siwa- Buddha dalam Kakawin Sutasoma yang bercirikan toleransi dan saling menghormati antaragama, Tuhan dianggap sebagai hakikat tunggal yang berwujud jamak, agama- agama dianggap setara dan semuanya baik sebagai jalan menuju kebenaran, serta pengabsahan Buddha sebagai perwujudan Siwa lebih ditekankan daripada sebaliknya. Penelitian juga mendapati bahwa Bhinneka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma adalah ungkapan yang mengajarkan pluralisme agama. Bhinneka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sebagai semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika cakupannya diperluas dan tidak mengajarkan pluralisme agama. Kata Kunci: bhinneka tunggal ika, kakawin sutasoma, pluralisme agama PENDAHULUAN Dewasa ini agama-agama di dunia mendapat tantangan dari paham-paham beragama baru yang berkembang seperti sekularisme agama dan pluralisme agama. Di Indonesia, paham-paham tersebut mendapat perhatian serius dari tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi keagamaan, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). -

421 Reference
420 Wacana, Vol. 12 No. 2 (October 2010) BOOK REVIEWS 421 in Indonesian might have been used. Then on page 163, there is mention of “toko P&D”, which is from the Dutch Provisiën en Dranken, meaning a "store selling daily necessities and drinks". Today it is the equivalent to a small supermarket. Then there are a few more little things that still need to be looked into. On page 191, for gadis Eurasia it is more common in Indonesian to use gadis Indo; pasangan penari, should be pasangan pedansa To conclude, this is a highly interesting book, telling in their own words the experiences of a variety of women who have one thing in common: they are, or are considered by others, ethnic Chinese in varying degrees, or as in Jane’s case, closely associated with an ethnic Chinese. Basically, the book explores the problem of identity and Chineseness, a topic that has become very important in view of the spread (some people see it as the threat) of globalism. Studies on this topic abound and many more will probably be written. Dewi Anggraeni’s book is a valuable contribution in this search for identity and I suggest a very readable one. Reference Tan, Mely G. 2007. “Ethnic Chinese women professionals in Indonesia; Tendency towards globalization?”, in: Leo Suryadinata (ed.), Chinese diaspora since Admiral Zheng He; With special reference to maritime Asia, pp. 279-295. Singapore: Chinese Heritage Centre. -------------------------------- Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma. Translated by Dwi Woro Retno Mastuti and Hastho Bramantyo. Depok: Komunitas Bambu, 2009, xxiv + 544 pp. -
![46 Mohammad Imam Farisi Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity]](https://docslib.b-cdn.net/cover/6860/46-mohammad-imam-farisi-bhinneka-tunggal-ika-unity-in-diversity-2126860.webp)
46 Mohammad Imam Farisi Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity]
Journal of Social Science Education ©JSSE 2014 DOI 10.2390/jsse.v14.i1.1261 Volume 13, Number 1, Spring 2014 ISSN 1618–5293 Mohammad Imam Farisi Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity]: From Dynastic Policy to Classroom Practice The purpose of this article is to discuss the concept of Bhinneka Tunggal Ika, in its narrowest sense, a policy on religious tolerance, as it is operationalized in social studies textbooks and in classroom practice in Indonesia. The focus of the research is on six electronic textbooks used by students aged 7‐12 years, in Indonesian elementary schools which are further considered in the context of Indonesian teachers’ actual experience of the operationalization of Bhinneka Tunggal Ika in a classroom setting. The study shows that the textbooks and classroom practice are able to describe and transform a concept such as Bhinneka Tunggal Ika into a real and meaningful concept or practice for students as practiced in the family, the school, the wider community and at a national level as well as in religious ceremonies, architecture, and gotong‐royong (or reciprocal) activities. However, the state also has a political goal and this concept should also be viewed as underlying cultural policy designed to build a character and civilization appropriate to a pluralistic Indonesian nation. Keywords: Bhinneka tunggal ika, dynastic policy, textbook, social Bhinneka Tunggal Ika is a concept dating back to the studies, elementary school third century which was central to the religious politics of 1 the ruling dynasty . It was later adopted by the Indonesian government as a motto of national unity. -

Bhinneka Tunggal Ika in Kakawinsutasoma in Multicultural Societyof Denpasar City
International Journal of Research in Social Sciences Vol. 8 Issue 3, March 2018, ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: [email protected] Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gage as well as in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A BHINNEKA TUNGGAL IKA IN KAKAWINSUTASOMA IN MULTICULTURAL SOCIETYOF DENPASAR CITY Ni Putu Winanti* Ni Gusti Ayu Kartika** Abstract: The pluralism of Denpasar City residents to this day still exist. The philosophy of Bhinneka Tunggal Ika is considered giving a strong contribution to it. This study will try to illustrate the roots of Bhinneka Tunggal Ika philosophy in Sutasoma’s Old Poetry (kakawin) by Mpu Tantular, the implementation of Bhinneka Tunggal Ika philosophy, and the perception of the multicultral community in Denpasar towards the Bhinneka Tunggal Ika. Through descriptive qualitative descriptions, this study tries to see the text of Sutasoma in general along with the implementation of Bhinneka Tunggal Ika philosophy in multicultural society in Denpasar City, which can be seen in the synergy of religious life behavior, the blend of art and culture, and the combination of beliefs seen in various development worship places. This study concludes that the philosophy of Bhineka Tunggal Ika is still relevant as a life guidance for the plural citizens in Denpasar. The basis of Bhineka Tunggal Ika made the community able to develop an attitude of helping each other, tolerance, mutual cooperation(gotong royong), mutual respect, and glorify each other. -

Chapter IV Temples in Context of Religion and Politics |
Chapter IV Temples in context of religion and politics architecture of the majapahit period The Javanese temples in general symbolically represent the mythical Mount Meru, the seat of the gods.1 The ways that this concept was incorporated into an architectural shape differed in Central and East Javanese art. While Central Javanese architecture has a concentric lay- out, East Javanese architecture displays a terraced and linear layout.2 The best example for Central Java is the Borobudur. This temple has been interpreted as a mandala, which is a concentric geometric structure.3 For the East Javanese period it is the Majapahit period which yielded the architectural characteristics in a most conspicuous way. The terraced structure is most obvious in the small-scale mountain sanctuaries, the layout of which follows the linear ascent of the mountain slope, such as Candi Kendalisodo and Candi Yudha on Mount Penanggungan. Most of these sanctuaries consist of a pemujaan, a place for worship, which is built in several terraces. In front or next to this structure there are often one or more small altars. Temple complexes such as Candi Panataran 1 Major publications in the field of ancient Javanese architecture are Krom 1923; Stutterheim 1931; Bernet Kempers 1959; Dumarçay 1986a, 1986b, 1993; Soekmono 1995. The issue of Mount Meru has been discussed by several authors, for example by Stutterheim (1931:13) and Bernet Kempers (1959:20-1). 2 Beyond the marked difference in layout it seems to me that there is also a difference in the size of East and Central Javanese temples, respectively. My impression is that most East Javanese temples are of a rather small scale compared to those in Central Java. -

Balinese War Gamelan (From the 10Th to the 21St Century) PROGRA
J.06 GAMELAN PERANG DI BALI (ABAD KE-10 SAMPAI AWAL ABAD KE-21) Balinese War Gamelan (from the 10th to the 21st Century) Oleh: Hendra Santosa NPM. 180130140006 DISERTASI untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Sejarah pada Universitas Padjadjaran Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran Sesuai dengan keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas Dipertahankan tanggal 12 Desember 2017 Di Universitas Padjadjaran PROGRAM STUDI ILMU-ILMU SASTRA PROGRAM PASCASARJANA (S3) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2017 ABSTRAK Judul Disertasi : GAMELAN PERANG DI BALI (ABAD KE-10 SAMPAI AWAL ABAD KE-21) Subjek : 1. Sejarah 2. Bali 3. Gamelan 4. Perang Abstrak Disertasi ini berisi kajian tentang gamelan perang di Bali, abad ke-10 sampai awal abad ke-21. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama bagaimana asal-usul gamelan perang di Bali, kedua mengapa terjadi perubahan nama dari mredangga, bedug, dan kemudian menjadi tambur, ketiga apakah instrumentasi gamelan Mrĕdangga sama dengan instrumentasi gamelan Bheri, dan keempat bagaimana proses perjalanan gamelan Banjuran menjadi Adi Merdangga. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang dilakukan dengan empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi, antara lain menggunakan teori perubahan perubahan yang dicetuskan oleh Claire Holt dimana perubahan dipicu oleh faktor eksternal. Selanjutnya perubahan dari John E. Keamer yang menyebutkan bahwa inovasi bisa berasal dari salah seorang anggota kelompok masyarakat yang bersangkutan (atau senimannya), maka dengan demikian konsep perubahan taksu dan jengah pada masyarakat Bali diterapkan dalam membedah perubahan yang terjadi pada gamelan perang. Untuk melihat perkembangan dan penyebarannya dipergunakan teori dari Bourdieu tentang habitus dimana kebiasaan merupakan pusat tindakan. -

Downloaded From
H. Creese Old Javanese studies; A review of the field In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Old Javanese texts and culture 157 (2001), no: 1, Leiden, 3-33 This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl Downloaded from Brill.com09/27/2021 04:40:52AM via free access HELEN CREESE Old Javanese Studies A Review of the Field For nearly two hundred years the academic study of the languages and liter- atures of ancient Java has attracted the attention of scholars. Interest in Old Javanese had its genesis in the Orientalist traditions of early nineteenth-cen- tury European scholarship. Until the end of the colonial period, the study of Old Javanese was dominated by Dutch scholars whose main interest was philology. Not surprisingly, the number of researchers working in this field has never been large, but as the field has expanded from its original philo- logical focus to encompass research in a variety of disciplines, it has remain1 ed a small but viable research area in the wider field of Indonesian studies. As a number of recent review articles have shown (Andaya and Andaya 1995; Aung-Thwin 1995; McVey 1995; Reynolds 1995), in the field of South- east Asian studies as a whole, issues of modern state formation and devel- opment have dominated the interest of scholars and commentators. Within this academic framework, interest in the Indonesian archipelago in the period since independence has also focused largely on issues relating to the modern Indonesian state; This focus on national concerns has not lent itself well to a .rich ongoing scholarship on regional cultures, whether ancient or modern. -

Kakawin Sutasoma
Universitas Indonesia Library >> Naskah Kakawin Sutasoma Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=20187061&lokasi=lokal ------------------------------------------------------------------------------------------ Abstrak Lontar ini berisi teks Kakawin Sutasoma, yaitu kisah upaya Sang Sutasoma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan dharma. Sutasoma, putra Prabu Mahaketu dari kerajaan Astina, lebih menyukai memperdalam ajaran Buddha Mahayana daripada harus menggantikan ayahandanya menjadi raja. Sutasoma pergi ke hutan untuk melakukan semadi di sebuah candi dan mendapat anugerah. Kemudian beliau pergi ke gunung Himalaya bersama beberapa pendeta. Di sebuah pertapaan, beliau mendengar cerita tentang raja raksasa bernama Prabu Purusada yang gemar makan daging manusia. Para pendeta dan Batari Pretiwi membujuk Sutasoma agar membunuh Prabu Purusada. Sutasoma menolak bujukan tersebut karena ingin melanjutkan perjalanan. Beliau bertemu dengan raksasa berkepala gajah pemakan manusia dan ular naga. Keduanya takluk dan bersedia menjadi muridnya untuk mempelajari agama Budha. Sutasoma juga bertemu dengan harimau betina yang akan memakan anaknya sendiri. Dalam perkelahian ini Sutasoma mati tetapi dihidupkan kembali oleh Batara Indra. Tersebutlah sepupu Sutasoma bernama Prabu Dasabahu, berperang dengan anak buah Prabu Kalmasapada (Purusada). Anak buah Prabu Kalmasapada kalah dan minta perlindungan Sutasoma. Prabu Dasabahu yang terus mengejar, akhirnya tahu bahwa Sutasoma itu sepupunya, lalu diajak ke negerinya dan dijadikan -

BUDDHIST APPROACH to RESPONSIBLE CONSUMPTION and SUSTAINABLE DEVELOPMENT ADVISORY BOARD His Holiness Thich Tri Quang Deputy Sangharaja of Vietnam Most Ven
BUDDHIST APPROACH TO RESPONSIBLE CONSUMPTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ADVISORY BOARD His Holiness Thich Tri Quang Deputy Sangharaja of Vietnam Most Ven. Dr. Thich Thien Nhon President of National Vietnam Buddihst Sangha Most Ven.Prof. Brahmapundit President of International Council for Day of Vesak CONFERENCE COMMITTEE Prof. Dr. Le Manh That, Vietnam Most Ven. Dr. Dharmaratana, France Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi, Thailand Bhante. Chao Chu, U.S.A. Prof. Dr. Amajiva Lochan, India Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu (Conference Coordinator), Vietnam EDITORIAL BOARD Dr. Do Kim Them, Germany Dr. Tran Tien Khanh, USA Nguyen Manh Dat, U.S.A. Bruce Robert Newton, Australia Dr. Le Thanh Binh, Vietnam Giac Thanh Ha, Vietnam Nguyen Thi Linh Da, Vietnam Tan Bao Ngoc, Vietnam VIETNAM BUDDHIST UNIVERITY SERIES BUDDHIST APPROACH TO RESPONSIBLE CONSUMPTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Editors: Most Ven. Thich Nhat Tu, D.Phil., Most Ven. Thich Duc Thien, Ph.D., HONG DUC PUBLISHING HOUSE CONTENTS Foreword ..................................................................................................ix Preface ......................................................................................................xi Editors’ Introduction ............................................................................. xv I. CONSUMPTION AND ENVIRONMENT 1. A Buddhist Perspective on Overconsumption and its Negative Effects towards Society and Environment Rev. Beragama Piyarathana Thero ..........................................................3 2. Attaining -

A STUDY of the SUTASOMA KAKAWIN.Pdf (PDF, 8.03MB)
l The University of Sydney Copyright in relation to this thesis* Under the Copyright Act 1968 (several provisions of which are referred to below), this thesis must be used only under the normal conditions of scholarly fa1r dealing for the purposes of research, criticism or review. In particular no results or conclusions should be extracted from it, nor should it be copied or closely paraphrased in whole or in part without the written consent of the author. Proper written acknowledgement should be made for any assistance obtained from this thesis. Under Section 35(2) of the Copyright Act 1968 'the author of a literary, dramatic, musical or artistic work is the owner of any copyright subsisting in the work·. By virtue of Section 32(1 ) copyright 1Subsists in an original literary, dramatic, musical or artistic work that is unpublished' and of which the author was an Australian citizen, an Australian protected person or a person resident in Australia. The Act, by Section 36(1) provides: 'Subject to this Act, the copyright in a literary, dramatic, musical or artistic work is infringed by a person who, not being the owner of the copyright and without the licence of the owner of the copyright, does in Australia, or authorises the doing in Australia of, any act comprised in the copyright'. Section 31 (1 )(a)(i) provides that copyright includes the exclusive right to 'reproduce the work in a material form'. Thus, copyright is infringed by a person who, not being the owner of the copyright and without the licence of the owner of the copyright, reproduces or authorises the reproduction of a work, or of more than a reasonable part of the v. -
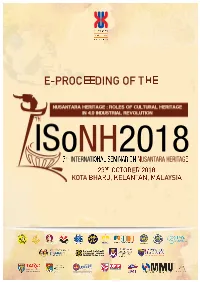
Story of Epos Sutasoma As Dance Oratorium Idea Creation in Improving Unity and Harmony of Nation
STORY OF EPOS SUTASOMA AS DANCE ORATORIUM IDEA CREATION IN IMPROVING UNITY AND HARMONY OF NATION Ida Ayu Wimba Ruspawati, I Ketut Sariada, Ni Ketut Suryatini Indonesian Institute of the Arts Denpasar Nusa Indah Street Denpasar [email protected] Abstract The Majapahit kingdom has a vast territory covering Nusantara archipelago and Malay peninsula. In addition to greatness and glory, the Majapahit kingdom also has great writers at that time, one of them is Mpu Tantular. One of his literary work is Kakawin Sutasoma which is taken as motto of the Republic of Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Kakawin Sutasoma tells a sacrifice of a King Prabu Mahaketu's son of the Astina kingdom named Sutasoma. This research is using a qualitative methodology with participative observation method by observing various performing art activities which is related to Sutasoma epics. The result obtained is the determination of character becoming an important part because it becomes a supporting element of dance. In addition, an artist involves intellectual potential, the emotional potential, and the spiritual potential proportionally to acquire aesthetic forms and open for a value understanding. Communication of symbols are created through dance movements that are expected to be interpreted by the audience and can be implemented in daily life. If this is realized, violence can be avoided and unity and harmony can be realized. Keywords: Sutasoma, Dance Oratorium, Character, Aesthetics, Communication Art I. INTRODUCTION Historically, Indonesia once had large kingdoms that is glorius in its era. One of them is the Majapahit kingdom. Majapahit Kingdom has a vast territory. In Kakawin Nagarakretagama pupuh 13 and 14, it is said that the extent of the Majapahit kingdom is in the archipelago of Nusantara and in the Malay Peninsula.